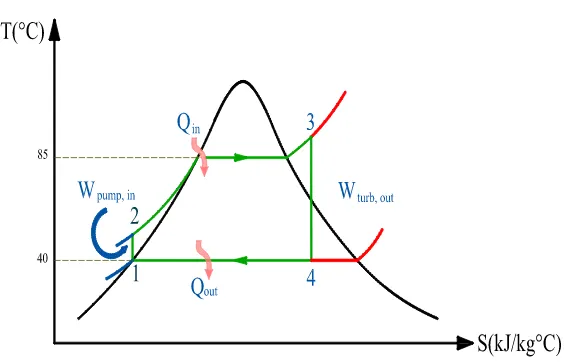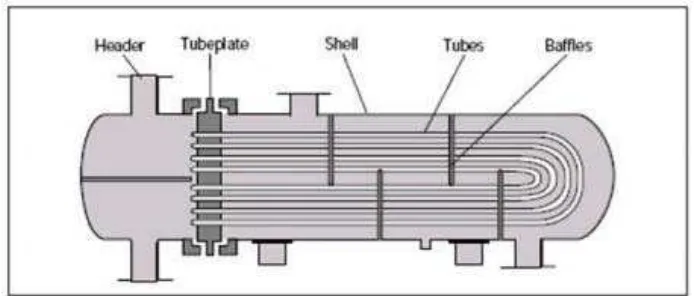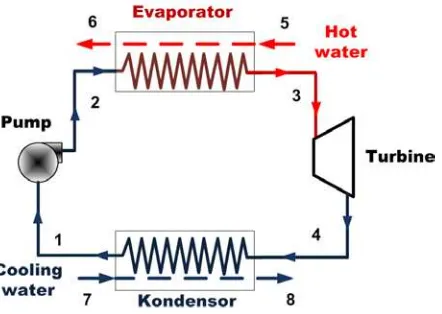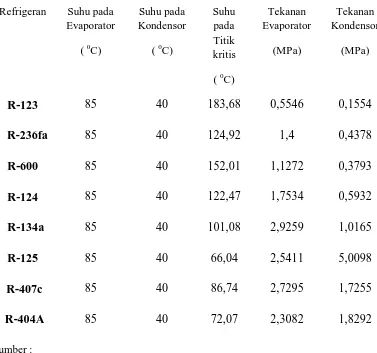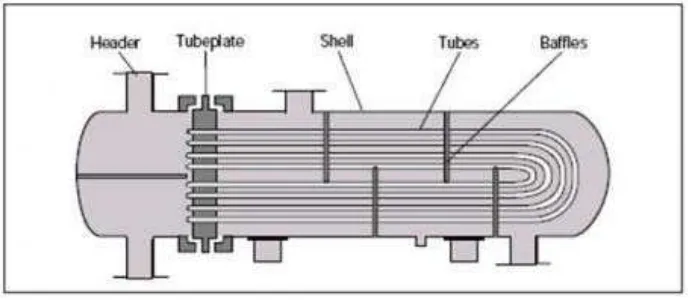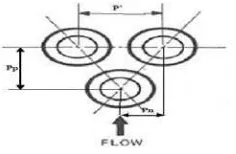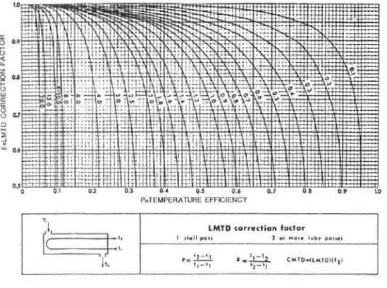PERANCANGAN KONDENSOR PADA SIKLUS RANKINE ORGANIK DENGAN KAPASITAS 1 MW
SKRIPSI
Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
EGO DEAR W SINAGA NIM. 05 0401 050
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karna
atas kasih dan kebaikan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas sarjana
ini dengan baik.
Tugas sarjana ini merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa
sebagai sarjana S-1 jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Sumatera
Utara. Adapun judul tugas sarjana ini adalah “ PERENCANAAN KONDENSOR
PADA SIKLUS RANKINE ORGANIK DENGAN KAPASITAS 1 MW “
Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih
kepada :
1. Bapak Ir.Mulfi Hazwi,M.Sc selaku Dosen pembimbing yang telah banyak
membantu dan mengajari pembimbing dalam penulisan dan penyelesaian
skripsi ini.
2. Bapak Ir. Isril Amir dan Bapak Tulus Burhanuddin Sitorus,ST,MT selaku
Dosen pembanding yang telah bersedia memberikan waktu dan
membimbing selama proses perbaikan hasil seminar
3. Bapak Dr-Ing Ir. Ikhwansyah Isranuri, selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin
Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak Tulus Burhanuddin,ST,MT selaku sekretaris Jurusan Teknik Mesin
Universitas Sumatera Utara.
5. Kedua orang tua saya yang telah banyak memberikan semangat dan
motivasi. Terima kasih untuk kasih sayang dan doa-doa kalian. I love you.
6. Kakak – Kakak ku yang baik ( kak Wince, kak Henni, kak Nora ). Terima
kasih untuk perhatian dan doa-doa nya.
7. Teman-teman TA ORC lae Payung ( ‘ paket kita lae...’ ), lae Dikki,
lae Jongat, lae David.
10.Kak Tetty dan B’Joy serta semua pelayan pemuda terima kasih untuk
dukungan doa-doa nya.
11.Franky dan Martogi serta teman – teman TS’04 Hanna,Hendra, Jubel,
Marta,Hetty, dll. Terima kasih untuk dukungan nya.
12.Semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas ini yang
tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
Penulis juga menyadari bahwa Tugas sarjana ini masih jauh dari
sempurna, maka dari itu penulis menerima segala saran maupun masukan yang
membangun untuk kebaikan penulisan Tugas sarjana ini.
Medan, November 2010
Penulis
ABSTRAK
Siklus Rankine Organik yang merupakan proses pengkonversi energi
hasil modifikasi siklus Rankine. Dengan menggunakaan bahan organik bertitik
didih rendah, ORC dapat digunakan untuk mengekstrak energi dari sumber panas
bersuhu rendah.
Dengan pemilihan jenis bahan organik yang sesuai, ORC mampu menghasilkan
efisiensi pembangkitan energi listrik yang lebih tinggi. Dalam perancangan ini
digunakan fluida kerja R-123.
Perancangan kondensor pada siklus rankine organic dengan
menggunakan fluida kerja R-123 dilakukan dengan perhitungan analisa
perpindahan panas secara konveksi yang selanjutnya dilakukan perhitungan
kerugian kalor dan penurunan tekanan pada kondensor, dari
perhitungan-perhitungan tersebut kemudian akan didapat geometri dari kondensor yang
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Gambar Diagram Siklus Rankine Organik
Gambar 1.2 Gambar Diagram T-S
Gambar 2.1 Gambar Kondensor
Gambar 2.2 Gambar Shell and Tube Kondensor
Gambar 2.3 Gambar Kondensor Shell and Coil
Gambar 2.4 Gambar Tubes and Tube Kondensor
Gambar 2.5 Gambar Evaporativ Kondensor
Gambar 2.6 Gambar Jenis-Jenis Buffle
Gambar 2.7 Gambar Lay-out Tube Kondensor
Gambar 2.8 Gambar Finned Tubes
Gambar 3.1 Diagram Alir Siklus Rankine
Gambar 4.1 Gambar U-Tube Kondensor
Gambar 4.2 Gambar Susunan Tube Segitiga
Gambar 4.3 Grafik Faktor Koreksi LMTD
DAFTAR NOTASI
SIMBOL KETERANGAN SATUAN
A,atas Luas Proyeksi Permukaan dinding atas m2
A,depan Luas Proyeksi Permukaan dinding depan m2
Do Diameter dalam tube mm
Di Diameter luar tube mm
Ds Diameter shell kondensor mm
f Koefisien Gesekan Fluida -
Fc Faktor Koreksi -
g Gravitasi m/s2
h1 Entalpi refrigeran masuk kondensor kJ/kg
h2 Entalpi refrigeran keluar kondensor kJ/kg
hi Koefisien Konveksi panas aliran internal W/m2.K
ho Koefisien Konveksi panas aliran eksternal W/m2.K
k Konduktivitas panas material W/m.K
kl Konduktivitas panas material pada fasa cair W/m.K
kv Konduktivitas panas material pada fasa uap W/m.K
L Panjang tube m
LMTD Rata-rata beda suhu logaritmik 0C
m laju aliran massa Kg/s
NuD Bilangan Nusselt
P Tekanan Pada kondensor Pa
Pr Bilangan Prandtl -
Prw Bilangan Prandtl fluida pada tube -
R Tahanan panas pada material ft2F/Btu
Re Bilangan Reynold -
Tcoil suhu rata-rata permukaan tube kondensor 0C
T,o suhu fluida 0C
T,r,i suhu refrigerant memasuki kondensor 0C
T,r,o suhu refrigerant keluar kondensor 0C
T,sat suhu saturasi refrigerant pada kondensor 0C
U Perpindahan panas global W/m2K
Uo Perpindahan panas global eksternal W/m2K
V Kecepatan aliran air m/s
ηp Efisiensi fluida %
υ Viskositas dinamik fluida kerja Pa.s
υL Viskositas dinamik fluida kerja pada keadaan jenuh Pa.s
π konstanta (phi) -
ρ Massa jenis fluida kerja kg/m3
ρL Massa jenis fluida kerja pada fasa cair kg/m3
ABSTRAK
Siklus Rankine Organik yang merupakan proses pengkonversi energi
hasil modifikasi siklus Rankine. Dengan menggunakaan bahan organik bertitik
didih rendah, ORC dapat digunakan untuk mengekstrak energi dari sumber panas
bersuhu rendah.
Dengan pemilihan jenis bahan organik yang sesuai, ORC mampu menghasilkan
efisiensi pembangkitan energi listrik yang lebih tinggi. Dalam perancangan ini
digunakan fluida kerja R-123.
Perancangan kondensor pada siklus rankine organic dengan
menggunakan fluida kerja R-123 dilakukan dengan perhitungan analisa
perpindahan panas secara konveksi yang selanjutnya dilakukan perhitungan
kerugian kalor dan penurunan tekanan pada kondensor, dari
perhitungan-perhitungan tersebut kemudian akan didapat geometri dari kondensor yang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Energi memiliki peranan penting dalam menunjang kehidupan manusia.
Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan akan energi pun terus meningkat.
Untuk dapat memenuhi kebutuhan energi yang digunakan oleh manusia maka
perlu dilakukan pemanfaatan energi yang tersedia di alam secara optimal.
Di Indonesia sendiri terdapat banyak sumber daya alam seperti panas
bumi dan apabila dimanfaatkan secara optimal tentunya akan dapat membantu
dalam memenuhi kebutuhan energi khusus nya di negara ini. Namun hal ini belum
dapat lakukan mengingat beberapa sumber panas ini hanya menghasilkan uap
dengan panas dan tekanan yang rendah, dimana suhu uap berkisar antara
80-1700C dengan tekanan yang rendah berkisar 3 bar jadi masih belum bisa
dimanfaatkan secara langsung jika menggunakan sistem pembangkit tenaga
berdasarkan siklus rankine yang menggunakan fluida kerja air untuk
menghasilkan uap.
Dengan kondisi ini maka agar sumber daya alam yang ada dapat
dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan oleh
manusia maka penggunaan Organik Rankine Cycle (ORC) bisa dijadikan
alternatif dalam memanfaatkan energi yang ada ini. Adapun organik rankine
cycle atau siklus rankine organik ini merupakan sistem pembangkit tenaga yang
menggunakan fluida organik sebagai fluida kerja nya. Kerja siklus ini sama
dengan siklus rankine konvensional yang membedakan nya hanyalah jenis fluida
kerja yang digunakan. Jika pada siklus rankine konvensional menggunakan fluida
kerja air maka pada siklus rankine organik menggunakan cairan organik sebagai
fluida kerja.
Sistem ini dipilih atas dasar karakteristik kerja ORC yang mampu
mengubah fluida kerja menjadi uap dengan menggunakan panas rendah dari
panas bumi, memanfaatkan panas terbuang, ataupun memanfaatkan panas
menguap pada suhu rendah (dibawah 1000C). Sehingga dengan sistem ini panas
bumi yang ada bisa dimanfaatkan.
Komponen utama siklus rankine organik yang paling sederhana adalah
pompa, evaporator, turbin dan kondensor. Selain fluida kerja perbedaan utama
siklus Rankine konvensional dan siklus rankine organik adalah terletak pada
evaporator. Jika siklus Rankine konvensional menggunakan boiler maka siklus
rankine organik menggunakan evaporator.
Cara kerja siklus rankine organik yang digunakan dalam pembangkit
listrik yang menggunakan fluida kerja cairan organik, hampir sama dengan siklus
rankine konvensional dimana cairan organik dipompa ke evaporator kemudian
dalam evaporator dialirkan sumber panas bumi (geothermal water) dengan suhu
yang mencapai 800C-1000C akan mengubah cairan organik dari cair menjadi uap.
Uap panas kemudian disalurkan ke turbin yang berfungsi menggerakkan
generator dan menghasilkan listrik. Kemudian uap tersebut diteruskan ke
kondensor dan dicairkan kembali untuk kemudian diteruskan ke pompa dan
kemudian mengulangi siklus. Gambar berikut menunjukkan prose siklus rankine
organik yang menggunakan geothermal water.
Dengan siklus rankine organik dapat yang dapat menggunakan suhu
panas rendah yaitu lebih rendah dari 100 derajat celcius (+80 derajat) maka selain
dapat memanfaatkan sumber panas bumi ( geothermal water ) juga dapat
memanfaatkan tenaga surya, waste energy maupun biomassa.
Sementara untuk fluida kerja yang dipakai dalam siklus rankine organik
haruslah memenuhi aspek keamanan lingkungan dan keamanan dalam
penggunaannya yakni nilai potensi pemanasan global dan penipisan lapisan ozon
yang dapat ditimbulkan, serta kemudahan dalam mendapatkan nya. Untuk itu
perlu dipilih fluida kerja yang optimal. Tabel berikut menunjukkan beberapa
cairan organik yang dapat digunakan sebagai fluida kerja yang telah memenuhi
standar keamanan lingkungan.
Tabel 1.1 : Literature review on ORC
Refrigerant
Suhu pada Evaporator
( oC)
Suhu pada kondensor
( oC)
Suhu pada Titik Kritis
( oC)
R-236fa 85 40 124,92
R-123 85 40 183,68
R-600 85 40 152,01
R-124 85 40 122,47
R-134a 85 40 101,08
R-125 85 40 66,04
R-407c 85 40 86,74
R404A 85 40 72,07
(Sumber : Organic Rankine cycle using low-temperature geothermal heat
Untuk mempermudah penganalisaan termodinamika siklus ini, proses-proses
diatas dapat di sederhanakan dalam diagram berikut :
Gambar 1.2 Diagram T-S Siklus Rankine Organik
Dari diagram T-S diatas dapat dilihat bahwa untuk siklus rankine organik
fluida kerja dipanaskan pada suhu dibawah 1000C ( 850C ) di evaporator berbeda
dengan siklus rankine konvensional yang fluida kerja nya dipanaskan hingga
mencapai suhu 1000C, hal ini tentunya dapat menyebabkan berkurang nya energi
untuk memanaskan fulida hingga menghasilkan uap. Berdasarkan diagram diatas
terdapat 4 proses dalam siklus Rankine organik :
Proses 1: Fluida organik dipompa ke evaporator dari bertekanan rendah ke
tekanan tinggi dalam bentuk cair. Proses ini membutuhkan sedikit input
energi.
Proses 2: Fluida organik cair masuk ke evaporator di mana fluida dipanaskan
hingga menjadi uap pada tekanan konstan menjadi uap jenuh
desuperheating.
Proses 4: Uap basah memasuki kondensor di mana uap diembunkan dalam
tekanan dan temperatur tetap hingga menjadi cairan jenuh.
Dalam siklus Rankine ideal, pompa dan turbin adalah isentropic Maka
analisa pada masing-masing proses pada siklus untuk tiap satu-satuan massa dapat
ditulis sebagai berikut:
1) Kerja pompa : ( 2 1)
.
h h m Wp = −
2) Penambahan kalor pada ketel : ( 3 2)
.
h h m Qin = −
3) Kerja turbin : ( 3 4)
.
h h m WT = −
4) Kalor yang dilepaskan dalam kondensor : ( 4 1)
.
h h m Qout = −
5) Efisiensi termal siklus :
e p
T th
Q W
W
+ =
η
Dimana :
.
m = Laju aliran massa (kg/s)
h = entalphi (kj/kg)
WT = Daya Turbin (W)
Qin = Kalor masuk (kJ/s)
1.2 Tujuan Perancangan
Adapun tujuan dari perancangan ini adalah :
a. Mahasiswa dapat menentukan jenis dan kebutuhan fluida organik untuk memenuhi kebutuhan sistem pembangkit tenaga berdasarkan siklus rankine
organik dengan kapasitas 1 MW.
b. Mahasiswa dapat merancang kondensor untuk memenuhi kebutuhan sistem pembangkit tenaga berdasarkan siklus rankine organik dengan kapasitas
1MW.
c. Mahasiswa dapat mengetahui keekonomisan dari refrigerant yang dipakai.
1.3 Manfaat Perancangan
Manfaat dari perancangan ini bagi pangembangan IPTEK adalah dapat
menjadi salah satu alternatif dalam rangka pemanfaatan sumber daya panas
bumi. Karena dalam sitem pembangkit ini tidak memerlukan panas yang tinggi
(850C), dan dapat terpenuhi oleh sumber panas bumi yang ada di Indonesia.
1.4 Batasan Masalah
Kondensor yang direncanakan akan digunakan pada proses pendistribusian
fluida organik pada sistem pembangkit tenaga berdasarkan siklus rankine organik.
Pembahasan perencanaan ini dibatasi pada :
a. Penentuan fluida organik.
b. Penentuan kebutuhan fluida organik pada sistem pembangkit tenaga
bersadarkan siklus rankine organik dengan kapasitas 1 MW.
c. Penentuan spesifikasi teknik kondensor.
1.5 Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
a. BAB I : Berisi latar belakang penelitian, Tujuan, Batasan masalah.
Pada bagian latar belakang berisi tentang pengertian dan proses siklus
rankine organik.
b. BAB II : Tinjauan Pustaka berisikan tentang teori-teori kondensor,
jenis-jenis dan cara kerja kondensor.
c. BAB III : Pemilihan fluida kerja, berisikan tentang penjelasan dari
siklus termodinamik dan pemilihan dari fluida kerja yang sesuai untuk
perancangan pembangkit tenaga berdasarkan siklus rankine organik
dengan menggunakan rumus-rumus yang sesuia.
d. BAB IV : Analisa perpindahan panas, dan menentukan ukuran –
ukuran utama kondensor. Berisikan tentang perhitungan-perhitungan
untuk mendapatkan ukuran-ukuran dari kondensor berdasarkan dengan
analisa perpindahan panas.
e. BAB V : Hasil dan Pembahasan, pada bagian ini membahas tentang
pemilihan jenis kondensor yang sesuai, serta perhitungan bagian-bagian
kondensor.
f. BAB VI : Kesimpulan, berisikan tentang pemaparan hasil dari
perencanaan kondensor dan bagian-bagian nya.
1.6 Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
g. BAB I : Berisi latar belakang penelitian, Tujuan, Batasan masalah.
Pada bagian latar belakang berisi tentang pengertian dan proses siklus
rankine organik.
h. BAB II : Tinjauan Pustaka berisikan tentang teori-teori kondensor,
jenis-jenis dan cara kerja kondensor.
i. BAB III : Pemilihan fluida kerja, berisikan tentang penjelasan dari
siklus termodinamik dan pemilihan dari fluida kerja yang sesuai untuk
perancangan pembangkit tenaga berdasarkan siklus rankine organik
dengan menggunakan rumus-rumus yang sesuia.
j. BAB IV : Analisa perpindahan panas, dan menentukan ukuran –
ukuran utama kondensor. Berisikan tentang perhitungan-perhitungan
untuk mendapatkan ukuran-ukuran dari kondensor berdasarkan dengan
analisa perpindahan panas.
k. BAB V : Hasil dan Pembahasan, pada bagian ini membahas tentang
pemilihan jenis kondensor yang sesuai, serta perhitungan bagian-bagian
kondensor.
l. BAB VI : Kesimpulan, berisikan tentang pemaparan hasil dari
perencanaan kondensor dan bagian-bagian nya.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pandangan Umum Tentang Kondensor
Didalam sistem kompresi uap (vapor compression) kondensor adalah suatu
komponen yang berfungsi untuk merubah fase refrigerant dari uap bertekanan
tinggi menjadi cairan bertekanan tinggi atau dengan kata lain pada Kondensor ini
terjadi proses kondensasi. Refrigerant yang telah berubah menjadi cair tersebut
kemudian dialirkan ke evaporator melalui pompa.
Sumber : Shell and tube exchangers design
Gambar 2.1 Kondensor
Prinsip kondensasi di kondensor adalah menjaga tekanan uap Superheat
Refrigerant yang masuk ke kondensor pada tekanan tertentu kemudian suhu
Refrigerantnya diturunkan dengan membuang sebagian kalornya ke medium
pendingin yang digunakan di kondensor. Sebagai medium pendingin digunakan
udara dan air atau gabungan keduanya. Dalam perancangan ini akan digunakan air
sebagai media pendingin.
Pada proses pendinginan (cooling) cairan Refrigerant yang menguap di
dalam pipa-pipa Cooling Coil (evaporator) telah menyerap panas sehingga
berubah wujudnya menjadi gas dingin dengan kondisi superheat pada saat
dibuang atau dipindahkan ke suatu medium lain sebelum ia dapat kembali diubah
wujudnya menjadi cair untuk dapat mengulang siklusnya kembali.
2.2 Komponen – komponen utama pada Kondenser
Kondensor pada umumnya memiliki beberapa komponen utama, dimana
masing – masing komponen memiliki fungsinya tersendiri. Adapun
komponen-komponen utama dari kondensor adalah sebagai berikut :
1. Suction Pipe dan Discharge Pipe ( Pipa saluran masuk dan pipa saluran keluar )
a. Suction Pipe
Suction Pipe adalah pipa saluran masuk untuk masuknya media pendingin
ke dalam kondenser,yang mana media pendingin itu berupa fluida cair yang
bertekanan yang merupakan hasil dari pemampatan di kompresor.
b. Discharge Pipe
Discharge pipe adalah pipa saluran keluar Refrigerant dari kompresor
melalui tube ke tangki receiver.
2. Tube ( Pipa dalam Kondenser )
Tube adalah pipa aliran yang dilalui Refrigerant yang bertekanan dan
panas yang merupakan hasil dari turbin melalui suction pipe dan akan disalurkan
ke discharge pipe dan kemudian diterima oleh tangki receiver.
Umumnya terdapat empat susunan tube yaitu ,Triangular ( 30o ),
Gambar 2.3 Lay-out pada tube
Susunan triangular memberikan nilai perpindahan panas yang lebih baik
bila dibandingkan dengan susunan rotate square dan square karena dengan
susunantriangular dapat menghasilkan turbulensi yang tinggi, namun
begitu tube yang disusun secara triangular akan menghasilkan pressure drop (
penurunan tekanan ) yang lebih tinggi dari pada susunan rotate
square dan square. Apabila fluida yang digunakan memiliki tingkat fouling yang
tinggi dan memerlukan pembersihan secara mekanik (mechanical cleaning )
susunan tube secara triangular tidak digunakan, sebaiknya digunakan
susunan square, apabila jenis cleaning yang digunakan adalah chemical
cleaning, maka susunan tube secara triangular dapat diperimbangkan kembali,
mengingat untuk chemical cleaning tidak memerlukan akses jalur ruang ( acess
lanes ) yang lebih seperti pada mechanical cleaning.
3. Baffle
Sumber : Engineering Data Book, 9th Edition
Gambar 2.2 Jenis – jenis baffle yang ada pada tube
2.3 Cara Kerja Kondenser
Uap panas yang masuk ke kondensor dengan temperatur yang tinggi dan
bertekanan yang merupakan hasil proses dari turbin. Kemudian uap panas masuk
ke dalam Suction Pipe dan kemudian mengalir dalam tube. Dalam tube, uap panas
didinginkan dengan media pendingin air yang dialirkan melewati sisi luar tube,
BAB III
PEMILIHAN FLUIDA KERJA
3.1 Analisa Termodinamika Siklus Rankine Organik
Diagram alir siklus rankine organik dapat dilihat seperti gambar berikut
Gambar 3.1 Diagram alir siklus rankine organik
Untuk mempermudah penganalisaan termodinamika siklus ini,
proses-proses diatas dapat disederhanakan dalam diagram T-s sebagai berikut :
Proses-proses pada setiap titik dapat diuraikan sebagai berikut :
• titik 1: Fluida dipompa dari bertekanan rendah ke tekanan tinggi dalam bentuk
cair Proses ini membutuhkan sedikit input energi.
• titik 2: Fluida cair bertekanan tinggi masuk ke evaporator di mana fluida
dipanaskan hingga menjadi uap pada tekanan konstan menjadi uap jenuh.
• titik 3: Uap jenuh bergerak menuju turbin, yang kemudian dapat dimanfaatkan
untuk menghasilkan energi listrik. Hal ini mengurangi temperatur dan tekanan
uap.
• Proses 4: Uap basah memasuki kondensor di mana uap diembunkan dalam
tekanan dan temperatur tetap hingga menjadi cairan jenuh.
Analisa pada masing-masing proses pada siklus untuk tiap satu-satuan
massa dapat ditulis sebagai berikut:
6) Kerja pompa : ( 2 1)
9) Kalor yang dilepaskan dalam kondensor : ( 4 1)
.
h h m Qout = −
Efisiensi termal siklus :
e
Dalam hal ini ada beberapa parameter suhu yang perlu ditetapkan sebagai
tahap awal perencanan yaitu suhu refrigerant dan suhu air dingin. Suhu refrigerant
dalam evaporator direncanakan 850C dan suhu refrigerant keluaran kondensor
sebesar 400C. adapun sebagai media pendingin akan digunakan air,temperatur air
di permukaan ditentukan oleh adanya pemanasan (heating) di daerah tropis dan
pendinginan (cooling) di daerah dataran tinggi. Kisaran harga temperatur air
dipermukaan adalah -2o s.d. 35oC (sumber : Equation of State of Water ). Maka
3.2 Pemilihan Fluida Kerja Berdasarkan Perhitungan Termodinamika.
Pemilihan refrigerant sebagai fluida kerja yang sesuai untuk dipakai
sebagai fluida kerja dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perhitungan
termodinamika pada tiap-tiap fluida kerja yang ada untuk kemudian dipilih yang
paling sesuai dan fluida kerja yang akan dipilih haruslah memenuhi persyaratan
lingkungan agar tidak merusak lapisan ozon. Beberapa fluida kerja yang telah
memenuhi persyaratan keamanan lingkungan seperti yang terdapat pada table
berikut :
Tabel 3.1 : Sifat fisik dari Refrigerant
Refrigeran Suhu pada Evaporator
( 0C)
Suhu pada Kondensor
( 0C)
Suhu pada Titik kritis ( 0C)
Tekanan Evaporator
(MPa)
Tekanan Kondensor
(MPa)
R-123 85 40 183,68 0,5546 0,1554
R-236fa 85 40 124,92 1,4 0,4378
R-600 85 40 152,01 1,1272 0,3793
R-124 85 40 122,47 1,7534 0,5932
R-134a 85 40 101,08 2,9259 1,0165
R-125 85 40 66,04 2,5411 5,0098
R-407c 85 40 86,74 2,7295 1,7255
R-404A 85 40 72,07 2,3082 1,8292
Berikut adalah perhitungan termodinamika dari fluida kerja yang akan
dipilih.
3.2.1 Refrigerant R-123
Refrigerant R-123 atau HCFC-123 adalah pendingin yang dirancang untuk
menggantikan R-11 untuk digunakan sebagai pendingin dimana tekanannya
rendah dan menyediakan effisiensi energi yang sangat baik. Refrigerant ini ramah
lingkungan dengan nilai ODP (Ozon Depleting potensial) nol dan GWP (Global
Warming Potensial) yang dapat diabaikan dan hemat energi. Refrigerant ini
dianggap praktis karena tidak beracun jika tertelan ataupun terhirup, tapi
refrigerant ini bisa menimbulkan iritasi jika terkena kulit dan sedikit mengganggu
mata karena terasa perih. Sedangkan dalam konsentrasi uap tinggi bisa
mengganggu sistem pernafasan dan sistem saraf pusat seperti pusing, sakit kepala
dan mengantuk. Oleh karena itu, untuk menghindari segala kemungkinan yang
tidak diinginkan dan supaya bekerja dengan prosedur yang benar, diperlukan
pengetahuan tentang karakteristik refrigerant ini.
Adapun karakterisrik fisik daripada refrigerant R-123 ini adalah sebagai
berikut :
1. properti kimia : cairan tak berwarna dan bau samareter
2. rumus kimia : CHCl2CF3
3. nama kimia : 2,2dichloro-1,1,1-trifluoroethane
4. titik didih : 27,85 0C pada tekanan 1 Atm.
5. titik kritis : 183,680C
6. massa jenis pada titik kritis : 550 kg/m3
a. Perhitungan Daya Kerja Turbin
Sifat fisik R-123 masuk ke turbin :
keadaan R-123 keluar dari turbin :
T4 = 40 0C
h4 = 404,1 kJ/kg (table : HCFC-123 saturatian properties – temperature )
hingga dapat dihitung :
Wt = ( h3-h4 )
= (430,76 – 404,1) kJ/kg
= 26,66 kJ/kg
b. Perhitungan Daya Kerja Pompa
Keadaan R-123 saat dihisap oleh pompa :
T1 = 40 0C
v = 0,000702 m3/kg
P1 = 154,48 kPa
h1 = 256,35 kJ/kg
keadaan R-123 keluar dari pompa :
T2 = 85 0C
P2 = 554,69 kPa
h2 = 287,78 kJ/kg
Kerja pompa :
Wp = v ( P2-P1 )
= 0,28094742 kJ/kg
c. Perhitungan pada kondensor
(Qout) = ( h4 – h1 )
= (404,1 – 256,35) kJ/kg
= 147,75 kJ/kg
d. Efisiensi Termal
e p
T th
Q W
W
+ =
η
kJ/kg 147,75 kJ/kg
0,28094742
kJ/kg 26,66
+ =
th
η
= 18 %
e. Laju aliran massa uap
Laju aliran massa yang melalui turbin ditentukan dari persamaan :
Wt = ( h3-h4 )
Dimana :
Wt = daya turbin ( W )
= laju aliran massa ( kg/s )
h3,h4 = enthalpy (kJ/kg )
Daya turbin :
t m g T
Wg W
η η η . .
=
dimana : efisiensi generator (
η
g ) = 0.97maka didapat daya turbin
kW kW
Wg W
t m g
T 1231,399
) 92 , 0 )( 91 , 0 )( 97 , 0 (
1000 .
. = =
=
η η
η
hingga dapat dihitung :
Wt = ( h3-h4 )
1231,399 kW = (430,76 – 404,1) kJ/kg
= 46,189 kg/s
Gambar 3.2 Diagram P – h refrigerant R-123
Dengan cara yang sama dilakukan perhitungan untuk masing-masing
Refrigerant
Tekanan Evaporator
(Pc) Mpa
Tekanan Kondensor
(Pc) Mpa
Laju Aliran Massa
( ṁ) kg/s
Kalor yang Keluar (Qout) kJ/kg
Effisiensi Thermal
(ηt) %
Suhu pada Titik Kritis
(Tc) 0C
Kerja Turbin (WT) kJ/kg
Kerja Pompa
WP kJ/kg
R-236fa 1,4 0,4378 47,728 137,2 18,7 124,92 25,8 0,3751
R-123 0,55469 0,15448 46,189 147,79 18 183,68 26,66 0,28094
R-600 1,1272 0,3793 20,1406 345,14 17,64 152,01 61,14 1,3483
R-124 1,7534 0,5932 55,974 135,5 16,3 122,47 22,01 0,9265
R-134a 2,9259 1,0165 147,82701 163,23 5,05 101,08 8,33 1,661176
R-125 2,5411 5,0098 1172,76 93,98 1,11 66,04 1,05 0,488
R-407c 2,7295 1,7255 456,073 168,3 1,55 86,74 2,7 0,903
Dalam pemilihan fluida kerja yang digunakan harus memenuhi persyaratan
lingkungan supaya tidak merusak lapisan ozon dan potensi pemanasan global, dan
memastikan effisiensi termal dan kerja turbin yang tinggi karena.tidak ada fluida
kerja yang memenuhi semua persyaratan, namun yang optimal harus dipilih.
Dari analisa delapan refrigerant diatas dapat dilihat setiap karakteristik
refrigerant, dimana untuk perencanaan ini dipilih refrigerant yang memiliki tekanan
pompa yang rendah sehingga tidak memerlukan energi yang besar pada saat
memompakan fluida ke evaporator, juga harus memiliki efisiensi termal yang tinggi
sehingga dapat menghasilkan energi yang besar, disamping juga dilihat faktor
keamanan terhadap lingkunngan. Melihat perhitungan sifat-sifat fisik dari berbagai
refrigerant (table 3.1), dapat dilihat efisiensi yang lebih tinggi yaitu refrigerant
R-236fa berkisar 18,7%. Namun jika dilihat dari tekanan pada evaporator berkisar 14
bar, dan daya kerja turbin hanya berkisar 25,8 kJ/kg sehingga refrigerant ini kurang
optimal. Jika dibandingkan dengan refrigerant R-123 efisiensinya 18%, tekanan
pada evaporator hanya berkisar 5,54 bar dan daya kerja turbin berkisar 26,6 kJ/kg
maka refrigerant ini lebih optimal dibanding R-236fa.
Sehingga dalam perancangan ini digunakan Refrigerant R-123 untuk
pengembangan sistem pembangkit tenaga berdasarkan siklus rankine organik karena
BAB IV
ANALISA PERPINDAHAN PANAS KONDENSOR 4.1 Perencanaan Kondensor
Dalam perencanaan ini kondensor yang akan direncanakan adalah jenis shell
and tube condensor. Refrigerant mengalir dalam tube kondensor sedangkan air akan
dialirkan melewati gugusan tube kondensor. air yang melewati tube kondensor akan
menyerap kalor refrigerant sementara refrigerant yang bertukar panas dengan air akan
mengalami kondensasi.
Sumber : Shell and tube exchangers design
Gambar 4.1 U-tube kondensor
Dalam perencanaan ini, tube kondensor direncanakan dari bahan tembaga
(copper), sedangkan shell direncanakan dari bahan baja (stell). Berdasarkan data dari
tabel 3.1 (hal.19) untuk refrigerant yang dipilih yaitu R-123 dengan laju aliran massa
sebesar 46,189 kg/s, Qout = 147,79 KJ/kg dan tekanan pada kondensor sebesar
0,15448 Mpa dan suhu masuk kondensor (T,ri ) = 500C dan suhu keluar kondensor
(T,ro) direncanakan sebesar 400C.
Selanjutnya akan dilakukan perhitungan dimensi kondensor berdasarkan
analisa perpindahan panas yang terjadi.
4.2 Perpindahan Panas Konveksi Eksternal
Perpindahan panas aliran eksternal terjadi disebelah luar tube karena air
yang mengalir menyilang melewati tube. Temperatur tube pada kondensor, berkisar
Temperatur refrigeran rata-rata ( T,r ) = C
Untuk menentukan susunan tube yang sesuai, akan dilakukan beberapa
perhitungan untuk mengetahui susunan tube yang bagaimanakah yang dapat
menghasilkan koefisien perpindahan panas konveksi eksternal terbesar. Untuk
menghitung koefisien konveksi aliran eksternal terlebih dahulu dihitung bilangan
Nusselt berdasarkan korelasi empiris yang dirumuskan oleh Zhukauskas.
(
)
4(Literatur : Incropera, Frank P. And David P. Dewitt, “fundamental of Heat and
Mass Transfer” hal.380 ) Nilai C dan n didapat dari tabel pada [ Lampiran 9 ].
Koefisien pindahan panas konveksi dapat dicari dengan rumus :
D
(Literatur : Incropera, Frank P. And David P. Dewitt, “fundamental of Heat and
Mass Transfer” hal.369 ).
Berikut akan dilakukan perhitungan koefisien pindahan panas konveksi
aliran eksternal terhadap susunan tube yang ada pada tabel 4.1 dengan kecepatan air
pada sisi masuk shell direncanakan 1 m/s. Sebagai contoh akan diambil data dari
tabel 4.1 yaitu : Diameter luar tabung (OD) = 0.75 in (19,05 mm )
Sp = PP = 0,814 in ( 20,6756 mm )
Sn = P’ = 0,938 in ( 23,8252 mm )
Bentuk susunan tube adalah segitiga.
4.2.1 Perpindahan Panas Konveksi Aliran Eksternal Ketika Refrigeran Mengalami Proses Desuperheating
Berdasarkan hasil penelitian laboratorium pendingin seltech bahwa
temperature tube pada kondensor berkisar 3 – 4oC lebih rendah dari temperatur
refrigeran. Pada saat proses Desuperheating temperatur masuk refrigeran (T,ri) =
500C dan temperatur refrigeran keluar proses Desuperheating (T,ro) = 400C. Maka
temperatur refrigeran rata-rata :
C
Sehingga diperoleh temperatur coil (Tcoil) = 45-3= 420C.
Temperatur air masuk (T,air in) = 300C
Temperatur air keluar (T,air out) = 37,010C
Sifat –sifat fluida air dievaluasi pada tekanan atmosfer dan suhu film maka :
C
Kecepatan maksimum air, Vmax :
Sehingga
(
)
4 1 36
, 0 max
Pr Pr Pr
Re, ,
=
w n
D
D C x x
Nu
Nu,D = 0,36(133306,1011)0,6 (4,75)0,36 (4,75/3,48)1/4 = 810,2159
Dan W m K
D k Nu
ho D 96,703 / .
01905 , 0
) 0022 , 0 ( 2159 , 810
. 2
,
= =
=
Dengan cara yang sama dapat dihitung nilai koefisien perpindahan panas
untuk berbagai jenis susunan tube berdasarkan tabel 4.1 dan hasil nya dapat dilihat
Dari hasil perhitungan nilai koefisien konveksi aliran eksternal untuk
masing-masing susunan tube maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :
1. Diameter Tube dari tipe susunan tube yang triangular dengan diameter tube
0,750 in memiliki nilai koefisien perpindahan panas eksternal yang besar.
2. Susunan Tube, Untuk susunan tube dengan selang-seling atau susunan tube
berbentuk triangular memiliki koefisien perpidahan panas yang lebih besar
dibanding dengan susunan tube yang segaris (inline).
Dari kesimpulan diatas maka dalam perencanaan ini akan dipilih tube dengan
susunan triangular dengan diameter nominal 5/8 in tipe L dan dari lampiran
[ L.11] maka diperoleh ukuran tube dengan :
Outer diameter (OD) : 0,75 in ( 19,05 mm )
Inside diameter (ID) : 0,67 in ( 16,92 mm )
Tebal dinding tube : 1,07 mm
Susunan tube : Sn = 0,938 in (23,8252 mm) dan
SP = 0,814 in ( 20,6756 mm)
Kecepatan air pada sisi shell adalah 1 m/s besar nya nilai koefisien konveksi aliran
eksternal adalah ho = 96,703 W/m2.K
dan temperatur refrigeran keluar proses kondensasi (T,ro) = 400c dalam bentuk
fasa cair. Sehingga diperoleh temperatur rata-rata yaitu
C
Sehingga diperoleh temperatur tube Tcoil = 40 – 4 = 360C. Temperatur air masuk
300C sifat fluida (air) dievaluasi pada tekanan atmosfer dan temperatur film,
)
Dari tabel R-123 diperoleh :
3
Kecepatan maksimum air, Vmax :
Dimana nilai dari (Sn/Sp) = 1,1523 maka nilai C = 0,35 (Sn/Sp)1/5 = 0,36 dan dari
Besarnya nilai koefisien konveksi aliran eksternal ketika refrigeran mengalami
proses kondensasi adalah ho = 87,1664 W/m2.K.
4.3 Laju Perpindahan Panas Konveksi Aliran Internal
Laju perpindahan panas konveksi aliran internal ini terdiri dari dua jenis yaitu :
4.3.1 Laju Perpindahan panas Konveksi Aliran Internal ketika refrigeran Mengalami proses Desuperheating
Pada proses ini refrigeran ( R-123 ) keluar dari pipa buang pada fasa
uap 500C, suhu kondensasi untuk kondensor pendingin air direncanakan 400C,
tekanan saturasi yang bersesuaian dengan suhu kondensasi tersebuat adalah
154,48 kPa. Besar nya koefisien perpindahan panas konveksi internal dapat
dihitung dengan korelasi empiris dari Dittus-Boelter :
Korelasi empiris diatas berlaku untuk aliran turbulen, yaitu dengan bilangan
reynold diatas 10.000.
Sifat-sifat fisik R-123 dievaluasi pada tekanan (P) = 154,48 kPa dan
)
Laju aliran refrigeran total kondensor adalah 46,189 kg/s. maka bilangan Reynold
adalah :
Dengan Re,D > 10.000 berarti aliran yang terjadi adalah aliran turbulen.
Bilangan Nusselt :
Nu,D = 0,023.(ReD)4/5.Pr0,3
= 0,023 (1022797,4281)4/5 (221,64 )0,3
Koefisien konveksi :
4.3.2 Laju Perpindahan panas Konveksi Aliran Internal ketika refrigeran
Mengalami proses Kondensasi
Untuk menghitung besarnya laju perpindahan panas konveksi di dalam
tube ketika refrigeran mengalami proses kondensasi dapat dihitung dengan
menggunakan korelasi empiris yang diajukan oleh Chato :
4
Sifat-sifat fisik R-123 saturasi liquid dievaluasi pada saat Tsat = 40 0C.
3
3
Maka nilai dari h’fg dapat dicari seperti dibawah ini :
h’fg = hfg + 3/8 Cp,l (Tsat – Ts ) = 165,43 + 3/8 (1,041)(40 – 36 ) = 166,9915 kJ/kg
dengan demikian nilai koefisien konveksi karena proses kondensasi adalah :
4
4.4 Faktor Pengotoran (Fouling Factor)
Faktor pengotoran (fouling faktor ) adalah besarnya tahanan termal yang
terjadi karena adanya kotoran pada fluida kerja setelah sekian lama beroperasi.
Faktor pengotoran ini akan menghambat laju perpindahan panas dan membentuk
suatu tahanan termal. Dari lampiran [ L.11 ] diambil faktor pengotoran :
R’’f,i= 0,0002 m2K/W untuk refrigeran.
R’’f,o= 0,0002 m2K/W untuk air umpan ketel olahan.
Berdasarkan nilai faktor pengotoran diatas dapat dihitung nilai koefisien
4.4.1 Koefisien Perpindahan Panas Konveksi Aliran Eksternal Kotor Untuk Proses Desuperheating
4.4.2 Koefisien Perpindahan Panas Konveksi Aliran Eksternal Kotor Untuk Proses Kondensasi
4.4.3 Koefisien Perpindahan Panas Konveksi Aliran Internal Kotor Untuk Proses Desuperheating
4.4.4 Koefisien Perpindahan Panas Konveksi Aliran Internal Kotor Untuk Proses Kondensasi
4.5 Perpindahan Panas Global
4.5.1 Perpindahan Panas Global Tube yang Mengalami Proses
Desuperheating
Perpindahan panas global dapat dihitung dengan rumus :
o
382,43 W/m.K maka perpindahan panas global dapat dihitung :
K
Menentukan LMTD (beda temperatur rata-rata logaritmik) :
Dengan data-data sebagai berikut :
Tr,i = 500C dan Tr,o = 400C
T,wi = 300C dan T,wo = 37,010C
C
Dengan besarnya kalor yang dilepas kondensor pada saat desuperheating :
( , , )
Kondensor direncanakan dengan menggunakan n = 150 buah tube paralel tiap
pass, sehingga panjang tube dapat dicari dengan :
Q = Uo.Ao.n.LMTD.Fc
Gambar 4.2 grafik faktor koreksi LMTD
Berdasarkan grafik LMTD untuk nilai P dan R diatas didapat nilai Fc = 0,9. Maka
Q = Uo.Ao.n.LMTD.Fc
351036,4 J/s = 106,561 W/m2.K x 0,0598L m2 x 150 x 284,43 K x 0,9
L = 1,43 m
4.5.2 Perpindahan Panas Global Tube yang Mengalami Proses Kondensasi
Perpindahan panas global dapat dihitung dengan rumus :
i
383,48 W/m.K maka perpindahan panas global dapat dihitung :
K
Menentukan LMTD (beda temperatur rata-rata logaritmik) :
Dengan data-data sebagai berikut :
Tr,i = 500C dan Tr,o = 400C
T,wi = 300C dan T,wo = 37,010C
LMTD adalah beda temperatur rata-rata logaritmik dapat dihitung dengan :
T T T
T ) ( )
Dengan besarnya kalor yang dilepas kondensor pada saat kondensasi :
( , , )
. .
ro ri p
p T mc T T
c m
Q= ∆ = −
Dimana cp dievaluasi pada suhu T = 40 0C, maka :
s kJ Q=46,189(1,041)(50−40)=480,8275 /
Dengan :
2 0 D L (0,01905)L (0,0598L)m
A =π o =π =
Kondensor direncanakan dengan menggunakan n = 150 buah tube paralel tiap
pass, sehingga panjang tube dapat dicari dengan :
Q = Uo.Ao.n.LMTD.Fc
Dimana nilai faktor koreksi (Fc) diambil berdasarkan grafik faktor koreksi LMTD
pada gambar 4.2 maka didapat nilai Fc = 0,9
Q = Uo.Ao.n.LMTD.Fc
480827,5 J/s = 81,35623 W/m2.K x 0,0598L m2 x 150 x 284,43 K x 0,9
L = 2,57 m
Maka panjang tube untuk proses kondensasi L = 2,57 m
Jadi panjang total tube kondensor adalah total panjang tube untuk proses
desuperheating ditambah dengan total panjang tube untuk proses kondensasi
BAB V
PERENCANAAN GEOMETRI KONDENSOR 5.1 Perencanaan Shell Kondensor
Dalam perencanaan ini akan memakai kondensor dengan tipe U-tube
kondensor
Gambar 5.1 U-tube kondensor
Pemilihan ini didasarkan atas beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari
pemakaian kondensor jenis ini dibandingkan dengan jenis lain nya, diantaranya
lebih murah dan mudah dibersihkan.
- Diameter shell (Ds), yang diperoleh dengan persamaan :
Ds = 1,4 ( nt)0,47. sn
Dimana : nt = jumlah total tube = 150 buah
Sn = jarak antar tube dalam arah vertikal = 23,8252 mm
Dari tabel 5.1 diatas akan dipilih model kondensor dengan spesifikasi :
- shell types : jenis one pass shell (E)
- head types : jenis bonet (integral cover) (B)
- Rear head types : jenis U-Tube bundle ( U )
Untuk panjang shell kondensor dapat dilihat dari table berikut :
Tube Length
(Ft.)
Dim. In.
Shell Diameter
6 8 10 14 16 18 20
6 A 86-1/4 88-1/4 89-1/4 95-1/2 96-1/2 97-3/4 99-1/2
B 61 55 55 57 57 57 57
9 A 122-1/4 124-1/4 125-1/4 131-1/2 132-1/2 133-3/4 135-1/2
B 97 91 91 93 93 93 93
12 A 158-1/4 160-1/4 161-1/4 167-1/2 168-1/2 169-3/4 171-1/2
B 133 127 127 129 129 129 129
14 A 182-1/4 184-1/4 185-1/4 191-1/2 192-1/2 193-3/4 195-1/2
B 157 151 151 153 153 153 153
16 A 206-1/4 208-1/4 209-1/4 215-1/2 216-1/2 217-3/4 219-1/2
B 181 175 175 177 177 177 177
18P A 230-1/4 232-1/4 233-1/4 239-1/2 240-1/2 241-3/4 243-1/2
B 205 199 199 201 201 201 201
20 A 254-1/4 256-1/4 257-1/4 263-1/2 264-1/2 265-3/4 267-1/2
B 229 223 223 225 225 225 225
ALL C 6-1/2 8-3/4 7-1/2 10-1/4 10-1/2 11 11-1/2
D 4-3/8 5-1/4 5-3/4 8-3/4 8 8-1/2 9-1/8
Tube Length
(Ft.)
Dim. In.
Shell Diameter
22 24 26 28 30 34 38
6 A 100-1/4 103 107-1/2 114 115-1/2 124-1/4 127
B 53 53 52 51 51 50 47
9 A 136-1/4 139 143-1/2 150 151-1/2 160-1/4 163
B 89 89 88 87 87 86 83
12 A 172-1/4 175 179-1/2 186 187-1/2 196-1/4 198
B 125 125 124 123 123 122 119
14 A 196-1/4 199 203-1/2 210 211-1/2 220-1/4 223
B 149 149 148 147 147 146 142
16 A 220-1/4 223 227-1/2 233 235-1/2 244-1/4 247
B 173 173 172 171 171 170 167
18 A 244-1/4 247 251 -1/2 258 259-1/2 268-1/4 271
B 197 197 196 195 195 194 191
20 A 268-1/4 271 275-1/2 282 283-1/2 292-1/4 295
B 221 221 220 219 219 218 215
ALL C 12-1/4 13-3/4 14-1/4 16-1/4 16-1/2 17 20-1/4
D 9-3/8 10-5/8 23-1/4 29-1/4 30-1/2 38-1/4 40-1/4
TUBE N1 6 6 6 8 8 8 10
N2 6 x 8 6 x 8 6 x 8 8 8 8 x 10 10
LENGTHS H 15 16 17 20 21 23 25
Pmax 10 12 12 16 16 20 20
G 26 28 30 32 34 38 42
O. D. 22 24 26 28 30 34 38
Tabel 5.2 spesifikasi shell kondensor
Berdasarkan data panjang tube dan diameter shell yang telah duhitung sebelum
nya dimana panjang total total tube = 4 m (13,124 ft ) dan diameter shell = 468,86
mm ( 19,167 in ) berdasarkan data ini dan data dari tabel 5.2 maka dipilih
panjang shell kondensor = 191 in ( 4,85 m ).
5.2 Perencanaan Buffle
Didalam kondensor ini nantinya akan dipasang buffles (sekat) dimana
tujuan nya adalah untuk mengarahkan dan mensirkulasikan aliran air didalam
shell yang melewati tube-tube didalam shell agar perpindahan panas yang terjadi
lebih efektif. Dalam perencanaan ini nantinya akan dipilih buffles jenis single
segmental buffles.
Gambar 5.3 jenis-jenis buffles
Adapun perencanaan buffle menurut standar TEMA (Tubular
Exchanger Manufacturer Association ) adalah :
- Diameter buffles ( Db ) : Diameter buffles harus berkisar dari 1/5Ds < lb <
Ds dalam perencanaan ini diameter buffles direncanakan Db = 97,372 mm
- Jarak antar buffles (lc) : 194,7 195 (7,67 )
2 mm mm in
l D
- Tebal buffles diambil dari tabel 5.3 berikut :
Tabel 5.3 Tebal Plat Buffles ( TEMA standard )
Berdasarkan besarnya diameter shell yaitu Ds = = 468,86 mm ( 19,167 in ) dan
jarak antar buffles (lc) = 7,67 in ( < 12 ) maka dari tabel diatas didapat tebal
buffles = 3/16 in (0,18 in) .
- Ruang bebas (clearance) yaitu jarak atau celah karena adanya kelonggaran
antara buffles dengan shell. Nilai nya dapat dilihat pada tabel 5.4
Berdasarkan tabel diatas untuk diameter shell (Ds) = 19,167 in maka nilai ruang
bebas (clearance) adalah 0,150 in (3,81 mm ).
- Jumlah buffles ( N ) = Ls/ lc = 4850 mm / 195 mm = 24,8 = 24 buah
Bahan yang digunakan adalah cooper.
5.2 Penurunan Tekanan (Pressure Drop )
Gesekan antara dinding pipa dan air pendingin yang mengalir didalam
nya, akan menyebabkan terjadinya kerugian tekanan pada air pendingin, dimana
besarnya kerugian tekanan bergantung pada jumlah dan kecepatan alirannya.
5.2.1 Penurunan Tekanan Pada Shell Kondensor
Besarnya nilai penurunan tekanan yang terjadi pada shell kondensor
dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut :
e s s s s
D N D G f P
ρ
2
) 1 ( ) (
4 +
= ∆
( Literatur : Zukauskas and Ulinskas 1998 )
Dimana :
fs = Faktor gesekan
Gs = kecepatan aliran massa pada shell (kg/m2.s)
Ds = Diameter dalam shell (m)
faktor gesekan (fs) dapat dicari dengan menggunakan persamaan :
(literatur : J.P Holman 1998 )
Dimana :
Temperatur shell :
dari tabel sifat-sifat air didapat nilai :
ρ= 994,78 kg/m3
Sehingga diperoleh :
008
A
Dari persamaan laju aliran massa diatas didapat nilai dari laju aliran massa air =
0,0014 kg/s. Sehingga nilai dari kecepatan aliran massa shell diperoleh :
s
Maka penurunan tekanan pada shell :
Pa
5.2.1 Penurunan Tekanan Pada Tube Kondensor
Besarnya nilai penurunan tekanan yang terjadi pada shell kondensor
dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut :
s
(Literatur : Incropera 1981 )
Dimana :
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 KESIMPULAN
Refrigerant
Refrigerant yang digunakan adalah R123 dengan :
- Laju aliran refrigeran = 46,189 kg/s
- Suhu refrigeran pada saat masuk kondensor = 50 0C
- Suhu refrigeran keluar kondensor = 400C
- Untuk penggunaan R-123 dalam waktu dekat ini masih belum disarankan
dikarenakan faktor nilai ekonomis nya yang masih agak tinggi. Jadi
pemakaian R-123 adalah sebagai alternatif sumber energi.
Kondensor
Dalam perencanaan ini digunakan :
- Tipe kondensor adalah jenis U-tube kondensor, dimana refrigeran
mengalir didalam tube kondensor sedangkan pendingin nya mengalir pada
shell kondensor
- Kondensor direncanakan terdiri dari 150 buah tubes dengan panjang
massing-masing tubes adalah 4 m.
- Kondensor menggunakan cooper tube berdiameter nominal 5/8 in dengan
tipe L, dengan ukuran sebagai berikut :
- Diameter luar = 19,05 mm
- Diameter dalam = 16,92 mm
- Tebal dinding tube = 1,07 mm
- Susunan tube adalah triangular ( bentuk segitiga ) dengan :
- susunan tube pada jarak vertikal ( sn) = 23,8252 mm
- susunan tube jarak horizontal ( sp ) = 20,6756 mm
- Shell kondensor direncanakan terbuat dari bahan cooper dengan diameter
shell Ds = 468,86 mm dengan panjang shell = 4,85 m.
- Buffles direncanakan dari bahan cooper dengan ukuran :
- Diameter buffles = 97,372 mm
- jarak antar buffles = 195 mm
- tebal buffles = 0,18 in
- jumlah buffles = 24 buah
- Proses desuperheating : ho = 96,703 W/m2.K
- Proses kondensasi : ho = 87, 1664 W/m2.K
- Laju perpindahan panas aliran internal :
- Proses Kondensasi : hi = 476, 416 W/m2.K
- Proses Desuperheating : hi = 5085,177 W/m2.K
- Penurunan Tekanan ( pressure drop ) :
- Pada shell kondensor = 3,1 x 10-7 Pa
- Pada tube kondensor = 47,75 Pa
6.2 SARAN
1. Dalam perencanaan ini agar diperhatikan proses dalam penentuan fluida kerja
yang akan dipakai.
2. Dalam penentuan dimensi kondensor agar dilakukan dengan
perhitungan-perhitungan yang tepat begitupun dalam pemilihan bahan untuk kondensor
agar dipilih bahan yang memenuhi untuk perencanaan ini.
3. Setiap literature yang dipakai agar dicantumkan dengan jelas sehingga dapat
memudahkan dalam mengetahui sumber-sumber bacaan yang dipakai dalam
perencanaan ini.
DAFTAR PUSTAKA
Cengel, A. Yunus & Boles, A. Michael, Thermodynamics An Engineering
Approach, Fourth Edition, McGraw-Hill, New York 2002.
Dietzel, Fritz, Dakso Sriyono. Turbin Pompa dan Kompresor, Erlangga, Jakarta,
1992.
Dicmas, John L. Vertical turbine, Mixed flow and propeller pumps. Mc Graw
Hill, Amerika Serikat, 1987.
Frank P. And David P. Dewitt, “fundamental of Heat and Mass Transfer”
hal.380, McGraw-Hill, New York 1999
Holman, J.P, Perpindahan Kalor, Erlangga, Jakarta,1998.
Khetagurov, M. Marine Auxiliary Machine system, Peace Publisher,
Moskow, 1970.
Kreith, Frank.”Principles of HeatTransfer”, Third edition. Harper & Row,
Publisher, Inc. 1973.
Witte, L.C. and Shamsundar, A thermodynamic efficiency concept for heat. N.
NewYork.1983.
Zukauskas, A. and Ulinskas, R. Banks of Plain and Finned Tubes, Heat
Exchanger Design Handbook, G. F. Hewitt Edition, Begell House, Inc.,