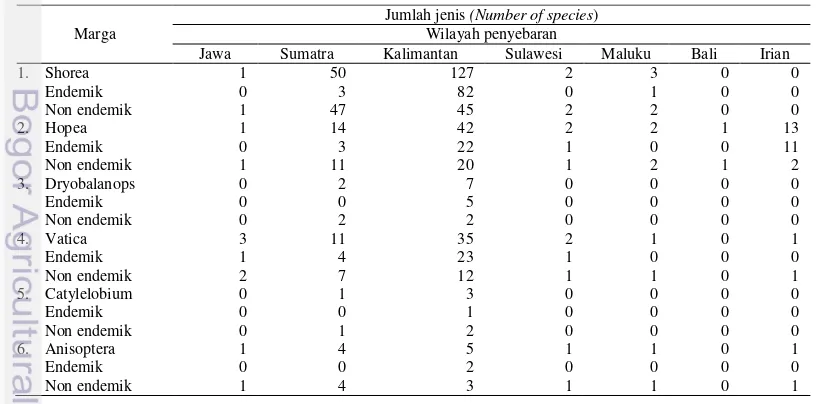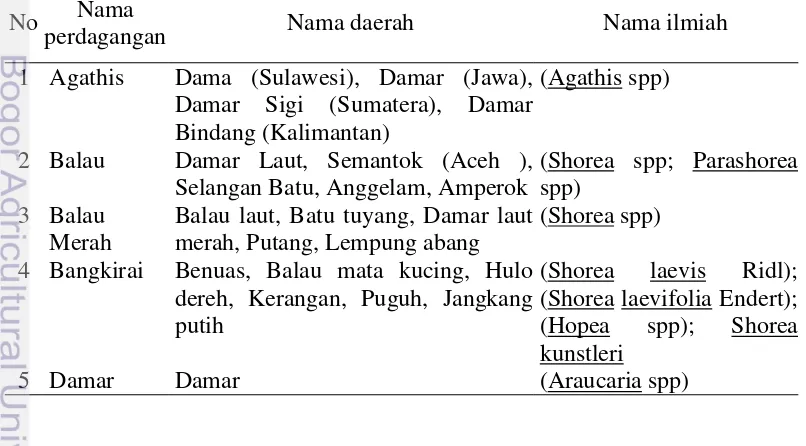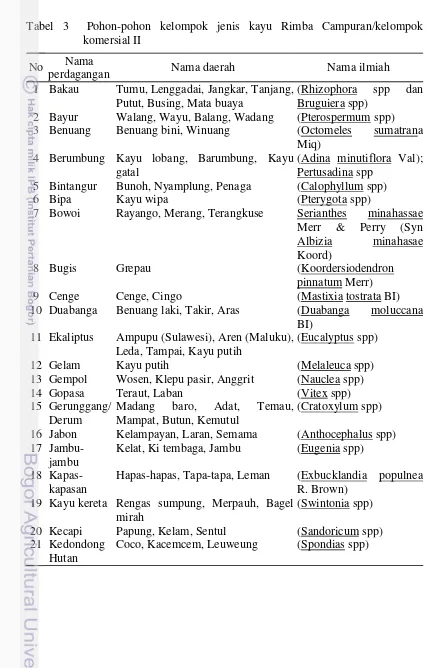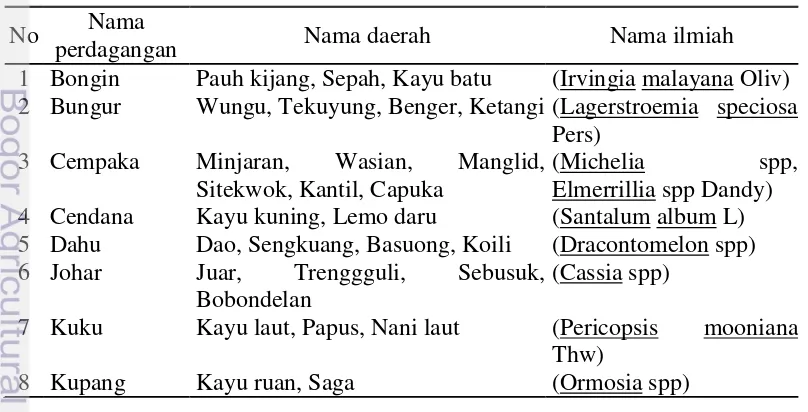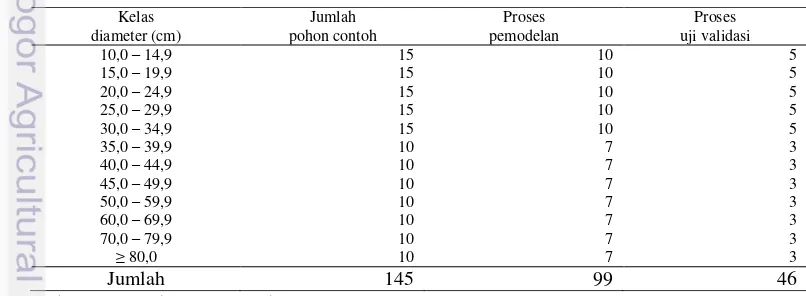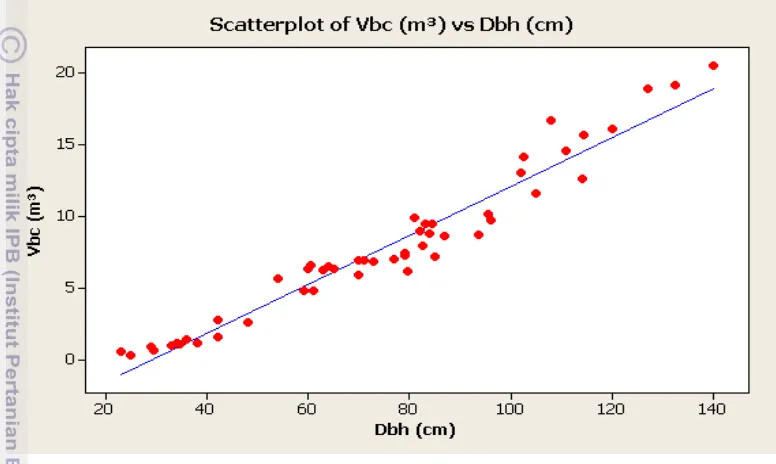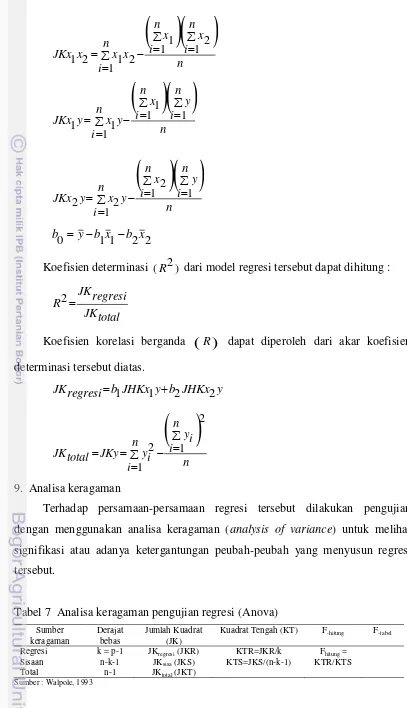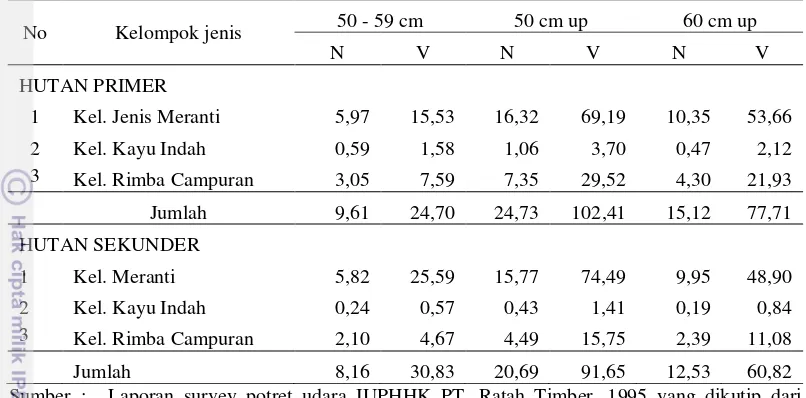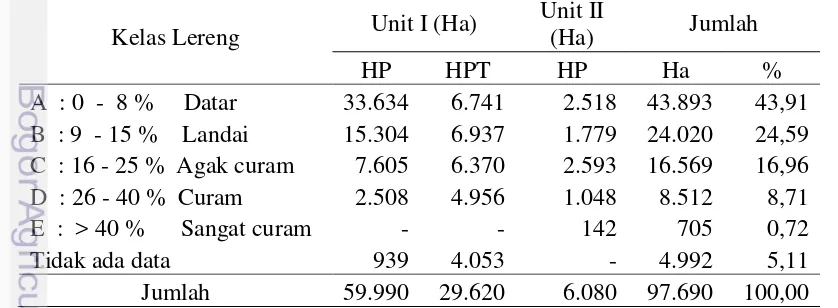1.1 Latar Belakang
Hutan merupakan komunitas yang tetap menjadi perhatian khusus saat ini,
karena kemampuan hutan untuk memberikan berbagai manfaat berupa barang dan
jasa lingkungan yang sangat begitu besar bagi kehidupan manusia dan seluruh
kehidupan di muka bumi ini. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa tingginya
jumlah penduduk dunia yang terus meningkat dari waktu ke waktu akan diikuti
dengan peningkatan kebutuhan hidupnya. Maka kebutuhan manusia terhadap
barang dan jasa lingkungan hutan akan terus meningkat. Banyak sekali manfaat
hutan yang sangat dibutuhkan manusia antara lain hutan sebagai penghasil kayu
yang digunakan sebagai bahan baku industri, sebagai tempat penyimpanan
karbon, sebagai tempat pemeliharaan keanekaragaman hayati, sebagai obyek
ekoturisme dan rekreasi alam, serta hutan dapat memberikan perlindungan
terhadap siklus air dalam DAS dan pengendalian erosi, dan juga berbagai manfaat
lainnya yang sangat penting bagi kehidupan manusia.
Mengingat begitu besarnya peranan hutan, baik sebagai penghasil kayu
maupun peranannya secara keseluruhan bagi kehidupan maka keberadaan hutan
dan lingkungannya perlu dipertahankan agar tetap lestari. Dalam upaya
mewujudkan keberadaan hutan yang lestari maka pengelolaannya perlu dilakukan
dengan baik melalui perencanaan hutan yang cermat, rasional dan terarah. Oleh
karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan,
pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam
(IUPHHK-HA) dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan
Tanaman (IUPHHK-HT), diwajibkan menyusun Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) sepuluh tahunan yang disusun
berdasarkan inventarisasi hutan berkala sepuluh tahunan. Hal ini diberlakukan
bertujuan untuk mengetahui kondisi sediaan tegakan hutan (timber standing stock)
secara berkala, serta sebagai bahan pematauan kecenderungan (trend) kelestarian
Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) sepuluh tahunan ini
penting untuk dilakukan pada setiap IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT yang
digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) sepuluh tahunan. Potensi tegakan suatu areal
IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT dapat diperoleh dari hasil IHMB yang baik dan
benar. Salah satu tujuan dari kegiatan IHMB ini adalah untuk menyajikan
taksiran-taksiran kuantitas kayu di hutan menurut suatu urutan klasifikasi seperti
jenis atau kelompok jenis, ukuran, kualitas dan sebagainya. Dalam kegiatan
IHMB, untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pengukuran terhadap
dimensi-dimensi pohon maupun tegakan, yang kadang-kadang sulit dan tidak praktis
diukur secara langsung dilapangan. Oleh karena itu, ketersediaan alat bantu dalam
IHMB adalah sangat diperlukan, untuk mempercepat kegiatan dan memperkecil
kesalahan yang terjadi dalam pengukuran. Pengertian alat bantu dalam
inventarisasi hutan ini adalah alat yang digunakan untuk mempercepat
pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan selain alat-alat ukur dimensi pohon
maupun dimensi tegakan, salah satunya adalah tabel volume pohon.
Penyusunan tabel volume pohon yang digunakan sebagai alat bantu dalam
kegiatan inventarisasi hutan adalah untuk menduga volume pohon per pohon dari
suatu pohon berdiri dalam tegakan hutan yang diukur, yang pada akhirnya untuk
menduga persediaan tegakan berdiri (standing stock). Dengan tersedianya tabel
volume pohon ini maka akan mempercepat dan memperlancar kegiatan
inventarisasi hutan, terutama dalam inventarisasi tegakan hutan dengan areal yang
luas.
1.2 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini
ditujukan untuk menyusun model penduga volume pohon kelompok jenis
Dipterocarpaceae dan kelompok jenis kayu Rimba Campuran sebagai alat bantu
dalam pelaksanaan kegiatan IHMB di PT. Ratah Timber Kalimantan Timur. Dari
1.3 Manfaat Penelitian
1. Menghasilkan alat bantu yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan
Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala di IUPHHK-HA PT. Ratah Timber
Kalimantan Timur.
2. Memudahkan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Hutan
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Deskripsi Singkat Hutan Hujan Tropis
Hutan adalah masyarakat tumbuh-tumbuhan yang dikuasai pohon-pohonan
dan mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan di luar hutan.
Hubungan antara masyarakat tumbuh-tumbuhan hutan, margasatwa, dan alam
lingkungannya begitu erat sehingga hutan dapat dipandang sebagai suatu sistem
ekologi atau ekosistem. Masyarakat hutan adalah suatu sistem yang hidup dan
tumbuh secara dinamis. Masyarakat hutan terbentuk secara berangsur-angsur
melalui beberapa tahap invasi oleh tumbuh-tumbuhan, adaptasi, agregasi,
persaingan, penguasaan, reaksi terhadap tempat tumbuh, dan stabilisasi. Proses
inilah yang disebut suksesi. Secara singkat suksesi adalah suatu proses perubahan
komunitas tumbuh-tumbuhan secara teratur mulai dari tingkat pionir sampai pada
tingkat klimaks di suatu tempat tertentu. Macam-macam suksesi berdasarkan
proses terjadinya terdapat dua macam suksesi yaitu (Soerianegara & Indrawan
2005) :
1. Suksesi primer (prisere) adalah perkembangan vegetasi mulai dari habitat tak bervegetasi hingga mencapai masyarakat yang stabil dan klimaks. Suksesi primer ini yang akan mengakibatkan terbentuknya hutan primer. Hutan primer terbentuk dari daratan yang mengalami suksesi yang ideal berkembang mulai dengan masyarakat tumbuhan Cryptogamae (tingkat rendah), tumbuh-tumbuhan herba (terna), semak, perdu, dan pohon, hingga tercapai hutan klimaks.
tahun akan terjadi hutan sekunder muda, dan sesudah 50 tahun akan terjadi hutan sekunder tua yang secara berangsur-angsur akan mencapai klimaks.
Letak geografis Indonesia yang berada diantara benua-benua Asia dan
Australia, di sekitar khatulistiwa mengakibatkan adanya berbagai macam tipe-tipe
hutan, salah satunya hutan hujan tropis (tropical rain forest). Hutan hujan tropis di
Indonesia memiliki luas ± 89.000.000 ha, terutama terdapat di Sumatra,
Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dengan ciri-ciri sebagai berikut:
1. Iklim selalu basah,
2. Tanah kering dan bermacam-macam jenis tanah,
3. Di pedalaman, pada tanah rendah rata atau berbukit (< 1000 m dpl) dan pada
tanah tinggi (s/d 4000 m dpl),
4. Dapat dibedakan menjadi tiga zone menurut ketinggiannya yaitu (Soerianegara
& Indrawan 2005) :
- Hutan hujan bawah 2-1000 m dpl, jenis kayu yang penting antara lain dari genus famili Dipterocarpaceae yaitu Shorea, Dipterocarpus, Dryobalanops, dan Vatica. Genus-genus lain antaralain Agathis, Altingia, Dialium, Duabanga, Dyera, Gossanepinus, Koompasia, dan Octomeles.
- Hutan hujan tengah 1000-3000 m dpl, jenis kayu yang umum terdiri dari famili Lauraceae, Fagaceae, Castanea, Nothofagus, Cunoniaceae, Magnoliaceae, Hammamelidaceae, Ericaceae, dan lain-lain.
- Hutan hujan atas 3000-4000 m dpl, jenis kayu utama yaitu Coniferae (Araucaria, Dacrydium, Podocarpus), Ericaceae, Loptospermum, Clearia, Quercus, dan lain-lain.
global, selain itu juga sebagai konservasi tanah, air, nutrisi, dan biodiversitas. (Soerianegara & Indrawan 2005).
2.2 Deskripsi Singkat Famili Dipterocarpaceae
Menurut Heyne (1987) famili Dipterocarpaceae memiliki ciri pohonnya besar, tinggi, batangnya lurus, silinder, dan berbanir. Pohon dari famili Dipterocarpaceae ini persebarannya banyak terdapat di Sumatra dan Kalimantan. Pohon-pohon ini tumbuh mulai dari dataran rendah hingga tinggi di pegunungan, namun juga banyak di rawa-rawa gambut. Tingginya biasanya 30-40 m dan bagian batangnya yang bebas cabang biasanya 20-25 m panjangnya. Batang-batangnya hampir selalu lurus, tetapi dekat pada tajuknya sering agak bengkok.
Menurut Heyne (1987) untuk kualitas kekuatannya jenis-jenis pohon famili Dipterocarpaceae ini dapat digolongkan kedalam kelas II, III, atau IV. Sedangkan menurut kualitas keawetannya kedalam kelas III atau IV. Karena banyak ditemukan dan bentuk batangnya yang baik serta mudah dikerjakan maka kayu ini di Sumatra dan Kalimantan termasuk jenis-jenis yang paling banyak digunakan. Jenis-jenis yang ringan, yang dapat lama bertahan terhadap bubuk namun kurang terhadap pengaruh cuaca, oleh penduduk biasa dipakai untuk papan, kasau pada bangunan rumah, dan untuk sampan. Sementara itu jenis-jenis yang lebih berat, yang lebih kuat, dan lebih awet digunakan untuk gelegar, papan lantai, dan bahkan papan geladak jembatan. Untuk di Eropa yang pada umumnya menuntut syarat-syarat yang lebih berat, biasanya memakai Meranti Merah hanya untuk maksud-maksud semi permanen, untuk dinding hias, dan terutama untuk acuan pada bangunan beton, serta untuk perancah pada bangunan gedung. Tetapi jenis-jenis yang lebih baik konon lambat laun dipakai juga untuk pekerjaan permanen. Meranti adalah jenis kayu perdagangan yang terpenting dari Sumatra dan Kalimantan, terutama di daerah-daerah yang ada kemugkinan pengangkutan di air. Jumlah-jumlah besar diekspor dari Bengkalis, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat dengan tujuan Singapura, Cina, dan Australia.
setinggi 20-40 m. Kulit batang yang halus biasanya mengelupas dalam kepingan-kepingan tipis yang lebar-lebar. Kayu gubal putih, putih kekuning-kuningan atau coklat muda dan biasanya mengandung banyak sekali resin. Kayu gubal ini jelas beda daripada kayu terasnya yang berwarna merah atau coklat kemerahan. Untuk persebarannya menunjukkan bahwa Sumatra dan Kalimantan bersama-sama dengan Semenanjung Malaya serta Filipina merupakan pusat daerah Dipterocarpaceae.
Menurut Prawira dan Tantra (1973) Shorea leprosula Miq atau Meranti Tembaga yang termasuk golongan Meranti Merah yang termasuk kedalam famili Dipterocarpaceae memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini :
1. Habitus : Pohon tinggi mencapai 50 m, batang bebas cabang 30 m, diameter mencapai 100 cm atau lebih, banir tinggi 3,5 m.
2. Batang : Kulit luar tebalnya kira-kira 5 mm, berwarna abu-abu atau coklat, sedikit beralur tidak dalam, mengelupas agak besar-besar dan tebal. Penampang berwarna coklat muda sampai merah, bagian dalamnya kuning muda. Kayu gubal tebalnya 1-8 cm, berwarna kuning muda sampai kemerahan. Kayu teras berwarna coklat muda sampai merah, peralihannya dari gubal keteras terjadi secara berangsur.
3. Daun : Rata, hampir menyerupai segiempat memanjang atau bulat telur terbalik yang memanjang, pangkal daun membulat, ujung runcing, panjangnya rata-rata 3-13 cm, lebar 3-6 cm, permukaan atas helaian daun mengkilat dan permukaan bawah suram.
4. Buah : Berbentuk bulat telur, ujungnya agak lancip, berbulu halus berwarna pucat, panjang 1-1,5 cm, diameter kira-kira 1 cm dan sayap-sayapnya tipis.
5. Tumbuh : terdapat banyak di Sumatra dan Kalimantan dalam hutan primer 5-800 m dpl. Pada tanah liat dan berpasir yang selamanya tidak digenangi air, kadang terdapat pula pada pinggir rawa, dan hidup berkelompok.
Menurut Djamhuri, Hilwan, Istomo, dan Soerianegara (2002) famili Dipterocarpaceae merupakan pohon raksasa, berdamar, kadang-kadang berbanir, serta kulit batang mengelupas. Daun tunggal berseling, tetapi rata, berdaun penumpu (besar dan tidak rontok), tulang daun ada yang berbentuk tangga (Scalariform veination). Bunga biseksual, beraturan, tersusun dalam malai, kelopak bunga ada lima helai, bebas atau bersatu di pangkal. Buah berbiji satu, keras tidak pecah dan bersayap, sayap merupakan perkembangan dari kelopak bunga. Famili ini mendominasi hutan hujan dataran rendah dan tersebar di kawasan Tropika Asia (India, Srilangka, Myanmar, Malaysia, Filipina, Indonesia, Cina Selatan, dan Papua Nugini), di Indonesia terbanyak di Kalimantan dan Sumatra. Famili Dipterocarpaceae ini sudah tercatat 512 jenis dalam 16 marga. Di Indonesia sendiri dijumpai sembilan marga, yaitu Shorea (Shorea leprosula, shorea pinanga, shorea multiflora, shorea hopeifolia, shorea polyandra, shorea leavifolia), Dryobalanops (Dryobalanops aromatic, Dryobalanops lanceolata, dan Dryobalanops oblongifolia), Dipterocarpus (Dipterocarpus cornutus, Dipterocarpus crinitus), Hopea (Hopea mengarawan, hopea dryobalanoides), Anisoptera (Anisoptera marginata, Anisoptera costata), Vatica (vatica rassak, Vatica wallichii), Parashorea, Upuna, dan Cotylelobium. Manfaat yang dapat diperoleh dari famili Dipterocarpaceae antaralain sebagai bahan konstruksi, plywood, damar.
Tabel 1 Penyebaran dan jumlah jenis pohon Dipterocarpaceae di Indonesia
Marga
Jumlah jenis (Number of species) Wilayah penyebaran
Lanjutan Tabel 1 Penyebaran dan jumlah jenis pohon Dipterocarpaceae di Indonesia
Marga
Jumlah jenis (Number of species) Wilayah penyebaran
Jawa Sumatra Kalimantan Sulawesi Maluku Bali Irian 7. Dipterocarpus Endemik Non endemik 4 1 3 25 1 24 41 15 26 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 8. Parashorea Endemik Non endemik 0 0 0 3 1 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Upuna Endemik Non endemik 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sumber : Dendrologi, 2002
2.3 Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala
Menurut Husch (1987) inventarisasi hutan adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menyajikan taksiran-taksiran kuantitas kayu di hutan menurut suatu urutan klasifikasi seperti spesies, ukuran, dan kualitas. Menurut Simon (1996) tujuan utama inventarisasi hutan adalah untuk mendapatkan data tentang areal berhutan dan komposisi tegakannya. Kegiatan inventarisasi hutan dapat dilaksanakan dengan pengindraan jauh, pengamatan langsung dilapangan, atau gabungan dari keduanya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), diwajibkan menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) sepuluh tahunan yang disusun berdasarkan inventarisasi hutan berkala sepuluh tahunan (Departemen Kehutanan Republik Indonesia 2007b).
kawasan hutan produksi setiap wilayah unit pengelolaan/unit managemen. Tujuan dari IHMB tersebut antaralain (Departemen Kehutanan Republik Indonesia 2007a) :
1. Untuk mengetahui kondisi sediaan tegakan hutan (timber standing stock) secara berkala.
2. Sebagai bahan penyusunan RKUPHHK dalam hutan alam dan atau RKUPHHK dalam hutan tanaman atau KPH sepuluh tahunan.
3. Sebagai bahan pemantauan kecenderungan (trend) kelestarian sediaan tegakan hutan di areal KPH dan atau IUPHHK.
Dalam kegiatan IHMB ini diperlukan alat bantu IHMB yang digunakan
untuk memperlancar kegiatan inventarisasi hutan, alat bantu ini terdiri dari :
1. Kurva tinggi yaitu kurva yang memberikan gambaran tentang hubungan
diameter dengan tinggi. Hubungan antara diameter dan tinggi dibentuk dengan
melalui pengukuran diameter dan tinggi sejumlah individu pohon, kemudian
menghubungkan keduanya dengan analisis regresi sehingga bisa dibentuk
sebuah persamaan kurva tinggi.
2. Tabel volume yaitu suatu tabel yang disusun untuk memperoleh taksiran
volume pohon melalui pengukuran diameter atau beberapa peubah lain penentu
volume pohon. Tabel volume yang digunakan adalah tabel volume lokal
maupun tabel volume standar.
3. Tabel berat pohon yaitu tabel yang menunjukkan hubungan antara diameter
dengan berat segar (fresh weight) pohon. Tabel berat ini penting
keberadaannya untuk menduga potensi kayu pulp dalam HTI pulp dan untuk
menduga biomassa serta banyaknya unsur karbon dalam hutan alam.
2.4 Volume Pohon
Menurut Husch (1963) volume pohon adalah ukuran tiga dimensi, yang tergantung dari lbds (diameter setinggi dada atau diameter pangkal), tinggi atau panjang batang, dan faktor bentuk batang.
feet) di atas pangkal batang (untuk pohon yang berdiri pada lereng, titik pengukuran harus ditentukan pada bagian atas lereng). Simon (1996) menyatakan bahwa terdapat beberapa macam tinggi pohon di dalam inventarisasi
hutan yaitu :
1. Tinggi total, yaitu tinggi dari pangkal pohon dipermukaan tanah sampai puncak
pohon,
2. Tinggi bebas cabang, yaitu tinggi pohon dari pangkal batang permukaan tanah
sampai cabang pertama untuk jenis daun lebar atau crown point untuk jenis
conifer, yang membentuk tajuk,
3. Tinggi batang komersial, yaitu tinggi batang yang pada saat itu laku dijual
dalam perdagangan, dan
4. Tinggi tunggak, yaitu tinggi pangkal pohon yang ditinggalkan pada waktu
penebangan.
Menurut Husch (1963), Penentuan volume suatu benda dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :
1. Cara langsung, yaitu berdasarkan prinsip perpindahan cairan. Alat yang digunakan disebut Xylometer. Penentuan volume dengan cara ini dilakukan terhadap benda-benda yang bentuknya tidak beraturan,
2. Cara analitik, yaitu penentuan volume dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus volume. Cara ini dilakukan terhadap benda-benda yang bentuknya beraturan, seperti segi banyak, prisma, piramida, prismoid, dan benda-benda seperti kerucut, silinder, paraboloid, dan neiloid, dan
3. Cara grafik, yaitu cara ini dilakukan untuk penentuan volume berbagai benda putar tanpa memandang ciri-ciri permukaannya.
Untuk menentukan volume dolok (sortimen kayu) sebagai bagian dari
volume kayu/pohon, telah dikembangkan rumus-rumus matematik (Spurs 1952;
Loetsch et al 1973) sebagai berikut :
Rumus Smalian : V = 0,5 x (B + b) x L
Rumus Huber : V = B1/2 x L
Rumus Brereton : V = {0,625 x x (D + d)2 x L}
Rumus Newton : V = {B + (B1/2 x 4) + b} x L x 1/6
Dimana : V = Volume dolok (logs) atau batang pohon dalam m3
B = Luas bidang dasar pangkal batang dalam m2
b = Luas bidang dasar ujung batang pohon dalam m2
B1/2 = Luas bidang dasar bagian tengah batang pohon dalam m2
D = Diameter pangkal batang pohon dalam meter
d = Diameter ujung batang pohon dalam meter
L = Panjang batang pohon
Penentuan volume sortimen (batang pohon) dengan menggunakan
rumus-rumus diatas, jika makin pendek panjang batang (L) akan menghasilkan volume
yang lebih tepat, karena rumus-rumus diatas merupakan perhitungan volume yang
mendasarkan kepada bentuk benda teratur, yaitu bentuk silinder, sedangkan
bentuk pohon pada umumnya tidak teratur dan lebih kearah bentuk neiloid.
Berdasarkan volume sortimen-sortimen kayu yang diukur maka volume pohon
dapat diketahui, yaitu merupakan penjumlahan dari volume sortimennya.
Rumus Smalian mempunyai ketepatan yang lebih kecil dibandingkan
dengan rumus Huber dan rumus Newton. Namun demikian rumus Smallian
banyak digunakan karena cukup praktis dan mudah dalam penerapannya. Rumus
Newton memberikan ketelitian yang tinggi dibanding dengan rumus lainnya,
namun rumus ini memerlukan pengukuran kedua ujung batang dan tengah batang,
sehingga penggunaannya lebih terbatas dan kurang praktis untuk digunakan
dilapangan.
Menurut Spurr (1952) angka bentuk batang adalah rasio antar volume aktual
dengan volume silinder yang berdiameter dan tinggi sama dengan diameter
setinggi dada dan tinggi pangkal tajuk pohon tersebut.
Menurut Husch (1987) Tabel volume ini merupakan pernyataan sistematik
mengenai volume sebatang pohon menurut semua atau sebagian dimensi yang
ditentukan dari Dbh, tinggi, dan angka bentuk pohon. Tipe-tipe tabel volume
pohon terdiri dari :
1. Tabel volume lokal (local volume tables)
Tabel volume lokal menyajikan volume menurut dimensi pohon diameter
pohon, meskipun pada penyusunan aslinya tinggi tetap dihitung, tetapi
dihilangkan di dalam bentuk akhirnya. Istilah ”lokal” digunakan karena tabel
-tabel tipe ini hendaknya hanya dipergunakan untuk wilayah terbatas yang
merupakan asal hubungan tinggi dan diameter yang dimanfaatkan kedalam
tabelnya.
2. Tabel volume normal (general standard volume tables)
Tabel volume standar didasarkan kepada pengukuran diameter setinggi dada
(Dbh), maupun tinggi. Tinggi dapat berupa tinggi pohon total atau tinggi kayu
perdagangan. Tabel volume standar dapat disusun untuk individu spesies
maupun kelompok spesies dari berbagai wilayah-wilayah geografis.
3. Tabel volume kelas bentuk (form class volume tables)
Tabel volume kelas bentuk disiapkan untuk menunjukkan volume menurut
beberapa ukuran bentuk pohon disamping diameter setinggi dada (Dbh) dan
tinggi pohon. Tabel volume ini dapat dipakai bilamana saja bentuk suatu pohon
yang bersangkutan secara jelas ditunjukkan oleh karakteristik-karakteristik
bentuk yang telah dimasukan dalam penyusunan tabel-tabelnya, tanpa
memandang spesies atau tempat.
Menurut Spurr (1952) menyatakan bahwa untuk menentukan volume,
apabila pengukuran dilakukan hanya pada satu peubah, maka dipakai diameter
setinggi dada (Dbh), bila menggunakan dua peubah maka yang diukur adalah
diameter setinggi dada (Dbh) dan tinggi pohon tersebut. Sedangkan bila
menggunakan tiga peubah selain mengukur diameter setinggi dada (Dbh) dan
tinggi pohon ditambahkan juga angka bentuk.
Penyusunan tabel volume pohon dimaksudkan untuk memperoleh taksiran
volume pohon melalui pengukuran satu atau beberapa peubah penentu volume
pohon serta untuk mempermudah kegiatan inventarisasi hutan dalam menduga
potensi tegakan. Meskipun demikian, untuk meningkatkan efisiensi dalam
penaksiran volume tegakan dengan tidak mengurangi ketelitian yang diharapkan,
diusahakan dalam penyusunan tabel volume pohon memperkecil jumlah peubah
bebas penentu volume pohon dan diberlakukan pada daerah setempat. Tabel yang
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian
Kegiatan penelitian dilakukan pada bulan Februari–April tahun 2009, yang
dilaksanakan di PT. Ratah Timber yang berlokasi di Desa Mamahaq Teboq,
Kecamatan Longhubung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
3.2 Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain data IHMB PT. Ratah
Timber khususnya data hasil pengukuran pohon contoh. Alat yang digunakan
antara lain peta hutan, alat tulis, Clinometer, pita ukur/phi band, meteran, tally sheet, kamera digital, perangkat keras PC (Personal Computer), Software Minitab 14, MS Excel 2007, MS Word 2007 dan alat hitung berupa kalkulator. Sedangkan
data yang digunakan untuk penelitian adalah pohon contoh kelompok jenis
Dipterocarpaceae dan kelompok jenis Rimba Campuran. Pengelompokkan jenis
pohon ini berdasarkan SK Menhut No. 163/KPTS-II/2003 tentang
pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan (Departemen
Kehutanan Republik Indonesia, 2003). Untuk pohon kelompok jenis
Dipterocarpaceae (Meranti) termasuk kedalam kelompok komersial I,
pohon-pohon yang termasuk komersial I dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2 Pohon-pohon kelompok jenis Meranti/kelompok komersial satu
No Nama
perdagangan Nama daerah Nama ilmiah
1 Agathis Dama (Sulawesi), Damar (Jawa),
Damar Sigi (Sumatera), Damar Bindang (Kalimantan)
(Agathis spp)
2 Balau Damar Laut, Semantok (Aceh ),
Selangan Batu, Anggelam, Amperok
(Shorea spp; Parashorea spp)
3 Balau Merah
Balau laut, Batu tuyang, Damar laut merah, Putang, Lempung abang
(Shorea spp)
4 Bangkirai Benuas, Balau mata kucing, Hulo
dereh, Kerangan, Puguh, Jangkang putih
(Shorea laevis Ridl);
(Shorea laevifolia Endert);
(Hopea spp); Shorea
kunstleri
Lanjutan tabel 2 Pohon-pohon kelompok jenis Meranti/kelompok komersial satu
No Nama
perdagangan Nama daerah Nama ilmiah
6 Durian Durian burung, Lahong, Layung,
Apun, Begurah, Punggai, Durian hantu, Enggang
(Durio carinatus Mast); (Durio spp, Coelostegia spp)
7 Gia Delingsem, Kayu batu, Melunas,
Kayu kerbau, Momala
(Homalium tomentosum
(Roxb) Benth, Homalium Foetidum (Roxb) Benth)
8 Giam Resak batu, Resak gunung (Cotylelobium spp)
9 Jelutung Pulai nasi, Pantung gunung,
Melabuai
(Dyera spp)
10 Kapur Kamper, Ky. kayatan, Empedu,
Keladan
(Dryobalanops spp)
11 Kapur Petanang
Kapur Guras (Dryobalanops
oblongifolia Dyer)
12 Kenari Kerantai, Ki tuwak, Binjau,
Asam-asam, Kedondong, Resung, Bayung, Ranggorai, Mertukul
(Canarium spp, Dacryodes spp, Trioma spp, Santiria spp)
13 Keruing Tempuran, Lagan, Merkurang,
Kawang, Apitong, Tempudau
(Dipterocarpus spp)
14 Kulim Kayu bawang hutan (Scorodocarpus borneensis
Becc)
15 Malapari Malapari (Pongamia Pinnata (L)
Pierre)
16 Matoa Kasai, Taun, Kungki, Hatobu, K.
sapi (Jawa), Tawan (Maluku), Ihi mendek (Irian Jaya)
(Pometia spp)
17 Medang Sintuk, Sintok lancing, KitTeja, Ki
tuha, Ki sereh, Selasihan
(Cinnamomum spp)
18 Meranti Kuning
Damar tanduk, Damar buah, Damar hitam, Damar kelepek
Shorea acuminatissima
Sym, Shorea
balanocarpoides Sym,
Shorea faguetiana Heim, Shorea Scollaris, V. Sloot; Shorea gibbosa Brandis 19 Meranti
Merah
Banio, Seraya merah, Kontoy bayor,
Campaga, Lempong, Kumbang,
Majau, Meranti ketuko, Ketrahan, Ketir, Cupang
(Shorea Palembanica Miq, Shorea lepidota BI, Shorea
ovalis BI, Shorea
Johorensis Foxw, Shorea leptoclados Sym, Shorea leprosula Miq) (Shorea
Platyclados sloot. Ex
Lanjutan tabel 2 Pohon-pohon kelompok jenis Meranti/kelompok komersial satu
No Nama
perdagangan
Nama daerah Nama ilmiah
20 Meranti Putih
Baong, Baung, Kebaong,
Belobungo, Bayong (Sumatera,
Kalimantan), Damar kaca, Damar kucing, Kikir, Udang, Udang ulang, Damar hutan, Anggelam tikus, Kontoi tembaga, Maharam potong,
Damar mata kucing, Bunyau,
Pongin, Awan punuk, Mehing
(Sumatera, Kalimantan), Damar
tenang putih, Honi (Maluku), Damar
lari-lari, Temungku (Sulawesi),
Lalari, Tambia putih (Sulawesi), Hili (Maluku)
(Shorea Virescens Parijs), Shorea retionodes V.SI), (Shorea Javanica K. et. Val), (Shorea bracteolata Dyer), (Shorea ochracea
Sym),(Shorea lamellata
Foxw), (Shorea assamica Dyer), (Shorea koordesii Brandis )
21 Merawan Ngerawan, Cengal, Amang besi,
Cengal balaw, Emang, Tekam
(Hopea spp); Hopea dyeri; (Hopea sangal Kort)
22 Merbau Anglai, Ipil, Tanduk (Maluku),
Kayu besi (Papua), Maharan
(Sumatera)
(Intsia spp)
23 Mersawa Damar kunyit, Masegar, Ketimpun,
Tabok, Tahan, Cengal padi
(Anisoptera spp)
24 Nyatoh Suntai, Balam, Jongkong,
Hangkang, Katingan, Mayang batu, Bunut, Kedang, Bakalaung, Ketiau, Jengkot, Kolan
(Palaquium spp); (Payena spp, Madhuca spp)
25 Palapi Mengkulang, Teraling, Dungun,
Talutung, Lesi-Lesi.
Heritiera (Tarrietia spp)
26 Penjalin Rempelas, Ki jeungkil, Ki endog
(Sunda), Cengkek (Jawa), Pusu (Sumbawa)
(Celtis spp)
27 Perupuk Kerupuk, Pasana, Aras, Mandalaksa (Lophopetalum spp)
28 Pinang Melunak, Ki sigeung, Kelembing,
Ki sinduk
(Pentace spp)
29 Pulai Kayu gabus, Rita, Gitoh, Bintau,
Basung, Pule, Pulai miang
(Alstonia spp)
30 Rasamala Tulasan (Sumatera), Mala (Jawa),
Mandung (Mnkb)
(Altingia excelsa
Noronha)
31 Resak Damar along, Resak putih (Vatica spp)
Sumber : SK Menhut No. 163/KPTS-II/2003
Sementara itu untuk pohon-pohon yang termasuk kedalam kelompok jenis
Rimba Campuran adalah kelompok jenis komersial II, termasuk di dalamnya
Untuk macam-macam pohon yang termasuk kedalam jenis-jenis di atas dapat
dilihat pada Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 5.
Tabel 3 Pohon-pohon kelompok jenis kayu Rimba Campuran/kelompok komersial II
No Nama
perdagangan Nama daerah Nama ilmiah
1 Bakau Tumu, Lenggadai, Jangkar, Tanjang,
Putut, Busing, Mata buaya
(Rhizophora spp dan
Bruguiera spp)
2 Bayur Walang, Wayu, Balang, Wadang (Pterospermum spp)
3 Benuang Benuang bini, Winuang (Octomeles sumatrana
Miq) 4 Berumbung Kayu lobang, Barumbung, Kayu
gatal
(Adina minutiflora Val); Pertusadina spp
5 Bintangur Bunoh, Nyamplung, Penaga (Calophyllum spp)
6 Bipa Kayu wipa (Pterygota spp)
7 Bowoi Rayango, Merang, Terangkuse Serianthes minahassae
Merr & Perry (Syn
Albizia minahasae
Koord)
8 Bugis Grepau (Koordersiodendron
pinnatum Merr)
9 Cenge Cenge, Cingo (Mastixia tostrata BI)
10 Duabanga Benuang laki, Takir, Aras (Duabanga moluccana
BI)
11 Ekaliptus Ampupu (Sulawesi), Aren (Maluku),
Leda, Tampai, Kayu putih
(Eucalyptus spp)
12 Gelam Kayu putih (Melaleuca spp)
13 Gempol Wosen, Klepu pasir, Anggrit (Nauclea spp)
14 Gopasa Teraut, Laban (Vitex spp)
15 Gerunggang/ Derum
Madang baro, Adat, Temau,
Mampat, Butun, Kemutul
(Cratoxylum spp)
16 Jabon Kelampayan, Laran, Semama (Anthocephalus spp)
17 Jambu-jambu
Kelat, Ki tembaga, Jambu (Eugenia spp)
18 Kapas-kapasan
Hapas-hapas, Tapa-tapa, Leman (Exbucklandia populnea
R. Brown) 19 Kayu kereta Rengas sumpung, Merpauh, Bagel
mirah
(Swintonia spp)
20 Kecapi Papung, Kelam, Sentul (Sandoricum spp)
21 Kedondong Hutan
Lanjutan tabel 3 Pohon-pohon kelompok jenis kayu Rimba Campuran/kelompok komersial II
No Nama
perdagangan Nama daerah Nama ilmiah
22 Kelumpang Kepuh, Kalupat, Lomes (Sterculia spp)
23 Kembang semangkok
Merpayang, Kepayang (Scaphium macropodum
J. B)
24 Kempas Impas, Tualang ayam, Hampas (Koompassia malaccensis
Maing)
25 Kenanga Kananga (Cananga sp)
26 Keranji Kayu lilin, Maranji (Dialium spp)
27 Ketapang Kalumpit, Jelawai, Jaha, Klumprit (Terminalia spp)
28 Ketimunan Seranai, Temirit, Kayu reen (Timonius spp)
29 Lancat Kundur, Modjiu, Raimagago (Mastixiodendron spp)
30 Lara Lompopaito, Nani, Langera (Metrosideros spp dan
Xanthostemon spp)
31 Mahang Merkubung, Mara, Benua (Macaranga spp)
32 Medang Manggah, Huru kacang, Keleban,
Wuru, Kunyit
(Litsea firma Hook f; Dehaasia spp)
33 Mempisang Mahabai, Hakai rawang, Empunyit, Jangkang, Banitan, Pisang-pisang
(Mezzetia parviflora
Becc); (Xylopia spp);
Alphonsea spp; Kandelia candell Druce
34 Mendarahan Tangkalak, Au-au, Ki mokla,
Kumpang, Ky luo, Darah-darah, Huru
Myristica spp, Knema spp
35 Menjalin Lilin, Ki endog, Segi landak (Xanthophyllum spp)
36 Mentibu Jongkong, Merebung (Dactylocladus
stenostachys Oliv)
37 Merambung Merambung (Vernonia arborea Han)
38 Punak Kayu malaka, Cerega (Tetramerista glabra Miq)
39 Puspa Sinar telu, Madang getah, Seru (Schima spp)
40 Rengas Rengas tembaga, Rangas (Gluta aptera (King) Ding
Hou
41 Saninten Sarangan, Kalimorot, Ki hiur (Castanopsis argentea A.
DC)
42 Sengon Jeungjing, Tawa kase, Sika
(Maluku)
(Paraserianthes falcataria (L) Nielsen Syn)
43 Sepat Waru gunung, Kalong (Berrya cordofolia Roxb)
44 Sesendok Kayu bulan, Sendok-sendok, Kayu
raja, Garung, Kayu labu
(Endospermum spp)
45 Simpur Sempur, Segel, Janti, Dongi (Dillenia spp)
46 Surian Kalantas, Suren (Toona sureni Merr)
47 Tembesu Tomasu, Kulaki, Malbira, Kitandu (Fragraea spp)
Lanjutan tabel 3 Pohon-pohon kelompok jenis kayu Rimba Campuran/kelompok komersial II
No Nama
perdagangan
Nama daerah Nama ilmiah
49 Tepis Banitan, Pemelesian, Kayu tinyang,
Kayu bulan, Banet, Kayu kalet
(Polyalthia glauca Boerl)
50 Tenggayun Buku ongko, Pejatai, Purut bulu (Parartocarpus spp)
51 Terap Tara, Cempedak, Kulur, Teureup (Artocarpus spp)
52 Terentang Tumbus, Pauh lebi (Campnosperma spp)
53 Terentang ayam
Pauhan, Antumbus, Talantang (Buchanania spp)
54 Tusam Pinus, Damar batu, Uyam (Pinus spp)
55 Utup Utup (Aromadendron sp)
Sumber : SK Menhut No. 163/KPTS-II/2003
Tabel 4 Pohon-pohon kelompok jenis kayu Eboni/kelompok kayu Indah I
No Nama
perdagangan Nama daerah Nama ilmiah
1 Eboni Bergaris Maitong, Kayu lotong, Sora, Amara
(Diospyros celebica Bakh)
2 Eboni Hitam Kayu hitam, Maitem, Kayu
waled
(Diospyros rumphii Bakh)
3 E b o n i Baniak, Toli-toli, Kayu arang,
Kanara, Gito-gito, Bengkoal, Malam
(Diospyros spp D. ebenum Koen, D. ferrea Bakh, D. lolin Bakh, D. macrophylla BI, D. cauliflora BI, D. areolata King et G)
Sumber : SK Menhut No. 163/KPTS-II/2003
Tabel 5 Pohon-pohon kelompok jenis kayu Indah II
No Nama
perdagangan Nama daerah Nama ilmiah
1 Bongin Pauh kijang, Sepah, Kayu batu (Irvingia malayana Oliv)
2 Bungur Wungu, Tekuyung, Benger, Ketangi (Lagerstroemia speciosa
Pers)
3 Cempaka Minjaran, Wasian, Manglid,
Sitekwok, Kantil, Capuka
(Michelia spp,
Elmerrillia spp Dandy)
4 Cendana Kayu kuning, Lemo daru (Santalum album L)
5 Dahu Dao, Sengkuang, Basuong, Koili (Dracontomelon spp)
6 Johar Juar, Trenggguli, Sebusuk,
Bobondelan
(Cassia spp)
7 Kuku Kayu laut, Papus, Nani laut (Pericopsis mooniana
Thw)
Lanjutan tabel 5 Pohon-pohon kelompok jenis kayu Indah II
No Nama
perdagangan
Nama daerah Nama ilmiah
9 Lasi Adina, Kilaki (Adinauclea fagifolia
Ridsd)
10 Mahoni Mahoni (Swietenia spp)
11 Melur Sampinur tali, Jamuju, Ki merah,
Cematan, Alau, Kayu embun, Kayu cina, Sandu, Sampinur bunga
(Dacrydium junghuhnii Miq); (Podocarpus spp); (Dacrydium spp)
12 Membacang Limus piit, Ambacang, Wani, Mempelam, Asam. Mangga
(Mangifera spp)
13 Mindi Bawang kungut (Melia spp)
14 Nyirih Nyireh, Niri (Xylocarpus granatum j.
Konig)
15 Pasang Mempening, Baturua, Kasunu, Triti (Quercus spp)
16 Perepat Darat Marapat, Teruntum batu (Combretocarpus
rotundatus Dans)
17 Raja Bunga Segawe, Klenderi, Saga (Adenanthera spp)
18 Rengas Ingas, Suloh, Rangas, Rengas
burung
(Gluta spp);
(Melanorrhoea spp)
19 Ramin Gaharu buaya, Medang keladi,
Keladi, Miang
(Gonystylus bancanus
Kurz)
20 Sawo kecik Subo, Ki sawo (Manilkara spp)
21 Salimuli Kendal, Klimasada, Purnamasada (Cordia spp)
22 Sindur Sepetir, Sasumdur, Mobingo (Sindora spp)
23 Sonokembang Angsana, Linggua, Nala, Candana (Pterocarpus indicus
Willd)
24 Sonokeling Linggota, Sono sungu, Sonobrits (Dalbergia latifolia
Roxb)
25 Sungkai Jati seberang, Jati londo (Peronema canescens
Jack)
26 Tanjung Sawo manuk, Karikis (Mimusops elengi L.)
27 Tapos Kelampai, Setan, Kedui, Wayang (Elateriospermum tapos
BI) 28 Tinjau
Belukar
Lontar kuning (Pteleocarpus lampongus
Bakh)
29 Torem Sawai, Torem (Manikara kanosiensis
H.j. L. et B. M.)
30 Trembesi Ki hujan (Samanea saman Merr)
31 Ulin Kayu besi, Bulian, Kokon (Eusideroxylon zwageri
T.et.b.)
32 Weru Beru, Ki hiyang, Bengkal (Albizia procera Benth)
3.3 Prosedur Analisis Data
1. Pengambilan pohon contoh dilapangan
Untuk penyusunan Tabel volume pohon, didasarkan pada data pohon contoh
atau pohon model yang dipilih secara purposive sampling dengan ketentuan
tersebar pada setiap jenis pohon, kelas diameter dan kelas tinggi pohon, pada
berbagai tipe tempat tumbuh. Pohon contoh adalah pohon yang pertumbuhannya
baik serta sehat. Pohon contoh diambil di dalam plot IHMB, apabila dalam plot
IHMB itu tidak terdapat pohon contoh maka pengambilan pohon contohnya dapat
dilakukan di luar plot IHMB. Berikut akan ditampilkan gambar plot contoh
IHMB.
Gambar 1 Plot contoh IHMB skala 1 : 10.000.
Menurut Sutarahardja (2009) plot contoh (sample unit) adalah suatu petak
tersebut dilakukan pengukuran-pengukuran terhadap dimensi pohon/tegakan dan
pencatatan informasi-informasi tentang pohon/tegakan yang diperlukan yang
penempatannya bersifat semi permanen. Plot contoh IHMB pada hutan alam luas
0,25 Ha dengan ukuran 20m x 125m diletakkan dalam jalur inventarisasi dengan
arah Utara-Selatan dan di dalamnya terdapat beberapa sub-plot contoh. Dalam
satu plot contoh terdapat 4 sub-plot contoh yang luasnya dibedakan berdasarkan
tingkat pertumbuhan pohon dan tingkat permudaan yang ada. (Lihat Gambar 1)
a. Sub-plot pancang
Diukur dari titik awal plot masing-masing 10 m ke arah Barat atau Timur,
pada ujung sisi kiri dibuat sub-plot pancang berbentuk lingkaran dengan jari-jari
plot 2,82 meter. Kemudian diamati keberadaan pancang dalam plot. Pasang pasak
pada pusat plot untuk memasang tali tersebut, setelah itu dilakukan pengamatan
plot secara berputar dengan ujung tali sebagai batas plot hingga selesai.
b. Sub-plot tiang
Dari titik awal plot, dibuat sub-plot tiang berbentuk bujur sangkar berukuran
10 m x 10 m di sisi kiri jalur. Dengan bantuan tali sepanjang 10 m sebanyak 2
buah dan kompas, dari titik awal plot ditarik tali ke arah kiri tegak lurus jalur
(270º) dan searah jalur (0º) lalu dipasang patok.
c. Sub-plot pohon kecil
Dibentuk plot bujur sangkar berukuran 20 m x 20 m, sepanjang 10 m
sebelah Barat dan 10 m sebelah Timur jalur, kemudian dirintis 20 m ke arah
Utara.
d. Sub-plot pohon besar
Bentuk plot contoh persegi panjang berukuran 20 m x 125 m adalah sebagai
perpanjangan dari sub-plot pohon kecil ke arah Utara.
2. Perhitungan volume pohon contoh
Perhitungan volume pohon contoh pada dasarnya perlu ditebang untuk
dihitung volumenya berdasarkan volume per seksinya yang terdiri dari :
untuk menghitung volume aktual (Va) dari pohon rebah dihitung dengan
menjumlahkan seluruh volume tiap seksi batang dari satu pohon yaitu
dengan : Va = ∑ Vsi
Keterangan : Va = volume aktual
Vsi = Volume seksi batang ke-i, dimana i = 1, 2, 3, ..., n
Volume seksi batang tersebut dihitung dengan menggunakan rumus
Smalian yaitu :
Vs = 0,5 x (B + b) x L
Keterangan : Vs = volume seksi
B = Luas bidang dasar pangkal seksi dalam m2
b = Luas bidang dasar ujung seksi dalam m2
L = Panjang seksi
Luas bidang dasar dihitung dengan rumus : Lbds = 0,25 π D2
b. Untuk diameter 10 cm - < 50 cm pada tebangan silin atau menebang
pohon contoh pada beberapa plot contoh.
c. Untuk pelengkap dapat menggunakan rumus volume
V = 0,25 π D2
T 0,6
3. Pemilahan pohon contoh untuk model dan validasi
Tahap selanjutnya dalam tahap pengumpulan data, harus dilakukan proses
pemilahan pohon contoh. Untuk melakukan pemodelan diperlukan suatu set data
yang berbeda dengan set data yang dipakai untuk uji validasi model. Proses
pemilahan pohon contoh terdiri dari 2/3 pohon contoh untuk proses pemodelan
dan 1/3 pohon contoh lainnya untuk proses uji validasi.
Tabel 6 Pemilahan pohon contoh pada setiap kelompok jenis
Sumber : Permenhut P.34/Menhut-II/2007
Kelas diameter (cm)
Jumlah pohon contoh
Proses pemodelan
Proses uji validasi
10,0 – 14,9 15 10 5
15,0 – 19,9 15 10 5
20,0 – 24,9 15 10 5
25,0 – 29,9 15 10 5
30,0 – 34,9 15 10 5
35,0 – 39,9 10 7 3
40,0 – 44,9 10 7 3
45,0 – 49,9 10 7 3
50,0 – 59,9 10 7 3
60,0 – 69,9 10 7 3
70,0 – 79,9 10 7 3
≥ 80,0 10 7 3
4. Analisa hubungan antara tinggi pohon dengan diameter pohon
Salah satu hipotesa dalam penyusunan tabel volume pohon lokal adalah
terdapatnya hubungan yang erat antara tinggi pohon dengan diameter pohon.
Hubungan ini dapat dilihat dari korelasi antara kedua peubah tersebut, yang
ditunjukkan oleh besarnya koefisien korelasinya. Apabila antara tinggi pohon
dengan diameter pohon terdapat korelasi yang erat, maka untuk menduga volume
pohon dapat hanya menggunakan peubah diameter atau tinggi pohon saja.
Mengingat pengukuran tinggi pohon lebih sulit dibandingkan mengukur diameter
pohon, maka dalam kaitan korelasi antara tinggi pohon dengan diameter pohon
cukup erat, tabel volume dapat disusun atas dasar peubah diameter pohon.
Koefisien korelasi ( r ) antara tinggi pohon dengan diameter pohon dapat dihitung
dengan rumius :
y JK x JK xy JHK r .
Dalam hal ini, JKx, Jky, dan JHKxy dapat dihitung dengan rumus sebagai
berikut : JKx = n n i i x n i i x 2 ) 1 ( 1 2 JKy = n n i i y n i i y 2 ) 1 ( 1 2
JHKxy =
n i n n i i y n i i x i y i x 1 1 1
di mana :
r = Koefisien korelasi contoh
JKX = Jumlah kuadrat peubah X (misal : diameter pohon)
JKy = Jumlah kuadrat peubah Y (misal : tinggi pohon)
Besarnya nilai koefisien korelasi adalah antara - 1 ≤ r + 1 dimana jika nilai r mendekati – 1 atau + 1, maka hubungan antara kedua peubah itu kuat, artinya
terdapat korelasi yang tinggi antara keduanya (Walpole 1993).
5. Pengujian koefisien korelasi antara tinggi pohon dengan diameter pohon
Dalam pengujian ini dilakukan perhitungan koefisien korelasi dari kedua
peubah tersebut ( r ) sebagai penduga koefisien korelasi populasinya, yaitu ( ρ ).
Apabila r = 0 maka besar kemungkinannya untuk menyimpulkan ρ = 0 dan
apabila nilai r mendekati + 1 atau –1, hal tersebut mencirikan bahwa ρ ≠ 0. Suatu
uji untuk menyatakan kapan nilai r berada cukup jauh dari nilai ρ adalah melalui
pengujian koefisien korelasi dengan uji Z-Fisher (Walpole 1993). Dalam uji Z-Fisher
ini, dilakukan transformasi nilai-nilai r dan ρ kedalam Z-Fisher. Dalam penyusunan
tabel volume lokal, Fakultas Kehutanan IPB (1985) dan Sutarahardja (1982) diacu
dalam Sutarahardja (2008) mensyaratkan bahwa nilai ρ harus lebih besar dari 0,7
atau ρ 0,7 yang berarti pada nilai ρ 0,7 maka hubungan antara tinggi pohon
dengan diameter pohon dianggap cukup kuat, dimana jika ρ 0,7071 artinya ρ2
adalah 50 %.. Hubungan yang kuat dengan ρ2 50 % tersebut berarti akan
menjamin bahwa sekurang-kurangnya 50 % keragaman volume pohon yang
disebabkan oleh keragaman tinggi pohon dapat dicakup oleh pengaruh keragaman
diameter pohon. Tahap pengujian koefisien korelasi bersyarat dengan
menggunakan transformasi Z-Fisher tersebut adalah dengan prosedur sebagai
berikut :
a. Menentukan hipotesis pengujian koefisien korelasi, yaitu :
H0: ρ = 0,7071
H1: ρ 0,7071
b. Menghitung nilai transformasi Z-Fisher dari nilai koefisien korelasi populasi
( ρ ) dan koefisien korelasi contoh ( r ) :
Zρ = 0,5 ln{( 1 + ρ )/( 1 –ρ )} dan
Zr = 0,5 ln{( 1 + r )/( 1 – r )}
c. Menentukan pendekatan simpangan baku dari hasil transformasi Z-Fisher,
σZr = 1/√(n-3)
Kriterium uji dalam pengujian transformasi Z-Fisher adalah :
Z-hitung = (Zr –Zρ)/ σZr
Dimana :
Z = Sebaran normal Z
σZr = Pendekatan simpangan baku transformasi Z-Fisher
d. Kaidah keputusannya adalah sebagai berikut :
Jika Z-hitung ≤ Z-tabel pada tingkat nyata tertentu (misalnya pada taraf nyata 5
%), maka H0 diterima artinya hubungan antara diameter pohon dengan tinggi
pohon tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan yaitu tidak memenuhi syarat
ρ > 0,7071artinya hubungan antara diameter pohon dengan tinggi pohon dianggap
kurang erat. Jika Z-hitung Z-tabel pada tingkat nyata tertentu, maka H0 ditolak
artinya bahwa hubungan antara diameter pohon dengan tinggi pohon memenuhi
syarat yang telah ditetapkan artinya hubungan diameter dengan tinggi pohon
dianggap cukup erat.
Bila keputusan H0 diterima, maka tabel volume yang disusun untuk tegakan
hutan yang diukur harus menyertakan peubah lain selain peubah diameter pohon,
misalnya antara lain mengikut sertakan tinggi pohon dan atau peubah lainnya, jadi
tabel volume yang disusun adalah tabel volume standar.
Sedangkan apabila H0 ditolak dalam pengujian tersebut artinya hubungan
antara diameter pohon dengan tinggi pohon dianggap cukup erat, artinya koefisien
korelasi populasi yang dihasilkan dari pohon-pohon contoh memenuhi syarat
sekurang-kurangnya sama dengan koefisien korelasi yang telah ditetapkan, maka
dalam tegakan hutan yang diukur dapat dibuat tabel volume lokal (tarif volume),
yaitu tabel volume dengan kunci pembacanya cukup dengan menggunakan satu
peubah, yaitu diameter pohon.
6. Scatter diagram dan penentuan model penyusunan tabel volume
Untuk membantu dalam pemilihan model, maka data pohon contoh
ditampilkan dalam Scatter diagram atau scatterplot (diagram tebar). Dari tebaran
mengikuti pola linier ataukah non linier, sehingga dapat membantu dalam
pemilihan model pendekatannya.
Salah satu contoh gambar scatterplot diagram persebaran kelas diameter
dengan volume pohon yang akan dijadikan model persamaan regresi dalam
penyusunan tabel volume pohon.
Gambar 2 Contoh Scatterplot diagram.
Karakteristik paling nyata untuk diukur yang berkaitan dengan volume
pohon adalah diameter setinggi dada (diameter at breast height). Oleh karena itu
semua persamaan volume akan mempunyai diameter setinggi data serta peubah
lainnya dan yang umum ditambahkan sebagai peubah penentu volume pohon
adalah jenis peubah tinggi pohon, baik tinggi total, tinggi bebas cabang ataupun
tinggi yang lain yang dianggap mempunyai peranan dalam tujuan untuk
pendugaan potensi tegakan.
Beberapa persamaan hubungan antara volume pohon dengan peubah-peubah
penentunya yang digunakan dalam penyusunan tabel volume pohon antara lain
(Loetsch et al, 1973) :
Peubah bebas hanya diameter pohon :
1. v = a + bD2 (Kopezky-Gehrhardt)
2. v = a + bD + cD2 (Hohenadl-Krenn)
Dimana :
V : Volume total pohon (m³)
D : Diameter setinggi dada (cm)
a, b, dan c : Konstanta
Dari ketiga persamaan diatas dibuat model persamaan regresi liniernya,
yaitu sebagai berikut :
1. V = a + b D² → model persamaan regresi liniernya adalah
Y1 = β0 + β1X1 + ε1 yang diduga oleh → y1 = b0 + b1X1 + e1
Dimana : V = Y1 = yi b = β1 = b ε1 = e1 = galat sisa
a = β0 = b0 D2 = Xi = x1
2. V = a + bD + cD² → model persamaan regresi liniernya adalah
Y1 = β0 + β1X1 + β2X2 + ε1 yang diduga oleh → y1 = b0 + b1X1 + b2X2 + e1
Dimana : V = Y1 = yi b = β1 = b ε1 = e1 = galat sisa
a = β0 = b0 D= X1i = x1
D2 = X2i = x2
3. V = a Db→ transformasi logaritmis → Log V = Log a + b Log D
Model persamaan regresi linearnya adalah
Y1 = β0 + β1X1 + ε1 yang diduga oleh → y1 = b0 + b1X1 + e1
Dimana : Log V = Y1 = yi b = β1 = b ε1 = e1 = galat sisa
Log a = β0 = b0 Log D= Xi = x1
Sedangkan untuk tabel volume standar dengan peubah bebas diameter dan
tinggi bebas cabang pohon terdiri dari :
1. Model Spurr : V = a (D²Tbc)b
2. Model Schumacher Hall : V = a DbTbcc
3. Model Stoate : V = a + bD2 +cD2Tbc + dTbc
Dimana :
V : Volume total pohon (m³)
D : Diameter setinggi dada (cm)
Tbc : Tinggi bebas cabang pohon (m)
a, b, dan c : Konstanta
Dari ketiga persamaan diatas dibuat model persamaan regresi liniernya,
1. V = a (D²Tbc)b→ transformasi logaritmis → Log V = Log a + b Log (D²Tbc)
Y1 = β0 + β1X1i + εi yang diduga oleh → y1 = b0 + b1X1i + ei
Dimana : Log V = Yi = yi b = β1 = b εi = ei = galat sisa
Log a = β0 = b0 Log(D²Tbc) = Xi = x1i
2. V = a DbTbcc→ transformasi log → Log V = Log a + b Log D + c Log Tbc
Y1 = β0 + β1X1i + β2X2i + εi yang diduga oleh → y1 = b0 + b1X1i + b2X2i + ei
Dimana : Log V = Yi = yi b = β1 = b1 ε1 = ei = galat sisa
Log a = β0 = b0 c = β2 = b2
Log Tbc= X2i = x2i Log D= X1i = x1i
3. V = a + bD2 +cD2Tbc + dTbc → Model persamaan regresi linearnya adalah
Y1 = β0 + β1X1i + β2X2i + β3X3i + εi yang diduga oleh → y1 = b0 + b1X1i + b2X2i +
b3X3i + ei
Dimana : V = Yi = yi a = β0 = b0 c = β2 = b2
D2 = X1i = x1i b = β1 = b1 d = β3 = b3
D2Tbc = X2i = x2i Tbc = X3i = x3i εi = ei = galat sisa
7. Penyusunan tabel volume
Tarif volume pohon maupun tabel volume pohon standar dapat disusun
dengan menggunakan analisa regresi linier dengan pengujian signifikasi
regresinya menggunakan analisa ragam (analysis of variance). Untuk penyusunan
tarif volume pohon dapat dianalisa dengan regresi linier sederhana (simple linear
regression), sedangkan untuk tabel volume pohon standar dianalisa dengan regresi
linier berganda (multiple linear regression). Banyaknya model regresi yang
dicoba sebanyak 2–3 model.
8. Menghitung koefisien regresi dan koefisien korelasi
Untuk dapat menghasilkan persamaan-persamaan regresi yang dimaksud,
maka perlu dihitung nilai-nilai dari koefisien-koefisien regresinya (Sutarahardja
et al, 1991).
a. Menghitung koefisien regresi pada penyusunan tabel volume pohon lokal :
Sebagai contoh untuk model regresi linier sederhana sebagai berikut :
i i X i
i e i x b b i
y 0 1 , maka besarnya nilai koefisien regresi b1 sebagai
penduga dari 1 dan besarnya nilai konstanta b0 (intersept) sebagai penduga dari
0
dapat dihitung dari nilai-nilai data pohon contoh.
JKx JHKxy
b
1 dan
x b y b
1 0
Dimana : y = volume pohon dalam m3 dan x = diameter pohon dalam cm.
Koefisien korelasi ( r ) antara volume pohon dengan diameter pohon dapat
dihitung dengan rumus (1) tersebut diatas atau dengan rumus :
JKy JHKxy b
r 1
b. Menghitung koefisien regresi pada penyusunan tabel volume pohon
standar
Sebagai contoh untuk model regresi linier berganda sebagai berikut :
i i X i X i
Y 01 1 2 2 , dengan penduga modelnya
i e i x b i x b b i
y 0 1 1 2 2 , maka besarnya nilai-nilai penduga
koefisien-koefisien regresi (b1,b2) serta intersept b0 dapat dihitung berdasar data pohon
contoh yang diambil.
2 ) 2 1 ( ) 2 )( 1 ( ) 2 )( 2 1 ( ) 1 )( 2 ( 1 x JHKx JKx JKx y JHKx x JHKx y JHKx JKx b
2
n n i x n i x n i x x x JKx 11 12
11 2 2 1
n n i y n i x n i y x y JKx 11 1
11 1
n n i y n i x n i y x y JKx 1 2 1
12 2 2 2 1 1
0 y b x b x
b
Koefisien determinasi (R2) dari model regresi tersebut dapat dihitung :
total JK
regresi JK
R2
Koefisien korelasi berganda
R dapat diperoleh dari akar koefisiendeterminasi tersebut diatas.
y JHKx b y JHKx b regresi
JK 1 1 2 2
n n i i y n i i y JKy total JK 2 1 1 2 9. Analisa keragaman
Terhadap persamaan-persamaan regresi tersebut dilakukan pengujian
dengan menggunakan analisa keragaman (analysis of variance) untuk melihat
signifikasi atau adanya ketergantungan peubah-peubah yang menyusun regresi
[image:31.595.99.506.69.777.2]tersebut.
Tabel 7 Analisa keragaman pengujian regresi (Anova)
Sumber keragaman Derajat bebas Jumlah Kuadrat (JK)
Kuadrat Tengah (KT) F-hitung F-tabel
Regresi Sisaan
k = p-1 n-k-1
JKregresi (JKR)
JKsisa (JKS)
KTR=JKR/k KTS=JKS/(n-k-1)
Fhitung =
KTR/KTS
Total n-1 JKtotal (JKT)
Dimana p = banyaknya konstanta (koefisien regresi dan intersept) dan n = banyaknya pohon contoh yang digunakan dalam penyusunan regresi tersebut.
Dalam analisa tersebut hipotesa yang diuji adalah :
a. Pada regresi linier sederhana :
0 : 0
H lawan H1:0
b. Pada regresi linier berganda :
0 : 0 i
H dimana : i = 1,2
: 1
H Sekurang-kurangnya ada i0
Jika H1 yang diterima, maka regresi tersebut nyata, artinya ada keterkaitan
antara peubah bebas (diameter pohon dan atau tinggi pohon) dengan peubah tidak
bebasnya (volume pohon). Dengan kata lain bahwa setiap ada perubahan pada
peubah bebasnya akan terjadi perubahan pada peubah tidak bebasnya. Jika Ho
yang diterima, maka regresi tersebut tidak nyata, artinya persamaan regresi tidak
dapat untuk menduga volume pohon berdasarkan peubah bebasnya.
10. Perhitungan kesalahan sampling (Sampling Error, SE)
Kesalahan sampling adalah kesalahan yang disebabkan karena dilakukannya
pengambilan contoh (sampling). Besarnya kesalahan dapat dihitung dengan
rumus:
� = �2 → � = �2
�
� =� �/2,�� × �
� × 100%
Dimana : SE = Sampling Error
Y = Volume pohon (m³)
� = Rata-rata volume pohon (m³/ha)
� = Simpangan baku rata-rata
�� = Derajat bebas
11. Validasi model
Hasil persamaan-persamaan regresi yang telah diuji tersebut diatas, baik
untuk tabel volume pohon standar, perlu dilakukan uji validasi dengan
menggunakan pohon contoh yang telah dialokasikan sebelumnya khusus untuk
pengujian validasi model. Data pohon contoh tersebut tidak digunakan dalam
penyusunan model-model tabel volume diatas. Uji validasi model dapat dengan
melihat pada nilai-nilai simpangan agregasinya (agregative deviation), simpangan
rata-rata (mean deviation), RMSE (root mean square error), biasnya serta uji beda
nyata antara volume yang diduga dengan tabel terhadap volume nyatanya. Uji
beda nyata bisa dilakukan dengan cara uji Khi-kuadrat.
12. Pengujian validasi model
Nilai-nilai pengujian validasi model tersebut dapat dihitung dengan
rumus-rumus sebagai berikut :
a. Simpangan agregat (agregative deviation)
Simpangan agregat merupakan selisih antara jumlah volume aktual (Va) dan
volume dugaan (Vt) yang diperoleh berdasarkan dari tabel volume pohon, sebagai
persentase terhadap volume dugaan (Vt). Persamaan yang baik memiliki nilai
simpangan agregat (SA) yang berkisar dari -1 sampai +1 (Spurr 1952). Nilai SA
dapat dihitung dengan rumus :
n i V n i V n i V SA ti ai ti 1 1 1
b. Simpangan rata-rata (mean deviation)
Simpangan rata-rata merupakan rata-rata jumlah dari nilai mutlak selisih
antara jumlah volume dugaan (Vt) dan volume aktual (Va), proporsional terhadap
jumlah volume dugaan (Vt). Nilai simpangan rata-rata yang baik adalah tidak
lebih dari 10 % (Spurr 1952). Simpangan rata-rata dapat dihitung dengan rumus :
c. RMSE (root mean square error)
RMSE merupakan akar dari rata-rata jumlah kuadrat nisbah antara selisih
volume dugaan dari tabel volume pohon (Vt) dengan volume aktualnya (Va)
terhadap volume aktual. Nilai RMSE yang lebih kecil, menunjukkan model
persamaan penduga volume yang lebih baik. RMSE dapat dihitung dengan rumus:
% 100 1 2 x n n i V V V RMSE ai ai ti d. BiasBias (e) adalah kesalahan sistematis yang dapat terjadi karena kesalahan
dalam pengukuran, kesalahan teknis pengukuran maupun kesalahan karena alat
ukur (Sutarahardja 1999). Bias dapat dihitung dengan rumus :
% 100 1 x n i n V V V e ai ai ti
e. Uji beda rata-rata Khi-kuadrat (Khi-square test)
Pengujian validasi model persamaan penduga volume pohon, dapat pula
dilakukan dengan menggunakan uji χ² (Khi-kuadrat), yaitu alat untuk menguji
apakah volume yang diduga dengan table volume pohon (Vt) berbeda dengan
volume pohon aktualnya (Va). Dalam hal ini hipotesa yang diuji adalah sebagai
berikut :
Va Vt
H :
0 dan H1 : Vt Va
Kriterium ujinya adalah :
n i V V V hitung ai ai ti 1 2 2 Kaidah keputusannya adalah sebagai berikut :
2 ) 1 , ( 2
tabel n
hitung
, maka terima
0 H 2 ) 1 , ( 2
tabel n
hitung
, maka terima
1
13. Pemilihan model regesi terbaik dan valid
Model persamaan regresi untuk penyusunan tabel volume pohon yang
akurat dan valid adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Dalam analisis regresi menghasilkan nilai-nilai R² yang besar, regresi yang
nyata berdasarkan hasil analisis keragamannya serta sampling error (SE)
yang rendah.
2. Dalam uji validasi harus memenuhi standar pengujian antara lain :
- Persamaan yang baik memiliki nilai simpangan agregat (SA) yang
berkisar berada diantara -1 sampai + 1 (Spurr 1952).
- Persamaan yang baik memiliki nilai Simpangan rata-rata tidak lebih dari
10 % (Spurr 1952).
- Nilai RMSE dan Bias yang kecil menunjukan model persamaan penduga
volume yang lebih baik.
- Apabila hasil uji beda antara nilai rata-rata yang diduga dengan tabel
volume dengan nilai rata-rata nyata (actual), tidak menunjukkan adanya
perbedaan yang nyata (Ho, diterima) maka persamaan penduga volume
BAB IV
KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN
4.1 Sejarah Perusahaan
PT. Ratah Timber merupakan perusahaan swasta nasional yang pada tahun
1970 telah memperoleh kepercayaan dari pemerintah RI melalui Menteri
Pertanian untuk mengusahakan hutan dalam bentuk HPH melalui SK HPH No.
526/Kpts/Um/II/1970 tanggal 7 November 1970. Luas areal IUPHHK adalah
sebesar 125.000 Ha yang terletak di kelompok hutan sungai Ratah Selatan di
Provinsi Kalimantan Timur.
Dasar pemberian hak pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut adalah Forest
Agreement (FA) No. FA/J/003/1970 tanggal 30 Januari 1976. Hak pemanfaatan
hasil hutan kayu tersebut di atas, sesuai dengan diktum terakhir disebutkan bahwa
berlaku selama dua puluh tahun terhitung sejak dikeluarkannya SK HPH. Dengan
demikian maka IUPHHK ini telah berakhir pada tanggal 6 Nopember 1990.
Setelah berakhirnya jangka pengusahaan hutan tersebut, perusahaan
memperoleh perpanjangan sementara dengan luas areal sebesar ± 115.000 Ha.
Luas areal ini didasarkan pada dokumen Project Proposal Perpanjangan.
Perubahan luas dari 125.000 Ha menjadi 115.000 Ha tersebut disebabkan oleh
pengurangan luas areal sebesar 10.000 Ha karena termasuk areal hutan lindung
(HL). Ijin prinsip perpanjangan ini tertuang di dalam Surat Menhut No.
477/Menhut-IV/1993 tanggal 27 Februari 1993.
Berdasarkan Surat Menhut No. 2039/Menhut-IV/1993 tanggal 20 November
1993, PT. Ratah Timber memperoleh tambahan areal seluas 12.000 Ha yang
berasal dari eks IUPHHK PT. Budi Dharma Bhakti Djayaraya, sehingga luas
areal IUPHHK PT. Ratah Timber menjadi 127.000 Ha.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 95/Kpts-II/2000 tanggal 22
Desember 2000 luas areal IUPHHK PT. Ratah Timber ditetapkan seluas 97.690
Ha. Pengurangan areal tersebut terjadi karena sebagian areal IUPHHK termasuk
dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) seluas 29.310 Ha. Pada
penyusunan RKUPHHK periode 1990-2010 ini luas yang digunakan adalah luas
Berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No. 477/Menhut-IV/1993 IUPHHK
PT. Ratah Timber diperpanjang ijin IUPHHK-nya dengan syarat menyertakan
BUMN PT. Inhutani II dan Koperasi dalam kepemilikan saham perusahaan.
Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana tertuang di
dalam akta notaris H. Azhar Alia, SH No. 2 tanggal 4 Juni 1998 susunan
pemegang saham PT. Ratah Timber adalah sebagai berikut:
– PT. Long Bangun Putra Timber : 37,5 %
– PT. Tansa Trisna : 37,5 %
– PT. Inhutani II : 20,0 %
– Koperasi : 5,0 %
4.2 Letak dan Luas Perusahaan
Areal kerja IUPHHK PT. Ratah Timber terletak di kelompok hutan Sungai
Ratah, Desa Mamahaq Teboq, Kecamatan Longhubung, Kabupaten Kutai Barat,
Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis terletak pada 114° 55’ - 115° 30’
Bujur Timur dan 0° 2’ LS - 0° 15’ LU. Menurut pembagian wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), areal kerja termasuk ke dalam kelompok hutan Sungai
Ratah, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Mamahaq Besar, Cabang
Dinas Kehutanan (CDK) Mahakam Hulu, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Timur. Sedangkan menurut pembagian wilayah administratif pemerintahan
termasuk dalam Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi
Kalimantan Timur. Batas-batas areal kerja tersebut adalah :
- Sebelah Utara : KBNK, Areal Perkebunan KSU Dayak Kaltim Abadi
dan IUPHHK PT. INHUTANI I (eks. IUPHHK PT.
Mulawarman Bhakti).
- Sebelah Timur : KBNK dan eks. IUPHHK PT. Hacienda Wood
Nusantara Industries.
- Sebelah Selatan : Hutan Lindung Batu Buring Ayok (eks. IUPHHK PT.
Budi Dharma Bhakti Djayaraya).
- Sebelah Barat : Hutan Lindung Batu Buring Ayok (eks. areal kerja PT.
Luas areal kerja IUPHHK PT. Ratah Timber mengalami beberapa
perubahan dimulai sejak diterbitkan SK IUPHHK tahun 1970, dengan dasar
sebagai berikut :
a. SK HPH tahun 1970 : 125.000 Ha
b. Hutan lindung (dikeluarkan) : (10.000) Ha
c. Persetujuan penggabungan areal eks IUPHHK PT. BDBD : 12.000 Ha
d. Ijin perpanjangan IUPHHK sementara (tahun 1993) : 127.000 Ha
e. SK Tata Batas Temu Gelang tahun 1998 : 126.753 Ha
f. SK IUPHHK pembaharuan tahun 2000 : 97.690 Ha
Berdasarkan Peta Paduserasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
(RTRWP) dan TGHK Kalimantan Timur yaitu Peta Penunjukan Kawasan Hutan
dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur skala 1 : 125.000, areal IUPHHK
tersebut terdiri dari Hutan Produksi tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas
(HPT). Rincian luas areal IUPHHK PT. Ratah Timber berdasarkan fungsi hutan
disajikan pada Tabel 8.
Tabel 8 Luas areal IUPHHK PT. Ratah Timber berdasarkan peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Timur
No Fungsi hutan Unit I Unit II Jumlah
Ha Ha Ha %
1 Hutan produksi terbatas 29.620 0 29.620 30,32
2 Hutan produksi tetap 59.990 8.080 68.070 69,68
Jumlah 89.610 8.080 97.690 100
Sumber : Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur Skala 1 : 250.000, yang dikutip dari RKUPHHK-HA PT. Ratah Timber Kalimantan Timur, 2005
4.3 Kondisi Hutan
1. Kondisi penutupan lahan
Hasil analisa dan pengukuran planimetris terhadap peta penutupan lahan
yang diperoleh dari hasil analisis antara peta interpretasi foto udara yang dikoreksi
dengan data hasil penafsiran Citra Landsat skala 1 : 100.000 (mosaik dari liputan
Mei 2006, April 2005, Juni 2005 yang dikoreksi Baplanhut sesuai surat No.
S.564/VII/Pusin-1/2006) dan realisasi tebangan sampai dengan 2005
menunjukkan bahwa areal IUPHHK-HA PT. Ratah Timber seluas 97.690 Ha
terdiri dari areal hutan primer seluas 10.007 Ha (10,24 %), bekas tebangan 78.072
Dari hutan primer yang tersisa tersebut seluruhnya adalah hutan
prenges/kerangas yang tidak produktif yang mana sampai saat ini ti