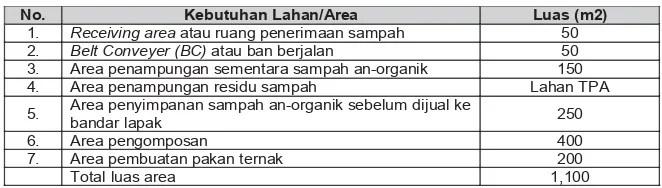Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Diterbitkan oleh: Kelompok Kerja Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan Penasihat/Pelindung: Direktur Jenderal Tata Perkotaan dan
Perdesaan, DEPKIMPRASWIL Penanggung Jawab: Direktur Permukiman dan Perumahan,
BAPPENAS
Direktur Penyehatan Air dan Sanitasi, DEPKES
Direktur Perkotaan dan Perdesaan Wilayah Timur, DEPKIMPRASWIL Direktur Bina Sumber Daya Alam dan
Teknologi Tepat Guna, DEPDAGRI Direktur Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, DEPDAGRI
Pemimpin Redaksi: Oswar Mungkasa Dewan Redaksi: Hartoyo, Johan Susmono, Indar Parawansa, Poedjastanto
Redaktur Pelaksana: Maraita Listyasari, Rewang Budiyana,
Rheidda Pramudhy, Joko Wartono, Essy Asiah, Mujiyanto
Desain/Ilustrasi: Rudi Kosasih
Produksi: Machrudin Sirkulasi/Distribusi:
Anggie Rifki Alamat Redaksi:
Jl. Cianjur No. 4 Menteng, Jakarta Pusat. Telp. (021) 31904113
e-mail: [email protected] [email protected] [email protected]
Redaksi menerima kiriman tulisan/artikel dari luar. Isi berkaitan dengan air minum dan penyehatan
lingkungan dan belum pernah dipublikasikan. Panjang naskah tak
Dari Redaksi 1
Suara Anda 2
Laporan Utama 3
Sampah Masih Jadi ‘Sampah’ 3
Seputar Sampah 6
Upaya Mengurangi Emisi Metan dari TPA 8
Belajarlah Sampah ke Negeri Cina 9
Program Bangun Praja, Memacu Daerah Peduli Lingkungan 11 Wawancara
‘Penanganan Sampah Jelek, Tingkat Kesehatan Rendah’ 13 Wawasan
Sampah Sebagai Sumber Energi, Tantangan Bagi
Dunia Persampahan Indonesia Masa Depan 16
Pre-Studi Masalah Sampah, Kasus Kota Surabaya 18
Pengelolaan Sampah di Makassar 20
Pengelolaan Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
dan Tantangan ke Depan 22
Masalah AMPL di Kabupaten Kebumen 23
Sistem Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga di Kota Tangerang 25 Sampah Membawa Berkah di Desa Temesi, Kabupaten Gianyar, Bali 27 Reportase
Kiprah Ny. Bambang ‘’Sampah’’ Wahono,
Kelola Sampah, Hijaukan Banjarsari 29
Ragam
Ragam Teknologi Pengolahan Sampah 32
Kapsul Sampah, Model Penyimpanan Sampah Jangka Panjang 34 Teropong
Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung 35
Info Buku 37
Info CD 38
Info Situs 39
Kunjungan
Diseminasi Program WASPOLA di Propinsi Gorontalo 40
Pringga Jurang Keruntuhan Bulan 41
Seputar WASPOLA
Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat di Daerah 42
Lokakarya Kelompok Kerja WASPOLA 44
Pertemuan Tim Pengarah WASPOLA 45
Seputar AMPL
Orientasi MPA/PHAST 46
Pokja AMPL Ikuti Nusantara Water 2004 47
Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Proyek ProAir 47 Seminar Teknologi Tepat Guna Pengolahan Limbah Cair 48
P
embaca, Percik mulai mena-paki babak baru yakni bagai-mana Percikmulai menjang-kau para pemangku kepentingan air minum dan penyehatan lingkungan di seluruh Tanah Air. Percik telah menyebar dari Sabang sampai Me-rauke meski dalam jumlah yang ter-batas.Alhamdulillah, berbagai kala-ngan menyambut hangat kehadiran
Percik. Ini dibuktikan dengan ba-nyaknya tanggapan yang datang kepada kami. Bahkan ada beberapa kalangan yang berharap bisa ber-langganan Percik kendati harus membayar –padahal Percik meru-pakan majalah gratis. Ini tentu hal yang membahagiakan kami.
Beberapa waktu lalu kami meng-ikuti Nusantara Water 2004 di Ja-karta Convention Center bersama dengan Program WASPOLA dan Ke-lompok Kerja Air Minum dan Pe-nyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) sebagai induk kami. Langkah itu merupakan upaya kami untuk ma-kin mendekatkan Percikke tengah-tengah pemangku kepentingan AMPL. Kami akan terus berupaya agar majalah ini makin eksis dan menjadi rujukan, referensi, dan wa-dah komunikasi bagi pihak-pihak terkait di bidang ini.
Pembaca, pada edisi ini, Percik
hadir dengan laporan utama menge-nai sampah. Mengapa ini diangkat? Sampah merupakan suatu hal yang masih menjadi persoalan di negeri ini. Isu penyehatan lingkungan tak pernah lepas dari sampah. Semua orang tahu itu, tapi tak semua orang memiliki kepedulian terhadap ma-salah yang satu ini. Ibarat peribaha-sa, ‘’Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu’’, sampah tak pernah kunjung usai penanganannya meski banyak pihak berbicara kebersihan dan kesehatan.
Persoalan sampah sebenarnya bukan sekadar persoalan teknis. Teknologi apa yang cocok dan bera-pa dana yang dibutuhkan. Sekjen Departemen Permukiman dan Pra-sarana Wilayah, Budiman Arief, menjelaskan itu. Kuncinya, pena-nganan sampah harus merupakan langkah yang sistemik. Lebih dari itu, menarik kiranya pandangan M. Gempur Adnan, Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kewilayahan bahwa itu semua tergantung men semua pihak. Tanpa ada komit-men, jangan diharap persoalan sam-pah akan tuntas. Dana hanyalah masalah nomor kesekian.
Percik kali ini juga banyak memuat artikel-artikel sampah dari para praktisi dan pegiat sampah. Kami berharap dengan banyaknya artikel yang sesuai dengan laporan
utama, pengetahuan kita mengenai sampah semakin bertambah luas.
Yang tak kalah menarik, ada reportase mengenai peran perempu-an dalam mengelola sampah sejak dari hulu. Berkat keuletannya itu, kampungnya yang berada di jantung kota Jakarta, berubah hijau dan asri. Bahkan kini kampung tersebut menjadi salah satu tujuan wisata lingkungan. Banyak orang, baik dari dalam dan luar negeri, yang belajar dari perempuan tersebut. Dan ber-kat usahanya itu pula ia menyabet berbagai penghargaan.
Seperti biasanya, Percik tetap menampilkan rubrik-rubrik rutin lainnya. Kami berharap ada ma-sukan dan kritik dari para pembaca demi perbaikan majalah ini ke de-pan.
Akhirnya kami berharap Percik
berguna bagi Anda, para pembaca. Salam.
A R I R E D A K S I
D
LESEHAN
MDGs Kurang Greget
Kami ucapkan selamat atas terbitnya media informasi Percik. Izinkanlah kami menyarankan agar Millennium Development Goals (MDGs) disosialisa-sikan terlebih dahulu ke daerah supaya gregetnya atau gaungnya sampai ke teli-nga masyarakat sehingga masyarakat sendiri terinspirasi dan memiliki tang-gung jawab moral untuk mewujudkan target MDGs.
Natalia Silitonga
Kantor Bupati Toba Samosir Bagian Perekonomian-Kasubbag Kimpraswil Jl. Pagar Batu No. 1 Balige Sumatera Utara
Saran Anda sangat sesuai dengan harapan kami. Para pemangku kepen-tingan soal ini kini sedang berupaya
melakukan sosialisasi. Kami pun ikut andil dalam masalah ini dengan memu-atnya pada Percik edisi 3 yang lalu. Apa yang kami lakukan memang belum apa-apa tanpa ada gerakan sosialisasi yang tersistem dari para pemangku ke-pentingan MDGs itu sendiri.(Redaksi)
Membantu
Stakeholder
di Daerah
Adanya media informasi air minum dan penyehatan lingkungan (Percik) akan sangat membantu kami dalam me-laksanakan interaksi dengan pemangku kepentingan (stakeholder)di bidang air minum agar tercipta suatu kerja sama para pemangku kepentingan dengan program seksi penyehatan air dan pengamanan limbah di Dinas
Kese-hatan Kabupaten Musi Rawas, Prop. Sumatera Selatan, menuju Indonesia Sehat 2010.
Drs. H. Syamsul Anwar, MF, MM
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas
Kami sangat senang bila para pembaca bisa mengambil manfaat dari Percik. Ma-jalah ini memang diterbitkan untuk menyo-sialisasikan berbagai kebijakan dan pro-gram air minum dan penyehatan lingkung-an sekaligus menjadi ajlingkung-ang para pemlingkung-angku kepentingan untuk saling berbagi penga-laman dan berkomunikasi. (Redaksi)
Kami menerima ucapan selamat dan terima kasih dari berbagai pihak yang tidak bisa kami sebut satu per satu atas terbit dan dikirimnya Percik.
(Redaksi)
U A R A A N D A
S
Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
(Pokja AMPL) bekerja sama dengan Departemen
Permukiman dan Prasarana Wilayah (Dep. KIMPRASWIL)
Menyelenggarakan Lomba Karya Tulis
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
TEMA :
PENYELENGGARAAN AIR MINUM DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT
SUB TEMA :
1) Pemberdayaan Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan
2) Pendanaan Berbasis Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan
3) Kelembagaan Pengelolaan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan berbasis masyarakat
4) Peran Wanita dalam Penyelenggaraan Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan
PERSYARATAN
1. Peserta Lomba : Masyarakat Umum
2. Panjang tulisan 10-15 halaman folio; 1,5 spasi
dan ditulis dalam bahasa Indonesia.
Naskah digandakan 5 (lima) kali.
3. Tulisan belum pernah dipublikasikan
4. Peserta melampirkan foto copy identitas.
5. Karya Tulis diserahkan ke Panitia Lomba
Paling Lambat tanggal
28 Oktober 2004
6. Pemenang Karya Tulis akan Diumumkan
tanggal
28 November 2004
7. Hadiah:
Pemenang 1 Rp. 5.000.000
Pemenang 2 Rp. 3.000.000
Pemenang 3 Rp. 1.500.000
Keterangan lebih lanjut silakan hubungi
Panitia Lomba Karya Tulis
Jl Cianjur No. 4 Menteng,
Jakarta Pusat
Telp. (021) 31904113
M
ungkin bagi sebagian orang selembar kertas, atau setas limbah rumah tangga tak jadi masalah. Tapi begitu kertas dan limbah rumah tangga itu berkumpul dengan sampah sejenis dari banyak orang, persoalan akan timbul, apalagi di perkotaan yang lahannya terbatas. Dan faktanya menunjukkan potensi timbulan sampah terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.Timbulan sampah
Tidak tersedia data berapa persisnya jumlah timbulan sampah di Indonesia. Namun berdasar hasil perhitungan Bappenas sebagaimana tercantum dalam Buku Infrastruktur Indonesia, pada tahun 1995 perkiraan timbulan sampah di Indonesia mencapai 22,5 juta ton, dan meningkat lebih dua kali lipat pada tahun 2020 menjadi 53,7 juta ton. Sementara di kota besar di Indonesia diperkirakan tim-bulan sampah per kapita berkisar antara
600 – 830 gram per hari.
Sebagai ilustrasi betapa besarnya tim-bulan sampah yang dihasilkan, data beberapa kota besar di Indonesia dapat menjadi rujukan. Kota Jakarta setiap hari menghasilkan timbulan sampah sebesar 6,2 ribu ton, Kota Bandung sebe-sar 2,1 ribu ton, Kota Surabaya sebesebe-sar 1,7 ribu ton, dan Kota Makassar 0,8 ribu ton (Damanhuri, 2002). Jumlah tersebut membutuhkan upaya yang tidak sedikit dalam penanganannya.
Berdasarkan data tersebut diperki-rakan kebutuhan lahan untuk TPA di Indonesia pada tahun 1995 yaitu seluas 675 ha, dan meningkat menjadi 1.610 ha pada tahun 2020. Kondisi ini akan men-jadi masalah besar dengan memper-hatikan semakin terbatasnya lahan kosong khususnya di perkotaan. Salah satu contoh terkini adalah kesulitan pemerintah DKI Jakarta dalam
menyedi-Kita tidak pernah lepas dari sampah. Setiap hari ada saja
sampah yang harus kita buang. Entah di kantor,
di rumah, di manapun kita berada. Tidak heran ketika
kita tidak mengelola dengan baik maka sampah
akan dengan mudah kita temui bertebaran
di sekitar kita.
A P O R A N U T A M A
L
SAMPAH
Masih Jadi ‘Sampah’
SAMPAH
Masih Jadi ‘Sampah’
akan lahan untuk pengolahan sampah setelah TPA Bantar Gebang tidak dapat dipergunakan lagi.
Penanganan Sampah
Menurut data BPS, pada tahun 2001 timbulan sampah yang diangkut hanya mencapai 18,03 persen, sementara selebih-nya ditimbun 10,46 persen, dibu-at kompos 3,51 persen, dibakar 43,76 persen, dan lainnya (dibuang ke sungai, pekarangan kosong dan lainnya) 24,24 persen. Terlihat bahwa sampah yang diangkut masih sangat sedikit, demikian pula sampah yang diproses menjadi kom-pos, sementara yang dibakar dan dibuang ke tempat yang tidak seharusnya bahkan masih mencapai 68 persen. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya potensi sampah menjadi sumber pencemaran baik udara, maupun air termasuk menja-di pemicu timbulnya penyakit. Di dae-rah perkotaan sekalipun, sampah yang dibakar dan dibuang sembarangan masih mencapai 50,76 persen. Proporsi sampah yang ditimbun sendiri masih cukup besar mencapai 10,46 persen. Sampah seperti plastik dan sejenisnya relatif sulit diurai sehingga penanganan sampah dengan cara menimbun menjadi kurang tepat. Pengomposan juga belum populer di masyarakat.
Sebagian besar Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah direncanakan meng-gunakan sistem sanitary landfill. Namun dalam perjalanan waktu, akhirnya seba-gian besar TPA tersebut akhirnya meng-gunakan sistem open dumping (70 persen) dan hanya sebagian kecil yang tetap menggunakan sistem controlled landfilldan sanitary landfill (30 persen). Beberapa kota yang menerapkan con-trolled landfill di antaranya Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Padang, Malang, Yogyakarta, Pontianak, Balik-papan, Banjarmasin, dan Denpasar.
Penyebab rendahnya penerapan sis-tem sanitary landfilldi Indonesia, antara lain, rendahnya disiplin pengelola dalam menerapkan prosedur teknis, terbatasnya anggaran untuk operasi dan pemeli-haraan, sulitnya mendapatkan tanah penutup, terbatasnya ketersediaan alat berat, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan belum terorganisasikannya pemulung di lokasi TPA sebagai bagian terpadu sistem sanitary landfill.
Karakteristik Sampah
Karakteristik sampah perkotaan berbeda dengan sampah perdesaan. Secara umum, sampah perkotaan di Indonesia memiliki komposisi 80 persen sampah organik, dan selebihnya sampah non-organik. Sampah non organik terse-but separuhnya merupakan sampah plas-tik.
Isu Utama
Cakupan pelayanan pengelolaan per-sampahan yang masih rendah khususnya di perkotaan dapat berdampak pada meningkatnya wabah penyakit menular seperti tipus, kolera, muntaber, disentri, pes, leptospirosis, salmonelosis, demam gigitan tikus. Selain juga sampah yang dibuang ke sungai dan saluran pembu-angan berpotensi menimbulkan banjir.
Prinsip pengurangan timbulan sam-pah pada dasarnya telah dikenal dan
mulai dilakukan walaupun masih dalam skala kecil dan sebagian besar dilakukan oleh pemulung. Pengomposan pun sudah dila-kukan namun dalam jumlah yang sangat terbatas.
Sementara itu TPA yang ada tidak dikelola dengan baik. Masih terjadi pembakaran sampah untuk mengurangi timbunan sampah, dan tidak terkelolanya gas metan yang dihasilkan oleh timbunan sampah. Sementara dalam Kyoto Protocolyang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, pengurangan gas metan men-jadi salah satu persyaratan. Masalah lain-nya yang timbul akibat pengelolaan TPA yang tidak sesuai persyaratan di antaranya timbulnya bau, menurunnya kualitas air akibat pembuangan sampah ke sungai, merembesnya air lindi dari TPA ke air tanah dangkal dan air per-mukaan, pencemaran udara serta mere-baknya dioxin yang bersifat karsinogen.
Kesadaran masyarakat akan kebersih-an sudah baik tetapi terbatas hkebersih-anya pada lingkungan halaman rumah saja. Rumah memang bebas dari sampah tetapi sam-pah tersebut dibuang tidak pada tempat-nya seperti selokan, sungai, dan bahkan halaman kosong milik tetangga. Feno-mena NIMBY (Not In My Backyard) sa-ngat terasa di sini.
Hal ini juga didorong oleh belum tersedianya pelayanan persampahan yang memadai.
Jika dibandingkan dengan kesediaan membayar pelayanan air minum maka kesediaan membayar pengelolaan sam-pah relatif lebih rendah. Ini terjadi kare-na masyarakat tidak mengetahui sebe-narnya seperti apa pengelolaan sampah itu berlangsung.
Rendahnya tingkat pengorbanan masyarakat untuk memberikan kon-tribusinya berbanding terbalik dengan jumlah timbulan sampah. Kebutuhan lahan untuk lokasi TPA meningkat. Perlu
A P O R A N U T A M A
L
Penanganan Sam pah (%)
0
Diangkut Ditimbun Dibuat Kompos
dicari alternatif pengolahan sampah yang tidak memerlukan lahan yang luas.
Di sisi lain, saat ini belum tersedia kebijakan nasional persampahan yang dapat menjadi payung pengelolaan per-sampahan oleh seluruh pemangku kepentingan. Peraturan-peraturan yang ada ‘tercecer’ di daerah atau instansi sek-toral. Wajar bila hingga kini belum terwu-jud sistem kelembagaan, koordinasi dan integrasi pengelolaan sampah.
Dimulainya era otonomi daerah men-jadikan pengelolaan sampah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun di lain pihak, masih banyak pemerintah daerah yang menganggap persampahan bukan prioritas. Ini terlihat dari minim-nya alokasi anggaran ke sektor ini.
Kebijakan ke Depan
Penyelesaian persampahan mau tidak mau harus dilakukan secara sistemik dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Apalagi pada 2025 telah dicanangkan sebagai tahun zero waste (bebas sampah) dunia. Beberapa langkah yang bisa diambil dalam rangka menuju ke arah itu yakni:
1. Mengurangi volume timbulan sam-pah dengan menggunakan konsep 3R (reduce, reuse, dan recycle).
Metode ini perlu disosialisa-sikan ke tengah-tengah masya-rakat agar mereka mau menggu-nakan kembali dan mendaur ulang sampahnya. Tentu langkah ini perlu dibarengi penyadaran akan pentingnya memilah sam-pah di rumah tangga sehingga memudahkan pengolahan pada tahap berikutnya. Konsep 3R akan makin efektif jika didukung peraturan perundang-undangan yang memberikan penghargaan dan hukuman (reward and pu-nishment) kepada semua pe-mangku kepentingan yang ter-kait, apakah itu pemulung,
ma-syarakat, dan lainnya. Selain itu, peman-faatan sampah sebagai sumber energi (wasre to energy) layak untuk diper-hatikan mengingat hingga kini belum ada pihak yang mempraktekkan langkah ini di Indonesia. Bila sampah telah terman-faatkan sejak dari hulu maka sistem sani-tary landfill tidak memerlukan lahan yang luas dengan biaya besar. Sanitary landfill hanya digunakan untuk mengo-lah residu dari hasil pembakaran insine-rator.
2. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha
Langkah mengurangi timbulan sam-pah tidak akan efektif tanpa peran aktif masyarakat. Merekalah penghasil utama sampah dan mereka pula yang merasakan dampak negatifnya bila sampah tak dikelola dengan baik. Kuncinya adalah peningkatan kesadaran dan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Masyarakat bisa berperan sebagai a) pe-ngelola (mengurangi timbulan sampah dari sumber); b) pengawas (mengawasi tahapan pengelolaan agar berjalan dengan benar); c) pemanfaat (memanfaatkan sampah secara individu, kelompok, atau kerja sama dengan dunia usaha); d) pengolah (mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana peng-olah sampah); e) penyedia biaya
pengelo-laan (lihat diagram.)
3. Peningkatan peran antarpemerin-tah daerah dalam pengelolaan sampah
Persoalan sampah pada dasarnya bukan persoalan individual kota tapi per-soalan regional. Polusi udara, air, dan tanah berdampak pada wilayah yang luas melintasi batas administratif. Oleh kare-na itu penentuan lokasi TPA yang selama ini berdasarkan wilayah administratif men-jadi tidak relevan. Di masa mendatang kon-sep TPA regional dan terpusat (regional solid waste management) perlu dikem-bangkan sebagai upaya bersama dalam mengatasi kesulitan lahan TPA.
4. Pengembangan teknologi baru Kemampuan pelayanan persampahan tergantung pada pilihan teknologi yang tersedia. Penggunaan teknologi yang tepat akan mengoptimalkan pengelolaan persampahan. Oleh karena itu, penggu-naan teknologi baru bisa menjadi alter-natif peningkatan kemampuan pengelo-laan persampahan khususnya di kota besar.
5. Peningkatan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat
Pengelolaan sampah tak akan berhasil tanpa ada kesadaran masyarakat bahwa lingkungan sehat juga merupakan kebutuhan pokok mereka. Peningkat-an kesadarPeningkat-an ini harus dilakukPeningkat-an secara terus menerus kepada seluruh lapisan masyarakat. Program edukasi di bidang kesehatan perlu ditanam-kan sejak dini kepada siswa sekolah.
Akhirnya, meningkatkan kepe-dulian semua pemangku kepenting-an (stakeholder) di bidang persam-pahan tak bisa ditawar-tawar lagi. Seberapa canggih teknologi, uang banyak, sumber daya bagus, tapi tidak ada perhatian serius dari pe-mangku kepentingan, maka persoal-an sampah akpersoal-an tetap menjadi ‘sam-pah’. OM/MJ
A P O R A N U T A M A
Apa itu sampah?
Sampah adalah suatu bahan yang ter-buang atau diter-buang dari sumber hasil ak-tifitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis
Bagaimana pengklasifikasian sampah?
zSampah dapat diklasifikasikan ber-dasar sumbernya yaitu (i) sampah domestik yang terdiri dari sampah rumah tangga, bongkaran bangunan, sanitasi dan sampah jalanan. Secara umum sam-pah jenis ini berasal dari perumahan dan kompleks perdagangan (ii) sampah berbahaya seperti sampah industri dan sampah rumah sakit yang kemungkinan mengandung racun. Beberapa sampah rumah tangga juga termasuk sampah berbahaya seperti baterai, semir sepatu-cat, botol obat; (iii) sampah medis
zSampah dapat diklasifikasikan ber-dasar bentuknya yaitu (i) sampah anorga-nik/kering seperti logam, besi, kaleng, bo-tol yang tidak dapat mengalami pembu-sukan secara alami; (ii) sampah or-ganik/basah seperti sampah dapur, res-toran, sisa makanan yang dapat mengala-mi pembusukan secara alamengala-mi; (iii) sam-pah berbahaya seperti baterai, jarum sun-tik bekas.
z Sampah dapat diklasifikasikan berdasar kemampuan sampah untuk di-hancurkan yaitu (i) biodegradableyaitu sampah yang dapat mengalami pembu-sukan alami termasuk sampah organik seperti sampah dapur, sayuran, buah, bunga, daun dan kertas; (ii) nonbio-degradableyang terdiri dari sampah da-ur ulang seperti plastik, kertas, gelas; sampah beracun seperti obat, cat, bate-rai, semir sepatu; sampah medis seperti jarum suntik.
Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan sampah?
Lama waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan sampah sangat beragam
tergantung pada jenis sampah. Pada umumnya sampah organik dapat dihan-curkan dalam jangka waktu singkat, se-mentara sampah seperti plastik bahkan diperkirakan baru akan hancur setelah 1 juta tahun.
Bagaimana langkah pengurangan produksi sampah domestik?
Produksi sampah dapat dikurangi.
Prinsipnya adalah pengurangan sampah tersebut harus dilakukan sedekat mung-kin dengan sumbernya. Dalam kaitan de-ngan pengurade-ngan sampah, maka kita te-lah mengenal prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang kemudian berkembang menjadi 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Re-fuse). Perbedaan mendasar dari prinsip 3R dan 4R terletak pada penambahan prinsip Refuse (kadang disebut juga replace) yang memfokuskan pada peng-gunaan barang yang lebih tahan lama dibanding barang sekali pakai.
Keuntungan penerapan prinsip 4R di antaranya adalah mengurangi efek rumah kaca, mengurangi polusi udara dan air, menghemat energi, konservasi sumber daya, mengurangi kebutuhan lahan untuk TPA, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong penciptaan teknologi hijau.
Jenis sampah sangat bergantung pada budaya masyarakat. Pada masyarakat modern khususnya di kota besar penggu-naan sampah plastik sangat dominan. Sebagai ilustrasi, sebagian besar sampah domestik berasal dari kantong plastik (kresek) belanja rumah tangga, atau sty-rofoam untuk wadah makanan. Semen-tara sampah plastik merupakan ancaman terbesar bagi lingkungan karena waktu hancurnya mencapai 1 juta tahun (mung-kin sudah keburu kiamat sebelum
sam-A P O R sam-A N U T sam-A M sam-A
Seputar Sampah
L
Sampah organik (tumbuhan, buah dan sejenisnya)
1-2 minggu
Kertas 10-30 hari Baju katun 2-5 bulan
Kayu 10-15 tahun
wool 1 tahun
Alumunium, kaleng, dan sejenisnya
100-500 tahun
Kantong plastik 1 juta tahun? Botol gelas Tidak diketahui
1. Refuse. Menggunakan barang yang lebih tahan lama dari pada barang sekali pakai. 2. Reduce. Mengurangi
timbulan sampah.
3. Reuse. Menggunakan barang yang bisa dipergunakan kembali.
4. Recycle. Menggunakan 4R (Refuse, Reuse, Recycle, Reduce)
1. Refuse.Menggunakan barang yang lebih tahan lama dari pada barang sekali pakai.
2. Reduce.Mengurangi timbulan sampah.
3. Reuse. Menggunakan barang yang bisa dipergunakan kembali.
4. Recycle.Menggunakan barang yang bisa didaur ulang.
FOTO: OSWAR MUNGKASA
pah plastik tersebut hancur). Kondisi ini menyadarkan kita akan semakin pen-tingnya penerapan prinsip 4R dalam mengurangi timbulan sampah. Jadi ge-rakan mengurangi timbulan sampah harus dimulai dari sumbernya yaitu rumah tangga itu sendiri. Oleh karenanya penerapan prinsip ini sangat tergantung pada kesadaran masyarakat.
Bagaimana cara pengolahan sampah?
Terdapat paling tidak lima cara yang dikenal secara umum dalam pengolahan sampah yaitu
(i). Open dumps. Open dumps me-ngacu pada cara pembuangan sampah pada area terbuka tanpa dilakukan proses apapun.
(ii). Landfills. Landfillsadalah lokasi pembuangan sampah yang relatif lebih baik dari open dumping. Sampah yang ada ditutup dengan tanah kemudian dipadatkan. Setelah lokasi penuh maka lokasi landfill akan ditutup tanah tebal dan kemudian lokasi tersebut biasanya dijadikan tempat parkir.
(iii). Sanitary landfills. Berbeda de-ngan landfills maka sanitary landfills menggunakan material yang kedap air sehingga rembesan air dari sampah tidak akan mencemari lingkungan sekitar.
Biaya sanitary landfillsrelatif jauh lebih mahal.
(iv).Insinerator.Pada cara pengolah-an menggunakpengolah-an insinerator, dilakukpengolah-an pembakaran sampah dengan terlebih dahulu memisahkan sampah daur ulang. Sampah yang tidak dapat didaur ulang kemudian dibakar. Biasanya proses
pem-bakaran sampah dilakukan sebagai alter-natif terakhir atau lebih difokuskan pada penanganan sampah medis.
(v). Pengomposan. Pengomposan adalah proses biologi yang memung-kinkan organisme kecil mengubah sam-pah organik menjadi pupuk.
Sampai seberapa jauh tanggung jawab produsen?
Jika rumah tangga diberi peran untuk mengurangi timbulan sampah melalui prinsip 4R, maka produsen seharusnya juga diberi tanggungjawab yang jelas. Produsen dapat membantu rumah tangga dalam menerapkan prinsip 4R tersebut. Salah satunya melalui EPR (Extended Producer Responsibility/Perluasan Tanggung jawab Produsen) yang meru-pakan usaha mendorong produsen untuk menggunakan kembali produk dan kemasan yang diproduksinya. Pemberian insentif bagi produsen menjadi suatu keniscayaan. OM
Fakta Sampah di Amerika Serikat
zTahun 2001 produksi sampah mencapai 229 juta ton atau sekitar 4,4 pon per orang per hari. Meningkat hampir dua kali produksi sampah tahun 1960.
zSekitar 30 persen sampah didaur ulang, 15 persen dibakar, dan 56 persen dibuang ke TPA
zPada tahun 1999, daur ulang dan pengomposan mengurangi 64 juta ton sampah yang seharusnya dikirim ke TPA. Sekarang ini proses daur ulang dilakukan terhadap 30 persen produksi sampah. Persentase ini meningkat dua kali lipat dibandingkan kondisi 15 tahun yang lalu
zDaur ulang baterai mencapai 94 persen, kertas 42 persen, botol plastik 40 persen, kaleng minuman ringan dan bir 55 persen
zJumlah TPA berkurang dari 8.000 lokasi pada 1998 menjadi 1.858 lokasi pada 2001 dengan kapasitas yang relatif sama.
z Amerika Serikat merupakan negara maju penghasil sampah terbesar di dunia yaitu 4,4 pon sampah per kapita per hari, disusul Kanada 3,75 pon dan Belanda 3 pon. Jerman dan Swedia merupakan negara maju dengan produksi sampah terendah.
z Amerika Serikat merupakan negara maju dengan proporsi daur ulang terbesar yakni 24 persen, disusul Swiss 23 persen, dan Jepang 20 persen.
Fakta Sampah Negara Lain
A P O R A N U T A M A
L
T
PA merupakan sumber terbesar emisi metan di Amerika Serikat bahkan mungkin juga di Indo-nesia. Padahal sebenarnya emisi metan dari TPA dapat menjadi salah satu sum-ber energi yang potensial. LFG (Landfill Gas) dihasilkan ketika sampah dihan-curkan di TPA. Gas ini terdiri dari 50 persen metan (CH4), komponen utama gas alam, dan sisanya CO2. Sebagai ilus-trasi per Desember 2003, terdapat 360 proyek energi berbasis LFG di Amerika Serikat dan sekitar 600 TPA yang poten-sial untuk proyek sejenis.Beberapa keuntungan dari penggu-naan energi LFG adalah (i) akan mengu-rangi bau; (ii) mencegah gas metan ter-lepas ke atmosfir dan mempengaruhi iklim global. Diperkirakan proyek LFG akan mencegah sekitar 60-90 persen metan yang dihasilkan dari proses di TPA, tergantung pada jenis teknologi yang dipergunakan. Metan tersebut diproses menjadi air dan CO2 ketika gas diubah menjadi listrik. Untuk sekitar
4 megawatt listrik setara dengan me-nanam 60 ribu are hutan setahun atau mengurangi emisi CO2 dari 45 ribu mobil setahun. Energi yang dihasilkan juga dapat menggantikan penggunaan batu bara dari 1.000 kereta api atau penggu-naan 500 ribu barel minyak; (iii) mengu-rangi polusi udara dengan mengumengu-rangi penggunaan bahan bakar yang tidak
ter-barukan seperti batu bara, gas alam dan minyak; (iv) menciptakan lapangan kerja, penghasilan dan penghematan biaya.
Program penggunaan LFG di Amerika Serikat telah secara signifikan mengu-rangi emisi metan sebesar 14 juta m3ton setara karbon (MMTCE). Keuntungan reduksi gas rumah kaca setara dengan penanaman 18 juta are hutan atau me-ngurangi emisi tahunan dari 13 juta mobil. Sementara 600 TPA yang berpotensi menghasilkan listrik dari gas metan, ternyata berdasar perhitungan dapat menghasilkan listrik bagi 1 juta rumah.
Terdapat beberapa pilihan proses LFG menjadi energi, di antaranya berupa (i) pembangkit listrik, (ii) penggunaan langsung untuk menggantikan bentuk bahan bakar yang ada seperti gas alam, batu bara, bensin; (iii) cogeneration, merupakan kombinasi panas dan tenaga (Combined Heat and Power/CHP) yang menghasilkan listrik dan energi panas.
Terlepas dari berbagai keuntungan mengubah LFG menjadi energi tetapi ternyata dalam prosesnya menghasilkan emisi NOx yang dapat merusak ozon dan membentuk kabut asap. OM
A P O R A N U T A M A
Upaya Mengurangi
Emisi Metan dari TPA
L
M
ungkin kita kurang menyadari bahwa sampah dapat mempe-ngaruhi iklim melalui emisi gas rumah kaca dengan berbagai cara.Bagaimana kaitan sampah dan perubahan iklim?
Pertama.Penghancuran sampah di TPA menghasilkan gas metan, yang ber-potensi 21 kali lebih kuat dari gas CO2 dalam menyumbang efek rumah kaca.
Kedua. Insinerator menghasilkan CO2. Sebagai tambahan, kendaraan yang mengangkut sampah juga mem-produksi CO2.
Bagaimana strategi pengelolaan sampah mengurangi emisi gas rumah kaca?
z Pengurangan timbulan sampah organik yang diolah di TPA akan me-ngurangi gas metan yang dihasilkan dalam proses penghancuran sampah tersebut.
z Pengurangan timbulan sampah yang diolah insinerator akan mengu-rangi emisi gas rumah kaca.
zBarang yang dapat di daur ulang biasanya menggunakan lebih sedikit energi dalam proses pengolahannya sehingga dapat mengurangi emisi.
Sampah dan Perubahan Iklim
P
esta Olimpiade di Athena baru saja usai, Negara tirai bambu China akan menyambut pesta Olimpiade berikutnya tahun 2008 di Bei-jing. Menjelang Olimpiade 2008 terse-but, Cina mulai sibuk berbenah diri mulai dari penataan infrastruktur kota sampai masalah kebersihan kota. Ini tampak kali di ibukota Cina, Beijing. Kendati se-cara hitungan masih lama, pembenahan perkotaan dan pembangunan infrastruk-tur sudah mulai dilakukan. Maklum, me-reka tak ingin kota berpenduduk 16 juta jiwa itu mengecewakan para atlet, ofisial, dan penggembira yang datang dari selu-ruh penjuru dunia.Dalam rangka event Olimpiade ini, Pemerintah Cina telah mengeluarkan ke-bijakan khusus untuk meningkatkan ku-alitas lingkungan perkotaan termasuk pe-ningkatan sistem pengelolaan persam-pahan. Khusus Kota Beijing, Pemerintah Kota setempat memformulasikan sebuah kebijakan persampahan yakni (i) meningkatkan pelayanan 98 % pada 2007; (ii) daur ulang dan kompos 30 % pada tahun 2007; (3) pemisahan sampah di sumber sampai dengan 50 % pada tahun 2007; (iv) tahun 2007 pengelolaan lokasi landfill harus sesuai dengan ke-tentuan standar lingkungan; dan (v) pe-ngembangan teknologi pengolahan le-chate terus dilakukan untuk mencapai standarefluentyang dipersyaratkan.
Kondisi Pengelolaan Persampahan
Aspek Teknis
Penanganan persampahan di Beijing pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan di Indonesia. Ini karena komposisi dan karakteristik sampah yang hampir sama. Pola penanganan sampah dari sumber sampai TPA hampir sama, termasuk ti-dak dilakukan proses pemilahan sampah di sumber. Hanya saja, Beijing dengan jumlah sampah 9000 ton per hari
(seba-gai perbandingan Jakarta menghasilkan sampah 6.000 ton/hari) memiliki pe-layanan yang yang jauh lebih baik, ter-utama bila ditinjau dari sudah tingginya cakupan pelayanan (90%) maupun kuali-tas pelayanannya. Meskipun tidak dila-kukan pemisahan sampah di sumber, namun transfer stationyang ada kota itu memiliki fasilitas pemisahan sampah, sehingga sampah yang dibuang ke TPA hanya residu. Selanjutnya sampah or-ganik dimanfaatkan sebagai bahan baku kompos (diproses di instalasi kompos skala kota, kapasitas 200–400 ton/hari) dan daur ulang.
Sistem pengumpulan dan pengang-kutan sampah juga hampir sama dengan yang dilakukan di Indonesia, seperti menggunakan gerobak sepeda dan truk (compactor truck). Namun kualitas dan efisiensi pengangkutan sampahnya sa-ngat baik karena setiap radius 8 km di-lengkapi dengan transfer station.
Metode pembuangan akhir sampah dilakukan dengan sistem sanitary land-fillyang sudah cukup memadai. Tabel di bawah ini menggambarkan jumlah land-fill,luas dan kapasitas.
Tabel 1. Lokasi Landfilldi Beijing
Fasilitas landfill tersebut meliputi lapisan dasar kedap air, jaringan pe-ngumpul leachate, kolam penampungan leachate, pengolahan leachate (oxidation ditch), saluran drainase keliling landfill dan drainase setiap lapisan, pengumpul-an gas (saat ini hpengumpul-anya dibakar melalui flare), jalan operasi dan keliling landfill, buffer zone, jembatan timbang, alat
berat, mobil tangki air, penutupan tanah (harian), perkantoran, fasilitas olah raga, dan stok tanah penutup.
Kendati fasilitas cukup lengkap, namun hasil proses pengolahan leachate masih belum sesuai dengan standar effluentyang berlaku untuk kota Beijing. Tabel berikut menggambarkan proses dan kualitas efflu-entdari beberapa landfill yang ada di Beijing dan standar effluentChina dan Beijing:
Tabel 2.
Hasil proses pengolahanleachate
A P O R A N U T A M A
Belajarlah Sampah
ke Negeri Cina
L
No Lokasi Landfill Luas (Ha) Kapasitas (ton/hari)
1 Beishinshu landfill 33,7 1000
2 Liulitun landfill 46,5 1500
3 Asuwei landfill 60 2000
4 Anding landfill 21,6 700
Parameter kualitas efluent leachate Landfills Tipe Proses Pengolahan Leachate COD BOD Amonia Beishinshu Diangkut ke sewerage treatment plant - - - Liulitun Oxidition Ditch 324 22,9 17
Asuwei Oxidation Ditch 787 126 24 Pilot Test RO
Membrane
Filtrasi dengan reverse osmosis 3 - 17 - 1,2 – 15 Pemilahan sampah melalui ban berjalan.
Tabel 3.
Standar efluent China dan Beijing
Penutupan tanah akhir dilakukan dengan menggunakan tanah lempung, geo textile, bentonitedan tanah lempung /top soil. Pemanfaatan lahan pasca ope-rasi sebagai lahan terbuka hijau.
Aspek Manajemen
Pengelolaan sampah di Beijing dila-kukan oleh “Dinas Persampahan” (BSW-AD). Lembaga ini memperoleh alokasi dana (dana investasi maupun O/M) ber-asal dari dana Pemerintah kota Beijing dan kontriibusi dari masyarakat berupa tarif.
Tarif ditentukan berdasarkan jumlah anggota keluarga. Untuk keluarga lebih dari tiga orang, setiap orang harus mem-bayar tarif 3 RMB per bulan (atau setara dengan Rp.3000/orang/bulan). Sedang-kan untuk keluarga yang kurang dari tiga orang tarifnya 2 RMB/orang per bulan (Rp. 2000/orang/bulan). Peran serta masyarakat kota Beijing sangat tinggi, na-mun peran swasta dalam pengelolaan sampah masih sangat terbatas.
Pembelajaran
Aspek Teknis
Peningkatan pelayanan hampir 100 % pada tahun 2007 menunjukkan komit-men Pemerintah sangat tinggi. Kondisi seperti ini diperlukan untuk kota-kota metropolitan seperti Jakarta
Meskipun program 3R belum dilak-sanakan di Beijing, namun proses pemilahan yang dilakukan di transfer station sudah cukup memadai. Kota-kota besar/metropolitan di Indonesia dapat mengembangkan sistem serupa dengan membuat transfer stationyang
dilengkapi dengan proses pemilahan Hal lain yang menarik adalah dalam rangka Olimpiade 2008, pemisahan sampah di sumber ditargetkan 50 % pada tahun 2007. Untuk penerapan di Indonesia program 3R harus mulai serius dilaksanakan
Proses pengangkutan sangat efisien karena setiap radius 8 km memiliki transfer station, di Indonesia transfer stationdiperlukan untuk jarak ke TPA > 25 km
Proses composting dengan kapasitas besar (200-400 ton/hari) cukup memadai (kualitas kompos baik dan digunakan oleh petani). Untuk pene-rapan di Indonesia, composting skala besar dapat dilakukan tanpa harus menerapkan prinsip benefit systemdari segi ekonomi
Pembuangan akhir yang dilakukan de-ngan sistem sanitary landfill sangat memadai ditinjau dari ketersediaan fasilitas dan kehandalan operasional. Untuk penerapan di Indonesia perlu kemauan dan kerja keras dalam me-ningkatkan kualitas landfill
Penerapan standar kualitas effluentyang lebih ketat di Beijing telah memacu pe-ngembangan teknologi pengolahan lea-chate seperti RO (reverse osmosis) se-mata-mata demi pengamanan kualitas lingkungan terutama sumber-sumber air
Pembakaran sampah dengan insinerator tidak dilakukan di Beijing, karena selain karakter-istik sampah yang tidak layak bakar juga masih menunggu ka-jian kelayakan. Di Indonesia, banyak ditawarkan insinerator kecil yang tidak ramah ling-kungan dan pada umumnya ha-nya menyelesaikan “masalah” dengan “masalah”
Aspek Manajemen
Pemerintah kota Beijing memi-liki komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kualitas landfill (saat ini dalam kondisi sangat baik, ke-cuali masalah effluent)
Adanya kesungguhan dan sikap profesio-nal dari petugas di lapangan merupakan modal yang menentukan keberhasilan program kebersihan di Beijing. Di Indo-nesia, SDM yang ditempatkan sebagai “orang kebersihan” pada umumnya mera-sa sebagai “terpinggirkan”
Retribusi pengelolaan sampah dengan sis-tem insentif bagi keluarga kecil, di Indone-sia sistem insentif dapat dikembangkan berdasarkan pengurangan volume sampah Penerapan peraturan sudah cukup me-madai, sementara di Indonesia buang sampah sembarangan sah-sah saja, le-bih takut kena tilang lampu merah atau Three In Oneatau sabuk pengaman Tingkat kesadaran masyarakat sudah sangat tinggi dalam bidang kebersihan. Di Indonesia perlu kesungguhan untuk membangun kesadaran masyarakat, bahkan mungkin perlu dikenalkan me-lalui pendidikan formal sejak dini
Pelajaran-pelajaran di atas bisa diambil oleh para pengambil kebijakan di Indonesia. Apa salahnya kita belajar persampahan ke Cina, negara tirai bambu yang kualitas kebersihan kotanya tidak kalah dengan negara Eropa maupun Jepang?
Endang Setyaningrum, Staf Direktorat Perkotaan, Ditjen TPTP, Depkimpraswil dan anggota Pokja AMPL
A P O R A N U T A M A
Salah satu TPA di Beijing.
T
ak ada Adipura, kebersihan pun diabaikan. Kepedulian pemerin-tah daerah yang dulu begitu ber-semangat berlomba menjaga kebersihan dan keindahan kota tak begitu tampak lagi utamanya setelah tahun 1998.Kota-kota yang dulunya memiliki nilai kebersihan cukup tinggi, mendadak menurun drastis pada evaluasi tahun 2003. Ini terjadi di hampir semua kota di Indonesia baik kota metropolitan, besar, sedang, dan kecil, seperti tergambar dalam tabel 1.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah lingkungan hidup cenderung meningkat di berbagai daerah di tanah air. Ada yang terjadi secara alami, tapi tak sedikit yang disebabkan oleh ulah manusia, seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan me-ningkatnya permintaan ruang dan sum-ber daya alam. Kerusakan lingkungan makin diperparah oleh rendahnya ke-kuatan politik yang memiliki sense of environment.
Oleh karena itu, perlu ada peningkat-an kapasitas pengelolapeningkat-an lingkungpeningkat-an hi-dup. Modelnya tentu tak lagi sentralistik,
tapi desentralisasi. Setiap daerah bisa mendayagunakan seluruh kemampuan-nya dan memobilisasi dukungan dari se-genap segmen masyarakat untuk bersa-ma-sama menyadari urgensi dari penye-lamatan kerusakan lingkungan hidup di da-erah masing-masing, dan menyusun ren-cana yang konkrit untuk pelestarian lingkungan. Hanya saja, untuk bisa mewu-judkan pengelolaan dan pelestarian hidup yang efektif perlu kepemerintahan yang baik (good governance).Dari sinilah kemu-dian muncul paradigma baru yaitu good en-vironmental governance yang diterje-mahkan sebagai Tata Praja Lingkungan.
Inilah yang mendasari lahirnya Pro-gram Bangun Praja, sebuah proPro-gram dari Kementerian Lingkungan Hidup yang bertujuan mendorong kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan kepemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup sekaligus untuk me-ningkatkan kinerja pemerintah. Program ini juga didukung oleh Program Warga Madani yang bertujuan memberdayakan masyarakat.
Program Bangun Praja dimulai pada tahun 2002. Pencanangannya
dilaksana-kan bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup pada 5 Juni 2002 di Denpasar, Bali.
Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelola-an LingkungPengelola-an Hidup KewilayahPengelola-an, M Gempur Adnan menjelaskan inti Tata Praja Lingkungan adalah penguatan sis-tem koordinasi sehingga pemerintah bisa mendapatkan respon yang tepat untuk penyelesaian masalah-masalah lingkung-an ylingkung-ang mendesak. Penguatlingkung-an sistem ini meliputi mekanisme yang dapat menja-min semua pihak yang berkepentingan menyampaikan suaranya secara demo-kratis, menjamin adanya prosedur yang transparan dan adil dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana, serta adanya standar dan kriteria untuk menilai pelak-sanaan yang adil dan transparan.
Beberapa unsur penentu dalam Program Bangun Praja agar Tata Praja Lingkungan tercapai yaitu:
1. Motivasi kepala daerah
2. Kompetensi dan komitmen pimpinan efektivitas institusi (kelembagaan) 3. Kapasitas dan kemampuan sumber
daya manusia
A P O R A N U T A M A
P r o g r a m B a n g u n P r a j a
Memacu Daerah
Peduli Lingkungan
L
4. Adanya kebijakan yang mendukung 5. Adanya sistem pertanggungjawaban
yang jelas
7. Ketersediaan dana
Kegiatan program ini tahun 2002-2003 difokuskan pada monitoring dan evaluasi isu-isu lingkungan perkotaan atau daerah urban meliputi: pengelolaan sampah, pengelolaan ruang terbuka hijau, pengelolaan fasilitas publik, dan pengendalian pencemaran air. Pada tahun ini, jumlah yang ikut 59 kota. Setiap daerah didata melalui kuisioner dan pengamatan langsung di lapangan.
Komponen yang dievaluasi yaitu manaje-men, daya tangkap, institusi, hasil (fisik), dan inovasi. Data itu kemudian disimpan pada data base dan diperbaharui setiap ada evaluasi setiap tahun. Kebijakan dan program peningkatan kapasitas daerah disusun berdasarkan data yang ada.
Pada tahun kedua (Juni 2003-Mei 2004) jumlah peserta Program Bangun Praja bertambah menjadi 133 kota. Dari jumlah tersebut, 31 kota masuk nominasi sebagai kota terbersih yang akan mem-peroleh penghargaan Adipura. Penghar-gaan ini terdiri atas Anugerah Adipura bagi kota-kota yang nilai kinerjanya
melewati batas yang ditentukan, dan Piagam Adipura bagi kota-kota yang ki-nerjanya mendekati nilai batas yang ditentukan. Pada 7 Juni lalu, 15 kota menerima Anugerah Adipura, dan 10 ko-ta meraih Penghargaan Adipura. Pe-nyerahan penghargaan itu dilakukan oleh presiden di Istana Negara.
Program ini tak berhenti sampai di sini. Program ini akan terus berlanjut, tentu dengan berbagai penyesuaian baik dalam pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaannya. Tujuannya, terwujud-nya tata praja lingkungan. (MJ)
A P O R A N U T A M A
L
S
emua orang sebenarnya tahu ba-gaimana mengatasi masalah sam-pah. Orang juga tahu hambatan-hambat-annya, seperti kendala teknis, dana, per-alatan, dan SDM. Tetapi mengapa ma-salah ini tak pernah terselesaikan? Bebe-rapa daerah yang dibantu juga tetap tak bisa menyelesaikan masalah ini.Lalu apa sebenarnya kata kunci dari permsalahan sampah itu? Kita sampai pada kesimpulan bahwa itu semua ter-gantung komitmen pemerintah daerah. Punya nggak pemerintah daerah dan masyarakat komitmen untuk mengatasi sampah? Kalau mereka punya komitmen, sebenarnya uang itu tak jadi masalah. Sampah bisa bersih kalau pemerintah dae-rah punya komitmen. Kalau tidak ada komitmen, diberikan apapun maka tak akan bisa berbuat banyak.
Masalah uang itu sebenarnya ada. Hanya masalahnya dialokasikan ke arah yang betul.
Melalui program ini, kita ingin me-naikkan komitmen pemerintah daerah.
Biar kalau daerah itu kotor, pemerintah-nya malu. Kita mendorong agar masalah sampah dan kota bersih menjadi isu. Kalau isu ini tidak diangkat maka peme-rintah daerah akan tenang-tenang saja. Saat ini kita terus berupaya mengangkat isu sampah ke level pengambil keputus-an di daerah sampai ke pusat. Kita ber-harap muncul komitmen daerah dan na-sional. Coba kalau presiden teriak, gu-bernur teriak, kita bisa mengatasi hal itu. Program ini bersifat sukarela. Ada dua hal dalam program ini yakni perta-ma mendorong daerah membuat kota-nya bersih dan teduh (clean and green city). Kedua adalah capacity building. Kita mendorong daerah meningkatkan kapasitasnya dalam bidang lingkungan khususnya perkotaan. Kita memberikan workshop, pelatihan, studi banding dan sebagainya yang berkaitan dengan cara mengelola kota.
Visinya untuk sementara sampah dulu, perbaikan fasilitas publik, dan ru-ang terbuka hijau. Kita batasi tiga dulu,
karena masalah di daerah sudah kacau. Kalau semuanya, mereka tidak akan bi-sa-bisa.
Sebenarnya program ini hampir sama dengan program Adipura dulu. Hanya saja berbeda, mekanismenya. Pa-da bangun praja aPa-da peningkatan kapa-sitas, tapi tidak pada Adipura. Sistem evaluasinya juga berbeda. Kalau Adipura sekali setahun, Bangun Praja tiga kali setahun. Semuanya transparan. Jadi se-tiap kota mengetahui perkembangan ko-tanya setiap ada pemantauan dan evalu-asi. Kota lain pun bisa tahu. Masyarakat pun juga tahu melalui media massa kare-na kita berusaha mengeksposnya.
Memang kita belum bisa berharap kota-kota yang memperoleh pengharga-an itu benar-benar bersih. Semupengharga-anya masih kotor. Tapi kalau kita menunggu, sampai kapan mereka sampai pada nilai tertentu bersih? Ini kan butuh waktu.
Kita berharap, dalam 5 tahun ke depan lahir 50 kota yang bersih di Indonesia. (MJ)
M. Gempur Adnan,
Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan
Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kewilayahan
M
engatasi persoalan sampah bukan hal mudah. Terbukti, hingga kini masalah persam-pahan di Indonesia tidak kunjung usai. Banyak faktor yang mempengaruhi dan faktor-faktor itu saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, pengelolaan sam-pah merupakan sebuah sistem sehingga penanganannya memerlukan sinergi semua pemangku kepentingan.Begitu intisari perbincangan PERCIK dengan Sekjen Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Budiman Arief, di kantornya beberapa waktu lalu. Berikut petikannya:
Bagaimana kondisi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini?
Secara umum, pengelolaan sampah, terutama sampah kota, masih kurang. Walaupun dulu pernah cukup baik pada waktu ada program Adipura pada tahun 1986-1996, karena waktu itu dibantu dengan reward(penghargaan) bagi kota-kota yang bisa menjaga kebersihan. Setelah itu kondisinya menurun. Dan baru saja ada lagi program Bangun Praja sejak 2002. Tapi gaungnya belum seperti Adipura karena pesertanya terbatas.
Mengapa kondisinya menurun? Apakah karena tidak ada reward
atau ada faktor lain?
Memang reward tidak ada. Yang kedua karena ada krisis. Penanganan sampah tak lagi menjadi prioritas. Pemerintah lebih banyak memperhatikan soal kemiskinan dan segala macamnya. Akhirnya penanganan sampah agak ter-tinggal. Perhatian pemerintah kota/ka-bupaten pun menurun. Saya kira ada
fak-tor saling mempengaruhi. Tidak ada reward maka perhatian berkurang. Padahal pengelolaan sampah itu meru-pakan layanan masyarakat yang sangat mendasar. Sampah terkait dengan kese-hatan. Kota yang tidak menangani sam-pah dengan baik, bisa dipastikan tingkat kesehatannya pun tidak baik sebab sam-pah merupakan salah satu vektor penya-kit.
Bagaimana dengan faktor dana? Kalau kita lihat pengelolaan sampah secara umum, dan ini sudah kita sam-paikan ke seluruh pemerintah kota/kabu-paten, bahwa ada lima aspek dominan dalam pengelolaan sampah. Antara aspek satu dan yang lain saling terkait. Kalau mau berhasil, maka kelima aspek itu harus diwujudkan. Pertama, aspek insti-tusi. Kedua, aspek pembiayaan. Ketiga,
aspek teknis. Keempat, aspek hukum. Dan kelima, aspek peran serta masyara-kat.
Mungkin banyak yang menganggap bahwa sampah ini hanya soal teknis, padahal tidak. Semua harus saling men-dukung. Sebagai contoh aspek kelemba-gaan. Kalau di kota bentuk/derajat insti-tusi itu kelewat rendah maka ini kan su-sah. Seorang kepala seksi/sub seksi akan sulit bertemu walikota karena tingkatnya terlalu jauh. Makanya dulu ada kesepa-katan, kalau kota besar/metropolitan maka pengelola sampah harus dinas. Ka-lau kota sedang bisa subdinas. Jadi ja-ngan kelewat rendah.
Pembiayaan juga jangan terlalu ren-dah. APBD untuk sampah jangan terlalu kecil. Susah. Walaupun sebetulnya, kalau nanti dikelola dengan bagus, sampah bisa menghasilkan retribusi meskipun tidak
A W A N C A R A
Budiman Arief, Sekjen Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
‘’Penanganan Sampah Jelek,
Tingkat Kesehatan Rendah’’
W
100 persen. Paling tidak 70 persen bisa didapatkan dari retribusi. Jadi subsidi hanya 30 persen saja. Tapi kalau aspek pembiayaan tidak dibenahi dan retribusi tidak ditarik dengan baik, maka akan membuang uang saja.
Dari aspek hukum, peraturan harus dibenahi. Perdanya bagaimana, supaya jelas. Kalau orang membuang sampah sembarangan didiamkan, wah susah. Sampah itu kan berasal dari manusia, maka hukumnya harus ditegakkan.
Dari aspek teknis juga jangan seenaknya. Ada hitungan-hitungannya. Sistemnya bagaimana, waktu meng-angkutnya bagaimana, waktu di TPA-nya bagaimana. Terus dari aspek peran serta masyarakat, itu satu hal yang sangat pen-ting. Kalau masyarakat tidak mendukung maka biaya menjadi mahal. Oleh karena itu peran masyarakat harus selalu di-tingkatkan. Kelima itu saling terkait.
Jadi tidak ada yang dominan? Ya. Tapi sebetulnya ada dananya dulu. Kalau tidak ada ya gimana? Tapi duit saja bukan jaminan.
Apa yang telah dilakukan peme-rintah selama ini dalam menangani sampah ini?
Tugas Depkimpraswil adalah membu-at pedoman-pedoman. Kita sudah banyak menghasilkan pedoman mengenai pe-ngelolaan sampah yang betul. Tapi tidak hanya itu. Kita juga memberikan stimu-lan. Kita berikan kepada pemerintah daerah yang memang ingin mengatasi masalah ini. Kalau tidak ingin, kita tidak memberikannya karena itu buang-buang uang saja. Jadi kita akan berikan kepada yang benar-benar ada upaya. Kekurangan mereka kita bantu. Ini juga sebagai reward.
Berapa banyak pemda yang mendapatkan stimulan ini?
Sejak 2001, sudah cukup banyak pem-da yang menpem-dapatkannya. Kita juga
membantu kota-kota yang baru terben-tuk, misalnya untuk modal awal kita berikan mobil pengangkut sampah. Kalau selanjutnya bagus, kita tambah lagi.
Apa rencana pemerintah ke de-pan?
Saya rasa kita akan tetap meneruskan apa yang sudah dilaksanakan. Pengelola-an TPA akPengelola-an kita perbaiki lagi. Maunya pemda, mereka ingin menerapkan sani-tary landfill, tapi faktanya hanya open dumping saja. Ini yang menyebabkan banyak protes. Mestinya open dumping ini sudah ditinggalkan. Meskipun kita belum bisa menuju sanitary landfill pe-nuh. Kita akan memberikan bantuan ke-pada pemda yang kesulitan dalam pena-nganan TPA.
Bagaimana penanganan terha-dap masyarakat?
Semua pemda harus memberikan pe-ngertian kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Sebagai contoh, ada warga yang merasa sudah membayar kepada tukang sampah tapi ada tagihan lagi dari dinas kebersihan. Kalau seperti ini masyarakat bisa bingung. Mestinya diberikan pengertian bahwa pengelolaan sampah dari sisi teknis itu ada yang mengumpulkan, ada yang mengangkut, dan ada yang mengolah di akhir. Kalau membayar ke RT/RW itu hanya me-ngumpulkan saja. Itupun sebenarnya hanya 30 persen dari seluruh proses tek-nis. Kadang-kadang yang diambil RT/RW itu terlalu besar sehingga dinas tidak kebagian. Makanya masyarakat harus diberi pengertian sejelas-jelasnya sehing-ga mereka terbuka dan mengetahui de-ngan jelas bagaimana mengelola sampah dengan betul.
Pandangan Anda terhadap kesa-daran masyarakat dalam hal sam-pah?
Saya kira masyarakat belum mema-hami secara utuh betapa pentingnya
pe-ngelolaan sampah itu. Bagi masyarakat desa mungkin sampah tak jadi masalah karena tanahnya luas, tapi tidak dengan masyarakat kota. Mereka tak bisa lagi mengelola sampah secara individual, tapi harus kolektif. Hanya saja persoalannya, kebanyakan masyarakat kota kan berasal dari desa. Jadi kelakuannya masih kela-kuan desa. Ini kan susah. Dan kalau sudah masuk kota tidak ada sistem pelayanan yang tidak bayar.
Bagaimana keterkaitan langkah pemerintah dalam penanganan sampah dengan MDGs?
Saya kira salah satu tujuan dari MDGs adalah perbaikan pelayanan sanitasi. Sekarang kita sedang menyusun National Action Plan. Kita harus menerjemahkan MDGs itu untuk Indonesia. Tujuan MDGs itu bisa dianggap cukup kuanti-tatif, tapi juga kualitatif. Bisa saja sampah itu habis, tapi kalau diangkutnya seming-gu sekali atau dua mingseming-gu sekali, secara kualitatif itu jelek. Karena sampah harus diangkut paling lambat tiga hari sekali supaya tidak busuk. Jadi tingkat pe-layanan bisa kita anggap kuantitatif dan kualitatif.
Bisakah target MDGs dalam masalah sanitasi khususnya sam-pah tercapai pada 2015?
Kalau kita seperti negara maju dengan sanitary landfill, saya kira kita belum bisa. Hanya saja kita bisa menerjemahkan bagaimana penanganan secara kualitatif. Yang penting ada peningkatan lebih baik dari sebelumnya. Makanya National Action Plan perlu ada kesepakatan de-ngan departemen-departemen terkait dan daerah, bagaimana mencapai target MDGs.
Bagaimana Anda melihat keter-kaitan otonomi daerah dan pena-nganan sampah?
Sebenarnya dari dulu pengelolaan sampah ini menjadi tugas dari
pemerin-A W pemerin-A N C pemerin-A R pemerin-A
tah kota/kabupaten karena ada UU 22, PP 25, tapi dulu ada PP 18 tahun 1953 yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah itu menjadi tugas pemerintah kota/kabupaten. Itu mestinya tugas yang melekat di pemerintah daerah.
Jadi adanya perubahan ke arah otonomi daerah beberapa tahun la-lu tak berpengaruh terhadap tugas pengelolaan sampah?
Sebetulnya tidak. Hanya saja kita ber-harap daerah menjadi lebih baik dalam menangani sampah ini. Yang dulu belum begitu tegas, sekarang sudah lebih tegas lagi.
Bagaimana dengan penanganan sampah lintas daerah yang banyak menimbulkan pergesekan seperti kasus Bantar Gebang dan Bojong?
Memang masalah muncul di kota met-ropolitan. Kalau kota kecil dan sedang, mereka bisa menyelesaikan karena masih cukup lahan yang tersedia. Di kota besar seperti Jakarta, penanganan menjadi su-lit. Makanya sebaiknya sanitary landfill itu dibangun secara bersama-sama de-ngan daerah lainnya. Insinerator saya ki-ra terlalu mahal baik dari sisi investasi maupun operasional. Makanya kita harus hati-hati dalam menilai aspek teknis. Ka-lauincomeper kapita kita 5.000 dolar AS, bisa kita memikirkan insinerator.
Bagaimana pandangan Anda ter-hadap perhatian pemerintah da-erah terhadap sampah?
Saya kira masih kurang. Mengapa Adipura itu diadakan? Karena dulu diang-gap pengelolaan sampah akan baik jika ada perhatian yang cukup baik. Saya kira investasi sampah tak cukup besar diban-dingkan dengan membuat jalan dan air minum. Kalau pemda ada perhatian seha-rusnya pengelolaan sampah itu bisa ber-langsung dengan baik.
Bagaimana alokasi anggaran pe-merintah pusat dalam menangani
sampah ini?
Seperti saya jelaskan, pemerintah hanya memberikan stimulan saja. Depar-temen ini hanya membina infrastruktur dasar yakni air minum, limbah, sampah, drainase, dan jalan. Kita tak hanya me-ngeluarkan pedoman saja tapi juga stimu-lan. Ini juga supaya ada perhatian daerah.
Maksudnya apakah anggaran yang ada sudah cukup?
Kurang. Masih terlalu kecil. Dan me-mang infrastruktur itu masih dianggap kurang.
Adakah negara yang mendekati Indonesia yang bisa dijadikan con-toh dalam penanganan sampah?
Saya kira perlu studi banding dengan negara lain yang kondisinya mirip dengan Indonesia. Tidak ke negara-negara maju seperti Jepang, Australia. Itu terlalu jauh. Yang dekat-dekat kita. Misalnya kita bisa studi banding ke Kuching (Malaysia). Kita sudah lakukan.
Dari apa yang Anda uraikan, pe-nanganan sampah ini sepertinya harus menggunakan pendekatan institusi?
Menurut saya begini, institusi itu kan
jelas penanggungjawabnya. Memang ha-rus ada institusinya, tapi masyarakat te-tap ikut dalam sistem yang jelas. Bisa saja RT/RW atau kelompok masyarakat bisa saja ditugaskan dalam pengumpulan. Institusi yang bertanggung jawab secara keseluruhan bisa bertugas mengambil dari TPS ke TPA. Jadi institusi yang me-nangani harus jelas dan tingkatnya cukup memadai.
Harapan Anda ke depan terha-dap kota-kota kita?
Kebersihan dan kerapian harus kita
wujudkan. Kalau keindahan barangkali itu suatu yang lux. Kebersihan adalah pangkal. Kalau mau membenahi yang lain, kebersihan harus didahulukan. Bu-pati dan Walikota perlu memberikan per-hatian yang lebih soal ini. Kalau perlu ada reward, saya kira juga tak masalah.
Bagaimana bentuk kerja samanya? Sampah itu kan dibilang nimby (not in my back yard), pokoknya jangan di tempat saya dech. Yang kena dampak harus memperoleh kompensasi yang memadai sehingga merasa ada manfaat-nya. Dan teknik penanganan masyarakat pun harus betul. (mujiyanto)
A W A N C A R A
W
B
eberapa teknologi pemusnahan sampah telah dicoba untuk dite-rapkan di Indonesia. Teknologi yang paling umum diterapkan adalah lahan urug saniter, yang dikembangkan di beberapa kota besar di Indonesia. Sesungguhnya lahan urug saniter terse-but merupakan suatu reaktor biologis untuk mendegradasi sampah secara an-aerobik. Salah satu produk yang diharap-kan dari degradasi anaerobik tersebut adalah gas metana (CH4) yang memiliki nilai kalor cukup tinggi. Ini bisa menjadi sumber energi yang signifikan.Kompos Belum Dimanfaatkan Kompos dari sampah kota di Indo-nesia tidak berhasil dipasarkan dengan baik kepada masyarakat. Para petani, pengelola perkebunan dan pertamanan belum tertarik menggunakannya. Ini bisa jadi karena kompos relatif tidak membe-rikan nutrisi tambahan bagi tanah dan ta-naman, serta tidak memberikan dampak yang langsung bagi peningkatan produksi tanaman. Selain itu, kompos tidak dituju-kan untuk berperan seperti layaknya pu-puk kimia. Kompos lebih berperan untuk memperbaiki tekstur tanah dan mening-katkan cadangan air pada tanah, sehing-ga penyerapan air oleh tanaman akan le-bih baik. Di sisi lain, pemerintah kurang menggalakkan gerakan pemanfaatan kompos. Produksi kompos dari beberapa instalasi pengomposan sampah tidak op-timum, dan akhirnya berhenti beroperasi akibat ketiadaan pelanggan tetap dan berkesinambungan.
Sumber Energi
Perlu konsep baru untuk menangani sampah perkotaan. Sebagai alternatif, sampah bisa diubah menjadi suatu ma-teri baru yang memiliki nilai jual lebih dan dibutuhkan oleh masyarakat. Ini adalah energi. Mengapa? Karena Indo-nesia mulai mengalami krisis energi. BBM mulai langka, sumber minyak bumi yang terbatas, harga minyak mentah du-nia semakin mahal. Perlu dicari sumber energi baru yang terbarukan dan membe-rikan dampak negatif yang lebih kecil ter-hadap lingkungan. Di sinilah sumber energi dari sampah bisa menjadi alterna-tif sumber energi baru, sekaligus menjadi sarana pemusnahan sampah secara
si-multan. Dengan demikian diharapkan pemanfaatan bahan bakar fosil dapat di-tekan, serta mereduksi tingkat eksploitasi bahan bakar fosil dari perut bumi.
Teknologi Yang Tersedia
Kompos pada dasarnya melakukan konversi energi. Namun energi yang ada terlepas dalam bentuk materi yang me-miliki nilai kalor yang lebih rendah. Hal ini disebabkan proses pengomposan se-cara aerobik akan melepas materi organik padatan lain yang lebih sederhana, serta gas CO2 yang tidak siap untuk dimanfaat-kan energinya secara langsung. Tersedia beberapa proses lain yang dapat meng-konversi energi yang tersimpan di dalam sampah menjadi suatu materi baru. Pro-ses itu antara lain yaitu:
A W A S A N
Sampah Sebagai Sumber Energi :
Tantangan Bagi Dunia
Persampahan Indonesia
Masa Depan
W
Sandhi Eko Bramono *)
Proses Anaerobik
Proses ini akan melepas energi yang tersimpan dalam gas CH4 ( metana ) yang memiliki nilai kalor tinggi yang akan ter-bentuk. Lahan urug saniter, sesungguh-nya merupakan reaktor anaerobik dalam kapasitas yang besar. Beberapa teknik telah dilakukan untuk meningkatkan pro-duksi gas metana yang terbentuk. Resirkulasi air lindi merupakan salah sa-tu teknik yang diterapkan unsa-tuk me-ningkatkan produksi gas metana, selain untuk mempercepat degradasi sampah itu sendiri. Akan tetapi, reaktor anaerobik yang direncanakan secara khusus dengan kapasitas yang lebih kecil, dapat lebih mudah untuk dimonitor dan dikontrol dalam kinetika pembentukan gas metana dengan lebih baik ketimbang pada lahan urug saniter. Residu yang terbentuk dapat dimanfaatkan untuk kompos, yang se-belumnya telah diambil sebagian ener-ginya menjadi gas metana, ketimbang proses aerobik pada pengomposan yang hanya akan menghasilkan kompos saja. Jika tahapan proses anaerobik ini dihen-tikan hanya pada tahapan fermentasi saja, yaitu tahapan sebelum
pemben-tukan gas metana, maka dapat dihasilkan alkohol yang memiliki nilai kalor tinggi. Penggunaan alkohol ataupun derivatnya sebagai sumber bahan bakar alternatif dari sampah dapat dipertimbangkan juga.
Proses Gasifikasi dan Pirolisis Kedua proses ini membutuhkan ener-gi tambahan untuk menaikkan tempe-ratur hingga 600 oC yang dilakukan de-ngan oksigen substoikiometrik atau tanpa kehadiran oksigen sama sekali. Proses pirolisis akan menghasilkan padatan (char) dan cairan (tar) yang memiliki nilai kalor tinggi. Produk ini dapat diman-faatkan sebagai biodiesel (salah satu bahan bakar pengganti atau aditif solar) yang sedang marak digunakan dewasa ini. Sedangkan gasifikasi, akan mengha-silkan gas yang memiliki nilai kalor tinggi. Pemanfaatannya sebagai sumber energi alternatif dapat dipertimbangkan pula.
Proses Insinerasi
Proses ini lebih mahal ketimbang dua proses di atas. Sampah dengan kadar air terendah sekalipun hanya dapat mengha-silkan temperatur alami sekitar 200 oC.
Sementara temperatur kerja pada proses ini adalah pada rentang 600 - 800 oC, yang bertujuan untuk mereduksi pem-bentukan senyawa karsinogenik dioksin dan furan. Riset pada beberapa buah insinerator di Amerika Serikat masih belum menunjukkan hasil yang memu-askan dalam mereduksi pembentukan ke-dua senyawa ini, meskipun proses dija-lankan pada temperatur jauh di atas 600 - 800 oC. Proses ini akan menghasilkan panas yang cukup tinggi sehingga bisa di-gunakan sebagai sumber energi pem-bangkit tenaga uap. Tenaga uap itu dapat dikonversi menjadi energi listrik.
Rentang Energi Yang Dihasilkan Sebagai suatu proses yang meng-hasilkan energi, jumlah input energi dan output energi harus dihitung dalam suatu neraca massa dan energi. Energi yang di-masukkan ke dalam suatu proses diha-rapkan seminimum mungkin, mengingat output dari proses yang diharapkan ada-lah energi pula, sehingga total energi yang dihasilkan dari proses dapat dihitung. Ji-ka terlalu banyak energi yang harus di-tambahkan ke dalam proses, maka proses tidak efisien.
Selain itu, masih perlu dikaji rentang energi yang dapat dimanfaatkan, karena setiap output dari suatu proses memiliki rentang pemakaian. Dalam hal ini, efi-siensi pemanfaatan energi dengan jumlah energi tertentu yang dihasilkan dari suatu volume sampah harus dipertimbangkan. Harus disadari bahwa setiap proses me-miliki jangkauan pemanfaatan dalam se-tiap produk yang dihasilkan. Dengan de-mikian pemanfaatannya bisa dilakukan secara tepat dan efisien.
*) Penulis adalah mahasiswa pascasarjana pada UNSW, Australia.
A W A S A N
W
P
erkembangan penduduk selain membutuhkan ruang/lahan, pe-nyediaan prasarana dan sarana kota yang memadai, juga menghasilkan sampah (Tchobanoglous, 1977: 4). Sesuai aturannya, sampah harus ditangani de-ngan cara ditampung pada tempat pem-buangan sementara (TPS), kemudian di-angkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan disortir antara sampah kering dan sampah basah. Barulah sampah dio-lah dengan berbagai macam teknologi, antara lain sanitary landfill, composting, pembakaran dengan incenerator, tekno-logi ATAD (autogenous Thermophilic Aerobic Digestion) dan sebagainya.Namun di lapangan proses tersebut tidak berjalan sesuai dengan perenca-naan fasilitas kesehatan lingkungan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota (Chiara, 1982: 6). Akibatnya, sampah me-nimbulkan persoalan yang sangat kom-pleks, tidak hanya di daerah tapi di tingkat nasional.
Sampah dan Kota Surabaya
Pengumpulan, pembuangan dan pengolahan sampah dalam wilayah perkotaan menjadi tanggung jawab pe-merintah kota (UU No. 22 Pasal 11, ayat 2; Cointreau, 1982: 4), khususnya dinas kebersihan. Tapi Pemerintah Kota Su-rabaya tak lagi mampu menangani sam-pah. Banyak kendala yang dihadapi se-perti pengadaan lahan untuk TPA, pem-biayaan pengelolaan sampah yang sangat besar dan kegiatan rutin pembangunan yang sudah cukup banyak. Untuk me-mecahkan persoalan tersebut pemkot Surabaya menggandeng pihak swasta. Hanya saja kerja sama ini terbatas pada jual beli, sahingga pemkot sebenarnya belum memiliki pengalaman kerja sama dalam pengelolaan sampah secara me-nyeluruh.
Komposisi dan Teknologi Peng-olahan Sampah
Pada dasarnya, suatu teknologi peng-olahan sampah yang akan diterapkan ha-rus dapat mengatasi masalah yang timbul atau minimal dapat mengurangi bobot dari masalah yang telah timbul (Ryding, 1994: 71). Dalam menentukan teknologi pengolahan sampah yang akan diterap-kan, maka hal tersebut sangat bergan-tung kepada jenis sampah yang di-hasilkan (Cointreau, 1982: iv).
Keterkaitan antara jenis sampah yang dihasilkan dan teknologi yang diterap-kan, menyebabkan perbedaan penerapan teknologi pengolahan sampah di negara industri dan negara berkembang. Di negara berkembang kepadatan sampah diperkirakan 2-3 kali lebih tinggi diban-dingkan kepadatan sampah di negara in-dustri. Komposisi sampah juga sebagian besar organik dengan porsi terbesar berasal dari tanaman, dan diperkirakan tiga kali lebih tinggi. Oleh karena jenis sampah seperti yang disebutkan di atas, maka di negara berkembang salah satu sistem pengolahan yang umum adalah
open dumping dan sanitary landfill. Ada beberapa macam teknologi peng-olahan akhir sampah (Moenir, 1983: 33) yaitu:
Masing-masing teknologi di atas mempunyai kelebihan dan kelemahan. Oleh karena itu perlu pengkajian menge-nai tiap-tiap teknologi tersebut agar tidak terjadi kesalahan yang dapat mengaki-batkan kegagalan penanganan sampah.
Pemindahan dan pengangkutan sam-pah juga berperan dalam menentukan keberhasilan teknologi pengolahan sam-pah yang dipilih. Jadwal pengangkutan sangat bergantung pada kapasitas pengo-lahan sampah di TPA, karena jika over-loadmaka akan menyebabkan pengolah-an tergpengolah-anggu.
Simpul Persoalan
Berdasarkan uraian mengenai ling-kup makro masalah sampah Kota Sura-baya, maka rumusan persoalan sampah Kota Surabaya adalah sebagai berikut:
1. Keterbatasan Pemerintah Kota Su-rabaya dalam penanganan sampah, baik dalam hal teknis, biaya, sumber daya ma-nusia, pengetahuan dan yang paling uta-ma, yaitu perencanaan penanganan sam-pah yang komprehensif dan terpadu;
2. Sistem pengelolaan sampah yang ti-dak berjalan dengan baik, mulai dari sistem pengangkutan, penyebaran dan penggu-naan TPS, fasilitas TPA, Fasilitas penunjang TPA, sistem pengolahan sampah dan sistem treatmentlimbah cair sampah;
A W A S A N
Pre-Studi Masalah Sampah
Kasus Studi: Kota Surabaya
W
Klasifikasi Musim Hujan Musim Kemarau
• Paper
• Textil • Organic • Wood/grass
• Plastic • Leather/rubber • Metal (Ferrous)
Fany Wedahuditama *)
1.
Metode open dumping Metode sanitary landfill
Metode pengepakan sampah (baling method)
Metode pembakaran ( incineration/-thermal converter)
Metode kompos
Metode ATAD (Autogenous Thermo-philic Aerobic Digestion)