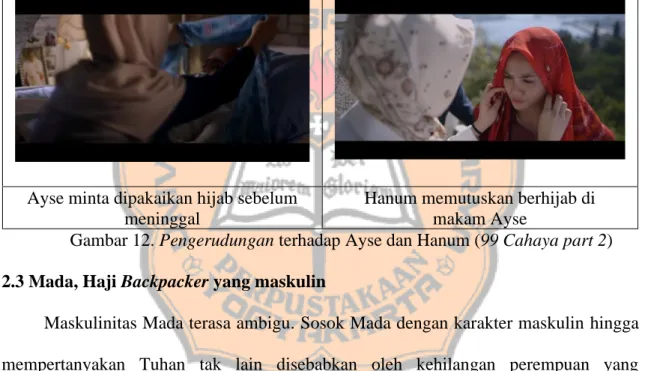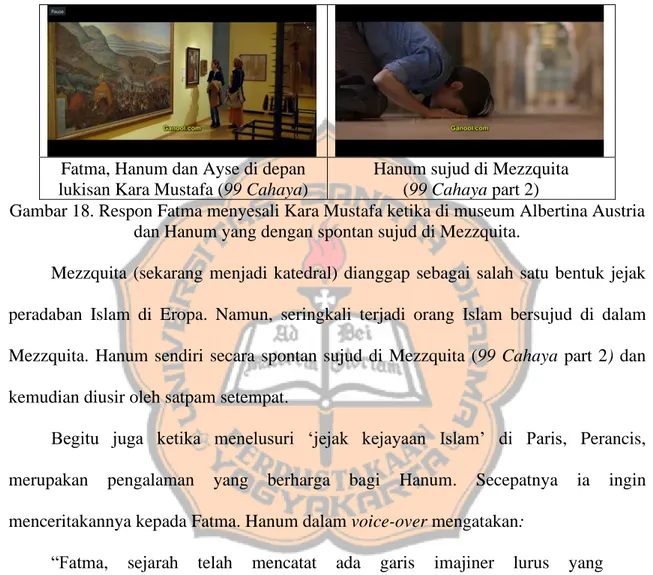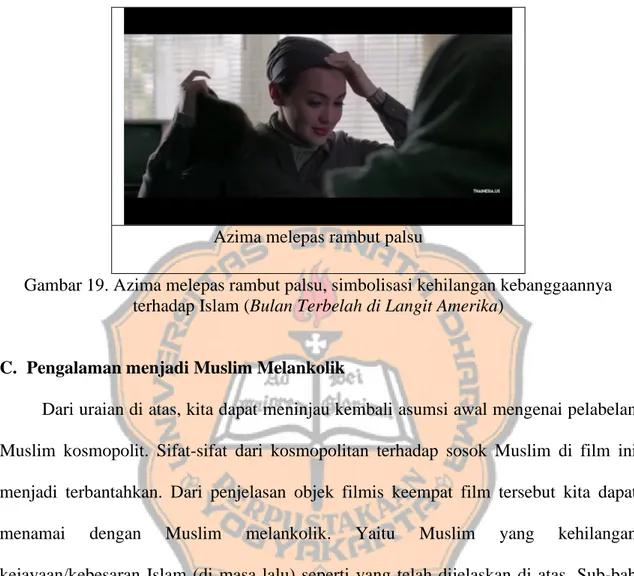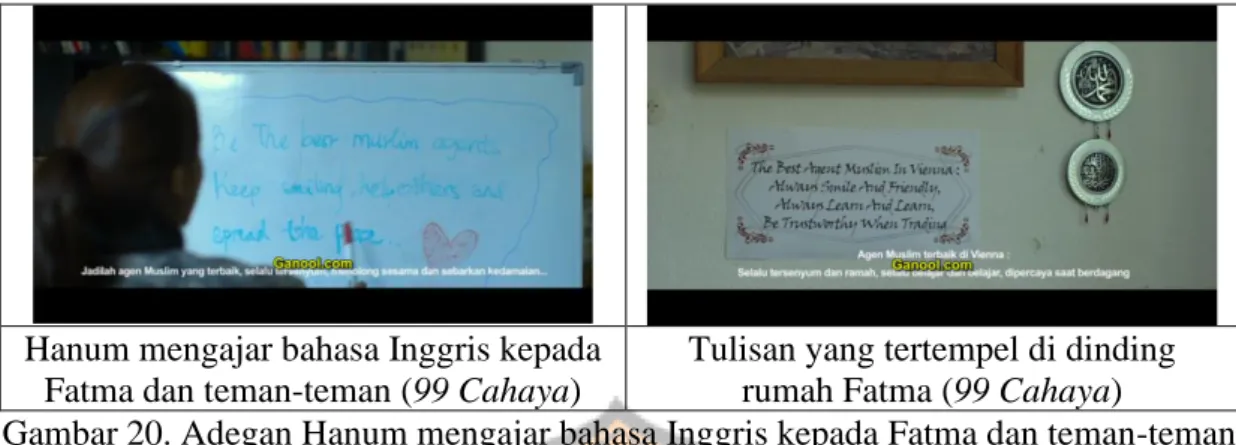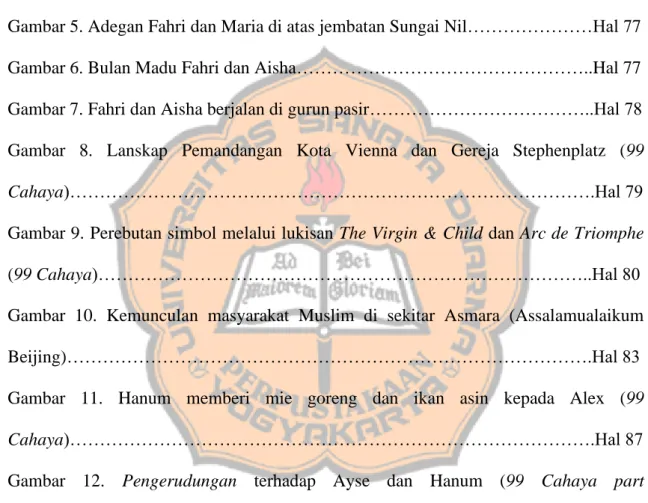1
Muslim Melankolik dalam Film Ayat-Ayat Cinta, 99 Cahaya di Langit
Eropa, Haji Backpacker, dan Assalamualaikum Beijing
Tesis
Untuk Memenuhi Persyaratan Mendapat Gelar Magister Humaniora (M.Hum) di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Oleh: Gusnita Linda
146322011
Program Magister Ilmu Religi dan Budaya
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2019
v
Abstrak
Film Islam Indonesia kembali tren semenjak Ayat-Ayat Cinta booming di tahun 2008. Pola kesuksesan Ayat-Ayat Cinta direpetisi oleh film Islam lainnya. Dengan mengambil latar luar negeri yang semakin beragam, film-film ini ingin menghadirkan sosok Muslim yang berbeda.
Penelitian ini menganalisis tren narasi dari film Ayat-Ayat Cinta, 99 Cahaya di
Langit Eropa, Haji Backpacker, dan Assalamualaikum Beijing dengan menggunakan
analisis ‘The Third Meaning’ Roland Barthes. Analisis pertama ini bertujuan untuk menemukan unsur filmis untuk menjawab pertanyaan mengenai identitas Muslim yang dihadirkan. Analisis ini menemukan sosok Muslim (kelas menengah) Indonesia yang dihadirkan empat film tersebut adalah Muslim yang melankolik. Yaitu Muslim yang gagal meratapi kehilangan kebesaran/kejayaan Islam. Temuan ini diteliti lebih jauh untuk menjawab pertanyaan Islam seperti apa yang sedang dikonstruksi oleh sosok Muslim melankolik tersebut. Dalam menjawab pertanyaan ini dibantu dengan menggunakan teori objek of desire virtual Deleuze.
Film ini ingin menulis kembali sejarah dunia (Islam), sejarah hubungan Timur-Barat. Subjek melankolik seolah ingin berdamai dengan trauma (sejarah), justru merepetisi orientalisme. Konstruk dunia yang sedang dibayangkan oleh Muslim melankolik ini; peradaban dunia berutang budi pada peradaban Islam, dengan begitu dunia akan lebih baik dengan adanya (kejayaan) Islam.
Kata kunci: film Islam, narasi, Muslim melankolik, melankolia, budaya populer, objek
vi
Abstract
Indonesian Islamic Films are back in trend since Ayat-Ayat Cinta boomed in 2008. The pattern of success of Ayat-Ayat Cinta is repeated by other Islamic films. By taking an increasingly diverse foreign background, these films want to present a different Muslim figure.
This research analyzes the narrative trends of Ayat-Ayat Cinta, 99 Cahaya di Langit Eropa, Haji Backpacker, and Assalamualaikum Beijing using the analysis of 'The Third Meaning' by Roland Barthes. This first analysis aims to find filmic elements that answer questions about the Muslim identity presented. This analysis found that an Indonesian Muslim (middle class) figure presented by the four films was a Muslim in melancholy, namely a Muslim who fails to lament the loss of the greatness/glory of Islam. This finding is further investigated to answer the question of what kind of Islam is being constructed by the Muslim melancholic figure. Deleuze's virtual object of desire theory is used to answer that question.
These films want to rewrite the (Islam) world history and the history of East-West relations. Melancholic subjects seem to want to make peace with trauma (of history), but instead repeating orientalism. The world construct that is being imagined by this melancholic Muslim is that the world civilization is indebted to Islamic civilization, so the world will be better with the existence (glory) of Islam.
Keywords: Islamic films, melancholic Muslim narrative, melancholia, popular culture,
vii
Kata Pengantar
Alih-alih menemukan subjek Muslim melankolik dalam tesis ini, saya justru menemui diri yang melankolik. Saya tak pernah menyangka pengalaman akademik menuntun perubahan yang begitu besar terhadap konsep dan tatanan diri. Pengalaman mengalami punctum, ketika saya bertemu dengan objek a rasanya gurih-gurih sepat. Pengalaman yang membuat saya gagap menentukan langkah dan memahami fase, apakah ia mourning ataukah melankolia. Mencicipi psikoanalisa mendorong orang seperti saya untuk merasai diri yang begini dan begitu. Lima tahun berdialog dengan Kajian Budaya, membuat diri tak lagi sama memandang sekitar. Semua terasa tidak sesederhana sebelumnya, tetapi lebih melegakan. Semakin merasa utuh, semakin keras juga tamparan akan lubang-lubang baru yang bermunculan. Saya bersyukur tak terhingga dipertemukan dengan Sang Ayah baru di IRB yang membangkitkan hasrat akademik saya untuk terus menikmati ilmu pengetahuan. Terima kasih atas kesabaran Pak Nardi yang tetap memercayai mahasiswa seperti saya bisa sampai pada fase ini. Fase yang saya sendiri inferior untuk melompatinya.
Saya sangat berterima kasih kepada semua pengalaman akademis yang menggiurkan selama di IRB bersama Bapak dan Ibu dosen yang saya cintai, Rama Banar, Pak Pratik, Pak Tri, Mbak Katrin, Bu Devi, Rama Bagus, Rama Baskoro, Rama Benni, dan Rama Budi. Pengalaman akademis ini tak lengkap tanpa bantuan dan fasilitas pelayanan canggih dari Mbak Desy, Mbak Dita, Pak Mul, dan Pak Sugeng yang baik hati.
viii
Orang yang terlalu traumatis seperti saya tak akan sampai pada fase ini tanpa bantuan yang begitu hebat dari teman-teman semuanya. Semua teman angkatan 2014 yang sangat saya banggakan; Heri, Abet, Ben, Riston, Kolis, Ajay, Dalijo, Pinto, Oom Keyong, Bayu, Wawan, Andreo, Si Mbah, Frans, Arman dan Malcom, kalian telah memberi iklim belajar yang memabukkan. Diskusi, curhat, dan candaan menyenangkan lintas angkatan IRB dan PUSdEP; Mbak Vini, Anne, Nita, Marino, dan lainnya tak bisa saya sebutkan satu-persatu. Semoga ke mana pun saya pergi akan bertemu lingkungan dan orang-orang seperti kalian semua. Rumah-rumah sunyi yang memberikan bantuan perenungan dan fasilitas terbaik buat saya selama lima tahun terakhir ini; Kosan Eyang dan manusianya, Ultimus Bandung, dan Trova Studio yang selalu sukarela menerima pengasingan saya. Serta teman-teman survei yang ikut menopang. Saya sangat berterima kasih atas semua bantuan teman-teman yang begitu mengharukan, Thesa (alm), hingga teman-teman di kota-kota lain yang tak bisa saya jangkau untuk berjabat tangan langsung mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya.
Bersyukur atas rahmat Semesta menempatkan saya di keluarga Apa Sariman dan Ama Nurbaiti serta anak-cucu beliau yang sampai saat ini selalu berkorban, mendoakan, dan bersabar atas perjalanan saya yang tak ‘senormal’ orang lain. Semoga tulisan yang jauh dari sempurna ini bisa mengobati semuanya. Terutama kepada Sangdenai, teman seperjalanan yang tak pernah pudar sedikitpun keyakinannya bahwa saya bisa sampai pada fase ini. Terima kasih atas penerimaan, penyertaan, dan pengorbanan selama sepuluh tahun terakhir. Semoga tulisan sederhana ini bisa menjadi kado perjalanan panjang, juga permulaan untuk menjalani keliaran hidup kita masing-masing.
ix
Daftar Isi
Lembar Persetujuan ... Lembar Pengesahan ... Pernyataan Keaslian Karya... Pernyataan Publikasi Karya Ilmiah untuk Kepentingan Akademis... Abstrak ... Abstract ... Kata Pengantar... Daftar Isi ... Bab I Pendahuluan ... A. Latar Belakang ... 1. Tema Penelitian ... 2. Rumusan Masalah ... 3. Tujuan Penelitian ... 4. Relevansi Penelitian ... 5. Tinjauan Pustaka ...
5.1 Komoditas Film Islam Populer dalam Negosiasi Politik dan Ekonomi ... 5.2 Film Islam dan Identitas (Anak Muda) Muslim ... 5.3 Transnasional dalam Arus Post-Islamisme ... 6. Kerangka Teori ... 6.1 Tiga Tingkat Makna ... 6.2 Melankolia dalam Narasi Pascakolonial ... 7. Metodologi Penelitian ... 8. Sistematika Penulisan ...
Bab II Film Islam: Kemunculan, Wacana, dan Fenomena ... Pendahuluan ... A. Film Religi, Dakwah atau Film Islam? ...
i ii iii iv v vi vii ix 1 1 11 11 11 12 12 13 15 16 19 23 27 28 30 30 32
x
B. Film Islam dalam Paradigma Budaya Populer dan Perkembangan Muslim Kelas Menengah di Indonesia ... C. Imajinasi Kosmopolitan dalam Film (Islam) Indonesia ... D. Film yang Diteliti dalam Tesis ini ...
1. Ayat-Ayat Cinta ... 2. 99 Cahaya di Langit Eropa ... 3. Haji Backpacker ... 4. Assalamualaikum Beijing ... E. “Pesan” dalam Keempat film ... 1. Latar ... 2. Tokoh dan Penokohan ... 3. Relasi Antar Tokoh ... 4. Tata Busana ... 5. Gaya Bahasa ...
Bab III Dunia yang Dibayangkan Muslim Melankolik:
Analisis Naratif Melalui Tingkat Kedua dan Ketiga Atas
Keempat Film ... Pendahuluan ... A. Kontestasi Simbol ... 1. Narasi Kejayaan Islam di Penjuru Dunia ... 2. Muslim Ideal dan Heroik ... 3. Identifikasi Diri dari Other/Liyan (Meliyankan) ... B. Mencari Filmis: Objek (a) yang Hilang ... 1. Moralitas ... 2. Agama ... C. Pengalaman Menjadi Muslim Melankolik ...
1. Munculnya Pahlawan dalam Bentuk Agen Islam (Sosok
Muslim Ideal) ... 2. Melanggengkan Wacana Kolonial ... D. Menulis Ulang Sejarah Dunia (Islam) ... Bab IV Penutup ... 39 42 47 47 52 56 58 59 59 61 65 68 72 74 74 75 75 84 90 93 95 97 104 109 112 113 115
xi Daftar Pustaka ... Daftar Istilah ... Daftar Gambar ... 123 128 130
1
Bab I
Pendahuluan
A. Latar Belakang
Film selalu bisa membuat saya merefleksikan pengalaman hidup dan religiusitas. Dari sebuah film saya berkaca tentang diri dan memahami pengalaman kehidupan. Saya lahir dan besar dari imajinasi masyarakat perantau, matrilineal, dan mayoritas Muslim di Ranah Minangkabau, Sumatera Barat. Imajinasi rantau ini menjadikan diri saya selalu haus untuk meneguk pengalaman baru di tanah jauh. Sejak kecil kami diprovokasi oleh orang tua dan masyarakat untuk merantau. “Ka rantau bujang daulu,
di rumah paguno balun” (ke rantau anak dahulu, di rumah belum lagi berguna), begitu
pepatah petitih orang tua yang sering diujarkan.
Berdarah Jawa-Minang (bapak berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah, dan ibu dari Pariaman, Sumbar), tak lantas mengerti ‘Jawa’ karena saya tumbuh besar di kota Padang. Padang, kota kecil di pinggir pantai barat Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Kota Padang merupakan daerah rantau dalam sistem wilayah adat Minangkabau sendiri. Meski begitu, kota Padang sebagai pusat ibukota Sumatera Barat ini berkarakter homogen (sama halnya dengan daerah ‘asal’ Minangkabau), yaitu (mayoritas) Muslim dan (suku) Minang. Hal ini menyebabkan saya tidak (banyak) punya teman dari agama dan etnis/daerah yang berbeda. Tentu saya berharap bisa menjejaki dan bersentuhan dengan ranah jauh (rantau). Ranah yang selalu dirindukan, diinginkan, sekaligus dicemburui oleh mental inferior sebagai warga dari kota kecil yang jauh dari ‘pusat’ ibukota.
2 Tidak setiap jengkal tanah imajinasi perantauan dan perjalanan benar-benar bisa saya alami dalam kenyataan. Film kemudian menjadi perpanjangan mata dan telinga untuk memenuhi hasrat tersebut. Hasrat bertualang untuk mengenal berbagai macam ranah budaya, agama, identitas, dan permasalahan dari beragam manusia. Gambar bergerak sekaligus bersuara (film) adalah refleksi terdekat dari keinginan untuk menemui dua hal penting, yaitu, pelekatan Minangkabau dengan Islam. Saya merefleksikan banyak hal dari dua sisi ini; pengalaman merantau dan religiusitas. Dua hal yang masih terus saya hasrati dan rindukan. Meski makin lama imaji tersebut tak lagi ‘utuh’.
Melalui sedikit perjalanan di Sumatera dan Jawa, saya merasakan (imaji) Indonesia yang berubah. Rupanya perubahan yang saya alami terbalik dari pengalaman masyarakat umum. Saya memutuskan berjilbab saat SMA kelas 2 di Padang (2002). Pada waktu itu belum banyak orang yang berjilbab (lebar). Bagi masyarakat umum, jilbab masih sebatas selendang yang lebih banyak digunakan oleh perempuan berumur lanjut (nenek-nenek). Selendang lazim digunakan pada saat agenda keagamaan. Istilah jilbab lebih banyak digunakan oleh siswa madrasah, tsanawiyah, dan pesantren. Di keluarga kami belum ada yang berjilbab. Bahkan Ibu saya sendiri melarang, katanya takut tidak dapat jodoh dan pekerjaan. Kakak-kakak saya sinis, begitu juga tetangga, teman, hingga seringkali disindir guru di sekolah. Saya dilabeli dengan istilah ‘Ninja’ dan dituduh mengikuti ‘aliran Islam’ tertentu. Saya dijadikan sesuatu yang menakutkan/berbahaya bagi diri dan orang sekitar. Seketika saya di-liyan-kan.
Dari pengajian di Rohis SMA, saya merasa dituntut untuk berubah secara kaffah (menyeluruh)1. Perubahan saya begitu mendadak dan mencolok. Dari yang tadinya
1Kaffah sering diartikan menjalankan aturan hukum (syariat) Islam secara menyeluruh tanpa terkecuali.
3 berpenampilan tomboy, menjadi terlihat feminine dengan rok, baju longgar panjang, jilbab lebar, dan tidak bersalaman dengan lelaki. Bacaan saya berubah dari yang tadinya bacaan popular khas remaja di zaman itu; Conan, Harry Potter, Lima Sekawan, novel Balai Pustaka, menjadi majalah Annida, Tarbawi, dan Sabili. Saya berhenti mengikuti ekskul basket untuk kemudian aktif di forum Annisa, Rohis, dan Perkumpulan Aktifis Dakwah Sekolah di Sumbar. Lingkungan saya terbatas pada Rohis sekolah dan teman-teman Liqo’2. Penggunaan pas foto berjilbab untuk ijazah di tahun 2002 masih dilarang. Kami dari Rohis melakukan demonstrasi ke sekolah untuk memprotes larangan tersebut. Pada 2003 larangan tersebut dicabut.
Saya masih kelas 1 SMA ketika Peristiwa 11 September 2001 terjadi. Tahun berikutnya (setelah aktif di Rohis) saya baru ngeh dengan peristiwa tersebut. Respon dan reaksi Barat terhadap Islam pada 11 September 2001 menjadi alasan banyak aktivis dakwah semakin gencar beraksi. Kami pun ikut melakukan demonstrasi. Rohis sekolah (SMP dan SMA) di kota Padang berasosiasi dengan Partai Keadilan (Sejahtera) dan KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia). Kami berpihak pada aktivisme Ikhwanul Muslimin. Musuh kami pada waktu itu adalah Barat, Amerika, Zionis, Yahudi, serta Kristenisasi. Tepatnya adalah hal-hal yang dianggap memusuhi dan menghancurkan Islam dan orang Islam di manapun berada. Idola kami adalah para jihadis, ‘pengantin’ bom bunuh diri. Ketika itu bercita-cita mati syahid membela Islam (di Palestina dari perang melawan Israel) sudah dimiliki sebagian besar anak Rohis.
2Liqo’ merupakan kelompok kecil yang terdiri dari tiga sampai delapan orang. Kegiatannya adalah belajar kajian ke-Islam-an, dari mulai membaca Al Quran, hafalan, tadabur alam hingga belajar memasak. Kegiatan ini diinisiasi oleh Rohis sekolah dan dimentori oleh anak-anak kuliahan dari Aktifis Dakwah Kampus (biasanya alumni dan jaringannya). Anggota Liqo’ tidak boleh keluar masuk kelompok yang lain begitu saja. Harus dengan sepengetahuan mentor. Termasuk jika pindah kota, akan dicarikan Liqo’ yang masih satu jaringan.
4 Di sisi lain, semua selain kami adalah liyan, yaitu kalangan yang kami anggap awam, tidak/belum memahami Islam, dan belum berislam secara kaffah (menyeluruh). Bahkan jika orang tua dan saudara kandung kami tidak menjalankan syariat seperti yang dijalankan komunitas Liqo’, seketika menjadi ‘yang lain’. Saya dan teman-teman menjadi kalangan yang eksklusif. Sebuah kenikmatan bagi remaja tanggung yang sedang mencari jati diri.
Rohis terlalu jauh masuk ke dalam ranah privat anggotanya. Beberapa orang bahkan dikeluarkan karena ketahuan pacaran. Saya mulai mengkritik kebijakan Rohis. Pertanyaan saya seputar bom bunuh diri dan perang Israel-Palestina tak kunjung menemukan jawaban. Opini yang ada dalam jaringan Rohis-Liqo’ seolah seragam. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mulai terasah lagi ketika saya kuliah di kampus seni pada pertengahan tahun 2007. Saya mulai berhenti Liqo’ dan bergaul dengan siapa saja. Saya mulai mengkritisi cara saya memandang tubuh dan apa yang melekat padanya.
Saya memutuskan berhenti berjilbab ketika tamat kuliah pada tahun 2012 dan pindah ke Bali. Begitu menemui Hindu Bali, menjadi minoritas di Tanah Dewata, saya gamang karena pada kenyataannya tidak tahu apa-apa tentang selain diri saya (yang Minang dan Islam). Saya bahkan ‘terteror’ (tidak nyaman, takut, dan gugup) ketika melihat simbol Katolik di kampus Sadhar. Sementara teman-teman Katolik yang baru saya kenal sangat terbiasa dengan simbol Islam, hafal Al Fatihah dan beberapa doa sederhana. Saya mulai mempertanyakan wacana ‘Islamofobia’, saya kok merasakan yang sebaliknya.
Namun, saya tidak sadar dengan lingkungan masyarakat yang rupanya sudah jauh berubah. Jilbab masuk mall, semakin tren dan ‘naik kelas’, warna-warni, dan beragam aksesoris pendukung. Pakaian gamis disukai, harganya makin mahal. Cerpen/novel
5 yang sarat muatan Islam seperti dipopulerkan Forum Lingkar Pena, dulu hanya saya baca di majalah Annida. Festival keislaman, sinetron, dan tayangan televisi soal Islam meningkat. Novel Ayat Cinta laku keras, menjadi best seller di Gramedia.
Ayat-Ayat Cinta dibaca oleh banyak orang di luar lingkarannya. Hingga Ayat-Ayat-Ayat-Ayat Cinta
dijadikan film dan booming! Untuk pertama kalinya perempuan berjilbab lebar, larangan pacaran, hingga taaruf terpampang di layar lebar Indonesia. Orang kaget dengan berjubelnya perempuan berjilbab lebar dan lelaki berjenggot masuk bioskop.3 Selama ini bagi kalangan Rohis, bioskop adalah ‘ladang maksiat’, untuk itu harus dijauhi. Media dakwah berkembang ke wilayah paling populer bagi anak muda. Akan tetapi, karena jauh dari bioskop, saya tidak mengikuti arus film Islam ini. Rupanya dakwah dan komodifikasi keislaman berjalan sembari perubahan sosial terjadi di masyarakat.
Ketika film Ayat-Ayat Cinta diikuti oleh film Ketika Cinta Bertasbih tayang di bioskop, saya berpikir bahwa hal ini hanya tren sementara saja. Namun saya salah besar. Perubahan arus perkembangan Islam dan imajinya berkembang jauh lebih pesat. Pada awal tahun 2014, saya menjalani Program Magang Nusantara (program Kelola) di Selasar Sunaryo Art Space selama tiga bulan. Saat-saat magang itulah film 99 Cahaya
di Langit Eropa hadir dan mengganggu saya dengan pencitraan Islam yang dihadirkan.
Film 99 Cahaya di Langit Eropa sangat membuka mata saya bahwa dunia berubah, wajah Islam dan pencitraannya di masyarakat dan industri mulai melesat ke tempat yang sebelumnya tak pernah saya bayangkan. Begitu juga dengan kota Bandung, banyak tulisan kos-kosan yang khusus menerima perempuan Muslim. Satu kali ketika berjalan di area Car Free Day Bandung, anak-anak muda HTI kampanye anti pluralisme dan anti
3Ariel Heriyanto. Identitas dan Kenikmatan; Politik Budaya Layar Indonesia. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2015. Hal 79-80.
6 demokrasi sambil berdemonstrasi. Saya tercekat. Sepuluh tahun sejak pertama kali saya mengenal gerakan Rohis, efeknya baru terasa meluas dan massif.
Pada saat itulah saya mulai membayangkan kembali pengalaman represi atas nama Perda Syariah Padangpanjang, Sumatera Barat, di tahun 2009. Saya melepas jilbab pada saat jilbab dan citra soleha pada perempuan Muslim makin melekat. Akibatnya dari yang tadinya dituduh ikut aliran, membuka jilbab membuat saya distigma, dilecehkan, dan dituduh sudah berpindah agama. Terlebih karena saya melanjutkan kuliah di kampus milik Yayasan Katolik.
Sementara itu saya sendiri mengalami shock culture ketika berhadapan dengan ‘perbedaan’ (adat istiadat, ras, suku, dan agama). Gejolak ini rasa-rasanya tercurah pada saat menonton film-film Islam (terutama dengan latar luar negeri).Sama seperti halnya saya yang merantau ke Bali dan Jawa, inferior dan phobia terhadap yang lain sekaligus.
Sehingga ketika menonton film yang disematkan kepadanya nilai-nilai keislaman, dakwah, dan transformasi menjadi Muslim yang utuh (kaffah) dalam perjalanan merantau, saya justru ingin berpaling. Saya seperti melihat cermin diri yang dulu sudah saya tanggalkan dihadirkan di depan mata secara vulgar. Saya ingat sekali ketika menonton film 99 Cahaya di Langit Eropa (Guntur Soeharjanto, 2014) tidak bisa saya lanjutkan hingga selesai. Ini menjadi pengalaman pertama saya untuk berhenti menonton hanya pada beberapa menit pertama saja. Terlebih film yang harusnya saya sukai, yaitu ‘film jalan-jalan’ (ke luar negeri).
Narasi yang dihadirkan oleh film 99 Cahaya di Langit Eropa ini bukan sesuatu yang asing, ia begitu sering saya temui dalam kehidupan sehari-hari. Narasi Muslim di luar negeri, stigma Barat terhadap Islam, idealisasi seorang Muslim, dan pertengkaran persoalan halal-haram tidak pernah absen di film-film bernuansa Islam. Hampir di
7 banyak film bernuansa Islam, topik-topik seperti ini selalu muncul. Pantulan narasi di dalam genre film Islam berlatar luar negeri seolah mengamini dan mendukung mental inferior saya ketika berhadapan dengan dunia asing yang ingin ditemui.
Film Ayat-Ayat Cinta tak sendiri, ia diulang dan diikuti (menjadi tren) oleh film sejenis dengan image yang populer hingga hari ini. Mulai dari film Ketika Cinta
Bertasbih, 99 Cahaya di Langit Eropa (sekuelnya hingga empat film), Haji Backpacker,
dan Assalamualaikum Beijing memiliki banyak kesamaan. Eric Sasono mengatakan bahwa ini adalah film yang mengimajinasikan Muslim transnasional.4 Ia memiliki ciri-ciri kosmopolit, akan tetapi justru menebalkan identitas tertentu. Benarkah bisa kita namai dengan Muslim kosmopolit?
Genre film Islam ini mendapatkan cap ‘film populer’ atau ‘budaya populer’ dikarenakan begitu massif dan populis penyebaran serta isu yang dihadirkan. Sesuatu yang populer tidak begitu saja berjarak dari masyarakatnya. Ibarat cermin, film dapat membantu kita untuk melihat masyarakat dan imajinasi yang sedang dibangunnya. Imajinasi apa yang sedang direpresentasikan, dihadirkan, diinginkan, dan didambakan, sekaligus ditolaknya? Patut dicurigai bahwa gambaran kosmopolitanisme dipinjam hanya untuk melegitimasi narasi politis agar diakui dan kemudian merasa berhak untuk menaklukkan kembali (Barat)? Namun, apakah narasi seperti ini selalu hadir di dalam film Islam yang berlatar luar negeri? John Storey mengutip dari Maltby mengenai perspektif melihat budaya pop sebagai dunia impian kolektif, sebagai berikut:
Kalau hal ini disebut kejahatan budaya pop karena merampas angan-angan kita kemudian mengemas dan menjualnya kembali pada kita, maka ia juga adalah prestasi, budaya pop telah membawa kita pada berbagai angan selain pada angan yang sudah kita kenal.5
4https://ericsasono. wordpress.com/2015/01/03/mencatat-film-indonesia-2014-bagian-1/ (diakses 03/01/2015)
5John Storey. Teori Budaya dan Budaya Pop: Memetakan Lanskap Konseptual Cultural
8 Dalam perspektif melihat budaya populer, kajian budaya sering memakai pendekatan strukturalisme (dan turunannya) untuk melihat struktur narasi yang memproduksi wacana. Strukturalisme dan post-strukturalisme tidak menempatkan budaya pop pada perspektif budaya massa dengan pendekatan moralistik. Ada ruang kritik untuk pembaca bisa menghindari kontradiksi tekstual tertentu karena budaya pop dilihat sebagai mesin ideologis yang mereproduksi ideologi dominan tertentu.6
Penelitian ini melihat beberapa film Islam yang berlatar luar negeri di era pasca-Orde Baru. Dengan tujuan mengetahui kecenderungan sistem/struktur naratif dalam membangun/membentuk sebuah tren naratif tertentu dalam film genre Islam yang berlatar luar negeri. Kemudian menelaah Muslim seperti apa yang sedang dihadirkan dan direpresentasikan. Begitu juga situasi politis dan global apa yang memengaruhi imajinasi Muslim di film-film tersebut.
Penelitian ini mengkhususkan empat film sebagai sumber utama objek penelitian. Pertama, film Ayat-Ayat Cinta (Hanung Bramantyo, 2008) berlatar Kairo, Mesir. Kedua, 99 Cahaya di Langit Eropa part 1 dan 2 (Guntur Soeharjanto, 2014/2015) berlatar Austria, Perancis, Spanyol, dan Mekkah, Arab Saudi. Ketiga, Haji Backpacker (Danial Rifki, 2014) memilih sembilan negara menuju Mekkah dengan jalur darat (Jalur Sutra). Keempat, Assalamualaikum Beijing (Guntur Soeharjanto, 2014) memilih Jakarta dan China sebagai latar utama film.
Empat film ini memilih ragam luar negeri yang kompleks. Mulai dari Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Film-film tersebut dianggap cukup mewakili perbincangan mengenai film Islam yang membicarakan isu-isu kosmopolit. Pengaruh film ini begitu
9 besar bagi kaum muda Islam perkotaan.7 Saya sering mendengar seseorang memutuskan berjilbab setelah menonton film 99 Cahaya di Langit Eropa. Empat film ini menjadi favorit, dipuja, dan menjadi patron untuk kisah cinta sebagian penontonnya. Mereka ingin mengalami kisah cinta seperti Fahri, Hanum, dan lainnya. Kisah cinta/romantisme dalam koridor Islam.
Dalam kritik film, baik independen dan akademis, perbincangan mengenai isu/konten film-film tersebut begitu ramai. Tak sedikit pula kritikus film menanggapi perkembangan genre film yang sarat nuansa Islam berlatar luar negeri ini dengan sinis. Film genre ini dianggap tidak berkembang, baik secara capaian visual ataupun narasi. Dalam suatu wawancara dengan Cinema Poetika8, Hikmat Darmawan mengatakan bahwa ia sudah tidak tertarik membahas film-film dengan isu keislaman. Menurut Hikmat, tidak ada lagi yang bisa dibicarakan dari film genre tersebut. Berikut kutipan pernyataan Hikmat:
Beberapa kali saya juga sempat menulis tentang film Islam di majalah Madina. Mendingan, tulisan-tulisan itu saya kumpulkan terus saya jadikan buku, dengan tema “Film Islam di Indonesia”. Tinggal tambah tulisan pengantar, pendahuluan, jadi deh satu buku. Tapi kalau saya terus-terusan menulis tentang itu di media, hmm, saya kan bukan kritikus khusus film-film Islam. Saya nggak mau terjebak di situ juga. Setidaknya secara pribadi, saya sudah tidak tertarik lagi (tertawa).9
Membicarakan film (populer) seringkali hanya diwakilkan oleh pembahasan aspek kultural sosial, politis, dan ekonomi seperti kritik film yang ditulis Hikmat Darmawan, Eric Sasono, Ariel Heryanto, dan lainnya. Maraknya ilmu humaniora yang mulai membicarakan medium film dalam perannya sebagai artefak budaya, membuat
7Hariyadi, “Islamic Films and Identity: The Case of Indonesian Muslim Youths”. Di dalam prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: Etnicity and Globalization”.
8Cinema Poetica merupakan sebuah situs online berbasis di Indonesia yang mengkhususkan film sebagai subjeknya.
9http://cinemapoetica.com/hikmat-darmawan-kritik-film-bukan-pemandu-belanja/ (diakses 26 April 2016)
10 penelitian ini dapat dilihat dari beragam aspek sosial budaya. Sayangnya, penelitian mengenai film tersebut hanya selesai pada pemaknaan simbolik. Beberapa sudah memperlihatkan latar ekonomi politik yang melatarinya, namun masih gagal ‘menamai’ Muslim yang sedang dibicarakan di dalam film-film itu. Sehingga wajar jika Hikmat Darmawan merasa tema ini tidak menarik lagi (mandeg). Dari berbagai macam penelitian tema yang ada, saya masih melihat beberapa hal belum terurai dari kritik atas film ini.
Empat film ini begitu berlimpah dengan penanda simbolik mengenai kejayaan Islam di masa lalu. Bagaimana memaknai ini agar tidak terjebak dalam kritik normatif? Mancanegara tampil eksotis sebagai latar cerita, mengusung berbagai ‘fakta’ sejarah Islam. Persis seperti kita melihat acara turisme sejarah Islam di berbagai belahan dunia ketika bulan puasa. Klaim soal kejayaan Islam di masa lalu di berbagai tempat dihadirkan begitu intens. Bangunan megah, penemuan teknologi, dan ahli/pemikir Islam dimunculkan secara bersamaan. Namun, seringkali kesan kejayaan Islam di masa lalu diakhiri dengan semacam penyesalan dan kekecewaan. Bahwa sejarah telah berlalu dan tak bisa ditemui lagi, yang ada hanya jejak kejayaannya. Klaim kejayaan dibalut oleh rasa kehilangan yang khas. Dibumbui penokohan berkarakter saleh dan ideal dalam pergaulan internasional. Muslim seperti apa yang sedang kita saksikan di dalam tren film Islam semacam ini? Penamaan Muslim kosmopolit dalam berbagai kritik film tematik ini, masih belum cukup kuat untuk mewakili sosok Muslim yang dihadirkan di film-film tersebut. Pengalaman kehilangan apa yang sedang mereka nikmati sehingga menciptakan film-film tertentu (secara terus-menerus). Khususnya pada pengalaman kehilangan akan kejayaan Islam di masa lalu. Pengalaman kehilangan ini menjadi fokus penelitian dengan menggunakan pendekatan kritis estetika melankolia.
11 1. Tema Penelitian
Menyoal tren narasi film Islam berlatar luar negeri dalam perwujudan narasi wacana pascakolonial yang membentuk imajinasi Muslim melankolik.
2. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, perlu merumuskan fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1) Tren narasi film seperti apa yang dibangun dalam beberapa film yang telah dipilih sebagai objek penelitian?
2) Bagaimana model/tren narasi tersebut membangun/membicarakan imajinasi wacana Muslim melankolik?
3) Islam atau Muslim seperti apa yang dikonstruksi melalui narasi film tersebut?
3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah di atas. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang ragam kritik estetis film dalam melacak sebuah tren naratif salah satu genre film Indonesia. Terkait dengan tren narasi dari film-film populer Islam Indonesia berlatar luar negeri di suatu masa tertentu. Sehingga memberi pemahaman berbeda dan masukan pada perkembangan film populer Indonesia. Serta dapat memberi masukan dalam cara pandang berbeda atas kritik film dan dialektika narasi Muslim melankolik sebagai masyarakat pasca-Orde Baru sekaligus pascakolonial.
12 4. Relevansi Penelitian
Kritik film merupakan salah satu kajian yang berada di bawah payung studi humaniora dan kajian budaya. Kajian budaya sebagai ruang lingkup tidak membatasi diri dari wacana dan relasi yang dihadirkan sebuah teks budaya, termasuk budaya populer. Teks budaya (populer) mempunyai struktur penting dalam mewujudkan makna. Untuk itu penelitian ini diharapkan menambah ragam perspektif melihat film sebagai sebuah mesin yang mempunyai bentuk dan struktur keseluruhan yang bisa dikenali dengan mengurainya dari sudut pandang naratif film. Sebagai sebuah mesin yang bertubuh, film mereproduksi pantulan/refleksi atas kondisi sosial masyarakat tempat ia dilahirkan. Dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia, yang selain pasca-Orde Baru, juga pascakolonial. Kebertubuhan terhadap isu wacana kolonial (serta neokolonial) dapat ditemui pada film sebagai produk budaya. Pertanyaan-pertanyaan terkait kebertubuhan ini dibicarakan melalui aspek karakteristik struktural-estetis film.
Subjek penelitian merupakan fenomena yang berkembang luas/populer dan masih terus direproduksi hingga saat ini. Sifatnya yang massal dan seragam menjadikan budaya populer mempunyai kecenderungan merepetisi wacana dan tren tertentu di dalam masyarakat. Hal ini dimaknai dalam berbagai macam sudut pandang kajian keilmuan, terkhusus kajian film sebagai salah satu pintu masuk penelitian kajian budaya di Indonesia. Sehingga penting untuk melihat bagaimana posisi penelitian ini di dalam ruang dialektika penelitian sebelumnya.
5. Tinjauan Pustaka
Dihidupi oleh beragam suku, agama, etnis, budaya, dan sikap politis masyarakatnya, Indonesia mempunyai potensi besar untuk diperbincangkan pada
13 produk budaya yang bernama film. Banyak genre film telah lahir dari tangan dingin sineas Indonesia. Film Islam adalah salah satu yang kemudian menjadi isu hangat dan banyak dibicarakan serta dikupas dari beragam sudut pandang. Sangat mustahil pernyataan mengenai orisinalitas tema penelitian ini secara keseluruhan. Untuk itu penting melihat hasil penelitian sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan yang sama. Orisinalitas penelitian akan ditemukan dengan menelisik lebih jauh sudut pandang yang berbeda. Pada tiga sub-bab tinjauan pustaka ini akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu dan posisi penelitian ini di antara penelitian yang sudah ada.
5.1 Komoditas Film Islam Populer dalam Negosiasi Politik dan Ekonomi
Sebagai sebuah film populer yang sering direpetisi dan masih terus direproduksi, tentunya penting untuk melacak konstruksi narasi secara teknik sinematografis dan historis style dan narasi yang dipakainya. Film sebagai artefak budaya seringkali dibahasakan (dibaca, diteliti, dan dikritisi) dalam konteks sosial budaya dan politik. Aspek formal film sebagai sebuah karya seni yang melibatkan kolaborasi tema, narasi, dan style filmis menjadi terabaikan. Bahwasanya pengabaian terhadap aspek formal tersebut dapat dirunut dari penelitian A Cultural Economy of the Contemporary
Indonesian Film Industry oleh Thomas Alexander Charles Barker. Penelitian ini
merupakan penelitian yang lebih luas mengenai industri perfilman Indonesia kontemporer pasca-Orde Baru. Tesis Barker di National University of Singapore (2011) mencatat perkembangan film Indonesia dari beragam genre, salah satunya adalah genre film populer Islam. Pembahasan Barker pada bab ini menjelaskan film Islam sebagai bentuk representasi dan artikulasi keislaman yang berbeda/beragam jika dibandingkan dari film Islam sewaktu rezim Soeharto. Barker menyimpulkan bahwa kebebasan
14 pembuat film mengartikulasikan Islam harus bernegosiasi dalam arena pertarungan logika ekonomi kapitalistik dan oligopoli nonformal. Barker baru menyentuh film Islam populer dari sudut pandang umum dan politis.
Kuasa dalam Sinema, Negara, Masyarakat, dan Sinema oleh Krishna Sen dapat
memberikan gambaran umum mengenai bagaimana situasi perfilman Indonesia dan karakteristik form filmis secara umum di masa Orde Baru. Krishna Sen mengungkapkan bahwa hampir semua film yang diproduksi di era Orde Baru memiliki struktur naratif yang bergerak dari kekacauan, kemudian ke pengembalian tatanan tersebut. Karakteristik formal ini tidak tergantikan oleh perbedaan tema, genre, atau atribut estetik lainnya. Meskipun begitu, Krishna Sen juga melihat adanya narasi berseberangan dari form filmis yang umum. Penelitian Krishna Sen setidaknya memberikan gambaran historis dari sikap politis dan perkembangan perfilman Indonesia di era Soeharto. Serta memberikan aspek sudut pandang dalam melihat karakteristik formal film seperti penelitian yang saya lakukan. Beberapa tulisan yang layak dijadikan sumber referensi untuk memahami perkembangan film Indonesia selain dari Krishna Sen adalah 100 Tahun Sejarah Bioskop di Indonesia oleh HM. Johan Tjasmadi (2008).
Gender and Islam in Indonesian Cinema (2017) oleh Alicia Izharuddin fokus
pada kesalehan dan dakwah atas film Islam dengan kacamata studi gender. Terutama menyangkut representasi perempuan dan relasi gender oleh film Islam pasca-Orde Baru. Begitu juga dengan Representasi Perempuan dalam Film Bernuansa Islami yang ditulis oleh Syiqqil Arofat sebagai tesis di Magister Universitas Indonesia. Secara umum, hasil penelitian ini membicarakan representasi perempuan (dalam lima film) yang hadir dalam relasinya dengan struktur sosial lainnya (perempuan sebagai anak, ibu, istri, pekerjaan, dll). Representasi perempuan dalam film dilihat dari aspek naturalisasi
15 perempuan dan laki-laki seperti halnya studi kasus gender (pada umumnya). Akan tetapi, seperti kebanyakan penelitian mengenai film Islami lainnya, tesis ini (juga) luput melihat aspek relasi kuasa (negara, politik, ekonomi, dll) yang menjadi latar belakang lahirnya representasi perempuan tertentu (dan terus-menerus diulang) dalam film Islam. Sehingga kesimpulan penelitian melihat fenomena hegemoni dalam film Islam seolah-olah muncul begitu saja.
5.2 Film Islam dan Identitas (Anak Muda) Muslim
Terdapat beberapa paper yang ditulis oleh Hariyadi, mahasiswa program PhD di Asian Studies, The University of Western Australia, mengenai film Islam, yaitu, “Finding Islam in Cinema: Islamic Film and the Identity of Indonesian Muslim Youth”. Kemudian, “Islamic Movies: Propagating Islam to the Youth in Indonesia” dan “Islamic Popular Culture and the New Identity of Indonesian Muslim Youth”. Dari ketiga paper ini, pembahasan Hariyadi pada film Islam mengenai identitas pemuda/i Muslim di Indonesia. Film menjadi salah satu bagian dari pembentukan identitas pemuda Muslim dinilai dari fungsinya yang mampu mempropagandakan isu tertentu. Fokus penelitian Hariyadi pada penonton (pemuda) di Yogyakarta dan Bandung mengenai negosiasi mereka terhadap film Ayat-Ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih. Haryadi belum menyentuh aspek estetis film sebagai sebuah karya seni.
Ariel Heryanto dalam Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia (2015). Dalam dua bab pertama buku ini, Ariel Heryanto melihat bahwa film populer Islam merupakan bagian dari wacana post-Islam dan Islamisasi di Indonesia pasca-Orde Baru. Penelitian Ariel mengenai hal ini merupakan pemetaan terhadap sikap politis dalam film Islam di arena historis perfilman Indonesia. Kemudian Budaya Populer di
16
Indonesia, Mencairnya Identitas Pasca-Orde Baru (2012) oleh Ariel Heryanto (ed).
Buku ini memperbincangkan identitas pasca-Orde Baru dalam budaya populer di Indonesia. Jelas penelitian Ariel penting sebagai landasan awal untuk melihat medan politis film Indonesia dan menempatkan film Islam di dalam arena tersebut.
5.3 Transnasional dalam Arus Post-Islamisme
Beberapa penelitian Eric Sasono berikut menarik untuk melihat film Islam dari sisi yang berbeda. Islamic-Themes Films in Contemporary Indonesia: Comodified
Religion or Islamizazion? (2010), “Muslim Sosial dan Pembaharuan dalam Beberapa
Film Islam di Indonesia” (makalah diskusi di Salihara, 2011), The Raiding Dutchmen:
Colonial Stereotypes, Identity, Islam in Indonesian B-Movies (2014). Catatan Eric
Sasono di blog personalnya10 mengenai film Islam yang dalam istilah Eric Sasono sebagai perkembangan lintas nasional arus post-Islamisme. Eric melihat film Islam yang berlatar luar negeri sebagai momentum baru: hasrat lintas nasional. Hipotesis Eric Sasono berdasar pada konsep imagined communities Bennedict Anderson. Letak perbedaannya dengan penelitian saya adalah dari titik berpijak. Eric hanya berpijak pada pemaknaan film sebagai artefak budaya. Sementara pijakan saya akan bermula dari aspek formal film. Melihat karakteristik narasi genre film (Islam) yang mengusung latar luar negeri dengan imajinasi ‘kosmopolit’. Yang kemudian saya analisis dalam narasi pascakolonial. Perbedaan titik pijak penelitian ini memungkinkan hasil penelitian yang lebih konkret dan mampu membaca corak tren film Islam dengan negosiasi kosmpolitannya.
10Blog Eric Sasono beralamat di
17 Wasisto Raharjo Jati dalam Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia (2017). Jati menelaah perkembangan Muslim kelas menengah Indonesia era modern. Buku ini merumuskan kembali kemunculan kelas menengah Muslim dan Islam populer yang berkelindan dengan budaya konsumsi sebagai faktor pembentuk identitas mereka. Hal ini juga dihubungkan dengan kesalehan dan keimanan dalam menyikapi produk budaya populer yang sedang berkembang. Penelitian ini sangat membantu saya dalam memahami perkembangan kelas menengah Muslim Indonesia hari ini. Perlu meninjau dinamika dan gaya hidup kelas menengah di kota-kota besar di Indonesia seperti yang ditulis oleh Gerry van Klinken dan Ward Berenschot (ed) di dalam In Search of Middle
Indonesia: Kelas Menengah di Kota-Kota Menengah (2016). Begitu juga dengan
penelitian Khairudin Aljunied dalam Muslim Cosmopolitanism: Southeast Asian Islam
in Comparative Perspective (2017). Aljunied meneliti perkembangan Muslim
kosmopolitan di kawasan Asia Tenggara melalui pasar global yang banyak disumbang oleh kaum hijabers. Aljunied juga memandang perkembangan Muslim kosmopolitan dari berbagai sisi yang melingkupinya di kawasan Asia Tenggara. Hal ini saya perlukan untuk bisa melihat perkembangan Muslim kosmopolitan dengan lebih luas.
Adrian Jonathan Pasaribu, dkk., di dalam Merayakan Film Nasional (2017). Buku yang terbit untuk memperingati Hari Film Nasional 2017 ini berusaha merumuskan apa itu film nasional hari ini. Buku ini merangkum sejarah perkembangan perfilman Indonesia sejak medium film itu diperkenalkan di Hindia Belanda. Salah satu yang pembahasan menarik dari Hikmat Darmawan dalam sub pembahasan “Film Nasional Dalam Dunia Pasca-Nasional”. Tulisan Darmawan dan yang lainnya di buku ini membantu saya untuk merumuskan perjalanan panjang sejarah film Indonesia yang berusaha memandang Indonesia hari ini dan tantangan yang akan dihadapinya. Dalam
18 bagian ini, Darmawan merumuskan pembahasan istilah Pasca-Indonesia (Romo Mangunwijaya) dan Pasca-Nasional oleh Seno Gumira Ajidarma dalam orasinya mengenai persoalan identitas film nasional. Simpulan dari tulisan Darmawan adalah pada masa 2000-an dengan adanya lanskap kosmopolitan, beragam, dan kontemporer mengesankan adanya sebuah “Indonesia baru”. Wacana Indonesia baru seringkali berkelindan dengan politik identitas yang semakin menguat. Tulisan Darmawan tadi menjadi menarik untuk ditelaah lebih jauh mengenai wacana Pasca-Nasional. Wacana Pasca-Nasional ini sangat berhubungan dengan wacana kosmopolitanisme yang menjadi salah satu pembahasan penelitian ini.
6. Kerangka Teori
Di dalam kajian budaya, budaya pop memiliki cakupan yang lebih luas dari sekadar sebuah hiburan dan pengisi waktu senggang. Budaya pop seperti yang dikutip John Storey dari Hall adalah sebuah situs di mana “pemahaman sosial kolektif tercipta”. Ia terlibat dalam “politik penandaan” sebagai upaya untuk menundukkan para pembacanya pada cara pandang tertentu tentang dunia.11 Pemahaman sosial kolektif dapat dilihat dari struktur di dalam teks budaya populer yang lazim digunakan oleh cara pandang strukturalisme dan turunannya. Struktur tidak hanya dipandang sebagai struktur binarinya, tetapi juga struktur narasinya.12
Cara pandang strukturalisme ini mengambil dua ide dasar Saussure. Pertama, perhatian pada hubungan yang mendukung teks dan praktik budaya, yaitu ‘tata bahasa’ yang memungkinkan makna. Kedua, pandangan bahwa makna selalu merupakan hasil dari hubungan seleksi kombinasi yang dimungkinkan terjadi di dalam struktur yang
11John Storey. Teori Budaya dan Budaya Pop: Memetakan Lanskap Konseptual Cultural Studies. Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2003. Hal 7.
19 mendukungnya. Aturan dan konvensi (struktur) inilah yang mengatur penciptaan makna (parole).13 Film sendiri menurut Robert Stam merupakan langue tanpa parole karena makna sebuah film bersifat arbiter (mana suka), pemaknaannya bisa beragam di penonton.14 Untuk itu kritik film dimungkinkan. Di dalam film genre, konvensi struktur/sistem inilah yang kemudian akan dilihat untuk meneliti sejauh mana ia memiliki kesamaan satu sama lainnya.
Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama. Teori pertama menggunakan tiga tingkat makna Roland Barthes. Teori ini digunakan untuk menganalisis film sebagai teks visual. Teks visual film dimaksudkan untuk menemukan
sequens, scene atau adegan penting yang bisa digunakan untuk pembedahan lebih
lanjut. Baik pesan yang terlihat maupun tidak. Untuk kemudian bisa dilacak makna simbolis. Dari makna simbolis ini kita bisa menarik makna filmis (tingkat ketiga). Sehingga bisa dianalisis menggunakan pisau bedah kedua yang lebih luas. Pisau bedah kedua adalah analisis wacana menggunakan konsep melankolia.
6.1 Tiga Tingkat Makna
Dalam buku Imaji Musik Teks15 Roland Barthes membedah scene (adegan) dari film Ivan the Terrible melalui tiga tingkat makna. Barthes membedah satu scene pada film ini menggunakan tiga lapisan makna yang disebut juga dengan tiga tingkat makna.
13Ibid, hal 109
14Robert Stam. New Vocabularies in Film Semiotic. London: Routledge, 1992. 15 Roland Barthes. Imaji Musik Teks. Yogyakata: Jalasutra, 2010. Hal 41.
Judul lengkap buku ini adalah Imaji Musik Teks: Analisis Semiologi atas Fotografi, Iklan, Film,
Musik, Alkitab, Penulisan dan Pembacaan serta Kritik Sastra oleh Roland Barthes (Esai-Esai
20 6.1.1 Makna Tingkat Pertama (Lapisan Informasional)
Makna tingkat pertama disebut juga tingkat komunikasi atau informasi. Analisis tingkat pertama bertujuan untuk mendapatkan pesan dengan melakukan pencatatan terhadap informasi atau pengetahuan dasar yang dimiliki oleh film tersebut. Pengetahuan dasar ini menjadi landasan komunikasi antara sineas, sesama penonton, serta dialog dengan diri sendiri (si peneliti/penonton). Informasi dasar tersebut adalah segala sesuatu yang bisa dicerap dari latar (setting), kostum, tata letak, karakter, kontak, atau relasi yang terjadi di antara pelaku, serta gerak laku tokoh berupa anekdot yang bisa langsung terlihat (sekalipun tidak langsung).
Barthes menyebut lapisan informasional ini sebagai semiotika tingkat pertama, yakni membedah ‘pesan’ yang terdapat di dalam lapisan informasional tersebut. Barthes membedakan ‘pesan’ dengan pesan. Pesan dengan tanda petik dimaksudkan untuk pesan dalam pengertian hal-hal informatif dan komunikatif. Dalam semiotika, makna tingkat pertama ini disebut juga makna denotatif.
Bersifat sebagai lapisan dasar atau informasional, analisis makna tingkat pertama ini akan diuraikan pada bab 2. Dengan pembedahan secara umum atas latar, penokohan, relasi antar tokoh, tata rias busana, pemilihan gaya bahasa, dan musik atas keempat film yang diteliti.
6.1.2 Makna Tingkat Kedua (Lapisan Simbolis/Neo-Semiotika)
Penelitian tingkat kedua merupakan tahap penafsiran pesan dengan menggunakan pendekatan neo-semiotika/ilmu simbol. Analisis tingkat ini disebut juga sebagai tahapan simbolik yang bersifat konotatif. Tahap simbolik ini terdiri dari empat tahap, yaitu; simbolisme referensial, merupakan simbol-simbol acuan yang terlihat jelas. Kedua,
21 simbolisme diegetik, semacam sudut pandang (pemaknaan tertentu) yang ingin diperlihatkan. Ketiga, simbolisme Eisenteinian, disebut juga simbolisme khas SME (Sergei Mikhailovic Eisenstein), dalam padanan lain disebut juga sebagai makna ideologis. Keempat, simbolisme historis.
Tingkat kedua ini bertujuan mencari signifikasi/penanda melalui petanda yang sudah diperoleh pada tingkat pertama. Disebut juga semiotika tingkat kedua atau neo-semiotika. Semiotika tingkat kedua, mengupas pesan dari beberapa ilmu (psikoanalisis, ekonomi, dramaturgi) yang berurusan dengan simbol. Artinya pesan bisa dimaknai dengan menggunakan kerangka teoretis lainnya. Pemaknaan ini bersifat kritik ideologis dan historis untuk menemukan pesan yang terkandung di dalam film.
Makna simbolis mempunyai dua sifat, yakni intensional (langsung/kelihatan karena makna inilah yang mau diperlihatkan oleh kreator) dan menggunakan simbol-simbol yang sudah umum.16 Makna simbolis berhulu pada SME (Sergeri Mikhailovich Eisenstein) dan bermuara pada subjek yang membaca-tafsir. Makna simbolis ini disebut juga makna yang jelas terlihat (obvius meaning) disebabkan maknanya lebih natural.
6.1.3 Makna Tingkat Ketiga
Pada tingkat ketiga, Roland Barthes memakai teori signifiance sastra pada film, yaitu mencari unsur filmis. Filmis di sini belum tentu berada di dalam film, ia bisa berdiri sendiri di luar film seperti novelistik di luar novel. Filmis berada di luar bahasa (di mana muncul ‘pesan’) dan berada di luar meta bahasa (di mana muncul signifikasi dan ideologi).17 Hal ini bagi Barthes dapat berfungsi sebagai kritik atas film dengan mencari hal filmis.
16Ibid, hal 44 17 Ibid, hal 56
22 Filmis dimulai ketika bahasa dan metabahasa berakhir. Orang menemukan bentuk baru tanpa tahu isinya. Disebut juga sebagai makna obtusus (the obtuse meaning) yaitu makna yang masih tumpul. Mengandung arti yang masih samar-samar. Makna obtusus ini mempunyai kekuatan denaturalisasi, signifier (bersifat kosong), dan berfungsi sebagai aksen.18 Filmis dapat berarti momen di mana seseorang berhenti dan ingin kembali.
Proses dalam analisis film pada makna ketiga mengandaikan bahwa analisis film tidak sekadar berhenti pada deskripsi tentang proses signifikasi, melainkan juga pada penciptaan narasi kita sendiri. Sehingga sebagai peneliti film, kita dituntut tidak hanya bicara tentang film, akan tetapi berbicara dalam dan lewat film.
Makna ketiga merangsang baca-tafsir yang bersifat interogatif (jadi, proses interogasi justru dilakukan pada penanda bukan petanda, atau pada aktivitas menafsir itu sendiri bukan pada intellection: ia menuntut pencerapan ‘puitis’). Jika dua lapisan pertama berurusan dengan komunikasi dan pertandaan, lapisan ketiga ini (sekalipun baca-tafsir terhadapnya masih samar-samar) berurusan dengan signifiance, suatu istilah yang berurusan dengan wilayah penanda (bukan pertandaan) dan ada kaitannya dengan semiotika teks.
Roland Barthes fokus pada makna kedua (pertandaan/signification) dan makna ketiga (signifiance). Maknanya ‘terlalu berlimpah’ tidak terserap dengan baik oleh pikiran (intellection), makna menghilang dengan cepat, licin, dan susah ditangkap, disebut juga dengan makna yang tumpul (obtuse meaning). Makna yang bersifat suplementer. Kata obtuse sendiri berarti sesuatu yang dibuat tumpul, informasi yang kabur. Obtuse meaning melempar kita pada wilayah ketakberhinggaan makna. Bisa
23 diartikan dengan bahasa peyoratif: bisa meluas ke wilayah selain budaya, pengetahuan, atau informasi. Namun, bisa juga sebaliknya, justru hal-hal yang remeh.19 Akan tetapi, makna yang remeh-temeh, tak berarti, sumbang, pastiche tersebut sebagai makna yang tumpul merupakan suatu karnaval atau perayaan makna.
Untuk menguraikan makna simbolis ini dilanjutkan dengan mencari makna filmis yang secara lengkap akan dijabarkan pada bab 3. Makna ketiga ini akan dibantu dengan teori psikoanalisa Lacanian dengan meminjam konsep objek a sebagai filmis.
6.2 Melankolia dalam Narasi Pascakolonial
Secara estetis, situasi sosial politik dapat berpengaruh pada naratologi sebuah film. Kerangka teori ini saya anggap mampu menguraikan bagaimana cara kerja estetika film yang tumbuh dan berkembang di dalam dinamika perubahan tradisi budaya (populer) di Indonesia. Selain itu, kerangka teori ini penjembatan untuk mengenali karakteristik estetis sebuah film genre (Islam) yang terbentuk dari dinamika sosial masyarakat Indonesia yang selain pasca-Orde Baru, juga pascakolonial. Teori ini digunakan untuk menarasikan pengalaman orang-orang yang pernah bersinggungan dengan Islam, Barat, dan kolonial.
Dalam artikelnya “Mourning and Melancholia” (1917e[1915]), Freud menjelaskan mengenai proses depresi yang dialami oleh manusia. Yaitu depresi dalam ruang lingkup kehilangan (loss). Freud membedakan pengalaman kehilangan dalam dua hal, mourning (ratapan) dan melancholia (kemurungan). Mourning dan melankolia merupakan reaksi orang terhadap pengalaman kehilangan, baik kehilangan sesuatu (objek) ataupun kehilangan sesuatu yang bersifat abstrak; negara/kota/desa/tanah
24 kelahiran, kemerdekaan, ideologi, cita-cita, dan sebagainya.20 Freud menghubungkannya dengan subjek neurosis dan narcissistic neurosis. Bahwa subjek
neurosis dilandasi dengan pengalaman kehilangan (lost), akan tetapi melankolia sendiri
berada di ranah narcissistic21.
Meski sama-sama menyoal kehilangan, mourning dan melankolia mempunyai perbedaan. Freud menjelaskan bahwa melankolia adalah kondisi kejiwaan diterpa kehilangan akan sesuatu (objek) yang mengakibatkan seseorang merasa kehilangan kepercayaan diri, ketertarikan akan dunia luar, semangat hidup hingga tak bisa beraktivitas seperti biasa.22 Akibatnya, orang terus mengandaikan/membayangkan objek yang hilang. Dalam melankolia, objek yang hilang tak bisa lepas begitu saja. Objek tersebut berada di ruang unconscious dan muncul sebagai ego. Bagi Freud, melankolia adalah penyangga (absorb) ego itu sendiri.23 Subjek tak bisa melepaskan objek tersebut, karena jika ia melepaskannya, ego akan terlepas. Ego sendiri adalah hasil dialektika dari id (hati nurani/keinginan) dan super-ego (norma yang memengaruhi/tatanan sosial/hukum adat atau agama). Ego adalah apa yang berhasil keluar dari menekan id karena super-ego sehingga membuat seseorang mengalami lack (terbelah). Dalam istilah Lacan, disebut juga split subjek (subjek yang terbelah). Istilah lack (pada Lacan) sama dengan lost (Freud).
Dalam teori psikoanalisa Lacan, ego muncul di ruang simbolik. Objek kehilangan ini muncul dalam bahasa (simbolik), terekspresi dalam simptom (jejak-jejak/residu/penanda). Simptom akan muncul secara berulang/intens, biasanya muncul
20Di dalam artikel Sigmund Freud “Mourning and Melancholia” (1917e[1915]) di buku buku Leticia Glocer Fiorni, dkk. On Freud’s “Mourning and Melancholia”. London: KARNAC, 2009. Hal 19. 21Dalam pengantar buku Leticia Glocer Fiorni, dkk, On Freud’s “Mourning and
Melancholia”.London: KARNAC, 2009. Hal 5.
22Ibid. Hal 20. 23Ibid, hal 22.
25 dalam mimpi, slip of the tongue, bungle action, dan lainnya. Objek a disebut juga sebagai objek yang hilang (the loss object). Objek a selalu bersentuhan dengan imajiner (liyan) dan simbolik. Objek a muncul sebagai sesuatu yang terlarang, namun dipatuhi dan mengalami kenikmatan (jouissance). Akan tetapi hanya berupa jouissance parsial, kenikmatan yang masih di dalam koridor ‘hukum’.
Identifikasi atas simptom merupakan fenomena patologis. Simptom sebagai jawaban atas lack yang dimiliki subjek. Untuk itu melankolia sendiri bersifat patologis (trauma/sakit), yang berarti seseorang gagal melakukan perkabungan/gagal meratap (mourning).
Mourning adalah kondisi kejiwaan di mana seseorang berhasil berkabung
sehingga bisa menyelesaikan hubungannya dengan apa yang hilang. Mourning dianggap sebagai proses kehilangan yang normal. Orang yang mengalami mourning berhasil mengatasi kehilangan karena paham akan kehilangannya. Sedangkan dalam melankolia, orang tak pernah selesai dengan kehilangannya. Bahkan orang bisa saja tidak menyadari akan kehilangannya sendiri, yaitu kehilangan akan kehilangan.
Konsep melankolia tak hanya bisa melihat proses kehilangan yang dialami oleh satu orang saja. Melankolia dapat menjelaskan situasi masyarakat yang lebih luas. Dengan ini kita bisa melihat depresi yang dialami oleh masyarakat (patologis masyarakat). Baik yang sedang berlangsung maupun yang sudah berlalu. Sebagai contoh, kita melihat sebagian besar rakyat Indonesia masih merindukan ‘kembalinya’, merindukan kehadiran Sang Ayah (Orde Baru), Soeharto. Di film ini, kita bisa membaca melankolia sebagian masyarakat Indonesia. Masyarakat yang direpresentasikan adalah masyarakat Muslim kelas menengah Indonesia yang pascakolonial dan pasca-Orde Baru.
26 Dari hal ini, kita bisa melihat jenis atau pengalaman kemurungan dan kehilangan seperti apa yang selalu muncul dalam film tersebut. Bagaimana pengalaman kehilangan tersebut dibicarakan dan menjadi hasrat yang membangkitkan gairah film. Sehingga kita bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi personal dalam relasi sosial di hadapan relasi kuasa global.
Melankolia dalam virtual diungkapkan oleh Gilles Deleuze. Jon Roffe dalam “Notes on a Deleuzean Theory of Melancholia: Object, Cinema, World” mengatakan bahwa bagi Deleuze untuk melihat melankolia di dalam film, kita harus menemukan objek penyebab hasrat (the object-cause of desire) yang berkelindan di dalam sistem kerja sinema.24 Deleuze menyebutnya sebagai objek a virtual. Pengertian objek a Deleuze meminjam pengertian psikoanalisa Lacan, yaitu berupa lack atau loss. Deleuze menyebut objek a virtual sebagai “a shred [lambeau] of the pure past”25 atau
residu/jejak/potongan murni dari pengalaman masa lalu. Deleuze mengatakan “Objects
a do not act - they give the subsject’s their raison d’etre by virtue of their irreducible insistence”, bahwa objek a bukan bahasa visual/aksi/adegan, tetapi sesuatu yang
menjadi alasan dasar/dorongan utama menggerakkan laku dari subjek di dalam film. Meminjam teori Kant soal subjektivitas dan psikoanalisa (Lacan), Deleuze menyimpulkan bahwa objek a virtual adalah objek parsial.26 Objek a tersebut berasal dari hasrat sosial yang menyejarah, seperti dikutip Roffe dari Deleuze “every investment
is social and in any case bears upon a socio-historical field”.27 Deleuze menempatkan
hal ini dalam masyarakat kapitalis, yaitu sebagai masyarakat yang
24John Roffe. “Notes on a Deleuzean Theory of Melancholia: Object, Cinema, World” dalam Crisis &
Critique volume 3/issue 2;
25Ibid. Hal 149. 26Ibid. Hal 150. 27Ibid. Hal 151.
27 sakit/traumatis/patologis akibat struktur sosial politik. Masyarakat seperti ini turut membentuk struktur subjektivitas.
Kita bisa melihat hal-hal patologis dari masyarakat pascakolonial seperti Indonesia melalui kacamata melankolia di atas. Dalam film ini berkaitan erat dengan citra Islam dan bagaimana Islam ditempatkan dalam relasi Barat-Timur. Dalam studi pascakolonial, Barat-Timur tak hanya soal pembagian wilayah (belahan dunia), namun berhubungan dengan kacamata Barat menginterpretasi Timur (Islam). Di dalam kajian orientalisme, Barat selalu dipertentangkan dengan Timur. Barat adalah Kristiani dan Timur adalah Islam. Pertentangan ini berlangsung terus-menerus seperti yang sudah disampaikan Edward W. Said.28 Barat-Islam berkembang menjadi dikotomi konseptual-ideologis sehingga tidak bisa dilepaskan begitu saja.29 Arti Barat yang Kristiani bisa meluas menjadi Barat yang non-Muslim, bahkan ateis. Seiring berjalannya waktu, wacana kolonial ini justru seringkali dipakai begitu saja oleh yang Timur. Wacana ini juga yang banyak digunakan oleh empat film ini dalam memandang Barat dan Islam.
7. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian, analisis tekstual film dan analisis naratif atas wacana pascakolonial. Pertama, analisis tekstual film akan membedah film form melalui sistem narasi (narration) yaitu struktur pembentuk narasi film. Bertujuan untuk melihat sejauh mana teks film dipengaruhi oleh semua struktur (di dalam tubuh film itu sendiri). Struktur formal membentuk film menjadi kesatuan yang bisa dimaknai. Analisis narasi formal inilah yang kemudian bisa digunakan untuk
28Edward W. Said. Orientalisme: Menggugat Hegemoni Barat dan Menundukkan Timur sebagai
Subjek.Yogyakara: Pustaka Pelajar, 2010
29Dr. Komaruddin Hidayat di dalam kata pengantar buku Hassan Hanafi, Oksidentalisme: Sikap Kita
28 memaknai/menginterpretasi wacana film. Narasi dalam film dibedah dengan tiga tingkat makna Roland Barthes.
Kedua, penelitian ini memakai analisis subjek melankolia yang berhubungan dengan subjek narasi pascakolonial dengan pendekatan-pendekatan yang telah dijabarkan pada kerangka teori di atas. Ada pun data primer dari penelitian ini adalah film-film Islam pasca-Orde Baru yang berlatar luar negeri dengan isu ‘kosmopolitan’. Terdapat empat judul film utama yang akan diteliti, di antaranya Ayat-Ayat Cinta, 99
Cahaya di Langit Eropa part 1-2, Haji Backpacker, dan Assalamualaikum Beijing.
Empat film ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari film sekualnya. Seperti sekual
Ayat-Ayat Cinta kedua dan sekual 99 Cahaya di Langit Eropa berjudul Bulan Terbelah di Langit Amerika 1 dan 2. Sekual film ini akan dipakai sebagai pelengkap
maupun pembanding untuk mendukung data primer penelitian ini.
Data sekunder dibutuhkan dalam penelitian ini. Terdiri dari kajian wacana dan historis yang berkaitan erat dengan topik penelitian. Beserta sejumlah film yang terhubung sebagai pembanding dan pelengkap untuk menjelaskan fenomena penelitian ini.
8. Sistematika Penulisan
Penulisan hasil penelitian ini terdiri dari empat bab. Bab pertama adalah Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tema Penelitian, Relevansi Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Kerangka Teoretis, serta Metodologi Penelitian. Latar Belakang ditulis berdasarkan pengalaman saya melihat dan mewakili historis perkembangan kelas menengah Islam di Indonesia dari sudut pandang
29 yang lebih personal. Pengalaman ini saya tuliskan di latar belakang karena beririsan dengan fenomena penelitian ini.
Bab kedua merupakan data penelitian. Menjelaskan beberapa bagian, pertama, sejarah singkat kemunculan film Islam berbasis isu kosmopolitan. Kedua, deskripsi objek penelitian dan info relevan yang berhubungan erat antara objek penelitian dengan tema penelitian. Ketiga, fenomena yang muncul dalam film-film tersebut melalui makna tingkat pertama, Roland Barthes.
Bab ketiga adalah analisis secara tekstual film melalui makna kedua dan makna tingkat ketiga Roland Barthes. Membedah makna simbolik dan filmis film ini dengan meminjam kacamata psikoanalisa Lacan. Dilanjutkan dengan analisis narasi Muslim melankolik dengan pendekatan subjek pascakolonial dan membandingkannya dengan bab sebelumnya.
Bab keempat adalah penutup. Bab ini menjelaskan jawaban topik permasalahan tesis berikut masukan dan refleksi terhadap penelitian selanjutnya.
30
Bab II
Film Islam: Kemunculan, Wacana, dan Fenomena
Pendahuluan
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembahasan tesis ini menyoal perkembangan film bertema Islam yang mulai marak setelah keruntuhan pemerintahan Orde Baru. Khususnya film bertema Islam yang berlatar luar negeri. Bab ini menjadi pengantar latar belakang situasi sosial politik kelahiran dan perkembangan tematik film ini. Bagian ini berguna khususnya sebagai konteks pembahasan analisis wacana lanjut di bab ketiga. Pembahasan bab ini terlebih dahulu akan mendudukkan permasalahan terminologi mengenai pemahaman istilah film religi, film Islam, film Islami, dan film dakwah.
Banyak perdebatan mengenai pemakaian istilah ini, termasuk klaim mana film yang paling Islami dan yang bukan. Seperti perdebatan Usmar Ismail dan Asrul Sani serta antara Kang Abik dan Hanung Bramantyo (ketika memproduksi film Ayat-Ayat
Cinta).30 Begitu juga dengan perdebatan antara Hanum Salsabiela Rais dan Film Hijab (2014). Paparan narasi alasan berjilbab dan tidak dalam film Hijab (Hanung Bramantyo, 2014) menuai kritik tajam dari sebagian besar sineas film Islam. Film Hijab dianggap tidak mewakili ‘Islam’ yang sebenarnya. Narasi film Hijab dianggap hanyalah 1% saja dari ‘wajah Muslim’ di Indonesia.31 Kritik tajam yang diterima film Hijab menegaskan
30Ariel Heriyanto (2015).
31https://www.facebook.com/hanumsalsabiela/posts/10153075179644198?comment_tracking=%7B%
22tn%22%3A%22O%22%7D&pnref=story# diunggah Januari 2015
Komentar Hanum Rais (Produser film 99 Cahaya di Langit Eropa) di akun Facebook miliknya mengatakan:
“…rakitan-rakitan adegan yang menunjukkan kemunafikan orang mengaku Islam begitu
ditonjolkan di sini, tanpa memberi ruang pada 99 persen Muslim kebalikannya. Film ini, (yang akhirnya saya baru tahu ya elah sutradaranya orang JIL) pada akhirnya hanya ingin
31 adanya dominasi wacana keislaman tertentu yang dianggap ‘benar’ atau ‘syari’. Ada dua hal penting dari kejadian ini, pertama, persoalan dominasi model keislaman tertentu dalam sebuah film yang dianggap Islami dan tidak Islami. Kedua, persoalan pengulangan atau repetisi terhadap film-film yang mendominasi wacana keislaman yang dianggap Islami tadi. Jika kita bandingkan secara keseluruhan dalam aspek narasi dan bahasa sinematik terhadap film bernuansa Islam yang dianggap lebih syari dan tidak, apakah ada perbedaan yang mencolok atau tidak?
Dalam bab kedua penting menguraikan perkembangan film Islam populer dan tema Muslim kelas menengah kosmopolitan yang sering diulang oleh film (Islam) Indonesia saat ini. Apa yang melandasi perkembangan isu-isu kosmopolitan yang sering dibawa oleh identitas Muslim kelas menengah saat ini. Perkembangan isu tersebut kita bedah lebih jauh dari empat film yang menjadi objek penelitian ini; Ayat-Ayat Cinta, 99
Cahaya di Langit Eropa, Haji Backpacker, dan Assalamualaikum Beijing. Tema apa
saja yang sering muncul dalam film-film tersebut. Dengan mengambil objek penelitian empat film sekaligus, tentu penting untuk menelaah benang merah film yang menjadikannya layak untuk diteliti lebih jauh. Penjelasan informatif mengenai data formal film dibantu oleh landasan makna tingkat pertama Roland Barthes sebagai landasan yang lebih empiris bagi analisis selanjutnya.
meneguhkan kembali ‘I am a Moslem, but I hate Islam, I just want to capitalize Islam for
making money’. Bukan film yang rekomen ditonton, kecuali Anda ingin membuat hater Islam
semakin kaya raya.31
Komentar Hanum yang punya banyak penggemar setelah film yang diproduserinya sukses di bioskop, berhasil membuat banyak orang urung menonton. Komentar Hanum dikutip dan disebar oleh banyak media online. Entah ada korelasi signifikan dengan komentar Hanum, Hijab memang sepi penonton meski telah menggandeng Din Syamsudin untuk menonton dan mengomentari Hijab.
32 A. Film Religi, Dakwah atau Film Islam?
Situasi politik pada setiap era pemerintahan di Indonesia turut memengaruhi wajah perfilman Indonesia.32 Wajah perfilman Indonesia erat kaitannya dengan politik pemerintah terhadap Islam. Baik Islam sebagai agama maupun sebagai basis ideologis kendaraan politik. Film sebagai bagian dari kerja-kerja kebudayaan berada di antara situasi politik tersebut.
Ada beberapa istilah yang lazim untuk menyebut genre film yang menjadikan agama sebagai tema utama, yaitu film religi, film dakwah, dan film Islam. Film religi memiliki tema yang lebih luas. Ia tak hanya membicarakan salah satu simbol keagamaan saja. Film religi menyangkut keimanan dan makna religiusitas yang lebih luas. Hariyadi mengutip dari Wright mengenai karakteristik film religi adalah:
They have plots that draw upon religion; they are set in the context of religious communities; they use religion for character definition; they deal directly or indirectly with religious characters, texts, or locations; they use religious ideas to explore experiences, transformations, or conversions of characters; they address religious themes and concerns.33
Dari ciri-ciri yang disebutkan Wright tersebut kita bisa mengambil contoh film religi yang populer di masyarakat seperti The Passion of the Christ (Mel Gibson, 2004) atau Soegija (Garin Nugroho, 2012). Film Islam dengan sendirinya masuk dalam kategori film religi. Film Islam menjadi genre tersendiri karena begitu masif dan populer kehadirannya setelah Orde Baru tumbang.34
Perkembangan wacana mengenai film Islam lahir dalam berbagai bentuk situasi politik zamannya. Istilah film Islam bukan sama sekali baru di Indonesia. Sebelumnya, pada pemerintahan Soekarno, film Islam dan film dakwah dipakai secara bergantian.
32Khrishna Sen. Kuasa Dalam Sinema: Negara, Masyarakat dan Sinema Orde Baru. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009
33Hariyadi.,hal 207.
34Alicia Izharuddin. Gender and Islam in Indonesian Cinema.Singapura: Springer Nature, 2017. Hal 32-33.