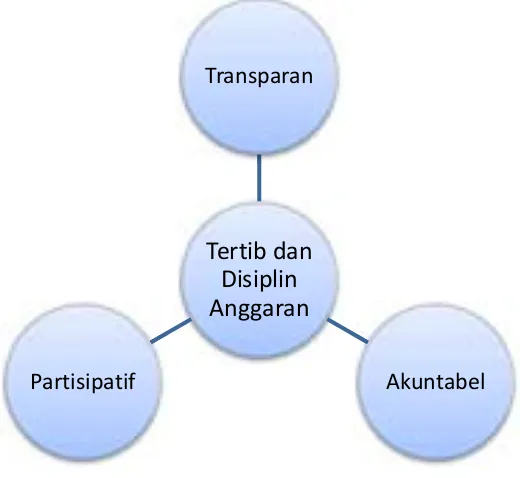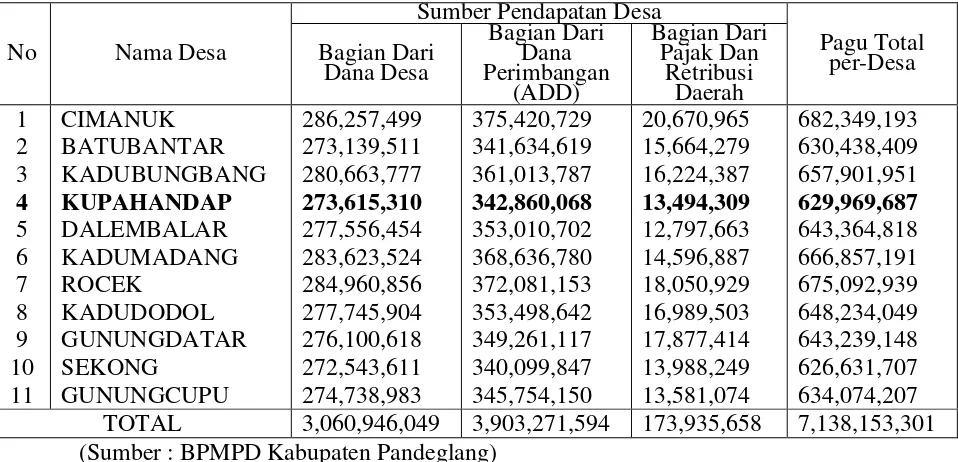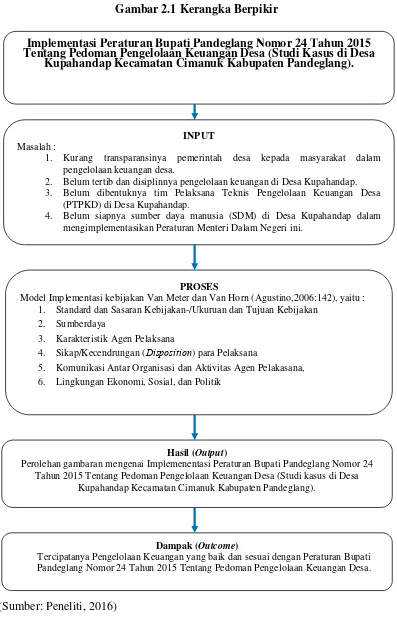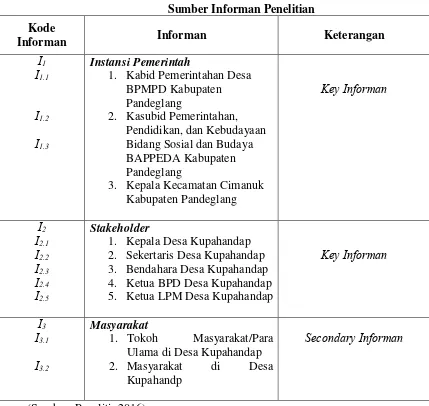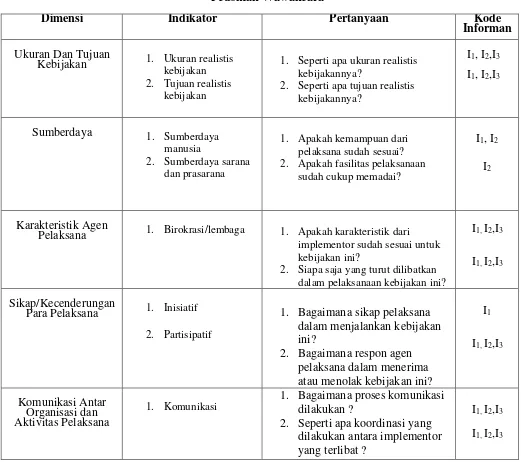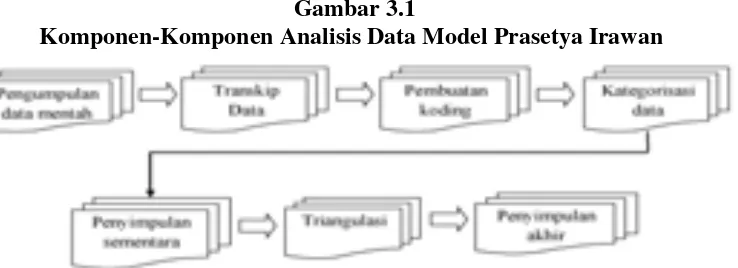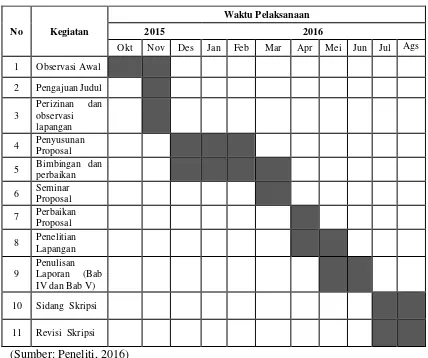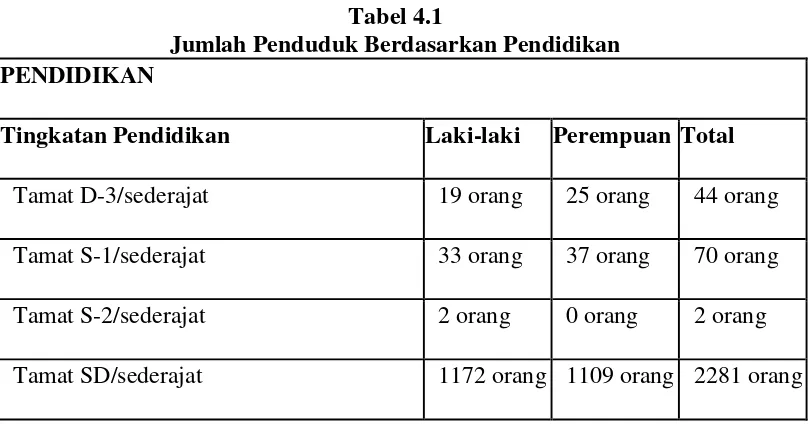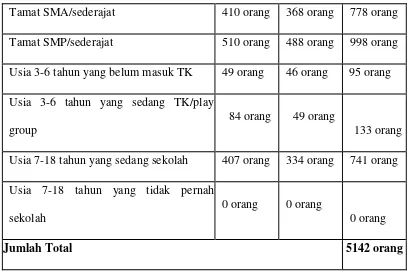(Studi Kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk
Kabupaten Pandeglang)
SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh: DIDI SURYADI NIM. 6661120118
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Kasus di Desa Kupahandap). Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dosen Pembimbing I: Abdul Hamid, Ph,D dan Pembimbing II: Listyaningsih, S.Sos., M.Si.
Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya transparansi pengelolaan keuangan di desa, belum tertib dan disiplinnya pengelolaan keuangan di desa, dan belum siapnya SDM di Desa Kupahandap dalam menjalankan Peraturan Bupati ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasusu di Desa Kupahandap). Informan penelitian ini adalah Kepala Desa, perangkatnya dan tokoh masyarakat. Teori yang digunakan adalah Van Metter Van Horn dengan metode deskriptif, pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data menggunakan triangulasi dan member check. Hasil menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang ini di Desa Kupahandap sudah baik namun ada beberapa hambatan seperti pegawai di desa kesulitan menjalankan peraturan ini, komunikasi dan koordinasi antar pelaksana kebijakan belum optimal. Saran penelitian adalah segera memberikan pelatihan kepada perangkat desa dan memperbaiki proses komunikasi dan koordinasi antar pelaksana.
ABSTRACT
Didi Suryadi.6661120118. Implementation of Pandeglang Regent Regulation No 24 of 2015 on Rural Financial Management Guidelines. (Case Study in Kupahandap Village) Study Program of Public Administration. Faculty of
Social Science and Political. Supervisor I: Abdul Hamid, Ph.D and Supervisor
II: Listyaningsih, S.Sos., M.Si.
Background of the research was lack of transparency of rural financial management in Kupa handap Village unpreparedness of human resources of Kupahandap Village in running of Regent Regulation No. 24 of 2015 on Rural Financial Management Guidelines (Case Study in Kupa Handap Village). Informant of the research was Head of Village, Staff and community figure. The research used theory of Van Metter Van Hom with descriptive method qualitative approach. Technique of collecting data was interview, observation and documentation. In testing validity of the data, the researcher used triangulation and member check. The result showed that the Implementation of Pandeglang Regent Regulation No 24 of 2015 on Rural Financial Management Guidelines in Kupahandap Village was running well, but there were some obstacles such as the staff village had difficulty in running this regulation, communication and coordination among the stakeholders has not optimal yet. Suggestion of the research was to give training to the village staff as soon as possible and improving the communicaton and coordinaton process among the stakeholders.
Sebuah Cita-cita Juga Beban,
Jika Itu Hanya Angan-angan.
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan
Hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini
penulis buat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa
Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang)”.
Hasil penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak
pihak yang selalu mendukung penulis baik secara moril maupun materil. Maka
dengan ketulusan hati dan dalam kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan
terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan
bimbingan dan bantuan sehingga penulisan proposal skripsi ini dapat terselesaikan
dengan baik. Ucapan dan rasa hormat serta terima kasih penulis tujukan kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Ibu Rahmawati, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Bapak Iman Nurokhman, S.Ikom., M.Ikom selaku Wakil Dekan II Fakultas
5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
sekaligus Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk
melakukan bimbingan dan memberikan masukan dalam setiap bimbingan
yang dilakukan selama ini.
7. Bapak Riswanda, Ph.D selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Bapak Abdul Hamid, Ph.D selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan
waktunya untuk melakukan bimbingan dan memberikan masukan dalam
setiap bimbingan yang dilakukan selama ini.
9. Bapak Rd.Goenara Darajat, S.Sos. M.Si, Kepala Bidang Pemerintahan Desa
BPMPD Kabupaten Pandeglang.
10.Bapak Guruh Safaat, S.Sos., M.Si., Kasubid Pemerintahan, Pendidikan dan
Kebudayaan Bidang Sosial dan Budaya BAPPEDA Kabupaten Pandeglang.
11.Bapak Djuanda, S.H. Sekertaris Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang.
12.Bapak H. Zainuddin, Kepala Desa Kupahandap.
13.Perangkat Desa dan Segenap Masyrakat Desa Kupahandap.
14.Untuk Keluarga saya yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan
serta doa yang selalu mengiringi tiap langkah saya dalam menyelesaikan
iii
15.Untuk sahabatku dari semester satu Adventure FC (Restu Ramadhan, Fahmy
Kurnia Eka Saputra, Didi Rosadi, M. Dodo Widarda, Pangku Shillazid, Abdul
Haris Djiwandono, Damar Aji Nusantara, M. Rafli Maulid, Pradytia
Herlyansah) yang selalu memberi dukungan kepada saya.
16.Teman-teman KKM 39 Desa Tonjong yang selalu memberikan dukungan
kepada saya.
17.Dan tidak lupa Teman-teman Administrasi Negara Angkatan 2012 yang selalu
berjuang bersama-sama serta saling mendukung satu sama lain dalam
mengerjakan tugas akhir.
Akhirnya penulis tak berhenti mengucapkan syukur kepada Allah SWT,
karena atas ridho-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis
menyadari banyak ditemukan kekurangan dalam penyajian materi. Oleh karen itu
penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut. Penulis mengharapkan
masukan, baik kritik maupun saran dari pembaca yang membangun.
Serang, Agustus 2016 Penulis
iv
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL LEMBAR PENGESAHAN
PERNYATAAN ORISINALITAS LEMBAR PERSETUJUAN KATA PERSEMBAHAN ABSTRAK
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... iv
DAFTAR TABEL ... vii
DAFTAR GAMBAR ... viii
DAFTAR LAMPIRAN ... ix
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1Latar Belakang Masalah ... 1
1.2Identifikasi Masalah ... 13
1.3Batasan Masalah... 13
1.4Rumusan Masalah ... 13
1.5Tujuan Penelitian ... 14
1.6Manfaat Penelitian ... 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 15
v
2.1.1 Definisi Kebijakan Publik ... 16
2.1.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik ... 19
2.1.3 Model-Model Implementasi Publik ... 20
2.1.4 Otonomi Desa ... 27
2.1.5 Otonomi Daerah ... 28
2.1.6 Definisi Desa ... 28
2.1.7 Pengertian Keuangan Desa ... 29
2.1.8 Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa ... 29
2.2Penelitian Terdahulu ... 32
2.3Kerangka Berfikir... 33
2.4Asumsi Dasar ... 37
BAB III METODE PENELITIAN ... 38
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian ... 38
3.2 Fokus Penelitian ... 39
3.3 Lokasi Penelitian ... 39
3.4 Fenomena yang Diamati... 40
3.4.1 Definisi Konsep ... 40
3.4.2 Definisi Operasional ... 41
3.5 Instrumen Penelitian ... 42
3.6 Informan Penelitian ... 43
3.7 Teknik Pengumpulan Data ... 45
3.8 Analisis Data ... 48
3.9 Uji Keabsahan Data ... 50
BAB IV PEMBAHASAN ... 53
4.1 Deskripsi Objek Penelitian ... 53
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang ... 53
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Cimanuk ... 54
4.1.3 Gambaran Umum Desa Kupahandap ... 55
4.2 Deskripsi Data ... 60
4.2.1 Informan Penelitian ... 64
4.2.2 Pelaksanaan Perbup di Desa Kupahandap ... 66
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian ... 69
4.4 Pembahasan ... 89
BAB V PENUTUP ... 99
5.1Kesimpulan... 99
5.2Saran ... 100
vii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Desa ... 5
Tabel 1.2 Perhitungan Pendapatan Desa Kecamatan Cimanuk ... 9
Tabel 3.1 Sumber Informan Penelitian ... 44
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara ... 47
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian... 52
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan ... 56
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ... 57
Tabel 4.3 Struktur Organisasi Desa Kupahandap ... 59
Tabel 4.4 Inventaris Barang di Desa Kupahandap ... 60
Tabel 4.5 Informan Penelitian ... 65
viii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa ... 7
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir ... 36
ix
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Lampiran 2 Member Check
Lampiran 3 Transkip Data Penelitian
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia sebagai sebuah negara dibangun di atas dan dari desa. Dan desa
adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama,
desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial
masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara bernama Indonesia
ini. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata
oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama
pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan. Istilah desa
disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat di
setiap daerah otonom di Indonesia. Setelah UUD 1945 diamandemen, istilah desa
tidak lagi disebut secara eksplisit.
Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara
Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum
perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih
kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” (Desa Otonom) dan “Volksgemeenschappen” (Desa Adat), seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di
Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu
mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang
daerah-2
daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai
daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu,
keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan
hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keberagaman karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan nama
lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini
untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari
bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara
Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap
keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak tradisionalnya.
Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya
mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan
tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”.
Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan
pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas
melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
undang-undang”.
Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan
tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965
tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya
Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang-Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan
susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki
kekayaan dan aset. oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan
desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan
perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di
Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang
4
diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan
kepala desa serta proses pembangunan desa.
Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus
komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2014 Tentang Desa, diberikan kewenangan yang mencakup, kewenangan
berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal bersekala desa, kewenangan yang
ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari
pelaksanaan otonomi desa adalah tersediannya dana yang cukup, sebab
pembiayaan atau keuangan merupakan faktor terpenting dalam mendukung
penyelenggaraan otonomi di desa. Sejalan dengan hal ini, di dalam
Undang-undang desa yang terbaru yaitu Undang-Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan kucuran dana sebesar
10% dari APBN, dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantar,
dana tersebut akan langsung sampai kepada desa.
Berdasarkan simulasi, jumlah APBN tahun 2014 dibagi dengan jumlah desa
di seluruh Indonesia, secara merata setiap desa akan memperoleh alokasi dana
desa dari APBN sekitar 850 juta. Dana tersebut bila ditambah dengan alokasi dana
desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bantuan keuangan maka
Persoalan krusial yang dihadapi oleh Pemerintahan desa adalah bagaimana
mengelola dana sebesar itu secara efektif, efisien dan akuntabel, sehingga dengan
demikian kemajuan masyarakat desa yang diharapkan dengan kehadiran
Undang-undang tersebut dapat diwujudkan. Dalam kaitannya membantu desa dalam
pengelolaan keuangan desanya, pada tahun 2014 Pemerintah memberikan
petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan di desa melalui Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Tabel 1.1
Sumber Pendapatan Desa
APBN 1. Bagian Dari Dana Desa
APBD 1. Bagian Dari Dana Perimbangan (ADD)
2. Bagian Dari Pajak Dan Retribusi Daerah
(sumber : BPMPD Kabupaten Pandeglang 2015)
Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang
telah melaksanakan Undang-Undang Desa terbaru. Melalui dua Peraturan Bupati
(Perbup) yaitu, yang pertama Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 42 Tahun 2015
Tentang Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015
Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang
menjadikan syarat pencairan dana desa dari pusat ke daerah. Dengan demikian
setiap desa yang ada di Kabupaten Pandeglang wajib berpedoman kepada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa dalam menjalankan atau mengelola keuangan desa yang ada di
6
Terkait akan hal tersebut, dalam membantu desa untuk melakukan
pengelolaan keuangan dengan baik diperlukan standar yang dapat dijadikan acuan
dalam menjalankan pengelolaan keuangan di desa. Dalam kaitannya membantu
desa dalam pengelolaan keuangan desa, dengan menimbang berdasarkan pada
ketentuan pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta ketentuan pasal 105 Peraturan daerah
Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, pada tahun 2015 pemerintah Kabupaten Pandeglang
memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24
Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Bab
VIII, Bagian Kesatu, Pasal 71 Ayat 1, keuangan desa adalah semua hak dan
kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
desa. Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara
sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang
Keuangan Negara. Dalam penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa
pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi
objek, subjek, proses dan tujuan.
Adapun dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di jelaskan bahwa pengelolaan keuangan
desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
peraturan ini juga dijelaskan asas pengelolaan keuangan desa, adapun asas-asas pengelolaan keuangan tersebut yaitu, transparan, partisipatif, akuntabel serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Gambar 1.1
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa
(sumber : Peraturan Bupati Pandeglang No.24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa)
Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Pandeglang terdiri atas 35 Kecamatan dengan 13 Kelurahan dan 326 Desa. Adapun total dana desa yang di peroleh Kabupaten Pandeglang tahun 2015 sebesar Rp.91,602,411,000. (sumber : BPMPD Kabupaten Pandeglang). Dana tersebut dibagi atas 326 Desa yang ada di Kabupaten Pandeglang dengan perhitungan 90% dibagi rata per desa dan 10% dibagi secara proporsional dengan
Tertib dan Disiplin Anggaran
Transparan
8
memperhitungkan, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kemiskinan serta
kesulitan letak geografis.
Dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang
Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, peneliti
mengambil lokus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten
Pandeglang Provinsi Banten. Adapun faktor yang menjadi latar belakang peneliti
mengambil lokus di Desa Kupahandap, karena menurut Bapak Gunara (Kabid
Pemerintahan Desa BPMPD Kabupaten Pandeglang) dalam wawancara peneliti
pada Lima Januari 2016 mengenai prestasi yang diperoleh oleh Desa Kupahandap,
beliau mengatakan bahwa Kecamatan Cimanuk merupakan kecamatan yang
paling baik dalam pelaporan administrasi keuangan di desa-desanya di Kabupaten
Pandeglang khususnya Desa Kupahandap. Menurut beliau Desa Kupahandap
dalam kurun waktu kisaran tahun 2008 desa tersebut masuk ke dalam Desa
Tertinggal (DT), namun dengan penggantian Kepala Desa yang baru pada tahun
tersebut yang memiliki kemampuan lebih dari Kepala Desa sebelumnya mampu
membawa perubahan yang sangat pesat baik itu dalam segi pemerintahan desa,
keamanana serta kebersihan di desa tersebut. Puncaknya Desa Kupahandap
meraih predikat desa terbaik se-Kabupaten Pandeglang di tahun 2011 serta
mendapatkan predikat ke-2 terbaik dalam perlombaan P2WKSS se-Provinsi
Banten.
Adapun besaran sumber pendapatan dana desa yang diperoleh oleh Desa
Tabel 1.2
PENGHITUNGAN SUMBER PENDAPATAN DESA KECAMATAN CIMANUK KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2015
No Nama Desa
TOTAL 3,060,946,049 3,903,271,594 173,935,658 7,138,153,301
(Sumber : BPMPD Kabupaten Pandeglang)
Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada Januari 2016 di
Desa Kupahandap. Dalam pelaksanaan Pengimplementasian Peraturan Bupati
Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa di Desa Kupahandap ditemukan beberapa permasalahan. Adapun
permasalahan tersebut akan peneliti uraikan sebagai berikut: Pertama, masalah
transparansi terhadap masyarakat dalam pengelolaan keuangan desanya. Hal ini
dapat dilihat dari hasil observasi awal peneliti pada bulan Januari 2016 di Desa
Kupahandap, peneliti tidak menemukan papan pengumuman laporan keuangan
atau laporan realisasi anggaran setiap tahun di kantor desa maupun di sekitar
wilayah Desa Kupahandap. Padahal jelas dikatakan dalam Peraturan Bupati
10
Desa pasal 37 ayat 1 yang berbunyi, Laporan realisasi dan laporan
pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara
tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini
akan mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan
terhadap desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa sehingga dapat
memberikan celah atau ruang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan
keuangan di desa. Hal ini membuktikan bahwa salah salah satu asas pengelolaan
keuangan desa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24
Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu asas transparan
belum dilakukan di Desa Kupahandap.
Kedua, belum tertib dan disiplin pengelolaan keuangannya di Desa Kupahandap. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti
pada observasi awal bulan Januari 2016 dengan Bendahara Desa Kupahandap
yang mengatakan bahwa di Desa Kupahandap dalam penatausahaan penerimaan
dan pengeluaran masih menggunakan buku biasa dan masih di gabungkan
keduanya. Hal ini tidak sejalan dengan amanat yang terkandung dalam Peraturan
Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, dimana dikatakan dalam peraturan tersebut bahwa bendahara
desa wajib menggunakan buku kas umum dan buku kas harian pembantu dalam
penatausahaan penerimaan dan pengeluaran pengelolaan keuangan di desa. Hal ini
juga membuktikan bahwa salah salah satu asas pengelolaan keuangan desa yang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu asas tertib dan disiplin anggaran
belum dilakukan di Desa Kupahandap.
Ketiga, belum dibentuknya tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) di Desa Kupahandap oleh Kepala Desa Kupahandap sehingga
dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Peraturan Bupati Pandeglang ini,
dimana melihat akan peran pentingnya tim PTPKD di desa dalam membantu
Kepala Desa mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangannya di desa sesuai
amanat yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pandeglang tersebut.
Keempat, mengenai Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Desa Kupahandap baik itu perangkat desa dan masyarakatnya dalam
mengimplementasikan Peraturan Bupati Pandeglang ini. Dalam Peraturan Bupati
Pandeglang ini di jelaskan asas-asas tentang pengelolaan keuangan desa
diantaranya, transparan, partisipatif, akuntabel serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran. Untuk menunjang agar asas-asas tersebut dapat di terapkan di
dalam pengelolaan keuangan desa di suatu desa harus ditunjang dengan sumber
daya manusia yang memadai, dalam hal ini yaitu kemampuan Kepala Desa dan
semua perangkat yang ada di desa harus memiliki kemampuan yang bisa
membantu berjalannya pengimplementasian Peraturan Bupati Pandeglang ini
berjalan dengan baik serta kemampuan masyarakat yang harus bisa menjadi peran
pengwasan atau kontroling bagi perangkat desa dalam menjalankan Peraturan
Bupati Pandeglang ini agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan
12
Namun kondisi yang ada di Desa Kupahandap keadaan sumberdaya
manusianya baik itu dari perangkat desa dan masyrakat yang ada di desanya
belum bisa dikatakan mampu menjalankan Peraturan Bupati Pandeglang ini, hal
ini dapat dilihat dari belum sepenuhnya asas-asas pengelolaan keuangan desa
dilakukan di Desa Kupahandap terutama asas transparansi serta tertib dan disiplin
anggaran. Hal ini dapat diasumsikan bahwa sumberdaya manusia yang ada di
Desa Kupahandap baik perangkatnya maupun masyarakatnya selaku pelaku
implementor kebiajkan Peraturan Bupati Pandeglang ini belum siap dalam
menjalankan kebijakan tersebut. Hal ini juga akan mengakibatkan terjadinya
kegagalan dalam Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun
2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ini.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai “Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti
mengidentifikasi masalah sebagai berikut:
1. Kurang transparansinya pemerintah desa kepada masyarakat dalam
pengelolaan keuangan desa.
2. Belum tertib dan disiplinnya pengelolaan keuangan di Desa
Kupahandap.
3. Belum dibentuknya tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
(PTPKD) di Desa Kupahandap.
4. Belum siapnya sumber daya manusia (SDM) di Desa Kupahandap
dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Pandeglang ini.
1.3 Batasan Masalah
Peneliti hanya membatasi penelitian ini pada bagaimana Implementasi
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Kupahandap Kecamatan
Cimanuk Kabupaten Pandeglang).
1.4 Rumusan Masalah
Merujuk pada batasan masalah di atas, maka perumusan masalah dari
penelitian ini yakni, “Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang
Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi
14
1.5 Tujuan Penelitian
Tanpa adanya tujuan penelitian, maka seorang peneliti tentunya akan
mengalami kesulitan dalam melakukan penelitian. Sesuai dengan latar belakang
dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui
bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Kupahandap
Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang).
1.6 Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:
a. Secara Teoritis
Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan
dan pengetahuan karena akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan
dalam dunia akademisi khususnya Ilmu Admnistrasi Negara, terutama
yang berkaitan dengan kinerja aparatur pemerintah. Selain itu,
penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk pengembangan studi
administrasi negara.
b. Secara Praktis
Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat mengembangakan kemampuan dan
penguasaan ilmu-ilmu yang pernah diperoleh peneliti selama mengikuti
pendidikan di Program Studi Ilmu Admnistrasi Negara Universitas Sultan Ageng
15
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
Teori menurut Kerlinger dalam (Sugiyono,2012:41) mengemukakan
bahwa:
“Theory is a set of interrelated construct (concepts), definitions, and proposition that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variabels, with purpose of explaining and predicting the phenomena.”
Teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi dan proposisi yang
berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan
antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan
fenomena.
William Wiersm dalam (Sugiyono,2012:41) menyatakan bahwa:
“A theory is a generalization or series of generalization by which we attempt to explain some phenomena in a systematic manner.”
Selain itu, teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat
digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Cooper dan
Schindler dalam (Sugiyono,2012:41) menyatakan bahwa:
“A theory is a set of systematically interrelated concepts, definition, and proposition that are advanced to explain and predict phenomena (fact).”
Teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun
secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan
16
teori merupakan seperangkat konsep dan definisi untuk menganalisis suatu
fenomena secara sistematik dan holistik.Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti
menggunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk
itu pada bab ini peneliti menggunakan beberapa teori yang relevan dengan
permasalahan dalam penelitian ini. Teori dalam ilmu administrasi mempunyai
peranan yang sama seperti ilmu-ilmu lainnya, yaitu berfungsi untuk menjelaskan
dan menjadi panduan dalam peneliatian.
Penggunaan teori dalam penelitian akan memberikan acuan bagi peneliti
dalam melakukan analisis terhadap masalah sehingga dapat menyusun pertanyaan
dengan rinci untuk penyelidikan sehingga memperoleh temuan lapangan yang
menjadi jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, pada bab
ini peneliti akan menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian, antara lain :
2.1.1 Definisi Kebijakan Publik
Kebijakan publik pada dasarnya terdiri dari dua kata yaitu kebijakan
dan publik. Secara etimologis istilah policy (kebijakan) berasal dari bahasa
Yunani, Sansakerta dan Latin. Akar kata policy dalam bahasa Yunani dan
Sansakerta yaitu polis (negara-kota) dan pur (kota), yang kemudian
dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (negara) dan pada
akhirnya dalam Bahasa Inggris pertengahan policie, yang berarti menangani
masalah-masalah publik atau administrasi dalam (Dunn, 2005:51).
Pengertian lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh Carl Friedrech
“Kebijakan adalah serangkaian tindakan kegiatan yang diusulkan oleh
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan
dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam
mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.
Adapun pengertian publik dalam rangkaian kata publik policy
memiliki tiga konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum dalam
(Abidin,2012:7). Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek, dan
lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subjek, kebijakan publik adalah
kebijakan dari pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan adalah “what
government do or not to do”. Kebijakan dari pemerintahlah yang dapat dianggap sebagai kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai kewenangan
yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhinya.
Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan sementara bahwa
kebijakan publik ialah serangkaian tindakan kegiatan yang diusulkan oleh
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam menyelesaikan
masalah-masalah orang banyak.
Pengertian lain diutarakan oleh ahli seperti Thomas R Dye mengenai
kebijakan publik. Menurut Thomas R Dye dalam (Agustino,2006:7)
“kebijakan publik adalah apa yang dipilih pemerintah untuk di kerjakan atau tidak dikerjakan”. Beradasarkan pengertian Thomas R Dye ini, baik apapun
yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan itu
adalahsuatu kebijakan publik.
Definisi lain diutarakan oleh James E Anderson. Menurut James E
18
yang ditetapkan oleh badan-badan pemerintah dan aparat pemerintah”.
Berdasarkan pengertian yang di ungkapkan oleh James E Anderson ini
kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh
pejabat atau badan pemerintah dalam bidang teretentu seperti bidang
pendidikan, politik,ekonomi, pertanian, industry, dan pertahanan.
Adapun pengertian lain mengenai kebijakan publik ditawarkan oleh
seorang pakar dari Perancis, Limeux. Menurut Limeux dalam
(Wahab,2012:15) kebijakan publik ialah :
“Produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah publik yang dilakukakan oleh actor-aktor politik yang sehubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu
berlangsung sepanjang waktu”.
Berdasarkan pengertian tersebut menjelaskan kebijakan publik itu
serangkaian aktivitaas guna memecahkan masalah publik yang dilakukan
oleh aktor-aktor politik yaitu pejabat negara.
Seorang pakar dari Nigeria Chief J.O. Udoji memberikan pengertian
mengenai kebijakan publik. Menurut Chief J.O Udoji dalam
(Wahab,2012:15) mengatakan bahwa kebijakan publik ialah “suatu tindakan
bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan
dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat”.
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan
publik adalah suatu tindakan yang diputuskan oleh pemerintah maupun
badan-badan pemerintah yang berisi sanksi dan bertujuan untuk
memecahkan masalah publik serta mempengaruhi sebagaian besar
2.1.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik
Impelementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting
dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah
merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan
bermasyarakat. Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat oleh
pemerintah, baik yang dirumuskan dengan meggunakan tenaga ahli dari laur
negeri, tetapi kemudian tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam
kehidupan negara tersebut karena tidak mampu atau tidak dilakasanakan.
Implementasi kebijakan merupakan tahap kelanjutan dari formulasi
kebijakan dan kemudian disahkan. Dalam praktiknya menurut Leo Agustino
dalam (2006:138) “implementasi merupakan suatu proses yang begitu
kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi
sebagai kepentingan”.
Implementasi kebijakan sendiri menurut Van Meter dan Van Horn
dalam (Agustino,2006:139), di definisikan, sebagai :
“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah
digariskandalam keputusan kebijaksanaan”
Adapun pengertian lain berikan oleh Daniel Mazmanian dan Paul
Sabatier. Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam
(Agustino,2006:129) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai:
“Pelaksanaan Keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk
20
yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau
mengatur proses im-plementasinya”.
Sedangkan menurut kamus Webster dalam (Wahab,2012:139)
meumuskan bahwa :
“istilah to implement (mengimplementasikan) itu berarti to provide
the means for carrying out (menydiakan sarana untuk melaksanakan
sesuatu), to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat
terhadap sesuatu)”.
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan
menyangkut 3 hal, yaitu (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan: (2)
adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan: (3) adanya hasil kegiatan.
Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dipaparkan di atas dapat
disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan
pelaksanakan kebijakan guna memecahkan masalah yang dihadapi dan
mendapatkan hasil yang ingin dicapai.
2.1.3 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik
Dalam studi kebijakan publik terdapat, terdapat bebrapa model
implementasi kebiajakan publik yang dikemukakan oleh ahli yang melihat
variable-varabel apa saja yang dapat memepengaruhi kinerja implementasi
suatu kebijakan publik. Adapun ahli tersebut ialah Van Meter dan Van
Horn, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, George Edward III, dan
Marilee S. Grindle.
Menurut Model Implementasi kebijakan yang diutarakan Van Meter
dan Van Horn dalam (Agustino,2006:142) terdapat 6 variabel yang dapat
1. Standard dan Sasaran Kebijakan/Ukuruan dan Tujuan Kebijakan.
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat
keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realiistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksanaan kebijakan.
2. Sumberdaya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memenfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia, waktu dan sumberadaya financial merupakan bentuk sumberdaya tersebut.
3. Karakteristik Agen Pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting banyak dipengarahi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya
4. Sikap/Kecendrungan (Disposition) para Pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Agen Pelakasana
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam
implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya keslahan-kesalah akan sangat kecil untuk terjadi.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.
Kondisi Ekonomi, social dan politik yang kondusif akan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Begitupun sebaliknya.
Sedangankan Menurut Model Implementasi Kebijakan yang di
utarakan Mazmanian dan Paul Sabatier dalam (Subarsono,2005:94)
terdapat 3 variabel yangdapat mempengaruhi kinerja impelementasi
kebijakan publik, yaitu :
1. Karakteristik dari Masalah
a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
Di satu pihak ada beberapa masalah social secarateknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan air minum bagi penduduk atau harga beras tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat masalah-masalah social yang relatif sulit dipecahkan.
b. Tingkat kemeajemukan dari kelompok sasaran.
Ini berarti bahwa suatu program akan relative mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen.
22
Sebuah program akan sulit diimpelementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Begitupun sebaliknya.
d. Cakupan perubahan perilak yang di harapkan.
Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relative lebih mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan unutk mngubah sikap dan perilaku masyarakat.
2. Karakteristik Kebijakan
a. Kejelasan isi kebijakan
Ini berarti semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan akan mudah diiplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakannya.
b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
Kebijakan yang memiliki dasarteoritis memiliki sifat lebih mantau karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan social tertentu perlu ada modifikasi.
c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.
Sumber daya keuangan adalahfaktor krusial untuk setiap program sosial.
d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai
institusi pelaksana.
Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikaldan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
e. Kejelasan dan konsistensi aturan yangadapada badan pelaksana.
f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
Rendahnya komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program dapat menyebabkan gagal suatu kebijakan diimplementasikan.
g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi
dalam implementasi kebijakan.
Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akanrelatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat.
3. Variabel Lingkungan
a. Kondisi social ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relative mudah menerima program-program pembaharuan disbanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program.
b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.
Kebijakan yang berpihakterhadap publik tentunya
akanmendapat dukungan yang lebih banyak di bandingkan kebijakan yang tidak berpihak pada publik.
Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat memepengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara lain, (1) kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untukmengubah keputusan (2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsun melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana.
d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.
Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.
Adapun menurut Model Impelementasi Kebijakan yang diberikan oleh
George C. Edward III dalam (Agustino,2006:149) terdapat 4 variabel yang
mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu ;
1. Komunikasi
Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Eward III, adalah komunikasi. Komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.
Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:
a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat
menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebagiankan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan
(street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu
komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
24
Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:
a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf.
Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam meng-implementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua
bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar
perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan ke-lompoknya.
d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam
implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
3. Disposisi
a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan
untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendukung yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.
4. Struktur Birokrasi
Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.
Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan Standar Operating Prosedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau
pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya peyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktiuvitas pegawai diantara beberapa unit kerja.
Dan menurut Model Impelemntasi Kebijakan yang di berikan oleh
Marielee S. Grindle dalam (Agustino,2006:154) terdapat 2 varibel besar
yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik , yaitu :
1. Content of Policy, meliputi :
26
kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
b. Type of benefit
Pada poin ini content of policy berupaya untuk menunjukkan
atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
c. Extent of change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai) Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Pada poin ini ingin dijelaskan bahwa seberapa berapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
d. Site of Decision Making
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
e. Program Implementer
Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus di dukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.
f. Resource Commited
Pelaksanaan suatu kebijakan harus di dukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaan-nya berjalan dengan baik.
2. Context Of Policy, meliputi :
a. Power, Interest, and Strategy of Actor involved
Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau keuaaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaansuatu implementasi kebijakan.
b. Institusion and Regime Charateristic
Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
c. Compliance and Responsiveness
2.1.4 Otonomi Desa
Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada
pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan
desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang
menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan
pengaturannya kepada desa.
Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada
kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh
karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam
penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai
tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa
dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi
desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan
kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang
dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku .
Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18
kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
28
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut
Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa
meliputi; kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala
Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain
yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau
Pemerintah.
2.1.5 Otonomi Daerah
Pengertian otonomi daerah secara etimologi yaitu, Istilah otonomi
berasal dari bahasa Yunani yang berarti auto dan nomous. Auto berarti
sendiri, dan nomus berarti hukum atau peraturan. Jadi pengertian otonomi
daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri. Secara umum
pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi
Daerah).
2.1.6 Definisi Desa
Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat
politik dan pemerintahan di indonesia jauh sebelum negara bangsa ini
terbentuk. Struktur sejenis desa, masyarakat adat dan sebagainya telah
menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa
hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukan dengan
tingkat keragaman yang tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa, mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau
yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
2.1.7 Pengertian Keuangan Desa
Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dalam
Bab VIII, Bagian Kesatu, Pasal 71 Ayat 1, keuangan desa adalah semua hak
dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik
berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban desa.
Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan
negara sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
Tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan Undang-undang tersebut
dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan
keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan.
2.1.8 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,
30
desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal satu
Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember.
A. Transparan
Menurut Nordiawan dalam (Sujarweni,2015:28) transparan
memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak
untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan
perundang-undangan. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau
kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan,
proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
B. Akuntabel
Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu
tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola
tersebut adalah akuntabilitas. Sabeni dan Ghozali dalam
(Sujarweni,2015:28) menyatakan “Akuntabilitas atau
pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu bentuk
keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin
bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilakasankan
sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui
(Sujarweni,2015:28) mengatakan “Akuntabilitas publik adalah
kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala
aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada
pihak pemberi amanah (Principal) yang memiliki hak dan kewenangan
untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Menurut Nordiawan
dalam (Sujarweni,2015:28) akuntabilitas adalah
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik
adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh
lapisan masyarakat secara terbuka.
C. Partisipatif
Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada
desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap
pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh
pemerintahan desa di mana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat
dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung
32
2.2 Penelitian Terdahulu
Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti akan
memaparkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.
Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut yakni:
Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Agus Subroto
dalam Tesisnya yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi
Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan
Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)”. Dalam penelitian tersebut,
ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah.
Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi di sini
memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama
untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan
masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.
Kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban
publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan,
penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan
dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya
memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk
menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran
tersebut.Ketiga, prinsip value for money. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga
pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi
berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan
masyarakat tersebut dapat menghasilkan ouput yang maksimal (berdaya guna).
Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai
target-target atau tujuan kepentingan publik.
Dalam penelitian tersebut akuntabilitas sistem pengelolaan ADD
dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance). Prinsip atau kaidah-kaidah good governance adalah
adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan.Pengelolaan ADD sebagai bagian dari
pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh
prinsip-prinsip yang merupakan indikator goodgovernance tersebut.
Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Agus Subroto dengan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti memfokuskan penelitian
pada Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan Agus Subroto hanya
memfokuskan penelitiannya pada akuntabilitas pengelolaan ADD nya saja untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
2.3 Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir merupakan alur berpikir peneliti dalam menjelaskan
permasalahan penelitian. Penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati
Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa (Studi Kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten
34
Van Meter dan Van Horn (Agustino,2006:142). Terdapat enam variabel yang
dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu :
1. Standard dan Sasaran Kebijakan/Ukuruan dan Tujuan Kebijakan.
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat
keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan
memang realiistis dengan sosio-kultur yang mengada di level
pelaksanaan kebijakan.
2. Sumberdaya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung
dari kemampuan memenfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia,
waktu dan sumberadaya financial merupakan bentuk sumberdaya
tersebut.
3. Karakteristik Agen Pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi
formal dan informal yang akan terlibat pengimplementasian
kebijakan publik. Hal ini sangat penting banyak dipengarahi oleh
ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya
4. Sikap/Kecendrungan (Disposition) para Pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan
sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja
implementasi kebijakan publik.
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam
implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi
diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi,
maka asumsinya keslahan-kesalah akan sangat kecil untuk terjadi.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.
Kondisi Ekonomi, social dan politik yang kondusif akan sangat
mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
36
Adapun kerangka berpikir peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
(Sumber: Peneliti, 2016)
Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa
Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang).
INPUT Masalah :
1. Kurang transparansinya pemerintah desa kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Belum tertib dan disiplinnya pengelolaan keuangan di Desa Kupahandap. 3. Belum dibentuknya tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
(PTPKD) di Desa Kupahandap.
4. Belum siapnya sumber daya manusia (SDM) di Desa Kupahandap dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.
PROSES
Model Implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (Agustino,2006:142), yaitu : 1. Standard dan Sasaran Kebijakan-/Ukuruan dan Tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap/Kecendrungan (Disposition) para Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Agen Pelakasana, 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Hasil (Output)
Perolehan gambaran mengenai Implemenentasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus di Desa
Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang).
Dampak (Outcome)