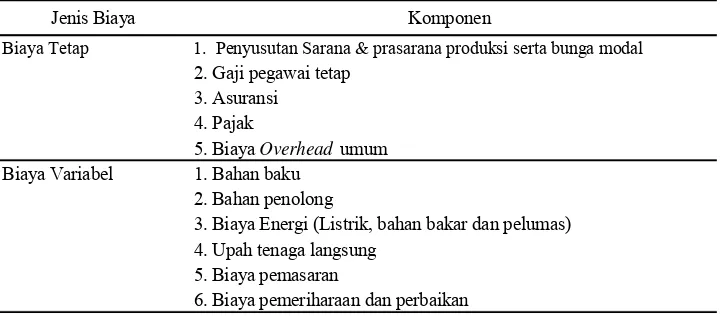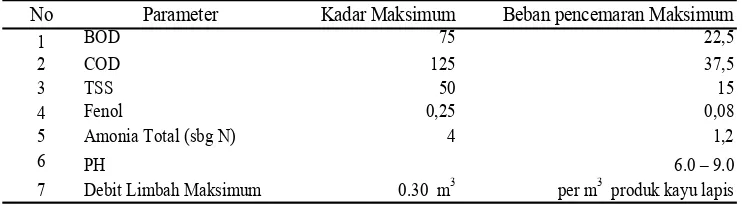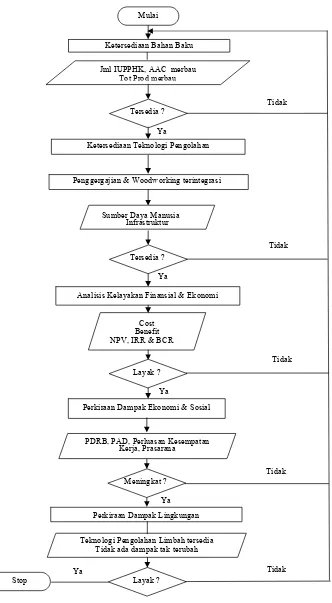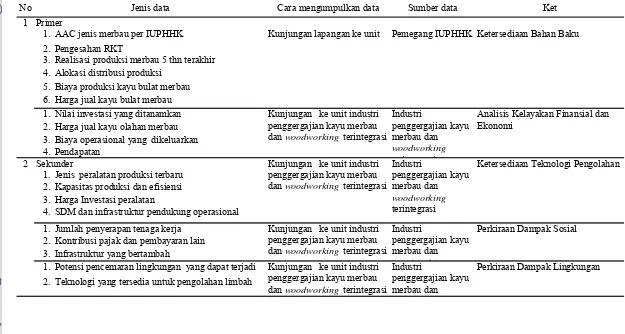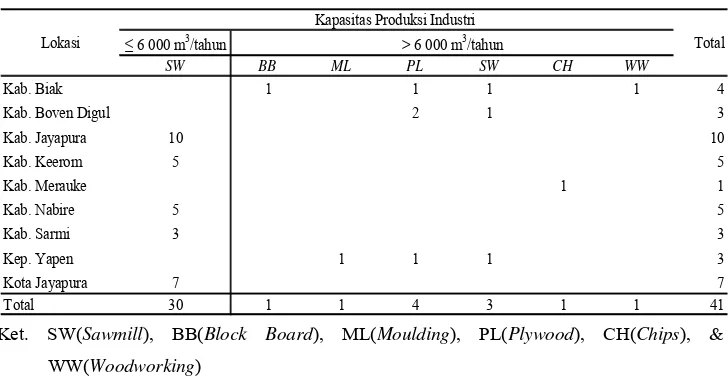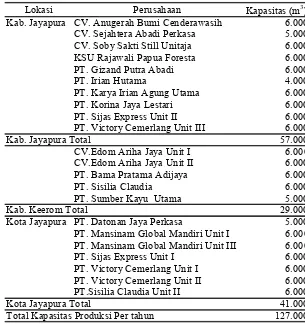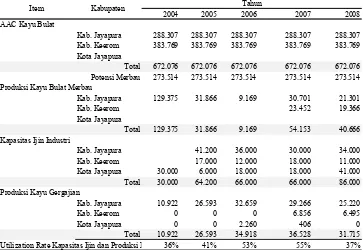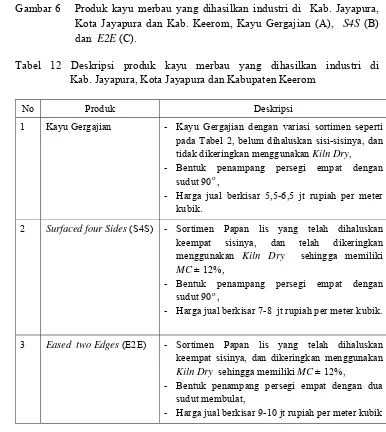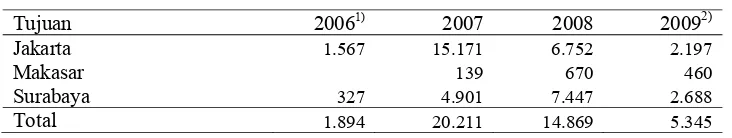ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL DAN EKONOMI
PERUSAHAAN KAYU GERGAJIAN MERBAU DAN
WOODWORKING TERINTEGRASI DI PAPUA
(STUDI KASUS DI KAB. JAYAPURA, KOTA JAYAPURA
DAN KAB. KEEROM)
GERALD TUA NADEAK
SEKOLAH PASCA SARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
ii
PERNYATAAN MENGENAI TESIS
DAN SUMBER INFORMASI
Dengan ini saya menyatakan, bahwa tesis Analisis Kelayakan Finansial dan Ekonomi Perusahaan Kayu Gergajian Merbau dan Woodworking terintegrasi di Papua (Studi Kasus di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom) merupakan karya saya dengan dibimbing oleh Komisi Pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada Perguruan Tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.
Bogor, November 2009
iii
ABSTRACT
GERALD TUA NADEAK. A Financial and Economic Feasibility Study of an
Integrated Merbau Woodworking and Sawmill in Papua (Case Study in The
Jayapura District, The Jayapura City and The Keerom District). Under
supervision of Bintang C.H. Simangunsong and E.G. Togu Manurung.
To follow up log export and intraseluler trade ban policy issued by Papua province Government, a Financial and Economic feasibility study of an integrated Merbau woodworking and sawmill was conducted. Two scenarios were proposed: an integrated Merbau Woodworking and Sawmill that produces only E2E (Scenario 1) and an integrated Merbau Woodworking and Sawmill that produces E2E, finger-joint and mosaic (Scenario 2). A raw material and technology availability as well as a financial feasibility were then investigated for each scenario. The results show that both scenarios are financially feasible as indicating by NPV of 23.5 billions rupiah, IRR of 31% and BCR of 1.10, for Scenario 1; and NPV of 50 billions rupiah, IRR of 47% and BCR of 1.19, for Scenario 2. Scenario 2 was than chosen because of all financial criteria are better than in scenario 1. An economic feasibility as well as a social and environment impacts of chosen scenario was studied. A economic feasibility for scenario 2 shows that NPV was 155.4 billion rupiah, IRR 93.15% and BCR 1,4. More over, scenario 2 would also create 112 jobs and contribute of 7.5 billion rupiah per year to regional government.
iv
RINGKASAN
GERALD TUA NADEAK . Analisis Kelayakan Finansial dan Ekonomi Perusahaan Kayu Gergajian Merbau dan Woodworking terintegrasi di Papua (Studi Kasus di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom). Dibimbing oleh BINTANG C.H. SIMANGUNSONG dan E.G. TOGU MANURUNG.
Sebagian besar wilayah Papua merupakan kawasan hutan dengan total luas kawasan hutan Provinsi Papua dan Papua Barat adalah 31 juta hektar yang terbagi atas kawasan konservasi (44,8%) dan kawasan hutan produksi (52,6%), sedangkan
sisanya (2,6%) berupa Areal Penggunaan Lain (APL) (Dishut Papua, 2007). Hutan Papua telah dimanfaatkan sebagai sumber kayu bulat untuk memasok
kebutuhan industri perkayuan di Papua maupun di luar Papua. Potensi masak tebang kayu merbau di alam rata-rata sebesar 19,69 m3 per hektar (Tokede et al.,2006).
Pemerintah Daerah menilai kegiatan eksploitasi kayu bulat untuk dijual keluar Papua tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan bahkan dianggap sebagai proses pemiskinan dan pembodohan rakyat Papua selaku pemilik sumber daya. Oleh karena alasan tersebut, pada tanggal 22
Desember 2008, Gubernur Provinsi Papua menetapkan Peraturan Daerah Khusus
Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua yang mana pada pasal 52 ayat 1 menyatakan bahwa kayu bulat dan hasil hutan lainnya wajib diolah di Provinsi Papua untuk optimalisasi industri kehutanan, meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, menambah peluang usaha, meningkatkan pengetahuan dan teknologi.
Tujuannya adalah untuk mendorong pengembangan industri pengolahan kayu di Tanah Papua, sehingga sumber daya hutan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Di lain pihak, larangan ini telah menyebabkan Industri woodworking di Jawa Timur yang umumnya menggunakan kayu bulat dari Papua mengalami kelesuan.
Dua skenario perusahaan berdasarkan kombinasi produk akhir kemudian dikaji kelayakannya; Skenario 1, perusahaan penggergajian kayu merbau dan woodworking terintegrasi dengan hanya satu jenis output produk E2E dengan rendemen produksi 45% dan Skenario 2, perusahaan penggergajian kayu merbau dan woodworking terintegrasi dengan output produk E2E ditambah produk sampingan Fingerjoint dan Mosaic dengan rendemen produksi 60%.
Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua skenario perusahaan Penggergajian kayu merbau dan woodworking terintegrasi layak secara finansial untuk dikembangkan di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom. Skenario 1 memberikan nilai NPV Rp 23,5 milyar, IRR 31,4%, BCR 1,10 dan Skenario 2 memberikan NPV Rp 50 milyar, IRR 47,11% dan BCR 1,19. Skenario 2 merupakan skenario yang lebih baik dari pada skenario 1 karena seluruh kriteria kelayakannya lebih baik dari pada skenario 1. Hasil analisis kelayakan ekonomi terhadap skenario 2 juga menunjukkan bahwa skenario 2 layak secara ekonomi karena memberikan NPV sebesar Rp 155,4 milyar, IRR 93,15 % dan BCR 1,44. Lebih lanjut skenario 2 akan menyerap tenaga kerja sejumlah l12 orang dengan kontribusi terhadap pendapatan pemerintah berupa pembayaran pajak sebesar Rp 7,5 milyar per tahun.
v
© Hak cipta milik IPB, tahun 2009
Hak cipta dilindungi
vi
ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL DAN EKONOMI
PERUSAHAAN KAYU GERGAJIAN MERBAU DAN
WOODWORKING TERINTEGRASI DI PAPUA
(STUDI KASUS DI KAB. JAYAPURA, KOTA JAYAPURA
DAN KAB. KEEROM)
GERALD TUA NADEAK
Tesis
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada
Departemen Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan
SEKOLAH PASCA SARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
vii
Judul Tesis : Analisis Kelayakan Finasial dan Ekonomi Perusahaan Kayu
Gergajian Merbau dan Woodworking Terintegrasi di Papua. (Studi Kasus di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Kabupaten
Keerom).
Nama : Gerald Tua Nadeak
NRP : E 251 070 051
Disetujui,
Komisi Pembimbing
Ir. Bintang C. H. Simangunsong, MS, Ph.D. Ketua
Ir. E.G. Togu Manurung, MS, Ph.D. Anggota
Diketahui,
Ketua Mayor
Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan
DR. Ir. Dede Hermawan, MSc
Dekan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
Prof. DR. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS
viii
PRAKATA
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa di Surga atas segala Berkat dan Anugerah-Nya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Tesis ini berjudul Analisis Kelayakan Finasial dan Ekonomi Perusahaan Kayu Gergajian Merbau dan Woodworking Terintegrasi di Papua. (Studi Kasus di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom).
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ir. Bintang C.H.
Simangunsong, MS, Ph.D dan Bapak Ir. E.G. Togu Manurung, MS, Ph.D selaku komisi pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan dalam
penyusunan tesis ini, dan kepada Bapak Dr. Ir. Bambang Sukmananto, M.Sc selaku Penguji Luar Komisi yang juga telah memberikan banyak masukan. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Departemen Kehutanan yang telah memberikan beasiswa kepada penulis selama melaksanakan studi dan juga kepada Institut Pertanian Bogor yang telah menyediakan sarana prasarana untuk penulis dapat menimba ilmu. Di samping itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada
Bpk Ir. Marthen Kayoi, MM, Bpk. Ir. T. Batubara, MSi, Bpk. Ir. L. Tokan, Bpk. Ir. Setiadi, dan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data
penelitian.
Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada orang tua, istri, anak, kerabat, rekan-rekan angkatan 2007 THH IPB dan seluruh keluarga, atas segala bantuan dan doanya.
Semoga tesis ini bermanfaat.
ix
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Manokwari-Papua pada tanggal 1 Februari 1976 dari pasangan (Alm.) M.R. Nadeak dan R. br. Parhusip. Penulis adalah anak kedua dari enam
bersaudara. Tahun 1993 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Manokwari dan melanjutkan studi ke Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Cenderawasih-Manokwari, Papua. Penulis meraih gelar Sarjana Kehutanan (S.Hut) pada tahun 1999. Pada tahun 2000, penulis diterima di Departemen Kehutanan, dan saat ini bekerja pada Balai
Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah XVII Jayapura. Atas
bantuan beasiswa dari Departemen Kehutanan, pada tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan ke Program Studi Ilmu dan Tehnologi Hasil Hutan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Selama menempuh studi, penulis telah mengkaji bidang-bidang ilmu yang terkait dengan ekonomi dan industri hasil hutan.
x
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI…... x
DAFTAR TABEL ………... xii
DAFTAR GAMBAR... xiv
DAFTAR LAMPIRAN………..……… xv
I. PENDAHULUAN ..………...……….. 1
1.1 Latar belakang ………..………..………. 1
1.2 Tujuan Penelitian ………. 3
1.3 Manfaat Penelitian ………..………. 3
II. TINJAUAN PUSTAKA……….………. 4
2.1 Kayu Merbau ………....……… 4
2.1.1 Risalah kayu Merbau ……….…………..….………. 4
2.1.2 Sifat dasar dan pengerjaan kayu merbau ..………..……. 7
2.1.3 Produk kayu merbau ………...…………..………..…… 7
2.2 Industri Hasil Hutan Kayu ………..……….……… 8
2.2.1 Penggergajian …….. ………….….………..………...…… 9
2.2.2 Woodworking ……….………..…….. 13
2.3 Studi Kelayakan Proyek .…………..……… 15
2.3.1 Tahapan Studi Kelayakan ..……… 16
2.3.2 Biaya, manfaat dan periode analisa …….……….. 16
2.3.3 Kelayakan Finansial dan Ekonomi ……….…………..……….. 18
III.METODOLOGI PENELITIAN ….………..….. 24
3.1 Waktu dan tempat ……….………..…. 24
3.2 Alur penelitian ..………...………..…. 24
3.3 Jenis dan sumber data ……….……….... 24
3.4 Analisis kelayakan …………..………. 24
IV.HASIL DAN PEMBAHASAN ………..………. 29
4.1 Hasil ………...……… 29
4.1.1 Kondisi Industri Perkayuan di Papua ……… 29
4.1.2 Kondisi Industri Woodworking di Surabaya-Jawa Timur ………… 38
4.1.3 Kelayakan Industri Penggergajian dan Woodworking terintegrasi di Kab. Jayapura, Kota Jayapura dan Kab. Keerom ...………… 42
4.2Pembahasan ……….……….. 55
4.2.1 Perkiraan Dampak Ekonomi dan Sosial ……… 57
xi
V. KESIMPULAN DAN SARAN ………... 62
6.1 Kesimpulan………. 62
6.2 Saran………. 62
DAFTAR PUSTAKA ….………. 64
xii
DAFTAR TABEL
Halaman
1 Potensi Kayu Merbau di beberapa kabupaten di Provinsi Papua ... 6
2 Sortimen Kayu Gergajian …………... 10
3 Perbandingan circular saw dan band saw ……….…….. 11
4 Perkembangan produksi dan nilai ekspor kayu gergajian Indonesia….. 12
5 Perkembangan volume produksi dan ekspor woodworking……….. 16
6 Jenis dan Komponen Biaya produksi ……….. 18
7 Baku mutu limbah cair untuk industri kayu lapis……… 23
8 Data analisis kelayakan……… 28
9 Penyebaran IUIPHHK di Propinsi Papua sampai dengan bulan Juni tahun 2009 ………... 29
10 Kapasitas produksi kayu gergajian per tahun IUIPHHK di Kab. Jayapura, Kota Jayapura dan Kab. Keerom………. 30
11 Kapasitas ijin dan Produksi kayu gergajian merbau Kab. Jayapura, Kota Jayapura dan Kab. Keerom ………. 31
12 Deskripsi produk kayu merbau yang dihasilkan industri di Kab. Jayapura, Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom ……… 33
13 Realisasi Pengiriman Kayu Olahan Merbau per tahun dari pelabuhan Jayapura ………... 34
14 Realisasi Pengiriman Kayu Olahan Merbau per tahun dari pelabuhan Jayapura berdasarkan jenis produk ……… 35
15 Luas areal konsesi IUPHHK berdasarkan redesign Dinas Kehutanan Provinsi Papua Tahun 2004 ……… 37
16 Deskripsi produk kayu merbau yang dihasilkan industri di Surabaya-Jawa Timur ……….. 41
17 Analisis rendemen pengolahan kayu merbau dengan menggunakan mesin utama multiripsaw……….. 47
18 Tabel Analisis biaya pengolahan kayu merbau dengan menggunakan mesin utama multiripsaw……….. 48
19 Analisis rendemen pengolahan kayu merbau output bandsaw dengan menggunakan Moulding………... 48
xiii
21 Hasil Analisis Kepekaan……….. 54
22 Hasil Analisis Ekonomi Industri penggergajian kayu merbau dan
woodworking terintegrasi Skenario I dan II ……….. 55
23 Aspek Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman industri
penggergajian kayu merbau dan woodorking terintegrasi di Kabupaten
Jayapura, Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom……… 56
xiv
DAFTAR GAMBAR
Halaman
1. Tekstur kayu dan daun Merbau …………... 4
2. Penyebaran Kayu Merbau di Papua …………... 5
3. Patung Asmat dan ornamen Asmat... 8
4. Kayu merbau sebagai deck, komponen tangga dan flooring…………. 8
5. Alur Penelitian Analisis kelayakan perusahaan penggergajian kayu merbau dan woodworking terintegrasi di Papua (Kab.Keerom, Kab.
Jayapura dan Kota Jayapura)………. 25
6. Produk kayu merbau yang dihasilkan industri di Kab. Jayapura, Kota
Jayapura dan Kab. Keerom, Kayu Gergajian , S4S dan E2E ………... 33
7. Histogram realisasi penerimaan kayu bulat Asal Papua dan Papua
Barat, 4 industri di Surabaya tahun 2007-2009………. 38
8. Histogram realisasi produksi kayu olahan industri pengolahan kayu di
Jawa Timur tahun 2004-2008 ………..……….. 39
9. Histogram realisasi penjualan kayu olahan industri pengolahan kayu di
Jawa Timur tahun 2004-2008 ………. 40
10.Produk akhir kayu merbau yang dihasilkan di Surabaya, Flooring
yang di Coating , Mozaic dan Fingerjoint ……… 40
11.Grafik realisasi penerimaan kayu bulat asal Papua dan Papua Barat di
Surabaya ….………..………...… 42
12.Penggergajian dengan menggunakan Multiripsaw dan menggunakan
Bandsaw ……….………. 45
13.Tebal bilah gergaji multiripsaw (A) dan bandsaw (B) diukur
menggunakan caliper……… 46
14.Grafik hubungan tebal keratan gergaji bandsaw dan circularsaw
dengan LRF……….. 46
15.Grafik volume ekspor woodworking Indonesia tahun 2004 sampai
dengan triwulan 3 tahun 2009………. 50
16.Grafik harga ekspor woodworking Indonesia tahun 2004 sampai
dengan triwulan 3 tahun 2009………. 50
17.Grafik kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
1. Realisasi Produksi KB Merbau Lingkup kerja Dinas Kehutanan Kota
Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom …………... 68
2. Realisasi Produksi KO Merbau IUIPHHK Lingkup kerja Dinas
Kehutanan Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten
Keerom …………... 69
3. Daftar IUIPHHK per tahun Lingkup kerja Dinas Kehutanan Kota
Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom ... 70
4. Daftar Pengiriman Kayu Olahan melalui Pelabuhan Jayapura (Des
2006-April 2009)………... 72
5. Daftar Penerimaan Kayu Bulat Provinsi Jawa Timur yang berasal dari
Provinsi Papua dan Papua Barat (Jan 2007- Apr 2009)………. 74
6. Realisasi Ekspor Produk Woodworking Indonesia tahun 2004-2009 77
7. Daftar peralatan, harga dan umur ekonomis untuk Industri
penggergajian kayu merbau dan woodworking terintegrasi Skenario I... 78
8. Rencana biaya investasi dan reinvestasi per tahun (Analisa Finansial
dengan produk akhir E2E)………..………. 79
9. Biaya pemeliharaan alat dan bangunan per tahun (Analisa Finansial
dengan produk akhir E2E)………...………. 81
10.Nilai penyusutan alat dan bangunan per tahun (Analisa Finansial
dengan produk akhir E2E)………..………. 83
11.Nilai bunga modal alat dan bangunan per tahun (Analisa Finansial
dengan produk akhir E2E)….………..……… 85
12.Daftar Rencana Volume dan Biaya kegiatan produksi (Analisa
Finansial dengan produk akhir E2E ) ………. 87
13.Jadwal Pembayaran Pinjaman (Analisa Finansial dengan produk akhir
E2E) ……….…. 89
14.Proyeksi Arus Kas (Analisa Finansial dengan produk akhir E2E) ……. 90
15.Proyeksi Laba Rugi (Analisa Finansial dengan produk akhir E2E)……. 92
16.Perhitungan IRR, NPV dan BCR (Analisa Finansial dengan produk
akhir E2E)………. ……….. 94
17.Daftar peralatan, harga dan umur ekonomis untuk Industri
penggergajian kayu merbau dan woodworking terintegrasi
xvi
18.Rencana biaya investasi dan reinvestasi per tahun (Analisa Finansial
dengan produk akhir E2E, Fingerjoint dan mosaic)…………..……… 96
19.Biaya pemeliharaan alat dan bangunan per tahun (Analisa Finansial
dengan produk akhir E2E, Fingerjoint dan mosaic)..……… 98
20.Nilai penyusutan alat dan bangunan per tahun (Analisa Finansial
dengan produk akhir E2E, Fingerjoint dan mosaic)….………. 100
21.Nilai bunga modal alat dan bangunan per tahun (Analisa Finansial
dengan produk akhir E2E, Fingerjoint dan mosaic)..………. 102
22.Daftar Rencana Volume dan Biaya kegiatan produksi (Analisa
Finansial dengan produk akhir E2E, Fingerjoint dan mosaic)…………. 104
23.Jadwal Pembayaran Pinjaman (Analisa Finansial dengan produk akhir
E2E, Fingerjoint dan mosaic) ……….. 106
24.Proyeksi Arus Kas (Analisa Finansial dengan produk akhir E2E,
Fingerjoint dan mosaic )………..……… 107
25.Proyeksi Laba Rugi (Analisa Finansial dengan produk akhir E2E,
Fingerjoint dan mosaic) ……….………. 109
26.Perhitungan IRR, NPV dan BCR (Analisa Finansial dengan produk
akhir E2E, Fingerjoint dan mosaic)……… 111
27.Proyeksi Arus Kas (Analisa Ekonomi dengan produk akhir E2E)..…… 112
28.Proyeksi Laba Rugi (Analisa Ekonomi dengan produk akhir E2E)..….. 114
29.Perhitungan IRR, NPV dan BCR (Analisa Ekonomi dengan produk
akhir E2E)…..……….. 116
30.Proyeksi Arus Kas (Analisa Ekonomi dengan produk akhir E2E,
Fingerjoint dan mosaic)………. 117
31.Proyeksi Laba Rugi (Analisa Ekonomi dengan produk akhir E2E,
Fingerjoint dan mosaic)……..………. 119
32.Perhitungan IRR, NPV dan BCR (Analisa Ekonomi dengan produk
xvii
1
I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Papua merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terletak di bagian paling timur gugusan kepulauan Nusantara.
Papua memiliki potensi kekayaan alam yang berlimpah berupa hutan yang luas
yang penuh dengan potensi hasil hutan kayu dan non kayu serta kekayaan
keanekaragaman hayati dan hasil tambang dalam kandungan tanah dibawahnya.
Total luas kawasan hutan Provinsi Papua dan Papua Barat adalah 31 juta hektar
yang terbagi atas kawasan konservasi (44,8%) dan kawasan hutan produksi
(52,6%), sedangkan sisanya (2,6%) berupa Areal Penggunaan Lain (APL).
Sampai dengan tahun 2007 untuk wilayah Provinsi Papua tercatat sebanyak
38 unit IUPHHK yang mengusahakan areal seluas 6,77 juta hektar (Dishut
Papua, 2007).
Produksi kayu bulat Provinsi Papua pada kurun waktu tahun 2002-2007
sebesar 2,84 juta m3 dengan produksi rata-rata per tahun sebesar 474 ribu m3
(Dishut Papua, 2007). Produksi tersebut telah mengisi kebutuhan bahan baku
bagi industri yang beroperasi di Papua maupun industri yang beroperasi di luar
Papua, bahkan untuk industri yang beroperasi di luar negeri. Tahun 2005, LSM
Telapak melaporkan bahwa sebanyak 300 ribu m3 kayu bulat merbau per bulan
diselundupkan ke luar negeri (Newman dan Lawson, 2005), meskipun pada
tahun 2001 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan melarang
ekspor kayu bulat.
Dengan produksi kayu bulat yang tinggi, pada kenyataannya kegiatan
eksploitasi kayu bulat dari hutan di Papua oleh Pemerintah Daerah dinilai tidak
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat
sekitar hutan. Bahkan lebih jauh Pemerintah Daerah menilai aktifitas ekstraksi
kayu bulat dari hutan Papua merupakan proses pemiskinan rakyat Papua selaku
pemilik Sumber Daya Alam (SDA) tersebut, dimana nilai yang didapatkan
masyarakat selaku pemilik proporsinya sangat kecil dan bahkan dinilai tidak ada
apa-apanya dibandingkan nilai yang diperoleh pedagang kayu, terlebih yang
2 SDA berupa produk kayu bulat menggambarkan suatu proses pembodohan,
karena penjualan dalam bentuk bahan baku seolah-olah menunjukkan bahwa
rakyat Papua tidak mampu untuk mengolah kayu bulat menjadi suatu produk
akhir yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi dengan mengembangkan
industri pengolahan kayu.
Oleh karena alasan tersebut, pada tanggal 22 Desember 2008, Gubernur
Provinsi Papua menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua yang mana pada pasal 52 ayat 1 menyatakan bahwa kayu bulat dan hasil hutan lainnya wajib diolah di Provinsi Papua untuk optimalisasi industri kehutanan, meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, menambah peluang usaha, meningkatkan pengetahuan dan teknologi.
Tujuan dikeluarkannya keputusan ini adalah untuk mendorong
pengembangan industri pengolahan kayu di Tanah Papua, sehingga SDA yang
ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan memberikan kontribusi yang
besar bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan potensi SDA berupa kayu
merbau yang selama ini dijadikan bahan baku oleh industri di luar Papua, maka
Papua pada saat ini memiliki peluang besar untuk mendapatkan nilai tambah
yang lebih besar dari kayu merbau dengan mendirikan industri pengolahan kayu
di Bumi Cenderawasih.
Newman dan Lawson (2005) menyatakan bahwa kayu merbau asal Papua
yang diseludupkan ke China telah mendorong berdirinya lebih dari 500 pabrik
lantai kayu (flooring) dan 200 penggergajian hanya dalam waktu lima tahun di
Kota Nanxun- satu kota yang terletak beberapa jam perjalanan ke arah selatan
Zhangjiagang. Sekitar 70% dari kayu merbau yang diimpor ke China diolah
menjadi lantai kayu. Kota ini menghasilkan sedikitnya 2,5 juta m2 flooring
berwarna gelap setiap tahunnya dengan nilai lebih dari US $ 200 juta.
Kenyataan ini membuka peluang untuk mengembangkan industri pengolahan
kayu merbau berupa penggergajian yang terintegrasi dengan woodworking di
Papua.
Industri penggergajian kayu merbau di Papua selama lima tahun terakhir
3 Kabupaten Keerom. Karena itu pengembangan industri penggergajian dengan
mengintegrasikan woodworking di ketiga wilayah tersebut perlu dikaji guna
memanfaatkan peluang yang ada untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
1.2.Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis kelayakan finansial
dan ekonomi perusahahaan kayu gergajian merbau dan woodworking
terintegrasi di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom -
Provinsi Papua.
1.3. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian akan memberikan manfaat paling tidak kepada dua pihak
yaitu :
1. Memberikan informasi kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas
Kehutanan, dalam menentukan kebijakan yang diperlukan guna
pengembangan industri pengolahan kayu merbau di Kota Jayapura,
Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom.
2. Memberikan gambaran prospek industri pengolahan kayu merbau kepada
para pelaku industri di Wilayah Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan
6
N (Pohon/Ha) V (m3/Ha)
I Kabupaten Keerom
1. PT. Risana Indah Fotest Ind. 2,00 9,42
2. PT. Hanurata Jayapura 4,69 19,45
II Kabupaten Sarmi
1. PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II 3,43 15,29
2. PT. Bina Balantak Utama 6,44 31,08
III Kabupaten Waropen
1. PT. Wapoga Mutiara Timber Unit III 0,73 1,95
IV Kabupaten Nabire
1. PT. Jati Dharma Indah 2,32 11,18
V Kabupaten Mimika
1. PT. Dyadini Timber 13,96 34,43
2. PT. Alas Tirta Kencana 0,80 2,80
VI Kabupaten Teluk Bintuni
1. PT. Rimba Kayu Arthamas 4,48 17,34
2. PT. Yotefa Sarana Timber 2,00 9,94
VII Kabupaten Kaimana
1. PT. Centrico 4,40 21,53
VIII Kabupaten Fak fak
1. PT. Hanurata Fak fak 1,78 12,21
IX Kabupaten Manokwari
1. PT. Megapura Mambramo Bangun 6,52 26,68
X Kabupaten Sorong
1. PT. Hanurata Unit Salawati 3,72 16,38
2. PT. Intimpura Timber 1,59 5,42
No Kabupaten/ IUPHHK Pohon berdiameter > 50 cm
redesain seluas 5,1 juta ha potensi masak tebang merbau di alam rata-rata
19,69 m3 per hektar, maka potensi yang tersedia sebesar 101 juta m3.
Berdasarkan data potensi kayu merbau di beberapa IUPHHK yang
beroperasi di beberapa kabupaten di Papua, potensi kayu merbau untuk pohon
kelas diameter di atas 50 cm berkisar 1,95-34,43 m3 per hektar (Tabel 1). Dinas
Kehutanan Provinsi Papua sendiri menyatakan bahwa rata-rata potensi kayu
merbau adalah 17 m3 per hektar.
Tabel 1 Potensi Kayu Merbau di beberapa kabupaten di Provinsi Papua
7 2.1.2 Sifat dasar dan pengerjaan kayu merbau
Kayu Merbau tergolong kayu berat, sangat keras, sangat kuat dan sangat
awet. Berat jenis kayu kering udara 0,66 – 0,85 atau 800 – 900 kg per m3 dan
515 -1.040 kg per m3, sehingga jenis merbau digolongkan sebagai kayu
tenggelam (Sinkers). Kelas kuat I – II, sehingga mampu menahan beban yang
berat. Kelas Awet I, dengan ketahanan terhadap serangan jamur dan serangga
perusak kayu yang tinggi hingga tahan untuk pemakaian jangka panjang baik di
luar maupun di dalam bangunan.
Kayu Merbau mudah kering dengan kembang kerut yang sangat rendah,
mudah dikerjakan, daya pagut terhadap paku maupun sekrup sangat baik,
namun perlu dibor terlebih dahulu (Tokede et al., 2006). Dalam pengerjaannya
kayu merbau umumnya tidak sulit digergaji, dapat diserut dengan mesin sampai
halus dan dapat dipelitur dengan memuaskan.
Namun jenis kayu ini biasanya pecah jika dipaku dan dapat menimbulkan
noda hitam jika berhubungan dengan besi atau terkena air. Kayu
I. palembanica menunjukkan sifat pemesinan berupa pemboran, pembuatan
lubang persegi dan pengamplasan yang sangat baik, penyerutan dan
pembentukan yang baik sampai sangat baik, serta dapat dibubut dengan hasil
sedang sampai baik. Sementara itu kayu I. bijuga dapat diserut, dibor, dibuat
lubang persegi, dibentuk dan diamplas dengan hasil yang sangat baik, tetapi
pembubutan akan memberi hasil yang buruk (Martawijaya et al., 1989).
2.1.3 Produk kayu merbau
Secara tradisional masyarakat Papua telah menggunakan kayu merbau
sebagai material dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari alat makan sampai
material untuk membangun rumah tinggal. Beberapa suku di Papua seperti
Suku Asmat dan Amugme di Agats dan Timika telah menggunakan kayu
merbau sebagai media untuk mengekspresikan kemampuan seni ukir mereka
untuk menghasilkan ukiran patung dan ornamen lainnya, seperti pada
9 Berdasarkan kapasitas terpasangnya industri pengolah kayu diketegorikan
dalam tiga kelas yaitu : Industri Kecil (kapasitas < 2.000 m3), Industri Sedang
(kapasitas 2.000 – 6.000 m3) dan Industri Besar (kapasitas > 6.000 m3).
Untuk kayu merbau ijin industri pengolahan yang diberikan pemerintah
daerah Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom adalah
Ijin Penggergajian.
2.2.1 Penggergajian
Penggergajian adalah proses mengolah kayu bulat untuk menghasilkan
kayu gergajian dengan menggunakan gergaji. Secara garis besar proses
penggergajian adalah kegiatan membelah dan memotong kayu. Dimana alat
utama dari penggergajian adalah headrig dan resaw. Proses pengolahan kayu
secara ringkas dimulai saat kayu bulat dibelah pada headrig yang bisa berupa
circular saw atau bandsaw dan selajutnya dibentuk sesuai ukuran dimensi hasil
akhir kayu gergajian yang diinginkan pada proses berikutnya yaitu resaw
(Walker, 2006).
Lebih lanjut Walker (2006), menyatakan beberapa faktor yang
mempengaruhi perancangan penggergajian yaitu:
1. Bahan baku yang berkaitan dengan jenis, kualitas, jumlah persediaan, dan perkiraan ukuran kayu bulat,
2. Permintaan pasar yang berkaitan dengan jenis, kualitas, jumlah produksi,
3. Lokasi, pilihan lokasi paling baik dibangun dekat dengan sumber bahan baku, dimana ini akan mengurangi biaya pengangkutannya dengan pertimbangan lain sebaiknya dibangun ditepi sungai atau poros jalan utama sehingga memudahkan akses masuk kayu bulat dan pengiriman kayu olahan, dan
4. Modal, modal akan membatasi rancangan sebuah penggergajian berkaitan dengan kapasitas penggergajian, jenis gergaji yang dipakai, tingkat otomatisasi peralatan dan kengkapan lainnya yang secara langsung akan menpengaruhi efisiensi penggergajian itu.
Berdasarkan dimensi ukuran produk, kayu gergajian dibagi menjadi tujuh
10
No. Sortimen Tebal (cm) Lebar Keterangan
1 Papan lebar (Boards) < 5,0 > 15 -2 Papan tebal (Planks) > 5,0 > 15 tebal < ½ lebar 3 Papan sempit (Narrow boards) < 5,0 10 - < 15 -4 Papan lis (Strips) < ½ lebar < 15 -5 Balok (Baulk) > 10 > 20 berhati 6 Broti (Scantlings) > ½ lebar - -7 Kayu gergajian pendek (Shorts) - - Panjang < 1 m
Tabel 2 Sortimen Kayu Gergajian
-) Tidak dipersyaratkan Sumber : SNI 01-5008.1-1999
2.2.1.1Bahan baku
Hariadi (1989), menyatakan bahwa perusahaan penggergajian adalah salah
satu perusahaan material intensive, yang mana tingginya biaya produksi
sebagian besar diakibatkan tingginya biaya pengadaan bahan baku. Data dari 11
unit penggergajian Perum Perhutani Unit I dan II menunjukkan bahwa biaya
pengadaan bahan baku rata-rata mencapai 82,4% dari biaya produksi tidak tetap
(variabel cost).
2.2.1.2Teknik penggergajian
Walker (2006) menyatakan penggergajian dapat dikelompokkan
berdasarkan sumber bahan baku yang digunakan, kapasitas produksinya, type
alat yang digunakan untuk membelah kayu bulat, dan tingkat otomatisasi.
Setiap penggergajian memiliki ciri khas yang membedakan satu dengan yang
lain, karenanya tidak ada desain baku suatu penggergajian. Setiap
penggergajian dibangun dengan tujuan memberikan efisiensi operasional yang
tinggi dan menguntungkan dimana hal ini dapat dicapai hanya bilamana
perancangan penggergajian dilakukan dengan baik dan dikelola dengan benar.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi suatau penggergajian
yaitu jenis peralatan yang dipakai, lay out peralatan, bahan baku, produk akhir
dan kemampuan sawdoctor. Faktor terpenting suatu penggergajian yang efisien
adalah pengetahuan dan pengalaman sawdoctor, lebih lanjut khususnya
kemampuan sawdoctor dalam mempertimbangkan sejumlah interaksi
11 bahan baku (feeding speed), kecepatan gergaji, tegangan gergaji dan lebar
gergaji. Penggergajian akan berjalan dengan efisien hanya bila mana
keseimbangan faktor-faktor yang mempengaruhi penggergajian dioptimalkan,
sehingga akan meminimumkan penggunaan energi, produk yang dihasilkan
berkualitas, dan produktifitas yang tinggi.
Bowyer et al., 2003, menyatakan cara terbaik untuk mengukur efisiensi
suatu penggergajian adalah dengan membandingkan volume kayu gergajian
yang dihasilkan dengan volume input kayu bulat, yang disebut LRF (Lumber
recovery faktor) atau rendemen kayu gergajian. Lebih lanjut ditambahkan
bahwa efisiensi penggergajian dapat ditingkatkan dengan menerapkan beberapa
hal penting berikut ini :
1. Mengurangi tebal potongan gigi gergaji (kerf),
2. Mengurangi variasi ketebalan yang memungkinkan terjadi ketebalan melebihi ukuran yang diinginkan,
3. Membuat keputusan keakuratan posisi membelah untuk tiap-tiap kayu bulat yang optimum sesuai ukuran kayu olahan yang akan dihasilkan.
Secara umum jenis gergaji yang banyak dipakai adalah circular saw dan
band saw, adapun perbandingan kelebihan dan kelemahan keduanya disajikan
sebagai berikut :
Tabel 3 Perbandingan circular saw dan band saw
No Circular saw Band Saw
1 Circular saw dengan diameter
antara 0,9-1,5 m dapat membelah kayu bulat dengan diameter sampai dengan 0,9 m. Jika kayu yang akan dibelah lebih besar maka dilakukaan penambahan Circular saw kedua diatas yang pertama.
Hampir semua kelas diameter kayu bulat dapat dibelah dengan
menggunakan gergaji ini.
2 Lebar keratan gergaji (Kerf) berkisar 4,8-9,5 mm.
Lebar keratan gergaji (Kerf) berkisar 3,2-4,8 mm.
3 Akurasi penggergajian kurang baik karena keratan gergaji yang lebar
Akurasi penggergajian lebih baik karena lebar keratan gergaji yang lebih tipis.
4 Serbuk gergaji yang dihasilkan banyak
Serbuk gergaji yang dihasilkan lebih sedikit
12
1 2002 623.495 124.753.559
2 2003 762.604 85.839.013
3 2004 432.967 26.876.307
4 2005 1.471.614 3.408.881
5 2006 679.247 37.008.627
No Tahun Produksi (m3) Nilai Ekspor (US$)
Juga ditambahkan, bahwa investasi awal dan biaya pemeliharaan band saw
lebih mahal dibandingkan circular saw namun kecepatan menggergaji band saw
lebih lambat dibanding circular saw.
Satu kemajuan dalam peningkatan efisiensi penggergajian pada saat ini
adalah dengan menggunakan alat pemindai kayu bulat (electronic log scanners)
yang dilengkapi komputer untuk mengukur dan menentukan posisi pemotongan
pertama serta pola penggergajian. Perpaduan alat pemindai ini dapat
meningkatkan volume kayu gergajian yang dihasilkan yang berarti
meningkatkan efisiensi penggergajian tersebut. Pada saat penggergajian
dilakukan, bantuan sinar laser memberi tanda garis lurus sepanjang kayu bulat
yang akan menuntun operator gergaji meluruskan posisi gergaji sehingga hasil
pengergajian akan lebih baik (Walker, 2006).
Departemen Kehutanan dalam surat Direktur Jenderal Bina Produksi
Kehutanan, No. S.948/VI-BPPHH/2004 tanggal : 26 Oktober 2004, menyatakan
rendemen kayu olahan yang dihasilkan dari proses penggergajian dengan bahan
baku kayu bulat dari hutan alam berkisar 53-72%.
2.2.1.3Produksi dan ekspor
Dalam perdagangan internasional Kayu gergajian masuk dalam kategori
HS 4407 (Wood Sawn Or Chipped Lengthwise, Sliced Or Peeled, Whether Or
Not Planed, Sanded Or Finger-Jointed). Total volume produksi dan nilai
ekspor kayu gergajian Indonesia dari tahun 2002 sampai dengan 2006 disajikan
pada Tabel 4 .
Tabel 4 Perkembangan produksi dan nilai ekspor kayu gergajian Indonesia
13 2.2.2 Woodworking
Industri woodworking merupakan proses pengolahan kayu lanjutan, di
mana kayu gergajian akan diproses lebih lanjut menjadi produk akhir, bisa
berupa furnitur, flooring atau produk lainnya sehingga kayu mempunyai nilai
tambah yang lebih besar dibandingkan produk setengah jadi atau kayu bulat.
Industri ini mensyaratkan ketersediaan sumber daya manusia dengan
kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri penggergajian. Ini
dikarenakan produk yang dihasilkan sangat luas dan lebih spesifik dan
seringkali didasarkan pada permintaan konsumen.
Salah satu Industri woodworking yang ada adalah Industri permebelan dan
kerajinan di mana industri ini didominasi oleh Usaha Kecil dan Menengah
(UKM) dengan sistem industri rumahan yang bekerjasama dengan industri -
industri besar. Penyerapan tenaga kerja per US$ 100 investasi adalah yang
terbanyak diantara seluruh sektor industri kehutanan (Manurung et al., 2007).
2.2.2.1Bahan baku
Bahan baku proses produksi woodworking sangat beragam baik dari segi
jenis maupun ukuran. Ini dikarenakan produk yang dihasilkan sangat beragam
mulai dari kerajinan kayu, furnitur, pintu, jendela dan lain sebagainya. Dari
alternatif industri pengolahan kayu, woodworking sangat fleksibel dalam hal
persyaratan bahan baku.
Kebutuhan bahan baku kayu industri furnitur dan kerajinan adalah sekitar
7 – 7,5 juta meter kubik per tahun yang umumnya dari jenis kayu jati, mahoni,
pinus, akasia, gmelina, durian, mangga, mbacang, kuweni, bungur, sonokeling,
mindi, waru, kayu karet dan sebagian kecil kayu-kayu yang berasal dari hutan
alam, seperti meranti, nyatoh, bangkirai dan kempas (Manurung et al., 2007).
2.2.2.2Teknik pengolahan
Pokok kegiatan yang dilakukan di dalam sebuah proses woodworking
adalah memotong, melubangi dengan bor, penghaluskan dengan amplas,
perakitan, pengecatan dan packing. Adapun proses baku tiap-tiap woodworking
tergantung pada produk yang akan di hasilkan, bahan baku yang tersedia dan
14 No Tahun Woodworking (m3) Nilai Ekspor (US$)
1 2004 2.290.054 1.062.407.358
2 2005 2.407.233 1.265.503.341
3 2006 2.313.012 1.295.685.621
4 2007 1.882.184 1.253.080.507
5 2008 1.682.015 1.197.729.784
2.2.2.3Produksi dan ekspor
Produk yang dihasilkan woodworking sangat luas, dalam Harmonized
System (HS) berdasarkan jenis komoditi perdagangan internasional, produk
woodworking masuk dalam beberapa kategori yaitu :
1. HS 4413: Densified Wood, In Blocks, Plates, Strips Or Profile Or Similar Objects,
2. HS 4414: Wooden Frames For Paintings, Photographs, Mirrors Or Similar Objects,
3. HS 4415: Packing Cases, Boxes, Crates, Drums And Similar Packings, Of Wood; Cable-Drums Of Wood; Pallets, Box,
4. HS 4416: Coasks, Barrels, Vats, Tubs And Other Coopers`Products And Parts Thereof, Of Wood, Including Stav,
5. HS 4417: Tools, Tool Bodies, Tool Handles, Broom Or Brush Bodies And Handles, Of Wood; Boot Or Shoe Lasts And,
6. HS 4418: Builders` Joinery And Carpentry Of Wood, Including Cellular Wood Panels, Assembled Parquet Pnales S,
7. HS 4419: Tableware And Kitchenware, Of Wood,
8. HS 4420: Wood Marquetry And Inlaid Wood; Caskets And Cases For Jewellery Or Cutlery, And Similar Articles,
9. HS 4421: Other Articles Of Wood.
Total produksi woodworking Indonesia dari tahun 2002 sampai dengan
2006 disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5 Perkembangan volume produksi dan ekspor woodworking
Sumber : www.brikonline.com
ASMINDO melaporkan pada tahun 2005, total nilai ekspor furnitur
Indonesia adalah US$ 1,79 milyar dengan negara tujuan ekspor Indonesia yang
utama adalah Amerika Serikat (37%), Jepang (12%), Inggris (8%) dan Belanda
15 Italia, Belgia, Spanyol, dan Australia. Sementara itu, perdagangan mebel dunia
meningkat dari US$ 51 milyar pada tahun 2000 menjadi US$ 80 milyar pada
tahun 2005 (Manurung et al., 2007).
2.3. Studi Kelayakan proyek
Gray et al., (1985) mendefinisikan proyek adalah kegiatan-kegiatan yang
dapat direncanakan dan dilaksanakan dalam satu bentuk kesatuan dengan
mempergunakan sumber-sumber untuk mendapatkan benefit (kemanfaatan).
Sumber-sumber yang dipergunakan dalam pelaksanaan proyek dapat berbentuk
barang-barang modal, tanah, bahan-bahan setengah jadi, bahan-bahan mentah,
tenaga kerja, dan waktu. Suharto (2002) mendefinisikan proyek adalah kegiatan
sekali lewat, di mana waktu dan sumber daya yang terbatas digunakan untuk
mencapai hasil akhir yang telah ditentukan, misalnya produk atau fasilitas
produksi.
Kadariah (2001) mendefinisikan proyek adalah suatu keseluruhan kegiatan
yang menggunakan sumber-sumber untuk memperoleh manfaat; atau suatu
kegiatan dengan pengeluaran biaya dan dengan harapan untuk memperoleh
hasil pada waktu yang akan datang, dan yang dapat direncanakan, dibiayai, dan
dilaksanakan sebagai satu unit.
Kegiatan suatu proyek selalu ditujukan untuk mencapai sesuatu tujuan dan
mempunyai suatu titik tolak (starting point) dan suatu titik akhir (ending point)
baik biaya maupun hasilnya yang penting biasanya dapat diukur.
Kegiatan-kegiatan dalam satu bentuk kesatuan berarti bahwa baik sumber-sumber yang
dipergunakan dalam satu proyek maupun hasil-hasil proyek tersebut dapat
dipisahkan dari sumber-sumber yang dipergunakan. Kegiatan yang dapat
direncanakan berarti bahwa baik biaya maupun hasil-hasil pokok dari proyek
dapat dihitung atau diperkirakan dan kegiatan-kegiatan dapat disusun
sedemikian rupa sehingga dengan penggunaan sumber-sumber yang terbatas
dapat diperoleh manfaatyang sebesar mungkin.
Tujuan dari analisis proyek adalah untuk mengetahui tingkat keuntungan
yang dapat dicapai melalui investasi dalam suatu proyek, menghindari
16 yang tidak menguntungkan, mengadakan penilaian terhadap kesempatan
investasi yang ada sehingga kita dapat memilih alternatif proyek yang paling
menguntungkan dan untuk menentukan prioritas investasi (Gray et al., 1985).
2.3.1 Tahapan Studi Kelayakan
Secara garis besar Gray et al., (1985) mengemukakan tahapan pelaksanaan
studi kelayakan adalah sebagai berikut : langkah pertama yang perlu dilakukan
adalah identifikasi proyek, yaitu menentukan calon-calon proyek yang akan
dipertimbangkan untuk dilaksanakan, langkah kedua adalah melakukan studi
persiapan, studi persiapan ini pada dasarnya adalah untuk melihat seberapa jauh
calon proyek dapat dilaksanakan, dan seberapa jauh rintangan-rintangan yang
ada dapat menghambat pelaksanaan proyek tersebut, langkah ketiga pemilihan
proyek adalah menghitung manfaat dan biaya yang diperlukannya sepanjang
umur proyek.
Kadariah (2001) menyebutkan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan
dalam melakukan analisis proyek, yaitu aspek teknis, aspek managerial dan
administrative, aspek organisasi, aspek komersial, aspek finansial, dan aspek
ekonomi.
2.3.2 Biaya, manfaat dan periode analisis
Ada beberapa konsep terkait definisi biaya diantaranya, biaya adalah
sesuatu akibat yang diukur dalam nilai uang yang mungkin timbul dalam
mencapai suatu tujuan tertentu, biaya adalah suatu harga tukar atau nilai tukar
sebagai akibat atau adanya pengorbanan yang dibuat untuk memperoleh suatu
manfaat . Biaya adalah pengorbanan atau pembebanan yang diukur dalam nilai
uang, yang harus dibayarkan untuk sejumlah barang dan jasa (McGuigan and
Moyer, 1986).
Dalam proses perencanaan ataupun produksi, analisis terhadap biaya
diperlukan untuk merencanakan besarnya keuntungan yang dapat diperoleh,
mengendalikan pengeluaran, mengukur keuntungan tahunan atau periodik,
membantu penetapan harga jual dan kebijaksanaan harga, dan penyediaan data
17 Biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat dan hubungannya dengan
proses produksi dan menurut jumlah satuan produksi atau tingkat kegiatan.
Berdasarkan sifat dan hubungannya dengan proses produksi biaya dapat
dikategorikan sebagai :
1. Biaya langsung yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar bahan dan tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi dan bahan tersebut menjadi bagian dari produk jadinya.
2. Biaya tidak langsung yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar bahan dan tenaga kerja tidak langsung yaitu bahan yang tidak secara langsung menjadi bagian dari produk jadi, misalnya bahan bakar mesin; pelumas dan lain-lain, sedangkan tenaga kerja yang tidak terkait langsung dengan proses produksi misalnya satpam pabrik, petugas kebersihan, pegawai kantor dan lain-lain. Biaya tak langsung lain adalah sewa alat ataupun penyusutan alat apabila dilakukan investasi pada alat produksi.
Berdasarkan jumlah satuan produksi atau tingkat kegiatan yang dihasilkan
biaya dikategorikan sebagai :
1. Biaya tetap yaitu biaya yang harus dikeluarkan secara periodik dan besarnya tetap dengan tidak dipegaruhi oleh jumlah produk yang dihasilkan. Contoh biaya tetap adalah biaya penyusutan, bunga modal, biaya asuransi, biaya sewa tempat/lahan, biaya perawatan dan perbaikan inventaris. Komponen biaya tetap biasanya dinyatakan dalam satuan waktu tertentu secara periodic ,misalnya per tahun.
2. Biaya Variabel yaitu biaya yang besarnya ditentukan oleh jumlah satuan produk yang dihasilkan. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan bakar, biaya pelumas, upah pekerja harian, biaya listrik, biaya untuk penyediaan air. Biaya variabel biasanya dinyatakan dalam satuan volume produk atau kegiatan (misalnya : ton, jam, dsb).
Manfaat atau benefit suatu proyek dapat berbentuk tingkat konsumsi yang
lebih besar, penambahan kesempatan kerja, perbaikan dalam tingkat pendidikan
atau kesehatan, dan perubahan/perbaikan dalam suatu sistem atau struktur
(Gray et al., 1985).
Suatu proyek dapat dinyatakan berakhir bila sudah atau diharapkan tidak
memberikan benefit lagi. Gittinger (1977), menyatakan bahwa dalam
melakukan analisis, waktu atau periode yang dipergunakan adalah periode
18
Biaya Tetap 1. Penyusutan Sarana & prasarana produksi serta bunga modal 2. Gaji pegawai tetap
3. Asuransi 4. Pajak
5. Biaya Overhead umum Biaya Variabel 1. Bahan baku
2. Bahan penolong
3. Biaya Energi (Listrik, bahan bakar dan pelumas) 4. Upah tenaga langsung
5. Biaya pemasaran
6. Biaya pemeriharaan dan perbaikan
Jenis Biaya Komponen
suatu proyek ditentukan berdasarkan waktu ekonomis dari alat-alat produksi
yang dipakai.
Secara garis besar komponen biaya produksi dapat dijabarkan sebagai
berikut:
Tabel 6 Jenis dan Komponen Biaya produksi
Sumber : Gray et al., 1985.
2.3.3 Kelayakan Finansial dan Ekonomi
Dalam menilai Kelayakan finansial dan ekonomi suatu proyek perlu
memperhatikan beberapa aspek yaitu, ketersediaan bahan baku, ketersediaan
teknologi pengolahan, kriteria kelayakan finansial dan ekonomi, dan perkiraan
dampak sosial serta lingkungan.
2.3.3.1 Ketersediaan bahan baku
Pabrik memerlukan bahan baku yang akan diproses menjadi produk.
Suatu perusahaan amat berkepentingan menjaga agar pasokan bahan baku dapat
berkesinambungan dengan harga yang layak dan biaya transportasi yang
rendah. Oleh karena itu, salah satu pertimbangan dalam lokasi adalah dekat
dengan sumber bahan baku. Bahkan untuk industri tertentu, hal ini merupakan
suatu keharusan bila ingin mencapai biaya produksi yang ekonomis (Suharto,
19 Ketersediaan bahan baku dinyatakan layak apabila :
1. Jumlah total volume produksi lestari kayu bulat merbau dari seluruh IUPHHK yang beroperasi dapat mencukupi kebutuhan industri pengolahan yang akan dikembangkan,
2. Kelangsungan pasokan kayu bulat paling kurang sama dengan umur proyek yang diharapkan
2.3.3.2 Ketersediaan Teknologi Pengolahan
Teknologi pengolahan dinyatakan layak apabila dapat dioperasikan pada
lokasi yang akan dibangun dengan ketersediaan sumber daya manusia dan
infrastruktur setempat.
2.3.3.3 Kriteria Kelayakan Finansial dan Ekonomi
Kadariah (2001) menjelaskan batasan dan tujuan dari penilaian aspek
finansial dan aspek ekonomi dalam menilai kelayakan proyek dengan
penjelasan sebagai berikut; Aspek finansial menyelidiki terutama perbandingan
antara pengeluaran dan "revenue earnings" proyek; apakah proyek itu akan
terjamin dananya yang diperlukan; apakah proyek akan mampu membayar
kembali dana tersebut, dan apakah proyek akan berkembang sedemikian rupa
sehingga secara finansial dapat berdiri sendiri. Sedangkan Aspek ekonomi
menyelidiki apakah proyek itu akan memberi sumbangan atau mempunyai
peranan yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi seluruhnya, dan
apakah peranannya cukup besar untuk membenarkan (to justify) penggunaan
sumber-sumber yang langka.
Lebih lanjut ditambahkan dalam analisis finansial, proyek dilihat dari sudut badan atau orang yang menanam modalnya dalam proyek atau yang berkepentingan langsung dalam proyek. Dalam analisis ini yang diperhatikan adalah hasil untuk modal saham (equity capital) yang ditanam dalam proyek.
Hasil finansial sering disebut 'private returns'. Analisis finansial ini penting
20
Dalam analisis ekonomi, proyek dilihat dari sudut perekonomian sebagai keseluruhan. Dalam analisis ini yang diperhatikan adalah hasil total, atau produktivitas atau keuntungan yang diperoleh dari semua sumber yang dipakai dalam proyek untuk masyarakat atau perekonomian sebagai keseluruhan, tanpa
melihat siapa yang menyediakan sumber-sumber tersebut dan siapa dalam masyarakat yang menerima hasil proyek tersebut. Hasil ini disebut 'the social return' atau 'the economic return' bagi proyek.
Ada beberapa unsur yang berbeda penilaiannya dalam kedua macam analisis tersebut di atas, yaitu harga, biaya, pembayaran transfer dan bunga.
Harga, di dalam analisis ekonomi selalu dipakai harga bayangan (shadow prices atau accounting prices), adalah harga yang menggambarkan nilai sosial atau nilai ekonomi yang sesungguhnya bagi unsur-unsur biaya maupun hasil, sedang dalam analisis finansial selalu dipakai harga pasar.
Biaya, di dalam analisis ekonomi biaya bagi input proyek adalah manfaat
yang hilang (the benefit foregone) bagi perekonomian karena input itu dipakai
dalam proyek, atau 'the opportunity cost' bagi input.
Pembayaran transfer, Pajak di dalam analisis ekonomi pembayaran pajak
tidak dikurangkan/dikeluarkan dari manfaat proyek. Pajak adalah bagian dari
hasil neto proyek yang diserahkan kepada pemerintah untuk digunakan bagi
kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan, dan oleh karenanya tidak
dianggap sebagai biaya. Subsidi, subsidi akan menimbulkan persoalan dalam
penghitungan biaya suatu proyek. Subsidi ini sesungguhnya adalah suatu
pembayaran transfer dari masyarakat kepada proyek, sehingga dalam analisis
finansial, subsidi mengurangi (menurunkan biaya proyek), jadi menambah
manfaat proyek, sedang dalam analisis ekonomi harga pasar harus
disesuaikan (adjusted) untuk menghilangkan pengaruh subsidi. Subsidi ini
menurunkan harga barang-barang input, maka besarnya subsidi harus
ditambahkan pada harga pasar barang-barang input tersebut. Bunga, di dalam
analisis ekonomi bunga modal tidak dipisahkan atau dikurangkan dari hasil
21 ( 3 ) ( 1 ) Dan untuk menilai kelayakan investasi terhadap proyek yang direncanakan,
Klemperer (1996) memberikan empat kriteria yang dapat dipakai untuk
menerima atau menolak rencana investasi suatu proyek yaitu Net Present Value
(NPV), Internal Rate of Return (IRR), Benefit Cost Ratio (BCR) dan Payback
Period. NPV adalah nilai saat ini dari selisih pendapatan yang diperoleh
dengan biaya yang dikeluarkan. IRR adalah suatu discount rate yang akan
membuat nilai NPV menjadi sama dengan 0, atau sama dengan satu nilai yang
akan membuat nilai sekarang pendapatan sama dengan nilai sekarang biaya.
BCR atau yang biasa disebut profitability index adalah rasio perbandingan
antara nilai sekarang pendapatan yang diperoleh dengan nilai sekarang biaya
yang dikeluarkan, dengan menggunakan tingkat bunga minimum yang
diinginkan pemodal. Dalam studi ini tiga kriteria investasi tersebut yang dipakai
sebagai pertimbangan. Ketiga kriteria kelayakan tersebut dapat dihitung dengan
menggunakan formula seperti pada persamaan (1), (2) dan (3).
∑
∑
Dimana,
Ry = pendapatan yang diperoleh pada tahun ke y,
Cy = biaya yang dikeluarkan pada tahun ke y,
n = adalah umur ekonomis proyek,
r = adalah realinterestrate.
22 Rencana investasi suatu proyek dikatakan layak finansial apabila :
1. NPV > 0, dimana NPV adalah Net Present Value,
2. IRR > RI dimana IRR adalah Internal Rate Return dan RI adalah (Rate of Interest) adalah suku bunga yang dipakai dalam perhitungan NPV,
3. BCR > 1, dimana BCR adalah Benefit Cost Ratio.
2.3.3.4 Perkiraan Dampak Ekonomi dan Sosial
Menurut Kadariah (2001), tujuan dilakukannya analisis kelayakan ekonomi
adalah untuk melihat apakah proyek yang akan dilaksanakan akan memberikan
sumbangan atau mempunyai peranan yang cukup besar dalam pembangunan
ekonomi seluruhnya, dan apakah peranannya cukup besar untuk membenarkan
penggunaan sumber-sumber daya yang langka.
Proyek dinyatakan layak secara ekonomi dan sosial apabila :
1. Dapat meningkatkan pertumbuhan PAD dan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) secara nyata,
2. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat lokal,
3. Menambah prasarana yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup
masyarakat setempat,
4. Tidak ditentang oleh masyarakat setempat.
2.3.3.5 Perkiraan Dampak Lingkungan
Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 mendefinisikan analisis Dampak
Lingkungan adalah hasil studi atas dampak penting suatu usaha atau kegiatan
yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan.
Dalam analisis ini potensi dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan
akan diprediksi berdasarkan pengalaman perusahaan penggergajian kayu
merbau dan woodworking terintegrasi yang telah beroperasi di Jawa Timur
kemudian dibandingkan dengan ambang batas mutu baku limbah cair yang
diperkenankan.
Dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.
23
1 BOD 75 22,5
7 Debit Limbah Maksimum 0.30 m3 per m3 produk kayu lapis No Parameter Kadar Maksimum Beban pencemaran Maksimum
2 COD 125 37,5
3 TSS 50 15
4 Fenol 0,25 0,08
5 Amonia Total (sbg N) 4 1,2
6 PH 6.0 – 9.0
mutu limbah industri yang relevan dengan pengolahan kayu adalah industri
kayu lapis dengan parameter baku mutu limbah cair seperti yang ditampilkan
pada Tabel 7.
Tabel 7 Baku mutu limbah cair untuk industri kayu lapis
Sumber : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP-51/MENLH/10/1995.
Proyek dinyatakan layak terhadap aspek dampak lingkungan apabila :
Dampak lingkungan dari industri pengolahan kayu merbau yang akan
24
III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Waktu Dan Tempat
Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret–Juni 2009 dengan lokasi
penelitian di :
1. Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom di Provinsi
Papua, untuk mengunjungi IUPHHK dan IUIPHHK yang beroperasi.
2. Surabaya, untuk mengunjungi industri penggergajian merbau dan
woodworking yang terintegrasi yang telah beroperasi sebagai pembanding.
3.2. Alur Penelitian
Adapun alur yang menjadi prosedur pelaksanaan penelitian ini disajikan
dalam diagram alir pada Gambar 5.
3.3. Jenis dan Sumber Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan
sekunder. Data primer dikumpulkan melalui peninjauan lapangan dan
wawancana dengan perusahaan pemegang IUPHHK dan Industri gergajian
merbau dan woodworking terintegrasi. Data sekunder diperoleh dari instansi di
lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Bapedalda,
Dinas Perindustrian, Dinas Kehutanan Provinsi dan instansi terkait lainya. Jenis
data primer dan sekunder yang akan dikumpulkan disajikan pada Tabel 8.
3.4. Analisis Kelayakan Finansial dan Ekonomi
Analisis kelayakan dilakukan terhadap beberapa aspek yang terkait
dengan industri pengolahan kayu yang akan dikembangkan, yaitu :
3.4.1 Ketersediaan Bahan Baku
Kelayakan ketersediaan bahan baku dilakukan dengan menginventarisir
jumlah IUPHHK yang memproduksi kayu merbau di ketiga lokasi penelitian
kemudian dilakukan rekapitulasi terhadap AAC masing-masing pemegang ijin
sehingga akan diperoleh jumlah lestari potensi kayu merbau yang dapat
dimanfaatkan. Kemudian dilakukan analisis alokasi distribusi poduksi kayu
bulat merbau beberapa tahun terakhir untuk mengetahui volume distribusi kayu
25 Jml IUPPHK, AAC merbau
Tot Prod merbau
Sumber Daya Manusia Infrastruktur
Cost Benefit NPV, IRR & BCR
PDRB, PAD, Perluasan Kesempatan Kerja, Prasarana
Teknologi Pengolahan Limbah tersedia Tidak ada dampak tak terubah
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Mulai
Ketersediaan Bahan Baku
Ketersediaan Teknologi Pengolahan
Analisis Kelayakan Finansial & Ekonomi
Perkiraan Dampak Ekonomi & Sosial
Perkiraan Dampak Lingkungan Tersedia ?
Penggergajian & Woodworking terintegrasi
Tidak
Tersedia ?
Tidak
Tidak
Tidak
Layak ?
Tidak Stop
Layak ?
Meningkat ?
26 3.4.2 Ketersediaan Teknologi Pengolahan
Kelayakan terhadap ketersediaan teknologi penggergajian kayu
merbau dan woodworking terintegrasi dilakukan dengan melihat harga
investasi, kapasitas produksi dan besaran rendemen yang dapat dihasilkan.
Analisis dilanjutkan dengan melihat operasional dari masing-masing
teknologi tersebut, yaitu besar biaya operasional peralatan masing-masing
teknologi yang ada, sumber daya manusia yang akan mengoperasikan dan
infrastruktur yang tersedia.
3.4.3 Kriteria Kelayakan Finansial dan Ekonomi
Analisis dilakukan dengan memprediksi dana investasi yang akan
ditanamkan, prediksi penerimaan, dan rugi-laba perusahaan penggergajian
kayu merbau dan woodworking terintegrasi.
Bentuk investasi sendiri yang diperhitungkan sebagai Cost berupa cash
outflow dibagi dua kelompok, yaitu :
1. Capital expenditure : jenis pengeluaran yg memberikan manfaat jangka panjang, seperti pembelian mesin-mesin, bangunan, tanah, dan aktiva tetap lainnya.
2. Operating expenditure : jenis pengeluaran yang diperhitungkan sebagai biaya operasional, seperti biaya tenaga kerja, biaya material, biaya bahan bakar dan lain-lain.
Penerimaan yang diperhitungkan sebagai Benefit berupa cash inflow
diperhitungkan berdasarkan prediksi penjualan kayu olahan/produk yang
akan dihasilkan.
Analisis finansial dilakukan dengan menggunakan harga beli kayu
bulat dan dan harga jual kayu olahan merbau menggunakan harga yang
berlaku di lokasi penelitian (Kab. Jayapura, Kota. Jayapura dan Kabupaten
Keerom), dengan memperhitungkan pajak sebagai pengeluaran dengan
bunga menggunakan nilai bunga pinjaman komersil pada bank yang
diperhitungkan dalam prediksi cash flow perusahaan.
Analisis ekonomi dilakukan dengan menggunakan harga beli kayu
bulat dan dan harga jual kayu olahan merbau menggunakan opportunity
27 diperhitungkan menggunakan nilai bunga menggunakan social rate yang
diperhitungkan dalam prediksi cash flow perusahaan.
Berdasarkan prediksi cash flow tersebut, akan dihitung NPV, IRR
dan BCR dari penggergajian kayu merbau dan woodworking terintegrasi
dengan menggunakan persamaan (1), (2) dan (3).
3.4.4 Perkiraan Dampak Ekonomi dan Sosial
Perkiraan terhadap dampak ekonomi dan sosial dilakukan dengan
menghitung besarnya penyerapan tenaga kerja yang akan terjadi,
kemungkinan besaran kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) melalui pembayaran pajak dan retribusi dan pengaruhnya
terhadap pembangunan ekonomi wilayah.
3.4.5 Perkiraan Dampak Lingkungan
Dalam perkiraan terhadap dampak lingkungan ini akan dilihat dampak
lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh teknologi penggergajian merbau
28
No Jenis data Cara mengumpulkan data Sumber data Ket
Primer
1. AAC jenis merbau per IUPHHK Kunjungan lapangan ke unit Pemegang IUPHHK Ketersediaan Bahan Baku 2. Pengesahan RKT
3. Realisasi produksi merbau 5 thn terakhir 4. Alokasi distribusi produksi
5. Biaya produksi kayu bulat merbau 6. Harga jual kayu bulat merbau 1. Nilai investasi yang ditanamkan 2. Harga jual kayu olahan merbau 3. Biaya operasional yang dikeluarkan 4. Pendapatan
Sekunder
1. Jenis peralatan produksi terbaru 2. Kapasitas produksi dan efisiensi 3. Harga Investasi peralatan
4. SDM dan infrastruktur pendukung operasional
1. Jumlah penyerapan tenaga kerja 2. Kontribusi pajak dan pembayaran lain 3. Infrastruktur yang bertambah
1. Potensi pencemaran lingkungan yang dapat terjadi 2. Teknologi yang tersedia untuk pengolahan limbah
Kunjungan ke unit industri penggergajian kayu merbau
2 Kunjungan ke unit industri
penggergajian kayu merbau
Kunjungan ke unit industri penggergajian kayu merbau
Kunjungan ke unit industri penggergajian kayu merbau dan woodworking terintegrasi
29
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil
4.1.1 Kondisi Industri Perkayuan di Papua
4.1.1.1 Penyebaran Industri
Penggolongan Industri primer hasil hutan berdasarkan kapasitas
produksinya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu industri dengan kapasitas
produksi per tahun ≤ 6.000 m3 dan > 6.000 m3. Di Provinsi Papua sampai
dengan bulan Juni 2009 terdapat 41 unit industri primer hasil hutan dengan
total kapasitas produksi kayu olahan per tahun sebesar 2,7 juta m3. Total
jumlah tersebut terdiri atas 30 unit industri dengan kapasitas produksi
≤ 6.000 m3 per tahun dan industri dengan kapasitas produksi > 6.000 m3 per tahunsebanyak11 unit (Tabel 9).
Tabel 9 Penyebaran IUIPHHK di Propinsi Papua sampai dengan bulan Juni tahun 2009
Ket. SW(Sawmill), BB(Block Board), ML(Moulding), PL(Plywood), CH(Chips), & WW(Woodworking)
Sumber : Laporan BP2HP Wilayah XVII Bulan Juni 2009.
Dari seluruh industri tersebut, 22 unit industri dengan kapasitas
produksi kayu gergajian ≤ 6.000 m3 per tahun tersebar ditempat dimana
penelitian ini dilaksanakan yaitu Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan
Kabupaten Keerom, dengan total kapasitas produksi sebesar 127 ribu m3 per
tahun yang secara rinci disajikan pada Tabel 10.
≤ 6 000 m3/tahun
SW BB ML PL SW CH WW
Kab. Biak 1 1 1 1 4
Kab. Boven Digul 2 1 3
Kab. Jayapura 10 10
Kab. Keerom 5 5
Kab. Merauke 1 1
Kab. Nabire 5 5
Kab. Sarmi 3 3
Kep. Yapen 1 1 1 3
Kota Jayapura 7 7
Total 30 1 1 4 3 1 1 41
Lokasi
Kapasitas Produksi Industri
30
Lokasi Perusahaan Kapasitas (m3)
Kab. Jayapura CV. Anugerah Bumi Cenderawasih 6.000
CV. Sejahtera Abadi Perkasa 5.000
CV. Soby Sakti Still Unitaja 6.000
KSU Rajawali Papua Foresta 6.000
PT. Gizand Putra Abadi 6.000
PT. Irian Hutama 4.000
PT. Karya Irian Agung Utama 6.000
PT. Korina Jaya Lestari 6.000
PT. Sijas Express Unit II 6.000
PT. Victory Cemerlang Unit III 6.000 57.000
CV.Edom Ariha Jaya Unit I 6.000
CV.Edom Ariha Jaya Unit II 6.000
PT. Bama Pratama Adijaya 6.000
PT. Sisilia Claudia 6.000
PT. Sumber Kayu Utama 5.000
29.000
Kota Jayapura PT. Datonan Jaya Perkasa 5.000
PT. Mansinam Global Mandiri Unit I 6.000 PT. Mansinam Global Mandiri Unit III 6.000
PT. Sijas Express Unit I 6.000
PT. Victory Cemerlang Unit I 6.000
PT. Victory Cemerlang Unit II 6.000
PT.Sisilia Claudia Unit II 6.000
Total Kapasitas Produksi Per tahun
Tabel 10 Kapasitas produksi kayu gergajian per tahun IUIPHHK di Kab. Jayapura, Kota Jayapura dan Kab. Keerom
Sumber : Laporan BP2HP Wilayah XVII bulan Juni tahun 2009.
Target pengolahan kayu ke-22 industri ini adalah kayu merbau, dengan
ijin produksi kayu gergajian. Ijin produksi woorworking dan moulding hanya
ada di kabupaten Biak dan Yapen, yaitu PT. Wapoga Mutiara Indutries di Biak
dengan kapasitas produksi 30 ribu m3 dan PT. Sinar Wijaya di Yapen dengan
kapasitas produksi 14,4 ribu m3 per tahun.
4.1.1. 2 Produksi dan Pemasaran Kayu Gergajian dan Woodworking Merbau
Produksi kayu olahan merbau Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan
Kabupaten Keerom dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 berfluktuasi
dengan produksi tertinggi dicapai pada tahun 2007 (Tabel 12). Produksi Kayu
bulat sebagai bahan baku industri pada periode yang sama menunjukkan
31 tercapai pada tahun 2004 yang kemudian menurun menjadi 40,6 ribu m3 pada
tahun 2007.
Berdasarkan kondisi industri di lapangan, data yang ditampilkan pada
Tabel 12 ini tidak menujukkan kenyataan yang sebenarnya. Berdasarkan total
produksi kayu bulat merbau dan total produksi kayu olahan pada periode
tersebut, maka jumlah kayu bulat yang dibutuhkan berdasarkan rendemen
produksi masing-masing industri adalah 432 ribu m3, sementara jumlah
produksi kayu bulat pada periode yang sama adalah 265 ribu m3, sehingga ada
selisih jumlah kayu bulat sebesar 167 ribu m3.
Tabel 11 Kapasitas ijin dan Produksi kayu gergajian merbau Kab. Jayapura, Kota Jayapura dan Kab. Keerom.
Peningkatan produksi ini seiring dengan peningkatan ijin kapasitas
produksi per tahun industri primer hasil hutan kayu yang dikeluarkan (Tabel
11). Kapasitas produksi industri primer hasil hutan dari tahun 2004 sampai
dengan 2008 terus mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2009 sampai Sumber : Dinas Kehutanan Propinsi Papua, BPPHP Wilayah XVII Jayapura, Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura, PT. Sumber Kayu Utama dan PT. Mansinam Global Mandiri. Data Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura meliputi data produksi industri penggergajian yang beroperasi pada lingkup kerja dinas kabupaten Keerom dan kota Jayapura.
2004 2005 2006 2007 2008
AAC Kayu Bulat
Kab. Jayapura 288.307 288.307 288.307 288.307 288.307 Kab. Keerom 383.769 383.769 383.769 383.769 383.769 Kota Jayapura
672.076 672.076 672.076 672.076 672.076 Potensi Merbau 273.514 273.514 273.514 273.514 273.514 Produksi Kayu Bulat Merbau
Kab. Jayapura 129.375 31.866 9.169 30.701 21.301
Kab. Keerom 23.452 19.366
Kota Jayapura
129.375 31.866 9.169 54.153 40.666 Kapasitas Ijin Industri
Kab. Jayapura 41.200 36.000 30.000 34.000
Kab. Keerom 17.000 12.000 18.000 11.000
Kota Jayapura 30.000 6.000 18.000 18.000 41.000 30.000 64.200 66.000 66.000 86.000 Produksi Kayu Gergajian
Kab. Jayapura 10.922 26.593 32.659 29.266 25.220
Kab. Keerom 0 0 0 6.856 6.495
Kota Jayapura 0 0 2.260 406 0
10.922 26.593 34.918 36.528 31.715 Utilization Rate Kapasitas Ijin dan Produksi K 36% 41% 53% 55% 37%