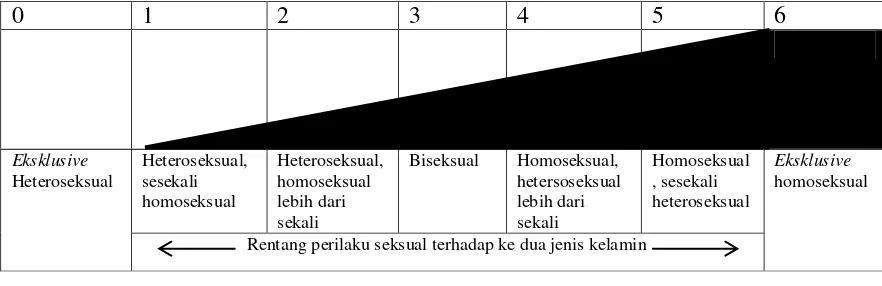Pada penelitian ini digunakan beberapa teori, yaitu teori tentang
kecemasan, teori mengenai Eudaimonic Well-Being, teori tentang perilaku seksual berkaitan dengan perilaku seks sejenis, teori mengenai M-S-M (Men who have Sex with Men), dan kemudian diakhiri dengan dinamika keseluruhan teori yang digunakan.
A. Kecemasan
A.1. Definisi Kecemasan
Banyak definisi kecemasan yang dikemukakan oleh para ahli. Kecemasan
dapat didefenisikan sebagai suatu keadaan perasaan gelisah, ketidaktentuan, takut
dari kenyataan atau persepsi ancaman sumber aktual yang tidak diketahui atau
dikenal (Stuart and Sundeens, 1998). Kecemasan adalah respon terhadap suatu
ancaman yang sumbernya tidak diketahui, internal, samar-samar atau bersifat
konfliktual (Kaplan & Sadock, 1997). Selain itu, Taylor (1953) mengemukakan
bahwa kecemasan merupakan suatu perasaan subyektif mengenai ketegangan
mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum dari ketidakmampuan
mengatasi suatu masalah atau tidak adanya rasa aman.
Kecemasan bersinonim dengan rasa takut, akan tetapi kecemasan memiliki
bahwa rasa takut hanya terjadi terhadap sesuatu hal di luar manusia, sedangkan
kecemasan dapat muncul dari luar diri individu maupun dari dalam dirinya
sendiri. Kecemasan yang muncul dari dalam diri sendiri umumnya muncul karena
adanya suatu konflik. Hal ini sesuai dengan Definisi kecemasan yang
diungkapkan oleh Dradjat (2003), yakni suatu manifestasi berbagai masalah emosi
yang bercampur baur, yang terjadi ketika seseorang mengalami tekanan perasaan
dan pertentangan batin.
Freud (dalam Hall, 1995) mengungkapkan bahwa kecemasan merupakan
hasil dari konflik psikis yang tidak disadari. Ketika mekanisme diri berhasil,
kecemasan menurun dan rasa aman datang lagi. Namun, bila konflik terus
berkepanjangan, maka kecemasan ada pada tingkat tinggi. Menurut Freud (dalam
Brintha & Ramakrishnan, 2013), kecemasan adalah konsekuensi dari pertentangan
kebutuhan, terutama frustrasi yang terjadi di situasi konflik. Teori Freud juga
mengatakan bahwa seseorang sebagian besar tidak menyadari sumber atau
penyebab kecemasan, tetapi sebetulnya dapat diidentifikasi dengan cara melihat
riwayat hidupnya. Dalam teori Freud, kecemasan yang bersumber dari konflik
batin yang terkait dengan pertentangan id dan superego dapat muncul dalam wujud perasaan bersalah dan malu.
Spielberg menyatakan bahwa kecemasan bisa dikarenakan dua hal, yaitu
faktor situasi yang menyebabkan konflik atau faktor kepribadian yang memang
cenderung pencemas (dalam McDowell, 2006). Dari kedua hal tersebut, Spielberg
sumber kecemasannya dari karakter pribadi. Situasi-situasi yang dimaksudkan
dalam state anxiety, tidak hanya berbicara dari faktor dari luar, tetapi juga kondisi yang sedang dialami oleh seseorang berkaitan dengan suatu hal, misalnya
kegagalan, tekanan, kekhawatiran, perasaan tidak aman, dan konflik-konflik.
Semua ini dialami dalam tingkat yang berbeda oleh setiap individu. Dari kedua
jenis tersebut, mengukur trait anxiety juga dapat dipakai untuk melihat apakah seseorang memiliki gangguan kecemasan atau tidak (Spielberg, dalam McDowell,
2006).
Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecemasan
adalah suatu perasaan yang tidak menyenangkan yang muncul secara samar tanpa
diketahui penyebab yang jelas sebagai suatu respon terhadap tekanan perasaan,
perasaan tidak aman, perasaan bersalah dan malu akibat konflik-konflik
ketegangan dalam diri individu, yang ditandai dengan adanya kekhawatiran atau
rasa takut dan hal ini dialami dalam tingkatan yang berbeda-beda oleh setiap
individu.
A.2. Jenis-jenis Kecemasan
Ada tiga jenis kecemasan yang dikemukakan oleh Freud, yakni kecemasan
realistis, kecemasan neurotis, dan kecemasan moral (dalam Feist and Feist, 2009).
Egolah yang dapat membentuk perasaan kecemasan, tetapi ketiga komponen,
yakni id, ego, dan superego berperan dalam ketiga jenis konflik yang dikemukakan oleh Freud tersebut (Feist and Feist, 2009). Antara ketiga
menyenangkan. Perbedaannya hanya terletak pada sumber penyebabnya (Hall,
1995).
1. Kecemasan realistis. Kecemasan ini disebut juga sebagai kecemasan akan
kenyataan yaitu suatu pengalaman perasaan akibat adanya suatu bahaya
dalam dunia luar. Bahaya tersebut adalah setiap keadaan dalam lingkungan
seseorang yang mengancam untuk mencelakakannya.
2. Kecemasan neurotis. Kecemasan ini ditimbulkan oleh suatu pengamatan
tentang bahaya dari naluri-naluri. Kecemasan ini juga sering dihasilkan
bila impuls id ingin ditampilkan, akan tetapi ledakannya di kontrol oleh
ego. Salah satu jenis kecemasan ini adalah ketakutan yang menegangkan dan tidak irasional, yakni phobia.
3. Kecemasan moral. Kecemasan ini muncul dalam bentuk perasaan bersalah
atau malu yang ditimbulkan oleh suatu pengamatan mengenai bahaya dari
hati nurani. Pada kecemasan ini, seseorang tidak dapat hidup leluasa dalam
standar moralnya atau berlawanan terhadap suatu perilaku yang dikatakan
tidak etis. Pada kasus ini ego mengingatkan terjadinya suatu kemungkinan pembalasan dari super ego. Sumber kecemasan ini adalah pertentangan yang terjadi dalam diri individu, yakni antara id dan superego.
Pertentangan ini sifatnya intra-psikis, yang berarti bahwa hal ini
merupakan pertentangan struktural dan tidak menyangkut paut hubungan
antara dirinya dengan dunia melainkan dengan nilai-nilai yang dianut oleh
Selain jenis kecemasan yang diungkapkan oleh Freud, Spielberg (dalam
Carducci, 2009) juga membagi kecemasan dalam dua bentuk, antara lain :
1. Kecemasan sesaat (state anxiety) merupakan reaksi emosi sementara yang timbul pada situasi tertentu yang dirasakan sebagai suatu ancaman. Reaksi
ini bersifat subjektif, dirasakan dengan sadar, perasaan tegang, gelisah dan
aktifnya sistem saraf otonom. Penilaian terhadap stimulus (situasi) yang
dianggap mengancam dipengaruhi oleh sikap, kemampuan, pengalaman
masa lalu dan kecemasan dasar. Kecemasan ini juga mengacu pada
keadaan “sekarang dan pada saat ini.”
2. Kecemasan dasar (trait anxiety) merupakan ciri atau sifat seseorang yang cukup stabil yang mengarahkan seseorang dalam menginterpretasikan
suatu keadaan yang mengancam. Trait anxiety sifatnya bawaan dan berbeda pada tiap individu. Seseorang yang memiliki trait anxiety yang tinggi memiliki kecenderungan yang tinggi pula dalam menanggapi suatu
situasi sebagai ancaman. Kecemasan ini adalah kecemasan yang secara
umum dialami oleh seseorang sepanjang hidupnya.
A.3. Faktor-faktor Penyebab Kecemasan
Kecemasan memiliki banyak faktor penyebab dan tidak datang dengan
sendirinya. Berikut ini adalah beberapa penyebab kecemasan:
1. Kecemasan objektif, merupakan kecemasan akan bahaya sesungguhnya
yang datangnya dari lingkungan atau dunia luar yang dapat mengancam
2. Kecemasan hati nurani, merupakan kecemasan yang timbul apabila
individu mengerjakan perbuatan yang berlawanan dengan moralitas
(Freud, dalam Hall, 1995). Lemahnya ego akan menyebabkan ancaman yang memicu munculnya kecemasan (Ardnt, 1974). Freud berpendapat
bahwa sumber ancaman terhadap ego berasal dari dorongan yang bersifat
insting dari id dan tuntutan - tuntutan dari superego. Freud (dalam Hall, 1995) menyatakan bahwa mengontrol arah tindakan, memilih segi - segi
lingkungan ke mana ia akan memberi respon dan memutuskan insting -
insting manakah yang akan dipuaskan dan bagaimana caranya. Dalam
melaksanakan fungsi – fungsi eksekutif ini ego harus berusaha mengintegrasikan tuntutan - tuntutan id, superego, dan dunia luar sering menimbulkan tegangan berat pada ego dan menyebabkan timbulnya kecemasan.
3. Kecemasan neurotik, merupakan kecemasan yang berasal dari tubuh
karena takut hukuman akibat telah dilakukan pemuasan insting (Freud, dalam Hall, 1995).
4. Kecemasan sosial, merupakan kecemasan yang timbul bila individu takut
pendapat umum atau pendapat lingkungannya mencela perbuatannya
(Binder dan Kielholzt, dalam Trismiati, 2006).
5. Kecemasan berbeda tingkatannya pada intensitas perilaku. Ketika
seseorang melakukan suatu perilaku amoral secara berulang, maka
kebahagiaan yang diperoleh dari aktivitas tersebut akan meredam rasa
2008). Hal ini sejalan dengan teori belajar mengenai habituasi, James W.
(2009), seorang psikolog menulis bahwa habituasi merupakan penurunan
respon/tanggapan terhadap rangsangan/stimulus yang diberikan, dan tidak
dijumpai perubahan pada rangsangan lain selain dari rangsangan yang
diberikan.
A.4. Indikator Kecemasan
Spielberg (dalam Marteau dan Bekker, 1992) membuat dua indikator
kecemasan, yakni Anxiety Present dan Anxiety Absent.
Anxiety Present yakni indikator hadirnya tanda-tanda kecemasan. Adapun tanda tanda kecemasan tersebut berupa perasaan yang dialami oleh seseorang
seperti:
1. Merasa resah terhadap apa yang ia lakukan
2. Stres dengan tindakannya
3. Kesal terhadap diri sendiri
4. Cemas terhadap nasib
5. Takut dengan apa yang ia lakukan dan yang akan terjadi.
6. Perasaan gugup dengan sekitarnya
7. Timbulnya perasaan gelisah
8. Bimbang dengan perilakunya
9. Kebingungan dengan pilihan
Anxiety absent, adalah indikator yang sebaliknya, dimana kehadiran perasaan-perasaan seperti ini memperlihatkan bahwa tidak adanya kecemasan
pada seseorang. Tanda-tanda tersebut adalah kebalikan dari tanda-tanda present,
yaitu:
1. Ketenangan setelah melakukan sesuatu
2. Tidak adanya perasaan khawatir
3. Perasaan lega
4. Kepuasan dalam melakukan tindakan
5. Tetap merasa nyaman
6. Tetap percaya diri
7. Rileks dengan tindakannya
8. Yakin dengan pilihannya
9. Mengetahui bahwa apapun yang dilakukan adalah sesuai keinginannya
10.Hadirnya perasaan senang
A.5. Jangka Waktu Kecemasan Umum
Menurut DSM IV, kecemasan umumnya terjadi selama kurang dari enam
bulan, yang mana jika telah terjadi lebih dari enam bulan sudah dapat dinyatakan
sebagai gangguan, yakni generality anxiety disorder. Selain itu, yang membedakan kecemasan umum dengan gangguan kecemasan umum adalah pada
gejalanya, yang mana pada gangguan kecemasan memiliki gejala ketakutan yang
berlebihan dan intens selama berbulan-bulan yang tidak hanya menonjol pada saat
penyebab yang pasti, tetapi menimbulkan kehawatiran di segala sisi
kehidupannya. Pada penelitian ini, kecemasan yang dimaksud bukanlah gangguan
kecemasan, melainkan kecemasan umum yang terkait dengan suatu situasi
tertentu yang menjadi sumber kecemasan.
B. Eudaimonic Well-Being
B.1. Definisi Eudaimonic Well-Being
Eudaimonic Well-Being fokus pada realisasi diri, dimana kesejahteraan dipandang dari sejauh mana seseorang telah berfungsi sepenuhnya (Lazarus and
Folkman, dalam Ryan and Deci 2001). Filosofi eudomonism mendefinisikan bahwa tindakan yang tepat akan membawa seseorang menuju kesejahteraan.
Aristoteles menyatakan bahwa seseorang akan menemukan kebahagiaan dalam
mengekspresikan kebajikan dan dalam melakukan apa yang layak untuk
dilakukan sesuai dengan prinsip yang ia pegang (Ryan & Deci, 2001).
Kebahagiaan memiliki dua perspektif dasar yang menentukannya.
Pandangan pertama adalah hedomonic dan pandangan yang kedua adalah
eudaimonic. Keduanya berfokus pada kebahagiaan yang dialami oleh individu. Akan tetapi, eudaimonic yang dipakai selanjutnya dalam penelitian ini berbeda dengan hedomonic. Hedomonic memandang tujuan hidup yang utama adalah mendapatkan kenikmatan secara optimal, atau dengan kata lain, yakni mencapai
kebahagiaan. Jenis kebahagiaan ini fokus mencapai kepuasan hidup dengan
Berbeda dengan konsep hedomonic, Waterman (1993) menyatakan bahwa konsepsi well-being dalam pandangan eudaimonic menekankan pada bagaimana cara manusia untuk hidup dalam daimon-nya, atau dirinya yang sejati (true self). Diri yang sejati itu terjadi ketika manusia melakukan aktivitas yang paling
kongruen atau sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan dilakukan secara
menyeluruh serta benar-benar terlibat di dalamnya (fully engaged) (Ryan & Deci, 2001). Oleh karena itu, Eudaimonic Well-Being mengacu pada kualitas hidup yang berasal dari perkembangan potensi terbaik seseorang dan aplikasi yang
bertujuan untuk pemenuhan ekspresi pribadi serta kesesuaian dengan tujuan hidup
(Waterman, 2010).
Mengejar keunggulan dan relisasi diri merupakan sifat-sifat khusus yang
mencerminkan fungsi eudaimonic. Selain itu, perasaan menikmati setiap kegiatan yang ia lakukan dan kemampuan untuk terus mengekspresikan pribadi adalah
pengalaman subjektif dari eudaimonia (Waterman et al, 2010). Teori eudaimonic
menyatakan bahwa kualitas hidup individu juga terletak pada kemampuan
individu mengidentifikasi bakat-bakat mereka serta tindakan mengembangkannya
untuk memperoleh tujuan dan makna hidup. Memilih tindakan yang paling sesuai
dengan diri sendiri akan menimbulkan perasaan eudaimonia. Waterman (2010)
mengemukakan bahwa ada enam komponen yang saling terkait dalam
Eudaimonic Well-Being, yakni: (1) penemuan diri, (2) pengembangan potensi terbaik yang dimiliki seseorang, (3) adanya tujuan yang berarti dalam hidup, (4)
usaha yang dituangkan dalam mengejar keunggulan, (5) keterlibatan intens dalam
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Eudaimonic Well-Being adalah kualitas hidup yang diperoleh dari pengembangan potensi terbaik yang dimiliki oleh seseorang sesuai dengan tujuan hidupnya, yang mana hal ini
dicapai dengan adanya pengenalan akan diri sendiri terkait potensi diri dan
pengembangannya, memiliki tujuan hidup, bersifat aktif, terlibat dalam kegiatan
yang sesuai, dan menikmati setiap keterlibatan pada kegiatan. Eudaimonic Well-Being mengacu pada bagaimana seseorang mengatasi tantangan dalam kehidupan serta menentukan tindakan yang paling sesuai dalam setiap hal yang mengganggu
kehidupannya.
B.2. Komponen Eudaimonic Well-Being
Berikut ini adalah enam komponen dalam Eudaimonic Well-Being yang dikemukakan oleh Waterman (2010):
1. Self discovery
Eudaimonism menekankan bahwa setiap orang harus mampu mengenali
dirinya dan hidup sesuai dengan daimonnya, yaitu diri yang sejati. Hal ini
bertujuan untuk membantu usaha dalam menuju realisasi diri. Seseorang harus
menyadari dirinya dalam tipe pribadi yang seperti apa dalam menjalani
kehidupannya. Pernyataan yang mengacu pada komponen ini dapat berupa “Saya
2. Perceived development one’s best potentials
Salah satu elemen penting dalam Eudaimonic Well-Being adalah mengenali potensi unik yang terbaik yang dimilikinya. Hal ini tidak berhenti pada
identifikasi potensi, tetapi juga keaktifan dalam usaha pengembangan potensi
tersebut agar berfungsi sepenuhnya. Pernyataan dalam komponen ini berupa
“Saya mengetahui potensi terbaik yang saya miliki dan saya mencoba
mengembangkannya di setiap kesempatan yang memungkinkan.”
3. A Sense of Purpose and Meaning in Life
Pada komponen ini seseorang mampu mengidentifikasi potensi diri yang
ia miliki dan tindakan mengembangkannya. Akan tetapi, potensi yang
dikembangkan lebih mengacu pada kesesuaian dengan tujuan hidup yang
memberikan makna bagi hidupnya. Dalam mengalami Eudaimonic Well-Being, individu harus menerapkan keterampilan dalam mengejar tujuan hidup yang
bermakna. Pernyataan dalam komponen ini berupa “Saya bisa berkata bahwa saya
telah menemukan tujuan hidup saya.”
4. Investment of Significant Effort in Persuit of Excellence.
Bukanlah suatu hal yang mudah dalam mencapai keunggulan. Realisasi
diri muncul dengan sendirinya sehingga membutuhkan upaya yang lebih untuk
mencapainya. Upaya yang maksimal yakni dilakukan dengan cara memfungsikan
Waterman menemukan bahwa ada hubungan yang postif antar Eudaimonic Well-Being dengan tingkat usaha yang diinvestasikannya dalam keterlibatan kegiatan.
5. Intense Involvement in Activities
Ketika seseorang menemukan kegiatan yang bermakna dan sesuai dengan
tujuan hidupnya, maka keterlibatannya juga harusnya lebih tinggi terhadap
kegiatan tersebut dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Seseorang akan
menemukan perasaan eudaimonia ketika menemukan kegiatan yang
membutuhkan bakat dan keterampilannya.
6. Enjoyment of Activities as Personally Expressive
Salah satu aspek paling jelas dalam menDefinisikan Eudaimonic Well-Being adalah pengalaman langsung berupa rasa bahagia dalam kegiatan yang dikerjakan. Seseorang yang mengalami Eudaimonic Well-Being harus merasakan bahwa apa yang mereka lakukan dalam hidup adalah ekspresi dari pribadi siapa
diri mereka sesungguhnya.
B.3. Aspek Eudaimonic Well-Being
Selain enam komponen yang disampaikan oleh Waterman, beberapa
peneliti lain, seperti Schutee, Wissing, dan Khumalo membuat sebuah analisis
faktor pada alat ukur Eudaimonic Well-Being Waterman pada tahun 2013. Pada penelitian tersebut, mereka menemukan adanya tiga aspek utama dalam variabel
1. Sense of Purpose (SoP) yaitu aspek yang berfokus pada sejauh mana seseorang mengenali dirinya (self knowledge) dan kebermaknaan suatu tujuan hidup dalam dirinya. Kebermaknaan tujuan hidup sejalan dengan
bagaimana seseorang mempersepsikan makna hidupnya. Hal ini sejalan
dengan konstruk makna hidup yang disampaikan Ryff (1989) yakni
adanya tujuan hidup, arah yang jelas, dan intensitas dalam pencapaiannya.
2. Purposeful Personal Exvressiveness (PPE) yaitu aspek yang fokus pada keaktifan seseorang secara penuh pada setiap aktivitas yang bermakna dan
bertujuan. Hal ini juga terkait dengan afeksi atau perasaan menikmati
setiap kegiatan yang mengekspresikan kepribadiannya serta usaha yang
dilakukan dalam pengembangan potensi. Aspek ini juga sejalan dengan
motivasi intrinsik dari teori self-determination yang dikemukakan oleh Ryan (2008), yakni adanya ketertarikan, otonomi, dan pengekspresian diri
pada setiap aktivitas yang dilakukannya.
3. Effortful Engagement (EE) yaitu aspek yang mengacu pada bagaimana seseorang memiliki suatu harapan sehingga menimbulkan upaya dalam
setiap kegiatan yang memungkinkan dalam pencapaian harapan tersebut,
sekalipun hal tersebut sulit. Tanggung jawab dalam pencapaian akan
berkebalikan dengan sifat menyerah dan mengikuti arus kehidupan. Aspek
ini berkaitan dengan optimalisasi diri di setiap pengalaman (Delle Fave
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Schutee, dkk. (2013) ditemukan
bahwa ketiga aspek tersebut memiliki korelasi negatif dengan ketiadaan makna
hidup pada alat ukur kebermaknaan hidup. Hal ini berarti bahwa mereka yang
belum mampu mengenali dirinya atau yang masih berada pada tahap pencarian
makna hidup belum memiliki tingkat SoP, PPE, dan EE yang baik. Termasuk mereka yang mengalami konflik batin karena belum mampu memilih hal yang
sesuai dengan dirinya.
B.4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Eudaimonic Well-Being
Dari penelitian yang dilakukan oleh Waterman, dkk. (2010) terkait dengan
alat ukur Eudaimonic Well-Being dengan beberapa demograpik maka ditemukan beberapa kondisi Eudaimonic yang berbeda pada kondisi berikut ini:
1. Gender. Pada aitem ini, ditemukan bahwa mereka yang berjenis kelamin perempuan memiliki tingkat Eudaimonic Well-Being dibandingkan dengan laki-laki.
2. Usia. Secara umum ditemukan bahwa orang-orang yang berusia tiga puluh tahun atau lebih memiliki tingkat EWB yang lebih baik dibandingkan tingkat usia lainnya. Di samping itu mereka yang berusia di kisaran 18-19
tahun memiliki tingkat Eudaimonic Well-Being yang lebih rendah. Akan tetapi, meskipun berbeda, hal ini tidak menjadi faktor penentu apakah usia
3. Etnis. Penelitian Waterman dilakukan pada empat kelompok etnis, yakni
etnis Spanyol, kulit hitam, kulit putih, dan orang Asia. Dari hasil
ditemukan bahwa ada perbedaan kecil dari keempat etnis tersebut, tetapi
tidak signifikan.
4. Pendapatan Keluarga. Pada aitem ini ditemukan bahwa mereka yang
berpenghasilan menengah memiliki tingkat EWB yang lebih baik dibandingkan mereka yang memiliki pendapatan yang rendah dan
pendapatan yang lebih tinggi.
5. Struktur Keluarga. Mereka yang terlahir di keluarga yang bercerai secara
umum memiliki tingkat EWB yang lebih rendah dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga yang utuh, keluarga yang single parent akibat kematian, dan lainnya.
Selain ke lima perbandingan demograpik di atas, dari penelitian Waterman
dkk. (2010) ditemukan bahwa tingkat Eudaimonic Well-Being berkebalikan dengan kondisi psikologis yang negatif, misalnya depresi, kecemasan umum, dan
kecemasan sosial. Masing-masing nilai korelasi antara EWB dengan depresi, kecemasan umum, dan kecemasan sosial adalah -0.37, -0,44, dan -0,42. Hal ini
juga sejalan dengan penelitian Schutee, dkk. (2013) yang juga menemukan
korelasi negatif antara EWB dengan kondisi psikologis yang buruk.
Mereka yang mengalami situasi konflik juga menandakan bahwa seorang
(Waterman, 2010). Oleh sebab itu, kondisi konflik juga salah satu yang
memengaruhi tingkat EWB yang rendah.
C. Perilaku Seksual M-S-M (Men Who Have Sex with Men)
C.1. Perilaku Seksual
Argyo (2012) menyatakan setiap manusia mempunyai dorongan seksual
akibat kerja hormon seks. Dorongan seksual muncul atau meningkat bila ada
rangsangan dorongan seksual dari luar, baik yang bersifat psikis maupun fisik.
Apabila dorongan seksual tersebut muncul maka akan terjadi ketegangan seksual
yang kemudian memerlukan penyaluran dalam bentuk tingkah laku seksual
tertentu. Hal inilah yang disebut sebagai perilaku seksual. Perilaku seksual
merupakan perilaku yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk
mendapatkan kesenangan organ seksual melalui berbagai perilaku (Feldman dan
Parrot dalam Argyo, 2012).
Menurut Hurlock (2004) manifestasi dorongan seksual dalam perilaku
seksual dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu
stimulus yang berasal dari dalam individu berupa bekerjanya hormon-hormon
reproduksi, dimana hormon tersebut menuntut pemuasan. Sedangkan faktor
eksternal yaitu stimulus yang berasal dari luar individu yang menimbulkan
dorongan seksual sehingga memunculkan perilaku seksual. Argyo (2012)
menyatakan bahwa perilaku seksual terjadi dalam beberapa tahapan, yaitu
Perilaku seksual bukanlah perilaku yang hanya dilakukan terhadap lawan
jenis kelamin. Sarwono (2008) menDefinisikan perilaku seksual sebagai segala
tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya
maupun dengan sesama jenis. Beberapa perempuan teridentifikasi melakukan
hubungan seksual dengan perempuan dan laki-laki berhubungan seksual dengan
laki-laki (Carroll, 2005). Akan tetapi, Vohs dan teman-temannya (dalam Miller &
Perlman, 2009) mengungkapkan bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang
lebih tinggi dibandingkan perempuan sehingga frekuensi laki-laki yang
melakukan hubungan seksual dengan laki-laki juga lebih tinggi dibandingkan
dengan perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan.
Huwller (1998) menyebutkan bahwa orang-orang yang melakukan
hubungan seksual dengan sesama jenisnya dikategorikan beorientasi
homoseksual. Laki-laki dengan sejenisnya disebut gay dan perempuan dengan
sejenisnya disebut lesbian. Akan tetapi, cukup banyak laki-laki yang berhubungan
seks dengan sejenisnya tidak mau mengidentifikasi diri sebagai gay (Argyo,
2012). Argyo menjelaskan bahwa identitas diri tidak ada hubungannya dengan
perilaku seksual yang dilakukan dengan pasangan seksual berjenis kelamin sama.
Argyo mengadopsi konsep Kinsey mengenai fenomena tersebut, yang
mana tidak menitikberatkan pada orientasi seksual. Kinsey (1948) memaparkan
dalam penelitiannya bahwa seorang homoseksual memiliki kemungkinan
melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya demikian pula bahwa
dengan sesama jenisnya. Jadi, bukan berarti pengalaman perilaku seksual tersebut
mengindikasikan orientasi seksual mereka.
C.2. Konsep Kinsey Mengenai Pengalaman Perilaku Seksual
Skala Kinsey mendeskripsikan tentang sejarah seksual seseorang dalam
waktu tertentu. Skala ini diperkenalkan oleh Kinsey dengan rekannya, Pomeroy
dan Martin, dalam jurnal perilaku seksual pada laki-laki (1948). Berikut gambar
skala tersebut:
Gambar 2.1
Dari skala yang dibuat oleh Kinsey dan rekannya, maka perilaku seksual
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
0. Mengindikasikan bahwa seseorang sepenuhnya hanya memiliki
pengalaman seksual terhadap lawan jenis (ekslusive heteroseksual). 1. Mengindikasikan seseorang yang secara dominan melakukan
hubungan seksual dengan lawan jenis, tetapi terdapat sekali
pengalaman seksual terhadap sesama jenis.
0 1 2 3 4 5 6
Eksklusive Heteroseksual Heteroseksual, sesekali homoseksual Heteroseksual, homoseksual lebih dari sekali
Biseksual Homoseksual, hetersoseksual lebih dari sekali Homoseksual , sesekali heteroseksual Eksklusive homoseksual
2. Mengindikasikan seseorang yang dominan melakukan hubungan
seksual dengan lawan jenis, tetapi terdapat lebih dari sekali
pengalaman seksual terhadap sesama jenis.
3. Mengindikasikan seseorang yang memiliki pengalaman seksual
seimbang baik terhadap lawan jenis maupun sesama jenis.
4. Mengindikasikan seseorang yang dominan memiliki pengalaman
seksual dengan sesama jenis, tetapi terdapat lebih dari sekali
pengalaman dengan lawan jenis.
5. Mengindikasikan seseorang yang dominan memiliki pengalaman
seksual terhadap sesama jenis, tetapi terdapat sekali pengalaman
seksual dengan lawan jenis.
6. Mengindikasikan bahwa seseorang sepenuhnya memiliki pengalaman
seksual hanya terhadap sesama jenis (eksklusive homoseksual)
Skala tersebut merupakan indikator dalam penelitian yang dilakukan oleh
Kinsey bersama rekannya yang didasarkan pada pengalaman seksual. Skala
tersebut merupakan metode yang murni untuk memperoleh informasi berdasarkan
evaluasi subjek terhadap dirinya sendiri. Kinsey melakukan penelitian tersebut
bukan bertujuan untuk menentukan orientasi seksual seseorang karena adanya
pemikiran bahwa perilaku seksual, sikap, dan perasaan seserorang terhadap orang
C.3. M-S-M (Men who have Sex with Men)
Argyo (2012) menjelaskan bahwa M-S-M dimaksudkan untuk menjelaskan semua laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, tanpa memandang
identitas seksual mereka. Hal ini digunakan karena hanya beberapa yang terlibat
dalam perilaku seks sesama jenis didefinisikan sebagai gay atau biseksual.
Mereka tidak menganggap hubungan seksual mereka dengan laki-laki lain dalam
terminologi identitas atau orientasi seksual.
M-S-M (Men who have Sex with Men) adalah istilah yang digunakan pada laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang tidak
diidentifikasi mengenai orientasi seksual mereka baik sebagai gay, biseksual,
ataupun straight (UNAIDS, 2006). Kort (dalam straight guise, 2006) menyatakan bahwa sering sekali laki-laki mengaku pernah melakukan hubungan seksual
dengan laki-laki, tetapi tidak merasa dirinya sebagai gay ataupun biseksual. Kort
(2013) menjelaskan bahwa ada beberapa alasan dan dasar yang mendorong
terjadinya hubungan seksual antar sesama laki-laki tersebut. Berikut ini adalah
alasan yang disebutkan oleh Kort:
1. Childhood sexual abuse. Keadaan yang disebabkan oleh pengalaman pelecehan seksual di masa kanak-kanak. Orang-orang seperti ini
sebetulnya tidak memiliki orientasi homoseksual. Laki-laki tersebut
tidak memiliki hasrat seksual ataupun terangsang oleh laki-laki lain.
Namun, mereka secara kompulsif menghidupkan kembali pengalaman
2. Sex Work/ escorting. Sebagian laki-laki, bahkan straight sekalipun, rela melakukan hubungan seksual sesama jenis untuk mendapatkan
imbalan finansial. Meskipun mereka terangsang dalam melakukan
hubungan seksual, mereka bukan berarti terangsang karena
pasangannya melainkan dengan kegiatan seksual itu sendiri.
3. Laki-laki yang malu melakukan variasi seksual dengan perempuan.
Kelompok ini adalah laki-laki yang memiliki fantasi yang “agak
memalukan” jika dilakukan dengan perempuan, misalnya melakukan
seks oral, ataupun menggunakan benda-benda tertentu, sehingga
mereka melarikan keinginan tersebut untuk melakukannya dengan
laki-laki gay yang dengan senang hati melakukannya.
4. First Sexual Experience. Sebagian laki-laki pernah melakukan hubungan seksual dengan coba-coba. Pengalaman tersebut biasanya
terjadi di usia remaja dan dilakukan terhadap sesama laki-laki karena
adanya rasa penasaran.
5. Availability/Opportunity. Laki-laki pada kelompok ini memiliki nafsu seksual yang sangat tinggi dan sangat mudah terangsang. Mereka
memilih untuk melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang
dapat dilakukan dengan gampang dan mudah tanpa harus ada ikatan
emosi.
dewasa seakan-akan menjadi cara mendapatkan perhatian yang
didambakan.
7. Narcissism. Kelompok laki-laki yang mengagumi diri mereka sendiri secara berlebihan. Mereka menginginkan perhatian dan pengakuan
ekstra dari lingkungan. Mereka melakukan hubungan seksual dengan
laki-laki hanya untuk memperoleh kepuasan dengan perasaan bahwa
mereka sangat diinginkan dan dipuja secara berlebihan.
8. Sexual Addiction. Ketagihan seksual yang dialami oleh seseorang dapat juga menimbulkan perilaku seks terhadap sesama jenis.
9. Cuckolding. Hal ini terjadi pada laki-laki yang memiliki pasangan perempuan, dimana laki-laki tersebut terangsang ketika melihat
pasangan wanitanya disetubuhi oleh laki-laki lain yang lebih perkasa.
Umumnya, laki-laki tersebut terlibat, seperti menyentuh dan meraba
laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan pasangan
wanitanya.
10.Laki-laki penghuni penjara. Laki-laki yang melakukan hubungan
seksual dengan laki-laki karena hanya menjadi satu-satunya pilihan
menyalurkan hasrat seksual di tempat tersebut.
Beberapa individu dan organisasi lebih suka memakai terminologi M-S-M
karena istilah ini menunjukkan kelompok yang lebih luas dari sejumlah individu
yang berhubungan seks dengan pasangan lain dari kelamin yang sama (Argyo,
sebagian dari kehidupan seks mereka dan tidak menentukan identitas seksual atau
sosial mereka. Laki-laki yang disebut M-S-M adalah sebagai berikut:
1. Laki-laki yang secara eksklusif berhubungan seks dengan laki-laki lain
2. Laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki lain tapi sebagian
besarnya berhubungan seks dengan perempuan
3. Laki-laki yang berhubungan seks baik dengan laki-laki maupun
perempuan tanpa ada perbedaan kesenangan
4. Laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki lain untuk uang atau
karena mereka tidak mempunyai akses untuk melakukan hubungan
seksual dengan perempuan, misalnya di penjara, ketentaraan.
Perilaku seksual, termasuk hubungan seksual dengan sejenis, bisa saja
menimbulkan dampak psikologis seperti perasaan marah, takut, depresi, rendah
diri, bersalah dan berdosa, serta kecemasan (Sarwono, 2003). Hal ini terjadi
karena adanya pengetahuan bahwa perilaku tersebut melanggar nilai dan norma,
baik agama, maupun nilai-nilai yang tertanam dalam masyarakat.
D. Dinamika Kecemasan pada M-S-M dengan Eudaimonic Well-Being (EWB)
Argyo (2012) sejalan dengan teori Kinsey memandang perilaku seksual
sesama laki-laki tidak dititikberatkan pada orientasi seksualnya. Argyo
menyebutnya dengan istilah yang sama dengan Kort, yakni M-S-M. M-S-M
dimaksudkan untuk menjelaskan semua laki-laki yang berhubungan seks dengan
laki-laki, tanpa memandang identitas seksual mereka. Kelompok ini mengacu
berjenis kelamin sama. Akan tetapi, hubungan seksual dengan sejenis seperti yang
dilakukan oleh M-S-M, bisa saja menimbulkan dampak psikologis seperti konflik batin, perasaan marah, takut, depresi, rendah diri, bersalah dan berdosa (Sarwono,
2003). Dampak psikologis lain yang diakibatkan tersebut dapat berupa hadirnya
kecemasan dan juga menurunnya kesejahteraan dalam diri seseorang.
Perilaku seksual M-S-M yang merupakan suatu aktivitas ternyata dapat menyebabkan seorang tidak dapat menikmatinya sepenuhnya. Akan tetapi, hal ini
memang tidak sepenuhnya terjadi pada setiap M-S-M karena beberapa di antara mereka justru tidak bermasalah sama sekali dengan perilaku tersebut. Namun,
bagi mereka yang berkonflik akibat perilaku ini menunjukkan bahwa kondisi
mereka berkebalikan dengan konsep Eudaimonic Well-Being yang dikemukakan oleh Waterman. Waterman memandang bahwa orang-orang yang sudah mampu
menjadi dirinya yang sejati memiliki perasaan menikmati setiap kegiatan yang ia
lakukan dan kemampuan untuk terus mengekspresikan pribadi sebagai
pengalaman subjektif dari eudaimonia (Waterman et al, 2010). Dari situasi tersebut dapat dilihat bahwa orang yang berkonflik dengan perilaku seks sejenis
dengan laki-laki memiliki tingkat EWB yang masih rendah.
Setiap orang memiliki tingkatan yang berbeda-beda dalam kesejahteraan
eudaimonic, berkisar dari yang murni tidak ada sampai pada kesejahteraan
eudaimonic yang sempurna. Eudaimonic Well-Being mengacu pada kualitas hidup seseorang yang ditandai dengan perkembangan potensi terbaik yang dimiliki serta
bagaimana potensi tersebut teraplikasi dalam pengekspresian dirinya dan
tidak berfokus pada perilakunya, tetapi pada kondisi psikologis yang diakibatkan
perilaku tersebut. Jika perilaku tersebut sesuai dengan dirinya maka EWB-nya akan baik-baik saja, tetapi jika tidak sesuai maka EWB akan terganggu.
Demikian pula dengan ketiga aspek Eudaimonic Well-Being, yakni, Sense of Purpose, Purposeful Personal Expressiveness, dan Efforful Engagement.
Sesuai dengan penelitian Schutee, dkk (2013) yang memperlihatkan bahwa ketiga
aspek tersebut berkebalikan dengan kebermaknaan hidup dalam diri seseorang.
Orang-orang yang masih berada pada tahap pencarian makna hidup secara umum
masih diliputi oleh keraguan dalam dirinya dalam menentukan pilihan hidup.
Sehingga kondisi mereka menjadi berkonflik ketika diperhadapkan pada beberapa
hal yang sepertinya sama-sama bernilai dalam diri seseorang. Seorang M-S-M
yang tidak berkonflik dan mantap dalam pilihannya untuk tetap melakukan
hubungan seksual sejenis berarti sudah mampu mengetahui tujuan hidupnya
(SoP), meyakini bahwa aktivitas perilaku M-S-M sesuai dengan tujuan hidup tersebut (PPE), dan berupaya maksimal dalam aktivitasnya (EE).
Selain EWB dan ketiga aspek EWB tersebut yang masih rendah pada M-S-M yang berkonflik, kondisi psikologis yang juga muncul pada mereka adalah hadirnya kecemasan. Kecemasan yang terjadi pada M-S-M terkait dengan perilaku melakukan hubungan seksual dengan laki-laki diistilahkan dengan state anxiety.
Disebut demikian karena kecemasan yang terjadi diakibatkan oleh suatu situasi,
Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kecemasan pada M-S-M.
Pertama, faktor yang dapat menyebakan kecemasan moral. Misalnya, ketika
individu termotivasi untuk mengekspresikan id (perilaku M-S-M) yang berlawanan dengan superego-nya (misalnya nilai-nilai agama dan budaya masyarakat), ia akan merasa malu atau bersalah. Kedua, faktor yang
menyebabkan kecemasan sosial pada M-S-M, yakni berasal dari sudut pandang nilai dan norma yang ada di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Contohnya di
Indonesia, perilaku M-S-M bukanlah suatu hal yang lazim dan dianggap sebagai perilaku sosial yang menyimpang (Musdah, dalam Fajriani, 2013). Ketiga,
berbicara mengenai kecemasan pada M-S-M tidak terlepas dari pandangan bahwa aktivitas seksual tersebut berisiko. Penggunaan anus dan mulut yang digunakan
sebagai alat untuk penetrasi rentan untuk menginfeksi setiap M-S-M (UNAIDS, 2006).
Faktor penyebab kecemasan juga bisa berasal dari intensitas melakukan
perilakunya. Ketika melakukan Hanya Sekali perilaku yang bertentangan dengan
moral akan berbeda kecemasannya dengan yang melakukan secara
berulang-ulang. Konflik yang merujuk pada kecemasan tentu umum terjadi pada M-S-M
ketika melakukan hubungan seksual sejenis, tetapi konflik tersebut bisa teredam
ketika perilaku tersebut terus dipupuk dan dilakukan berulang-ulang. Ketika
seseorang melakukan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma secara
berulang, maka rasa bersalah ataupun konflik akan perilaku tersebut akan
Dari dinamika di atas, Kecemasan akan perilaku M-S-M memiliki kaitan dengan Eudaimonic Well-Being. Sejalan dengan itu, korelasi tersebut dapat digambarkan juga dengan tingkat ketiga aspek EWB, yakni Sense of Purpose (SoP) yang mengacu pada prinsip dan tujuan hidup yang dimiliki oleh seseorang,
Purposeful Personal Expressiveness (PPE) yang merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan tujuan hidupnya, dan Effortful Engagement (EE) yakni keterlibatan dalam aktivitas yang ia lakukan (Schutee, Wissing, dan Khumalo, 2013). Hal ini dapat dijelaskan bahwa masing-masing
variabel dan aspek tersebut terpaut dengan kondisi psikologis yang tidak baik,
seperti konflik. Mereka yang berkonflik mengalami tingkat EWB dan aspek-aspeknya yang rendah disertai dengan adanya kecemasan.
Sekalipun demikian, seorang M-S-M yang mengalami kecemasan tidak dapat dipastikan tidak memiliki kesejahteraan eudaimonic atau sebaliknya. Perilaku tersebut memang bertentangan dengan agama, pandangan masyarakat,
berisiko, dan sebagainya, tetapi hal tersebut bisa saja menjadi suatu aktivitas yang
sesuai dengan internal dirinya sehingga kecemasan yang terjadi mungkin tidak
terkait dengan pilihan untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, untuk
membuktikan lebih jauh fenomena tersebut maka penelitian ini perlu untuk
dilakukan, melihat bahwa asumsi-asumsi tersebut belum sepenuhnya dapat
E. Hipotesa Penelitian
Dari dinamika yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik hipotesis
utama dalam penelitian ini, yakni “Ada korelasi Kecemasan yang diakibatkan
oleh perilaku seks sejenis dengan Eudaimonic Well-Being pada M-S-M (Men who Have Sex with Men).” Korelasi ini bersifat dua arah. Selanjutnya, korelasi tersebut
juga akan dijelaskan dengan gambaran dari ketiga aspek Eudaimonic Well-Being