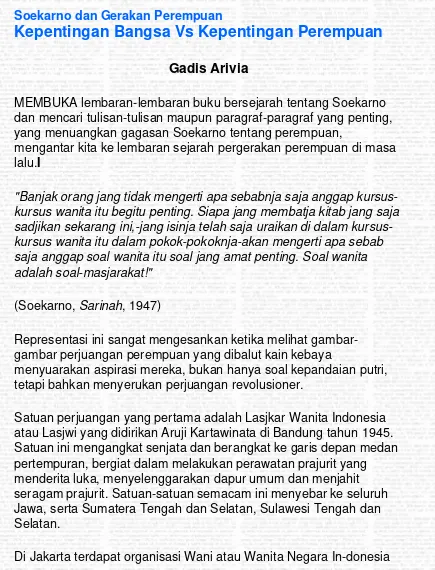>Jumat, 1 Juni 2001
Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran
Soekarno Muda
Baskara Wardaya
Dok Kompas
PADA tanggal 17 Mei 1956 Presiden Soekarno mendapat kehormatan untuk
menyampaikan pidato di
depan Kongres Amerika Serikat dalam rangka
kunjungan resminya ke negeri tersebut. Sebagaimana dilaporkan dalam halaman pertama New York Times pada hari berikutnya, dalam pidato itu dengan gigih Soekarno menyerang kolonialisme. Perjuangan dan pengorbanan yang telah kami lakukan demi pembebasan rakyat kami dari belenggu kolonialisme," kata Bung Karno, "telah berlangsung dari generasi ke generasi selama berabad-abad." Tetapi, tambahnya, perjuangan itu masih belum selesai. "Bagaimana perjuangan itu bisa dikatakan selesai jika jutaan manusia di Asia maupun Afrika masih berada di bawah dominasi kolonial, masih belum bisa menikmati kemerdekaan?" pekik Soekarno di depan para pendengarnya.
negara-negara Barat, ia mendapat sambutan luar biasa di Amerika Serikat (AS). Namun, lebih menarik lagi karena pidato itu menunjukkan konsistensi pemikiran dan sikap-sikap Bung Karno. Sebagaimana kita tahu, kuatnya semangat antikolonialisme dalam pidato itu bukanlah merupakan hal baru bagi Bung Karno. Bahkan sejak masa mudanya, terutama pada periode tahun 1926-1933, semangat antikolonialisme dan anti-imperialisme itu sudah jelas tampak. Bisa dikatakan bahwa sikap antikolonialisme dan anti-imperialisme Soekarno pada tahun 1950-an dan selanjutnya hanyalah merupakan kelanjutan dari pemikiran-pemikiran dia waktu muda.
Tulisan berikut dimaksudkan untuk secara singkat melihat pemikiran Soekarno muda dalam menentang kolonialisme dan imperialisme-dan selanjutnya elitisme-serta bagaimana relevansinya untuk sekarang.
Antikolonialisme dan anti-imperialisme
Salah satu tulisan pokok yang biasanya diacu untuk menunjukkan sikap dan pemikiran Soekarno muda dalam menentang kolonialisme adalah tulisannya yang terkenal yang berjudul Nasionalisme, Islam dan
Marxisme". Dalam tulisan yang aslinya dimuat secara berseri di jurnal
Indonesia Muda tahun 1926 itu, sikap antikolonialisme tersebut tampak jelas sekali. Menurut Soekarno, yang pertama-tama perlu disadari adalah bahwa alasan utama kenapa para kolonialis Eropa datang ke Asia
bukanlah untuk menjalankan suatu kewajiban luhur tertentu. Mereka datang terutama "untuk mengisi perutnya yang keroncong belaka." Artinya, motivasi pokok dari kolonialisme itu adalah ekonomi.
Sebagai sistem yang motivasi utamanya adalah ekonomi, Soekarno percaya, kolonialisme erat terkait dengan kapitalisme, yakni suatu sistem ekonomi yang dikelola oleh sekelompok kecil pemilik modal yang tujuan pokoknya adalah memaksimalisasi keuntungan. Dalam upaya
memaksimalisasi keuntungan itu, kaum kapitalis tak segan-segan untuk mengeksploitasi orang lain. Melalui kolonialisme para kapitalis Eropa memeras tenaga dan kekayaan alam rakyat negeri-negeri terjajah demi keuntungan mereka. Melalui kolonialisme inilah di Asia dan Afrika,
termasuk Indonesia, kapitalisme mendorong terjadinya apa yang ia sebut sebagai exploitation de l'homme par l'homme atau eksploitasi manusia oleh manusia lain.
Soekarno muda menentang kolonialisme dan kapitalisme itu. Keduanya melahirkan struktur masyarakat yang eksploitatif. Tiada pilihan lain baginya selain berjuang untuk secara politis menentang keduanya,
mahasiswanya, sang profesor mengatakan, "Kamu harus berjanji bahwa sejak sekarang kamu tak akan lagi ikut-ikutan dengan gerakan politik."
"Tuan," jawab Soekarno, "Saya berjanji untuk tidak akan mengabaikan kuliah-kuliah yang Tuan berikan di sekolah." "Bukan itu yang sama minta," sanggah si profesor. "Tetapi hanya itu yang bisa saya janjikan, Profesor," jawab Soekarno lagi.
Sebagai suatu sistem yang eksploitatif, kapitalisme itu mendorong imperialisme, baik imperialisme politik maupun imperialisme ekonomi. Tetapi Soekarno muda tak ingin menyamakan begitu saja imperialisme dengan pemerintah kolonial. Imperialisme, menurut dia, "bukanlah pegawai pemerintah; ia bukanlah suatu pemerintahan; ia bukan
kekuasaan; ia bukanlah pribadi atau organisasi apa pun." Sebaliknya, ia adalah sebuah hasrat berkuasa, yang antara lain terwujud dalam sebuah sistem yang memerintah atau mengatur ekonomi dan negara orang lain. Lebih dari sekadar suatu institusi, imperialisme merupakan "kumpulan dari kekuatan-kekuatan yang kelihatan maupun tak kelihatan."
Soekarno mengibaratkan imperialisme sebagai "Nyai Blorong" alias ular naga. Kepala naga itu, menurut dia, berada di Asia dan sibuk menyerap kekayaan alam negara-negara terjajah. Sementara itu tubuh dan ekor naga itu ada di Eropa, menikmati hasil serapan tersebut. Bersama
dengan kolonialisme dan kapitalisme, imperialisme merupakan tantangan besar bagi setiap orang Indonesia yang menghendaki kemerdekaan.
Anti-elitisme
Selain kolonialisme dan imperialisme, di mata Soekarno muda ada tantangan besar lain yang tak kalah pentingnya untuk dilawan, yakni elitisme. Elitisme mendorong sekelompok orang merasa diri memiliki status sosial-politik yang lebih tinggi daripada orang-orang lain, terutama rakyat kebanyakan.
Elitisme ini tak kalah bahayanya, menurut Soekarno, karena melalui sistem feodal yang ada ia bisa dipraktikkan oleh tokoh-tokoh pribumi terhadap rakyat negeri sendiri. Kalau dibiarkan, sikap ini tidak hanya bisa memecah-belah masyarakat terjajah, tetapi juga memungkinkan
lestarinya sistem kolonial maupun sikap-sikap imperialis yang sedang mau dilawan itu. Lebih dari itu, elitisme bisa menjadi penghambat sikap-sikap demokratis dalam masyarakat modern yang dicita-citakan bagi Indonesia merdeka.
Soekarno muda melihat bahwa kecenderungan elitisme itu tercermin kuat dalam struktur bahasa Jawa yang dengan pola "kromo" dan "ngoko"-nya mendukung adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Untuk
rapat tahunan Jong Java di Surabaya pada bulan Februari 1921,
Soekarno berpidato dalam bahasa Jawa ngoko, dengan akibat bahwa ia menimbulkan keributan dan ditegur oleh ketua panitia. Upaya Soekarno yang jauh lebih besar dalam rangka menentang elitisme dan
meninggikan harkat rakyat kecil di dalam proses perjuangan
kemerdekaan tentu saja adalah pencetusan gagasan marhaenisme. Bertolak dari pertemuan pribadinya dengan petani Marhaen, Soekarno merasa terpanggil untuk memberi perhatian yang lebih besar kepada kaum miskin di Indonesia, serta kepada peranan mereka dalam
perjuangan melawan kolonialisme yang kapitalistik itu. Kaum Marhaen ini, sebagaimana kaum proletar dalam gagasan Karl Marx, diharapkan akan menjadi komponen utama dalam revolusi melawan kolonialisme dan dalam menciptakan suatu tatanan masyarakat baru yang lebih adil.
Dalam kaitan dengan usaha mengatasi elitisme itu ditegaskan bahwa Marhaneisme "menolak tiap tindak borjuisme" yang, bagi Soekarno, merupakan sumber dari kepincangan yang ada dalam masyarakat. Ia berpandangan bahwa orang tidak seharusnya berpandangan rendah terhadap rakyat. Sebagaimana dikatakan oleh Ruth McVey, bagi Soekarno rakyat merupakan "padanan mesianik dari proletariat dalam pemikiran Marx," dalam arti bahwa mereka ini merupakan "kelompok yang sekarang ini lemah dan terampas hak-haknya, tetapi yang nantinya, ketika digerakkan dalam gelora revolusi, akan mampu mengubah dunia."
Kompleks
Lantas, langkah-langkah apa yang diusulkan oleh Soekarno untuk melawan kolonialisme, imperialisme serta elitisme itu? Pertama-tama ia mengusulkan ditempuhnya jalan nonkooperasi. Bahkan sejak tahun 1923 Soekarno sudah mulai mengambil langkah nonkooperasi itu, yakni ketika ia sama sekali menolak kerja sama dengan pemerintah kolonial. Dalam kaitan dengan ini ia kembali mengingatkan bahwa motivasi utama
kolonialisme oleh orang Eropa adalah motivasi ekonomi. Oleh karena itu mereka tak akan dengan sukarela melepaskan koloninya. "Orang tak akan gampang-gampang melepaskan bakul nasinya," kata Soekarno, "jika pelepasan bakul itu mendatangkan matinya." Oleh karena itu pula ia yakin bahwa kemerdekaan tidak boleh hanya ditunggu, melainkan harus diperjuangkan.
Langkah lain yang menurut Soekarno perlu segera diambil dalam menentang kolonialisme dan imperialisme itu adalah menggalang persatuan di antara para aktivis pergerakan. Dalam serial tulisan
Nasionalisme, Islam dan Marxisme ia menyatakan bahwa sebagai bagian dari upaya melawan penjajahan itu tiga kelompok utama dalam
"Bahtera yang akan membawa kita kepada Indonesia Merdeka," ingat Soekarno, "adalah Bahtera Persatuan."
Pada saat yang sama Soekarno juga mengingatkan bahwa perjuangan melawan kolonialisme itu lebih kompleks daripada perjuangan antara kelompok pribumi melawan kelompok kulit putih. Pada satu sisi perlu dibedakan antara "pihak Sini" yakni mereka yang mendukung, dan "pihak Sana" yakni mereka yang menentang perjuangan kemerdekaan. Pada sisi lain perlu disadari pula bahwa kedua "pihak" itu ada baik di kalangan pribumi maupun di kalangan penguasa kolonial.
Seruan-seruan Soekarno itu pada tanggal 4 Juli 1927 dilanjutkan dengan pendirian Partai Nasional Indonesia (PNI) yang sebagai tujuan utamanya dicanangkan untuk "mencapai kemerdekaan Indonesia." Guna memberi semangat kepada para aktivis pergerakan, pada tahun 1928 ia menulis artikel berjudul Jerit Kegemparan di mana ia menunjukkan bahwa
sekarang ini pemerintah kolonial mulai waswas dengan semakin kuatnya pergerakan nasional yang mengancam kekuasaannya. Ketika pada tanggal 29 Desember 1929 Soekarno ditangkap dan pada tanggal 29 Agustus 1930 disidangkan oleh pemerintah kolonial, Soekarno justru memanfaatkan kesempatan di persidangan itu. Dalam pleidoinya yang terkenal berjudul Indonesia Menggugat dengan tegas ia menyatakan perlawanannya terhadap kolonialisme. Dan tak lama setelah dibebaskan dari penjara pada tanggal 31 Desember 1931 ia bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo), yakni partai berhaluan nonkooperasi yang dibentuk pada tahun 1931 untuk menggantikan PNI yang telah
dibubarkan oleh pemerintah kolonial.
Mendua
Menarik untuk disimak bahwa meskipun Soekarno amat berapi-api dalam melawan kolonialisme, imperialisme dan elitisme, sebenarnya
perlawanan itu tidak total, dalam arti tidak sepenuhnya dimaksudkan untuk menuntaskan ketiga tantangan itu. Hal ini tampak misalnya ketika ia mendirikan PNI. Di satu pihak memang dengan jelas digariskan bahwa tujuan utama PNI adalah mencapai Indonesia merdeka. Tetapi di lain pihak cita-cita kemerdekaan itu tidak disertai hasrat untuk mengubah sistem politik yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial dengan sistem politik yang sama sekali baru. Alih-alih perubahan total,
Soekarno-sebagaimana banyak aktivis pergerakan waktu itu-berkeinginan bahwa negeri yang merdeka itu nanti akan ditopang oleh sistem yang mirip dengan sistem yang menopangnya saat terjajah. Hanya elitenya akan diganti dengan elite baru, yakni elite pribumi.
menjadi lebih jauh daripada sekadar pertarungan antara buruh pabrik melawan para kapitalis, tetapi di lain pihak hal ini juga membuat fokus revolusi menjadi kabur. Kekaburan ini menjadi bertambah ketika disadari bahwa pemerintah kolonial, yakni pihak yang mau dilawan oleh kaum Marhaen, melibatkan juga banyak sekali pejabat dan pegawai pribumi. Dan dalam hal ini rupa-rupanya Soekarno memang tidak bermaksud mengadakan suatu perubahan total. "Kita berjuang bukan untuk melawan orang kaya," tulisnya di harian Fikiran Rakjat tahun 1932, "melainkan untuk melawan sistem."
Betapapun "galak"-nya Soekarno muda dalam menentang kolonialisme dan imperialisme dengan menggunakan prinsip nonkooperasi, ternyata ia tidak selalu konsisten. Sekitar bulan-bulan Agustus-September 1933, sebagaimana dilaporkan oleh pemerintah kolonial, ia menyatakan mundur dari keanggotaan Partindo, memohon maaf, dan meninggalkan prinsip nonkooperasi. Ia bahkan dilaporkan bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah penjajah Belanda. Lepas dari benar atau tidaknya laporan pemerintah itu, berita ini mengagetkan dan mengecewakan para pendukung gerakan kemerdekaan waktu itu. Mereka kecewa karena tokoh perjuangan yang mereka agung-agungkan, telah menyerah. Dalam koran Daulat Ra'jat edisi 30 November 1933 Mohammad Hatta bahkan menyebut peristiwa ini sebagai "Tragedie-Soekarno." Hatta amat
menyesalkan inkonsistensi serta lemahnya semangat perlawanan tokoh taktik nonkooperasi itu.
Berhubungan dengan sikap anti-elitismenya perlu dilihat bahwa
meskipun dalam pidato dan tulisan-tulisannya Soekarno tampak melawan elitisme, tetapi sebenarnya bisa diragukan apakah ia sepenuhnya
demikian. Hal ini tampak misalnya dalam pidato yang ia sampaikan pada tanggal
26 November 1932 di Yogyakarta, kota pusat aristokrasi Jawa. Dalam pidato itu Soekarno mengajak setiap orang, apa pun status sosialnya, untuk bersatu demi kemerdekaan. Tetapi sekaligus ia menegaskan bahwa bersama Partindo dirinya tidak menginginkan perjuangan kelas. Dalam tulisan Nasionalisme, Islam dan Marxisme, sebagaimana disinyalir oleh McVey, sebenarnya Soekarno sama sekali tidak sedang bicara dengan rakyat banyak. Dalam tulisan itu ia, menurut McVey, "tidak menyampaikan imbauannya kepada kelompok-kelompok radikal
Kelompok elite metropolitan yang dituju oleh tulisan Soekarno itu
sebenarnya jumlahnya amat kecil, dan kebanyakan dari mereka tinggal di kota-kota dengan pengaruh Eropa, seperti misalnya Bandung, Surabaya, Medan atau Jakarta. Di satu pihak, kelompok elite ini mempunyai
komitmen yang tinggi terhadap kemerdekaan Indonesia serta telah berpikir dalam rangka identitas nasional dan tidak lagi dalam rangka identitas regional seperti generasi pendahulunya. Di lain pihak, kelompok ini tidak melihat perlunya mengadakan suatu revolusi sosial yang akan secara total mengubah sistem yang ada, dengan segala corak kolonial-kapitalisnya. Yang lebih mendesak menurut para aktivis generasi ini adalah melengserkan elite pemerintahan kolonial asing dan
menggantinya dengan elite lokal yang dalam hal ini adalah diri mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka menghendaki adanya revolusi
nasional, tetapi bukan revolusi sosial.
Dalam kaitannya dengan rakyat banyak, anggota kelompok elite ini merasakan perlunya dukungan rakyat dalam perjuangan melawan pemerintah kolonial. Pada saat yang sama mereka berupaya mengikis sikap-sikap tradisional rakyat yang mereka pandang sebagai penghalang bagi langkah menuju dunia modern, yakni dunia sebagaimana tercermin dalam kaum kolonialis Barat.
Perasaan yang serupa tampaknya juga dimiliki oleh Soekarno. Bagi Soekarno muda, massa rakyat-betapapun tampak penting sebagai simbol dan sebagai potensi politik-sebenarnya lebih dibutuhkan sebagai sumber dukungan baginya dalam mengambil langkah-langkah politis.
Oleh karena itu tidak mengherankan, sebagaimana pernah dikeluhkan oleh Hatta, jika kontak Soekarno dengan rakyat kebanyakan itu
sebenarnya amat sedikit, terbatas pada kontak melalui pidato-pidato yang penuh tepuk tangan dan sorak-sorai.
Dikatakan oleh Bernhard Dahm, penulis biografi Bung Karno, di satu pihak Soekarno menentang sikap rakyat yang mudah pasrah pada nasib, tetapi di lain pihak ia "membutuhkan sorak-sorai tepuk tangan (mereka) guna mendukung rasa percaya dirinya." Dengan demikian tampak
adanya sikap mendua (ambivalen) dalam sikap-sikap Soekarno terhadap kapitalisme, imperialisme maupun elitisme: Di satu pihak ia membenci ketiganya. Di lain pihak, sadar atau tidak, ia melihat bahwa beberapa aspek di dalam ketiganya layak untuk dipertahankan atau setidaknya untuk tidak dikutak-katik.
Tidak sendirian
pada tahun 1920-an. Berbeda dengan generasi 1908 yang berorientasi pada perubahan sistem tanpa disertai kuatnya gagasan mengenai Indonesia merdeka, generasi Soekarno lebih berorientasi pada pentingnya kemerdekaan, tetapi lemah dalam hal perjuangan demi perubahan sistem. Lebih dari itu, generasi tahun 1920-an - dengan lebih banyak lulusan pendidikan Barat - cenderung untuk justru
mempertahankan sistem pemerintahan Barat yang ada, tetapi dengan menggeser elite kolonialnya untuk diganti dengan elite lokal.
Sebagaimana ditunjukkan oleh Takashi Shiraishi, berbeda dengan generasi pendahulu yang menekankan ketokohan individu, generasi Soekarno menekankan kepartaian. Tetapi pada tahun 1920-an partai-partai itu mengalami banyak pertentangan internal yang di mata
Soekarno akibatnya bisa fatal bagi gerakan menuju kemerdekaan. Pada tahun 1920, misalnya, terjadi pertentangan dalam tubuh Sarekat Islam, terutama antara apa yang disebut sebagai "SI Putih" dengan lawannya, "SI Merah." Pertentangan ini kemudian mendorong lahirnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun 1923 gerakan nasionalisme mengalami kemandekan total, ditandai dengan dibubarkannya National-Indische Partij (NIP) pada tahun itu, dan suburnya gerakan-gerakan yang lebih bercorak internasional, khususnya gerakan Islam dan Komunis. Pada tahun 1926-1927 PKI memutuskan untuk berontak terhadap pemerintah kolonial Belanda, tetapi karena kurangnya dukungan masyarakat, pemberontakan itu gagal. Soekarno sadar bahwa jika perpecahan itu tidak diatasi sekarang, hal itu bisa berakibat fatal bagi perjuangan kemerdekaan selanjutnya.
Jika Soekarno muda tampak terpisah dari rakyat, sebenarnya ia tidak sendirian. Banyak tokoh elite perjuangan pada zamannya juga demikian. Ketika membubarkan PNI pada tanggal 25 April 1931, misalnya, para pemimpin partai itu tidak banyak berkonsultasi dengan rakyat
kebanyakan yang menjadi anggotanya. Akibatnya rakyat menjadi kecewa, membentuk apa yang disebut "Golongan Merdeka," dan memperjuangkan pentingnya pendidikan rakyat.
Tentang perubahan sikap atau permohonan maaf Soekarno kepada pemerintah kolonial, hal itu perlu dilihat dalam konteksnya. Waktu dipenjara untuk kedua kalinya, Soekarno muda adalah bagaikan ikan yang dipisahkan dari "air"-nya, yakni massa yang biasa mendukungnya, dan yang membuatnya bersemangat dalam perjuangan kemerdekaan. Dalam penjara itu ia disel sendirian selama delapan bulan tidak hanya tanpa harapan akan adanya keringanan hukum, melainkan juga
dibayang-bayangi kemungkinan pembuangan ke "neraka" Boven Digul. Dalam keadaan demikian tidak mengherankan jika sebagai manusia Soekarno ada unsur menyerah.
Apa pun latar belakang sikap-sikap itu, pola hubungan elite rakyat yang diambil oleh Soekarno dan para aktivis pergerakan waktu itu rupa-rupanya memiliki dampak yang luas. Ketika pada tahun 1933-1934 Soekarno serta para pemimpin lain ditangkap dan diasingkan oleh Belanda, gerakan kemerdekaan mengalami kemacetan total. Tanpa adanya elite metropolitan itu seolah-olah rakyat tidak bisa lagi bergerak dalam perjuangan demi kemerdekaan. Pergerakan itu baru muncul kembali ketika para pemimpin yang diasingkan itu dibebaskan oleh Belanda saat mereka terancam oleh kedatangan balatentara Jepang.
Bahkan pada masa revolusi sendiri bisa dipertanyakan apakah sebenarnya rakyat yang ikut gigih bertempur dan berkorban mempertahankan kemerdekaan itu mendapat kesempatan yang
maksimal dalam menentukan arah revolusi. Dalam tulisannya mengenai pola hubungan antara elite dan rakyat pada zaman revolusi, Barbara Harvey menyatakan bahwa hubungan itu tidak hanya amat lemah, tetapi juga berakibat cukup fatal bagi revolusi kemerdekaan itu sendiri.
Lemahnya hubungan antara para pemimpin nasional di tingkat pusat dengan rakyat di desa-desa, menurut dia, "merupakan faktor utama bagi gagalnya elite kepemimpinan untuk menggalang dan mengarahkan kekuatan rakyat demi terwujudnya tujuan-tujuan revolusi."
Dengan kata lain, sebenarnya rakyat tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses bernegara. Jika ini benar, mungkin tak terlalu mengherankan jika PKI-meskipun pada tahun 1948 ditekan besar-besaran setelah peristiwa Madiun-dalam waktu singkat berkembang pesat pengikutnya. Ini antara lain karena di dalam PKI banyak rakyat merasakan bahwa justru dalam partai yang menekankan antikemapanan (baca: anti-elite metropolitan) itu kepentingan dan cita-cita mereka mendapat tempatnya. Dalam Pemilu 1955 PKI bahkan berhasil memperoleh suara terbanyak keempat.
Sayang sekali bahwa keterpisahan antara elite dan masyarakat itu pada zaman pasca-Soekarno tidak mengecil, melainkan justru membesar. Meskipun sejak naiknya Orde Baru pada akhir 1960-an aksespara elite kepada rakyat kebanyakan telah terbuka semakin luas-antara lain
dengan naiknya tingkat pendidikan, semakin tersedianya sarana-sarana komunikasi dan menguatnya ekonomi-akses itu tak sepenuhnya
termanfaatkan. Di bawah orde yang katanya "baru" itu tetap saja rakyat menjadi komponen massal yang dalam proses bernegara, berada di bawah kontrol elite metropolitan sebagai penentu hampir semua kebijakan yang ada.
Tak jarang bahwa upaya-upaya untuk mendorong partisipasi rakyat lebih luas justru harus berhadapan dengan tindakan militer yang keras.
militeristik masa Orde Baru tidak disusul dengan tumbuh suburnya demokrasi, melainkan dengan kaotiknya kehidupan politik, yang konon justru dimulai dari kalangan elitenya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa sekarang ini di lapisan bawah rakyat merasa semakin kecewa terhadap perilaku, komentar-komentar, serta percekcokan yang lahir di antara kelompok elite politik yang ada.
Ketika pada tahun 2001 bangsa ini memperingati seratus tahun lahirnya Soekarno dan lima puluh enam tahun Proklamasi Kemerdekaan, kita masih dilanda berbagai ketidakpastian, yang salah satu akarnya adalah keterpisahan antara elite dengan rakyatnya.
Masih panjang
Dengan sedikit meminjam seruan Bung Karno yang terkenal, sekarang ini kita perlu "membangun dunia baru." Tetapi upaya untuk membangun dunia yang baru itu kiranya harus dimulai dengan terlebih dahulu
"membangun Indonesia baru." Dan upaya membangun Indonesia baru itu mungkin harus dimulai dengan membangun elite politik yang benar-benar lahir dari kalangan rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam Indonesia yang baru itu diharapkan tiada lagi-kalaupun ada kecil peranannya-kelompok elite yang hanya sibuk berebut kekuasaan dan pengaruh.
Hal ini bisa terjadi jika para aktivis muda reformasi sekarang ini tidak enggan untuk belajar dari para aktivis pergerakan generasi tahun 1920-an. Di satu pihak meneruskan sikap militan generasi itu dalam
memperjuangkan cita-cita bersama dan rela berkurban demi cita-cita itu. Di lain pihak menolak kecenderungan untuk mewarisi sistem
pemerintahan sebelumnya, yakni kecenderungan untuk mengganti elite lama dengan elite yang baru tetapi yang pola dan orientasi politiknya tetap sama. Dengan demikian akan bisa diharapkan lahirnya elite politik yang benar-benar berorientasi pada semakin terwujudnya demokrasi.
"Kaki kami telah berada di jalan menuju demokrasi," lanjut Presiden Soekarno dalam pidatonya di depan Kongres AS itu. "Tetapi kami tidak ingin menipu diri sendiri dengan mengatakan bahwa kami telah
menempuh seluruh jalan menuju demokrasi," sambungnya. Ia sadar bahwa meskipun selama bertahun-tahun bangsa Indonesia telah
beperang melawan kolonialisme, imperialisme dan elitisme, jalan menuju demokrasi masih tetap panjang. Tetapi Bung Karno juga sadar bahwa betapapun panjangnya sebuah perjalanan, ia harus dimulai dengan langkah-langkah pertama.
>Jumat, 1 Juni 2001
Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over"
Spiritualitas Bung Karno
Bambang Noorsena
Setelah dahulu pada zaman-zaman sebelumnya Brahma-Wishnu-Ishwara menjelma dalam berbagai raja-raja di dunia, kini pada zaman kaliyuga turunlah Sri Jinapati (Buddha) untuk meredakan amarah Kala. Sebagaimana Sidharta Gautama, sebagai titisan Sri Jinapati, Sutasoma putra Mahaketu raja Hastina, keturunan
Pandawa, meninggalkan kehidupan istana dan memilih hidup sebagai seorang pertapa.Pada suatu hari, para pertapa mendapat gangguan dari Porusada, raja raksasa yang suka menyantap daging manusia. Mereka memohon kepada Sutasoma untuk membunuh raksasa itu, tetapi permintaan itu ditolaknya. Setelah dalam olah spiritualnya Sutasoma mencapai kemanunggalan dengan Buddha Wairocana, akhirnya ia kembali ke istana dan dinobatkan menjadi Raja Hastina. Sementara itu, Porusada yang ingin disembuhkan dari sakit parah pada kakinya, bernazar akan mempersembahkan
seratus raja sebagai santapan Bathara Kala. Tetapi, Sutasoma menyediakan diri disantap oleh Kala, asalkan seratus raja itu dibebaskan. Kerelaan ini sangat menyentuh hati Kala, bahkan Porusada pun menjadi terharu. Dewa Siwa yang menitis pada Porusada akhirnya meninggalkan tubuh raksasa itu, karena disadarinya bahwa Sutasoma adalah Buddha sendiri. Mangka Jinatwa lawan Siwatatwa tunggal, Bhinneka Tunggal Ika, tan hana dharma mangrwa (Hakikat Buddha dan hakikat Siwa adalah satu, berbeda-beda dalam perwujudan eksoterisnya tetapi secara esoteris satu. Tidak ada dualisme dalam kebenaran agama).
Lalu Bung Karno mensitir ungkapan bahasa Jawa kuno yang dimaksud, "Nanging hana pamintaku uripana sahananing ratu kabeh" (Tetapi permohonanku, hidupkanlah raja-raja itu semua). Itulah ucapan Sutasoma kepada raksasa Porusada, sambil
menyerahkan dirinya sebagai santapan Kala, asal seratus raja itu dibebaskan.
Ada dua hal yang perlu digarisbawahi dari penggalan karya Mpu Tantular ini. Pertama, dari karya Tantular ini berasal dari istilah "mahardhika" (yang menjadi asal kata merdeka), "Pancasila" dan seloka "bhinneka tunggal Ika"-ungkapan yang menurut Dr Soewito dalam tulisannya Sutasoma, A Study in Javanese Wajrayana (1975)- "is a magic one of great significance and it embraces the sincere hope the whole nation in its struggle to become great, unites in frame works of an Indonesian Pancasilaist community".
Kedua, perhatian yang diberikan Bung Karno pada ucapan Sutasoma yang rela mengorbankan dirinya sendiri demi
kesejahteraan umat manusia. Yang kedua ini juga tidak kurang penting, sebab ternyata jalan yang sama akhirnya ditempuh oleh Bung Karno demi menyelamatkan bangsanya dari pecahnya "perang saudara" pasca-Gestok (Gerakan 1 Oktober) 1965. Jadi, yang
pertama terkait erat dengan pandangan religi Bung Karno, khususnya dalam melacak pandangan-pandangan dasar
keagamaannya, sedangkan yang kedua menyangkut religiusitas atau penghayatan keagamaannya.
Memang, kini ungkapan Bhinneka Tunggal Ika tercantum sebagai seloka dalam lambang negara kita dalam makna kebangsaan yang lebih kompleks. Akan tetapi, makna semula ungkapan ini penting kita kedepankan kembali, justru karena secara khusus kita kaitkan
dengan wacana religi dan religiusitas Bung Karno di atas. Begitu juga, istilah Pancasila yang juga tercantum dalam karya Tantular ini, aslinya berasal dari kelima hukum moral Buddhis: "Pancasila ya gegen den teki away lupa" (Pancasila harus dipegang teguh jangan sampai dilupakan). Salah satu sila dari Pancasila Buddhis adalah larangan untuk membunuh sesama makhluk hidup (Panapati vermanai sikkapadam samadiyami) yang kiranya menjiwai kisah Sutasoma dan mengilhami pilihan moral Bung Karno untuk lebih baik dirinya sendiri tenggelam demi keutuhan bangsa dan negara yang sangat dicintainya.
Bung Karno di mata kawan dan lawan politiknya
politisi kaum abangan yang "kurang islami". Mereka bahkan menggolongkannya sebagai gembong kelompok "nasionalis sekuler". Akan tetapi, di mata Syeikh Mahmud Syaltut dari Cairo, penggali Pancasila itu adalah Qaida adzima min quwada harkat al-harir fii al-balad al-Islam (Pemimpin besar dari gerakan kemerdekaan di negeri-negeri Islam). Malahan, Demokrasi Terpimpin, yang di negerinya sendiri diperdebatkan, justru dipuji oleh syeikh al-Azhar itu sebagai, "lam yakun ila shuratu min shara asy syuraa' allatiy ja'alha al-Qur'an sya'ana min syu'un al-mu'minin" (tidak lain hanyalah salah satu gambaran dari permusyawaratan yang dijadikan oleh Al Quran sebagai dasar bagi kaum beriman).
Di mata lawan politiknya di Barat, seperti tampak dari ucapan Willard A Hanna, Bung Karno adalah "politisi tanpa identitas dan tanpa prinsip, yang berpadu dalam dirinya nabi dan playboy, tukang sulap dan tukang obat". Tetapi, orang-orang Arab menamakannya ra'is, dan orang-orang Mesir di Kota Cairo menjulukinya al-hakim. Tak seorang pun meragukan popularitasnya di negeri-negeri Islam itu. Nama besar Bung Karno diabadikan antara lain dalam Qamus al-Munjid. Konon, hanya dua tokoh Indonesia yang dicatat dalam kamus karya Louise Ma'louf, seorang Arab-Kristen itu. Soekarno, dan satunya lagi Syeikh Nawawi al-Bantani.
Tatkala memuncaknya ketegangan antara Israel dan negara-negara Arab soal status Palestina, pers sensasional Arab yang salah paham dengan pencabutan sebutan Deicidium (pembunuh Tuhan) kepada kaum Yahudi, menyambut Bung Karno, "Juara untuk kepentingan-kepentingan Arab telah tiba". Pada pihak lain, Tahta Suci Vatikan sendiri memberikan kepadanya tiga gelar penghargaan kepada presiden pertama dari Republik yang mayoritas Muslim itu.
Gaya religius Bung Karno
Relevansi mengemukakan faham keagamaan Bung Karno ini, minimal terkait erat dengan pertanyaan: Seberapa jauhkah
peranannya dalam menentukan masa depan Indonesia, berangkat dari pluralisme agama yang merupakan problem tersendiri apabila tidak diberikan perhatian khusus dalam membangun sebuah bangsa? Kenyataan ini dikemukakan, dengan sepenuhnya
menyadari bahwa mengemukakan spiritualitas Bung Karno adalah juga merupakan bagian dari kontroversi itu sendiri.
hendak merangkul seluruh dunia". Sebaliknya, ungkapan semacam itu-pada hemat BJ Boland dalam The Struggle of Islam in Modern Indonesia (1982)-"hanya merupakan perwujudan dari perasaan keagamaan sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya Jawa". Bagi penghayatan spiritual Timur, ucapan itu justru "merupakan keberanian untuk menyuarakan berbagai pemikiran yang mungkin bisa dituduh para agamawan formalis sebagai bidah".
Ungkapan Bung Karno ini, di mata para penghayat tasawuf bukanlah hal yang asing. Dengarlah, Ibn Al-'Arabi (1076-1148)
mendendangkan kesadaran yang sama. "Laqad shara qalbiy qabilan kulla shuratin, famar'a lighazlanin wa diir liruhbanin wa baytun li autsanin wa ka'batu thaifi wal wahu tawrati wa mushafu qur'anin
(Hatiku telah siap menerima segala simbol, apakah itu biara rahib-rahib Kristen, rumah berhala, Kabah untuk thawaf, lembaran Taurat atau mushaf Al Quran).
"Panteis-monoteisme" Bung Karno?
Ketika menerima gelar doctor honoris causa (doktor kehormatan) di Universitas Muhammadiyah, Jakarta, Bung Karno menyebut bahwa tauhid yang dianutnya sebagai Panteis-monoteis. Bung Karno yakin bahwa Tuhan itu satu, tetapi Ia hadir dan berada di mana-mana. Tentu saja di kalangan Islam dan Kristen, istilah panteisme ini bisa mengundang salah paham. Kontan saja, orang langsung
menghubungkannya dengan sosok legendaris Syekh Siti Jenar, "Al-Hallaj"-nya orang Jawa.
Di satu pihak, dalam berbagai kesempatan Bung Karno mengritik paham kalam asy'ariyah mengenai ketidakcukupan 20 sifat Allah, berbareng dengan kritiknya terhadap paham taqlid dan kejumudan-kejumudan kaum tradisionalis pada zamannya. Kritik Bung Karno ini bisa dilacak dari kegandrungannya pada paham rasionalisme Islam klasik Mu'tazilah dan pemikiran-pemikiran pembaru Islam khususnya Jamaluddin al-Afghani. Tetapi pada pihak lain, Bung Karno tidak bisa melepaskan diri dengan warisan keagamaan Jawa yang sangat kental berciri mistik.
Karena itu, menarik sekali dalam deskripsinya mengenai tauhid, Bung Karno merujuk juga Baghawad Gita. "The Gospel of Hinduism" itu pun dikutipnya begitu bebas, sambil di sana-sini membuat
antara semua keindahan, Akulah kecantikan" (Bhagawad Gita X,36). Menurut saya, Bung Karno belum sampai menjadi seorang panteis tulen, atau menganut monisme radikal-menurut istilah PJ Zoetmulder SJ-yang sama sekali menyangkal bahwa segenap realitas itu lebur menyatu tanpa dualitas.
Sebab di mata Bung Karno, penekanan pada aspek tasybih
(imanensi) Tuhan, sama sekali tidak menghapuskan aspek tanzih
(transendensi)-Nya. Barangkali, istilah yang tepat untuk menggambarkan keyakinan Bung Karno adalah
"panentheisme" (pan, "segala sesuatu"; en, "dalam" dan theos, "Tuhan"). Jadi, segala sesuatu ada dalam Tuhan. Maksudnya, totalitas segenap realitas yang diciptakan ada dalam Tuhan, tetapi Tuhan sendiri melebihi totalitas tersebut. Kita dapat
membandingkannya dengan ucapan Imam al-Ghazali (wafat 1111),
At Tauhid al-khalis an layaraha fii kulli syai'in ilallah (Tauhid sejati adalah penglihatan atas Allah dalam segala sesuatu). Juga, menurut Ibn al-'Arabi, segenap alam semesta adalah tajjali atau penampakan dari Allah.
Indonesia sebagai sebuah mitos
Akan tetapi, apa pun rincian dari perkembangan legitim dalam faham teologisnya, yang jelas dengan latar belakang pandangan
teologisnya itu, Bung Karno sangat mengakrabi alam semesta. Dan kunci untuk mengerti hal itu adalah Tat Twam Asi (Aku adalah dia, dia adalah aku). Mencintai sesama berarti mencintai Tuhan, bahkan mencintai alam berarti mencintai Pencipta-Nya. Dan cinta Bung Karno terhadap kosmos itu diawali dari Bumi tempat kakinya
berpihak, Bumi pertiwi Indonesia yang disapanya dengan takjub dan hormat sebagai "Ibu". Bagi Bung Karno, Indonesia telah menjadi sebuah mitos. Mungkin karena itu, Agus Salim dan A Hassan mengkhawatirkan nasionalisme Bung Karno akan jatuh kepada faham ashabiyah (spirit of clan), yang menjurus kepada tindakan
syirk atau pemberhalaan.
Lebih jelas lagi, kita bisa mengikuti deskripsi Bung Karno mengenai nasionalisme Indonesia yang diungkapkan begitu berapi-api: "Bukan saya berkata Tuhan adalah Indonesia", kata Bung Karno, "tetapi Tuhan bagiku tercermin pula dalam Indonesia". Sang Putra Fajar itu tidak dapat menahan hentakan-hentakan gelora jiwa dalam dadanya yang begitu mencintai negerinya, sampai harus bercakap akrab dan berdendang takjub dengan sungai-sungainya, pohon-pohonnya, langit biru dan awan gemawannya, ombak laut dan pantai-pantainya. Singkat kata, di mata Bung Karno, Indonesia adalah satu totaliteit
Gambaran ini, seperti pernah ditulis Bung Karno sendiri, mengingatkan kita pada sebuah seloka dari Ramayana karya pujangga Valmiki, mengenai cinta dan bakti kepada Janani
Janmabhumi- yaitu agar setiap orang mencintai Tanah Airnya seperti ia mencintai ibu kandungnya sendiri. Meskipun sikap ini bisa
ditafsirkan secara ekstrem, seperti pembelaan Kumbakarna terhadap negeri Alengka yang diteladankan dalam Serat Tripama (karya
Mangkunegara IV).
Ksatria berwujud raksasa ini ketika terjadi perang antara Rama dengan Rahwana, akhirnya tetap membela Tanah Airnya.
Alasannya, bukan karena ia mendukung kejahatan Rahwana, tetapi karena ia tidak tega melihat Tanah Airnya: yang sumur dan
ladangnya sehari-hari ia makan dan minum itu, diinjak-injak oleh pasukan musuh, sekalipun musuhnya itu berada di pihak yang benar. Sikap Kumbakarna ini, bisa saja diartikan sebagai sikap right or wrong my country. Namun, Bung Karno tidak akan sampai
menafsirkan nasionalisme dalam makna seekstrem itu, karena penolakannya yang tegas terhadap chauvinisme, dan sebagai gantinya Bung Karno menawarkan sebuah "nasionalisme yang
tumbuh subur dalam tamansari perikemanusiaan". My Nasionalism is humanity, begitu ucapan Gandhi yang acap dikutipnya.
Spiritualitas Bung Karno juga berciri "sakramentalis". Sebagaimana nabi-nabi semitis dari zaman dahulu, Bung Karno "believed in the beauty of holiness" (percaya kepada kecantikan dari keagungan), berbeda dengan orang-orang Yunani yang "believed in the holiness of beauty" (percaya pada keagungan dari kecantikan) sehingga memberhalakan alam itu (Max I. Dimont, 1995). Sebagaimana "jiwa kosmis" Fransiskus dari Asisi, alam raya dinilainya bukan hanya bernilai profan, melainkan sekalian makhluk adalah sakramen Sabda Ilahi yang menunjuk kepada pribadi Ilahi. Dalam diri Bung Karno, gaya religiusnya yang unik ini: "religius intelektual artistik"-menurut istilah Clifford Geertz-tidak dapat dilepaskan dari warisan
tradisionalisme Jawa dan darah seni Bali dari ibunya. "Ingat, aku adalah anak Ida Ayu Nyoman Rai, keponakan Raja Singaraja, wanita dari Bali", kata Bung Karno pada suatu saat.
Tak ayal, Bung Karno, seperti para pujangga Jawa kuno (yang karya-karyanya masih dilestarikan di Bali)-"berbakti kepada
keindahan" (ahyun ing kalangwan) karena keyakinan bahwa Tuhan sendirilah "tattwa ning lango" (inti segala keindahan). Bukankah para sufi mendendangkan tembang yang sama? Tidak seorang pun dari mereka yang berzikir mengagungkan asma-Nya, kecuali
bersenandung dengan syair-syair mereka. Kullu jamilun min
mencintai keindahan).
"Passing over" spiritualitas Bung Karno
Latar belakang warisan keluarga Soekarno seperti yang diuraikan di atas, sudah barang tentu membentuk dan menentukan sosialisasi pemikiran keagamaan selanjutnya. "Spiritualitas semesta" (holistic spirituality) Bung Karno itu-untuk tidak menyebutnya sinkretisme (percampuran) agama-agama, suatu istilah yang sama sekali tidak tepat dalam menggambarkan kecenderungan dasar pemikiran Jawa yang sebenarnya-khususnya tampak dari bahasa teologisnya yang "melintas batas" (passing over) berbagai agama dan tradisi spiritual. Hal itu tampak dari pidato-pidato tanpa teks, ketika ia
mengemukakan perbandingan-perbandingan dari berbagai agama, tamsil-tamsil dari ajaran Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Ayat-ayat suci itu dikutipnya bahkan di luar komunitas agama yang menganutnya. Misalnya, tanpa ragu-ragu ia mengutip Injil atau
Bhagawad Gita di forum Islam.
Warisan keberagaman itu bukan diterimanya sebagai kontradiksi atau pertentangan, sebaliknya sebagai suatu kekayaan rohani berdasarkan kesadarannya akan kesatuan transendental agama-agama. Dalam menggembleng rakyatnya, Bung Karno, misalnya sering mengutip Al Quran. ar Ra'd 11: Innallaha laa yughayiru maa bi qaumin hatta yughayiru ma bi anfusihim (Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum sehingga kaum itu mengubah sendiri nasibnya).
Tetapi kita juga mendengar dari Bung Karno kutipan dari Bhagawad Gita (II,47) ketika menekankan prinsip yang sama: Karmany
ewadhikaras te maphalesu kadacana (Berjuanglah dengan tanpa menghitung-hitung untung rugi bagimu).
Bahkan Bung Karno pernah membuat terperanjat Mr Siegenbeek van Heukelom yang mengadilinya di Landraad Bandung tahun 1930. "Ik ben een revolutionaire" (Saya seorang revolusioner), tegas Bung Karno. Tetapi kata dia selanjutnya: "Ik werk niet met bommen en granaten" (Saya bekerja tanpa bom dan granat). Hakim kolonial itu sangat kaget, karena Bung Karno menyebut bahwa Yesus adalah seorang yang revolusioner, meskipun Ia bekerja tanpa kekerasan. "Revolusi", kata Bung Karno, adalah "eine Umgestaltung von Grundaus" (perubahan sampai ke akar-akarnya), baik dalam hal politik maupun dalam ajaran keagamaan. Dalam suatu pidatonya, Bung Karno di luar kepala dapat menghapal Injil Yohanes Pasal 1 dalam bahasa Belanda.
Sebagai seorang Muslim, Bung Karno meyakini petunjuk-petunjuk wahyu dalam
juga turut memperkaya spiritualitasnya. Hal itu dapat dimengerti, sebagaimana ditulis Cindy Adams, karena kesadaran Bung Karno bahwa kebenaran itu tunggal dan satu-satunya suara kemanusiaan adalah Kata dari Tuhan (Sukarno An Autobioghraphy, 1965).
Menariknya, seperti diungkapkannya sendiri, spiritualitasnya yang begitu luas dan "melintas batas" agama-agama itu, lahir dari " mi'raj-nya dunia pemikiran", sebagaimana pendakian seorang salik juga disebut "uruj mir'raj". Hua al-khuruj 'an kulli syai'in siwallah (Keluar dari segala sesuatu yang bukan Allah). Bung Karno memakai ungkapan sejajar, "Saya naik ke langit, mi'raj dalam dunianya pemikiran. Bung Karno, in the world of the mind, bertemu dengan tokoh-tokoh dunia, seperti Thomas Jefferson, Garibaldi, Mustafa Kemal Atarturk, Mustafa Kamil, Karl Marx, Engel, Stalin, Trosky, Dayananda Saraswati, Krisna Ghokale dan Aurobindo Gosye. Kalau ada hadits Nabi berbunyi Utlubul ilma' wa lau bissin (Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina), Bung Karno juga in the world of the mind
pergi ke Tiongkok "minum teh bersama Sun Yat Sen", atau mengalami saat-saat "duduk bersila dengan Gandhi".
Meskipun Bung Karno menimba, menimba dan menimba dari tokoh-tokoh "negeri seberang" itu, namun akhirnya Bung Karno kembali ke
realiteit-nya Indonesia, tatkala pada saatnya ia harus menentukan masa depan dan kelangsungan bangsa menghadapi kenyataan pluralisme yang menjadi warisan sejarah beratus-ratus tahun, termasuk di dalamnya pluralisme agama.
Ketika Ernest Renan mengucapkan pidatonya yang terkenal di Sorbone tahun 1882, "Qu'est ce qu'une Nation" (Apakah suatu bangsa itu?), salah satu aspek yang ditekankannya adalah bahwa nasionalisme modern tidak dapat lagi didasarkan atas kesamaan agama. Pada zaman itu, agama masih menjadi unsur perekat negara Belgia yang berdiri tahun 1830. Dari pidato Renan ini, bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia, telah menggali konsepnya tentang hakikat suatu bangsa. Meskipun Bung Karno menimba konsep nasionalisme dari Renan, namun nasionalisme Indonesia mendapat pijakan historis yang lebih kokoh. Bukan hanya baru abad ke-19, tetapi sejak zaman Majapahit, Mpu Tantular, tidak hanya telah diletakkan landasan politis bagaimana mengatasi
pluralisme agama, melainkan malah sudah dikembangkan landasan teologis yang lebih memadai.
Bung Karno juga "berdialog spiritual" dengan Mpu Tantular, lalu dikembangkanlah kesadaran yang kini oleh teolog agama-agama acap disebut sebagai philosophia perennis yang meyakini bahwa kebenaran abadi berada di pusat semua tradisi spiritual, apakah itu
istilah sufi Islam, atau logos spermatikos (benih sabda Ilahi) dalam pemikiran patristik Kristen. Sesungguhnya kebenaran itu satu dan tidak terbagi, meskipun mewujud dalam simbol-simbol yang secara eksoteris berbeda-beda. Prinsip kasunyatan Tantular ini, oleh Bung Karno diterjemahkan secara politis dalam sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pancasila, berbareng dengan dibabtisnya seloka Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara. Dengan sila pertama itu, Bung Karno telah membebaskan bangsanya dari "keharusan menantikan pesawat penyelamat dari Moskwa atau seorang kalifah dari Istanbul". Maksudnya, Indonesia tidak menjadi negara Islam, karena bertentangan dengan realitas kemajemukan bangsa, tetapi juga bukan negara sekuler, karena melawan degup hati sanubari rakyat yang sangat religius.
Relung-relung religiusitas Bung Karno
Bukan rahasia lagi, Bung Karno dijatuhkan oleh sebuah creeping coup d'etat (kudeta merangkak) yang dirancang sangat sistematis. Pada hari-hari terakhirnya, Bung Karno harus menjalani via dolorosa
(jalan sengsara) di sebuah "karantina politik". Sendiri dan sepi. Bung Karno tetap menjadi Bapak yang mencintai semua rakyatnya,
meskipun orang-orang di sekelilingnya telah mengkhianatinya. Saat itu, di tengah-tengah badai fitnah dan ancaman pecahnya perang saudara, ibu pertiwi laksana harimau lapar hendak memangsa anaknya sendiri. Dan seperti Sutasoma, Bung Karno justru
menyerahkan dirinya sendiri, rela tenggelam demi keutuhan bangsa dan negaranya. "Cak Ruslan, saya tahu saya akan tenggelam. Tetapi ikhlaskan Cak, biar saya tenggelam asalkan bangsa ini selamat, tidak terpecah belah", tegasnya kepada Ruslan Abdulgani.
Bung Karno sadar, pilihan moral itu ibarat salib yang harus dipikulnya menuju "puncak Kalvari politik yang kejam". Masih menurut Cak Ruslan, Bung Karno terakhir kali menerima delegasi mahasiswa dari GMKI dan PMKRI pada tahun 1967. Pada waktu itu Bung Karno mengutip sabda Yesus: "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati". Juga, "Mereka akan menyesah kamu, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja" (Injil Matius 10:16-18). Maka Bung Karno menempuh jalan ahimsa (tanpa kekerasan), ketika drama pengalihan kekuasaan itu bahkan hanya berlangsung 2-3 babak saja. Semua berjalan
begitu cepat dan rapi. Sang Penyambung Lidah Rakyat pun akhirnya tenggelam, meskipun Orde Baru yang "menjambret" kekuasaannya tidak pernah mampu menguburkan pengaruhnya yang besar.
menjadi satu.
Kini di tengah-tengah fenomena politisasi agama pada tahun-tahun terakhir, kita diingatkan dengan semboyan kaum sufi yang kiranya dapat kita terapkan untuk Bung Karno: "ash Shufi laa madzaba lahu ila madzab al-haqq"-seorang sufi tidak mempunyai religi kecuali religi Kebenaran.
>Jumat, 1 Juni 2001
Bung Besar, Ideolog yang Kesepian
Bagus Takwin"AKU ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, aku berjuang karena rakyat dan aku penyambung lidah rakyat." Pengakuan ini meluncur dari Soekarno, Presiden RI
pertama, dalam karyanya Menggali Api Pancasila. Sadar atau tidak sadar ia mengucapkannya, terkesan ada kejujuran di sana.
Soekarno, sang orator ulung dan penulis piawai, memang selalu membutuhkan dukungan orang lain. Ia tak tahan kesepian dan tak suka tempat tertutup. Dari pidato dan tulisannya yang
memperlihatkan betapa mahirnya ia menggunakan bahasa, tersirat sebuah kebutuhan untuk selalu mendapat dukungan dari orang lain.
Gejala berbahasa Soekarno, Bung Karno, merupakan fenomena langka yang mengundang kagum banyak orang. Wajar kalau muncul pertanyaan "Apakah kemahiran Soekarno menggunakan bahasa dengan segala ma-cam gayanya berhubungan dengan
kepribadiannya?" Analisis terhadap kepribadian Soekarno melalui autobiografi, karangan-karangannya, dan buku-buku sejarah yang memuat sepak terjangnya dapat membantu memberikan jawaban. Dengan menggunakan pendekatan teori psi-kologi individual dari Alfred Adler (Hall dan Lindzey, 1985) dapat dipahami bagaimana Proklamator Kemerdekaan RI ini bisa menjadi pribadi yang berapi-api, pembakar semangat banyak orang, gagah dan teguh sekaligus sensitif, takut pada kesendirian, dan sangat membutuhkan dukungan sosial.
Pribadi yang kesepian
Di akhir masa kekuasaannya, Soekarno sering merasa kesepian. Dalam autobiografinya yang disusun oleh Cindy Adams, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, ia menceritakannya.
sekejap. Kadang-kadang, di larut malam, aku menelepon seseorang yang dekat denganku seperti misalnya Subandrio, Wakil Perdana Menteri Satu dan kataku, 'Bandrio datanglah ke tempat saya, temani saya, ceritakan padaku sesuatu yang ganjil, ceritakanlah suatu lelucon, berceritalah tentang apa saja asal jangan mengenai politik. Dan kalau saya tertidur, maafkanlah.'... Untuk pertama kali dalam hidupku aku mulai makan obat tidur. Aku lelah. Terlalu lelah."
(Adams, 2000:3)
"Ditinjau secara keseluruhan maka jabatan presiden tak ubahnya seperti suatu pengasingan yang terpencil... Seringkali pikiran oranglah yang berubah-ubah, bukan pikiranmu... Mereka turut menciptakan pulau kesepian ini di sekelilingmu."
(Adams, 2000:14)
Apa yang ditampilkan Soekarno dapat dilihat sebagai sindrom orang terkenal. Ia diklaim milik rakyat Indonesia. Walhasil, ia tak bisa lagi bebas bepergian sendiri menikmati kesenangannya (Adams,
2000:12). Namun, melihat ke masa mudanya, kita juga menemukan tanda-tanda kesepian di sana. Semasa sekolah di Hogere Burger School (HBS), ia menekan kesendiriannya dengan berkubang dalam buku-buku, sebuah kompensasi dari kemiskinan yang dialaminya. Kebiasaan ini berlanjut hingga masa ia kuliah di Bandung. Soekarno terkenal sebagai pemuda yang pendiam dan suka menarik diri
(Adams, 2000:89-91).
Indikasi kesepian juga kita dapatkan dalam ceritanya tentang
penjara. Malam-malam di penjara menyiksanya dengan ruang yang sempit dan tertutup. Dinding-dinding kamar tahanannya terlalu menjepit dirinya. Lalu muncullah perasaan badannya yang membesar hingga makin terjepit dalam ruang tahanan itu.
"Yang paling menekan perasaan dalam seluruh penderitaan itu adalah pengurungan. Seringkali jauh tengah malam aku merasa seperti dilak rapat dalam kotak kecil berdinding batu yang begitu sempit, sehingga kalau aku merentangkan tangan, aku dapat
menyentuh kedua belah dindingnya. Rasanya aku tak bisa bernafas. Kupikir lebih baik aku mati. Suatu perasaan mencekam diriku, jauh sama sekali dari keadaan normal." (Adams, 2000:135)
mengungkapkan ketidakpuasan sekaligus ketakberdayaannya. Selain itu, di lingkungan sekolah ia harus berhadapan dengan anak-anak Belanda yang sudah terbiasa memandang remeh pribumi.
Pengalaman yang cukup traumatis terjadi di masa lima tahun
pertama. Soekarno pernah berturut-turut menderita penyakit seperti tifus, disentri, dan malaria yang berujung pada penggantian
namanya dari Kusno menjadi Karno, nama seorang tokoh
pewayangan putra Kunti yang berpihak pada Kurawa demi balas budi dan kewajiban membela negara yang menghidupinya. Sakit yang melemah-kan secara fisik dapat berpengaruh terhadap kondisi psikis. Sangat mungkin muncul perasaan lemah, tak berdaya, dan terasing pada diri Soekarno kecil. Untungnya dilakukan penggantian nama disertai penjelasan dari ayahnya tentang makna pergantian nama yang memberinya kebanggaan karena menyandang nama pejuang besar.
Pengalaman sakit-sakitan dan hidup dalam kemiskinan tampak membekas kuat dalam ingatan Soekarno. Di masa tuanya, ia
menafsirkan kegemarannya bersenang-senang sebagai kompensasi dari masa lalunya yang dirampas kemiskinan (Adams, 2000). Ada semacam dendam terhadap kemiskinan dan ketidakberdayaan yang telah berkilat dalam dirinya. Dendam yang kemudian
menggerakkannya pada semangat perjuangan kemerdekaan dan keinginan belajar yang tinggi.
Mitos-mitos dari masa kecil
Sejak kecil, Soekarno sudah menyimpan mitos tentang diri-nya sebagai pejuang besar dan pembaru bagi bangsanya. Ibunya, Ida Nyoman Rai, menceritakan makna kelahiran di waktu fajar.
"Kelak engkau akan menjadi orang yang mulia, engkau akan menjadi pemimpin dari rakyat kita, karena ibu melahirkanmu jam setengah enam pagi di saat fajar mulai menyingsing. Kita orang Jawa
mempunyai suatu kepercayaan, bahwa orang yang dilahirkan di saat matahari terbit, nasibnya telah ditakdirkan terlebih dulu. Jangan lupakan itu, jangan sekali-kali kau lupakan, nak, bahwa engkau ini putra dari sang fajar." (Adams, 2000:24)
Tanggal kelahiran Soekarno pun dipandangnya sebagai pertanda nasib baik.
Soekarno melihat dirinya yang terdiri dari dua sifat yang berlawanan sebagai satu kemungkinan pertanda nasibnya di dunia politik.
"Karena aku terdiri dari dua belahan, aku dapat memperlihatkan segala rupa, aku dapat mengerti segala pihak, aku memimpin semua orang. Boleh jadi ini secara kebetulan bersamaan. Boleh jadi juga pertanda lain. Akan tetapi kedua belahan dari watakku itu
menjadikanku seseorang yang merangkul semua-nya."
Kejadian lain yang dianggap pertanda nasib oleh Soekarno adalah meletusnya Gunung Ke-lud saat ia lahir. Tentang ini ia menyatakan, "Orang yang percaya kepada takhayul meramalkan, 'Ini adalah penyambutan terhadap bayi Soekarno," Selain itu, penjelasan tentang penggantian nama Kusno menjadi Karno pun memberi satu mitos lagi dalam diri Soekarno kecil tentang dirinya sebagai calon pejuang dan pahlawan bangsanya.
Kepercayaan akan pertanda-pertanda yang muncul di hari kelahiran Soekarno memberi semacam gambaran masa depan dalam benak Soekarno sejak masa kecilnya. Dalam kerangka pemikiran Adler, gambaran masa depan itu disebut fictional final goals (tujuan akhir fiktif). Meskipun fiktif (tak didasari kenyataan), tetapi gambaran masa depan ini berperan menggerakkan kepribadian manusia untuk
mencapai kondisi yang tertuang di dalamnya (Adler, 1930:400). Riwayat hidup Soekarno memperlihatkan bagaimana gambaran dirinya di masa depan dan persepsinya tentang Indonesia menggerakkannya mencapai kemerdekaan Indonesia.
Bombasme bahasa dan keinginan merengkuh massa
Setelah menjadi presiden, Soekarno berpidato tiap tanggal 17 Agustus. Di sana dapat kita temukan kalimat-kalimat muluk,
penggunaan perumpamaan elemen-elemen alam yang megah dan hiperbolisme bahasa. Dari tahun ke tahun pidatonya makin gegap-gempita, mencoba membakar semangat massa pendengarnya dengan retorika kata-kata muluk.
Dari kalimat-kalimat itu dapat dibayangkan seperti apakah kondisi psikis orang yang menggunakannya. Dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1949, contohnya, ia berseru, "Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa pancaroba, tetaplah
bersemangat elang rajawali." Di sini ada indikasi ia menempatkan diri sebagai orang yang bersemangat elang rajawali sehingga
Seruan-seruan yang sering dilontarkan dalam pidatonya adalah tentang perjuangan yang harus dilakukan tak henti-henti.
"Kemerdekaan tidak menyudahi soal-soal, kemerdekaan malah membangun soal-soal, tetapi kemerdekaan juga memberi jalan untuk memecahkan soal-soal itu."
(Pidato 17 Agustus 1948)
"Tidak seorang yang menghitung-hitung: Berapa untung yang kudapat nanti dari Republik ini, jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya."
(Pidato 17 Agustus 1956)
"Karena itu segenap jiwa ragaku berseru kepada bangsaku
Indonesia: "Terlepas dari perbedaan apa pun, jagalah Persatuan, jagalah Kesatuan, jagalah Keutuhan! Kita sekalian adalah machluk Allah! Dalam menginjak waktu yang akan datang, kita ini se-olah-olah adalah buta."
(Pidato 17 Agustus 1966)
Selain ajakan untuk berjuang, tersirat juga dari petikan-petikan tersebut bahwa Soekarno memandang dirinya sebagai orang yang terus-menerus berjuang mengisi kemerdekaan. Pengaruh fictional final goals-nya terlihat jelas, Soekarno yang sejak kecil
membayangkan diri menjadi pemimpin bangsanya dengan
kepercayaan tinggi menempatkan dirinya sebagai guru bagi rakyat.
"Adakanlah ko-ordinasi, ada-kanlah simponi yang seharmonis-harmonisnya antara kepentingan sendiri dan kepentingan umum, dan janganlah kepentingan sendiri itu dimenangkan diatas
kepentingan umum."
(Pidato 17 Agustus 1951)
"Kembali kepada jiwa Proklamasi .... kembali kepada sari-intinya yang sejati, yaitu pertama jiwa Merdeka Nasional... kedua jiwa ichlas... ketiga jiwa persatuan... keempat jiwa pembangunan."
(Pidato 17 Agustus 1952)
bertindak revolusioner.... jangan ragu-ragu, jangan mandek setengah jalan..." kita adalah "fighting nation" yang tidak mengenal "journey's-end"
(Pidato 17 Agustus 1956)
Keinginannya untuk merengkuh massa sebanyak-banyaknya tampak dari kesenangannya tampil di depan massa.
Bombasme-kecenderungan yang kuat untuk menggunakan kalimat-kalimat muluk dan ide-ide besar yang tidak disertai oleh tindakan konkret-praktis untuk mencapainya yang ditampilkannya dapat diartikan sebagai usaha memikat hati rakyat. Pidato-pidatonya banyak mengandung gaya hiperbola dan metafora yang berlebihan seperti "Laksana Malaikat yang menyerbu dari langit", "adakanlah simfoni yang seharmonis-harmonisnya antara kepentingan sendiri dan kepentingan umum", "Bangsa yang gila kemuktian, satu bangsa yang berkarat", dan "memindahkan Gunung Semeru atau Gunung Kinibalu sekalipun." Simak kutipan-kutipan berikut bagaimana gaya bahasa yang digunakan untuk memikat massa.
"Janganlah melihat ke masa depan dengan Mata Buta! Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca mata
benggalanya dari pada masa yang akan datang."
(Pidato 17 Agustus 1966)
"Atau hendakkah kamu menjadi bangsa yang ngglenggem"? Bangsa yang 'zelfgenoegzaam'? Bangsa yang angler memeteti burung
perkutut dan minum teh nastelgi? Bangsa yang demikian itu pasti hancur lebur terhimpit dalam desak mendesaknya bangsa-bangsa lain yang berebut rebutan hidup!"
(Pidato 17 Agustus 1960)
Kita mau menjadi satu Bangsa yang bebas Merdeka, berdaulat penuh, bermasyarakat adil makmur, satu Bangsa Besar yang
Hanyakrawati, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kertaraharja, otot kawat balung wesi, ora tedas tapak palune pande, ora tedas gurindo.
(Pidato 17 Agustus 1963)
bersifat fiktif, tak didasari kenyataan. Soekarno melambung tinggi dengan ide-idenya dan cenderung mengabaikan kondisi konkret bangsanya terutama kondisi ekonomi.
Strategi penyebaran ideologi dalam tulisan Soekarno
Lalu jadilah Soekarno sebagai ideolog yang piawai menyebarkan kepercayaan-kepercayaannya. Strategi penyebaran ideologi yang oleh Terry Eagleton (1991) terdiri dari rasionalisasi, universalisasi, dan naturalisasi, dengan baik dimanfaatkan Soekarno dalam tulisan-tulisannya.
Rasionalisasi tampil dalam argumentasi-argumentasi yang
diusahakan tersusun selogis mungkin dan menggunakan rujukan-rujukan teori-teori ilmuwan terkemuka seperti Herbert Spencer, Havelock Ellis, dan Ernst Renan. Rasionalisasi dapat ditemukan dalam setiap karangannya, termasuk penggunaan data statistik demi memperkuat pendapatnya.
Strategi universalisasi dalam tulisan dan karangan Soekarno melibatkan ajaran-ajaran agama kutipan dari tokoh ternama dalam sejarah dan peristiwa penting dalam peradaban manusia. Gagasan-gagasannya seolah berlaku universal dan diperlukan di mana-mana."Firman Tuhan inilah gitaku, Firman Tuhan inilah harus
menjadi pula gitamu: "Innallaha la yu ghoiyiru ma bikaumin, hatta yu ghoiyiru ma biamfusihim"
(Pidato 17 Agustus 1964)
"Asal kita setia kepada hukum sejarah dan asal kita bersatu dan memiliki tekad baja, kita bisa memindahkan Gunung Semeru atau Gunung Kinibalu sekalipun."
(Pidato 17 Agustus 1965)
"Tetapi Tanah Air kita Indonesia hanya satu bahagian kecil saja dari pada dunia! Ingatlah akan hal ini! Gandhi berkata: "Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan."
(Pidato Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945)
"Ke Tuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Kedaulatan Rakyat, Keadilan Sosial. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini, yang nyata selalu menjadi isi daripada jiwa bangsa Indonesia."
(Pancasila sebagai Dasar Negara, hal:38)
Bukan hal yang aneh jika Soekarno berkembang menjadi seorang ideolog. Kepercayaan sejak kecil tentang kemuliaan, kepeloporan dan kepemimpinannya, mendorong kuat Bung Besar ini
menyebarkan kebenarannya. Gambaran diri yang fiktif dan mistis ini pula yang memberinya kepercayaan diri tampil berapi-api di depan lautan massa.
Dari mitos ke ideologi, dari kesepian ke kekuasaan
Merujuk Adler, benang merah perkembangan kepribadian Soekarno jadi begitu jelas. Masa dewasanya merupakan proyeksi dari
keinginan masa kecil. Soekarno membayangkan dirinya sebagai pembaru bangsa sejak kecil. Ia tumbuh sebagai manusia yang penuh dengan gagasan-gagasan yang terbilang baru di masa hidupnya. Kegemaran akan buku dan belajar berbagai hal tak lepas dari cita-cita yang digenggamnya erat-erat: menjadi penyelamat bangsa. Disiplin belajar yang dibiasakan ayahnya berpengaruh besar terhadap hal ini. Hingga di usia melampaui 60 tahun, ia masih gemar membaca. Kamar tidurnya penuh dengan buku sekaligus kutunya (Adams, 2000). Daya serapnya pun luar biasa.
Perpaduan berbagai aspek kepribadian dengan kualitas luar biasa inilah yang memungkinkannya tampil sebagai orator dengan wawasan begitu luas. Kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia juga berperan penting bagi perkembangan Soekarno. Mitos akan datangnya Ratu Adil, kepercayaan terhadap titisan dewa dan kepemimpinan politik yang tak lepas dari aspek spiritualitas memompa Soekarno berkembang menjadi tokoh yang dikultuskan.
Namun, sehebat-hebatnya ia mempengaruhi massa, seluas-luasnya wawasan di benaknya dan sebesar-besarnya kekuasaan yang dimilikinya, Bung Karno tak bisa lepas dari kebutuhannya untuk selalu memperoleh dukungan sosial. Kesepian menjadi derita yang menyakitkan hingga akhir hayatnya. Apa yang dilakukannya untuk memperoleh dukungan massa di sisi lain menjadikannya sebagai orang yang terasing, terpencil dari rakyat.
berikutnya. Kesakitan yang diderita Soekarno itu bisa menimbulkan perasaan lemah, tak berdaya, dan tersiksa yang disebut Adler
sebagai pe-rasaan inferioriti. Jika perasaan ini tidak ditangani secara tuntas maka akan timbul kecemasan yang mendukung munculnya perasaan inferioriti baru di ta-hap berikutnya hingga terakumulasi menjadi kompleks inferioriti-sebuah kondisi kejiwaan yang ditandai dengan perasaan rendah diri berlebihan dan kecemasan yang tinggi terhadap lingkungan sosial.
Untungnya lingkungan keluarganya memberi perhatian dan semangat yang memadai, terutama ibu, sehingga ia dapat menemukan perasaan aman dan nyaman di sana. Ia lalu sering tampil sebagai pemimpin yang dominan. Namun, ini pun
memunculkan suatu ketergantungan akan afeksi. Hingga dewasa kebutuhan afeksi itu tak jua tercukupi. Ia mengaku selalu
membutuhkan wanita sebagai pegangan.
Penggantian nama Kusno menjadi Karno dan penjelasan maknanya juga menjadi cara yang baik untuk menangani perasaan inferioriti yang dialami Soekarno kecil. Ia dapat menyusun sebuah
pemahaman di benaknya bahwa apa yang dialami merupakan sesuatu yang wajar sebagai seorang calon pahlawan besar sekelas Karna putra Kunti. Demikian pula dengan mitos-mitos tentang dirinya. Namun, ini pun mengakibatkan dirinya cenderung terpaku pada hal-hal besar dan mengabaikan hal-hal kecil.
Dalam kondisi-kondisi penuh dukungan lingkungan sosial, Soekarno bisa memperoleh perasaan superioritas, perasaan aman dan
nyaman menghadapi dunia. Untuk itu, ia selalu berusaha menarik perhatian banyak orang agar selalu berada di sekelilingnya, berpihak padanya. Pidatonya yang penuh kalimat bombastis merupakan cara memikat hati orang lain seperti seorang perayu yang tak ingin
kehilangan kekasihnya. Namun, di saat-saat kesepian ia bisa
mengalami perasaan frustrasi dan depresi. Ia sangat tidak menyukai kesendirian. Tragisnya, hukuman ini yang ia terima di akhir hidup, menjadi seorang tahanan rumah dan meninggal dalam kesepian.
Penutup
Liku-liku kepribadian Soekarno menunjukkan ada beberapa
kelemahan pada dirinya. Lepas dari kekurangan-kekurangannya, ia adalah orang besar. Kekurangan yang dimiliki adalah kekurangan yang sangat wajar dimiliki oleh manusia. Namun, kelebihannya dan cara mengatasi kekurangannya merupakan hal yang luar biasa. Ia mampu melampaui banyak orang dengan kelebihannya.
Soekarno memiliki kelemahan, tetapi bukan untuk mengecilkan arti sebagai manusia dengan segudang prestasi. Soekarno tetap layak menjadi orang yang dipuji, dihormati, dan dikenang selalu baik sebagai orang yang berjasa mendirikan Republik Indonesia maupun sebagai pribadi yang selalu terus berusaha mencapai kebaikan bagi dirinya dan orang lain.
>Jumat, 1 Juni 2001
Bung Karno di Bawah Bendera Jepang
Aiko KurasawaMENGAPA Soekarno, Bung Karno, memutuskan bekerja sama dengan Jepang pada waktu Indonesia diduduki oleh tentara Jepang? Riwayatnya bagaimana?
Pada waktu tentara Jepang masuk Indonesia, pada awal tahun 1942, Bung Karno ada di Sumatera. Dia dibuang oleh Belanda, pertama ke Ende, Flores, lalu ke Bengkulu. Dia sudah 13 tahun dibuang ke luar Jawa dengan istrinya, Ny Inggit Garnasih.
Riwayat Bung Karno bertemu dengan utusan tentara Jepang dan dibawa kembali ke Jawa yang ditulis dalam otobiografinya,
mengisahkan, waktu ada kabar tentara Jepang akan segera mendarat di Sumatera, petugas Belanda datang ke rumah Bung Karno di Bengkulu. Mereka memutuskan membawa Bung Karno ke Padang, dan dari sana membawanya ke Australia bersama dengan petinggi Belanda.
Belanda mungkin takut Bung Karno akan dimanfaatkan oleh Jepang. Agar tidak diketahui Jepang yang sudah mendekati pantai barat Sumatera, Bung Karno dan istrinya, disuruh jalan kaki di dalam hutan menuju ke Padang. Beberapa hari kemudian mereka keluar dari hutan, naik bus ke Padang. Waktu itu situasi Kota Padang sangat kacau, dan kebanyakan orang Belanda sudah lari. Ternyata sudah tidak ada kapal lagi yang bisa membawa Bung Karno ke Australia, artinya Bung Karno ditinggalkan Belanda. Dan, menurut Bung Karno, itulah kesalahan besar Belanda. Dia memutuskan tinggal di Padang, menumpang di rumah teman. Seminggu kemudian, tentara Jepang memasuki kota ini.
Perancis. Dan Sakaguchi mengundang Bung Karno ke Bukittinggi, Markas Besar Angkatan Darat Jepang Ke-25. Bung Karno dibawa ke sana dan dipertemukan dengan Kolonel Fujiyama.
Beberapa minggu lewat, tanpa kemajuan apa-apa. Lantas ada perintah dari Jawa agar Bung Karno dipulangkan ke Jakarta. Tentu saja Bung Karno senang sekali, dan pada bulan Juli 1942-empat bulan sesudah penjajahan militer Jepang dimulai-Bung Karno dan istrinya kembali ke Jakarta dengan naik kapal dari Palembang.
Dalam memoar Jenderal Imamura, Panglima Besar Pertama Angkatan Darat Jepang Ke-16 yang menduduki Pulau Jawa, ada cerita tentang pemulangan Bung Karno itu. Pada suatu hari, pemerintahan militer Jepang menerima permintaan dari pemuda-pemuda Indonesia agar Jepang membebaskan Bung Karno yang sedang dibuang di Bengkulu. Barisan Propaganda (Sendenbu) Jepang di Jawa yang waktu itu dipimpin Letkol Keiji Machida, mempertimbangkan dampaknya. Ia menyimpulkan, Bung Karno sangat berguna. Ia pun memerintahkan agar mencari Bung Karno di Sumatera. Mungkin di situlah Kapten Sakaguchi, atas perintah dari Jakarta, mencari Bung Karno.
Pembesar-pembesar Nanpo Sogun (Markas Besar Tertinggi di
Daerah Selatan) yang ada di Singapura waktu itu, ragu-ragu. Mereka khawatir munculnya dampak negatif pembebasan Bung Karno. Bung Karno dianggap sebagai seorang nasionalis yang sangat fanatik. Sebaliknya, Jenderal Imamura tidak peduli, dan menyetujui keputusannya Sendenbu.
Menurut catatan Jenderal Imamura, tidak lama sesudah Bung Karno kembali ke Jawa, Bung Karno minta bertemu Imamura. Tentu saja Jenderal Imamura setuju, dan Bung Karno diterima.
Kepala Barisan Propaganda Letkol Keiji Machida memberi
keterangan sedikit lain. Menurut dia, pertemuan itu diselenggarakan atas prakarsa Barisan Propaganda. Agar pertemuan itu bisa diterima oleh Jenderal Imamura, Machida memakai pelukis Basuki Abdullah sebagai alasan. Basuki Abdullah dikirim untuk melukis Jenderal Imamura, sedangkan Bung Karno dan Bung Hatta mendampingi. Letkol Machida pun mengatakan, Bung Karno adalah saudara Basuki Abdullah.
Dalam memoar Jenderal Imamura, diceritakan juga tentang seorang pelukis yang bernama Basuki Abdullah yang pernah melukis
Imamura. Menurut ingatannya, pelukis itu adalah saudara Soekarno. Saya tidak mengerti kenapa Machida harus memakai alasan
pertemuan panglima Jepang dan pemimpin Indonesia itu dan saya kurang yakin apakah pertemuan itu adalah pertemuan pertama antara Bung Karno dan Imamura.
Bukti terjadinya pertemuan adalah sebuah foto Jenderal Imamura dengan Basuki Abdullah, Bung Karno, Bung Hatta, dan Machida yang memegang lukisan Imamura hasil karya Basuki Abdullah. Kejadian ini sangat menarik, sebab pelukis yang terkenal itu pernah melukis Panglima Besar Tentara Jepang.
Tentang Bung Karno, Jenderal Imamura punya kesan sebagai sosok yang tenang, santun, bicaranya sopan. Juru bahasa yang dipakai pada waktu itu adalah seorang pemuda Jepang yang lahir di
Kalimantan dan dididik di sekolah Belanda. Meskipun umurnya baru 18 tahun, kemampuan bahasanya sangat baik.
Pada pertemuan pertama itu, Jenderal Imamura menanyakan apakah Bung Karno siap bekerja sama dengan Jepang. Menurut Imamura, ia tidak mekso. Dia memberi pilihan antara "bekerja sama" atau "bersikap netral". Dia hanya mengatakan kalau Bung Karno menentang Jepang, terpaksa akan dipakai cara-cara kekerasan. Jenderal Imamura juga tidak menjanjikan kemerdekaan, karena Pemerintah Jepang masih punya rencana untuk menguasai terus Indonesia. Imamura hanya berjanji, akan meningkatkan situasi keamanan dan memperbaiki kedudukan bangsa Indonesia.
Catatan Bung Karno tentang pertemuan dengan Jenderal Imamura tidak bertentangan dengan tulisan Imamura. Katanya, Imamura tidak memaksa Bung Karno bekerja sama dengan Jepang. Imamura juga tidak pernah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Imamura
mengatakan, semua keputusan tergantung pada kaisar, bahkan dia pun tidak tahu bagaimana status Indonesia di kemudian hari.
Sesudah pertemuan dengan Imamura, Bung Karno berunding
dengan teman-temannya selama beberapa hari. Akhirnya diputuskan untuk bekerja sama dengan Jepang. Sesuai dengan otobiografinya, maksud pertama Bung Karno bukan untuk "membantu" Jepang, tetapi "memanfaatkan" kesempatan itu untuk memperbaiki nasib bangsa Indonesia. Memang besar risikonya, tetapi Bung Karno mungkin merasa yakin bisa mengatasinya. Bung Karno
memperkirakan tentara Jepang tidak akan tinggal lama di Indonesia. Mereka nanti akan segera kalah. Oleh karena, itu dia pikir sebaiknya tidak menentang Jepang secara terbuka.
tahun 1936, dan sudah dijanjikan diberi kemerdekaan penuh pada tahun 1946. Harapan itu dihancurkan oleh masuknya tentara
Jepang. Presiden Quezon melarikan diri bersama pasukan Amerika, sambil memerintahkan kepada anak buahnya agar berpura-pura kerja sama dengan Jepang demi keselamatan bangsa. Mereka yang bekerja sama dengan Jepang antara lain adalah Jose P Laurel-ayah mantan Wakil Presiden Laurel-dan Benigno S Aquino-ayah
almarhum Benigno Aquino Junior-sekaligus mertua mantan Presiden Cora-zon Aquino. Waktu Amerika kembali dan menguasai Filipina, para pemimpin Filipina yang bekerja sama dengan Jepang dituntut sebagai pengkhianat dan diadili. Tetapi, sesudah Filipina mendapat kemerdekaan penuh pada tahun 1946, proses pengadilan mereka dihentikan. Dengan kata lain, pemimpin pemerintahan baru mengerti kenapa mereka terpaksa bekerja sama dengan Jepang.
(2) Bung Karno dalam film Jepang
Bung Karno diberi tugas memimpin organisasi rakyat, seperti Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dan Jawa Hokokai. Ia juga diberi tugas memberikan ceramah dan pidato untuk membangkitkan rasa benci terhadap Belanda dan rasa nasionalisme yang sudah lama ditindas Belanda. Dia sering menjadi "bintang film" dalam propaganda Jepang. Pada zaman pendudukan Jepang, film adalah media yang sangat menonjol sebagai sarana komunikasi. Tentara Jepang mempelajari strategi itu dari Nazi dan membuat banyak film propaganda dan film berita.
Pada waktu itu, angka buta huruf di kalangan rakyat Indonesia masih tinggi. Oleh karena itu, film yang sifatnya audio-visual, lebih mudah dimengerti dan punya dampak lebih besar daripada media cetak. Kantor cabang sebuah perusahaan film Jepang, Nippon Eigasha, dibuka di Jakarta. Dan mereka setiap bulan meluncurkan dua film berita dan dua film "budaya" (istilah terjemahan dari bahasa Jerman, artinya hampir sama dengan film dokumenter yang dibuat untuk maksud pendidikan dan propaganda).
Bung Karno sendiri dimasukkan hampir setiap bulan, baik dalam film berita maupun film budaya. Dalam film-film itu ia menyampaikan pidato yang cukup panjang. Suara dan wajah Bung Karno