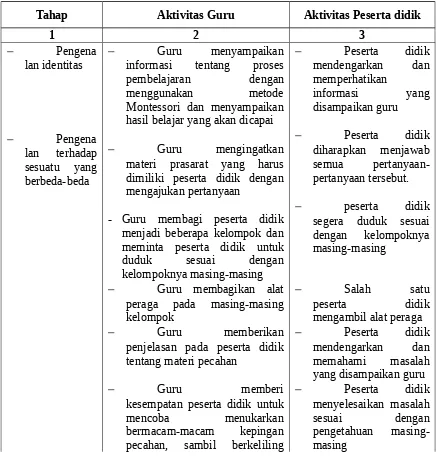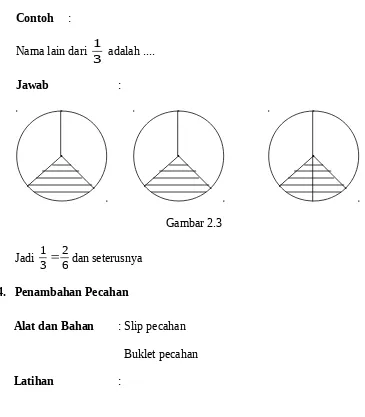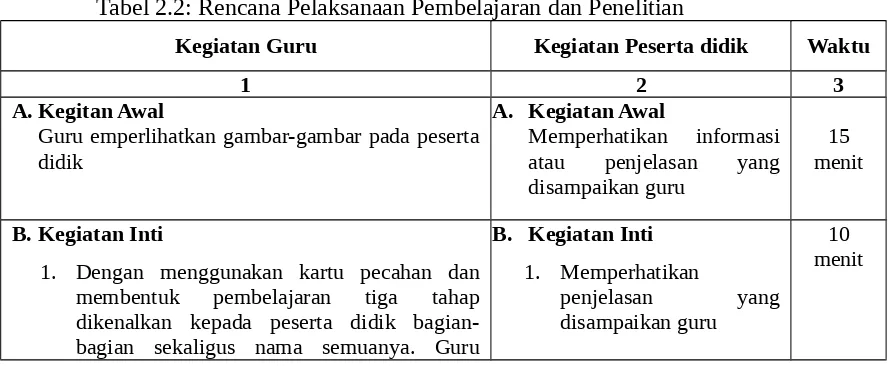BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tinjauan tentang Belajar Matematika 1. Pengertian Belajar
Belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk
mendapatkan aneka ragam competencies, skills, and attitudes.9 Dalam hal ini tentu saja ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan
sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk
seperti berubah pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku,
ketrampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada
pada individu yang belajar.
Hasil belajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk
dapat menguasai pengetahuan, kemampuan, kebiasaan, keterampilan dan
sikap melalui hubungan timbal balik antara orang yang belajar dengan
lingkungannya.10
Berbagai kegiatan tersebut dapat bersifat positif, progresif dan
konstruktif. Suatu kegiatan dapat bersifat positif jika tingkah laku,
kebiasaan-kebiasaan rutin yang diperbuatnya itu berguna. Progresif artinya perbuatan itu
bersifat konstruktif artinya kemajuan-kemajuan yang diperoleh dapat
dimanfaatkan bagi perkembangan lingkungannya.
9 Udin S.Winata Putra, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007),
1.5
10 E.P. Hutabarat, Cara Belajar Pedoman Praktis, Secara Efisien dan Efektif, (Jakarta: PT.
2. Pengertian hasil belajar
Hasil belajar atau lebih dikenal dengan prestasi adalah hasil yang telah
dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan).11 Seseorang dapat dikatakan
berprestasi apabila ia dapat mencapai hasil maksimal dari apa yang telah
dilakukan. Begitu halnya seorang peserta didik apabila memperoleh
prestasi belajar yang tinggi, maka peserta didik
tersebut berarti telah mencapai tujuan-tujuan belajar yang telah
ditentukan.
Prestasi belajar adalah hasil secara maksimal dicapai oleh seseorang.
Hasil maksimal tersebut telah dicapai berdasarkan kemampuan yang dimiliki,
karena setiap peserta didik memiliki perbedaan kemampuan, kemauan, minat
dan intelegensi yang tidak sama. Usaha yang tekun dari diri sendiri dan
dorongan dari luar yakni berupa motivasi dan bimbingan dari guru akan
menentukan hasil maksimal yang dicapai oleh peserta didik.
Hasil belajar peserta didik pada hakikatnya adalah perubahan tingkah
laku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan
aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari
oleh pembelajar. Dalam pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai
oleh pembelajar setelah melaksanakan aktifitas belajar dirumuskan dalam tujuan
pembelajaran. Perubahan sebagai hasil proses dapat ditunjukkan dalam berbagai
11 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta : Balai
bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kecakapan,
serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar.
Aspek penilaian hasil belajar dalam KTSP dalam penelitian ini adalah
aspek pemahaman konsep. Pemahaman konsep merupakan kompetensi yang
ditunjukkan peserta didik dalam memahami konsep dan dalam melakukan
prosedur secara luwes, akurat, efisien dan tepat. Indikator yang menunjukkan
pemahaman konsep antara lain adalah sebagai berikut:
a. Menyatakan ulang sebuah konsep.
b. Mengklasifikasi objek menurut sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya).
c. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep.
d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis.
e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep.
f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu.
g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah.
Dengan demikian keberhasilan pembelajaran terletak pada proses
belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Sedangkan dari segi prestasi adalah
hasil belajar yang diperoleh peserta didik sebagai akibat proses belajar yang
dilakukan oleh peserta didik. Muhibbin Syah mengatakan bahwa kunci pokok
untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar peserta didik adalah
mengetahui garis-garis besar indikator (petunjuk adanya prestasi tertentu)
dikaitkan dengan jenis prestasi yang hendak diungkapkan atau diukur.
Jadi usaha dari peserta didik dan guru merupakan unsur yang
mempunyai peranan yang sangat penting bagi terwujudnya pembelajaran
kemampuan para pendidik dalam membimbing belajar murid-muridnya amat
dituntut. Jika guru dalam keadaan siap dan memiliki profesi (berkemampuan
tinggi) dalam menunaikan kewajibannya, maka harapan terciptanya sumber
daya manusia yang berkualitas sudah tentu akan tercapai.
Selain itu, peserta didik juga harus ditekankan mengguasai
keterampilan proses. Keterampilan proses lebih menekankan pada
keterampilan untuk memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan
hasilnya. Hal ini berarti proses belajar mengajar di SD/MI tidak hanya
berlandaskan pada teori pembelajaran perilaku, tetapi lebih menekankan pada
penerapan prinsip-prinsip belajar dari teori kognitif. Implikasi teori belajar
kognitif dalam pengajaran Matematika adalah memusatkan kepada berpikir
atau proses mental anak, dan tidak sekedar kepada hasilnya. Relevansi dari
teori konstruktivis, peserta didik secara aktif membangun pengetahuan
sendiri. Dengan menggunakan keterampilan-keterampilan memproses
perolehan, peserta didik akan mampu menemukan dan mengembangkan
sendiri fakta dan konsep serta menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan
nilai.
Dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan memproseskan
perolehan, anak akan mampu menemukan dan mengembangkan sendiri fakta
dan konsep serta menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai yang
dituntut. Dengan demikian keterampilan-keterampilan itu menjadi roda
penggerak, penemuan dan pengembangan fakta dan konsep serta penumbuhan
proses belajar mengajar seperti ini akan menciptakan kondisi pembelajaran
yang aktif dan efektif.
Paparan di atas mengisyaratkan bahwa secara psikologis guru harus
mengetahui kemajuan anak didik yang menjadi tanggung jawabnya itu.
Pengetahuan hal ini akan memberikan rasa pasti dan memberinya dasar untuk
menentukan langkah-langkah lebih lanjut.
Untuk mengetahui keberhasilan belajar, maka perlu dilakukan evaluasi
untuk mengukur proses. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data
deskriptif tentang produk peserta didik dan hubungannya dengan standart
prestasi atau norma.12
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Pada pendahuluan telah diuraikan tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi prestasi belajar secara ringkas, tetapi masih ada perlunya
untuk memberikan perhatian khusus kepada salah satu hal, yaitu hal yang
mendorong aktifitas dilakukannya perbuatan belajar itu.
Proses mengajar itu diarahkan agar terjadi peristiwa belajar. Belajar
matematika akan berhasil bila melibatkan intelektual peserta didik secara
optimal. Peristiwa belajar yang kita kehendaki bisa tercapai bila faktor-faktor
berikut ini dapat dikelola sebaik-baiknya. 13
a. Faktor yang berasal dari diri peserta didik (intern)
12 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Bumi Aksara, 2001), 146-147 13 Bustanul Arifin, Perpustakaan dan Konteks Pembelajaran, (Kediri: Jurnal Tribakti, Volume
Kegagalan atau keberhasilan belajar sangatlah tergantung kepada
peserta didik, antara lain dipengaruhi faktor-faktor berikut ini:
1) Kemampuan dan kesiapan peserta didik untuk mengikuti kegiatan
belajar matematika
2) Sikap dan minat peserta didik terhadap matematika
3) Kondisi fisiologis dan psikologis peserta didik
4) Intelegensi peserta didik
b. Faktor yang berasal dari luar diri peserta didik (ekstern)
Faktor yang berasal dari diri peserta didik terdiri dari beberapa hal
sebagaiman berikut:
1) Faktor yang berasal dari lingkungan sekolah. Faktor lingkungan
sekolah adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik
di lingkungan belajarnya secara formal. Jadi jelas bahwa lingkungan
sekolah mempunyai sistem khusus dalam proses pembelajaran,
misalnya; kapasitas kompetensi guru, metode pembelajaran,
materi/kurikulum, teknik evaluasi dan sebagainya.
Seorang pengajar melaksanakan kegiatan mengajar dengan
tujuan agar agar proses-proses belajar dapat berlangsung efektif.
Keberhasilan pengajar dalam melaksanakan kegiatan mengajar
matematika ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut:
a) Kemampuan pengajar dalam menyampaikan materi matematika
c) Kepribadian, pengalaman dan motivasi pengajar dalam mengajar
matematika
Begitu juga dengan teknik penilaian. Fungsi penilaian adalah
untuk meningkatkan kegiatan belajar sehingga diharapkan dapat
membaiki hasil belajar maupun proses belajar peserta didik. Penilaian
dipergunakan disamping untuk melihat bagaimana hasil belajarnya,
tetapi juga untuk melihat bagaimana berlangsungnya interaksi antara
pengajar dan peserta didik. Misalnya kita dapat menganalisis tentang:
a) Keberhasilan peserta didik dalam belajar matematika.
b)Apakah di dalam proses belajar matematika itu didominasi pengajar
ataukah komunikasi terjadi dua arah.
c) Apakah pertanyaan yang diajukan pengajar kepada peserta didik
merangsang belajar atau mematikan.
d)Apakah jenis pertanyaan yang diajukan pengajar menyangkut ranah
kognitif rendah seperti ingatan dan pemahaman saja, ataukah ranah
kognitif tinggi seperti penyelesaian masalah.
2) Faktor yang berasal dari lingkungan keluarga. Faktor ini teruma
ditujukan pada kedua orang tua yang tentunya lebih dekat dengan
keadaan peserta didik, baik secara fisik maupun psikis.
3) Faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan
masyarakat ini juga sangat mempengaruhi hasil belajar peserta didik.
adalah media massa, teman pergaulan, kegiatan organisasi dan pola
hidup lingkungan dimana ia tinggal.
Dari paparan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar
diatas, tentu erat kaitannya dengan proses belajar. Apabila faktor-faktor
tersebut lebih mengarah ke arah yang positif, dapat diharapkan hasil belajar
lebih baik dari pada yang mengarah ke arah yang negatif.
B. Pembelajaran Matematika 1. Hakekat Matematika
Kata Matematika secara etimologi berasal dari Yunani “mathein” atau
“mathenein” yang artinya mempelajari.14 Ada pula yang mengatakan
matematika berasal dari bahasa latin yaitu “mathematike” yang artinya
relating to learning atau berkaitan dengan pengetahuan.15 Jadi berdasarkan
asal usulnya kata matematika itu berarti pengetahuan yang diperoleh dari
proses belajar, namun pengertian matematika secara istilah banyak pengertian
yang diberikan oleh para ahli dan para matematikawan yang semua itu sesuai
sudut pandangnya masing-masing, sehingga pemaknaanya sangat luas dan
fleksibel, sebagaimana James dan James mengatakan bahwa, “matematika
adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk susunan, besaran, dan
konsep-konsep berhubungan lainnya yang jumlahnya banyak.”16 Tokoh lain yaitu
14 Andi Hakim Nasution, Landasan Matematika, (Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1982), 12 15 The Liang Gie, Filsafat Matematika Bagian Kedua, (Yogyakarta : Yayasan Studi Ilmu dan
Teknologi, 1993), 5
16 E.T. Ruseffendi, Pengajaran Matematika Modern dan Masa Kini Untuk Guru dan PGSD
D2 Seri pertama, (Bandung : Tarsito, 1990), 1
W.W. Sawyer mengatakan, “mathematic is the classification and study of all
possible pattern”17 (Matematika adalah penggolongan dan penelaahan tentang
semua pola yang mungkin). O.G. Sutton mengemukakan matematika adalah
“suatu penelaahan tentang pola-pola dari ide-ide, yang dilakukan dengan
suatu teknik khusus yang telah dikembangkan secara tinggi, yang dipercayai
akan kebenarannya”.18 Selain pendapat di atas, ada pula yang mengatakan
bahwa, “hakekat matematika adalah berkenaan dengan ide-ide, struktur, dan
hubungannya yang diatur menurut urutan yang logis”.19 Ada pula yang
mengemukakan bahwa, “matematika adalah telaahan tentang pola dan
hubungan suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu
alat”.20
Sedangkan Kline mengatakan bahwa, “Matematika bukanlah
pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi
adanya matematika itu untuk membantu manusia dalam memahami dan
menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam”.21
Pengertian matematika sebagai ilmu adalah salah satu cabang ilmu yang tersusun secara sistematis dan eksak. Pengertian eksak tersebut tidak berarti eksak secara mutlak, akan tetapi matematika sebagai ilmu lebih eksak daripada ilmu-ilmu sosial dan lebih eksak daripada ilmu-ilmu fisik oleh karena sifatnya yang eksak ini maka matematika sering disebut sebagai ilmu pasti.22
17 The Liang Gie, Filsafat…, 28 18 Ibid, 30
19 Herman Hudojo, Pengembangan Kurikulum Matematika dan Pelaksanaannya di Depan
kelas, (Surabaya : Usaha Nasional, 1979), 96
20 E.T. Ruseffendi, Pengajaran…, 2
Seperti dikatakan diawal, bahwa pendefinisian matematika berfokus
pada tinjauan dan sudut pandang pembuat definisi, sehingga tidak ada kata
sepakat mengenai apa itu arti matematika secara terminologi, akan tetapi
dapat terlihat dari ciri khusus atau karakteristik pengertian matematika secara
umum, yaitu:
a. Memiliki obyek kajian abstrak. b. Bertumpu pada kesepakatan. c. Berpola pikir deduktif.
d. Mempunyai simbol yang kosong dari arti. e. Memperhatikan semesta pembicaraan. f. Konsisten dalam sistemnya.23
Adapaun penjabaran dari masing-masing item tersebut di atas adalah
sebagai berikut:
a. Memiliki obyek kajian abstrak
Dalam matematika obyek dasar yang dipelajari adalah abstrak atau
obyek mental. Obyek-obyek itu merupakan obyek pikiran. Obyek dasar ini
meliputi fakta, konsep, operasi ataupun relasi dan prinsip. Dari obyek
dasar inilah dapat disusun suatu pola dan struktur matematika.
b. Bertumpu pada kesepakatan
Dalam matematika kesepakatan merupakan tumpuan yang amat
penting. Kesepakatan yang amat mendasar adalah aksioma dan konsep
primitif. Aksioma diperlukan untuk menghindarkan berputar-putar dalam
pembuktian. Sedangkan konsep primitif diperlukan untuk menghindarkan
berputar-putar pada pendefinisian.
23 R. Soejadi, Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia Konstalasi Keadaan Masa
c. Berpola pikir deduktif
Dalam memahami matematika sebagai “ilmu” adalah hanya
diterima pola pikir deduktif. Maksud pola berpikir deduktif secara
sederhana dapat dikatakan pemikiran yang berpangkal dari hal yang
bersifat umum diterapkan atau diarahkan kepada hal yang bersifat khusus.
d. Mempunyai simbol yang kosong dari arti
Dalam matematika banyak sekali simbol-simbol yang digunakan,
baik berupa huruf ataupun bukan huruf. Makna dari huruf dan tanda itu
tergantung dari permasalahan yang mengakibatkan terbentuknya model
tersebut.
e. Memperhatikan semesta pembicaraan
Dalam menggunakan matematika diperlukan kejelasan dalam
lingkup apa model itu dipakai. Bila lingkup pembicaraannya bilangan,
maka simbol–simbol diartikan bilangan. Namun bila lingkup
pembicaraannya transformasi, maka simbol–simbol itu diartikan
transformasi. Lingkup pembicaraan inilah yang disebut dengan semesta
pembicaraan.
f. Konsisten dalam sistemnya
Dalam matematika terdapat banyak sistem yang berkaitan satu
sama lain, tetapi ada pula sistem yang dapat dipandang terlepas satu sama
lain. Kontradiksi antara sistem tersebut tetap bernilai benar pada sistem
Beberapa uraian diatas tersebut adalah tentang matematika sebagai
ilmu, sedang matematika yang diajarkan di sekolah mulai pra sekolah sampai
SMU sering disebut dengan matematika sekolah. Berikut ini penulis akan
membahas tentang matematika sekolah (School Mathematic). Definisi
matematika sekolah adalah unsur-unsur atau bagian-bagian dari matematika
yang dipilih berdasarkan kepada kepentingan pendidikan dan perkembangan
IPTEK.24 Hal ini menunjukkan bahwa matematika sekolah tidak sepenuhnya
sama dengan matematika sebagai ilmu. Adapun perbedaanya terletak pada:
a) Cara penyajiannya, penyajian dalam buku matematika di sekolah tidak selalu diawali dengan teorema ataupun definisi. Disesuaikan dengan perkembangan intelektual peserta didik.
b) Pola pikirnya, dalam matematika sekolah meski tetap diharapkan mampu berfikir deduktif, namun pada proses pembelajarannya dapat menggunakan pola pikir induktif.
c) Keterbatasan semestanya, dalam matematika di SD terlihat secara bertahap diperkenalkan bilangan bulat positif, kemudian lebih atas lagi diperkenalkan pecahan dan bilangan negatif. Jadi semestanya sempit kemudian meluas.
d) Tingkat keabstrakannya, diawal pendidikan tingkat abstraksi rendah, semakin tinggi pendidikan semakin tinggi pula tingkat abstraksinya.25
Terkait dengan fungsi dan tujuan matematika diajarkan di sekolah
dasar, matematika berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berhitung,
memgukur, menurunkan dan mengggunakan rumus matematika yang
diperlukan dalam kehidupan sehari-hari melalui materi pengukuran dan
geometri, dan aljabar. Selain itu matematika sekolah berfungsi untuk
mengembangkan kemampuan mengomunikasikan gagasan dengan bahasa
melalui model matematika yang dapat berupa kalimat dan persamaan
matematika, diagram grafik atau tabel.26
2. Proses Mengajar dan Belajar Matematika
Sebagaimana pembahasan sebelumnya matematika berkenaan dengan
ide-ide terstruktur yang sangat hirarkis, sehingga untuk mempelajari suatu
konsep tertentu haruslah menguasai konsep-konsep sebelumnya. Misalnya
saja untuk mempelajari konsep “B” haruslah paham dan menguasai konsep
sebelumnya yaitu konsep “A”, tidak mungkin seorang peserta didik mampu
memahami konsep “B” sebelum mampu memahami konsep “A”. Jadi kalau
misalnya untuk memahami konsep perkalian, haruslah terlebih dahulu
memahami konsep penjumlahan. Misal lain untuk memahami tentang
bilangan pecahan harus dipahami terlebih dahulu tentang bilangan asli, karena
bilangan pecahan didasarkan pada bilangan asli.
Disamping itu, atas dasar struktur kognitif peserta didik maka bahan
pelajaran harus disusun menurut urut-urutan tingkat kesukaran yang logik dan
berdasarkan atas pengalaman-pengalaman belajar yang terdahulu. Menurut
Ausubel, bahan pelajaran yang dipelajari haruslah “bermakna” (meaningful)
artinya bahan pelajaran itu cocok dengan kemampuan peserta didik dan harus
relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik.27 Dengan
26 Depdiknas, Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran Matematika SMP dan
MTs, (Jakarta : Dediknas, t.t.), 5
27 Hudoyo, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika, (Malang : UNM,
perkataan lain, pelajaran baru haruslah dikaitkan dengan konsep-konsep yang
sudah ada sedemikian sehingga konsep-konsep baru benar-benar terserap.
Dengan demikian intelektual-emosional peserta didik terlibat didalam
kegiatan belajar mengajar. Jelas pula kiranya, matematika sebagai suatu
pengetahuan yang tersusun menurut struktur, disajikan kepada peserta didik
dengan cara yang dapat membawa kebelajar bermakna seperti pengertian
Ausuble tadi. Belajar yang bermakna adalah bertentangan dengan belajar
secara menghafal.28 Belajar dengan menghafal berarti bahwa belajar
dikerjakan secara mekanis, sekedar suatu latihan mengingat tanpa suatu
pengertian. Jika matematika dipelajari dengan hafalan, maka peserta didik
akan menjumpai kesulitan sebab bahan pelajaran yang diperoleh dengan
hafalan belum “siap pakai” untuk menyelesaikan masalah bahkan juga dalam
situasi-situasi yang mirip dengan bahan yang dipelajari itu.
Secara singkat, pengajaran matematika kepada peserta didik adalah
sebagai berikut :
(1) Dalam proses belajar matematika kita harus memperhatikan tahap peserta didik memahami konsep, yaitu tahap: bermain bebas, permainan, penelaahan sifat bersama, representasi, penyimbulan, dan penformalan. (2) Dalam menanamkan konsep matematika itu kita supaya menggunakan alat
peraga dan atau model, penyajiannya supaya beranekaragam dan sesuai dengan konsep yang akan ditanamkan.
(3) Sesuai dengan hakekat matematika sebagai ilmu kreatif dan hakekat anak yang suka bermain, sajikanlah pengajaran matematika sedemikian rupa sehingga menunjang kondisi dan harapan itu.29
28 Ibid.
Seperti yang telah dikemukakan, bahwa belajar berkenaan dengan
proses perubahan tingkah laku dan dalam mengajar guru sebagai fasilitator
maka dalam proses belajar mengajar matematika guru merupakan mediator,
peracik lingkungan bagaimana agar peserta didik mampu menerima, mengatur
dan mengolah informasi secara sistematis dalam mata pelajaran matematika
sesuai kehirakisan matematika.
Agar proses mengajar belajar matematika ini berlangsung baik, perlu
diatur strateginya. Strategi berkaitan dengan cara-cara yang dipilih pengajar
dalam menentukan ruang lingkup, urutan bahasan, kegiatan dan sebagainya
untuk menyampaikan materi matematika kepada peserta didik, sehingga dapat
memperlancar tercapainya tujuan belajar matematika.
Strategi yang dipilih oleh pengajar tergantung pada bahasan
matematika yang akan disampaikan. Misalnya, jika pengajar menghendaki
agar peserta didik mempunyai kemauan dan keterampilan dalam
menyelesaikan masalah-masalah yang sangat kompleks dan sukar
diperhitungkan yang dihadapi kelak dikemudian hari, maka strategi yang
relevan yang dipilih oleh pengajar dalam pembelajaran matematika adalah
pemecahan masalah.
Strategi belajar mengajar yang berorientasi pada belajar berdasarkan
hirarkinya menurut Gagne adalah membilah-bilah bahan yang akan diajarkan
kedalam bagian-bagian lebih lanjut (makin komplek).30 Gagne memandang
pada pembelajaran semua mata pelajaran hendaknya terus ditingkatkan mulai
dari kaitan-kaitan stimulus-respon sederhana, serta konsep-konsep atau
aturan-aturan (dalil-dalil) sampai pada pemecahan masalah yang tingkat
berpikirnya lebih tinggi dalam penerapan strategi belajar mengajar. Namun
demikian, harus disesuaikan dengan tingkat-tingkat proses belajar peserta
didik, atau disesuaikan dengan kesiapan belajar peserta didik.
C. Metode Pengajaran Matematika dengan Teknik Montessori
Metode pengajaran Montessori pertama kali diperkenalkan oleh Dr.
Maria Montessori yang lahir di Italia pada tahun 1870 dan metode ini sendiri
mulai diajarkan Montessori setelah diangkat menjadi kepala sekolah yang khusus
menangani masalah anak yaitu pada tahun 1898. Metode ini merupakan
pengajaran untuk anak sekolah dasar. Karena itu metode pengajaran Montessori
dapat dilakukan oleh orang tua di rumah untuk membantu pengajaran anak. Tetapi
tidak menutup kemungkinan metode ini digunakan di sekolah untuk
menyampaikan konsep-konsep yang sesuai.31
Pada materi pecahan digunakan beberapa materi yang sesuai. Melalui
pemanfaatan materi-materi pecahan, anak melihat bagaimana suatu kesatuan
dipecah dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Pada awalnya, ini lebih merupakan
latihan visual dari pada latihan intelektual. Tetapi dengan memegang
kepingan-kepingan pecahan, anak menjadi akrab dengan pecahan dan komposisinya.
Simbol-simbol tertulis untuk pecahan diperkenalkan dan soal-soal sederhana
dikerjakan.
Pengajaran Montessori pada sembarang tingkatan senantiasa mengikuti
prinsip-prinsip dasar observasi, kebebasan individu dan persiapan belajar dalam
mata pelajaran matematika, metode pengajaran Montessori mengenalkan
konsep-konsep dasar dengan menggunakan alat peraga. Materi-materi harus senantiasa
dipergunakan dengan tepat sebelum anak dibiarkan belajar sesuai dengan
kecapatannya sendiri.
Metode pembelajaran tiga tahap dan metode demontrasi digunakan secara
bersama-sama dalam metode pembelajaran Montessori untuk menyampaikan
konsep-konsep dalam pengajaran matematika. Metode demontrasi digunakan
karena dalam setiap pengenalan konsep selalu melibatkan alat peraga.
Tujuan pembelajaran tiga tahap dalam pengajaran konsep-konsep baru
dengan cara repetitive (pengulangan) dengan demikian membantu anak
memahami lebih baik materi-materi yang disajikan, dengan pembelajaran tiga
tahap guru lebih mudah mengetahui seberapa jauh anak menyerap dan menguasai
apa yang diperlihatkan kepada mereka.
Pembelajaran tiga tahap meliputi :
Tahap pertama : Pengenalan identitas (Recognition of identity)
Tahap kedua : Pengenalan terhadap sesuatu yang berbeda-beda
(Recognition of contrasis)
Tahap ketiga : Membedakan antara benda-benda yang serupa
(Diskrimination between similar objects)
konsep-konsep matematika dasar pada usia dini anak-anak tidak akan menemui
kesulitan dalam mengasimilasi fakta-fakta dan kecakapan-kecakapan dasar.
Secara fisik anak memegang kuantitas-kuantitas yang dia lihat terwakili dalam
simbol-simbol tertulis. Anak-anak memadukan materi-materi, hitungan-hitungan,
pemisahan-pemisahan dan membandingkan sementara secara visual menyentuh
dan memperkuat gagasan sampai batas tertentu bahwa ini nyata, bukunya abstrak.
Guru menyodorkan kepada anak sebuah konsep jadi dan membiarkan kepada
mereka meraih realisasinya melalui belajar sesuai dengan kecepatan
masing-masing anak. Dengan cara lain anak memahami dan melihat hubungan antara
angka-angka dan juga mampu menyerap gagasan bahwa nilai suatu angka
ditandai dengan posisi dimana nilai tersebut dituliskan. Pertama-tama yang
diajarkan adalah nama-nama kuantitas dan akhirnya keduanya dipadukan.
Tujuan pembelajaran Montessori ini sendiri berbasis pada pengembangan
seluruh potensi anak sejak dini hingga anak dapat melakukan segala sesuatunya
secara mandiri. Pembelajaran dilakukan secara nyata dengan mempraktekannya.
Dengan menggunakan materi berbeda yang tersedia bagi macam-macam
proses matematis, anak berulang kali disodori keberagaman persoalan pada suatu
tema pokok. Dengan memegang materi dan menggunakannya dalam cara-cara
yang berbeda-beda, konsep-konsep yang sepintas kurang jelas menjadi gamblang
karena anak tidak hanya melihat gagasan-gagasan dasar tetapi menemukan
gagasan-gagasan baru lainnya.
Fakta-fakta tidak hanya diingat lebih dari itu melalui pengulangan
fakta-fakta lebih cepat dimengerti. Dan begitu operasi-operasi yang diperlukan
operasi.
Dari uraian di atas diambil kesimpulan metode pengajaran Montessori
adalah metode pengajaran yang memadukan metode demonstrasi dan metode
pembelajaran tiga tahap dengan menggunakan materi-materi manipulatif untuk
mengajarkan konsep-konsep matematika dasar.
Tabel 2.1 Langkah-langkah metode pembelajaran Montessori materi pecahan
Tahap Aktivitas Guru Aktivitas Peserta didik
1 2 3
Guru menyampaikan
informasi tentang proses
pembelajaran dengan
menggunakan metode
Montessori dan menyampaikan hasil belajar yang akan dicapai
Guru mengingatkan peraga pada masing-masing kelompok pecahan, sambil berkeliling
kelas memperhatikan perkejaan untuk membandingkan dan
mendiskusikan dengan
kelompoknya masing-masing,
sambil berkeliling
memperhatikan diskusi masing-masing kelompok
Guru memberi petunjukn bagi kelompok yang mengalami kesulitan
Guru menunjuk secara acak beberapa peserta didik mewakili kelompoknya untuk menampilkan hasil diskusi didepan kelas.
Guru menunjukan bahwa bagian yang kosong dapat diganti dengan slip pecahan yang lain yang cocok
Berdasarkan hasil diskusi kelas guru mengarahkan peserta didik untuk menarik kesimpulan
Guru menegaskan
kembali hal-hal penting yang berkaitan dengan materi pemebelajaran Beberapa peserta
didik yang telah
D. Tinjauan Materi Tentang Pokok Bahasan Pecahan 1. Materi Pecahan
tebal berbentuk lingkaran, masing-masing diletakkan pada sebuah bidang
persegi. Antara lingkaran dan bidang persegi tersebut harus berwarna
mencolok satu sama lain. Lingkaran pertama kosong, sedangkan yang kedua
terbagi dua dan seterusnya sampai lingkaran kesepuluh yang terbagi menjadi
sepuluh bidang sama besar. Setiap pecahan lingkaran memiliki semacam
tombol kecil atau pegangan agar mudah diambil. Lingkaran-lingkaran bisa
dipotong dari kertas poster, menggunakan sebuang kerangka berukuran “ 5
persegi dan lingkaran berdiameter 3,5 ”, manik-manik kecil atau seutas kain
mungkin diletakkan pada bidang yang ada untuk tombol-tombol pegangan.
Gambar 2.1
a. Kartu Pecahan
Ada dua macam kartu pecahan. Keduanya berukuran kecil
kira-kira 4 1
persegi, dipotong dengan menyesuaikan pada bidang-bidang
pecahan lingkaran seperti dijelaskan diatas. Satu macam kartu ditulis
sesuai dengan bidang-bidang pecahan tunggal misalnya 2 1
dan
bidang pecahan kombinasi atau gabungan misalnya 3 2
dan sebagainya.
Gambar 2.2
b. Buklet pecahan
Buklet pecahan ini merupakan buklet atau buku berukuran kecil
kira-kira "3 x 2"(ukuaran folio) masing-masing berisi enam sampai
delapan halaman. Pada salah satu sisi halaman dituliskan sebuah soal
pecahan untuk dikerjakan. Ada sejumlah buklet pecahan semacam ini
yang diperuntukan bagi penambahan, pengurangan, perkalian dan
pembagian. Berawal dari soal-soal yang mudah sampai soal-soal yang
sulit. Ada juga sejumlah buklet yang berisi pecahan yang semakin
berkurang sampai pembilang terkecil
2. Pengenalan Pecahan
Alat dan Bahan : Slip pecahan Kartu pecahan
Buklet pecahan
Demontrasi :
Latihan 1 :
1) Bawalah slip dan kerangka pecahan untuk kesatuan, setengah, sepertiga
2) Letakkan bagian yang berkesesuaian dengan setiap slip diatas meja,
gunakan pembelajaran bentuk tiga tahap untuk memperkenalkan kepada
anak bagian-bagian sekaligus nama kesemuanya.
3) Bila anak sudah memahami bagian dan keterkaitan dengan smua
masing-masing, tunjukan bagaimana caranya bagian-bagian kerangka tersebut
saling terhubung untuk membentuk satu kesatuan misalnya tiga pertiga
4) Tunjukan bagaimana agar kepingan atau bagian dapat saling ditukar
misalnya setengah bisa disusun dari dua kepingan seperempat
5) Perkenalan kerangka pecahan-pecahan lain dengan cara yang sama
Tujuan :
Memperhatikan bahwa satu kesatuan tersusun dari bagian-bagian pecahan.
Latihan 2 :
1) Tunjukan kepada anak bagaimana pecahan ditulis misalnya setengah
ditulis 2 1
,
2) Keluarkan semua kartu pecahan untuk setiap stel pecahan dan letakkan
setiap kepingan pecahan. Gunakan pembelajaran bentuk tiga tahap.
3) Ajarkan nama-nama penyebut dan pembilang, jelaskan bahwa pembilang
menjelaskan berapa banyak dan penyebut memberi nama pada pecahan.
4) Biarkan anak-anak menukarkan bermacam-macam kepingan pecahan.
5) Tunjukan bagaimana suatu kepingan dapat dikelompokan untuk
membentuk satu bagian yang lebih besar, dan letakkan kartu pecahan
6) Lakukan banyak pergantian, untuk mendapatkan satu pengetahuan proses
kerja pecahan, juga bagaimana kesemuanya dan dikombinasikan satu
sama lain.
7) Anda hendaknya selalu memiliki sebuah kerangka kosong ukuran tangan
untuk mengerjakan soal anda sendiri. Ini dimaksudkan untuk
mempermudah anak untuk melihat contoh penyesuaian
Tujuan :
Untuk mengakrabkan anak pada bilangan pecahan.
3. Nama Lain Pecahan
Alat dan Bahan : Slip pecahan Buklet pecahan
Latihan :
1) Ambilah sebuah pecahan setengah dari lingkaran dan tanya anak apakah
dia dapat memasang kepingan yang sesuai untuk bagian kosong tersebut
dari sliip pecahan yang lain. Saat mengerjakan ini anak melihat bahwa
setengah tidak dapat diisi dengan sepertiga, tetapi dua seperempat sangat
cocok untuk mengisi bagian kosong yang ditinggalkan kepingan setengah
tersebut. Dia bekerja terus dengan cara ini untuk melihat pecahan mana
lagi yang dapat mengisi bagian setengah serta mencatat hasil misalnya:
10
anak menjadi akrab dengan beragam bilangan pengganti
setiap halamannya
4) Jika contohnya 10
4
jelaskan anda ingin menukar pecahan dengan yang
memiliki dengan sekecil mungkin namun sama besarnya
5) Bila anak telah menggunakan bahan beberapa kali dengan memahaminya,
jelaskan aturan untuk memperkecil pecahan dan untuk memperkecil dan
tunjukan bagaimana jawaban dapat diperkecilkan akar penyebut terkecil.
Tujuan :
Untuk memahami pecahan dan bagian-bagian pembentuknya.
Contoh : Nama lain dari
3 1
adalah ....
Jawab :
Gambar 2.3
Jadi 6 2 3 1
dan seterusnya
4. Penambahan Pecahan
Alat dan Bahan : Slip pecahan Buklet pecahan
1) Gunakan kerangka kosong untuk mengerjakan soal
2) Anak mengambil buku kecil, membaca soal pertama dan dengan slip yang
tepat mendapatkan jawaban kemudian menuliskannya
3) Sebagai contoh, jika soalnya adalah
yang lain dan menyaksikan bahwa 1 3
4) Ketika anak telak melaksanakan beberapa kali latihan seperti ini, jelaskan
bahwa jika pecahan-pecahan memiliki bilangan penyebut yang sama,
maka pembilangnya saja yang harus ditambahkan dan jawabannya
diperkecil dengan akar penyebut terkecil.
5) Pada akhirnya anak mampu mengerjakan soal-soal diatas kertas tanpa
mempergunakan bahan-bahan
Tujuan :
Untuk membekali anak dengan penambahan pecahan
Gambar 2.4
Buklet pecahan untuk soal-soal pengurangan yang memiliki penyebut yang
sama besar
= ..., sebagaimana pada penambahan, jelaskan bahwa
satu pembilang dikurangi dari yang lain dan jawabannya diperkecil bila
perlu.
Tujuan :
Untuk membekali anak dengan pengurangan pecahan
Gambar 2.5
E. Penerapan Pengajaran Montessori Mata Pelajaran : Matematika Kelas/semester : V / 2
Alokasi Waktu : 4 Jam pelajaran (2 x pertemuan)
Kompetensi Dasar : Mengenal dan menggunakan pecahan dalam pemecahan
masalah
Hasil Belajar : Menjelaskan arti pecahan dan urutannya
Indikator : - Menyatakan beberapa bagian dari keseluruhan bentuk pecahan
- Menyajikan nilai pecahan melalui alat peraga Materi : Pecahan dan Operasinya
Tabel 2.2: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Penelitian
Kegiatan Guru Kegiatan Peserta didik Waktu
1 2 3
A. Kegitan Awal
bagian-mengambil slip pecahan untuk menjelaskan kepada anak masing-masing bagian dan keterkaitannya untuk membentuk satu kesatuan. Misalnya : menyebut nama pecahan untuk bagian (slip pecahan) yang ditunjuk.
seterusnya.Ditunjukan kepada peserta didik bahwa antar kepingan dapat saling ditukar,misalnya setengah dapat ditukar dengan dua keping slip seperempat
4. Membagi peserta didik dalam kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 peserta didik. Kemudian guru membagikan kartu pecahan kepada masing-masing kelompok. Dengan pembelajaran tiga tahap :
2. Peserta didik yang
4. Dengan menggunakan kartu pecahan dan slip bagaimana pecahan ditulis misalnya
setengah ditulis pembilang memperlihatkan beberapa banyak dan penyebut memberi nama pada pecahan. Memberi contoh menulis pembilang dan penyebut dari kepingan pecahan yang diambil
C. Kegiatan Akhir
Memberi PR
mencatat
Penerapan desain pembelajaran sebagaimana di atas proses pembelajaran akan
menjadi lebih aktif. Artinya, pembelajaran sebagaimana di atas tentunya melibatkan
siswa untuk maksimal dalam melaksanakan proses pembelajaran. Aktif di sini
dikarenakan siswa melakukan aktifitas belajar dan disadarkan dengan aplikasi media
yang sangat mudah dicerna dan dipahami. Dengan aktifnya siswa dalam proses
pembelajaran, tentunya siswa akan lebih memahami materi yang diberikan. Dan pada
akhirnya, siswa lebih terbiasa untuk berpikir dan menyelesaikan masalah matematika,