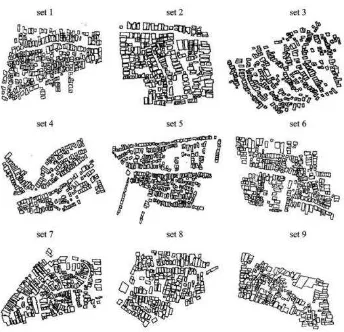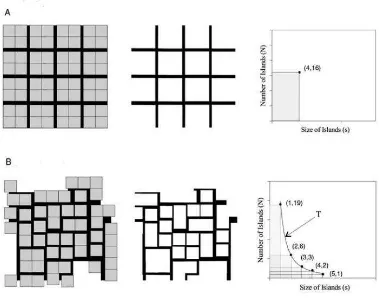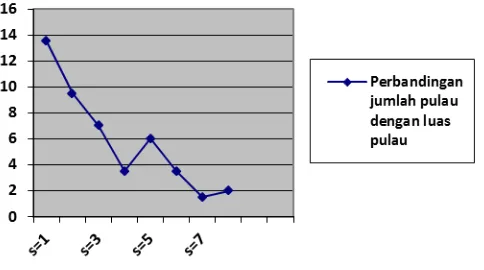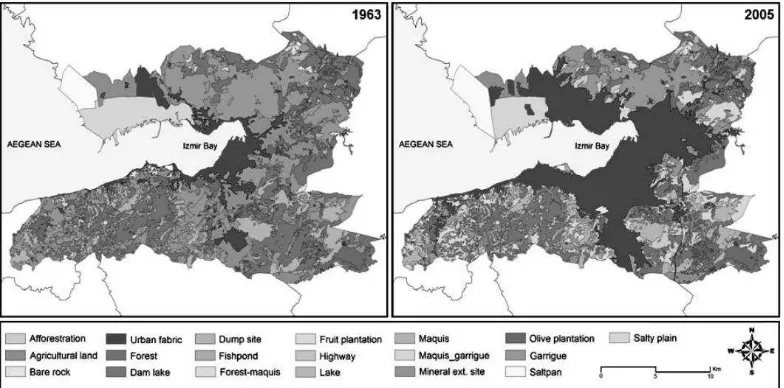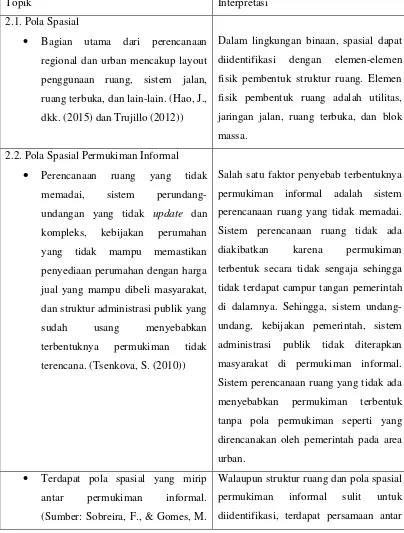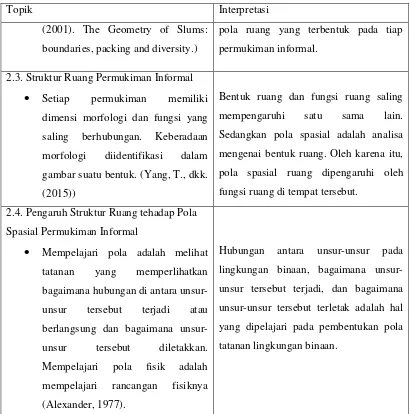TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pola Spasial
Spasial secara luas dapat didefinisikan sebagai ruang. Sedangkan pada
lingkungan binaan, spasial merujuk kepada elemen fisik bangunan seperti sistem
struktur, sistem utilitas, jaringan jalan, dan ruang terbuka. Spasial merujuk kepada
elemen fisik suatu lingkungan binaan (Trujillo, 2012). Perencanaan ruang atau
spasial adalah bagian utama dari perencanaan regional dan urban yang mencakup
layout penggunaan ruang, sistem jalan, ruang terbuka, dan lain-lain (Hao, dkk.,
2015).
Fungsi pembentuk ruang adalah bagian dari sistem struktur ruang. Sistem
struktur ruang ini kemudian membentuk sebuah pola tersendiri. Pola-pola ini
dapat terbagi sesuai dengan letak bangunan, letak jalan, area gerak dan berkumpul
masyarakat, serta fasilitas air bersih atau utilitas. Pola-pola ini dapat terbentuk
akibat dari terkumpulnya kebutuhan masyarakat di tempat tersebut. Pola spasial
dapat dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan penggunaan tata guna lahan,
perubahan sistem jaringan jalan, perkembangan permukiman, dan lain-lain.
Selain dapat didefinisikan sebagai bagian dari sistem struktur ruang, pola
spasial juga dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan tata guna lahan (land use) dan land cover. Perubahan pola spasial atau analisa spasial digunakan untuk mendeteksi perubahan penggunaan lahan hutan mangrove pada pinggiran pantai
lahan di Bukit Chyulu, Kenya (Muriuki, dkk., 2010); perubahan persebaran dan
tata guna lahan permukiman informal di sekitar Pantai Izmir, Turki (Hepcan, dkk.,
2012) dan lain-lain.
Mengetahui persebaran penduduk pada permukiman juga dapat dilakukan
dengan analisa pola spasial dan statistikal. Metode ini dilakukan oleh Doan dan
Oduro (2012) untuk mengetahui pola persebaran pertumbuhan penduduk pada
area pinggiran kota di Accra, Ghana. Doan dan Oduro (2012) mengkaji pola
persebaran pertumbuhan penduduk dengan menggunakan empat hipotesa tipe
persebaran penduduk. Dalam mengkaji hal tersebut, analisa pola spasial
digunakan untuk menghitung banyaknya penduduk yang tersebar di sekitar
pinggiran kota Accra dengan pembagian radius beberapa meter.
2.2. Pola Spasial dan Permukiman Informal
2.2.1. Pemukiman Informal
Permukiman informal adalah sebuah respon terhadap gagalnya pasar untuk
memproduksi tempat tinggal yang cukup secara kuantitas dengan harga yang
terjangkau bagi masyarakat miskin (Tsenkova, 2010). Salah satu penyebab
bertambah maraknya pertumbuhan rumah di permukiman informal adalah
kebutuhan rumah di kota yang tidak terjangkau oleh masyarakat miskin.
Sehingga, pilihan tersebut mengantar masyarakat kepada perumahan yang
Selain itu, salah satu penyebab terbentuknya permukiman informal adalah
urbanisasi besar-besaran masyarakat dari daerah terpencil ke pusat kota. Hal ini
terjadi pada kawasan yang dinamakan Chengbiancun di China (Lang, dkk., 2015).
Akibat dari urbanisasi besar-besaran tersebut terbentuklah sebuah kampung kota
yang disebut Chengbiancun dengan kualitas rumah yang buruk dan tidak adanya
perencanaan yang matang dalam membentuk permukiman. Urbanisasi
besar-besaran ini apabila terus berlanjut akan mencapai presentase 50% pada 2020 di
China. Urbanisasi ini terjadi akibat keinginan untuk meningkatkan pendapatan
sebagai hasil dari dominasi industrialisasi dan strategi pembangunan yang
berorientasi produksi. Hal ini juga terjadi pada kawasan Hout Bay di Selatan
Afrika. Permukiman informal terbentuk akibat dari proses urbanisasi masyarakat
daerah ke kota, masyarakat pindah dari area kota yang sudah sangat padat, dan
pertambahan populasi secara natural (Oelofse dan Dodson, 1997).
Menurut Seto dan Shepherd (2009), diperkirakan pada 2050 ada 70%
masyarakat menempati area perkotaan. Hal ini kemungkinan besar terjadi pada
benua Asia dan Afrika. Juga pada 2050 di mana sekitar sepertiga permukiman
kumuh akan berada di Asia. Urbanisasi besar-besaran ini dapat menyebabkan
dampak lingkungan yang besar akibat dari perubahan penggunaan tata guna lahan.
Dalam hubungannya dengan pola spasial, peningkatan masyarakat dalam suatu
daerah yang disebabkan oleh urbanisasi besar-besaran akan menciptakan suatu
pola permukiman yang padat penduduk. Permukiman yang padat sering sekali
menciptakan kondisi lingkungan yang tidak ramah terhadap lingkungan karena
masyarakat dari desa ke perkotaan juga akan menyebabkan ketimpangan jumlah
masyarakat desa dengan kota. Benua Asia dengan sebagian besar negara dunia
ketiga sedang mengalami perkembangan. Negara dunia ketiga belum memiliki
sistem ekonomi dan sosial yang settle. Ketimpangan sosial dan ekonomi kerap terjadi di negara dunia ketiga. Ketimpangan ini pun terjadi pada masyarakat kota
dan desa di negara dunia ketiga yang menyebabkan banyak masyarakat desa
pindah ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Hal ini juga disebabkan
oleh perputaran atau pusat ekonomi yang berada di kota.
Sedangkan menurut Tsenkova (2010), faktor penyebab terbentuknya
permukiman informal adalah perencanaan ruang yang tidak memadai, sistem
perundang-undangan yang tidak update dan kompleks, kebijakan perumahan yang
tidak mampu memastikan penyediaan perumahan dengan harga jual yang mampu
dibeli masyarakat, dan struktur administrasi publik yang sudah usang.
Perencanaan ruang yang telah ditentukan oleh pemerintah sering sekali tidak
selalu sejalan dengan keadaan di lapangan. Kebutuhan ruang masyarakat yang
tidak dapat tertampung atau diatasi oleh pemerintah pada akhirnya membentuk
ruang-ruang baru tersendiri di luar dari kehendak pemerintah tersebut.
Terbentuknya ruang tidak terencana ini dapat bersifat sporadik dan meluas akibat
dari kesamaan latar belakang sosial, ekonomi, mata pencaharian, pendidikan,
kekerabatan, dan lain sebagainya. Ruang-ruang baru yang tidak terencana ini
kemudian dapat membentuk suatu pola ruang.
Makna pola ruang tersendiri dalam hal ini mengandung arti bahwa ruang
polanya terbangun berdasarkan pemikiran penghuninya cenderung bukan
berdasarkan kebijakan dan aturan undang-undang yang menaungi tempat
pemukiman tersebut berada. Struktur permukiman yang tumbuh dengan konsep
seperti ini tidak mengenal sistem administrasi publik karena proses terjadinya
secara tidak terencana. Padatnya ruang-ruang pada permukiman masyarakat kota
juga dapat menyebabkan berpindahnya masyarakat ke tempat lain yang lebih
lapang. Permukiman informal pun terbentuk akibat dari tidak mampunya
masyarakat menemukan daerah lain yang terjangkau secara ekonomi bagi
kebutuhan mereka akan rumah.
Untuk dapat membedakan pemukiman informal dengan permukiman
formal, diperlukan sebuah standard pembeda. Permukiman informal didefinisikan
dengan kurangnya sistem perumahan yang aman, kurangnya area gerak yang
cukup, akses terhadap air bersih atau sanitasi yang tidak memadai, dan tidak
adanya status kepemilikan yang aman (UN-Habitat, 2003). Isu yang ada pada
permukiman informal di seluruh dunia meliputi kemiskinan, rumah-rumah yang
dibangun dengan perencanaan sendiri, dan kurangnya fasilitas-fasilitas dasar.
Keterbatasan ekonomi masyarakat yang tinggal di pemukiman informal
mengakibatkan terbatasnya pilihan masyarakat dalam membangun sistem
perumahan yang baik. Hal ini kemudian mempengaruhi kepadatan permukiman
yang menyebabkan kurangnya area gerak di antara perumahan. Kurangnya area
terbuka di antara perumahan kemudian menyebabkan terbatasnya akses
masyarakat terhadap sumber air. Semua keterbatasan ini diikuti dengan tidak
keterbatasan ekonomi tersebut menyebabkan masyarakat tinggal di tanah yang
bukan miliknya sendiri. Keterbatasan ini saling mempengaruhi satu sama lain.
Keterbatasan ini pula yang menyebabkan masyarakat memiliki
kemampuan untuk mengatur dan mengontrol sendiri rumahnya, negosiasi harga
atau membeli lahan, berkontribusi secara finansial dalam satu kelompok pada
permukiman tersebut dan memperbaiki sendiri infrastruktur dan perumahan
mereka (Archer, dkk., 2012). Rumah pada permukiman informal sering sekali
dibangun menggunakan kemampuan pemukim itu sendiri dengan bahan-bahan
yang mereka dapatkan atau beli sendiri pula. Kebutuhan ruang pada rumah
disesuaikan dengan budget yang mereka miliki. Sering sekali pula dalam
menentukan lahan, pemukim memancang sendiri lahan yang mereka inginkan dan
melaporkan hal tersebut ke ketua lingkungan setempat. Untuk perubahan pada
area jalan atau lahan di sekitar rumah, pemukim pun memperbaiki sendiri fasilitas
tersebut.
Walaupun permukiman informal sering sekali dikaitkan dengan kaum
miskin di mana susunan hunian tidak tertata karena terjadi secara tidak terencana.
Walaupun demikian tidak semua permukiman yang tumbuh informal akan tampak
kumuh (Tsenkova, 2012). Permukiman informal yang tidak bersifat kumuh ini
terdapat di daerah pinggiran kota di tenggara Eropa. Juga tidak semua daerah yang
terbentuk tanpa rencana termasuk kategori permukiman informal, seperti yang
2.2.2. Permukiman Informal dan Keterkaitannya dengan Pola Spasial
Keadaan suatu daerah dan faktor-faktor geografis yang spesifik mengenai
situasi suatu permukiman dapat mempengaruhi pola permukiman manusia
(Zhang, dkk., 2014). Menurut Zhang, dkk. (2014), daerah dengan ketinggian
lahan yang rendah lebih menguntungkan untuk dijadikan tempat pembangunan.
Distribusi spasial dari populasi dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan
seperti area gurun yang melebar, daerah berbukit, dan perubahan iklim.
Keadaan spasial suatu permukiman dapat dipengaruhi oleh beberapa
faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah faktor geografis permukiman
tersebut. Pola permukiman pada area pinggiran pantai dan permukiman pada area
pinggiran lereng gunung dapat berbeda bentuk karena efek geografis tempat
tersebut. Aspek geografis daerah tersebut dapat mempengaruhi persebaran
pemukim dalam menentukan area permukimannya.
Keadaan spasial permukiman informal tidak memiliki struktur ruang
tersendiri yang terukur. Permukiman informal dapat dibedakan dari daerah kota
yang memiliki struktur ruang yang lebih terukur dan teratur. Sepanjang sejarah,
kota biasanya dideskripsikan dan dimodelkan sebagai agregasi linear dari
kumpulan grup atau pulau-pulau bangunan yang saling berhubungan, teratur, dan
memiliki pola yang sama walau dengan berbagai bentuk pola dan skala yang
berbeda (Sobreira dan Gomes, 2001). Struktur kota ini pun dapat ditemukan pada
permukiman informal. Walaupun permukiman informal terbentuk tanpa rencana,
permukiman informal berdiri sebagai struktur permukiman urban yang
biasanya. Permukiman informal adalah salah satu hasil perkembangan kota urban
yang tidak mengikuti standard peraturan kota. Bentuk permukiman informal
menyimpang dari pola dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau
perencana kota. Selain itu, bentuk atau pola permukiman informal tidak
diintervensi oleh publik.
Pola permukiman informal tidak memiliki aturan yang jelas sehingga
bentuk pola yang muncul akan sangat beragam. Keberagaman bentuk pola pada
permukiman tidak terencana disebabkan oleh optimasi luas ruang terhadap
kebutuhan ruang. Terdapat pola permukiman yang padat dengan sedikit ruang
terbuka, namun juga terdapat pola permukiman dengan ruang terbuka yang sangat
luas dan permukiman yang satu saling terisolasi dari permukiman yang lain. Pada
gambar 2.1, bentuk yang tergambar adalah massa yang digambarkan dari atap
rumah. Penyusunan massa terlihat tidak teratur atau spontan namun tersusun
Gambar 2.1 Contoh Pola Permukiman Tidak Terencana
(sumber: Sobreira dan Gomes, 2001)
Dalam menganalisa pola permukiman informal pada Gambar 2.1, Sobreira
dan Gomes (2001) membagi bagian dari pola permukiman sesuai dengan
kerapatan massa. Blok massa yang berdiri sendiri diidentifikasi sebagai satu buah
titik tersendiri yang dinamakan dengan variabel s, kemudian blok massa yang tergabung rapat diidentifikasi sebagai satu buah titik lain. Sehingga, pada akhirnya
akan muncul banyak titik pengelompokan. Contohnya, s = 1 diidentifikasi sebagai
lain. Kemudian s = 2 diidentifikasi sebagai satu bagian pulau yang terdiri dari dua
pulau yang saling berhubungan atau berdekatan, dan seterusnya.
Gambar 2.2 Contoh Pola Permukiman Tidak Terencana
(sumber: Sobreira dan Gomes, 2001)
Misalnya dapat dilihat pada Gambar 2.2, area-area yang berdiri sendiri
dapat diidentifikasi sebagai s = 1 sedangkan area dengan dua pulau yang
berdekatan diidentifikasi sebagai s = 2. Pada Gambar 2.2 dapat dilihat akan
terdapat s = 19 karena terdapat sebuah area dengan 19 buah pulau yang
berdekatan (Sobreira dan Gomes, 2001).
Pada 9 pola permukiman tidak terencana (Gambar 2.1), dapat terlihat pola
massa bangunan terpencar dan tersusun secara tidak merata. Massa berkumpul
secara rapat sehingga terlihat padat pada beberapa tempat, area ruang terbuka
yang tersedia cukup sedikit dan tidak seimbang dengan blok massa yang
terbangun.
Massa yang dibangun rapat dan padat dapat mengindikasikan kesamaan
atau struktur bangunan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Ruang-ruang
terbuka yang muncul dapat berupa jaringan jalan, taman, atau lahan kosong tanpa
penghuni. Rapatnya jarak antar blok massa dapat dilihat sebagai besarnya
kebutuhan masyarakat akan hunian namun kurangnya lahan yang dapat dibangun.
Hal ini menyebabkan lahan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kebutuhan
pemukim yang disesuaikan seminim mungkin.
Gambar 2.3 Perbandingan Pola Permukiman Formal dan Informal dengan Menggunakan Analisa
Struktural Geometris
(sumber: Sobreira dan Gomes, 2001) Keterangan Gambar:
Sobreira dan Gomes (2001) menghitung persamaan pola (pattern) antara dua permukiman informal di Brazil dan Kenya. Dalam menghitung persamaan
pola tersebut, Sobreira dan Gomes (2001) menggunakan perhitungan struktural
geometris dengan membandingkan ukuran pulau dengan banyaknya
pulau-pulau yang tersebar. Dalam Gambar 2.3 dapat dilihat bagaimana perhitungan
tersebut dijelaskan ke dalam grafik. Pada Gambar 2.3 (A), permukiman formal
membentuk sebuah titik sedangkan pada gambar 2.3 (B), permukiman informal
membentuk sebuah grafik melengkung. Sumbu X menerangkan ukuran
pulau-pulau yang ditemukan pada pola permukiman. Contoh ukurannya misalnya 1x1,
2x1, 3x1, dan lain sebagainya. Sedangkan sumbu Y menerangkan banyaknya
pulau-pulau dengan ukuran tertentu yang tersebar pada pola permukiman tersebut.
Pada grafik (B) (Gambar 2.3), terdapat 19 buah pulau dengan ukuran 1, 6 buah
pulau dengan ukuran 2, dan lain sebagainya. Sobreira dan Gomes (2001)
melakukan penelitian pada permukiman informal di Brazil dan Nairobi, Kenya.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemungkinan terdapat distribusi fungsi
Gambar 2.4 Perbandingan jumlah pulau dengan luas pulau pada permukiman informal di Nairobi, Kenya
(sumber: Sobreira dan Gomes, 2001)
2.3. Struktur Ruang
Sistem struktur ruang terdiri dari banyak bagian pembentuk ruang tersebut,
salah satunya adalah sistem blok massa, jaringan jalan, utilitas, dan ruang terbuka.
Menurut Hillier (1984), terdapat dua karakteristik tatanan ruang pada masyarakat.
Pertama, adalah pengaturan manusia dalam ruang dan pengaturan ruang itu
sendiri. Kedua, memperlihatkan bagaimana keduanya merupakan cara di mana
masyarakat bekerja dan menghasilkan ruang-ruang. Sistem struktur ruang
berhubungan dengan fungsi ruang. Setiap bagian dari sistem struktur ruang
dipengaruhi dan mempengaruhi fungsi-fungsi ruang lain di sekitarnya.
Pada jaringan jalan di China, kepadatan jalan dan jenis jaringan jalan dapat
dibedakan berdasarkan letak jalan tersebut dan situasi kota di mana jalan tersebut
berada (Zhang, dkk., 2015). Jalan-jalan besar (jalan arteri primer) dan jalan tol
berada pada daerah pusat ekonomi, budaya, dan politik di China yaitu Beijing,
menghubungkan jalan-jalan primer sebelumnya. Jalan-jalan ini berperan penting
dalam menghubungkan area-area metropolitan, antar provinsi, dan area-area
otonom. Jalan-jalan ini biasanya lebih pendek dibandingkan jalan primer dan jalan
tol. Berdasarkan penelitian Zhang dkk. (2015) letak dan besar jalan disesuaikan
dengan keadaan atau fungsi kawasan di sekitarnya. Jalan-jalan besar dihubungkan
ke kawasan-kawasan penting di satu kota. Jalan-jalan yang lebih kecil difungsikan
untuk menghubungkan jalan-jalan besar dan kawasan-kawasan penting lainnya.
Dalam menemukan perbedaan jenis dan letak jalan Zhang dkk. (2015) mengambil
pola spasial kota China lewat software OpenStreetMap.
Menurut Yang, dkk. (2015), setiap permukiman memiliki dimensi
morfologi dan fungsi yang saling berhubungan. Secara harfiah morfologi berarti
pengetahuan tentang bentuk. Bentuk ruang saling berhubungan dengan fungsi dari
ruang tersebut. Bentuk dan fungsi ruang sering sekali tidak terpisahkan karena
saling mempengaruhi. Sistem struktur ruang pun terbentuk akibat dari adanya
fungsi-fungsi yang melekat pada tiap bagian dari sistem tersebut. Pemukiman
informal yang salah satunya mencakup pemukiman kumuh sebenarnya adalah
salah satu dari struktur permukiman urban yang tumbuh di luar dari kerangka
batasan dengan sedikit atau sama sekali tidak memiliki campur tangan publik.
Struktur informal biasanya termanifestasikan pada pendistribusian permukiman
yang tidak teratur, akibatnya, tempat tinggal tersebut biasanya dianggap tidak
Gambar 2.5 Contoh bentuk (A) regular dan (B) irregular
(sumber: Sobreira dan Gomes, 2001)
Pada gambar (A) dapat dilihat pola massa yang teratur sedangkan pada
gambar (B) (Gambar 2.5) pola massa terlihat seperti tidak dapat diidentifikasi.
Namun, apabila void pada ruang ditutup, pola ruang dapat terlihat secara lebih
jelas. Identifikasi bentuk dapat dilakukan sesuai dengan ukuran, bentuk, dan skala
bangunan. Selain dapat mengidentifikasi pola massa lewat bentuk dan fungsi,
massa dapat diidentifikasi lewat hubungan antar bentuk tersebut. Pada gambar (B)
di Gambar 2.5, massa dapat diidentifikasi sebagai bentuk dasar persegi atau
persegi panjang. Bentuk dasar ini dapat diidentifikasi kembali seperti: apakah
bentuk dasar yang satu dan yang lain yang berdekatan memiliki hubungan antar
fungsi, atau apakah setiap bentuk dasar yang sama memiliki pola persebaran
fungsi yang terukur. Identifikasi bentuk irregular pada pola permukiman akan
membantu menjawab permasalahan persebaran fungsi ruang yang terjadi pada
permukiman tersebut.
Suatu sistem struktur ruang dapat dinilai keaktifannya dalam menciptakan
aksesibilitas. Penilaian ini dapat dihitung dengan mengukur dimensi jumlah ruang
yang secara langsung terhubung dengan masing-masing ruang lainnya dalam
suatu konfigurasi ruang atau connectivity (Hillier, 1993). Ruang-ruang yang diamati adalah ruang-ruang yang termasuk ke dalam pengamatan dan ruang yang
berada di luar observasi tidak diperhitungkan. Jumlah ruang yang terhubung
dihitung dengan menggunakan konsep jarak (depth). Dengan demikian, apabila ruang A dan B terhubung secara langsung maka hanya memiliki jarak sebesar 1
step depth. Pengukuran ini dilakukan untuk dapat mengidentifikasi tingkat interaksi tiap ruang. Namun, untuk dapat mengetahui hubungan antar ruang dan
aksesibilitas yang lebih akurat perlu dilakukan perhitungan integrity.
Integrity adalah dimensi yang mengukur property global berupa posisi relatif dari masing-masing ruang terhadap ruang-ruang lainnya dalam suatu
matematis yang dapat dihitung menggunakan rumus apabila ingin mengetahui
nilai integrity suatu ruang.
Ruang dengan nilai integrity yang tinggi (kedalaman/depth yang rendah) dianggap memiliki interaksi yang tinggi secara relatif terhadap ruang lainnya pada
konfigurasi tersebut atau terkoneksi secara baik ke ruang pengamatan. Nilai
integrity yang tinggi (kedalaman/depth yang rendah) berarti ruang tersebut dapat dengan mudah dicapai dari setiap ruang lainnya sementara nilai integrity yang
rendah (kedalaman /depth yang tinggi) berarti ruang tersebut tidak dapat dicapai
dengan mudah sebab observer harus melewati beberapa ruang antara terlebih
dahulu. Integrity lebih lanjut dipergunakan untuk mempelajari kekompakan ruang
dalam sistem ruang. Ruang dengan nilai integrity yang tinggi dapat
diinterpretasikan sebagai ruang yang memiliki derajat kesatuan yang tinggi
terhadap konfigurasi ruang secara keseluruhan (global), demikian sebaliknya,
ruang dengan nilai integrity yang rendah akan cenderung memisahkan diri dalam
konfigurasi.
2.4. Pengaruh Struktur Ruang terhadap Pola Spasial Permukiman Informal
Struktur ruang yang terdiri dari jaringan jalan, blok massa, ruang terbuka,
dan sistem utilitas memiliki bentuk spasialnya tersendiri. Bentuk-bentuk ini tidak
dapat dipisahkan dari fungsi ruang yang menaunginya. Berdasarkan perspektif
ruang, hubungan antara morfologi dan fungsi memiliki dua aspek utama. Yang
sosial-ekonomi. Yang kedua mengidentifikasi bentuk fisik dan mekanisme
morfologi yang berlandaskan pada transformasi fungsional, walaupun fitur
morfologi dapat diinterpretasikan sebagai ukuran blok, kepadatan bangunan,
bentuk spasial, garis pandang, pola fasad bangunan, koneksi dengan fisik, atau
bahkan hubungannya secara topologi (Yang, dkk, 2015).
Bentuk dan fungsi ruang saling mempengaruhi satu sama lain dan dapat
dilihat melalui dua metode perspektif. Perspektif pertama adalah bagaimana
kegiatan sosial-ekonomi dilihat pada hubungannya dengan penyebaran pola
ruang. Artinya, fungsi ruang dikaitkan dengan kegiatan sosial-ekonomi dan
kemudian mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi terhadap ruang di
lingkungannya. Kegiatan sosial dapat berarti bagaimana masyarakat di satu daerah
berkumpul atau bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam membentuk area
permukimannya. Sedangkan kegiatan ekonomi mengindikasikan bagaimana
persebaran spasial masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
Perspektif kedua adalah mengidentifikasi bagaimana mekanisme ruang
tersebut terbentuk. Ruang tersebut dapat dilihat melalui ukuran, kepadatan,
bentuk, garis pandang, pola, dan lain sebagainya. Aspek-aspek dari ruang tersebut
bertransformasi terus menerus sesuai dengan fungsi atau kebutuhan masyarakat di
tempat tersebut. Selain aspek fisik, aspek yang terus berubah seperti persebaran
hunian dan penduduk juga dapat diidentifikasi melalui ruang-ruang yang
terbentuk untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut. Mempelajari pola adalah
tersebut terjadi atau berlangsung dan bagaimana unsur-unsur tersebut diletakkan.
Mempelajari pola fisik adalah mempelajari rancangan fisiknya (Alexander, 1977).
Pada Pantai Izmir di Turki, Hepcan dkk. (2013) menganalisa perubahan
penggunaan lahan pada pinggir pantai Izmir dari tahun 1963-2005 seperti pada
Gambar 2.6. Perubahan penggunaan lahan ini disebabkan oleh meningkatnya
pertambahan penduduk yang tidak terkontrol di sekitar pinggir pantai Izmir.
Perubahan penggunaan fungsi lahan tersebut digambarkan pada Gambar 2.6. di
bawah ini.
Gambar 2.6 Perkembangan Struktur Permukiman di Sepanjang Pantai Izmir di Turki
(sumber: Hepcan, dkk., 2013)
Perkembangan yang signifikan terdapat pada meluasnya struktur
permukiman urban di sepanjang pantai Izmir di Turki. Perubahan tersebut
dihitung berdasarkan data penduduk pada tahun 1963 di mana terdapat kurang
lebih 1 juta penduduk di pinggir pantai Izmir, sedangkan pada tahun 2005 terdapat
sekitar 3.6 juta penduduk. Pemukiman yang tumbuh tersebut berpusat pada
oleh meluasnya jalur transportasi di daerah tersebut. Pada daerah sekitar
permukiman yang dulunya memiliki fungsi sebagai daerah agrikultur dan kebun
beralihfungsi menjadi permukiman warga. Hal ini menyebabkan berkurangnya
area hijau pada daerah tersebut. Perubahan fungsi ruang pada area pinggir pantai
Izmir kemudian mempengaruhi pola ruang di daerah tersebut. Perubahan pola
ruang dipengaruhi oleh berubahnya sistem jaringan jalan yang meningkat,
perumahan yang semakin padat, dan kurangnya ruang luar pada pinggiran pantai.
Selain perubahan pola spasial pada daerah pinggir pantai Izmir, perubahan
pola spasial juga terjadi pada kawasan area jalan Rajawali, Kembang Jepun, dan
Kapasan di Jawa Timur. Perubahan tatanan spasial pada satu daerah ini
dihubungkan dengan perkembangan ekonomi dan sosial di daerah tersebut juga.
Menggunakan aplikasi GIS, dapat diketahui konfigurasi antara jalan dengan
fungsi yang berada di dalamnya.
Melalui penelitian Darjosanjoto (2005), sistem jaringan jalan semakin
berkembang dan terintegrasi dengan ketiga jalan utama tersebut. Perubahan pola
jaringan jalan ini disebabkan oleh keadaan sosial dan ekonomi yang ada pada
ketiga jalan tersebut. Pada ketiga jalan tersebut terdapat pusat ekonomi seperti
pusat jajanan dan toko-toko dan banyak terdapat interaksi sosial dari masyarakat
yang tinggal di daerah tersebut. Pemetaan pola spasial pada jaringan jalan di
Surabaya ini dapat mendeteksi di mana pusat-pusat jaringan jalan berada dan apa
penyebab jaringan jalan tersebut terbentuk.
Pemetaan pola spasial juga dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan
Bukit Chyulu di Kenya (Muriuki, dkk., 2010). Pertumbuhan masyarakat
menyebabkan perubahan pada tata guna lahan. Banyak dari permukiman informal
di Kenya tumbuh pada daerah yang gersang. Daerah tersebut dulunya tidak
banyak ditempati oleh pemukim. Namun, seiring dengan berjalannya waktu
fungsi lahan pada Bukit Chyulu berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat
pemukim di sana.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Muriuki dkk. (2010), perubahan tata
guna lahan dapat dilihat melalui analisa spasial yang dilakukan dengan
menggunakan software GIS. Melalui analisa spasial, besarnya penggunaan lahan
dapat diukur dan dibandingkan.
Melalui penelitian Muriuki dkk. (2010), perubahan pola spasial pada satu
area berhubungan dengan perubahan fungsi lahan. Perubahan fungsi lahan juga
dipengaruhi oleh kebutuhan pemukim di tempat tersebut. Akibat dari
bertambahnya pemukim, area-area seperti semak belukar, hutan-hutan yang padat,
Gambar 2.7 Perubahan tata guna lahan pada (a) Mtito dan (b) Kiboko yang merupakan area dari
Bukit Chyulu
(sumber: Muriuki, dkk., 2010)
Pada daerah Mtito pada tahun 1968 terdapat banyak semak-semak dan
hutan (Gambar 2.7). Mayoritas lahan dipenuhi oleh semak. Kemudian, pada tahun
1978, area semak dan sebagian hutan dijadikan area penanaman atau perkebunan
oleh pemukim. Area yang sebelumnya tidak diberdayakan menjadi area budidaya
oleh pemukim. Area yang diberdayakan pada 1978 tidak tersebar merata dan
area tersebut hampir sepenuhnya berubah menjadi area penanaman dan sebagian
area diubah menjadi hutan terbuka (Muriuki, dkk., 2010).
Pada Gambar 2.7 poin (b) di daerah Kiboko, Kenya, terdapat juga
perubahan penggunaan fungsi lahan yang signifikan. Pada area ini, awalnya
terdapat hutan, semak, dan bebatuan pada tahun 1968. Pada tahun 1978, sebagian
area semak-semak dibudidayakan oleh pemukim. Kemudian, pada 1999 area yang
dibudidayakan semakin besar dan berkembang menggantikan area semak belukar.
Pada area ini, hutan tertutup dan terbuka serta padang rumput tidak ditutupi oleh
pemukim. Fungsi lahan sebagian besar berubah dari area semak belukar menjadi
area yang dibudidayakan. Dengan mengetahui pola spasial pada area ini, peneliti
dapat menemukan fungsi lahan yang dibutuhkan oleh pemukim. Kemudian, pola
spasial sebuah area juga selalu berhubungan dengan fungsi ruang pada area
tersebut.
Menurut Hillier (1996), perubahan kecil yang terjadi pada suatu sistem
ruang akan mempengaruhi konfigurasi ruang secara keseluruhan. Ruang penting
untuk mengatur aksesibilitas penggunanya. Ruang saling mempengaruhi satu
sama lain, oleh karena itu massa bangunan dan jaringan jalan sebagai elemen fisik
suatu permukiman dapat saling berdampak apabila salah satu atau sebagian
elemen dihilangkan. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh antara suatu ruang
terhadap ruang-ruang lainnya dan akan berdampak signifikan terhadap kondisi
2.5. Rangkuman
Adapun rangkuman dari tinjauan pustaka terdapat pada Tabel 2.1. berikut.
Tabel 2.1. Rangkuman Kajian Teori
Topik Interpretasi
2.1. Pola Spasial
Bagian utama dari perencanaan
regional dan urban mencakup layout
penggunaan ruang, sistem jalan,
ruang terbuka, dan lain-lain. (Hao, J.,
dkk. (2015) dan Trujillo (2012))
Dalam lingkungan binaan, spasial dapat
diidentifikasi dengan elemen-elemen
fisik pembentuk struktur ruang. Elemen
fisik pembentuk ruang adalah utilitas,
jaringan jalan, ruang terbuka, dan blok
yang tidak mampu memastikan
penyediaan perumahan dengan harga
Salah satu faktor penyebab terbentuknya
permukiman informal adalah sistem
perencanaan ruang yang tidak memadai.
Sistem perencanaan ruang tidak ada
diakibatkan karena permukiman
terbentuk secara tidak sengaja sehingga
tidak terdapat campur tangan pemerintah
di dalamnya. Sehingga, sistem
undang-undang, kebijakan pemerintah, sistem
administrasi publik tidak diterapkan
masyarakat di permukiman informal.
Sistem perencanaan ruang yang tidak ada
menyebabkan permukiman terbentuk
tanpa pola permukiman seperti yang
direncanakan oleh pemerintah pada area
urban.
Terdapat pola spasial yang mirip
antar permukiman informal.
(Sumber: Sobreira, F., & Gomes, M.
Walaupun struktur ruang dan pola spasial
permukiman informal sulit untuk
Topik Interpretasi
mempengaruhi satu sama lain.
Sedangkan pola spasial adalah analisa
mengenai bentuk ruang. Oleh karena itu,
pola spasial ruang dipengaruhi oleh
fungsi ruang di tempat tersebut.
2.4. Pengaruh Struktur Ruang tehadap Pola
Spasial Permukiman Informal
Mempelajari pola adalah melihat
tatanan yang memperlihatkan
bagaimana hubungan di antara
unsur-unsur tersebut terjadi atau
berlangsung dan bagaimana
unsur-unsur tersebut diletakkan.
Mempelajari pola fisik adalah
mempelajari rancangan fisiknya
(Alexander, 1977).
Hubungan antara unsur-unsur pada
lingkungan binaan, bagaimana
unsur-unsur tersebut terjadi, dan bagaimana
unsur-unsur tersebut terletak adalah hal
yang dipelajari pada pembentukan pola