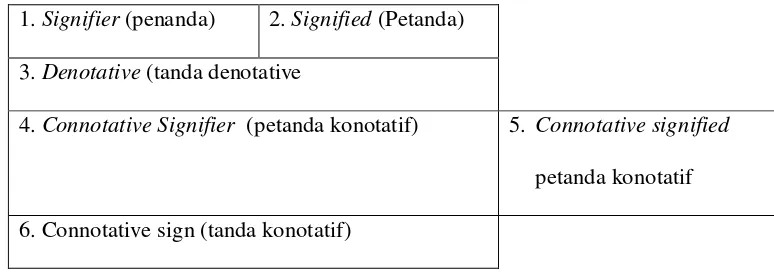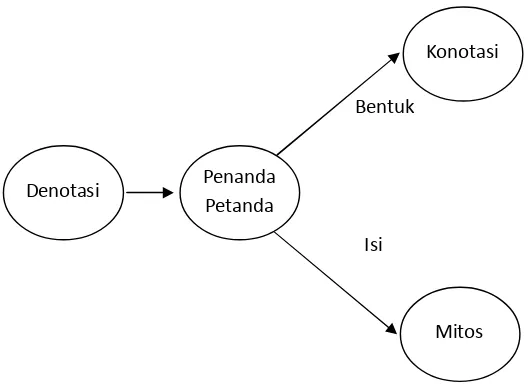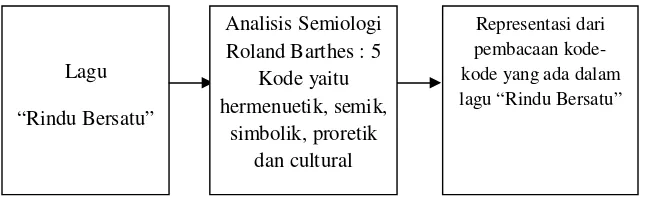SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Pada FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur
Oleh :
ANALISA ROFIQ
0643010228
YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
Alhamdullillahirabbil’alamin. Puji syukur kehadiratAllah SWT yang telah
memberi rahmat-Nya, sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan
skripsi ini dengan lancar, meskipun masih belum dapat dikatakan sempurna.
Selama mengerjakan hingga terwujudnya skripsi ini, penulis dalam
pengerjaannya tidak lepas dari berbagai pihak yang telah bersedia meluangkan
waktunya dalam memberikan bantuan. Penulis ingin mengucapkan terima kasih
kepada :
1.
Allah SWT yang memberikan kemampuan, kesehatan, kelancaran kepada
penulis, sehingga penulis masih diberi kesempatan hingga saat ini untuk
menyelesaikan skripsi ini.
2.
Kedua Orang Tuaku yang telah banyak memberikan dorongan, dukungan,
semangat dan doa baik secara moril maupun material sehingga terselesainya
skripsi ini.
3.
Ibu Dra.Hj.Suparwati,Msi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur.
4.
Bapak Juwito,S.Sos,Msi selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur.
5.
Zainal Abidin Achmad, MSi.M.Ed selaku dosen Pembimbing “Terima Kasih
atas waktu dan saran yang diberikan serta bimbingannya”.
ini.
7.
Teman-teman Fisip angkatan 2006 (Rully, Winda) makasih atas dukungan dan
semangat dari kalian semua.
8.
Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
banyak memberikan bantuan dalam menyusun skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun
besar harapan bahwa skripsi ini insya Allah akan berguna bagi semua pembaca,
khususnya teman-teman di Jurusan Ilmu Komunikasi.
Surabaya, 20 November 2010
Penulis
HALAMAN JUDUL... i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ... ii
KATA PENGANTAR... iii
DAFTAR ISI
... v
DAFTAR GAMBAR ... vii
ABSTRAKSI ... viii
BAB I
PENDAHULUAN ... 1
1.1. Latar Belakang Masalah ... 1
1.2 Perumusan Masalah ... 8
1.3 Tujuan Penelitian ... 8
1.4 Manfaat Penelitian ... 8
1.4.1 Manfaat Teoritis ... 8
1.4.2 Manfaat Praktis ... 9
BAB II KAJIAN PUSTAKA... 10
2.1 Landasan Teori ... 10
2.1.1 Musik ... 10
2.1.2 Lirik Lagu ... 11
2.1.3 Nasionalisme ... 12
2.1.4 Representasi... 16
2.1.5 Pendekatan Semiotika... 19
2.2 Kerangka Berpikir ... 33
BAB III METODE PENELITIAN ... 35
3.1 Metode Penelitian ... 35
3.1.1 Analisis Semiotika ... 36
3.1.2 Unit Analisis ... 37
3.1.3 Korpus Penelitian ... 37
3.2 Teknik Pengumpulan Data ... 38
3.3 Metode Analisis Data ... 39
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 40
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian ... 40
4.1.1. ST12 Band ... 40
4.2. Penyajian dan Analisis Data ... 45
4.2.1. Penyajian Data ... 45
4.2.2. Analisis Data ... 46
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 69
5.1. Kesimpulan ... 69
5.2. Saran ... 70
DAFTAR PUSTAKA ... 71
Gambar 2.1 Peta Tanda Roland Barthes ... 23
Gambar 2.2 Dua Tatanan Pertandaan Barthes ... 27
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir ... 34
semiologi Nasionalisme dalam Lagu “Rindu Bersatu” )
Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan representasi Nasionalisme
dalam lagu tersebut. Nasionalisme adalah paham yang menunjukkan bahwa
kesetiaan dari setiap individu atau warga Negara ditujukan kepada bangsanya.
Studi penelitian ini diarahkan pada pendekatan semiotika Roland Barthes.
Konsep yang digunakan adalah peta tanda Roland barthes dan lima kode
pembacaan, yaitu kode hermeneutik, kode proaretik, kode semik, kode gnomik,
dan kode simbolik yang akan digunakan untuk memaknai setiap lirik dalam lagu
tersebut.
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif interpretative dengan
menggunakan pendekatan semiotik berdasarkan konsep signifikasi dua tahap
Roland Barthes. Unit analisis yang digunakan adalah tanda-tanda yang berupa
kata-kata yang terdapat dalam lirik lagu “Rindu Bersatu”.
Dari data yang sudah diinterpretasi dan dianalisis, maka disimpulkan bahwa
karena pencipta lagu melihat masyarakat Indonesia sudah mulai kehilangan rasa
nasionalisme, maka pencipta lagu menciptakan lagu tersebut untuk mengajak
warga Indonesia meningkatkan rasa nasionalisme dengan mmperkuat rasa
persatuan.Saran yang disampaikan penulis adalah agar kita sebagai warga Negara
Indonesia lebih bisa menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, serta terus
menjaga dan memelihara rasa Nasionalisme dan cinta tanah air.
Kata Kunci: representasi, Nasioanalisme, lirik lagu, semiologi, Charly ST 12,
Rindu Bersatu
ix
ANALISA ROFIQ. Nationalism REPRESENTATION IN THE SONG
(semiology Nationalism Studies in Song "missed United").
This study aimed to describe the representation of Nationalism in the song.
Nationalism is understood that indicates that the fidelity of each individual or
citizens addressed to the nation.
This research study focused on Roland Barthes' semiotic approach. The
concept used is a map of Roland Barthes and five signs reading code, namely
hermeneutic code, code proaretik, semik code, code gnomik, and symbolic codes
that will be used to interpret any lyrics in the song.
The method used is qualitative interpretative method by using a semiotic
approach based on the historical significance of the two stages of Roland Barthes.
The unit of analysis used are the signs that form of words contained in the lyrics
of the song "Missed United".
From the data that has been interpreted and analyzed, it was concluded that
because the creator of the song to see the people of Indonesia have started to lose
a sense of nationalism, then create the song to invite citizens of Indonesia to
increase a sense of nationalism with a sense of unity. Suggestions submitted by
the authors is that we as citizens of the State of Indonesia more able to maintain
unity and integrity of Indonesia, and continues to maintain and preserve a sense of
nationalism and love of our homeland.
1 1.1Latar Belakang Masalah
Musik merupakan hasil budaya manusia yang menarik diantara banyak budaya yang lain, dikatakan menarik karena musik memegang peranan yang sangat banyak di berbagai bidang. Seperti jika dilihat dari psikologinya, musik kerap menjadi sarana pemenuhan kebutuhan manusia dalam hasrat akan seni dan rekreasi. Dari sisi sosial musik dapat disebut sebagai cermin tatanan sosial yang ada dalam masyarakat saat musik tersebut diciptakan.
Musik dapat dikatakan sebagai bahasa yang universal, dapat juga dikatakan sebagai media ekspresi masyarakat dan musik mampu menyatukan banyak kalangan masyarakat, baik itu kalangan bawah hingga lapisan paling atas. Tanpa disadari musik juga mempengaruhi kehidupan sosial di dalam kehidupan masyarakat, sehingga musik banyak tercipta dari pengungkapan beberapa fenomena-fenomena yang ada di dalam kehidupan masyarakat, karena musik banyak tercipta dari tema yang cukup beraneka ragam mulai masalah percintaan, kehidupan sehari-hari, seni budaya, agama, olah raga, mode maupun sampai alat control sosial dan kritik terhadap salah satu pihak seperti pemerintahan.
manusia disebut vocal, sedangkan ungkapan yang dikeluarkan melalui bunyi alat musik disebut instrumental (Subagyo,2006:4).
Musik dalam sebuah lagu adalah sekumpulan lirik diberi instrument akor dan melodi, meskipun terlihat sederhana, namun proses pembuatan sebuah lagu dibutuhkan keahlian, baik itu keahlian memainkan alat musik, keahlian menulis lirik lagu hingga keahlian dalm berimajinasi menciptakan sebuah ide, meskipun dalam prakteknya lirik tersebut berdasarkan pengalaman pribadi atau keadaan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Lirik lagu merupakan sebuah media komunikasi verbal yang memiliki makna pesan di dalamnya. Sebuah lirik lagu bila tepat memilihnya bisa memiliki nilai yang sama dengan ribuan kata atau peristiwa, juga secara individu mampu memikat perhatian. Kekuatan lirik lagu adalah unsur yang penting bagi keberhasilan bermusik, sebab pesan yang disampaikan oleh seorang pencipta lagu ternyata tidak berasal dari luar diri pencipta lagu tersebut, dalam artian bahwa pesan tersebut bersumber pada pola pikirnya serta kerangka acuan (frame of reference) dan pengalaman (field of experience) sebagai hasil interaksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Lirik
lagu juga menjadi parameter sosial untuk mengukur tingkat kebutuhan masyarakat.
nada dan lirik maka pendengar tersebut akan ikut merasakan ungkapan perasaan pencipta musik tersebut. Langer berpendapat bahwa musik ekspresi perasaan, bentuk simbolik yang signifikasinya dapat dirasakan, tetapi tidak dapat didefinisikan karena ia hanya bersifat implicit, tetapi secara konvensional tetap.
Dapat dikatakan musik yang didalamnya terdapat lirik sebuah lagu adalah sebuah proses komunikasi, hal ini seperti diungkapkan Tubbs and Moss dalam Human Communication: Proses komunikasi itu sebenarnya mencakup pengiriman pesan dari system saraf kepada system saraf orang lain, denagn maksud untuk menghasilkan sebuah makna yang sama dengan yang ada dalam benak pengirim. Pesan verbal melakukan tersebut melalui kata-kata yang merupakan unsure dasar bahasa dan kata-kata, sudah jelas merupakan simbol verbal (Tubbs dan Moss:66).
Musik juga merupakan bagian dari komunikasi, seperti yang dikemukakan oleh William I. Gorden menyatakan bahwa komunikasi itu mempunyai empat fungsi. Keempat fungsi tersebut meliputi komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan instrumental, yang tidak saling meniadakan (mutually exclusive).
Erat kaitannya dengan komunikasi sosial komunikasi ekspresif yang dapat dilakukan baik sendirian maupun kelompok. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrument untuk menyampaikan perasaan-perasaan (emosi). Perasaan tersebut dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal, emosi kita juga dapat kita salurkan lewat bentuk-bentuk sejenis seperti novel, puisi, musik tarian atau lukisan. Harus diakui musik juga dapat mengekspresikan perasaan, kesadaran, bahkan pandangan hidup (Mulyana, 2005:21).
Setiap kata mengandung makna, makna itu ada yang sudah jelas, tetapi ada juga yang maknanya kabur. Setiap kata dapat saja mengandung lebih dari satu makna. Dapat saja sebuah kata mengacu pada sesuatu yang berbeda sesuai dengan lingkungan pemakaian bahasa. Disinilah kedudukan lirik sangat berperan karena mempunyai banyak makna, sehingga musik tidak hanya bunyi suara saja.
Musik memainkan peran dalam evolusi manusia, dibalik perilaku dan tindakan manusia terdapat pikiran dan perkembangan diri dipengaruhi oleh musik. Pemakaian bahasa pada karya seni musik berbeda dengan bahasa sehari-hari atau dalam kegiatan lain. Musik berkaitan erat dengan setting sosial kemasyarakatan tempat dia berada, sehingga mengandung makna yang tersembunyi dan berbeda didalamnya.
hanya bertujuan memperlihatkan akan sesuatu hal sampai mengajak melakukan sesuatu. Salah satu contoh pesan yang disampaikan adalah pentingnya rasa nasionalisme akan suatu perdamaian terhadap bangsa sendiri.
Belakangan ini masyarakat Indonesia sudah kekurangan akan nilai nasionalisme terhadap bangsanya, memudarnya rasa persatuan dan kesatuan, semakin banyaknya kerusuhan, pertengkaran, perkelahian pertikaian yang hingga menimbulkan korban jiwa. Contohnya kerusuhan di Poso, dan Boul Sulawesi Tengah, makam Mbah Priok, dan yang baru-baru ini kerusuhan di Tarakan, Kalimantan Timur. Melihat kondisi yang seperti itu banyak band di Indonesia yang masih perduli akan rasa nasionalisme, dan menuangkan inspirasinya dengan melihat keadaan di sekitarnya melalui sebuah lirik lagu.
disumbangkan kepada program Save A Teen – Sampoerna Foundation; sebuah program yang ditujukan untuk memberikan beasiswa untuk mencegah anak-anak tak mampu putus sekolah.
Lirik lagu yang diciptakan oleh Charly ST12 tersebut adalah sebuah proses komunikasi yang mewakili seni karena terdapat informasi dan pesan yang terkandung dalam lirik lagu tersebut yang sengaja digunakan oleh komunikator untuk disampaikan kepada kominukan dalam hal ini masyarakat luas, dengan menggunakan bahasa yang verbal. Penggunaan bahasa pada kegiatan pembuatan hasil karya lirik lagu pada sebuah karya seni musik berbeda pada pemakaian bahas pada kegiatan yang lain, seperti pada pemakaian sehari-hari (natural atau ordinary language). Perbedaan itu terlihat dari kalimat-kalimat yang dibuat, karena didalamnya mengandung makna tersembunyi yang dapat dipersepsikan oleh khalayak sebagai sebuah tanda tanya terhadap maksud lirik tersebut. Makna pada kata-kata merupakan suatu jalinan asosiasi, pikiran yang berkaitan serta perasan yang melengkapi konsep yang diterapkan.
yang penuh makna sebagi hasil dari interpretasi data mengenai liriklagu tersebut.
Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan studi semiologi agar dapat menunjukkan representasi nsionalisme dalam lirik lagu “Rindu Bersatu” yang diciptakan Charly ST12 dan dibawakan oleh 14 artis dan group band.
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “ Representasi nasionalisme dalam lirik lagu “Rindu Bersatu” yang diciptakan Charly ST 12 ? “
1.3. Tujuan Penelitian
Dari perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi nasionalisme dalam lagu tersebut.
1.4. Manfaat Penelitian
1.4.1. Manfaat Teoritis
10
2.1. Landasan Teori
2.1.1 Musik
Musik dan lagu merupakan salah satu budaya manusia yang menarik
dibandingkan dengan budaya-budaya manusia yang lain dari sisi psikologis
humanistik, musik atau lagu bisa menjadi saran untuk memenuhi kebutuhan
manusia dalam hasrat akan seni dan kreasi. Dari sisi sosial, lagu bisa disebut
sebagai cermin dari tatanan sosial yang ada dalam masyarakat saat lagu tersebut
diciptakan. Dari sisi ekonomi, lagu merupakan sebuah komoditi yang
menguntungkan (Rahmat, 1993:19).
Sistem tanda musik adalah oditif, namun untuk mencapai pendengarnya,
penggubah musik mempersembahkan kreasinya dengan perantara pemain musik,
adanay tanda-tanda perantara, yakni musik yang dicatat dalam partitur orkestra.
Hal ini sangat memudahkan dalam menganalisis karya musik sebagai teks.
Itulah sebabnya mengapa penelitian terarah pada sintaksis.
Meski demikian, semiotik tidak dapat hidup hanya dengan sintaksis:
tidak ada semiotik tanpa semantik musik. Semantik musik, bisa dikatakan,
2.1.2 Lirik Lagu
Lirik lagu dalam musik yang sebagaimana bahasa, dapat menjadi sarana
atau media komunikasi untuk mencerminkan realitas sosial yang beredar dalam
masyarakat. Lirik lagu, dapat pula sebagai srana untuk sosialisasi dan pelestarian
terhadap suatu nilai. Oleh karena itu, ketika sebuah lirik lagu diaransir dan
diperdengarkan kepada khalayak juga mempunyai tanggung jawab yang besar
atas tersebar luasnya sebuah keyakinan, nilai-nilai, bahkan prasangka tertentu
(Setianingsih, 2003:7-8)
Suatu lirik lagu dapat menggambarkan realitas sosial yang terjadi di
masyarakat. Sejalan dengan pendapat Seorjono dalam Rachmawati (2001:1)
yang menyatakan:
“Musik berkait erat dengan setting sosial kemasyarakatan tempat dia
berada. Musik merupakan gejala khas yang dihasilkan akibat adanya
interaksi sosial, dimana dalam interaksi tersebut manusia menggunakan
bahasa sebagai mediumnya. Disinilah kedudukan lirik sangat berperan,
sehingga dengan demikian musik tidak hanya bunyi suara belaka, karena
juga menyangkut perilaku manusia sebagai individu maupun kelompok
sosial dalam wadah pergaulan hidup dengan wadah bahasa atau lirik
sebagai penunjangnya.”
Berdasarkan kutipan di atas, sebuah lirik lagu dapat berkaitan erat pula
dengan situasi sosial dan isu-isu sosial yang sedang berlangsung didalam
Penelitian tentang lirik lagu merupakan penelitian tentang makna isi
pesan dalam lirik lagu tersebut. Dimana lirik lagu merupakan suatu produk yang
salah satu sumbernya adalah situasi sosial. Diman lirik lagu berada didalamnya,
kemudian merefleksikannya dalam sistem tanda berupa lirik lagu. Maka, dapat
dikatakan bahwa lirik lagu “Rindu Bersatu” ciptaan Charly ST 12 merupakan
proses komunikasi yang mewakili seni karena terdapat pesan yang terkandung
dalam simbol lirik lagu tersebutyang sengaja digunakan oleh komunikator
sebagai pencipta lagu untuk disampaikan kepada komunikan dengan bahasanya
tentang suatu rasa nasionalisme bangsa Indonesia terhadap bangsanya sendiri.
Namun dalam hal ini bahasa verbal yang berupa kata-kata yang tertuang dalam
teks lirik lagu.
2.1.3 Nasionalisme
Nasionalisme adalah suatu paham, yang berpendapat bahwa kesetiaan
tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Perasaan sangat
mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tumpah darahnya dengan tradisi
setempat dan penguasa-penguasa rsemi di daerahnya selalu ada di sepanjang
sejarah dengan kekuatan yang berbeda-beda. Bangsa-bangsa adalah buah hasil
tenaga hidup dalam sejarah, dan karena itu selalu bergelombang dan tak pernah
membeku. Bangsa-bangsa merupakan golongan-golongan yang beraneka ragam
dan tak terumuskan secara eksak (Kohn 1984:84).
Kelayakan bangsa-bangsa itu memiliki faktor-faktor obyektif tertentu
turunan, bahasa, daerah, kesatuan politik, adat istiadat dan tradisi, atu persamaan
agama. Meskipun faktor-faktor obyektif itu penting, namun unsur yang
terpenting ialah kemauan bersama yang hidup nyata. Kemauan inilah yang
dinamakan nasionalisme (Kohn 1984:12).
Nasionalisme merupakan suatu paham yang memberikan ilham kepada
sebagian terbesar penduduk yang mewajibkan dirinya untuk mengilhami
segenap anggota-anggotanya. Nasionalisme adalah faham yang menunjukkan
bahwa kesetiaan dari setiap individu atau warga negara ditujukan bangsanya
(Boehn dalam sukarna, 1991:92).
Jadi, seorang nasionalis adalah pecinta nusa dan bangsa sendiri atau
orang yang memprjuangkan kepentingan bangsanya. Bangsa merupakan
komunitas yang para anggota masyarakat terkecil sekalipun tidak akan mengenal
sebagian besar anggota yang lainnya, hal yang terpenting tetap berdirinya suatu
bangsa adalah adanyaperasan kebersamaan dan persaudaraan sebagai anggota
komunitas bangsa tersebut.
Nasionalisme kebangsaan Indonesia adalah sifat yang tidak keras
terhadap fakta multi etnik, multi kultur, multi agama, multi lingual. Karena
Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila yang mencegah nasionalisme Indonesia
berubah menjadi fasisme. Sehingga nasionalisme kebangsan Indonesia
membuka pintu bagi siapa saja untuk berpartisipasi membangun negara Repiblik
Indonesia tanpa pembedaan dalam rasialis, etnis agama dan orientasi politik.
zaman memiliki kondisi dan tantangan yang berbeda sehingga membutuhkan
wujud nasionalisme yang dinamis.
Wawasan yang kita anut adalah wawasan kebangsaan yang berlandaskan
Pancasila. Dengan landasan Pancasila itu, wawasan kebangsaan yang kita anut,
menentang segala bentuk penindasan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain,
oleh suatu golongan terhadap golongan lain, juga oleh manusia terhadap
manusia lain, karena dilandasi oleh Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap yang
mengajarkan kepada kita untuk menghormati harkat dan martabat manusia dan
menjamin hak-hak manusia. Sebagai bangsa yang majemuk, wawasan
kebangsaan Indonesia yang menentang praktek-praktek yang mengarah pada
dominasi dan diskriminasi sosial, juga menetang segala bentuk separatisme
sebab sila Persatuan Indonesia memberikan tempat kepada kemajemukan dan
mengakomodir adanya perbedaan alamiah maupun budaya dari anak-anak
bangsa ini (Yudohusodo:13-14).
Gagasan nasionalisme yang berkembang di Indonesia seharusnya tidak
dipahami hanya dari sudut perkembangan obyektif semata, tetapi juga dalam
ruang politik pembentukan negara republik dan kebutuhan survival sebuah
negara baru dalam pergaulan internasioanl. Tidak dapat dipungkiri, saat
terbentukrepublik bernama Indonesia, konteks sejarah saat itu menunjukkan
beragamnya pikiran dan ideologi manusia Indonesia yang mengambil inspirasi
dari gagasan-gagasan religius atau sekuler. Selain itu, kekuatan-kekuatan politik
komunisme, termasuk kelompok-kelompok etnis dan keturunan Tionghoa dan
Arab.
Republik Indonesia dibentuk dari institusi yang dilahirkan masyarakat
modern. Dengan demikian, bisa disimpulkan, sejarah pembentukan republik
tidak menunjukkan keberadaan suatu gagasan nasionalisme Indonesia dalam arti
bulat dan utuh. Bukan berarti Sumpah Pemuda tahun 1928 tidak berarti, tetapi
makna Indonesia memiliki arti berbeda ketika negara republik dibentuk,
dibanding saat pertama kali gagasan itu diikrarkan.
Perlu disebutkan juga teori tiga dunia yang dipelopori Mao Tse Tung dan
Chou En Lai yang membagi kondisi politik internasional dalam blok Barat
dibawah Amerika Serikat, blok Timur di bawah Uni Soviet saat itu, dan
negara-negar dunia ketiga yang baru merdeka. Cetusannya dalam konteks historis
adalah Konferensi Asia-Afrika dan lahirnya gagasan Non_Blok yang menjadi
kekuatan baru di dunia.
Indonesia sebagai imagined community terbentuk dari kesadaran politik
orang-orang Indonesia saat itu dalam membangun republik baru dan pertarungan
dalam politik internasioanl. Presiden RI Soekarno tidak pernah terlalu pusing
membahas apa itu nasionalisme Indonesia. Ia adalah seorang romantik yang
mencintai rakyatnya dan mengagumi keragaman budaya Nusantara. Ia tidak
merasa tidak Indonesia meski lebih akrab berbahasa Belanda atau Jawa dengan
kolega sahabat, atau saat berpidato di depan massa.
(http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/02/18530855/nasionalisasi.nasionali
Kini kita butuh semangat nasionalisme dalam menyelamatkan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kita butuh nasionalis yang
berperang keras terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nasionalis
modern adalah nasionalis yang memperjuangkan harkat, martabat, dan keutuhan
NKRI. Nasionalisme kita adalah nasionalisme pembelaan kepada rakyat
Indonesia. Semangat yang terakhir inilah semangat praksis nasionalisme
Indonesia yang dibutuhkan
(http://www.kompas.com/read/xml/2008/01/20/10391319)
2.1.4 Representasi
Representasi adalah salah satu praktek penting yang mempreoduksi
kebudayaan menyangkut pengalaman berbagi. Sseorang dikatakn berasal dari
kebudayaan yang sama, berbicara dalam “bahasa” yang sama dan saling berbagi
konsep-konsep yang sama (Juliastuti, 2005:5).
Konsep lama mengenai representasi didasarkan pada premis bahwa ada
sebuah gap representasi yang menjelaskan perbedaan antar makna yang
diberikan oleh representasi dan arti beda yang sebenarnya digambarkan.
Berlawanan dengan pemahaman standar itu, Stuart Hall berargumentasi bahwa
representasi harus dipahami dari peran aktif dan kreatif orang memaknai dunia.
Representasi mengacu pada sebuah proses konstruksi didalam tiap medium
(khususnya dalam media massa) apek-aspek realitas seperti orang, tempat,
lainnya. Representasi dapat hadir dalam sebuah percakapan, tulisan, serupa
dengan representasi yang hadir dalam sebuah media audio visual.
Hal menunjukkan bahwa sebuah imaji akan mempunyai makna yang
berbeda dan tidak ada garansi bahwa imaji akan berfungsi atau bekerja
sebagaimana mereka dikerasi atu dicipta. Hall menyebutkan “representasi
sebagai konstitutif”. Representasi tidak hadir sampai setelah direpresentasikan,
representasi tidak terjadi setelah sebuah kejadian. Representasi adalah konstitutif
darisebuah kejadian. Representasi adalah bagian dari objek itu sendiri, ia adalah
konstitutif darinya.
Dalam representasi, bahasa adalah yang menjadi medium perantara kita
dalam memaknai sesuatu, memproduksi dan mengubah makna. Bahasa mampu
melakukan semua ini karena bahasa beroperasi sebagai sistem representasi.
Lewat bahasa (simbol-simbol dan tanda tertulis lisan atau gambar) kita dapat
mengungkapkan pikiran, konsep, dan ide-ide kita tentang sesuatu. Makna
sesuatu hal sangat tergantung dari cara mempresentasikannya. Dengan
mengamati kata-kat yang kita gunakan dalam mempresentasikan sesuatu, bisa
terlihat jelas nilai-nilai yang kita berikan pada sesuatu tersebut (Juliastuti,
2006:6).
Untuk menjelaskan bagaimana representasi makna lewat bahasa, ada tiga
teori representasi. Pertama adalah pendekatan reflektif, bahasa berfungsi untuk
merefleksikan makna yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada. Kedua
adalah pendekatan intensional, dimana kita menggunakan bahasa untuk
Sedangkan yang ketiga adalah pendekatan konstusionis, dalam pendekatan ini
kita percaya bahwa kita mengkontruksi makna bahasa yang kita pakai (Juliastuti,
2007:7).
Ada dua proses representasi yaitu representasi mental dan representasi
bahasa. Representasi mental adalah konsep tentang “sesuatu” yang ada dikepala
kita masing-masing, representasi ini masih berbentuk sesuatu yang abstrak.
Sedangkan representasi bahasa adalah representasi yang berperan penting dalam
konstruksi makna. Konsep abstark yang ada dalam kepala kita diterjemahkan
dalam bahasa yang lazim, supaya kita dapat menghubungkan konsep dan ide-ide
kita tentang sesuatu dengan tanda-tanda dan simbol-simbol tertentu (Julianti,
2000:8).
Proses pertama memungkinkan kita untuk memaknai dengan
mengkontruksi seperangkat rantai korepondensi antara sesuatu dengan sistem
:konseptual” kita. Dalam proses kedua, kita mengkontruksi seperangkat rantai
korespondensi antara “peta konseptual” dengan bahasa atua simbol yang
berfungsi merepresentasikan konsep-konsep kita tentang sesuatu. Relasi antara
“sesuatu”, “peta konseptual” dan simbol dalam bahasa adalah suatu proses
makna lewat bahasa. Proses yang menghubungkan ketiga elemen ini secara
bersama-sama itulah yang dinamakan representasi.
Inti kajian representasi memfokuskan kepada isu-isu mengenai
bagaimana caranya representasi itu dibentuk hingga menjadi sesuatu yang
kelihatan alami. Jika sudah sampai pada tahap ini, maka representsai itu
normalitas alami yang tidak perlu dipertanyakan kembali karena sudah dianggap
sebuah kewajaran. Dalam sebuah representasi terdapat sebuh sistem yang
disebut sistem representasi, yang artinya pembangun sebuah konsep representasi
selalu identik dengan nilai-nilai ideologis yang melatar belakanginya.
Konsep representasi pada penelitian merujuk apada pengertian, tentang
bagaiman seseorang yaitu pencipta lagu membentuk makna dalam sebuah lirik
lagu. Dalam lirik lagu alat representasi itu berupa tulisan-tulisan syair apada
lirik laguyang bahasanya berbeda dengan bahasa sehari-hari yang digunakan
masyarakat. Lewat lirik lagu pencipta dapat mengungkapkan pikiran yang ada
dalam dirinya dalam mempresentasikan sesuatu.
2.1.5 Pendekatan Semiotika
Semiotika sebagai suatu model dari ilmu pengetahuan sosial memahami
dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut dengan
‘tanda’. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha
mencari jalan dunia ini, ditengah-tengah manusia, dan bersama-sama manusia
semiotik pada dasarnya hendak mempelajari bagaiman kemanusiaan (humanity),
memaknai hal-hal (things).
Secara etimologis istilah semiotik berasal dari kata Yunani semenion yang
berarti “tanda”. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar
konvensi yang terbngun sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain
sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa,
seluruh kebudayaan sebagai tanda (Eco, 1979:6).
Bagi seseorang yang tertarik dengan semiotik, maka tugas utamanya
adalah mengamati (observasi) terhadap fenomena-gejala di sekelilingnya
melalui berbagai tanda yang dilihatnya. Tanda sebenarnya representasi dari
gejala yang memiliki sejumlah kriteria seperti : nama (sebutan), peran, fungsi,
tujuan, keinginan.
Menurut Littejohn (1996:64) dalam Sobur (2001:15) tanda-tanda (signs)
adalah basis dari seluruh komunikasi dengan sesamanya. Tanda-tanda adalah
perangkat yang dipakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini,
ditengah-tengah manusia dan bersama manusia.
Semiotika seperti kata Lechte (2001:19) adalah teori tentang tanda dan
penandaan . lebih jelasnya lagi, semiotika adalah suatu disiplin yang menyelidiki
semua bentuk komunikasi yang terjadi dengan sarana signs “tanda-tanda” dan
berdasarkan pada sign system (code) (Segers, 2004:4). Hjelmslev (dalam
Chistomy, 2001:7) mendefinisikan tanda sebagai “suatu keterhubungan antara
wahana ekspresi (expression plan) dan wahan isi (content plant). Charles Morris
menyebutkan semiosis sebagai suatu “proses tandanya”, yaitu proses ketika
sesuatu merupakan tanda bagi beberapa organism. Dari beberapa definisi diatas
maka semiotika atau semiosis dalah ilmu atau proses yang berhubungan dengan
Pada dasarnya semiosis dapat dipandang sebagai suatu proses tanda yang
dapat diberikan dalam istilah semiotika sebagai suatu hubungan antara lima
istilah
S (s, i, e, r,c)
S adalah semiotic relation (hubungan semiotik); s untuk sign (tanda); I
untuk interpreter (penafsir); e untuk effect atau pengaruh (misalnya suatu
disposisi dalam I akan bereaksi dengan cara tertentu terhadap r pada kondisis
tertentu c karena s); r untuk reference (rujukan); dan c untuk contex (konteks)
atau conditions (kondisi).
2.1.6 Semiologi Roland Barthes
Roland Barthes dikenal sebagai salah satu seorang pemikir strukturalis
yang getol mempraktikkan model linguistic dan semiologi Saussurean. Ia juga
intelektual dan kritikus sastra Prancis yang ternama, ekspones penerapan
struktualisme dan semiotika pada studi sastra. Barthes (2001:208) menyebutkan
seagai tokoh yang memainkan peranan central dalam struktualisme tahun
1960-an d1960-an 70-1960-an. Barthes berpendapat bahasa adalah sebuah sistem t1960-anda y1960-ang
mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam waktu
tertentu. Ia mengajukan pendapat ini dalam Writing Degree Zero (1953;terj.
Ingrris 1977) dan Critical Essays (1964;terj. Inggris 1972) (Sobur, 2004:63).
Sedangkan pendekatan karya strukturalis memberikan perhatian terhadap
kode-kode yang digunakan untuk menyusun makna. Strukturalisme merupakan
Fenomena kesastraan dan estetika didekati sebagai sistem tanda-tanda
(Budiman, 2003:11).
Linguistik merupakan ilmu tentang bahasa yang sangat berkembang
menyediakan metode dan peristilahan dasar yang dipakai oleh seseorang
semiotikus dalam mempelajari semua sistem-sistem sosial lainnya. Semiologi
adalah ilmu tentang bentuk, sebab ia mempelajari pemaknaan secara terpisah
dari kandungannya (Kurniawan, 2001:156). Didalam semiologi, seseorang
diberikan kebebasan disalam memaknai sebuah tanda.
Dalam kajian tekstual, Barthes menggunakan analisis naratif struktural
yang dikembangkannya. Analisis naratif struktural secara metodologis berasal
dari perkembangan awal atas apa yang disebut linguistik struktural sebagaimana
perkembangan akhirnya dikenal sebagai semiologi teks atau semiotika. Jadi
secara sederhana analisis naratif struktural dapat disebut juga sebagai semilogi
teks karena memfokuskan diri pada naskah. Intinya sama yakni mencoba
memahamimakna suatu karya dengan menyusun kembali makna-makna yang
tersebar dengan suatau cara tertentu (Kurniawan, 2001:89).
Selain satu area penting yang dirambah Barthes dalam studinya tentang
tanda adalah peran pembaca konotasi, walaupun merupakan sifat asli tanda,
membutuhkan keaktifan pembaca agar berfungsi. Barthes secara panjang lebar
mengulas apa yang sering disebut sebagai sistem pemaknaan tataran kedua yang
dibangun atas sistem lain yang telah ada sebelumnya (Sobur, 2004:68-69).
Sastra merupakan contoh paling jelas sistem pemaknaan tataran kedua
Barthes disebut konotatif, yang dalam Mythologies-nya secara tegas ia bedakan
dari denotative atau sistem pemaknaa tataran pertama Barthes
[image:30.612.123.510.234.374.2]menggambarkannya dalam sebuah peta tanda:
Gambar 2.1 Peta Tanda Roland Barthes
1. Signifier (penanda) 2. Signified (Petanda)
3. Denotative (tanda denotative
4. Connotative Signifier (petanda konotatif) 5. Connotative signified
petanda konotatif
6. Connotative sign (tanda konotatif)
Dari peta Barthes diatas terlihat bahwa tanda denotative (3) terdiri atas
penanda (1) da petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan tanda denotative
adalah juga petanda konotatif (4). Dengan kata lain, hal tersebut merupakan
unsure material: hanya jika anda mengenal tanda “singa”, barulah kootasi seperti
harga diri, kegarangan, dan keberanian menjadi mungkin (Cobley & Janz,
1999:51 dalam Sobur, 2004:69).
Jadi, dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak hanya sekedar memiliki
makna tambahan. Namun, juga mengandung makna kedua bagian tanda
denotative yang melandasi keberadaannya. Sesungguhnya, inilah sumbangan
Barthes yang sangat berarti bagi penyempurnaan semiologi Sasurre, yang hanya
Pada dasarnya, ada perbedaan antara denotasi dan konotasi dalam
pengertian secara umum serta denotasi dan konotasi yang dimengerti oleh
Barthes. Dalam pengertian umum, denotasi biasanya dimengerti sebagi makna
harfiah, makna yang “sesungguhnya”, bahkan kadang kala juga dirancukan
dengan referensi atau acuan. Proses signifikasi yang secara tradisional disebut
sebagai denotasi ini biasanya mengacu pada penggunaan bahasa dengan arti yang
sesuai dengan apa yang terucap. Akan tetapi, didalam semiologi Roland Barthes
dan para pengikutnya, denotasi merupakan sistem signifikasi tingkat pertama
sementara, sementara konotasi merupakan tingkat kedua. Dalam hal ini denotasi
justru lebih diasosiasikan dengan keterutupan makna dan dengan demikian, sensor
atau represi politis. Sebagai reaksi yang paling ekstrim melawan keharfiahan
denotasi yang bersifat opresif ini, Barthes mencoba menyingkirkan dan
menolaknya. Baginya, yang ada hanyalah konotasi semata-mata. Penolakan ini
mungkin terasa berlebihan, namun ia tetap berguna bagi sebuah koreksi atas
kepercayaan bahwa makna “harfiah” merupakan sesuatu yang bersifat alamiah
(Budiman, 1992:22 dalam Sobur, 2004:0-71).
Dalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi ideology, yang
disebut sebagai “mitos”, dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan
pembenaran bagi nilai-nilai dominant yang berlaku dalam suatu periode tertentu
(Budiman, 2001:28 dalam Sobur, 2004:1). Didalam mitos juga terdapat pola tiga
dimensi penanda, petanda, dan tanda. Namun, sebagai suatu sistem yang unik,
mitos dibangun oleh suatu rantai pemaknaan tataran kedua. Didalam mitos pula
pemunculn sebuah konsep secara berulang-ulang dalam bentuk-bentuk yang
berbeda. Mitologi mempelajari bentuk-bentuk tersebut (Sobur, 2004:71).
Menurut Bertens (2001) tanda adalah kesatuan dari suatu bentuk penanda
atau petanda. Penanda adalah “bunyi yang bermakna” atau “coretan yang
bermakna”. Jadi penanda adalah aspek material dari bahasa; apa yang dikatakan,
apa yang didengar dan apa yang ditulis atau dibaca. Petanda adalah gambaran
mental, pikiran atau konsep. Jadi Petanda adalah aspek mental dari bahasa.
Yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam tanda bahasa yang konkret,
-kedua unsur tersebut tidak dapat dilepaskan. Tanda bahasa selalu mempunyai
dua segi signifier (penanda) dan signified (petanda). Suatu penanda tanpa
petanda tidak berarti apa-apa dan karena itu tidak merupakan tanda.
Sebaliknya suatu petanda, tidak mungkin disampaikan atau ditangkap lepas
dari penanda, petanda atau yang ditandakan itu termasuk tanda sendiri dan
dengan demikian merupakan suatu faktor linguistik. "Penanda dan Petanda
merupakan, seperti dua sisi dari sehelai kertas" (Sobur, 2004:46). Setiap tanda
kebahasaan, menurut Saussure pada dasarnya menyatukan sebuah konsep dan
suatu citra suara (sound image), bukan menyatakan sesuatu sebagai nama.
Suara yang muncul dari sebuah kata yang diucapkan merupakan penanda
(signifier), sedang konsepnya adalah petanda (signified). Dua unsur ini tidak
dapat dipisahkan, memisahkannya hanya akan menghancurkan "kata" tersebut
(Sobur, 2004:47).
Semiologi Roland Barthes tersusun atas tingkatan-tingkatan sistem
pada tingkat pertama adalah sebagai objek dan bahasa tingkat kedua yang
disebut sebagai metabahasa. Bahasa ini merupakan suatu sistem tanda yang
memuat penanda dan petanda tingkat pertama sebagai petanda baru nada taraf
yang lebih tinggi. Sistem tanda pertama kadang disebutnya sebagai konotasi
atau sistem retoris atau mitologi. Fokus kajian Barthes terletak pada sistem
tanda tingkat kedua atau metabahasa (Kurniawan, 2001:115).
Tatanan penandaan pertama adalah landasan kerja Saussure. Tatanan ini
menggambarkan relasi antara penanda dan petanda di dalam tanda, dan antara
tanda dengan referennya dalam realitas eksternal. Barthes menyebut tatanan ini
sebagai denotasi. Hal ini mengacu pada anggapan umum, maka jelaslah
tentang tanda. Sebuah contoh foto tentang keadaan jalan mendenotasi jalan
tertentu; kata jalan mendenotasi jalan tertentu; kata jalan mendenotasi jalan
pertokoan yang membentang diantara bangunan (Fiske, 2006:118). Denotasi
menurut Barthes merupakan sistem signifikasi tingkat pertama, dan lebih
diasosiasikan dengan ketertutupan makna (Sobur, 2004:70).
Konotasi dan Matabahasa adalah cerminan yang berlawanan satu sama
lain. Metabahasa adalah operasi yang membentuk mayoritas bahasa-bahasa
ilmiah yang berperan sistem riil, dan dipahami sebagai petanda di luar kesatuan
penanda-penanda asli, diluar alam deskriptif. Sedangkan konotasi meliputi
bahasa-bahasa yang sifat utamanya sosial dalam hal pesan literatur memberi
dukungan bagi makna kedua dari sebuah tatanan artifisila atau ideologis secara
Mengenai bekerjanya tanda dalam tatanan kedua adalah melalui mitos.
Mitos biasanya mengacu pada pikiran bahwa mitos itu keliru, namun
pemakaian yang biasa itu adalah bagi penggunaan oleh orang yang tak
percaya. Barthes menggunakan mitos sebagai seorang yang percaya dalam
artiannya orisinal. Mitos adalah cerita yang digunakan suatu kebudayaan untuk
menjelaskan atau memahami beberapa aspek dari realitas suatu alam. Mitos
primitive berkenaan dengan hidup dan mati, manusia dan dewa, baik dan
buruk. Mitos kita yang lebih bertaktik-taktik adalah tentang maskulinitas dan
feminitas, tentang keluarga, tentang keberhasilan atau tentang ilmu. Bagi
Barthes, mitos merupakan cara berfikir dari suatu kebudayaan tentang sesuatu,
cara untuk mengkonseptualisasikan atau memahami sesuatu. Barthes
memikirkan mitos sebagai mata rantai dari konsep-konsep terkait. Bila
konotasi merupakan pemaknaan tatanan kedua dari petanda, maka mitos
Gambar 2.2 Dua Tatanan Petandaan Barthes
sumber: Fiske, 2006 121- 123
Pada tatanan kedua, sistem tanda dari tatanan pertama
disisipkan ke dalam sistem nilai budaya
Barthes menegaskan bahwa cara kerja pokok mitos adalah untuk
menaturalisasikan sejarah. Ini menunjukkan kenyataan bahwa mitos
sebenarnya merupakan produk kelas sosial yang mencapai dominasi melalui
sejarah tertentu. Mitos menunjukkan maknanya sebagai alami, dan bukan
bersifat historis atau sosial. Mitos memistifikasi atau mengaburkan
asal-usulnya sehingga memiliki dimensi, sambil menguniversalisasikannya dan
membuat mitos tersebut tidak bisa diubah, tapi juga cukup adil (Fiske,
2006:123).
Untuk membuat ruang atensi yang lebih lapang bagi deseminasi
makna dan pluralitas teks, maka Barthes mencoba memilah-milah
penanda-Denotasi Penanda
Petanda
Konotasi
Mitos Bentuk
penanda pada wacana naratif ke dalam serangkaian fragmen ringkas dan
berutun yang disebutnya sebagai leksi-leksia (Iexias), yaitu satuan-satuan
pembacaan (unit of reading) dengan panjang pendek yang bervariasi.
Sepotong bagian teks yang apabila dibandingkan dengan teks lain
disekitarnya adalah sebuah leksia. Akan tetapi sebuah leksia sesungguhnya
bisa berupa apa saja, kadang hanya berupa satu-dua patah kata kadang
kelompok kata, kadang beberapa kalimat, bahkan sebuah paragraph,
tergantung pada ke"gampang"annya (convenience) saja. Dimensinya
tergantung kepada kepekatan dari konotasi-konotasinya yang bervariasi
sesuai dengan momen-momen teks. Dalam proses pembacaan teks,
leksia-leksia tersebut dapat ditemukan baik pada tataran kontak pertama diantara
pembaca dan teks maupun pada saat satuan-satuan itu dipilah-pilah
sedemikian rupa sehingga diperoleh aneka fungsi pada tatanan-tatanan
pengorganisasian yang lebih tinggi (Budiman, 2003:54).
Dalam memaknai sebuah "teks" kita akan dihadapkan pada
pilihan-pilihan pisau analisis mana yang bisa kita pakai dari sekian jumlah,
pendekatan yang begitu melimpah. Ketika kita sampai pada pilihan tertentu
semestinya "setia" dengan satu pilihan, namun bisa juga mencampuradukkan
dengan beberapa pilihan tersebut, tergantung kepentingan dari tujuan
"pembaca" dalam membeda pembacaannya. Bisa pula benar-benar hanya
memfokuskan pada teks dan "melupakan" sang pengarang, "pembaca"
Dalam hal ini "pembacalah" yang memberikan makna dan penafsiran.
"Pembaca" mempunyai kekuasaan absolut untuk memaknai sebuah hasil
karya (lirik lagu) yang dilihatnya, bahkan tidak hanis sama dengan maksud
pengarang. Semakin cerdas pembaca itu menafsirkan, semakin cerdas pula
karya lirik. dalam lagu itu memberikan maknanya. Wilayah kajian "teks"
yang dimaksud Barthes memang sangat luas, mulai bahasa verbal seperti
karya sastra hingga fashion atau cara berpakaian. Barthes melihat seluruh
produk budaya merupakan teks yang bisa dibaca secara otonom dari pada
penulisnya.
2.1.6.1 Kode Pembacaan
Segala sesuatu yang bermakna tergantung pada kode. Menurut Roland
Barthes di dalam teks setidaknya beroperasi lima kode pokok yang di
dalamnya semua penanda tekstual (baca: leksia) dapat dikelompokkan. Setiap
atau masing-masing leksia dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari lima
buah kode ini. Kode-kode ini menciptakan sejenis jaringan. Adapun
kode-kode pokok tersebut yang dengannya seluruh aspek tekstual yang signifikasi
dapat dipahami, meliputi aspek sintagmatik dan semantik sekaligus, yaitu
menyangkut bagaimana bagian-bagiannya berkaitan satu sama lain dan
terhubung dengan dunia luar teks.
Lima kode yang ditinjau oleh Barthes adalah kode herneutika (kode
teka-teki), kode proretik, kode budaya, kode semik, dan kode simbolik.
1. Kode Hermeneutika atau kode teka-teki berkisar pada harapan untuk
mendapatkan "kebenaran" bagi pertanyaan yang muncul dalam teks.
Kode teka-teki merupakan unsur terstruktur yang utama dalam narasi
tradisional. Di dalam narasi ada suatu kesinambungan antara
permunculan suatu peristiwa teka-teki dan penyelesaian di dalam
cerita. (Sobur, 2004:65). Di bawah kode ini, orang dapat mendaftar
beragam istilah yang sebuah teka-teki dapat dibedakan, diduga,
diformulasikan, dipertahankan, dan akhirnya disikapi. Kode ini
disebut juga suara kebenaran (The Voice of Truth) (Kurniawan,
2001:69).
2. Kode Proaetik atau kode tindakan/lakuan dianggapnya sebagai
perlengkapan utama teks yang dibaca orang; artinya, antara lain,
semua teks yang bersifat naratif (Sobur, 2004:66). Kode proaetik
yaitu kode yang mengandung cerita urutan narasi, atau antar narasi
(Tinarbuko, 2008:19).
3. Kode Budaya sebagai referensi kepada sebuah ilmu atau lembaga
pengetahuan. Biasanya orang mengindikasikan tipe pengetahuan
mengacu pada, tanpa cukup jauh mengkontruksi (merekonstruksi),
budaya yang mereka ekspresikan (Kurniawan, 2001:69). Gnomik atau
kode kultural (Budaya) banyak jumlahnya. Kode ini merupakan acuan
teks ke benda-benda yang sudah diketahui dan di kodifikasi oleh
kea pa yang telah diketahui. Rumusan suatu budaya atau sub budaya
adalah hal-hal kecil yang telah dikodifikasikan (Sobur, 2004:66).
4. Kode semik atau semantic, yaitu kode yang mengandung konotasi
pada level penanda (Tinarbuko, 2008:18). Kode semik menawarkan
banyak sisi. Dalam proses pembacaan, pembaca menyusun tema suatu
teks. Ia melihat bahwa konotasi kata atau frase tertentu dalam teks
dapat dikelompokkan dengan konotasi kata atau frase yang mirip. Jika
melihat kumpulan satuan konotasi melekat, kita menemukan suatu
tema di dalam cerita. Perlu dicatat bahwa Barthes menganggap
bahwa denotasi sebagai konotasi yang paling kuat dan paling "akhir"
(Sobur, 2004: 65-66).
5. Kode simbolik (tema) yang bersifat tidal: stabil dan dapat dimasuki
melalui beragam sudut pendekatan. Kode simbolik merupakan aspek
pengkodean fiksi yang paling khas bersifat struktural, atau tepatnya
menurut konsep Barthes, pascastruktural. Hal ini didasarkan pada
gagasan bahwa makna berasal dari beberapa oposisi biner atau
pembedaan baik dalam taraf bunyi menjadi fonem dalam proses
produksi wicara, maupun taraf oposisi psikoseksual yang melalui
2.2 Kerangka Berfikir
Manusia adalah Homo Semioticus, dimana masing-masing individu
mempunyai latar belakang pemikiran yang berbeda-beda dalam memaknai
suatu objek atau peristiwa. Manusia dapat memproklamasikan sesuatu, apa
saja sebagai tanda karena hat itu dapat dilakukan oleh semua manusia
(Van Zoest, 1993 dalam Sobur 2004:vii).
Oleh karena latar belakang pengalaman (field of experience) dan
pengetahuan (frame of reference) yang berbeda pada setiap individu
tersebut. Dalam menciptakan sebuah pesan komunikasi, dalam hat ini
pesan disampaikan dalam bentuk lagu, maka pencipta lagu juga tidak
terlepas dari dua hal di atas.
Begitu juga peneliti dalam memaknai tanda dan lambang yang ada
dalam obyek, juga berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki
peneliti melakukan interpretasi terhadap tanda dan lambang berbentuk
tulisan pada lirik lagu "Rindu Bersatu" dalam hubungannya dalam
representasi nasionalisme dengan menggunakan metode semiologi dari
Roland Barthes, sehingga akhirnya dapat diperoleh hasil dari interpretasi
data mengenai representasi nasionalisme tersebut.
Dari data-data berupa lirik lagu "Rindu Bersatu", kata-kata dan
rangkaian kata dalam lirik lagu tersebut kemudian dianalisis dengan
menggunakan metode signifikasi dua tahap (two order of signification) dari
Roland Barthes. Dimana pada tataran pertama tanda denotatif (denotative
kedua tanda denotatif (denotative sign) juga merupakan penanda konotatif
(konotative signifier) sehingga muncul petanda konotatif (konotative
signified) yang akan membentuk tanda konotatif (konotatif signifier)
sehingga muncul petanda konotatif (konotative sign). Dalam tahap kedua
dari tanda konotatif akan muncul mitos yang menandai masyarakat yang
berkaitan dengan budaya sekitar. Kemudian teks akan dimaknai dengan
menggunakan lima macam kode Barthenz, yaitu kode hemeunitik, kode
semik, kode simbolik, kode proaetik dan kode kultural untuk pemaknaan
melalui pembacaan dari kode-kode tersebut akan di ungkap substansi dari
[image:41.612.161.485.393.496.2]pesan dibalik lirik lagu "Rindu Bersatu”
Gambar 2.3 Bagan kerangka pikir peneliti tentang representasi Lagu "Rindu
Bersatu”
Representasi dari pembacaan kode-kode yang ada dalam lagu “Rindu Bersatu” Lagu
“Rindu Bersatu”
Analisis Semiologi Roland Barthes : 5
Kode yaitu hermenuetik, semik,
35
3.1 Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Artinya data yang
digunakan merupakan data kualitatif yaitu tidak menggunakan data atas
angka-angka, melainkan berupa pesan-pesan verbal atau (tulisan) yang terdapat dalam
lirik lagu “Rindu bersatu Charly ST12. Data-data kualitatif tersebut berusaha
diiterpretasikan dengan rujukan, acuan, atau referensi-referensi secara ilmiah.
Penelitian kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama
menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila behadapan dengan
kenyataan ganda. Kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat peneliti
dan yang diteliti. Dan yang ketiga, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri
dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola yang dihadapi
(Moleong, 2002:5)
Metode yang digunakan didalam penelitian ini bersifat
kualitatif-interpretative, penelitian ini akan mendekonstruksi tanda-tanda dengan
menggunakan metode semiotik dari Roland Barthes, yaitu metode signifikasi dua
tahap (two order signification). Dimana pada tataran pertama tanda denotative
(denotative sign) terdiri atas penanda dan petanda (signifier signified) dan pada
tataran kedua, tanda denotative (denotative sign) juga merupakan penanda
yang membentuk tanda konotatif (connotative sign). Dalam tahap kedua dari
tanda konotative akan muncul mitos yang menandai masyarakat yang berkaitan
dengan budaya sekitar.
Melalui pandangan dari Rolland Barthes tersebut kemudian dijelaskan
lewat penafsiran dengan menggunakan teori perspektif nasionalisme yang pada
akhirnya akan dapat ditarik makna nasionalisme yang tersirat dari lirik lagu
tersebut. Sesuai dengan definisi nasionalisme itu sendiri, yaitu paham yang
menunjukkan bahwa kesetiaan dari tiap individu atau negara ditujukan kepada
kepribadian bangsanya
Dengan menggunakan paradigma konstruktivisme, analisis semiotika
bersifat kualitatif, jenis penelitian ini memberi peluang besar bagi dibuatnya
interpretasi-interpretasi alternatif (Sobur, 2001: 147)
3.1.1. Analisis Semiologi
Metode semiotika adalah sebuah metode yang memfokuskan pada “tanda
dan teks” sebagai obyek kajiannya. Serta bagaimana peneliti menafsirkan dan
memahami kode (decoding) dibalik tanda dan teks tersebut (Pilliang, 2003 : 270).
Penggunaan semiotika sebagai metode pembacaan di dalam berbagai cabang
keilmuan dimungkinkan, oleh karena ada kecenderungan dewasa ini untuk
memandang berbagai diskursus sosial, politik, ekonomi, budaya dan seni sebagai
fenomena bahasa. Berdasarkan pandangan semiotika, bila seluruh praktek sosial
dianggap sebagai fenomena bahasa, maka ia dapat pula dipandang sebagai tanda
Dengan semiotika kita berurusan dengan tanda dengan tanda-tanda kita
mencoba mencari keteraturan ditengah dunia yang centang penerang ini, setidak
nya agar kita mempunyai pegangan. “Apa yang dikerjakan oleh semiotika adalah
pada sebuah kesadaran” (Sobur, 2003:16).
3.1.2 Unit Analisis
Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanda-tanda berupa
tulisan, yaitu terdiri atas kata-kata yang membentuk kalimat yang ada pada lirik
lagu dan “Rindu Bersatu”.
3.1.3. Korpus Penelitian
Korpus adalah sekumpulan bahan yang terbatas, yang ditentukan pada
perkembangannya oleh analisis semacam kesemenaan bersifat sehomogen
mungkin (Kurniawan, 2001:70). Korpus atau data yang dikumpulkan berwujud
teks. Pada penelitian ini yang menjadi korpus adalah lirik lagu berjudul “Rindu
Bersatu” yang menunjukkan atau mewakili konsep nasionalisme..
Alasan peneliti menggunakan lagu dan “Rindu Bersatu” sebagai korpus
adalah dikarenakan dalam lagu tersebut menggambarkan rasa nasionalisme
bangsa Indonesia.
Berikut lirik lagu lagu “Rindu Bersatu” yang mewakili konsep nasionalisme
RINDU BERSATU
Ada satu yang hilang Dari negeriku
Tak seperti dahulu saling bersatu
Ada yang tlah berubah Dari bangsaku
Hilangnya kasih sayang itu menyakitkanku
Percuma ada cinta
Kalau tuk bertengkar terus Percuma ada rindu
Kalau tak saling bersatu
Jangan takut menjadi Indonesia Teruslah maju negeriku
Teruslah bertahan bangsaku Dan tetap indah seperti dulu
3.2 Tehnik Pengumpulan data
Tehnik pengumpula data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan
sekunder yang diperoleh dari:
1. Data primer : pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
cara mendengarkan lagu “Rindu Bersatu”, kemudian membaca serta
memahami kata-perkata dari lirik lagu tersebut, yang kemudian dipilih
kembali oelh peneliti lirik-lirik yang menggambarkan nasionalisme.
2. Data sekunder : data yang berasal dari bahan-bahan referensi, seperti
buku-buku artikel dan data dari internet yang berhubungan dengan objek
3.3 Metode Analisis Data
Peneliti menginterpretasikan teks dalam lirik lagu “Rindu Bersatu”, serta
menyimpulkan berbagai makna mengenai bagaimana nasionalisme digambarkan
dalam lirik lagu tersebut. Nasionalisme kebangsaan adalah kesetiaan masyarakat
terhadap wilayah, yaitu terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme ini yang
kemudian mendorong seseorang untuk memiliki perasaan rela berkorban sebagai
wujud rasa cinta terhadap tanah air. Dari lirik lagu terdirir judul lagu dan
reffinilah yang akan dianalisis dalam penelitian ini dengan menggunakan
pandangan dari roland barthes, yaitu metode signifikasi dua tahap (two order of
signification) yang akan dianalisis menggunakan lima macam kode pembacaan
menurut barthes, yaitu kode hermeunitik, kode semik, kode simbolik, kode
proaretik, dank ode cultural untuk pemaknaan sebuah tanda sehingga akan
mengetahui tanda denotative dan tanda konotatifnya.
Melalui pandangan dari Roland Barthes tersebut kemudian dijelaskan lewat
penafsiran dengan menggunakan teori persfektif nasionalisme yang pada akhirnya
akan dapat ditarik suatu makna yang sebenarnya tentang rasa nasionalisme
40
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1. ST12 Band
ST12 adalah grup musik yang mengusung aliran musik berkarakter
musik melayu. ST 12 didirikan di Bandung oleh Hilman Febry alias Pepep
(drum), Dedy Sudrajad alias Pepeng (gitar), Muhammad Charly Van Houten
alias Charly (vokal) dan Iman Rush (gitar).
Awalnya, keempat personil ini tak saling kenal, meskipun mereka telah
lama berkecimpung di dunia musik. Mereka mulai akrab setelah ssering
bertemu di studio rental di Jalan Stasiun Timur 12, Bandung, milik Pepep.
Mereka pun akhirnya mendirikan ST12 pada tanggal 20 Januari 2005. Nama
ST12 yang merupakan kependekan dari Jl. Stasiun Timur No.12 adalah
pemberian dari Pepep, Helmi Aziz. (www.st12Band.com, diakses pada 06
November 2010).
Meskipun keempat personel ini memiliki aliran music favorit yang
berbeda, Charly menggemari Jazz, Pepep suka jazz dan rock, sementara
Pepeng tumbuh bersama music rock, namun mereka kompromi untuk
membuat ST12 beraliran melayu. Jika yang lain menyanyikan notasi minor
melayuyang merupakan akar budaya Indonesia. (
www.tentangst12-band.com, diakses pada 06 November 2010).
St12 terpaksa merilis album perdana mereka melalui jalur independent
(indie) Karen tak ada label yang mau menampung mereka. Saying, pada
bulan Oktober 2005, saat tour promosi album di Semarang, Iman Rush
meninggal dunia akibat pecah pembuluh darah di otak. Trinity Optima
Production mulai melirik ST12 setelah album perdananya, Jalan terbaik
(2005), meraih sukses. Album kedua, P.U.S.P.A (2008) yang didesikan
untuk Iman, dirilis dibawah label Trinity.
Album perdana ‘Jalan Terbaik’ yang berhasil menarik perhatian
masyarakat luas. ATSL (Aku Tak Sanggup Lagi), Rasa Yang Tertinggal
atau Aku Masih Sayang menjadi single andalan mereka. Masih ada
beberapa single yang menarik perhatian di album pertama ini, diantaranya
Ruang Rindu, Kepedihan Jiwa, Cinta Abadi, Sirna Sudah, Dewiku, jiwa
Yang Hilang, dan Jalan Terbaik.
Meski duka melanda karena salah satu personil mereka Iman Rush
meninggal, ST12 tetap bertahan. 3 tahun kemudian mereka membuktikan
eksistensinya dengan album kedua P.U.S.P.A. diman album kedua ini
berisikan 12 lagu andalan, diantaranya P.U.S.P.A (Putuskan Saja Pacarmu),
jangan Pernah Berubah, Cari Pacar Lagi, Putri Iklan, S.K.J (saat kau Jauh),
Saat Terakhir, Tak Dapat Apa-Apa (My Hot), Cinta Jangan Dinanti, Cinta
Sukses dengan kedua albumnya, kali ini ST12 mencoba merilis single
rohani dengan judul Kebesaranmu. Setelah album rohani yang juga meraih
sukses, Charly dengan spontan menciptakan single lagu terbarunya berjudul
“Sinar Pahlawanku”, yang dinyanyikan bersama Regina (istri), dan Restu
(anaknya). Single lagu ini terinspirasi karena bentuk simpati terhadap cinta
bocah perempuan bernama Sinar yang masih berumur 6 tahun kepada
ibunya yang menderita lumpuh. (http:///berandakawasan.wordpress.
com/2010/11/06/kisah-sinar-menggugah-banyak-orang/).
Moch.Charly van houten yang lahir 5 November 1981 tak pernah luput dari
Gitar.Charly selalu membawa Gitar nya kemana pun,entah ketika tidur,hang
out,sarapan,bahkan mau masuk kamar mandi.Untuk sarapan Pagi Charly
selalu memakan Roti,agar stamina saat bernyanyi diatas panggung kalau
Libur, Charly selalu menghabiskan waktu bersama pacarnya
dipegunungan/lesehan.menurut Charly, ia bisa sukses berkat kedua Orang
Tuanya Soegendri & Toethe Hartika.Tanpa dukungan ke2 Ortu mungkin
bisa tak seperti Cekarang.Ada satu Hobi Charly yang Unik.Rupanya
Lulusan Fakultas Seni Musik Universitas Pasundan ini sering mengisengi
para personel ST12. Saat temannya sedang Bermain Ps Charly suka
mencabut stop kontak Tv/mematikan Tv, cowok bernama asli Muhammad
Charly Van Houtten ini awalnya tertarik untuk jadi gitaris, gara-gara
uwaknya yang musisi itu pernah memberinya hadiah berupa gitar. Gitar
kesayangannya itu lalu dia bawa kemana-mana sebagai instrumen membuat
Charly cukup merdu untuk jadi seorang vokalis. Akhirnya sejak tahun 1998,
saat mulai manggung dari kafe ke kafe bareng teman-temannya, Charly
dipercaya untuk memegang posisi vokal.
Buat cowok kelahiran Cirebon, 5 November 1982 ini, musik bukan cuma
sekedar hobi, tapi juga tujuan hidup. Ini yang jadi alasan utamanya hijrah
ke Bandung dari Cirebon di tahun 2000, yaitu untuk mengambil kuliah
jurusan seni musik di Universitas Pasundan Bandung.
Selama di Bandung, Charly mengaku nggak pernah punya tempat tingggal.
Biasanya dia menginap di rumah teman atau di studio musik tempatnya
latihan. Sedangkan untuk membeli makan, dia terpaksa mengamen di
perempatan jalan Dago.
Untungnya perjuangan ini nggak sia-sia, karena pengagum Al Jarreau dan
Armand Maulana ini berhasil menelurkan satu album bareng sebuah band
bernama Afterclose, sebelum akhirnya ditarik bergabung oleh ST12.
Perannya di ST12 cukup penting, karena hampir semua lirik lagu band ini
adalah ciptaan Charly. Bahkan, cowok yang menulis lagu sejak kelas 1 SMP
ini sekarang mulai mencoba-coba membuat lagu untuk dinyanyikan artis
lain. Pingkan Mambo dan Aris Idol adalah beberapa di antaranya.
Mengenai Aris, Charly punya alasan sendiri untuk kagum pada salah satu
peserta Indonesian Idol itu.
"Waktu itu di salah satu episode Idol, Aris sempat bawain lagu ST12 yang
judulnya Rasa Yang Tertinggal. Jujur aja aku sempat nangis liatnya, dia
nggak jauh sama aku, dia dulunya pengamen juga. Jadi aku salut lah sama
dia, mudah-mudahan aja dia nggak patah semangat," kata Charly
sSukses dengan single Sinar Pahlawanku dan mendapat respon yang
baik oleh masyarakat. Charly menciptakan single lagu bertemakan
nasionalisme “Rindu Bersatu”, single ini terinspirasi karena suatu kerinduan
bahwa Indonesia sangat indah waktu Charly masih kecil, tetapi sekarang
Charly melihat Indonesia semakin semrawut denganpeperangan antar
kepentingan yang membuat hancur. Lagu ini menyadarkan bila kita punya
cinta dan bagaimana menyatukan sesuatu yang tadinya semrawut. Charly
mengaku sangat bangga karena lagunya, ‘Rindu Bersatu’ bias terpilih untuk
program Indonesia Bersatu (Indonesia Unite). Lagu ini dinyanyikan oleh 14
artis dan group band papan atas yang menguasai 80 persen pangsa music
nasional. Mereka adalah Gita Gutawa, ST12, Ungu, Changcuters, Rio
Febrian, Kangen Band, Sherina, Nidji, d’masiv, Vierra, Kotak, Geisha,
Alexa, dan Azura. Sebagai hasil penjualan RBT lagu ini disepakati untuk
disumbangkan kepada program Save A Teen – Sampoerna Foundation;
sebuah program yang ditujukan untuk memberikan beasiswa untuk
mencegah anak-anak tidak mampu ptutus sekolah. Lagu ini juga di
dedikasikan untuk persatuan dan kstuan bangsa. (http://wap.vivanews.
com/news/read/162945-lagu-rindu-bersatu-keprihatinan-charlie-st12),
4.2 Penyajian dan Analisis Data
4.2.1 Penyajian Data
Lagu Rindu Bersatu sangat kental nuansa Nasionalisme karena dalam
lirik lagu terdapat lirik lagu yang menunjukkan kerinduan bahwa dahulu
Indonesia sangat indah, tetapi sekarang Indonesia semakin semrawut
dengan peperangan antar kepentingan yang membuat hancur. Lagu ini
menyadarkan bila kita punya cinta dan bagaimana menyatukan sesuatu yang
tadinya semrawut.
Korpus dalam penelitian ini adalah lirik lagu dengan judul “Rindu Bersatu”.
Lirik lagu “Rindu Bersatu ” selengkapnya sebagai berikut:
RINDU BERSATU
Ada satu yang hilang
Dari negeriku
Tak seperti dahulu saling bersatu
Ada yang tlah berubah
Dari bangsaku
Hilangnya kasih sayang itu menyakitkanku
Percuma ada cinta
Kalau tuk bertengkar terus
Percuma ada rindu
Kalau tak saling bersatu
Jangan takut menjadi Indonesia
Teruslah maju negeriku
Teruslah bertahan bangsaku
4.2.2 Analisis Data
Judul lagu mencerminkan isi dari lirik lagu yang diwakilinya.
Representasi lirik lagu “Rindu Bersatu” ini akan dilakukan peneliti dengan
menentukan penanda dan petanda dalam peta tanda Roland Barthes,
mengkategorikan kalimat dari bait ke dalam lima kode dan leksia yaitu kode
hermeneutik (kode teka-teki), kode semik (makna konotatif), kode simbolik,
kode proaretik (logika tindakan), dan kode gnomik atau kode kultural. Pada
lirik lagu “Rindu Bersatu” ini terdapat tiga bait dan satu bait puisi, isi bait
yang pertama terdiri dari tiga kalimat yaitu :
……….
Ada satu yang hilang
Dari negeriku
Tak seperti dahulu saling bersatu
……….
Bait 1 kalimat 1 :
Ada satu yang hilang
1.Signifier (penanda)
Ada Satu Yang
Hilang
2. Signified
(petanda) Sesuatu yang hilang
3. Denotative sign (tanda denotatif) Ada sesuatu yang telah musnah
4. Connotative Signifier (penanda konotatif) Kerinduan akan sesuatu yang telah musnah
5. Connotative
Signified (Petanda
Konotatif)
Suatu rasa yang
musnah 6. Connotative Sign (Tanda Konotatif)
Kalimat pertama dari bait pertama ini termasuk dalam kode
hermeneutik, karena dalam kalimat Ada