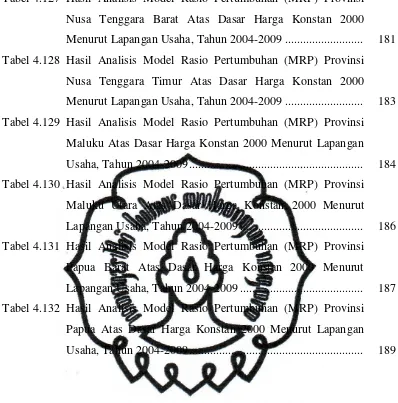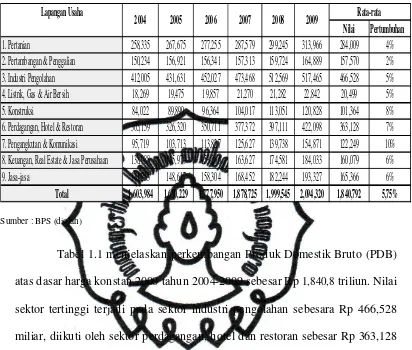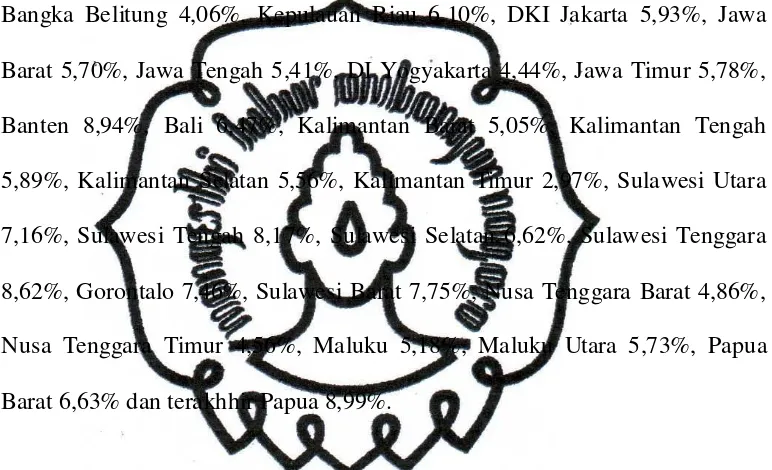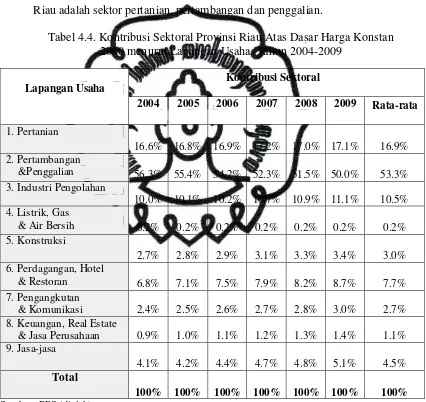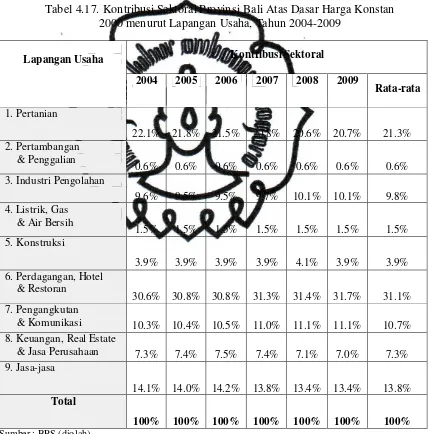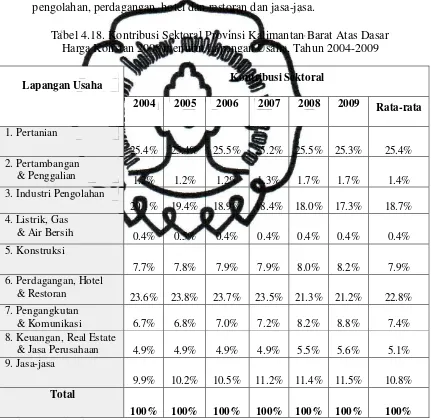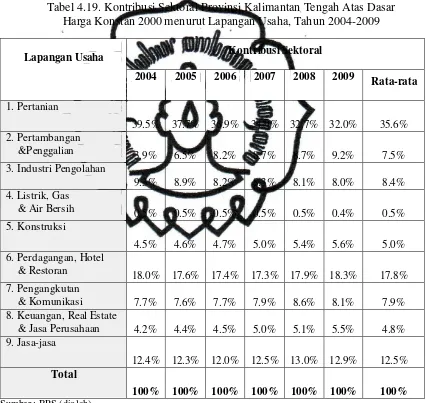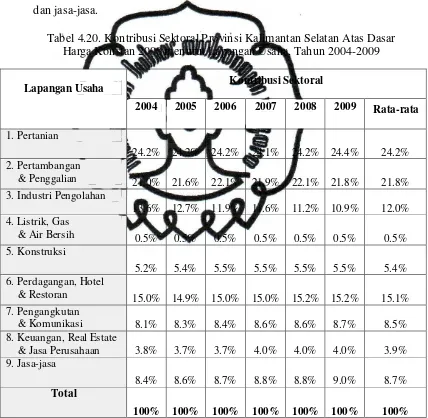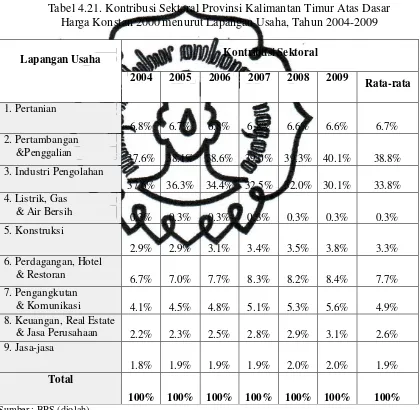ANALISIS STRUKTUR EKONOMI PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2009
SKRIPSI
Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi
Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh :
DIMAS ARYO SUGANDI F0108052
commit to user
commit to user
iv MOTTO
Aku cinta negeri ini, tapi aku benci dengan sistem
yang ada, hanya ada satu kata...LAWAN.
(Jeruji)
Pikiran yang besar membicarakan ide-ide.
Pikiran yang rata-rata membicarakan kejadian-kejadian.
Dan pikiran yang kerdil membicarakan orang-orang.
PERSEMBAHAN
Penulis persembahan kepada:
Ø Abah dan Mama yang telah memberikan do’a,
kasih sayang, moral, spiritual, dan material yang
takkan pernah ternilai.
Ø Kakak dan adikku yang telah mendorong dan
memotivasi aku untuk terus berjuang.
Ø Taurista Mega S.P. yang selalu memberikan
semangat dalam hidupku.
Ø Semua mahkluk Allah yang telah menyayangi
commit to user
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Struktur Ekonomi Provinsi Di Indonesia Tahun 2004-2009”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Strata (S-1) pada program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Dr. Wisnu M.S selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret
Surakarta
2. Drs. Supriyono selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas
Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
3. Malik Cahyadin, SE, M.Si selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberi
bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Nurul Istiqomah, SE, M.Si selaku Tim Penguji Skripsi yang memberi
masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Sumardi, SE, MESPselaku Dosen Penguji Skripsi.
6. Mugi Rahardjo, Drs, M.Si selaku Tim Penguji Skripsiyang memberi masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
commit to user
vi
8. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya Drs. Djainudin Suryo Bono dan Halimah Purba yang telah mendidik, merawat dan menyekolahkan saya sehingga saya dapat lulus menjadi Sarjana (S1). Terima kasih Abah dan Mama atas segala ketulusanmu untuk selalu mendukung, menyemangati dan mendoakanku sampai skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kakakku yang telah menemani dalam segala hal serta memberikan dukungan dan doa sampai skripsi ini selesai.
10. Taurista Mega S.P. yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, bantuan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Buat seluruh teman ku yang telah menemaniku selama aku kuliah disolo. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
commit to user
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN... ii
HALAMAN PENGESAHAN ... iii
HALAMAN PERSEMBAHAN ... iv
HALAMAN MOTTO ... iv
KATA PENGANTAR ... v
DAFTAR ISI ... vii
DAFTAR TABEL ... ix
DAFTAR GAMBAR ... xxi
ABSTRAK ... xxii
BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1
B. Perumusan Masalah ... 7
C. Tujuan Penelitian ... 7
D. Manfaat Penelitian ... 7
II. TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori... ... 8
1. Perubahan Struktural... . 8
2. Perencanaan Ekonomi.. ... 8
3. Pertumbuhan Ekonomi ... 10
4. Pembangunan Ekonomi... 11
5. Pembangunan Ekonomi Daerah ... 19
6. Produk Domestik Bruto (PDB) ... 24
7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ... 26
B. Penelitian Terdahulu... 27
commit to user
viii III. METODE PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian ... 29
B. Jenis dan Sumber Penelitian……….… ... 29
C. Definisi Operasional Variabel ... 30
1. Struktur Ekonomi ... 30
2. Produk Domestik Bruto (PDB) ... 30
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ... 30
D. Teknik Analisis Data……….… .. 31
1. Kontribusi Sektoral ... 31
2. Analisis Shift Share (SS) ... 31
3. Tipologi Klassen ... 34
4. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) ... 35
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Analisis Pendahuluan……….…. .... 38
B. Hasil Analisis dan Pembahasan……….…. . 40
1. Kontribusi Sektoral ... 40
2. Analisis Shift Share (SS) ... 73
3. Tipologi Klassen ... 107
4. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) ... 141
V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan……… ... 191
B. Saran….………... 192
DAFTAR PUSTAKA ... ... 194
commit to user
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Produk Domestik Bruto (PDB) Harga Konstan 2000 Menurut
lapangan usaha, 2004-2009 (Miliar Rupiah) ...
3
Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan
2000 Menurut lapangan usaha, 2004-2009 (Miliar Rupiah) ... 5
Tabel 3.1 Klasifikasi wilayah menurut Tipologi Klassen ... 35
Tabel 4.1 Kontribusi Sektoral Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan
2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 40
Tabel 4.2 Kontribusi Sektoral Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga
Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 41
Tabel 4.3 Kontribusi Sektoral Provinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga
Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 42
Tabel 4.4 Kontribusi Sektoral Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan
2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 43
Tabel 4.5 Kontribusi Sektoral Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Konstan
2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 44
Tabel 4.6 Kontribusi Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 45
Tabel 4.7 Kontribusi Sektoral Provinsi Begkulu Atas Dasar Harga
Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 46
Tabel 4.8 Kontribusi Sektoral Provinsi Lampung Atas Dasar Harga
Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 47
Tabel 4.9 Kontribusi Sektoral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 48
Tabel 4.10 Kontribusi Sektoral Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
commit to user
x
Tabel 4.11 Kontribusi Sektoral Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga
Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 50
Tabel 4.12 Kontribusi Sektoral Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga
Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 51
Tabel 4.13 Kontribusi Sektoral Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga
Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 52
Tabel 4.14 Kontribusi Sektoral Provinsi DI Yogyakarta Atas Dasar Harga
Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 53
Tabel 4.15 Kontribusi Sektoral Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga
Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 54
Tabel 4.16 Kontribusi Sektoral Provinsi Banten Atas Dasar Harga
Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 55
Tabel 4.17 Kontribusi Sektoral Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan
2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 56
Tabel 4.18 Kontribusi Sektoral Provinsi Kalimantan Barat Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 57
Tabel 4.19 Kontribusi Sektoral Provinsi Kalimantan Tengah Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 58
Tabel 4.20 Kontribusi Sektoral Provinsi Kalimantan Selatan Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 59
Tabel 4.21 Kontribusi Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 60
Tabel 4.22 Kontribusi Sektoral Provinsi Sulawesi Utara Atas Dasar Harga
Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 61
Tabel 4.23 Kontribusi Sektoral Provinsi Sulawesi Tengah Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
commit to user
Tabel 4.24 Kontribusi Sektoral Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 63
Tabel 4.25 Kontribusi Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 64
Tabel 4.26 Kontribusi Sektoral Provinsi Gorontalo Atas Dasar Harga
Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 65
Tabel 4.27 Kontribusi Sektoral Provinsi Sulawesi Barat Atas Dasar Harga
Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 66
Tabel 4.28 Kontribusi Sektoral Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 67
Tabel 4.29 Kontribusi Sektoral Provinsi Nusa Tenggara Timur Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 68
Tabel 4.30 Kontribusi Sektoral Provinsi Maluku Atas Dasar Harga
Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 69
Tabel 4.31 Kontribusi Sektoral Provinsi Maluku Utara Atas Dasar Harga
Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 70
Tabel 4.32 Kontribusi Sektoral Provinsi Papua Barat Atas Dasar Harga
Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 71
Tabel 4.33 Kontribusi Sektoral Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan
2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 72
Tabel 4.34 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Aceh Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 73
Tabel 4.35 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Sumatera Utara Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
commit to user
Tabel 4.39 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Sumatera Selatan Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 78
Tabel 4.40 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Begkulu Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 79
Tabel 4.41 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Lampung Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 80
Tabel 4.42 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan
Usaha, Tahun 2004-2009 ... 81
Tabel 4.43 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Kepulauan Riau Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 82
Tabel 4.44 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi DKI Jakarta Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 83
Tabel 4.45 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Jawa Barat Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
commit to user
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 88
Tabel 4.50 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Bali Atas Dasar Harga
Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 89
Tabel 4.51 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Kalimantan Barat Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 90
Tabel 4.52 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Kalimantan Tengah
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,
Tahun 2004-2009 ... 91
Tabel 4.53 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Kalimantan Selatan
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,
Tabel 4.56 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Sulawesi Tengah Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
commit to user
xiv
Tabel 4.57 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Sulawesi Selatan Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 96
Tabel 4.58 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Sulawesi Tenggara
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,
Tahun 2004-2009 ... 97
Tabel 4.59 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Gorontalo Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 98
Tabel 4.60 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Sulawesi Barat Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 99
Tabel 4.61 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Nusa Tenggara Barat
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,
Tahun 2004-2009 ... 100
Tabel 4.62 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Nusa Tenggara Timur
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 105
Tabel 4.67 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Aceh Atas Dasar
commit to user
2004-2009 ...
...
106 ...
Tabel 4.68 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Sumatera Utara Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 108
Tabel 4.69 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Sumatera Barat Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 109
Tabel 4.70 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Riau Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 110
Tabel 4.71 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Jambi Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 111
Tabel 4.72 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Sumatera Selatan
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,
Tahun 2004-2009 ... 112
Tabel 4.73 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Begkulu Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 113
Tabel 4.74 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Lampung Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 114
Tabel 4.75 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan
Usaha, Tahun 2004-2009 ... 115
Tabel 4.76 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Kepulauan Riau Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
commit to user
xvi
Tabel 4.77 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi DKI Jakarta Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 117
Tabel 4.78 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Jawa Barat Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 118
Tabel 4.79 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Jawa Tengah Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 119
Tabel 4.80 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi DI Yogyakarta Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 120
Tabel 4.81 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Jawa Timur Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 121
Tabel 4.82 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Banten Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 122
Tabel 4.83 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Bali Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 123
Tabel 4.84 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Kalimantan Barat
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,
Tahun 2004-2009 ... 124
Tabel 4.85 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Kalimantan Tengah
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,
Tahun 2004-2009 ... 125
Tabel 4.86 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Kalimantan Selatan
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,
commit to user
Tabel 4.87 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Kalimantan Timur
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,
Tahun 2004-2009 ... 127
Tabel 4.88 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Sulawesi Utara Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 128
Tabel 4.89 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Sulawesi Tengah
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,
Tahun 2004-2009 ... 129
Tabel 4.90 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Sulawesi Selatan
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,
Tahun 2004-2009 ... 130
Tabel 4.91 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Sulawesi Tenggara
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,
Tahun 2004-2009 ... 131
Tabel 4.92 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Gorontalo Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 132
Tabel 4.93 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Sulawesi Barat Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 133
Tabel 4.94 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Nusa Tenggara Barat
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,
Tahun 2004-2009 ... 134
Tabel 4.95 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Nusa Tenggara
Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan
Usaha, Tahun 2004-2009 ... 135
Tabel 4.96 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Maluku Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
commit to user
xviii
Tabel 4.97 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Maluku Utara Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 137
Tabel 4.98 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Papua Barat Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 138
Tabel 4.99 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Papua Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2004-2009 ... 139
Tabel 4.100 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan
Usaha, Tahun 2004-2009 ...
...
141 ...
Tabel 4.101 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 142
Tabel 4.102 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 144
Tabel 4.103 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan
Usaha, Tahun 2004-2009 ... 145
Tabel 4.104 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Jambi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan
Usaha, Tahun 2004-2009 ... 147
Tabel 4.105 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 148
Tabel 4.106 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Begkulu Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan
commit to user
Tabel 4.107 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 151
Tabel 4.108 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 153
Tabel 4.109 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 154
Tabel 4.110 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
DKI Jakarta Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 156
Tabel 4.111 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 157
Tabel 4.112 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 159
Tabel 4.113 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi DI
Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 160
Tabel 4.114 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 161
Tabel 4.115 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Banten Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan
Usaha, Tahun 2004-2009 ... 163
Tabel 4.116 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Bali Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan
commit to user
xx
Tabel 4.117 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 166
Tabel 4.118 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Kalimantan Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 167
Tabel 4.119 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 169
Tabel 4.120 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 171
Tabel 4.121 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Sulawesi Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 172
Tabel 4.122 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Sulawesi Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 174
Tabel 4.123 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 175
Tabel 4.124 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Sulawesi Tenggara Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 177
Tabel 4.125 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Gorontalo Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 178
Tabel 4.126 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Sulawesi Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
commit to user
Tabel 4.127 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Nusa Tenggara Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 181
Tabel 4.128 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 183
Tabel 4.129 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Maluku Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan
Usaha, Tahun 2004-2009 ... 184
Tabel 4.130 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Maluku Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 186
Tabel 4.131 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Papua Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 187
Tabel 4.132 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi
Papua Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan
commit to user
xxii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian ...
28
Gambar 4.1 Rata-rata Pertumbuhan PDRB Provinsi di Indonesia
commit to user
ANALISIS STRUKTUR EKONOMI PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2004 - 2009
DIMAS ARYO SUGANDI
F 0108052
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah: a) menganalisis struktur ekonomi provinsi di Indonesia berdasarkan analisis Kontribusi sektoral dan Shift Share (SS) tahun 2004 – 2009, dan b) menganalisis kondisi ekonomi provinsi di Indonesia berdasarkan pendekatan Tipologi Klassen dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) tahun 2004 – 2009. Data yang digunakan adalah PDRB provinsi dan PDB Indonesia pada tahun 2004 – 2009.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur perekonomian Provinsi di Indonesia cenderung mengarah ke sektor sekunder (yaitu sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor konstruksi) dan sektor tersier (yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa). Berdasarkan temuan-temuan tersebut dapat direkomendasikan bahwa Pemerintah Daerah perlu memacu pertumbuhan perekonomian pada sektor sekunder dan tersier dengan cara peningkatan output, peningkatan pendapatan dan lapangan kerja serta dampaknya terhadap sektor-sektor lain.
Kata-kata kunci : Struktur ekonomi provinsi di Indonesia, Shift Share (SS), Klassen
commit to user
1 BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan
nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah sebagaimana di
jelaskan dalam UU No. 34 tahun 2004, penyelenggaraan Otonomi Daerah
dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada
daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan
dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan
Daerah maupun pembangunan antardaerah.
Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan ekonomi berhubungan
erat dengan pola perkembangan, jenis ekonomi dan perubahan peranan
berbagai kegiatan ekonomi. Berkaitan hal tersebut, maka analisis pembangunan
ekonomi daerah perlu dilakukan secara lebih konperhensif dengan melibatkan
berbagai faktor baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro.
Keberhasilan pembangunan dalam suatu daerah terkait dengan
keadaan sumber daya yang dimilikinya, baik sumber daya alam maupun
sumber daya manusia. Keunggulan akan sumber daya yang dimilikinya akan
membuat suatu daerah lebih berkembang.
Keunggulan ekonomi daerah dapat diamati berdasarkan sektor - sektor
ekonomi yang dikembangkan oleh daerah tersebut. Sektor – sektor ekonomi
yang ada di Indonesia adalah :
commit to user
2. Sektor pertambangan dan penggalian
3. Sektor industri pengolahan
4. Sektor listrik, gas dan air bersih
5. Sektor bangunan
6. Sektor perdagangan, hotel dan restoran
7. Sektor pengangkutan dan komunikasi
8. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
commit to user
Tabel 1.1
Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2004 - 2009 (Miliar Rupiah)
Nilai Pertumbuhan
1. Pertanian 258,335 267,675 277,255 287,579 299,245 313,966 284,009 4%
2. Pertambangan & Penggalian 150,234 156,921 156,341 157,313 159,724 164,889 157,570 2%
3. Industri Pengolahan 412,005 431,631 452,027 473,468 512,569 517,465 466,528 5%
4. Listrik, Gas & Air Bersih 18,269 19,475 19,857 21,270 21,282 22,842 20,499 5%
5. Konstruksi 84,022 89,899 96,364 104,017 113,051 120,828 101,364 8%
6. Perdagangan, Hotel & Restoran 305,159 326,320 350,711 377,372 397,111 422,098 363,128 7%
7. Pengangkutan & Komunikasi 95,719 103,713 113,827 125,627 139,738 154,871 122,249 10%
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan 138,988 145,979 153,266 163,627 174,581 184,033 160,079 6%
9. Jasa-jasa 141,253 148,617 158,304 168,452 182,244 193,327 165,366 6%
Total 1,603,984 1,690,229 1,777,950 1,878,725 1,999,545 2,094,320 1,840,792 5,75% 2009 Rata-rata Lapangan Usaha
2004 2005 2006 2007 2008
Sumber : BPS (diolah)
Tabel 1.1 menjelaskan perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB)
atas dasar harga konstan 2000 tahun 2004-2009 sebesar Rp 1,840,8 triliun. Nilai
sektor tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan sebesara Rp 466,528
miliar, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp 363,128
miliar, sektor pertanian sebesar Rp 284,009 miliar, sektor jasa-jasa sebesar Rp
165,366 miliar, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan sebesar Rp
160,079 miliar, sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 157,570
miliar, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp 122,249 miliar, sektor
konstruksi sebesar Rp 101,364 miliar dan yang paling rendah yaitu sektor
sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 20,499 miliar. Pertumbuhan tertinggi
terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 10%,
diikuti oleh sektor konstruksi 8%, sektor perdagangan, hotel dan restoran 7%,
commit to user
listrik, gas dan air bersih 5%, sektor pertanian 4%, dan yang paling rendah
adalah sektor pertambangan dan penggalian 2%.
Sehubungan dengan keinginan untuk mewujudkan pembangunan
seperti apa yang diharapkan, ada dua kondisi yang perlu diperhatikan karena
dapat berpengaruh terhadap proses perencanaan pembangunan daerah, yaitu:
(1) tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri
yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan
perekonomiannya; (2) kenyataannya bahwa perekonoiam daerah dalam suatu
negara dipengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda-beda, misalkan beberapa
daerah mengalami pertumbuhan pada sektor industrinya sedangkan daerah lain
mengalami penurunan. Inilah yang menjelaskan perbedaan perspektif
masyarakat daerah mengenai arah dan makna pembangunan daerah. (Kuncoro,
commit to user
Tabel 1.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi, 2004 - 2009 (Miliar Rupiah)
Nilai Pertumbuhan
1 Aceh 40,374 36,287 36,853 35,983 34,097 32,220 35,970 -4.33%
2 Sumatera Utara 83,328 87,897 93,347 99,792 106,172 111,559 97,016 6.01%
3 Sumatera Barat 27,578 29,159 30,949 32,912 35,176 36,683 32,077 5.88%
4 Riau 75,216 79,287 83,370 86,213 91,085 93,786 84,827 4.52%
5 Jambi 11,953 12,619 13,363 14,275 15,297 16,272 13,964 6.36%
6 Sumatera Selatan 47,344 49,633 52,214 55,262 58,065 60,452 53,829 5.01%
7 Bengkulu 5,896 6,239 6,610 7,037 7,444 7,923 6,859 6.09%
8 Lampung 28,262 29,397 30,86 32,694 34,443 36,221 31,980 5.09%
9 Kepulauan Bangka Belitung 8,414 8,707 9,053 9,464 9,899 10,266 9,301 4.06%
10 Kepulauan Riau 28,509 30,381 32,441 34,713 37,014 38,318 33,563 6.10%
Sumatera 356,878 369,611 389,067 408,349 428,697 443,704 399,385 4.45%
11 DKI Jakarta 278,524 295,270 312,826 332,971 353,723 371,469 324,131 5.93%
12 Jawa Barat 230,003 242,883 257,499 274,180 291,205 303,405 266,530 5.70%
13 Jawa Tengah 135,789 143,051 150,682 159,110 168,034 176,673 155,557 5.41%
14 DI. Yogyakarta 16,146 16,910 17,535 18,291 19,212 20,064 18,027 4.44%
15 Jawa Timur 242,228 256,442 271,249 287,814 305,538 320,861 280,689 5.78%
16 Banten 54,880 58,106 61,341 65,046 79,699 83,440 67,086 8.94%
Jawa 957,573 1,012,666 1,071,135 1,137,414 1,217,414 1,275,913 1,112,020 5.91%
17 Bali 19,963 21,072 22,184 23,497 25,910 27,290 23,320 6.47%
18 Kalimantan Barat 22,483 23,538 24,768 26,260 27,438 28,754 25,541 5.05%
19 Kalimantan Tengah 13,253 14,034 14,853 15,754 16,726 17,647 15,378 5.89%
20 Kalimantan Selatan 22,171 23,292 24,452 25,922 27,593 29,051 25,414 5.56%
21 Kalimantan Timur 91,050 93,938 96,612 98,386, 103,206 105,368 98,094 2.97%
Kalimantan 148,957 154,803 160,687 166,323 174,965, 180,822 164,427 3.96%
22 Sulawesi Utara 12,149 12,744 13,473 14,344 15,902 17,149 14,294 7.16%
23 Sulawesi Tengah 10,925 11,752 12,671 13,683 15,047 16,177 13,376 8.17%
24 Sulawesi Selatan 34,345 36,421 38,867 41,332 44,549 47,326 40,474 6.62%
25 Sulawesi Tenggara 7,480 8,026 8,643 9,331 10,506 11,301 9,215 8.62%
26 Gorontalo 1,891 2,027 2,175 2,339 2,520 2,710 2,278 7.46%
27 Sulawesi Barat 2,922 3,120 3,321 3,567 3,998 4,239, 3,528 7.75%
Sulawesi 69,714 74,093 79,152 84,599 92,524 98,904 83,165 7.25%
28 Nusa Tenggara Barat 14,928 15,183 15,603 16,369 16,831 18,869 16,298 4.86%
29 Nusa Tenggara Timur 9,537 9,867 10,368 10,902 11,429 11,920 10,671 4.56%
30 Maluku 3,101 3,259 3,440 3,633 3,787 3,993 3,536 5.18%
31 Maluku Utara 2,128 2,236 2,359 2,501 2,651 2,811 2,448 5.73%
32 Papua Barat 4,969 5,307 5,548 5,934 6,399 6,848 5,835 6.63%
33 Papua 16,282 22,209 18,402 19,200 18,931 23,237 19,711 8.99%
Nusa Tenggara, Maluku & Papua 50,947 58,063 55,722 58,540 60,031 67,679 58,498 6.06% Jumlah 33 Provinsi 1,603,984 1,690,229 1,777,950 1,878,725 1,999,545 2,094,320 1,840,814 5.75%
Rata-rata Provinsi 2004 2005 2006 2007 2008 2009
commit to user
Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa perekonomian
Indonesia tahun 2004-2009 mengalami rata-rata pertumbuhan PDRB sebesar
5,75%. Pertumbuhan ekonomi setiap wilayah berada di bawah rata-rata
nasional dengan disparitas antar wilayah yang cukup tajam. Pertumbuhan
Provinsi Aceh -4,33%, Sumatera Utara 6,01%, Sumatera Barat 5,88%, Riau
4,52%, Jambi 6,36%, Sumsel 5,01%, Bengkulu 6,09%, Lampung 5,09%, Kep.
Bangka Belitung 4,06%, Kepulauan Riau 6,10%, DKI Jakarta 5,93%, Jawa
Barat 5,70%, Jawa Tengah 5,41%, DI Yogyakarta 4,44%, Jawa Timur 5,78%,
Banten 8,94%, Bali 6,47%, Kalimantan Barat 5,05%, Kalimantan Tengah
5,89%, Kalimantan Selatan 5,56%, Kalimantan Timur 2,97%, Sulawesi Utara
7,16%, Sulawesi Tengah 8,17%, Sulawesi Selatan 6,62%, Sulawesi Tenggara
8,62%, Gorontalo 7,46%, Sulawesi Barat 7,75%, Nusa Tenggara Barat 4,86%,
Nusa Tenggara Timur 4,56%, Maluku 5,18%, Maluku Utara 5,73%, Papua
Barat 6,63% dan terakhhir Papua 8,99%.
Perkembangan ekonomi daerah provinsi, sebagaimana dijelaskan pada
Tabel 1.2 diatas menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kemenarikan ini didasarkan
pada variasi perkembangan PDRB setiap tahunnya. Dengan demikian judul
penelitian ini adalah Analisis Struktur Ekonomi Provinsi Di Indonesia Tahun
commit to user
B.Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, perumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana struktur ekonomi provinsi di Indonesia berdasarkan analisis
Kontribusi Sektoral dan Shift Share (SS) tahun 2004 – 2009?
2. Bagaimana kondisi ekonomi provinsi di Indonesia berdasarkan
pendekatan Tipologi Klassen dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP)
tahun 2004 – 2009 ?
C. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk menganalisis struktur ekonomi provinsi di Indonesia berdasarkan
analisis Kontribusi Sektoral dan Shift Share (SS) tahun 2004 – 2009.
2. Untuk menganalisis kondisi ekonomi provinsi di Indonesia berdasarkan
pendekatan Tipologi Klassen dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP)
tahun 2004 – 2009.
D. Manfaat penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Sebagai salah satu penjelasan dan pendalaman teori/ pendekatan
ekonomi daerah.
b. Sebagai wacana dan sumber informasi bagi penelitian ekonomi.
2. Manfaat Praktisi
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perumusan/ perencanaan
commit to user
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A.Landasan Teori
1. Perubahan Struktural
Perubahan struktural menitikberatkan pada mekanisme transformasi
ekonomi yang dialami oleh negara sedang berkembang yang semula lebih
bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke
struktur perekonomian yang lebih modern dan sangat di dominasi oleh sektor
industri dan jasa (Todaro, 1999).
2. Perencanaan Ekonomi
(Lincolin, 1999) menyebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses
yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan
dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun
secara sistematis. Pelaksanaan perancangan pembuatan perencanaan itu pada
dasarnya adalah mengambil suatu kebijaksanaan dengan mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut :
a. Perencanaan berarti memilih berbagai alternatif yang terbaik dari sejumlah
alternatif yang ada.
b. Perencanaan berarti pula alikasi sumber daya yang tersedia baik.
c. Sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
d. Perencanaan mengandung arti rumusan yang sistematis yang didasarkan
pada kepentingan masyarakat banyak.
commit to user
Menurut Jhingan (2003) perumusan dan kunci keberhasilan suatu
perencanaan biasanya memerlukan hal-hal sebagai berikut :
a. Prasyarat pertama bagi suatu perencanaan adalah pembentukan suatu komisi
perencanaan yang harus diorganisir dengan cara tepat.
b. Perencanaan yang baik membutuhkan adanya analisis yang menyeluruh
tentang potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara beserta segala
kekurangannya. Oleh karena itu, pembentukan suatu kantor jaringan
statistik dari pusat hingga daerah yang bertugas mengumpulkan informasi
dan data-data statistik menjadi suatu kebutuhan utama.
c. Penetapan berbagai sarana dan tujuan yang ingin dicapai hendaknya realistis
dan disesuaikan dengan kondisi di negara tersebut.
d. Penetapan sasaran dan prioritas untuk pencapaian suatu tujuan perencanaan
dibuat secara makro dan sektoral.
e. Dalam perencanaan ditetapkan adanya pembiayaan oleh pemerintah sebagai
dasar sumber daya yang tersedia.
f. Suatu perencanaan hendaknya mampu menjamin keseimbangan
perekonomian.
g. Administrasi yang baik, efisien, dan tidak korup adalah syarat mutlak
keberhasilan suatu perencanaan.
h. Pemerintah harus menetapkan kebijakan pembangunan yang tepat demi
berhasilnya rencana pembangunan dan menghindari kesulitan yang mungkin
commit to user
i. Setiap usaha harus dibuat berdampak ekonomis dalam administrasi,
khususnya dalam pengembangan bagian-bagian departemen dan
pemerintahan.
j. Administrasi harus bersih dan efisien memerlukan dasar pendidikan yang
kuat, perencanaan yang berhasil harus memperhatikan standart moral dan
etika masyarakat.
k. Dukungan masyarakat merupakan faktor penting bagi keberhasilan suatu
perencanaan didalam suatu negara yang demokratis, tanpa dukungan
masyarakat tak ada perencanaan yang dapat berhasil.
3. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi sering diartikan sama dengan pembangunan
ekonomi oleh pakar ekonomi, yaitu sebagai kenaikan PDB/PNB saja. Akan
tetapi pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa
memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat
pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau
tidak (Lincolin, 1999).
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam
melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu
negara. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan
masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.
Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil
commit to user
tahun sebelumnya (pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar
dari pendapatan masyarakat pada tahun sebelumnya).
4. Pembangunan Ekonomi
Pembangunan diartikan sebagai suatu proses perbaikan yang dinamis
dan terus-menerus atas suatu masyarakat atau sistem sosial yang membawa
perubahan dan peningkatan keadaan dari yang mempunyai corak sederhana ke
tingkatan yang lebih maju. Sementara itu, pembangunan ekonomi didefinisikan
sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita
penduduk suatu negara dalam jangka panjang disertai oleh perbaikan
kelembagaan (Lincolin, 1999:6).
Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf
hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan
riil per kapita (Irawan dan Suparmoko, 1993 : 1994). Menurut Todaro
(2000:23), proses pembangunan harus memiliki 3 (tiga) tujuan inti, yaitu :
a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang
kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan, kesehatan, perlindungan
keamanan).
b.Peningkatan standar kehidupan yang tidak hanya berupa peningkatan
pendapatan namun juga meliputi penambahan penyediaan lapangan
pekerjaan, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas
nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, di mana semuanya itu tidak hanya
untuk memperbaiki kesejahteraan materiil melainkan juga untuk
commit to user
c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi tiap individu dan bangsa
secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari sikap
ketergantungan.
Permasalahan yang timbul akibat kesalahan upaya pembangunan yang
dilakukan adalah (Widodo, 2006 :7) :
a. Kemiskinan
Permasalahan kemiskinan dalam pembangunan sangat sering
dijumpai di hampir seluruh negara di dunia. Permasalahan yang terjadi pun
memiliki karakteristik yang hampir sama di mana kemiskinan yang tinggi
terjadi di sebuah wilayah pedesaan atau sebuah wilayah yang memiliki
tingkat kepadatan yang sangat tinggi. Secara sederhana kemiskinan
(absolut) dapat didefenisikan sebagai ketidakmampuan sejumlah penduduk
untuk hidup di atas garis kemiskinan atau batas kemiskinan yang ditetapkan
berdasar kategori tertentu.
Untuk menggambarkan tingkat kemiskinan yang terjadi di sebuah
negara atau wilayah tertentu, para ekonom sering menggunakan indikator
tingkat kemiskinan. Indikator ini mengukur total pendapatan yang
dibutuhkan oleh penduduk miskin agar dapat hidup di atas garis kemiskinan.
b. Pemerataan
Permasalahan kedua yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangun-
an adalah tidak meratanya distribusi pendapatan yang diterima oleh
penduduk. Ketimpangan ini terjadi karena rata-rata pendapatan per kapita
masyarakat di daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata
commit to user
Ketimpangan pendapatan yang terjadi di daerah pedesaan jauh lebih rendah
bila dibandingkan dengan ketimpangan yang terjadi dalam distribusi
pendapatan di kawasan perkotaan. Perbedaan kedalaman ketimpangan
antara yang terjadi di daerah pedesaan dengan ketimpangan yang terjadi di
kawasan perkotaan disebabkan karena variasi tipe pekerjaan yang terdapat
di kedua wilayah tersebut.
c. Pertumbuhan
Proses pembangunan yang dilakukan di setiap negara tidak dapat
dilepaskan dari permasalahan kemiskinan dan ketimpangan distribusi
pendapatan. Profesor Kuznets mengajukan sebuah teori mengenai
perkembangan ketimpangan distribusi pendapatan dimana ketimpangan
yang dialami oleh negara yang sedang membangun akan tinggi ketika
pembangunan sedang berada dalam tahap awal pembangunan. Tingkat
ketimpangan ini akan terus naik seiring dengan pembangunan yang
dilakukan hingga pada titik tertentu tingkat ketimpangan ini akan turun.
Dalam pembahasan mengenai teori pembangunan, khususnya
pembangunan ekonomi terdapat teori-teori pembangunan yang ada yaitu
Teori pertumbuhan linear dan Teori pertumbuhan struktural (Kuncoro,
2000):
1. Teori Pertumbuhan Linear
a. Teori Pertumbuhan Adam Smith
Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan menjadi 5 tahap
yang berurutan yaitu dimulai dari masa perburuan, masa beternak,
commit to user
perindustrian. Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari
masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam
prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan
adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Adam Smith
memandang pekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi.
Menurut teori ini, akumulasi modal akan menentukan cepat atau
lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara.
Proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki
hubungan keterkaitan satu sama lainnya. Timbulnya peningkatan
kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi
pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan
spesialisasi dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong
pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat. Proses pertumbuhan
ekonomi sebagai suatu fungsi tujuan pada akhirnya harus tunduk
pada fungsi kendala yaitu keterbatasan sumber daya ekonomi
(Kuncoro, 2000 : 38-41).
b. Teori Pembangunan Karl Marx
Karl max dalam bukunya Das Kapital membagi evolusi
perkembangan masyarakat menjadi tiga yaitu dimulai dari feodalisme,
kapitalisme dan kemudian yang terakhir adalah sosialisme. Evolusi
perkembangan masyarakat akan sejalan dengan proses pembangunan
yang dilaksanakan. Masyarakat feodalisme mencerminkan kondisi
dimana perekonomian yang ada masih bersifat tradisional. Dalam
commit to user
posisi tawar-menawar relatif tinggi terhadap pelaku ekonomi lain.
Perkembangan teknologi yang ada menyebabkan terjadinya
pergeseran di sektor ekonomi, dimana masyarakat yang semula
agraris-feodal kemudian beralih menjadi masyarakat industri yang
kapitalis.
Pada masa kapitalis ini para pengusaha merupakan pihak yang
memiliki tingkat posisi tawar menawar tertinggi terhadap pihak
lain khususnya kaum buruh. Artinya kaum buruh tidak memiliki
posisi tawar-menawar sama sekali terhadap majikannya yang
merupakan kaum kapitalis. Eksploitasi terhadap kaum buruh dan
peningkatan pengangguran yang terjadi akibat substitusi tenaga
manusia dengan input modal yang padat kapital pada akhirnya akan
menyebabkan revolusi sosial yang dilakukan kaum buruh. Fase ini
merupakan tonggak baru bagi munculnya suatu tatanan sosial
alternatif di samping tata masyarakat kapitalis, yaitu tata masyarakat
sosialis (Kuncoro, 2000 : 41-42)
c. Teori Pertumbuhan Rostow
Rostow membagi proses pembangunan ekonomi suatu negara
menjadi lima tahap yaitu :
1) Perekonomian Tradisional
Perekonomian pada masyarakat tradisional cenderung bersifat
subsisten. Pemanfaatan teknologi dalam sistem produksi masih
sangat terbatas. Perekonomian semacam ini sektor pertanian
commit to user
2) Pra-kondisi Tinggal Landas
Tahap kedua dari proses pertumbuhan Rostow ini pada dasarnya
merupakan proses transisi dari masyarakat agraris menuju
masyarakat industri. Sektor industri mulai berkembang di samping
sektor pertanian yang masih memegang peranan penting dalam
perekonomian (Kuncoro, 2000 :45)
3) Tinggal Landas
Tinggal landas didefinisikan sebagai tiga kondisi yang saling
berkaitan sebagai berikut (Kuncoro, 2000 :46):
a) Kenaikan laju investasi produktif antara 5-10 persen dari
pendapatan nasional.
b) Perkembangan salah satu atau beberapa sektor manufaktur
penting dengan laju pertumbuhan tinggi.
c) Hadirnya secara cepat kerangka politik, sosial dan institusional
yang menimbulkan hasrat ekspansi di sektor modern dan
dampak eksternalnya akan memberikan daya dorong pada
pertumbuhan ekonomi.
4. Tahap Menuju Kedewasaan
Tahap ini ditandai dengan penerapan secara efektif teknologi
modern terhadap sumber daya yang dimiliki. Tahapan ini
merupakan tahapan jangka panjang dimana produksi dilakukan
secara swadaya. Tahapan ini juga ditandai denga munculnya
beberapa sektor penting yang baru (Kuncoro, 2000 :47)
commit to user
Tahap konsumsi masa tinggi merupakan akhir dari tahapan
pembangunan yang dikemukakan oleh Rostow. Pada tahap ini akan
ditandai dengan terjadinya migrasi besar-besaran dari masyarakat
pusat perkotaan ke pinggiran kota, akibat pembangunan pusat kota
sebagai sentral bagi tempat bekerja. Pada fase ini terjadi perubahan
orientasi dari pendekatan penawaran menuju pendekatan
permintaan dalam sistem produksi yang dianut. Sementara itu
terjadi pula pergeseran perilaku ekonomi yang semula lebih banyak
menitikberatkan pada sisi produksi kini beralih ke sisi konsumsi
(Kuncoro, 2000 :47)
2. Teori Perubahan Struktural
a. Teori Pembangunan Arthur Lewis
Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas
proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa
yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi diantara
diantara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola
investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan
upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan
berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Mengawali
teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara
pada dasarnya akan terbagi menjadi dua yaitu (Kuncoro, 2000 : 51-52)
commit to user
1) Perekonomian Tradisional
Dalam teorinya Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan,
dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga
kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama
perekonomian yang diasumsikan berada pada perekonomian
tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada
kondisi subsisten pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk
marginal dari tenaga kerja yang bernilai nol.
2) Perekonomian Industri
Perkotaan tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat
penampungan tenaga kerja yang ditransfer dari sektor subsisten.
Model ini diarahkan pada terjadinya proses pengalihan tenaga
kerja, pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga
kerja di sektor modern. Keadaan ini ditentukan oleh peningkatan
investasi dan akumulasi modal secara kesuluruhan di sektor
modern. Peningkatan investasi terjadi karena adanya kelebihan
keuntungan sektor modern dari selisih upah dengan asumsi bahwa
“para kapitalis” bersedia menanamkan kembali seluruh
keuntung-an. Rangkaian proses pertumbuhan berkesinambungan atas sektor
modern dan perluasan kesempatan kerja diatas diasumsikan akan
terus berlangsung sampai dengan semua surplus tenaga kerja
pedesaan diserap habis oleh sektor industri.
commit to user
Teori ini memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan
proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari
perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami
transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri
sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian Hollis
Chenery tentang transformasi struktur perekonomian suatu negara
akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian
menuju ke sektor industri. Chenery menunjukkan bahwa tingkat
pertumbuhan ekonomi dan peranan suatu sektor dalam
menciptakan produksi nasional tergantung pada tingkat
pendapatan dan jumlah penduduk negara tersebut. Makin besar
pertumbuhan pendapatan suatu daerah dibanding dengan
pertumbuhan penduduk daerah tersebut maka dikatakan bahwa
pertumbuhan ekonomi meningkat (Kuncoro, 2000 : 57-58).
5. Pembangunan Ekonomi Daerah
Menurut Arsyad (1999:108), Pembangunan ekonomi daerah adalah
suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola
sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan
antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu
lapangan kerja dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi
(pertumbuhan ekonomi) di dalam wilayah tersebut.
Tujuan dari pembangunan daerah secara umum adalah :
1. Mendorong terciptanya pekerjaan yang berkualitas bagi penduduk,
commit to user
lebih berkualitas, sehingga mampu berperan dalam aktivitas yang lebih
produktif dibanding dengan yang sudah dilakukan.
2. Berusaha menciptakan stabilitas ekonomi dengan cara menyiapkan sarana
prasarana yang dibutuhkan bagi pengembangan aktivitas ekonomi daerah
yang meliputi: penyediaan lahan, tenaga kerja, pembiayaan dan bantuan
teknis/ manajemen untuk mencegah timbulnya ketimpangan-ketimpangan
yang dapat menghambat pembangunan.
3. Mengusahakan terciptanya basis diversifikasi aktivitas ekonomi yang luas,
yang diharapkan dapat memperkecil resiko fluktuasi bisnis. Dengan adanya
basis ekonomi yang kuat maka resiko fluktuasi ekonomi regional/wilayah
dapat diperkecil.
4. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam
barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti sandang, pangan, papan,
kesehatan dan perlindungan keamanan.
5. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan
pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja,
perbaikan kualitas pendidikan, serta peningktan perhatian atas
nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang semuanya itu tidak hanya untuk
memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan jati
diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
6. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta
bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari
commit to user
orang atau bangsa lain, namun terhadap setiap kekuatan yang berpotensi
merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka (Todaro, 2000:23-24).
Pembangunan ekonomi apabila dilihat dari sisi kegiatan ekonomi
dan dari sudut penyebarannya adalah (Lincolin, 1999:107-108):
a. Daerah Homogen, yaitu daerah yang dianggap sebagai ruang di
mana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam pelosok ruang terdapat
sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari
segi pendapatan per kapita, sosial-budayanya, geografinya dan
sebagainya.
b. Daerah Nodal, yaitu daerah yang dianggap sebagai suatu ekonomi
ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi
sehingga perbatasan daerah tersebut ditentukan oleh tempat-tempat di
manapengaruh dari satu atau beberapa pusat kegiatan-kegiatan
ekonomi digantikan dengan pengaruh dari pusat lainnya.
c. Daerah Perencanaan, yaitu daerah administrasi di mana dalam daerah
yang bersangkutan juga merupakan suatu ekonomi ruang.
d. Yang berada dibawah suatu daerah administrasi tertentu, seperti propinsi,
kabupaten, kota, dan sebagainya. Jadi pengertian daerah disini lebih
ditunjukkan pada pembagian daerah administrasi suatu wilayah.
Ada beberapa teori yang dapat membantu untuk mengetahui arti
penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hakekatnya inti dari teori
tersebut berkisar pada dua hal, yaitu: metode dalam menganalisis
commit to user
yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu (Lincolin,
1999).
a. Teori Ekonomi Neo-Klasik
Teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan
ekonomi daerah, yaitu keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas
faktor-faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai
keseimbangan alaimiahnya jika modal mengalir tanpa retriksi
(pembatasan). Oleh karena itu, daerah akan mengalir dari daerah
yang berupah tinggi menuju daerah yang berupah rendah (Lincolin,
1999:116).
b. Teori Basis Ekonomi
Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama
pertumbuhan ekonomi suatu daerah mempunyai hubungan dengan
permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan
industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja
dan penciptaan lapangan kerja (Lincolin, 1999:116).
Strategi pembangunan daerah yang muncul yang didasarkan
pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan kepada
dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun
internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan
hambatan/batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi
ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut. Inti dari teori
basis ekonomi ini adalah karena industri basis menghasilkan barang
commit to user
bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan
pendapatan bagi daerah tersebut (Lincolin, 1999:141).
c. Teori Lokasi
Para ekonom regional sering mengatakan bahwa faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan daerah yaitu lokasi. Perusahaan cenderung
akan meminimumkan biayanya dengan cara memilih lokasi yang
memaksimumkan peluangnya mendekati pasar. Model pengembangan
industri kuno menyatakan bahwa lokasi terbaik adalah biaya
termurah antara bahan baku dengan pasar. (Lincolin, 1999:116-117).
Dari keterangan di atas maka dapat diketahui bahwa lokasi sangat
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pemilihan lokasi yang tepat
mendekati pasar dapat meminimumkan biaya dan memaksimumkan
peluang.
d. Teori Tempat Sentral
Tempat sentral merupakan suatu pemukiman yang menyediakan
jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Teori ini dapat
diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik itu di daerah
perkotaan maupun di daerah perdesaan (Lincolin, 1999:117).
e. Teori Kausasi Kumulatif
Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk
menunjukkan konsep dasar teori ini. Kekuatan-kekuatan pasar
cenderung memperparah kesenjangan antara daerah-daerah tersebut.
Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif
commit to user
f. Model Daya Tarik
Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi
yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang
mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki
posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan
insentif (Lincolin, 1999:118).
6. Produk Domestik Bruto (PDB)
PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang
diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya
per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan
pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut.
Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa
memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor
produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul
faktor produksi yang digunakan.PDB Nominal (atau disebut PDB Atas Dasar
Harga Berlaku) merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh
harga. Sedangkan PDB riil (atau disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan)
mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga.
Analisa Mekanisme (kinerja) Ekonomi Nasional berdasar PDB
melalui 3 pendekatan, yaitu :
1. Pendekatan Produksi
Pendekatan produksi diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai
tambah (value added) dari semua sektor produksi. Besarnya nilai produksi
commit to user
berbagai jenis barang dan jasa. diklasifikasikan menjadi sembilan sektor,
terbagi menjadi 3 kelompok besar :
1.Sektor Primer
2.Sektor Sekunder
3.Sektor Tersier
Besarnya ‘value added’ tiap sektor, yi : VAs = OPs – Ips,
sedangkan nilai PDB-nya diperoleh dengan : PDB = VAsp + VAss + Vast
2. Pendekatan Pengeluaran/Pembelanjaan
Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari
unit/komponen-komponen ekonomi, yaitu:
Konsumsi Rumah Tangga (RT)=C
Perusahaan, berupa investasi/pembentukan modal bruto =I
Pengeluaran Pemerintah (konsumsi/belanja pemerintah) =G
Expor – Impor =( X – M )
Dalam Keseimbangan Perekonomian Nasional, di formulasikan
dalam persamaan sbb: PDB = C + I + G + ( X – M)
3. Pendekatan Pendapatan
Diperoleh dengan cara menghitung jumlah balas jasa bruto (blm
dipotong pajak) / hasil dari faktor produksi yang digunakan.
PDB = sewa + upah + bunga + laba
Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap
seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan
laba untuk pengusaha. Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran
commit to user
dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit
dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan
pengeluaran.
7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur dengan
indikator utama yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (BPS,
Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010). Salah satu indikator penting untuk
mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/propinsi dalam suatu
periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga
konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang
dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah, atau merupakan
jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh
unit ekonomi di suatu wilayah.
PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah
barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap
tahunnya. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan
nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada
tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan
untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomis. Sedangkan harga
konstan digunakan untuk mengetahui pertambahan ekonomi dari tahun ke
commit to user
B.Penelitian Terdahulu
Hasil penelitian Lihan dan Yogi (2003) menunjukkan bahwa peranan
sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa di Indonesia sangat
berpengaruh nyata terhadap perkembangan PDB di Indonesia. Hal ini sejalan
dengan pendapat Jung dan Marshall (1985) yang mengemukakan sebagian
besar negara-negara berkembang mendukung bahwa sektor pertanian, industri,
dan jasa akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Penelitian Supomo (1993) tentang Analisis Struktur Perekonomian
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan
teknik perencanaan pembangunan analisis Shift Share. Adapun kesimpulan
dari penelitian tersebut adalah jumlah tenaga kerja di D.I.Y pada tahun 1980
– 1990 bertambah di semua sektor dengan kenaikan absolut tebesar di
sektor industri, disusul dengan sektor perdagangan dan jasa.
Yunariah (2007) melakukan penelitian tentang analisis struktur
ekonomi dan struktur perkotaan di Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota
commit to user
C. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat ditunjukkan oleh gambar
sebagai berikut:
Gambar 2.1 Kerangka pemikiran Penelitian
Analisis dan pembahasan
Kesimpulan
1. Struktur ekonomi dengan pendekatan Kontribusi
Sektoral dan shift share (SS).
2. Kondisi ekonomi dengan pendekatan Tipologi
Klassen dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Struktur Ekonomi