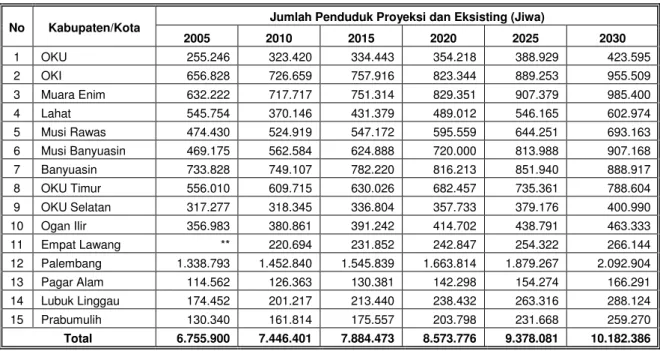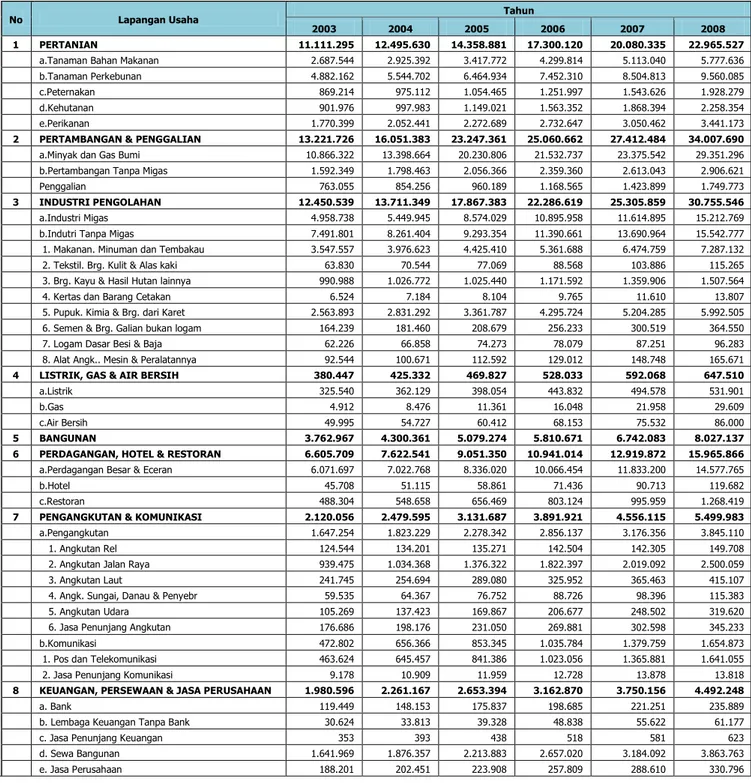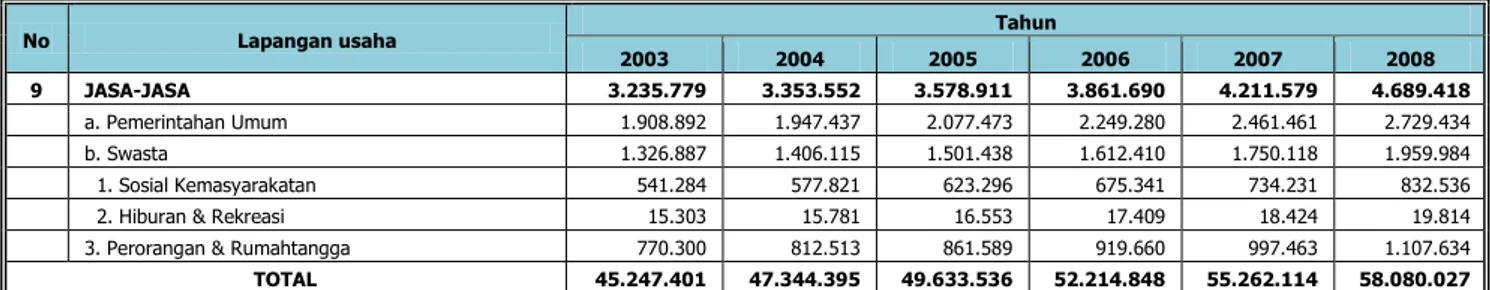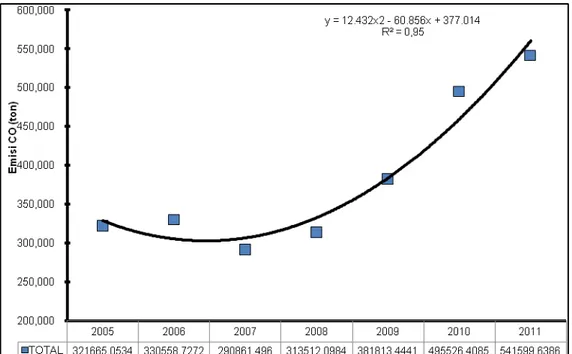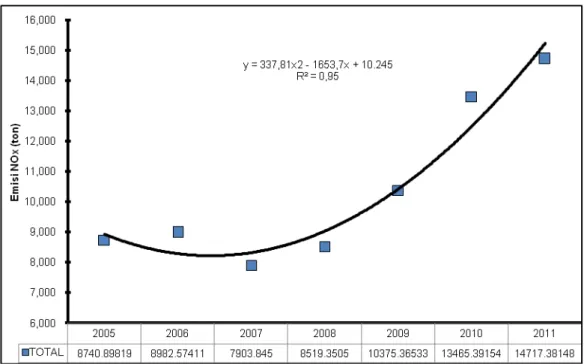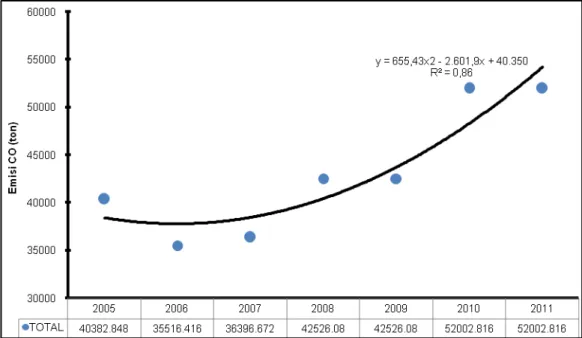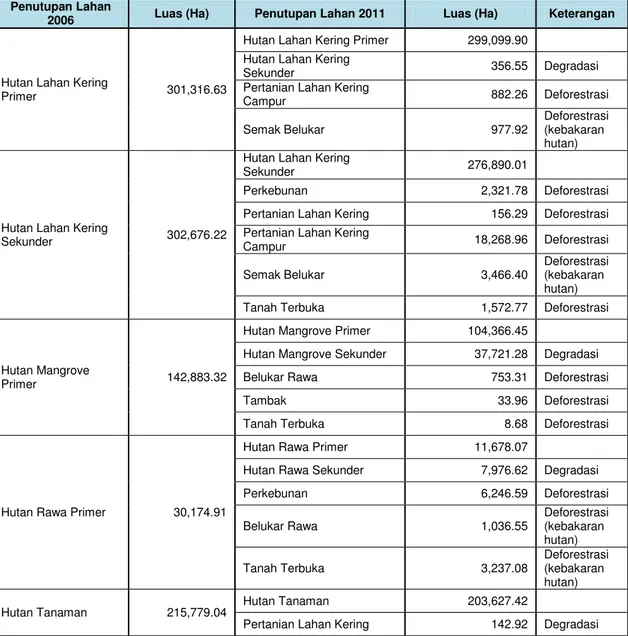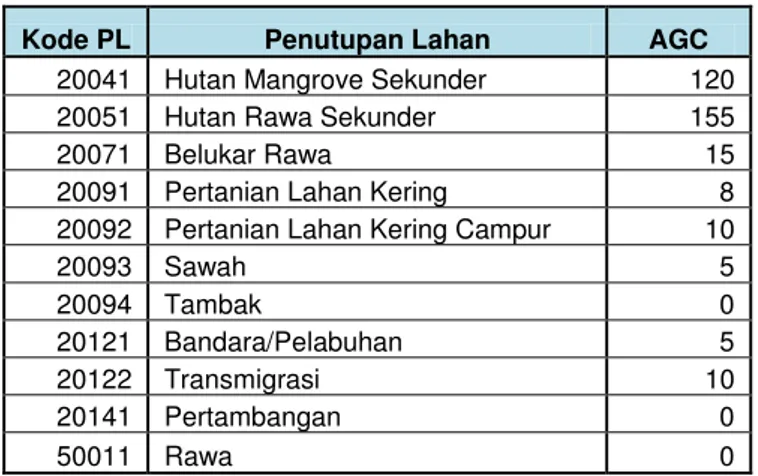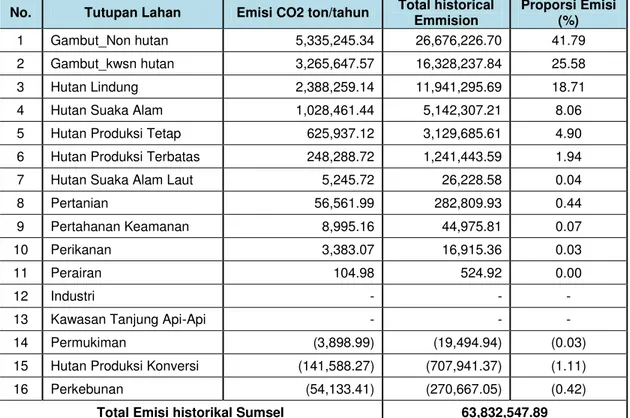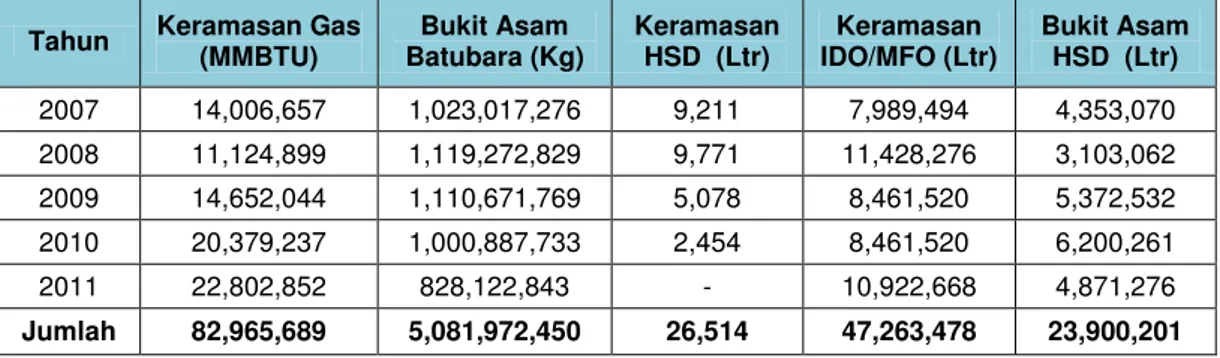Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan i
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dengan upaya sendiri jika dibandingkan dengan garis dasar pada kondisi Bisnis Seperti Biasa (BAU baseline) dan sebesar 41% apabila ada dukungan internasional. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) disusun sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut dan memberikan kerangka kebijakan dan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan dan pelaku usaha dalam pelaksanaanya untuk kurun waktu tahun 2010-2020.
Perpres Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) mengamanatkan kepada provinsi bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) selambat-lambatnya 12 bulan sejak ditetapkannya Perpres RAN-GRK yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Penyusunan RAD-GRK merupakan penjabaran komitmen daerah dalam penurunan emisi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan daerah dan didukung dengan pengalokasian anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan ii
Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun yang berasal dari para Tim Ahli dan seluruh pihak terkait. Terima kasih pula kepada Bappenas dan JICA atas dukungan dana yang diberikan sehingga Rencana Aksi Daerah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga hasil kerja yang baik ini dapat memberikan sumbangsih dan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terkait.
Palembang, 5 Oktober 2012
Kepala Bappeda Sumatera Selatan,
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan iii
Penanggungjawab
: Gubernur Sumatera Selatan
Ketua
: Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
Sekretaris
: Kepala BAPPEDA Provinsi Sumsel
Tim Ahli
Koordinator
: Budhi Setiawan, Ph.D
Anggota
: 1. Sabaruddin, Ph.D (Sektor Pertanian)
2. Febrian Hadinata, ST, MT (Sektor Limbah)
3. Dr. M. Faizal (Sektor Energi)
4. Prof. Dr. Erika Buchary (Sektor Transportasi)
5. Prof. Dr. Hilda Zulkifli (Sektor Industri)
6. Dr. Najib Asmani (Sektor Kehutanan)
Editor
1.
Regina Ariyanti
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan iv
1.5 Kerangka Waktu Penyusunan 3
BAB II PROFIL DAERAH DAN PERMASALAHAN EMISI GRK 4
2.1 Profil dan Karakteristik Daerah 4
2.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi 4
2.1.2 Klimatologi 4
2.2 Program Prioritas Daerah 30
A. Rencana Pembangunan Jagka Panjang Daerah (RPJPD) 30
B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 33
C. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
SKPD) 41
D. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 42
2.3 Permasalahan Emisi GRK 42
2.3.1 Sumber Emisi Sektor Pertanian 43
a. Budidaya Padi 44
b. Pembakaran Limbah Pertanian 47
c. Peternakan 53
2.3.2 Sumber Emisi Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut 63
2.3.3 Sumber Emisi Sektor Energi 70
a. Emisi CO2 dari PLTU 71
b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik PLN 71
c. Emisi CO2 dari Bahan Bakar (Pertamina) 72
d. Emisi CO2 eq dari PLTG Bukit Asam dan PLTD Keramasan 73
e. Emisi GRK dari Pembangkit Listrik PLTG milik PLN 74
f. Emisi GRK dari Pembangkit Listrik PLTG, PLTM milik swasta 76
g. Emisi CO2 dari Kayu Bakar 77
2.3.4 Sumber Emisi Sektor Transportasi 78
1 TIER 1 81
2 TIER 2 82
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan v
1) Penghitungan Emisi CO2 untuk kota Palembang 90
2) Perhitungan Emisi CO2 Sumatera Selatan 91
2.3.5 Sumber Emisi Sektor Industri 96
2.3.6 Sumber Emisi Sektor Sampah/Sampah 100
a. Sampah Domestik 101
b. Limbah Cair Domestik 107
c. Limbah Industri 111
BAB III PEMBAGIAN URUSAN DAN RUANG LINGKUP 116
3.1. Pembagian Urusan 116
3.2. Ruang Lingkup Daerah 121
3.2.1 Sektor Pertanian 121
3.2.2 Sektor kehutanan dan lahan gambut 121
3.2.3 Sektor berbasis energi 121
3.2.4 Sektor Sampah/Limbah 122
BAB IV ANALISIS EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI SUMATERA SELATAN 123
4.1 BAU-Baseline Emisi Gas Rumah Kaca 123
4.1.2 Pertanian 123
a. Budidaya Padi 123
b. Pembakaran Limbah Pertanian 125
c. Peternakan 131
4.1.2 Kehutanan dan Lahan Gambut 135
4.1.3 Energi 135
a. Emisi CO2 dari PLTU 136
b. Emisi CO2 eq dari PLTD milik PLN 136
c. Emisi CO2 eq dari Bahan Bakar 137
d. Emisi CO2 Kayu Bakar 139
e. Total Proyeksi Emisi CO2 di Sektor Energi 140
4.1.4 Transportasi 140
a. Proyeksi Emisi TIER 1 140
b. Proyeksi Emisi TIER 2 141
c. Proyeksi TIER 3 143
4.1.5 Industri 144
4.1.6 Sampah/Limbah 146
a. Sampah Domestik 147
1) Emisi dari Open Dumping: Un-managed Deep dan Un-categorized
152
2) Emisi dari Open Burning 156
3) Emisi dari Aktifitas Pengomposan Sampah
Terolah 157
b. Limbah Cair Domestik dan Industri 158
4.2 Usulan Aksi Mitigasi dan Perkiraan Penurunan Emisi 161
4.2.1 Pertanian 161
a. Budidaya Padi 161
b. Pembakaran Limbah Pertanian 165
c. Peternakan 167
d. Rekapitulasi Emisi Pertanian Hasil Perhitungan GRK 171
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan vi
4.2.3 Energi 179
a. Usulan Aksi Mitigasi 180
4.2.4 Transportasi 181
a. Skenario Penurunan Emisi CO2 Kota Palembang 182
b. Scenario Penurunan Emisi CO2 Sumatera Selatan 183
4.2.5 Industri 187
4.2.6 Sampah/Limbah 191
a. Kelompok Rencana Aksi Mitigasi -1: Program
Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Persampahan
191
b. Kelompok Rencana Aksi Mitigasi -2: Program Minimasi Sampah dengan prinsip 3R
192
c. Kelompok Rencana Aksi Mitigasi -3: Program Peningkatan Sarana-Prasarana Persampahan
197
d. Kelompok Rencana Aksi Mitigasi -4: Program Peningkatan Pengelolaan Gas Sampah
200
e. Kelompok Rencana Aksi Mitigasi -5: Program Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Air Limbah
201
f. Kelompok Rencana Aksi Mitigasi -6: Program Pembangunan prasarana Waste Water Treatment Pemukiman
201
g. Kelompok Rencana Aksi Mitigasi -7: Program Pengelolaan Badan Air
203
h. Kelompok Rencana Aksi Mitigasi -9: Program
Pemberdayaan Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat
203
i. Kelompok Rencana Aksi Mitigasi-10: Program Inventori dan Pengelolaan Limbah Industri
204
j. Kelompok Rencana Aksi Mitigasi -11: Program Monitoring dan Evaluasi
205
k. Kelompok Rencana Aksi Mitigasi -12: Program Non-teknis RAD-GRK Sektor Limbah
205
4.3. Skala Prioritas 207
4.3.1 Pertanian 207
4.3.2 Kehutanan dan Lahan Gambut 212
4.3.3 Energi 215
4.3.4 Transportasi 219
4.3.5 Industri 224
4.3.6 Sampah/Limbah 227
BAB V STRATEGI IMPLEMENTASI RAD-GRK 232
5.1 Pemetaan Kelembagaan dan Pembagian Peran 232
5.1.1 Pertanian 232
5.1.2 Kehutanan dan Lahan Gambut 234
5.1.3 Energi 235
5.1.4 Transportasi 236
5.1.5 Industri 237
5.1.6 Sampah/Limbah 238
5.2 Identifikasi Sumber Pendanaan 241
5.2.1 Pertanian 241
5.2.2 Kehutanan dan Lahan Gambut 245
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan vii
5.2.4 Transportasi 255
5.2.5 Industri 256
5.2.6 Sampah/Limbah 257
5.3 Penyusunan Jadwal Implementasi 260
5.3.1 Pertanian 260
5.3.2 Kehutanan dan Lahan Gambut 261
5.3.3 Energi 263
5.3.4 Transportasi 263
5.3.5 Industri 264
5.3.6 Sampah/Limbah 265
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI 267
6.1. Monitoring 267
6.2. Evaluasi 268
BAB VII PENUTUP 271
7.1 Kesimpulan 271
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan viii DAFTAR TABEL
Tabel II.1 Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004-2010
10
Tabel II.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2030
12
Tabel II.3 Proyeksi Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2030
12
Tabel II.4 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2003-2008
21
Tabel II.5 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2003-2008
22
Tabel II.6 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003-2008 (%)
23
Tabel II.7 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003-2008 (%)
24
Tabel II.8 Kontribusi kelompok Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003-2008 (%)
25
Tabel II.9 Pendapatan Perkapita di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003-2008
25
Tabel II.10 Potensi Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 29
Tabel II.11 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi Industri Besar dan Sedang di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008
29
Tabel II.12 Program Prioritas Pembangunan di RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 35
Tabel II.13 Sebaran keragaman dan luas sawah di Prov Sumatera Selatan (2010) 44
Tabel II.14. Nilai default EF(T) untuk estimasi emisi CH4 asal enteric fermentation
masing-masing jenis ternak di Provinsi Sumatera Selatan
54
Tabel II.15 Nilai default EF(T) untuk estimasi emisi CH4 asal kotoran ternak akibat sistem
pengelolaan kotoran ternak masing-masing jenis ternak di Provinsi Sumatera Selatan
56
Tabel II.16 Nilai default MS(T, S), Nex(T), dan EF3(ST) untuk estimasi emisi langsung N2O asal
kotoran ternak di bawah sistem pengelolaan tertentu masing-masing jenis ternak di Provinsi Sumatera Selatan
61
Tabel II.17 Nilai default FracGasMS asal kotoran ternak di bawah sistem pengelolaan tertentu
masing-masing jenis ternak di Provinsi Sumatera Selatan
61
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan ix
Tabel II.19 Faktor Emisi Karbon Diatas Permukaan Tanah 67
Tabel II.20 Faktor Emisi Karbon dari Lahan Gambut menggunakan model Hooijer, et.al., 2010 yang dimodifikasi
68
Tabel II.21 Emisi GRK pada masing – masing zonasi tutupan lahan 69
Tabel II.22 Emisi CO2 Baseline pada PLTU Provinsi Sumatera Selatan 71
Tabel II.23 Emisi CO2 Baseline pada PLTD Provinsi Sumatera Selatan 71
Tabel II.24 Faktor Emisi Bahan Bakar 72
Tabel II.25 Penjualan BBM di Sumsel (2004-2010) menurut jenis konsumen 73
Tabel II.26 Emisi Co2 berdasarkan Jenis Konsumen 73
Tabel II.27 Jumlah Pemakaian Gas Batu Bara dan Diesel pada Pembangkit Listrik Bukit Asam dan Keramasan
74
Tabel II.28 Emisi CO2 eq Baseline pada Pembangkit Listrik Bukit Asam dan Keramasan. 74
Tabel II.29 Daftar PLTG milik PLN pada Februari 2012 74
Tabel II.30 Emisi CO2 Baseline PLTG Sumatera Selatan 75
Tabel II.31 Emisi CO2 dari Lima Pembangkit PLTG, PLTMG Swasta 77
Tabel II.32 Asumsi Jumlah Pemakain Kayu Bakar dan Emisi CO2 yang dihasilkan 78
Tabel II.33. Penggunaan Energi Transportasi menurut moda, tahun 2004 dan 2025 80
Tabel II.34 Jumlah Kendaraan Terdaftar 82
Tabel II.35 Pemakaian Jumlah BBM Tiap Kendaraan 83
Tabel II.36 Jumlah Pemakaian BBM Menurut Jenis Bahan Bakar 85
Tabel II.37 Jumlah Pemakaian BBM dan EMisi Baseline Menurut Jenis Kendaraan 86
Tabel II.38 Penggunaan BBM tahun 2012 87
Tabel II.39 Perbandingan CO2 (gram) antar moda transportasi 89
Tabel II.40 Emisi CO2 di Wilayah Kota Palembang 91
Tabel II.41 Analisa Emisi CO2 (Gr/Km) Di Ogan Komering Ilir Berdasarkan Perhitungan
Counting Tahun 2011
91
Tabel II.42 Analisa Emisi CO2 ( Gr/Km ) Di Linggau-Jambi Berdasarkan Perhitungan Counting Tahun 2011
92
Tabel II.43 Analisa Emisi CO2 ( Gr/Km ) Di MUBA-Jambi Berdasarkan Perhitungan
Counting Tahun 2011
93
Tabel II.44 Analisa Emisi Co2 (gr/km ) Di Oku Timur Berdasarkan Perhitungan Counting
Tahun 2011
93
Tabel II.45 Analisa Emisi CO2 (Gr/Km) Di Linggau-Curup Berdasarkan Perhitungan
Counting Tahun 2011
94
Tabel II.46 Jumlah industri kecil formal di Sumatera Selatan Tahun 2012 97
Tabel II.47 Jumlah industri kecil non-formal di Sumatera Selatan 97
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan x
propinsi Sumatera Selatan.
Tabel II.49 Kontribusi emisi GRK dari sektor industri di Indonesia 99
Tabel II.50 Data emisi CO2 dari enam industri potensial penghasil emisi di Propinsi
Sumatera Selatan (tahun 2010 dan 2012)
100
Tabel II.51. Komposisi Sampah Domestik Sumsel di TPA 103
Tabel II.52. Dry atter Content Sampah Domestik Sumsel di TPA 104
Tabel II.53. TPA di Wilayah Sumatera Selatan 104
Tabel II.54 Industri CPO di wilayah Sumatera Selatan 113
Tabel II.55 Industri Crum Rubber di wilayah Sumatera Selatan 113
Tabel II.56. Industri (bukan CPO dan Crum Rubber) di wilayah Sumsel 114
Tabel II.57 Rekapitulasi Potensi Emisi GRK Sumsel dan Permasalahannya 114
Tabel II.58. Rekapitulasi Identifikasi Awal Sumber Emisi Sektor Limbah Sumatera Selatan 115
Tabel II.59. Status Emisi GRK Sumsel Sektor Pengelolaan Limbah Domestik pada Tahun 2010
115
Tabel III.1 Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007
116
Tabel III.2.Keterkaitan Bidang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada RAN dengan Pembagian Urusan Pemerintahan
118
Tabel III.3. Pembagian Urusan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari Kelompok
Kerja/SKPD masing – masing sektor pada kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca
di Provinsi Sumatera Selatan
119
Tabel IV.1. Proyek populasi ternak besar di Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun 2020 131
Tabel IV.2. Total emisi GRK asal ternak di Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun 2020 134
Tabel IV.3. Potensi Emisi GRK (BAU Baseline/REL) sektor Kehutanan dan Lahan Gambut 135
Tabel IV.4. Proyeksi Emisi CO2 PLTU Provinsi Sumatera Selatan 136
Tabel IV.5. Emisi BAU-Baseline PLTD PLN 137
Tabel IV.6. Prediksi Penjualan BBM dari Tahun 2011 sampai 2020 137
Tabel IV.7. Proyeksi Emisi CO2 menurut Jenis Konsumen Pertamina 138
Tabel IV.8. Proyeksi Emisi CO2 dari Kayu Bakar 139
Tabel IV.9. Proyeksi Total Emisi CO2 sektor Energi 140
Tabel IV.10. Proyeksi Emisi CO2 Sumatera Selatan sampai tahun 2020 144
Tabel IV.11. Proyeksi Emisi CO2 dari Industri di Provinsi Sumatera Selatan 145
Tabel IV.12. Prediksi Jumlah Penduduk Sumatera Selatan tahun 2010 dan Proyeksinya s.d 2020
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan xi
Tabel IV.13. Komposisi dan Dry Matter Content Sampah Domestik Sumsel 149
Tabel IV.14. Estimasi dan Proyeksi Volume Sampah Sumsel per Tahun dari 2010 s.d 2020 152
Tabel IV.15 Rekapitulasi Aktifitas Pengangkutan, Pembuangan Sampah Sembarangan,
Komposting dan Open Burning (2010)
153
Tabel IV.16 Estimasi dan Proyeksi (BAU) Volume Sampah Sumsel Masuk ke TPA dari 2010 s.d 2020
154
Tabel IV.17 Estimasi dan Proyeksi (BAU) Sampah Terolah dari 2010 s.d 2020 154
Tabel IV.18 Rekapitulasi Sampah Open Dumping, Open burning dan terolah/dikomposkan (BAU).
155
Tabel IV.19 Hasil Estimasi Emisi GRK dari aktifitas Open Dumping (BAU). 156
Tabel IV.20 Estimasi-Proyeksi Emisi GRK Sumsel dari Aktifitas Open Burning (BAU). 156
Tabel IV.21 Estimasi-Proyeksi Emisi GRK Sumsel dari Aktifitas Pengomposan Sampah Domestik( BAU).
157
Tabel IV.22 Rekapitulasi Estimasi dan Proyeksi Emisi GRK Sumsel dari sektor Sampah( BAU).
158
Tabel IV.23 Potensi Emisi CH4 dan N2O untuk Air Limbah, Pengolahan Lumpur, dan Sistem
Pembuangan Air Limbah Domestik di Sumatera Selatan
159
Tabel IV.24. Potensi Emisi GRK dari Limbah Cair Domestik di Sumsel 159
Tabel IV.25. Potensi Emisi GRK Sektor Limbah Provinsi Sumatera Selatan 160
Tabel IV.26. Proyeksi cakupan luas areal budidaya padi metode SRI di Provinsi Sumatera Selatan
161
Tabel IV.27. Rekapitulasi proyeksi besaran emisi GRK asal pembakaran jerami padi 166
Tabel IV.28. Rekapitulasi proyeksi besaran emisi GRK asal pembakaran jerami tebu 166
Tabel IV.29. Proyeksi potensi emisi CO2-e sektor pertanian di Provinsi Sumatera Selatan 171
Tabel IV.30. Skenario mitigasi pada zonasi perencanaan 175
Tabel IV.31. Proporsi Emisi Tutupan Lahan Pada BAU Baseline and Setelah Aksi Mitigasi 176
Tabel IV.32. Emisi Gas Rumah Kaca BAU Baseline dan Target Penurunan Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut
179
Tabel IV.33. Emisi CO2e sebelum dan sesudah mitigasi sampai tahun 2020 180
Tabel IV.36. Reduksi Emisi CO2 Perhitungan Counting Selama 24 Jam Tahun 2011 182
Tabel IV.37. Perbandingan Emisi CO2 (ton/tahun) dengan rencana mitigasi untuk beberapa perbatasan wilayah di Sumatera Selatan tahun 2012
184
Tabel IV.38. Rencana Mitigasi Emisi CO2 (ton/tahun) sampai dengan tahun 2020 di Sumatera Selatan
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan xii
Tabel IV.39. Skenario Penurunan Emisi CO2 mengikuti target nasional 26 % dan 41 % 187
Tabel IV.40.Rencana Pembangunan TPST 195
Tabel IV.41. Penurunan Emisi Aksi Mitigasi-1 s.d 2020 197
Tabel IV.42 Penurunan Emisi dari Aksi Rehabilitasi/Pembangunan TPA Semi-Aerobic 198
Tabel IV.43 Daftar dan Rencana Rehabilitasi TPA di Sumatera Selatan 199
Tabel IV.44 Biaya Operasional dan Maintenance TPA Semi-aerobic Skema Mitigasi-3 200
Tabel IV.45 Penurunan emisi dari flaring gas di TPA I Sukawinatan Palembang 201
Tabel IV.46 Trendline Penurunan Emisi dari Aksi Migrasi Pit-Latrin ke Septic Tank 203
Tabel IV.47 Estimasi Penurunan Emisi Kelompok Aksi Mitigasi-9 204
Tabel IV.48. Rekapitulasi Penurunan Emisi 206
Tabel IV.49. Prioritas strategi mitigasi Pertanian GRK di Provinsi Sumatera Selatan 207
Tabel IV.50 Matriks RAD – GRK Sektor Pertanian 208
Tabel IV.48 Matriks Skala Prioritas Sektor Pertanian 211
Tabel IV.52 Matriks RAD – GRK Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut 212
Tabel IV.53 Matriks Skala Prioritas Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut 213
Tabel IV.54 Matriks RAD – GRK Sektor Energi 215
Tabel IV.55 Matriks Skala Prioritas Sektor Energi 217
Tabel IV.56 Matriks RAD – GRK Sektor Transportasi 219
Tabel IV.57 Matriks RAD – GRK sektor Industri 224
Tabel IV.58 Matriks Skala Prioritas Sektor Industri 226
Tabel IV.57 Matriks RAD – GRK Sektor Pengelolaan Limbah 227
Tabel IV.58 Matriks Skala Prioritas Aksi Mitigasi Sektor Pengelolaan Limbah 230
Tabel V.1 Lembaga terkait dalam implementasi RAD-GRK di Provinsi Sumatera Selatan 233
Tabel V.2 Kelembagaan Publik Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut 234
Tabel V.3 Kelembagaan Masyarakat/Pelaku Usaha 235
Tabel V.4 Pemetaan Kelembagaan dan Pembagian Peran dalam Rencana Aksi Daerah Sumsel dalam penurunan GRK
236
Tabel V.5 Estimasi penurunan emisi dalam RKPD 2011 dan RKPD 2012 239
Tabel V.6. Pemetaan Kelembagaan terkait Implementasi RAD-GRK sektor Pengelolaan Limbah
240
Tabel V.7. Matriks Pendanaan Aksi Mitigasi sector Pertanian 242
Tabel V.8. Matriks Pendanaan Aksi Mitigasi Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut 246
Tabel V.9. Matriks Pendanaan Aksi Mitigasi Sektor Energi 249
Tabel V.10. Matriks Pendanaan Aksi Mitigasi sector Transportasi 255
Tabel V.11. Matriks Pendanaan Aksi Mitigasi Sektor Sampah/Limbah 258
Tabel V.12. Jadwal Implementasi RAD – GRK Sektor Pertanian 260
Tabel V.13. Jadwal Implementasi RAD – GRK Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut 261
Tabel V.14. Jadwal Implementasi RAD - GRK Sektor Energi 263
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan xiii DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Peta Administrasi Propinsi Sumatera Selatan 4
Gambar 2.2 Perbandingan pola spasial antara pengamatan dan proyeksi curah hujan diatas wilayah Sumatera Selatan.
5
Gambar 2.3 Peta Geologi Provinsi Sumatera Selatan 8
Gambar 2.4 Persentase Tutupan lahan Eksisting di Provinsi Sumatera Selatan (Sumber : Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan)
9
Gambar 2.5 Peta Tutupan lahan Eksisting tahun 2010 Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan)
9
Gambar 2.6 Peta Distribusi Penduduk Provinsi Sumatera Selatan (2010) 11
Gambar 2.7 Peta Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan (2010) 11
Gambar 2.8 Peta Sebaran Lahan Gambut di Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan)
13
Gambar 2.9 Peta Sebaran Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan)
14
Gambar 2.10 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan)
16
Gambar 2.11 Peta Sebaran Kawasan Pertambangan di Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan)
20
Gambar 2.12 Kontribusi sektor pertanian dalam emisi GRK di Indonesia 44
Gambar 2.13. Historis emisi CH4 dari areal sawah di Provinsi Sumatera Selatan
(2005-2011)
47
Gambar 2.14. Historis emisi CO2 akibat pembakaran jerami padi di Provinsi Sumatera
Selatan (2005-2011)
49
Gambar 2.15. Historis emisi CO akibat pembakaran jerami padi di Provinsi Sumatera Selatan (2005-2011)
50
Gambar 2.16. Historis emisi CH4 akibat pembakaran jerami padi di Provinsi Sumatera
Selatan (2005-2011)
50
Gambar 2.17. Historis emisi N2O akibat pembakaran jerami padi di Provinsi Sumatera
Selatan (2005-2011)
51
Gambar 2.18. Historis emisi NOx akibat pembakaran jerami padi di Provinsi Sumatera
Selatan (2005-2011)
51
Gambar 2.19. Historis emisi CO2 akibat pembakaran biomassa tebu sebelum panen di
Provinsi Sumatera Selatan (2005-2011)
52
Gambar 2.20. Historis emisi CO akibat pembakaran biomassa tebu sebelum panen di Provinsi Sumatera Selatan (2005-2011)
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan xiv
Gambar 2.21.Historis emisi CH4 akibat pembakaran biomassa tebu sebelum panen di
Provinsi Sumatera Selatan (2005-2011)
53
Gambar 2.22. Historis emisi N2O akibat pembakaran biomassa tebu sebelum panen di
Provinsi Sumatera Selatan (2005-2011)
53
Gambar 2.23. Historis emisi CH4 asal enteric fermentation ternak besar utama di Provinsi
Sumatera Selatan (2005-2012)
55
Gambar 2.24. Historis emisi CH4 asal kotoran ternak asal sistem pengelolaan kotoran
ternak besar utama di Provinsi Sumatera Selatan (2005-2012)
57
Gambar 2.25. Historis total emisi N2O secara langsung asal kotoran ternak pada berbagai
sistem pengelolaan kotoran ternak besar utama di Provinsi Sumatera Selatan (2005-2011)
59
Gambar 2.26. Historis total emisi N secara tidak langsung melalui volatilisasi NH3 dan NOx
asal kotoran ternak pada berbagai sistem pengelolaan kotoran ternak besar utama di Provinsi Sumatera Selatan (2005-2011)
62
Gambar 2.27. Historis total emisi N2O secara tidak langsung melalui volatilisasi asal
kotoran ternak pada berbagai sistem pengelolaan kotoran ternak besar utama di Provinsi Sumatera Selatan (2005-2011)
63
Gambar 2.28 Peta Tutupan Lahan Tahun 2006 (kiri) dan 2011 (kanan) Provinsi Sumatera Selatan (Sumber : Baplan)
64
Gambar 2.29 Peta Sebaran Gambut di Provinsi Sumatera Selatan 66
Gambar 2.30 Proporsi Historikal Emisi GRK masing – masing zonasi Tutupan Lahan di
Provinsi Sumatera Selatan
69
Gambar 2.31 Emisi Baseline (historical) Total Bahan Bakar Provinsi Sumatera Selatan 72
Gambar 2.32 Emisi CO2 Baseline PLTG di Sumatera Selatan 75
Gambar 2.33 Hasil Perhitungan Emisi CO2 menggunakan Tier 1 Tahun 2010 81
Gambar 2.34 Prediksi Penggunaan Solar untuk mobil penumpang tahun 2010 84
Gambar 2.35 Proyeksi Penggunaan Premium untuk mobil penumpang tahun 2010 84
Gambar 2.36 Emisi Baseline (Historikal) Transportasi Provinsi Sumatera Selatan 86
Gambar 2.37 Emisi CO2 (ton/tahun) untuk masing-masing wilayah menggunakan metode
KAYA
96
Gambar 2.38 Kategori sumberutama emisi GRK dari kegiatan pengelolaan limbah 101
Gambar 2.39 Estimasi timbulan sampah Sumsel tahun 2010 berdasarkan standar timbulan PU)
103
Gambar 2.40 Kondisi sampah yang terhampar sembarangan, juga dapat dikategorikan
dalam Uncategorized.
105
Gambar 2.41 Kondisi timbunan sampah di TPA I Sukawinatan (kanan) dengan ketinggian timbunan > 5m dan TPA II Karya Jaya dengan muka air tanah tinggi, dikategorikan
dalam Un-managed deep.
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan xv
Gambar 2.42 Salah satu upaya rehabilitasi TPA dari open dumping menuju semi-aerobic
landfill di TPA Bukit Kancil, Muara Enim, Sumsel
106
Gambar 2.43Tantangan dalam aspek peran serta masyarakat, belum siapnya masyarakat
terlibat dalam minimasi sampah di sumber.
107
Gambar 2.44 53 % TPA di Sumsel diketahui telah memiliki bangunan pengomposan. Gambaran yang cukup baik untuk program mitigasi dengan minimasi sampah skala kota.
107
Gambar 2.45 Distribusi Pengolahan dan Pembuangan Air limbah domestik on-site Sumsel . 109
Gambar 2.46 Baffled Septic Tank, salah satu upaya aplikasi teknologi untuk pengolahan air limbah domestik terpusat skala lingkungan yang sedang diuji coba di Palembang.
110
Gambar 2.47 Baffled Septic Tank, salah satu upaya aplikasi teknologi untuk pengolahan air limbah domestik terpusat skala lingkungan yang sedang diuji coba di Palembang
110
Gambar 2.48 Tantangan: Sistem Pembuangan Air Limbah (Domestik) menyatu dengan saluran drainase, berakhir di sungai atau retensi/rawa.
111
Gambar 4.1. Proyeksi BAU emisi CH4 dari areal sawah di Provinsi Sumatera Selatan
(2012-2020)
125
Gambar 4.2. Proyeksi emisi CO2 asal pembakaran jerami padi di Provinsi Sumatera
Selatan (2012-2020)
127
Gambar 4.3. Proyeksi emisi CO asal pembakaran jerami padi di Provinsi Sumatera Selatan (2012-2020)
127
Gambar 4.4. Proyeksi emisi CH4 asal pembakaran jerami padi di Provinsi Sumatera
Selatan (2012-2020)
128
Gambar 4.5. Proyeksi emisi N2O asal pembakaran jerami padi di Provinsi Sumatera
Selatan (2012-2020)
128
Gambar 4.6. Proyeksi emisi NOx asal pembakaran jerami padi di Provinsi Sumatera Selatan (2012-2020)
129
Gambar 4.7. Proyeksi emisi CO2 asal pembakaran biomassa tebu sebelum panen di
Provinsi Sumatera Selatan (2012-2020)
130
Gambar 4.8. Proyeksi emisi CO asal pembakaran biomassa tebu sebelum panen di Provinsi Sumatera Selatan (2012-2020)
130
Gambar 4.9. Proyeksi emisi CH4 asal pembakaran biomassa tebu sebelum panen di
Provinsi Sumatera Selatan (2012-2020)
131
Gambar 4.10. Proyeksi emisi N2O asal pembakaran biomassa tebu sebelum panen di
Provinsi Sumatera Selatan (2012-2020)
131
Gambar 4.11. Proyeksi emisi NOx asal pembakaran biomassa tebu sebelum panen di Provinsi Sumatera Selatan (2012-2020)
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan xvi
Gambar 4.12. Proyeksi total emisi CH4 asal ternak besar di Provinsi Sumatera Selatan
(2012-2020)
133
Gambar 4.13. Proyeksi total emisi N2O secara langsung asal ternak besar di Provinsi
Sumatera Selatan (2012-2020)
134
Gambar 4.14. Proyeksi total emisi N2O secara tidak langsung asal ternak besar di Provinsi
Sumatera Selatan (2012-2020).
134
Gambar 4.15 Emisi BAU Baseline (REL) sektor Kehutanan dan Lahan Gambut Provinsi Sumatera Selatan
136
Gambar 4.16 Emisi BAU – Baseline PLTD milik PLN 138
Gambar 4.17 Prediksi Emisi CO2e dari penjualan BBM tahun 2011 sampai 2020 139
Gambar 4.18 Emisi BAU – Baseline Kayu Bakar 140
Gambar 4.19 Proyeksi emisi CO2e total dari sektor energy di Provinsi Sumatera Selatan sampai 2020
141
Gambar 4.20 Grafik Penjualan BBM sampai tahun 2020 142
Gambar 4.21 Grafik Emisi (Gg CO2 eq) dengan TIER 1 142
Gambar 4.22 Grafik Penjualan BBM Solar pada Kendaraan Mobil, Bus, dan Truck 143
Gambar 4.23 Grafik Penjualan BBM Premium pada Kendaraan Jenis Mobil dan Sepeda Motor
143
Gambar 4.24 Emisi CO2 per jenis kendaraan dan bahan bakar, dan Emisi Total CO2
Provinsi Sumatera Selatan
144
Gambar 4.25 Prediksi Emisi CO2 (ton/tahun) untuk beberapa wilayah tahun 2020 144
Gambar 4.26 Prediksi Emisi CO2 (ton/tahun) sector Transportasi di Sumatera Selatan 145
Gambar 4.27 Proyeksi Emisi CO2 Sektor Industri Provinsi Sumatera Selatan 146
Gambar 4.28 Pengukuran bulk density sampah (Survey JICA SP3 2011 FY) 149
Gambar 4.29 Perbandingan tipe timbunan sampah (domestic) provinsi Sumatera Selatan. 156
Gambar 4.30 BAU Baseline Emisi GRK sector sampah Provinsi Sumatera Selatan. 159
Gambar 4.31 BAU Baseline Emisi GRK sector limbah provinsi Sumatera Selatan 161
Gambar 4.32 Skenario proyeksi (2011-2020) penurunan emisi CH4 asal sawah di Provinsi
Sumatera Selatan melalui implementasi SRI.
164
Gambar 4.33. Skenario proyeksi (2011-2020) penurunan emisi CH4 asal sawah di Provinsi
Sumatera Selatan melalui penanaman varietas padi emisi CH4 rendah.
165
Gambar 4.34. Skenario proyeksi (2011-2020) penurunan emisi CH4 asal sawah di Provinsi
Sumatera Selatan melalui kombinasi Metode SRI dan Varietas Rendah Emisi.
166
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan xvii
ternak di Provinsi Sumatera Selatan melalui pemberian pakan konsentrat.
Gambar 4.36. Skenario proyeksi (2011-2020) penurunan emisi N2O secara langsung asal
kotoran ternak ternak di Provinsi Sumatera Selatan melalui penggalakan fermentasi anaerob.
171
Gambar 4.37. Skenario proyeksi (2011-2020) penurunan emisi N2O secara tidak langsung
asal kotoran ternak ternak di Provinsi Sumatera Selatan melalui penggalakan fermentasi anaerob.
172
Gambar 4.38. Proyeksi penurunan emisi sektor pertanian melalui impelementasi aksi mitigasi
173
Gambar 4.39 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2010 - 2030 175
Gambar 4.40 Emisi BAU Baseline dan Target Penurunan Emisisektor Kehutanan dan Lahan Gambut Provinsi Sumatera Selatan
180
Gambar 4.42 Emisi CO2e (ton) sebelum dan sesudah mitigasi sampai tahun 2020 181
Gambar 4.43 Target Penurunan Emisi CO2 terhadap Emisi BAU – Baseline 186
Gambar 4.45 Target Penurunan Emisi CO2 pada Industri di Provinsi Sumatera Selatan 188
Gambar 4.46 Skematik Pengelolaan/Minimasi Sampah integrasi TPST-Bank Sampah 195
Gambar 4.47 Perkiraan distribusi pengelolaan sampah Sumsel 2020 dengan aksi mitigasi-1 197
Gambar 4.48 Trendline distribusi pengelolaan sampah Sumsel 2010-2020 dengan aksi mitigasi-1
197
Gambar 4.49 Kenaikan persentase timbunan di semi-aerobic landfill dan penurunan timbunan di un-managed deep, seiring rehabilitasi TPA di 10 kota/kab pada 2012 s.d 2015.
200
Gambar 4.50 Target Penurunan Emisi GRK sektor Sampah/Limbah 207
Gambar 5.1 Trendline penurunan Emisi dengan Program/Kegiatan pada RKPD 2011 dan 2012
241
Gambar 5.2 Pagu anggaran program/kegiatan penurunan emisi GRK dalam RKPD 2011-RKPD 2012
242
Gambar 5.3 Proporsi Sumber Dana Program/Kegiatan Mitigasi Penurunan EMisi GRK sektor Kehutanan dan Lahan Gambut
248
Gambar 5.4 Total Anggaran Program/kegiatan Mitigasi RAD-GRK Sektor Pengelolaan Limbah Th. 2013 – 2020
257
Gambar 6.1. Kerangka implementasi RAD-GRK Provinsi Sumatera Selatan 267
Gambar 6.2. Konsep continous improvenment dalam monev implementasi RAD-GRK
Provinsi Sumatera Selatan
270
Gambar 7.1 Emisi BAU-Baseline Provinsi Sumatera 272
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas
Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dengan upaya sendiri dan
sebesar 41% dengan dukungan internasional. Komitmen ini disampaikan oleh
Presiden Republik Indonesia dalam pertemuan G-20 di Pittsburg, Amerika Serikat
pada bulan September 2009, dan dalam pertemuan Conference Of the Parties
(COP) 15 di Copenhagen, Denmark pada bulan Desember 2009. Sebagai tindak
lanjut dari komitmen tersebut maka Pemerintah menyusun Rencana Aksi Nasional
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) untuk memberikan pedoman bagi
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat dalam
melaksanankan berbagai kegiatan/program untuk mengurangi emisi GRK dalam
periode tahun 2010-2020.
Rencana aksi ini harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
2010-2014. RAN-GRK ini dikukuhkan dalam bentuk Perpres No. 61 Tahun 2011 tersebut
mengamanatkan Pemerintah Provinsi untuk menyusun rencana aksi daerah
penurunan emisi di provinsinya masing-masing, agar target/sasaran penurunan
emisi secara nasional dapat tercapai. Substansi di dalam RAN-GRK merupakan
dasar penyusunan RAD-GRK di setiap provinsi, yang dikembangkan sesuai dengan
potensi, kemampuan, dan selaras dengan kebijakan pembangunan masing–masing
provinsi.
RAD-GRK adalah dokumen yang menyediakan arahan bagi pemerintah daerah
untuk melaksanakan berbagai kegiatan penurunan emisi, baik berupa kegiatan
langsung maupun tidak langsung menurunkan emisi Gas Rumah Kaca dalam kurun
waktu tertentu. Adapun kegiatan inti untukmenurunkan emisi GRK meliputi 5
bidang, yaitu: pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi,
industri, serta pengelolaan limbah. Sedangkan kegiatan penurunan emisi Gas
Rumah Kaca diatur dalam Peraturan presiden No 71 tahun 2011 tentang pedoman
penyelenggaraan inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca di daerah. Inventarisasi
GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data mengenai tingkat, status, dan
kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi
dan penyerapnya termasuk simpanan karbon di tingkat peopinsi dan
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 2
Propinsi Sumatera Selatan dipilih sebagai salah satu propinsi yang akan menjadi
sebagai Pilot Project penyusunan dokumen RAD-GRK. Di Sumatera Selatan,
kegiatan yang berhubungan dengan perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas
Rumah Kaca, bukanlah sesuatu yang baru, karena Sumatera Selatan telah memiliki
beberapa kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Seperti diketahui,
Sumatera Selatan dalam kegiatan perubahan iklim telah memiliki program REDD+,
NAMA, Inventarisasi GRK disektor persampahan, KRAPI (Kajian Risiko dan
Adaptasi perubahan Iklim), dll. Sehingga kegiatan penyusunan RAD-GRK ini akan
menyatukan semua kegiatan mitigasi yang pernah dilakukan di propinsi Sumatera
Selatan.
1.2 Tujuan
Berdasarkan Peraturan Presiden No 61 Tahun 2011, kegiatan RAD-GRK bertujuan
untuk menyusun dokumen kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara
langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan
target pembangunan daerah yang tertuang di RPJP (Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah), RTRWP/K (Rencana tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota) dan
Rencana Strategis SKPD terutama sector yang berhubungan langsung dengan
emisi gas rumah kaca.
1.3 Keluaran
Sesuai dengan tujuan dari kegiatan ini maka diharapkan akan menghasilkan
sebuah dokumen kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan menurunkan emisi
gas rumah kaca, dimana dokumen tersebut berisi informasi mengenai tingkat,
status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai
sumber emisi (source) dan penyerapnya (sink) termasuk simpanan karbon (carbon stock) di Sumatera Selatan.
1.4 Dasar Hukum
Landasan hukum penyusunan RAD-GRK di propinsi Sumatera Selatan antara lain:
a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang pengesahan United
Nations Framework Convention on Climate Change.
b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 3
d. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindangan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
f. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010 – 2014.
g. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
h. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.
i. Draft Akhir RTRW Propinsi Sumatera Selatan
1.5 Kerangka Waktu Penyusunan
Menurut Undang – Undang nomor 6i Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca yang menyatakan bahwa penyusunan RAD-GRK
diselesaikan dan ditetapkan dengan peraturan gubernur paling lambat 12 (dua
belas) bulan sejak ditetapkan Peraturan Presiden ini tanggal 20 September 2011.
Berdasarkan hal tersebut maka penyusunan dokumen RAD-GRK propinsi
Sumatera Selatan mempunyai batas waktu hingga bulan September tahun 2012.
Selengkapnya akan diuraikan dibawah ini.
RAD-GRK Development Maret April Mei Juni Juli Agust Sept
Pembentukan Tim
Pengembangan Working Plan Kick Off Meeting
Pengumpulan Data Perhitungan BAU Baseline Pengajuan Aksi Mitigasi Penentuan Skala Prioritas
Menentukan Target Reduksi Emisi GRK Pengembangan Strategi Pelaksanaan dari RAD-GRK
Draft Teks Peraturan Gubernur Meeting/Workshop
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 4
BAB II PROFIL DAERAH DAN PERMASALAHAN EMISI GRK
2.1 Profil dan Karakteristik Daerah
2.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi
Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari Pulau Sumatera yang
mempunyai luas wilayah 91.806,36 Km2, yang terletak pada 1°- 4° Lintang Selatan dan 102°-106° Bujur Timur. Provinsi Sumatera Selatan secara administratif dibagi
menjadi 11 (sebelas) kabupaten dan 4 (empat) kota, serta 217 kecamatan.
Adapun batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Jambi.
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Lampung.
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Gambar 2.1 Peta Administrasi Propinsi Sumatera Selatan
2.1.2 Klimatologi
Di Palembang, musim kering juga terpisah dengan jelas dari Juni hingga
September, sebagaimana diindikasikan oleh curah hujan rata - rata bulanan yang
kurang dari 150 mm, tetapi dua curah hujan maksimum terjadi pada sekitar bulan
Desember dan Maret. Dengan demikian, curah hujan di Palembang mewakili suatu
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 5
monsoonal dan dua jenis equatorial. Pengaruh topografi, lautan, dan pulau-pulau
kecil dilepas pantai timur juga menambah kerumitan iklim di Sumatera Selatan.
Berdasarkan hasil kajian Sain Basis (Hadi, 2011), pola iklim di Sumatera Selatan
ditandai dengan perbedaan musim kering dan dua puncak curah hujan sekitar
Desember dan Maret dengan curah hujan rata – rata bulanan sekitar 250 mm. Suhu rata - rata bulanan dengan dua puncak kelihatan tertinggal satu bulan atau lebih
dari equinoxes dengan nilai rata-rata sedikit diatas 27°C. Sangat menarik untuk dicatat bahwasanya perbedaan suhu diantara bulan terpanas (Mei) dan bulan
terdingin ( Januari ) hanya sekitar 1°C. Meskipun hasil ini kelihatannya memberikan
indikasi bahwa iklim di Sumatera Selatan dapat dianggap tidak mengalami
perubahan dalam kurun waktu seabad.
Kejadian kekeringan di Sumatera Selatan adalah berkorelasi dengan kejadian El
Niño kuat serta Dipole Mode (+). Dampak ENSO/ Dipole Mode terhadap kekeringan
di Sumatera Selatan yang paling signifikan terjadi pada musim kemarau dan pada
saat peralihan dari musim kemarau memasuki musim penghujan. Tingkat
kekeringan kritis dapat juga diidentifikasi dari dry spell yaitu lamanya hari kering tanpa hujan. Panjang rata - rata dry spell gabungan untuk September-Oktober-November (SON) sepanjang lebih dari 8 hari yang sangat dipengaruhi oleh Dipole
Mode +.
(a)
(b)
(c)
(d)
Gambar 2.2 Perbandingan pola spasial antara pengamatan ((a) dan (c))
dan proyeksi ((b) dan (d)) curah hujan diatas wilayah Sumatera Selatan.
Contoh menampilkan data bulan September ((a) dan (c)) dan Desember
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 6
2.1.3 Topografi
Wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki topografi yang bervariasi mulai dari
daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Wilayah pantai
timur sebagian besar merupakan daerah rawa dan payau yang dipengaruhi oleh
pasang surut air laut.
Wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki bentangan wilayah Barat-Timur
dengan ketinggian antara 1.700 mdpl. Daerah dengan ketinggian antara
400-500 mdpl mencakup areal seluas 37 %. Wilayah barat merupakan wilayah
pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian rata-rata antara 900-1.200 mdpl.
Sedangkan kearah timur lahannya berbukit dan bergelombang. Pegunungan Bukit
Barisan ini terdiri dari Puncak Gunung Seminung (1.964 mdpl), Gunung Dempo
(3,159 mdpl), Gunung Patah (1.107 mdpl), dan Gunung Bungkuk (2.125 mdpl).
Disebelah barat Bukit Barisan merupakan lereng.
2.1.4 Geologi
Menurut penafsiran modern, lempeng Samudera Hindia saat ini mengalami
pergerakan di bawah Pulau Sumatera sebesar 6 cm per tahun. Pergerakan tersebut
dimulai sejak periode pertengahan tersier (Miocen). Pegunungan Bukit Barisan
akan terdorong kebawah membentuk saluran dalam kearah Sumatera bagian Barat.
Terjadi kenaikan permukaan benua di pantai timur dan gerakan penurunan di pantai
yang berlawanan, diluar daerah tangkapan air. Hal ini menunjukkan bahwa
pergerakan tersebut masih terus berlangsung, seperti digambarkan dibawah ini:
a. Pengurangan ukuran pantai barat, secara perlahan – lahan terjadi penyusutan di bawah laut karena pergerakan penurunan.
b. Pengurangan kemiringan lereng dan daerah – daerah rawa di dataran pantai timur yang disebabkan oleh pergerakan tilt-up.
Kemunculan penuh daerah Peneplain terjadi di akhir periode tersier sampai periode
awal Quarter (Villafranchien) karena pengikisan lapisan sedimen oleh erosi regresif
dan kadang – kadang menghasilkan perkerasan batuan. Pengujian Pedologik dihasilkan dari pewarnaan ulang pada tanah (latosol).
Kejadian menekuk terjadi di seperempat bagian dari Bukit Barisan. Keretakan
terbuka dari arah Barat Laut sampai Tenggara melintasi Danau Ranau mengikuti
puncak bukit. Pergerakan lateral membagi Pulau Sumatera menjadi dua bagian.
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 7 puncaknya dengan ledakan kawah Ranau dan pembentukan breksi, aliran lava dan abu tufa. Abu Vulkanik juga menutupi dataran Peneplain dimana material menutupi perkerasan erosi yang dapat diamati secara cepat disepanjang jalan
Trans-Sumatera antara Muararupit dan Surulangun-Rawas.
Tatanan Tektonik (Tectonic Setting)
Berdasarkan tatanan tektoniknya (Tectonic Setting), wilayah Provinsi Sumatera
Selatan menempati cekungan belakang busur Paleogen (Paleogene Back-Arc
Basin) yang dikenal sebagai Cekungan Sumatera Selatan (South Sumatera Basin)
di bagian timur, dan mendala busur vulkanik (volcanic arc) yang membentang secara regional di sepanjang Bukit Barisan bagian barat. Kedua mendala tektonik
ini terbentuk akibat adanya interaksi menyerong (oblique) antara Lempeng Samudera Hindia di barat daya dan Lempeng Benua Eurasia di timur laut pada
tersier (Malod, 1995. Hall, 1997 dan 2002). Pertemuan kedua lempeng bumi tersebut terletak di sepanjang Parit Sunda (Sunda Trench) yang berada di lepas Pantai Barat Sumatera, dimana lempeng samudera menyusup dengan penunjaman
miring -300(Fith, 1970) dibawah kontinen yang dikenal sebagai Paparan Sunda atau
Sundaland(de Coster, 1974).
Jenis struktur yang umum dijumpai dicekungan Sumatera Selatan terdiri dari
lipatan, sesar dan kekar. Struktur lipatan memperlihatkan orientasi barat
laut-tenggara, melibatkan sikuen batuan berumur Oligosen-Plistosen (Gafoer dkk, 1986). Sedangkan sesar yang ada merupakan sesar normal dan sesar naik. Sesar normal dengan pola kelurusan barat laut-tenggara tampak berkembang pada
runtutan batuan berumur Oligosen-Moisen, sedangkan struktur dengan arah umum
timur laut-barat daya, utara-selatan, dan barat-timur terdapat pada sikuen batuan
berumur Plio-Plistosen. Sesar naik biasanya berarah barat tenggara, timur laut-barat daya dan laut-barat-timur, dijumpai pada batuan berumur Plio-Plistosen dan kemungkinan merupakan hasil peremajaan (reactivation) struktur tua yang berupa sesar tarikan (extensional faults).
Struktur rekahan yang berkembang memperlihatkan arah umum timur laut-barat
daya, relatif tegak lurus dengan strike struktur regional atau sejajar dengan arah pergerakan tektonik (tectonic motion) di Sumatera. Pembentukan struktur lipatan, sesar dan kekar di cekungan Sumatera Selatan memberikan implikasi yang
signifikan terhadap akumulasi sumber daya minyak bumi, gas alam, batubara dan
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 8
litologi penyusun stratigrafi cekungan Sumatera Selatan telah pula mengontrol
penyebaran sumberdaya energi fosil non fosil di wilayah ini.
Batuan yang mendasari (Basement) Cekungan Sumatera Selatan merupakan
kompleks batuan berumur pra-tersier, yang terdiri dari batu gamping, andesit,
granodiorit, pilit, kuarsit dan granit.
a. Formasi Lahat terdiri dari endapan tufa, aglomerat, breksi tufan, andesit, serpih,
batu lanau, batu pasir dan batubara.
b. Formasi Talang Akar terdiri dari batu pasir berukuran butir kasar-sangat kasar,
serpih, batu lanau dan batubara.
c. Formasi Baturaja terdiri dari batu gamping terumbu, serpih gampingan dan napal
atau batu lempung gampingan.
d. Formasi Baturaja terdiri dari serpih gampingan dan serpih lempungan.
e. Formasi Air Benakat dengan penyusun utama batu pasir.
f. Formasi Muara Enim terdiri dari batu pasir, batu lanau, batu lempung dan
batubara.
g. Formasi Kasai terdiri dari batu pasir tufaan dan tufa.
Gambar 2.3 Peta Geologi Provinsi Sumatera Selatan
2.1.5 Penutupan Lahan
Pola penggunaan lahan eksisting di Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh
pertanian lahan kering yaitu 3.509.121,849 Ha (38,236%) yang tersebar hampir di
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 9
Gambar 2.4 Persentase Tutupan lahan Eksisting di Provinsi Sumatera Selatan (Sumber : Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan)
Jenis penggunaan lahan semak belukar merupakan jenis penggunaan yang cukup
luas di Provinsi Sumatera Selatan yaitu 1.696.092 Ha (18,48%). Hal ini
menunjukkan masih cukup luasnya lahan non produktif yang masih dapat
ditingkatkan produktifitasnya menjadi kegiatan budidaya produktif. Berdasarkan
hasil analisis kesesuaian lahan, lahan semak belukar ini memiliki kesesuaian untuk
dikembangkan sebagai kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan
pertanian tanaman tahunan.
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 10
2.1.6 Penduduk
Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2004 hingga tahun 2010
terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 tercatat bahwa jumlah penduduk di
Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 7.446.401 jiwa, dimana jumlah penduduk
Provinsi Sumatera Selatan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 sebanyak
7.019.984 jiwa, dan 6.628.416jiwa pada tahun 2004.
Tabel II.1. Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2004-2010
No Kabupaten/ Kota
Jumlah Penduduk (%)
2010
2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010**
1 OKU 1.112.854 255.246 259.292 262.383 264.743 332.945 323.420 4,34 2 OKI 1.000.152 656.828 672.192 685.296 696.505 654.813 726.659 9,76 3 Muara Enim 621.876 632.222 649.691 656.318 660.906 754.708 717.717 9,64 4 Lahat 541.895 545.754 550.478 553.093 340.555 410.645 370.146 4,97 5 Musi Rawas 465.682 474.430 484.281 492.437 498.592 642.745 524.919 7,05 6 Musi Banyuasin 455.739 469.175 484.245 497.864 510.387 623.588 562.584 7,56 7 Banyuasin 712.813 733.828 757.398 778.627 798.360 748.161 749.107 10,06 8 OKU Timur *** 556.010 557.843 571.577 329.071 683.776 609.715 8,19 9 OKU Selatan *** 317.277 322.307 326.162 576.699 442.304 318.345 4,28 10 Ogan Ilir *** 356.983 365.333 372.431 378.570 416.803 380.861 5,11 11 Empat Lawang *** *** *** *** 213.559 247.350 220.694 2,96 12 Palembang 1.304.211 1.338.793 1.369.239 1.394.954 1.417.047 1.756.198 1.452.840 19,51 13 Pagar Alam 113.752 114.562 121.352 122.440 123.848 132.253 126.363 1,70 14 Lubuk Linggau 171.235 174.452 178.074 181.068 183.580 230.647 201.217 2,70 15 Prabumulih 128.207 130.340 132.752 134.686 136.253 189.531 161.814 2,17
Total 6.628.416 6.755.900 6.899.892 7.019.984 7.121.790 8.266.467 7.446.401 100,00
Jumlah penduduk terbesar di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 terdapat
di Kota Palembang yaitu 1.452.840 jiwa atau sekitar 19,51% dari total jumlah
penduduk di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan penduduk terkecil terdapat di
Kota Pagar Alam yaitu 126.363 jiwa atau 1,70 % dari total jumlah penduduk
Provinsi Sumatera Selatan.
Laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan terjadi pada
periode tahun 2008-2010 yaitu sebesar 2,13%, sedangkan pertumbuhan penduduk
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 11
Gambar 2.6 Peta Distribusi Penduduk Provinsi Sumatera Selatan (2010)
Kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 adalah 78
jiwa/km2. Kabupaten/kota dengan kepadatan penduduk>100 jiwa/km2 meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Ilir, Kota Palembang, Pagar Alam,
Lubuk Linggau dan Prabumulih. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota
Palembang yaitu sekitar 3.627 jiwa/km2.Hal ini disebabkan karena Kota Palembang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang berfungsi melayani seluruh
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 12
Berdasarkan hasil proyeksi penduduk di Provinsi Sumatera Selatan, jumlah
penduduk tahun 2015 diprediksikan sebanyak 7.769.471 jiwa, pada tahun 2020
sebanyak 8.573.776 jiwa, dan pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2030 sebanyak 10.182.386 jiwa. Dimana jumlah penduduk terbanyak masih sama
dengan tahun 2005-2010, yaitu Kota Palembang. Hal ini disebabkan Kota
Palembang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan merupakan Ibukota
Provinsi Sumatera Selatan yang sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk.
Tabel II.2. Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2030
No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Proyeksi dan Eksisting (Jiwa)
2005 2010 2015 2020 2025 2030 12 Palembang 1.338.793 1.452.840 1.545.839 1.663.814 1.879.267 2.092.904 13 Pagar Alam 114.562 126.363 130.381 142.298 154.274 166.291 14 Lubuk Linggau 174.452 201.217 213.440 238.432 263.316 288.124 15 Prabumulih 130.340 161.814 175.557 203.798 231.668 259.270
Total 6.755.900 7.446.401 7.884.473 8.573.776 9.378.081 10.182.386
Sumber : Dokumen RTRW.
Apabila dilihat berdasarkan kepadatan penduduk pada tahun 2015, 2020, 2025 dan
2030, kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan.
Kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 sekitar 81 jiwa/km2,
pada tahun 2020 sekitar 93 jiwa/km2, dan pada tahun 2030 sekitar 111 jiwa/km2.
Tabel II.3. Proyeksi Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2030
No Kabupaten/Kota Tahun (Jiwa/Km
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 13
No Kabupaten/Kota Tahun (Jiwa/Km
2
)
2015 2020 2025 2030
8 OKU Timur 187 203 218 234
9 OKU Selatan 61 65 69 73
10 Ogan Ilir 147 156 165 174
11 Empat Lawang 103 108 113 118
12 Palembang 3609 4153 4691 5224
13 Pagar Alam 206 225 243 262
14 Lubuk Linggau 532 594 656 718
15 Prabumulih 404 469 533 597
Total 85 93 102 111
Sumber : Dokumen RTRW, 2010. 2.1.7 Potensi Sumber Daya Alam
A. Kawasan Gambut
Wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki kawasan bergambut seluas 1,42
juta ha atau 15,46 % dari luas wilayah. Dengan luasan seperti ini menjadikan
Provinsi Sumatera Selatan sebagai provinsi terluas kedua di Pulau Sumatera
(setelah Provinsi Riau) yang memiliki kawasan gambut. Dilihat dari
ketebalannya, kawasan gambut di Provinsi Sumatera Selatan memiliki
ketebalan yang bervariasi antara 50 - 400 cm atau termasuk kategori dangkal
hingga dalam. Namun demikian 96,8 % termasuk gambut dangkal hingga
sedang, sisanya 3,2 % atau 45.009 ha merupakan gambut dalam yang
sebarannya terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin,
Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan
Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung, bahwa gambut
yang termasuk dalam kategori kawasan lindung apabila mempunyai ketebalan
lebih dari 3 m
.
Gambar 2.8 Peta Sebaran Lahan Gambut di Provinsi Sumatera Selatan
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 14
B. Hutan
Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumberdaya hutan yaitu seluas
3.829.522,435 ha atau sekitar 41,73 % dari luas Provinsi Sumatera Selatan.
Namun pada saat ini dengan potensi sumberdaya hutan yang dimiliki Provinsi
Sumatera Selatan yang tidak dibarengi dengan kontrol dari pengelolaan
kawasan hutan mengakibatkan sering terjadinya penebangan kayu liar dan
perambahan hutan. Selain itu Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu
provinsi di Indonesia yang rentan terhadap bencana kebakaran hutan, baik
yang disebabkan oleh manusia/masyarakat maupun yang disebabkan oleh
musim kemarau. Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan di Provinsi
Sumatera Selatan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di dalam Provinsi
Sumatera Selatan saja, tapi dirasakan oleh masyarakat yang berada di wilayah
provinsi yang berdekatan, bahkan hingga menimbulkan dampak internasional
hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Gambar 2.9 Peta Sebaran Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan (Sumber:
Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan)
C. Sumberdaya Air
Sumberdaya air di Provinsi Sumatera Selatan dibedakan menjadi 2 bagian,
yaitu sumberdaya air permukaan dan sumberdaya air tanah.
1. Air permukaan
Wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah kaya sumberdaya
air, karena dialiri oleh banyak sungai. Beberapa sungai yang relatif besar
adalah Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering dan Sungai Lematang.
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 15
tergantung dari sungai-sungai utama, yakni Sungai Musi dan anak-anak
sungainya. Ketergantungan masyarakat yang tinggal di sepanjang pinggiran
sungai terhadap keberadaan sungai tersebut masih sangat besar terutama
dalam memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Sehingga masih
banyak penduduk yang memanfaatkan air sungai sebagai sumber air
bersih. Mereka mengambil air dari sungai kemudian diendapkan atau
ditambahkan kaporit, kemudian langsung digunakan sebagai air untuk
dimasak atau pada saat musim hujan mereka menampung air hujan untuk
dijadikan air minum. Kebiasaan ini sudah terjadi secara turun menurun sejak
dahulu. Hanya saja dulu air sungai masih belum terlalu tercemar. Saat ini
penggunaan air sungai tanpa pengolahan khusus akan sangat berbahaya
bagi kesehatan, karena pencemaran sungai sudah sangat tinggi.
2. Air tanah
Komponen utama pembentuk air tanah adalah air hujan yang sebagian
meresap ke dalam tanah di daerah imbuh (recharge area) dan sebagian tersimpan di dalam akuifer serta sebagian lagi keluar secara alamiah di
daerah luah (discharge area). Berdasarkan tempatnya air tanah tidak terlepas dari litologi dan morfologinya. Melihat persebaran keberadaan air
tanah di Provinsi Sumatera Selatan dapat dibedakan menjadi : wilayah air
tanah dataran, wilayah air tanah perbukitan dan wilayah air tanah kaki
gunung api (Robert, H. 1996). Namun, secara umum data potensi air tanah
di wilayah Provinsi Sumatera Selatan belum banyak dilakukan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Geologi Tata
Lingkungan, diketahui bahwa cekungan air tanah yang terdapat di Provinsi
Sumatera Selatan sebanyak 9 (sembilan) lokasi, yaitu :
- Dua cekungan di dalam provinsi
a) CAT Karangagung (Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Ogan Komering
Ilir);
b) CAT Palembang-Kayuagung (Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan
Komering Ilir, dan Kota Palembang dan Prabumulih).
- Tujuh cekungan lintas batas provinsi
a) CAT Jambi-Dumai (Prov. Sumsel, Prov. Jambi, dan Prov. Riau);
b) CAT Bangko-Sarolangun (Prov. Sumsel dan Prov. Jambi);
c) CAT Sugiwaras (Prov. Sumsel dan Prov. Jambi);
d) CAT Lubuk Linggau-Muara Enim (Prov. Sumsel, Prov. Bengkulu, dan
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 16
e) CAT Muaraduo-Curup (Prov. Sumsel dan Prov. Bengkulu).
f) CAT Baturaja (Prov. Sumsel dan Prov. Lampung).
g) CAT Ranau (Prov. Sumsel dan Prov. Lampung).
Gambar 2.10 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan)
D. Mineral dan Energi
Provinsi Sumatera Selatan mempunyai potensi sumberdaya energi yang
sangat melimpah, baik sumberdaya energi fosil maupun nonfosil. Jenis
sumberdaya energi fosil seperti batubara, minyak, dan gas bumi merupakan
cadangan yang patut diperhitungkan secara nasional karena potensinya yang
cukup besar. Demikian juga dengan potensi sumberdaya non fosil yang bersifat
terbarukan seperti panas bumi, biomasa, dan mini/mikro-hidro, terdapat dalam
jumlah yang signifikan. Potensi sumberdaya energi terbarukan ini apabila
dikembangkan secara optimal akan memberikan alternatif untuk menggantikan
penggunaan energi fosil.
1. Minyak Bumi
Potensi cadangan minyak bumi di Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini
tersebar di Kabupaten Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Banyuasin,
Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, Ogan Ilir dan Kota Prabumulih. Cadangan
minyak di 8 (delapan) daerah tersebut diperkirakan sebesar 757,6 MMSTB
atau sekitar 8,78 % dari total cadangan minyak bumi nasional. Berdasarkan
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 17
status terbukti sebesar 448,2 MMSTB atau 10,7 % dari total cadangan
terbukti minyak bumi nasional.
Berdasarkan besarnya lifting yang terdapat di setiap derah penghasil, maka terdapat beberapa sentra akumulasi besar dari minyak bumi di Provinsi
Sumatera Selatan, mulai dari yang terbesar sampai terkecil berturut-turut
adalah Kabupaten Musi Banyuasin (48,50%), Kabupaten Muara Enim
(24,04%), Kabupaten Musi Rawas (10,85%) dan Kabupaten Ogan Komering
Ulu (5,69%). Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi di 4 (empat)
kabupaten tersebut dapat dikategorikan sebagai area prospek ekonomi
tinggi.
2. Gas Bumi
Cadangan gas bumi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 24.179.980
BSCF. Bila dibandingkan dengan cadangan gas bumi nasional yaitu
185.797.870 BSCF, maka rasio potensi gas bumi Provinsi Sumatera Selatan
terhadap cadangan gas bumi nasional adalah 13,01%. Ada 2 (dua) sentra
akumulasi besar dari gas alam di Provinsi Sumatera Selatan apabila dilihat
berdasarkan lifting gas buminya, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin (48,41%) dan Kabupaten Musi Rawas (39,21%). Wilayah kerja pertambangan gas
bumi di kedua kabupaten tersebut dapat dikategorikan sebagai area prospek
ekonomi tinggi.
3. Batubara
Potensi batubara di Provinsi Sumatera Selatan cukup besar, yaitu 22.240,4
juta ton atau sekitar 38,5 % dari total cadangan sumberdaya batubara
nasional yaitu 57.847,7 juta ton. Sedangkan potensi cadangan yang siap
tambang di Provinsi Sumatera Selatan adalah sekitar 2.653,9 juta ton atau
sekitar 38 % dari cadangan siap tambang nasional yaitu 6.981,6 juta ton.
Cadangan batubara di Provinsi Sumatera Selatan tersebar di 6 (enam)
kabupaten. Cadangan batubara di Provinsi Sumatera Selatan dengan status
terukur sebesar 19.843,68 juta ton, cadangan batubara dengan status
terunjuk sebesar 2.071,79 juta ton dan cadangan batubara dengan status
terekam sebesar 325 juta ton. Pengusahaan batubara di Provinsi Sumatera
Selatan terlihat sangat prospektif untuk masa-masa yang akan datang. Hal
ini dapat dilihat dari penjualan batubara yang memperlihatkan
kecenderungan naik dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Kenaikan
penjualan batubara terlihat signifikan seiring dengan peningkatan kebutuhan
Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 18
dimanfaatkan juga untuk memenuhi kebutuhan pabrik semen dan industri
lain (baja, smelter dan lain-lain).Pada tahun 2009 penjual batubara
mencapai 12.561.564 ton yang terdiri dari 7.547.714 ton dijual di dalam
negeri dan 4.416.311 ton dijual ke luar negeri.
4. Gas Metana(Coal Bed Methane/CBM)
Gas metana adalah gas yang terdapat didalam lapisan batubara. Pada
umumnya gas metana berasosiasi dengan gas CO2, N2 dan air. Wilayah
Provinsi Sumatera Selatan memiliki daerah prospektif seluas 20.000 km2 atau 27,03 % dari luas daerah prospektif di Indonesia. Sedangkan potensi
sumberdaya gas metana di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 120 TCF.
Gas metana dapat digunakan untuk keperluan gas domestik, pembangkit
listrik dan bahan baku untuk industri kimia. Peralatan dan infrastruktur yang
diperlukan dalam pemanfaatan gas metana adalah sama dengan yang
dipergunakan untuk gas bumi, sehingga di masa mendatang apabila gas
CBM telah diproduksi, maka dapat langsung disalurkan pada jaringan
pemipaan gas bumi yang telah tersedia.
5. Panas Bumi (Geothermal)
Panas bumi merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Energi
tersebut berasal dari magma yang mendidihkan air yang ada di dalam tanah,
kemudian uap air yang ada dapat diubah menjadi tenaga listrik. Energi ini
tidak menimbulkan limbah seperti minyak bumi dan batubara. Potensi panas
bumi di Provinsi Sumatera Selatan berada di 3 (tiga) kabupaten yaitu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Muara Enim dan Lahat. Potensi
panas bumi terbesar dan telah dikembangkan di Provinsi Sumatera Selatan
terdapat di Bukit Lumut Balai Kabupaten Muara Enim (835 MWe).
Berdasarkan manifestasi panas bumi di permukaan, lapangan Marga Bayur
dan Rantau Dedap mempunyai prospek untuk dikembangkan seperti
lapangan Lumut Balai. Akan tetapi, aksesibilitas menuju ke lokasi belum
memadai. Pengembangan lapangan-lapangan tersebut memerlukan
dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dan
kebijakan pemanfaatan energi terbarukan. Pemanfaatan energi panas bumi
sebagai salah satu sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan
tentunya akan mendukung program Lumbung Energi Nasional bagi
Sumatera Selatan, dan sekaligus mendukung pengembangan energi mix