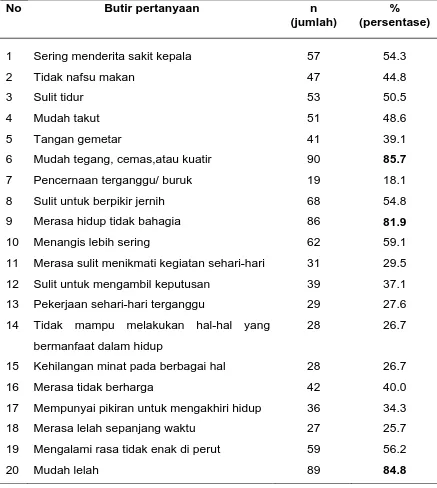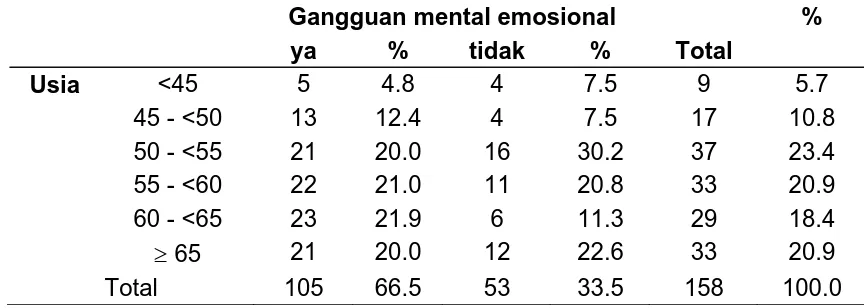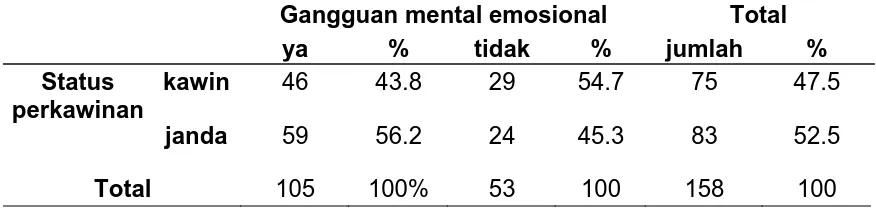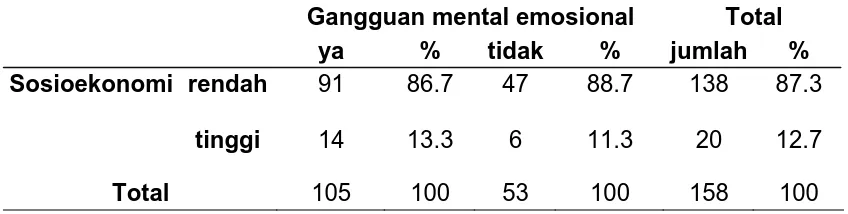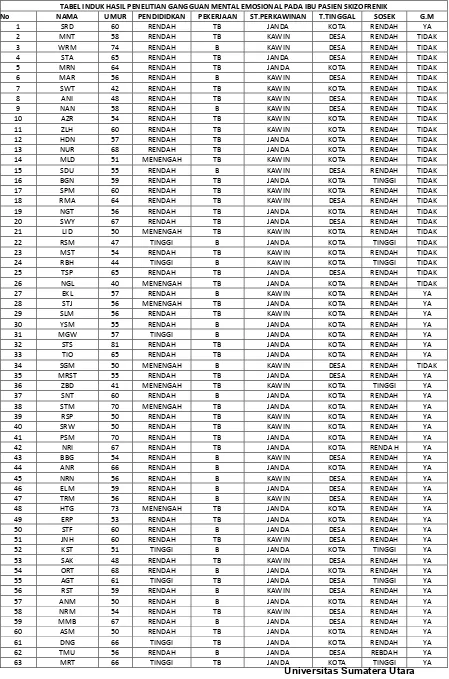GANGGUAN MENTAL EMOSIONAL PADA IBU DARI PASIEN
SKIZOFRENIK YANG BEROBAT KE POLIKLINIK PSIKIATRI
BLUD RSJ PROVINSI SUMATERA UTARA
TESIS
RINI GUSYA LIZA 107106004
PROGRAM MAGISTER KEDOKTERAN KLINIK – SPESIALIS ILMU KEDOKTERAN JIWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
GANGGUAN MENTAL EMOSIONAL PADA IBU DARI PASIEN
SKIZOFRENIK YANG BEROBAT KE POLIKLINIK PSIKIATRI
BLUD RSJ PROVINSI SUMATERA UTARA
TESIS
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kedokteran Klinik di Bidang Ilmu Kedokteran Jiwa / M. Ked (KJ) pada Fakultas Kedokteran
Universitas Sumatera Utara
RINI GUSYA LIZA 107106004
PROGRAM MAGISTER KEDOKTERAN KLINIK – SPESIALIS ILMU KEDOKTERAN JIWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
Judul Tesis : Gangguan Mental Emosional Pada Ibu dari Pasien Skizofrenik yang Berobat ke Poliklinik Psikiatri BLUD RSJ Provinsi Sumatera Utara
Nama Mahasiswa : Rini Gusya Liza Nomor Induk Mahasiswa : 107106004
Program Magister : Magister Kedokteran Klinik Konsentrasi : Ilmu Kedokteran Jiwa
Menyetujui :
Komisi Pembimbing :
Prof. dr.Bahagia Loebis, Sp.KJ (K)
Ketua Program Studi Ketua TKP PPDS Magister Kedokteran Klinik
Prof. dr. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K) dr. Zainuddin Amir, Sp.P(K) NIP: 19540620198011001
Telah diuji pada
Tanggal : 21 Januari 2012
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua : Prof. dr. Bahagia Loebis, Sp.KJ (K) ... .
Anggota : Prof. dr. M. Joesoef Simbolon, Sp.KJ (K) ...
PERNYATAAN
GANGGUAN MENTAL EMOSIONAL PADA IBU DARI PASIEN SKIZOFRENIK YANG BEROBAT KE POLIKLINIK PSIKIATRI
BLUD RSJ PROVINSI SUMATERA UTARA
TESIS
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis mengacu dalam naskah ini dan disebutkan di dalam daftar rujukan.
Medan, Januari 2012
UCAPAN TERIMAKASIH
Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena
atas berkah limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya maka penulisan tesis ini
dapat diselesaikan.
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang
sebesar-sebesarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis
selama mengikuti Program Magister Klinik - Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa.
Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah penulis menyampaikan
ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :
1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Dekan Fakultas kedokteran Universitas
Sumatera Utara, Ketua TKP PPDS-I dan Ketua Program Studi Magister
Kedokteran Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang
telah memberikan kepada penulis kesempatan untuk mengikuti Program
Magister Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu kedokteran Jiwa di Fakultas
Kedokteran Universitas Sumatera Utara.
2. dr. Mustafa Mahmud Amin, Sp.KJ, selaku Ketua Departemen Ilmu
Kedokteran Jiwa FK USU, sebagai guru dan pembimbing penulis dalam
penyusunan tesis ini yang telah membimbing, mengoreksi, dan memberi
masukan-masukan berharga kepada penulis sehingga tesis ini dapat
diselesaikan.
3. dr. Hj. Elmeida Effendy, Sp.KJ, selaku Ketua Program Studi PPDS-I Ilmu
Kedokteran Jiwa FK USU, sebagai guru yang telah banyak memberikan
bimbingan, pengarahan, dan memberi masukan-masukan yang berharga
4. Prof. dr. Bahagia Loebis, Sp.KJ (K), sebagai guru dan pembimbing penulis
dalam penyusunan tesis ini yang penuh kesabaran dan perhatian telah
membimbing, mengarahkan, memberikan dorongan dan masukan-masukan
yang berharga kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. dr. H Harun Taher Parinduri, Sp.KJ (K), selaku guru penulis, yang banyak
memberikan bimbingan, pengetahuan, dorongan serta pengarahan yang
berharga kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Alm. Prof. dr. H. Syamsir BS, Sp.KJ (K), selaku guru penulis, yang banyak
memberikan bimbingan, pengetahuan, dorongan serta pengarahan yang
berharga kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Prof. dr. H. M. Joesoef Simbolon, Sp.KJ (K), selaku guru penulis, yang
banyak memberikan bimbingan, pengetahuan, dorongan serta pengarahan
yang berharga kepada penulis selama penulis mengikuti Program magister
Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa.
8. dr. Juskitar, Sp.KJ, sebagai guru dan pembimbing penulis yang telah
banyak memberikan bimbingan, pengarahan, pengetahuan, dorongan,
dukungan dan buku- buku bacaan yang berharga selama penulis mengikuti
Program Magister Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa.
9. dr. Vita Camelia, Sp.KJ, sebagai guru yang telah banyak memberikan
bimbingan, pengarahan, pengetahuan, dorongan, dukungan dan buku- buku
bacaan yang berharga selama penulis mengikuti Program Pendidikan
Magister Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa.
10. dr. Muhammad Surya Husada, Sp.KJ, sebagai guru dan senior yang telah
dukungan dan buku-buku bacaan yang berharga selama saya mengikuti
Program Magister Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa.
11. dr. Dapot Parulian Gultom, Sp.KJ, sebagai Direktur Badan Layanan Umum
Daerah RSJ Propinsi Sumatera Utara dan guru penulis, yang telah
memberikan izin, kesempatan, fasilitas, dan pengarahan kepada penulis
selama mengikuti Program Magister Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu
Kedokteran Jiwa.
12. dr. Herlina Ginting, Sp.KJ, sebagai guru yang telah banyak memberikan
bimbingan dan pengetahuan serta dorongan selama penulis mengikuti
Program Magister Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa.
13. dr. Mawar Gloria Taringan, Sp.KJ, sebagai guru yang telah banyak
memberikan bimbingan dan pengetahuan serta dorongan selama penulis
mengikuti Program Magister Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran
Jiwa.
14. dr. Freddy S. Nainggolan, Sp.KJ, sebagai guru yang telah banyak
memberikan bimbingan, pengetahuan, dorongan, serta literatur-literatur
yang berharga selama penulis mengikuti Program Magister Kedokteran
Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa.
15. dr. Arlinda Sari Wahyuni, M.Kes, selaku staf pengajar Ilmu Kesehatan
Masyarakat / Ilmu Kedokteran Komunitas / Ilmu Kedokteran Pencegahan FK
USU dan konsultan metodologi penelitian dan statistik penulis dalam
penelitian ini, yang banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan
berdiskusi dengan penulis dalam penelitian ini.
16. dr. Donald F. Sitompul, Sp.KJ, dr. Hj. Sulastri Effendi, Sp.KJ, dr Rosminta
Siahaan, Sp.KJ, dr. Paskawani siregar, Sp.KJ, dr. Citra J. Taringan, Sp.KJ,
dan dr. Vera RB. Marpaung, Sp.KJ, sebagai senior yang telah memberikan
semangat dan dorongan selama penulis mengikuti Program Magister
Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa.
17. dr. Adhayani Lubis, Sp.KJ dr. Yusak P. Simanjuntak, Sp.KJ, dr. Juwita
Saragih, Sp.KJ, dr. Friedrich Lupini, Sp.KJ, dr. Rudyhard E. Hutagalung,
Sp.KJ, dr. Laila Sari, Sp.KJ, dr. Evalina Perangin-Angin, Sp.KJ, dr. Victor
Eliezer P, Sp.KJ, dr. Siti Nurul Hidayati, Sp.KJ, dr. Lailan Sapinah, Sp.KJ,
dr. Silvy Agustina Hasibuan, Sp.KJ, sebagai senior yang banyak
memberikan bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis selama
mengikuti program Magister Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran
Jiwa.
18. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Direktur
Rumah Sakit Tembakau Deli, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Pirngadi Medan atas izin, kesempatan dan dan fasilitas yang diberikan
kepada penulis untuk belajar dan bekerja selama penulis mengikuti Megister
Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa.
19. Rekan-rekan sejawat peserta PPDS-I Psikiatri FK USU: dr. Herny Taruli
Tambunan, M.Ked (KJ), dr. Mila Astari. H, M.Ked (KJ), dr. Ira Aini Dania,
M.Ked (KJ), dr. Baginda Harahap, M.Ked (KJ), dr. Muhammad Yusuf,
M.Ked (KJ), dr. Ricky Wijaya Tarigan, M.Ked (KJ), dr. Superida Ginting
Suka, dr. Lenni Crisnawati Sihite, dr. Saulina Dumaria Simanjuntak, M.Ked
(KJ), dr. Hanip Fahri, M.Ked (KJ), dr. Ferdinan Leo Sianturi, M.Ked (KJ), dr.
Andreas Xaverio Bangun, dr. Dian Budianti A, dr. Tiodoris Siregar, dr.
Nanda Sari Nuralita, dr.Wijaya Taufik Tiji, dr. Alfi Syahri Rangkuti, dr.
Agussyah Putra, dr. Gusri Girsang, dr. Dessi Wahyuni, dr. Ritha Mariati
Sembiring, dr. Reny Fransiska Barus, dr. Susiati, dr. Annisa Fransiska, dr.
Dessy Mawar Zalia, dr. Nazli Mahdinasari Nasution, dr. Andi Syahputra
Siregar, dr. Nining Gilang Sari, dr. Rossa Yunilda, dr. Arsusy Widyastuty,
yang banyak memberikan masukan berharga kepada penulis melalui
diskusi-diskusi kritis dalam berbagai pertemuan formal maupun informal,
serta selalu memberikan dorongan-dorongan yang membangkitkan
semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Program Magister
Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa.
20. Para perawat dan pegawai di berbagai tempat dimana penulis pernah
bertugas selama menjalani pendidikan spesialis ini, serta pasien, keluarga
pasien dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,
yang telah banyak membantu penulis dalam menjalani Program Magister
Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa.
21. Kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan sayangi, papa Amrizal
SAZ dan mama Erlisniati. K yang dengan penuh kesabaran, cinta serta
kasih sayangnya telah membesarkan, memberikan dorongan, dukungan
dalam segala hal kepada penulis, serta doa restu sejak lahir hingga saat ini.
22. Kedua mertua, papa Drs. M. Mukhtar dan mama Maidirni yang banyak
memberikan semangat dan doa kepada penulis selama menjalani program
Magister Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa.
23. Seluruh saudara kandung saya, Riche Ariza Valensia, Ridho Oktomi Tressia
kepada penulis selama menjalani Magister Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu
Kedokteran Jiwa.
24. Buat suami tercinta, Febri Andonal, SE, terima kasih atas segala doa dan
dukungan, kesabaran dan pengertian yang mendalam serta pengorbanan
atas segala waktu dan kesempatan yang tidak dapat penulis habiskan
bersama-sama dalam sukacita dan keriangan selama penulis menjalani
Magister Kedokteran Klinik Spesialis dan menyelesaikan tesis ini. Tanpa
semua itu, penulis tidak akan mampu menyelesaikan Program Magister
Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa dan tesis ini dengan baik.
Akhirnya penulis hanya mampu berdoa dan memohon semoga Allah
SWT memberikan rahmat-Nya kepada seluruh keluarga, sahabat, dan handai
tolan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, baik secara langsung
maupun tidak langsung yang telah banyak memberikan bantuan, baik moril
maupun materil, penulis ucapkan terimakasih.
Medan, Januari 2012
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG
DALYs : Disability Adjusted Life Years
DSM-IV-TR : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder - Fourth Edition - Text Revision
ICD-10 : International Classification of Disease - Tenth edition
Riskesdas : Riset Kesehatan Dasar
SD : Sekolah Dasar
SMP : Sekolah Menengah Pertama
SMA : Sekolah Menengah Atas
SPSS : Statistical Package Social Sciences
SRQ : Self Reporting Questionnaire
WHO : World Health Organization
< : Lebih Kecil Dari
> : Lebih Besar Dari
≥ : Lebih Besar Atau Sama Dengan
DAFTAR ISI
Lembar Persetujuan Pembimbing ... ii
Ucapan Terima Kasih ... v
Daftar Singkatan dan Lambang ... xi
Daftar Isi ... xii
2.1.4. Hubungan dengan faktor sosiodemografik 8
2.2. Skizofrenia suatu penyakit mental yang paling berat 12 2.2.1. Kriteria diagnostik ... 12
3.10. Definisi operasional ... 26
3.11. Izin subyek penelitian ... 28
3.12. Etika penelitian ... 28
BAB 4. HASIL PENELITIAN ... 30
4.1 Karakteristik demografi subjek penelitian ... 30
4.2. Proporsi gangguan mental emosional subjek penelitian ... 33
4.3. Proporsi gejala-gejala gangguan mental emosional subjek penelitian ... 34
4.4. Distribusi gangguan mental subjek penelitian berdasarkan status sosiodemografik ... 36
BAB 5. PEMBAHASAN ... 39
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN ... 44
6.1. Kesimpulan ... 44
6.2. Saran ... 44
BAB 7. RINGKASAN ... 45
DAFTAR PUSTAKA ... 46
Lampiran
1. Tabel Induk Hasil Penelitian
2. Lembaran Penjelasan Kepada Keluarga
3. Lembar Persetujuan Setelah Penjelasan (Informed Concent)
4. Data Dasar Subjek Peneltian
5. Kuesioner Penelitian
6. Surat Persetujuan Komite Etik
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Pertanyaan Self Reporting Questionnaire (SRQ) ... 19
Tabel 4.1 Distribusi subjek penelitian yang mengalami gangguan
mental emosional berdasarkan gejala yang banyak dialami ... 34
Tabel 4.2 Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian
berdasarkan usia ... 36
Tabel 4.3 Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian
berdasarkan tingkat pendidikan ... 36
Tabel 4.4 Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian
berdasarkan status pekerjaan ... 37
Tabel 4.5 Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian
berdasarkan tempat tinggal ... 37
Tabel 4.6 Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian
berdasarkan status perkawinan ... 37
Tabel 4.7 Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian
DAFTAR DIAGRAM
Diagram 4.1 Distribusi karakteristik demografik subjek penelitian
berdasarkan usia ... 30
Diagram 4.2 Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian
berdasarkan tingkat pendidikan ... 31
Diagram 4.3 Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian
berdasarkan status pekerjaan ... 31
Diagram 4.4 Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian
berdasarkan tempat tinggal ... 32
Diagram 4.5 Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian
berdasarkan status perkawinan ... 32
Diagram 4.6 Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian
berdasarkan status sosioekonomi ... 34
Diagram 4.7 Proporsi gangguan mental emosional pada subjek penelitian 34
Diagram 4.6 Distribusi gejala gangguan mental emosional pada subjek
ABSTRAK
Latar belakang: Skizofrenia memiliki dampak sosial dan ekonomi yang cukup
besar, dan juga menjadi beban berat bagi penderita dan keluarganya. Hal ini dapat menimbulkan gangguan mental emosional pada keluarga terutama ibu yang biasanya paling banyak merawat pasien.
Tujuan penelitian: untuk mengetahui proporsi gangguan mental emosional
dan mengidentifikasi gejala-gejala gangguan mental pada ibu dari pasien skizofrenik serta mengetahui distribusi gangguan mental emosional pada ibu pasien skizofrenik berdasarkan faktor sosiodemografik (usia, status perkawinan, tingkat pendidikan, status pekerjaan, tempat tinggal, status sosioekonomi)
Metode penelitian: Penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional study, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik nonprobability sampling jenis consecutive sampling, jumlah sampel 158 orang ibu dari pasien
skizofrenik, yang datang membawa anaknya berobat ke poliklinik psikiatri BLUD RSJ Provsu selama periode 1 September 2011 sampai 31 Oktober 2011. Kriteria inklusi adalah Ibu dari pasien yang didiagnosis skizofrenia sesuai DSM-IV-TR, bersedia sebagai subjek penelitian, mampu diajak berkomunikasi. Kriteria eksklusi adalah menderita penyakit medis umum dan mempunyai riwayat gangguan mental sebelumnya. Penilaian gejala gangguan jiwa dilakukan melalui wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan kuesioner self reporting quessionnaire (SRQ) yang terdiri dari 20 butir pertanyaan. Apabila menjawab minimal 6 jawaban “ya” maka responden diidentifikasi mengalami gangguan mental emosional.
Hasil penelitian: Karakteristik demografik yang paling banyak adalah pada
kelompok umur 50-<55 tahun (23.4%), pendidikan rendah (74.1%), tidak bekerja (60.8%), janda (52.5%), tempat tinggal di desa (57%) dan sosioekonomi rendah (87.5%). Proporsi gangguan mental emosional pada ibu dari pasien skizofrenik adalah (66.5%), sedangkan gejala mental emosional yang paling banyak dialami ibu dari pasien skizofrenik adalah gejala depresi.
Kesimpulan: Proporsi gangguan mental emosional maupun proporsi
gejala-gejala gangguan mental emosional pada ibu dari pasien skizofrenik lebih tinggi dibanding populasi umum di Indonesia sehingga diperlukan perhatian yang lebih baik kepada ibu dari pasien skizofrenik dalam pencegahan timbulnya gangguan mental yang lebih berat.
Kata kunci:
ABSTRAK
Latar belakang: Skizofrenia memiliki dampak sosial dan ekonomi yang cukup
besar, dan juga menjadi beban berat bagi penderita dan keluarganya. Hal ini dapat menimbulkan gangguan mental emosional pada keluarga terutama ibu yang biasanya paling banyak merawat pasien.
Tujuan penelitian: untuk mengetahui proporsi gangguan mental emosional
dan mengidentifikasi gejala-gejala gangguan mental pada ibu dari pasien skizofrenik serta mengetahui distribusi gangguan mental emosional pada ibu pasien skizofrenik berdasarkan faktor sosiodemografik (usia, status perkawinan, tingkat pendidikan, status pekerjaan, tempat tinggal, status sosioekonomi)
Metode penelitian: Penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional study, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik nonprobability sampling jenis consecutive sampling, jumlah sampel 158 orang ibu dari pasien
skizofrenik, yang datang membawa anaknya berobat ke poliklinik psikiatri BLUD RSJ Provsu selama periode 1 September 2011 sampai 31 Oktober 2011. Kriteria inklusi adalah Ibu dari pasien yang didiagnosis skizofrenia sesuai DSM-IV-TR, bersedia sebagai subjek penelitian, mampu diajak berkomunikasi. Kriteria eksklusi adalah menderita penyakit medis umum dan mempunyai riwayat gangguan mental sebelumnya. Penilaian gejala gangguan jiwa dilakukan melalui wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan kuesioner self reporting quessionnaire (SRQ) yang terdiri dari 20 butir pertanyaan. Apabila menjawab minimal 6 jawaban “ya” maka responden diidentifikasi mengalami gangguan mental emosional.
Hasil penelitian: Karakteristik demografik yang paling banyak adalah pada
kelompok umur 50-<55 tahun (23.4%), pendidikan rendah (74.1%), tidak bekerja (60.8%), janda (52.5%), tempat tinggal di desa (57%) dan sosioekonomi rendah (87.5%). Proporsi gangguan mental emosional pada ibu dari pasien skizofrenik adalah (66.5%), sedangkan gejala mental emosional yang paling banyak dialami ibu dari pasien skizofrenik adalah gejala depresi.
Kesimpulan: Proporsi gangguan mental emosional maupun proporsi
gejala-gejala gangguan mental emosional pada ibu dari pasien skizofrenik lebih tinggi dibanding populasi umum di Indonesia sehingga diperlukan perhatian yang lebih baik kepada ibu dari pasien skizofrenik dalam pencegahan timbulnya gangguan mental yang lebih berat.
Kata kunci:
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
Pada tahun 2000, World Health Organization (WHO) memperoleh data
gangguan mental pada penduduk dunia adalah sebesar 12%, tahun 2001
meningkat menjadi 13% dan diprediksi pada tahun 2015 menjadi 15%.1 Berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007, yang
menggunakan Self Reporting Questionnaire (SRQ) untuk menilai kesehatan
jiwa penduduk, prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk
Indonesia yang berumur ≥ 15 tahun sebesar 11.6%.
Skizofrenia merupakan gangguan mental yang paling berat. Risiko
seumur hidup sekitar 0.5-1%, dan karena awitannya dini dan kecenderungan
untuk kronik menyebabkan prevalensi penyakit ini relatif tinggi.
Ketidakmampuan terutama disebabkan oleh gejala negatif dan defisit kognitif,
merupakan gambaran yang memiliki dampak yang lebih besar pada fungsi
jangka panjang dibandingkan dengan waham dan halusinasi yang dramatis
serta sering menyebabkan kekambuhan. Dampak sosial dan ekonomi dari
penyakit tersebut cukup besar, dan dampak pada penderita dan keluarga
mereka cukup buruk.
2
3
Jauh sebelum didiagnosis skizofrenia, keluarga dari seseorang dengan
gangguan tersebut mungkin mulai merasa stres. Prodromal, atau tanda-tanda
awal skizofrenia dapat muncul beberapa tahun sebelum diagnosis dibuat.
Perubahan perilaku dapat menyebabkan banyak kecemasan, kekhawatiran,
atau rasa bersalah bagi anggota keluarga dari seseorang dengan skizofrenia.
Salah satu cara untuk mengetahui adanya gangguan mental emosional
pada seseorang yang memberikan data yang cukup baik dengan cara yang
relatif murah, mudah dan efektif adalah dengan menggunakan alat ukur Self
Reporting Questionnaire (SRQ). Dikatakan murah karena dapat dilakukan
dalam waktu yang cukup singkat serta tidak memerlukan sumber daya manusia
khusus untuk menilainya. Self Reporting Questionnaire efektif karena memiliki
validitas yang cukup baik dalam hal sensitivitas dan spesifitasnya.
4
Self Reporting Questionnaire adalah kuesioner yang dikembangkan oleh
WHO untuk penyaringan gangguan psikiatri dan keperluan penelitian yang
telah dilakukan diberbagai negara. Self Reporting Questionnaire banyak
digunakan di negara-negara yang sedang berkembang dan tingkat pendidikan
penduduknya masih rendah. Selain itu SRQ juga sangat cocok digunakan di
negara yang kebanyakan penduduknya berasal dari tingkat sosioekonomi
rendah. Self Reporting Questionnaire terdiri dari 20 pertanyaan, apabila
minimal menjawab 6 jawaban “ya”, maka responden dinilai memiliki gangguan
mental emosional. Selain itu melalui SRQ dapat diidentifikasi gejala-gejala
gangguan mental emosional baik itu gejala depresi, gejala ansietas, gejala
kognitif, gejala somatik maupun gejala penurunan energi.
5
Pada penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah ibu dari
pasien skizofrenik oleh karena ibu yang paling dekat dan paling banyak terlibat
dalam pengasuhan pasien mulai dari kehamilan, menyusui dan membesarkan
pasien.
1.2. Rumusan masalah
Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas dapat
dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:
a. Berapa proporsi gangguan mental emosional pada ibu dari pasien
skizofrenik.
b. Apa saja gejala gangguan mental emosional yang paling banyak dialami ibu
dari pasien skizofrenik
1.3. Tujuan penelitian
a. Tujuan umum: Untuk mengetahui proporsi gangguan mental emosional
pada ibu dari pasien skizofrenik dengan menggunakan kuesioner SRQ.
b. Tujuan khusus:
• Untuk mengetahui proporsi gejala-gejala gangguan mental emosional
yang dialami ibu dari pasien skizofrenik
• Untuk mengetahui gejala gangguan mental emosional yang paling
banyak dialami ibu dari pasien skizofrenik
• Untuk mengetahui distribusi gangguan mental emosional pada ibu
pasien skizofrenik berdasarkan faktor sosiodemografik (usia, status
perkawinan, tingkat pendidikan, status pekerjaan, tempat tinggal, status
1.4. Manfaat penelitian
a. Dapat diperoleh gambaran mengenai proporsi gangguan mental emosional
pada ibu pasien skizofrenik.
b. Dengan diperolehnya proporsi gangguan mental emosional pada ibu pasien
skizofrenik dapat memberikan masukan kepada tenaga kesehatan untuk
dapat mengantisipasi dan melakukan penanganan atau pengobatan pada
ibu pasien skizofrenik yang mengalami gangguan mental emosional agar
tidak semakin berat dan bisa meningkatkan kualitas hidup ibu pasien
skizofrenik.
c. Penelitian ini adalah penelitian penyaringan sehingga dapat dilanjutkan
untuk mendapatkan diagnosis gangguan mental emosional yang lebih
terperinci pada ibu dari pasien skizofrenik.
d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berlanjut untuk penelitian selanjutnya
atau yang sejenis atau penelitian lain yang memakai penelitian ini sebagai
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
Kesehatan mental adalah sama pentingnya dengan kesehatan fisik
dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, keduanya saling berkaitan, individu
dengan masalah kesehatan fisik sering mengalami kecemasan atau depresi
yang mempengaruhi respons mereka terhadap penyakit fisik. Individu dengan
penyakit mental dapat mengembangkan gejala-gejala fisik dan penyakit, seperti
penurunan berat badan dan ketidakseimbangan biokimia darah yang terkait
dengan gangguan makan. Perasaan, sikap dan pola pikir sangat
mempengaruhi pengalaman seseorang terhadap kesehatan fisik atau penyakit,
dan dapat mempengaruhi perjalanan penyakit dan efektivitas pengobatan.6
2.1. Gangguan mental emosional
2.1.1. Definisi
Gangguan mental emosional merupakan suatu keadaan yang
mengindikasikan individu mengalami suatu perubahan emosional yang dapat
berkembang menjadi keadaan patologis terus berlanjut sehingga perlu
dilakukan antisipasi agar kesehatan jiwa masyarakat tetap terjaga. Istilah lain
gangguan mental emosional adalah distres psikologik atau distres emosional.6 Gangguan mental ditandai dengan perubahan dalam berpikir, perilaku
atau suasana hati (atau beberapa kombinasinya) terkait dengan tekanan yang
bermakna dan gangguan fungsi selama jangka waktu tertentu. Gejala
gangguan mental bervariasi dari ringan sampai parah, tergantung pada jenis
perjalanan seumur hidup, setiap individu mengalami perasaan isolasi,
kesepian, tekanan emosional atau pemutusan. Ini biasanya normal, reaksi
jangka pendek terhadap situasi sulit, daripada gejala penyakit mental. Orang
belajar untuk mengatasi perasaan sulit hanya saat mereka belajar untuk
mengatasi situasi sulit. Pada beberapa kasus, durasi dan intensitas perasaan
menyakitkan atau pola membingungkan dari pikiran dapat serius mengganggu
kehidupan sehari-hari.7
2.1.2. Epidemiologi
Prevalensi gangguan mental pada populasi penduduk dunia menurut
World Health Organization (WHO) pada tahun 2000 memperoleh data
gangguan mental sebesar 12%, tahun 2001 meningkat menjadi 13% dan
diprediksi pada tahun pada tahun 2015 menjadi 15%. Sedangkan pada
negara-negara berkembang prevalensinya lebih tinggi. Prevalensi gangguan mental di
negara Amerika Serikat (6%-9%), Brazil (22.7%), Chili (26.7%), Pakistan
(28.8%) sedangkan di Indonesia hasil laporan Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) 2007, yang menggunakan SRQ untuk menilai kesehatan jiwa
penduduk, prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk Indonesia
yang berumur lebih dari 15 tahun sebesar 11.6%.
Gangguan mental dan perilaku yang tidak eksklusif untuk kelompok
tertentu, mereka ditemukan pada orang dari semua daerah, semua negara dan
semua masyarakat. Sekitar 450 juta orang menderita gangguan mental
menurut perkiraan WHO diberikan dalam Laporan Kesehatan Dunia 2001. Satu
dari empat orang akan mengembangkan satu atau lebih gangguan mental atau
perilaku selama hidup mereka. Gangguan mental dan perilaku terjadi pada
setiap titik waktu pada sekitar 10% dari populasi orang dewasa di seluruh
dunia. Seperlima dari remaja di bawah usia 18 tahun mengalami masalah
perkembangan, emosional atau perilaku, satu dari delapannya memiliki
gangguan mental, sedangkan pada anak-anak yang kurang beruntung angka
ini adalah satu dari lima. Gangguan neurologis dan mental terhitung 13% dari
keseluruhan Disability Adjusted Life Years (DALYs) dikarenakan semua
penyakit dan cedera di dunia. Lima dari sepuluh penyebab utama kecacatan di
seluruh dunia adalah kondisi kejiwaan, termasuk depresi, penggunaan alkohol,
skizofrenia dan kompulsif. Proyeksi memperkirakan pada tahun 2020 gangguan
neuropsikiatri akan mencapai 15% dari kecacatan di seluruh dunia, dengan
depresi unipolar sendiri terhitung 5.7% dari DALYs.
2.1.3. Gejala-gejala
9
Gangguan mental yang paling umum adalah gangguan ansietas dan
depresi. Dimana seseorang mengalami perasaan ketegangan, ketakutan, atau
kesedihan yang kuat dalam waktu bersamaan, gangguan mental timbul ketika
perasaan ini menjadi begitu mengganggu dan luar biasa, bahwa seseorang
memiliki kesulitan besar mengatasinya pada kegiatan hari-hari, seperti bekerja,
menikmati waktu luang, dan mempertahankan hubungan.10 Diantara gejala-gejala gangguan mental antara lain: perubahan suasana hati (mood), depresi,
kesedihan, pikiran bunuh diri, mudah marah, ansietas, panik, gangguan tidur,
stres, trauma, perilaku menghindar, kebingungan, kompulsif (tekanan),
gangguan selera makan, perilaku antisosial, penyangkalan, kelelahan,
ketakutan, kebohongan, gangguan seksual, preokupasi seksual, kesulitan
bicara, nyeri dan keluhan fisik, hiperaktivitas, kecemburuan, gangguan
preokupasi terhadap agama, obsesi, mania, euforia, impulsif, histerionik,
gangguan belajar, gangguan pencitraan tubuh, pemisahan diri dan
lain-lain.
Orang yang menderita salah satu dari gangguan mental yang berat
bermanifestasi dengan berbagai gejala yang dapat mencakup kecemasan yang
tidak beralasan, gangguan pikiran dan persepsi, disregulasi suasana hati, dan
disfungsi kognitif. Banyak dari gejala ini mungkin relatif spesifik untuk diagnosis
tertentu atau pengaruh budaya. Misalnya, gangguan pikiran dan persepsi
(psikosis) yang paling sering dikaitkan dengan skizofrenia. Demikian pula,
gangguan berat dalam ekspresi mempengaruhi dan regulasi suasana hati yang
paling sering terlihat dalam depresi dan gangguan bipolar. Namun, tidak jarang
untuk melihat gejala psikotik pada pasien yang didiagnosis dengan gangguan
mood atau suasana hati untuk melihat gejala yang berhubungan pada pasien
yang didiagnosis dengan skizofrenia. Gejala yang terkait dengan suasana hati,
kecemasan, proses berpikir, atau kognisi dapat terjadi pada setiap pasien
selama perjalanan penyakitnya.
11,12,13
13
2.1.4. Hubungan dengan faktor sosiodemografik
a. Hubungan jenis kelamin dengan gangguan mental emosional
Terlepas dari kemungkinan peran faktor biologis, yang mungkin
menjelaskan mengapa ada perbedaan seks konsisten pada risiko untuk
terjadinya gangguan mental yang umum dalam semua masyarakat, adalah
masuk akal bahwa jender (faktor tekanan yang cukup besar yang dihadapi oleh
berkembang, perempuan menanggung beban dari kemalangan yang terkait
dengan kemiskinan: sedikit akses ke sekolah, kekerasan fisik dari suami,
pernikahan paksa, perdagangan seksual, kesempatan kerja lebih sedikit dan,
dalam beberapa masyarakat, keterbatasan partisipasi mereka dalam kegiatan
di luar rumah.
b. Hubungan tingkat pendidikan dengan terjadinya gangguan mental emosional
8
Buta huruf atau miskin pendidikan merupakan faktor risiko yang
konsisten untuk gangguan mental umum. Beberapa penelitian juga
menunjukkan hubungan antara tingkat pendidikan dan risiko terjadinya
gangguan mental. Hubungan sebab akibat sepertinya bukan merupakan faktor,
karena pendidikan dasar terjadi di anak usia dini ketika gangguan mental yang
tidak umum terjadi. Hubungan antara tingkat pendidikan rendah dan gangguan
mental mungkin dikacaukan atau dijelaskan oleh sejumlah jalur: ini termasuk
status gizi buruk yang mana dapat merusak perkembangan intelektual, yang
mengarah ke tingkat pendidikan yang buruk dan buruknya perkembangan
psikososial. Risiko yang berhubungan dengan penghasilan rendah untuk
gangguan mental pada usia anak merupakan faktor terkuat untuk gangguan
perilaku, ini adalah terkait dengan kegagalan sekolah dan gangguan mental
yang umum di masa dewasa. Konsekuensi sosial dari pendidikan yang buruk
adalah jelas yaitu kurangnya pendidikan merupakan berkurang kesempatan.
c. Hubungan antara sosioekonomi dengan terjadinya gangguan mental 8
Banyak bukti-bukti dari negara-negara industri menunjukkan hubungan
mental yang umum adalah depresi dan kecemasan, gangguan yang
diklasifikasikan dalam International Classification of Disease- Tenth edition
(ICD-10) sebagai: "neurotik, stres-terkait dan gangguan somatoform "dan"
gangguan mood ". Pentingnya kesehatan masyarakat dari gangguan mental
dan perilaku yang ditunjukkan oleh fakta bahwa mereka salah satu penyebab
paling penting dari morbiditas di pelayanan kesehatan primer dan
menghasilkan ketidakmampuan yang cukup bermakna. Definisi kemiskinan
bervariasi tergantung pada sistem sosial, budaya dan politik di daerah tertentu
dan sesuai kepada pengguna data. Definisi orang miskin mengungkapkan
bahwa kemiskinan adalah sebuah fenomena sosial multidimensi. Dari
perspektif epidemiologi, kemiskinan berarti status sosial ekonomi rendah
(diukur dengan kelas sosial atau pendapatan), pengangguran dan tingkat
pendidikan yang rendah. Kemiskinan mungkin akan berhubungan dengan
malnutrisi, kurangnya akses ke air bersih, hidup di lingkungan tercemar,
perumahan tidak memadai, kecelakaan sering dan faktor risiko lain yang terkait
dengan kesehatan fisik yang buruk. Ada bukti menunjukkan komorbiditas
antara penyakit fisik dan gangguan mental yang umum, dan asosiasi ini
sebagian dapat menjelaskan hubungan antara kemiskinan dan gangguan
mental. Masalah kesehatan mental dan fisik menyebabkan peningkatan biaya
perawatan kesehatan dan memburuknya kemiskinan.
Penyelidikan epidemiologis di negara-negara berkembang banyak
menghubungkan tingginya tingkat gangguan mental dengan faktor-faktor
seperti diskriminasi, pengangguran dan hidup melalui periode perubahan sosial
yang cepat dan tak terduga. Penyidik di India yang baru-baru ini dilakukan
sebuah studi komunitas gangguan mental di daerah pedesaan, 20 tahun
setelah penelitian serupa di daerah yang sama, menemukan bahwa tingkat
keseluruhan gangguan mental tidak berubah. Namun, tingkat kategori
diagnostik tertentu telah berubah sehingga tingkat depresi meningkat dari 4,9%
menjadi 7.3% (P<0.01), yang disebabkan oleh efek dari perubahan gaya hidup.
Di Cina, peneliti menyarankan bahwa perubahan sosial (termasuk
meningkatnya prevalensi kerugian ekonomi utama bagi individu, peningkatan
biaya perawatan kesehatan, melemahnya ikatan keluarga, migrasi ke daerah
perkotaan untuk sementara atau kerja musiman, dan ketidaksetaraan
pendapatan) diduga menyebabkan meningkatnya angka bunuh diri, sebagian
karena pengaruhnya pada tingkat peningkatan gangguan depresi yang
sebagian besar tidak diobati.
d. Hubungan tempat tinggal dengan terjadinya gangguan mental emosional
8
Sebuah studi pada orang dewasa muda di daerah urbanisasi baru
(Khartoum, Sudan) menemukan bahwa gejala gangguan mental umum lebih
banyak terjadi di perkotaan daripada di daerah pedesaan. Faktor risikonya
adalah kesepian, ekspresi dari pengusiran, isolasi dan kurangnya dukungan
sosial yang terjadi ketika penduduk pedesaan bermigrasi dari keluarga dan
saudara-saudara mereka. Ada bukti bahwa faktor-faktor sosial, khususnya
peristiwa yang mengancam jiwa, kekerasan dan kurangnya dukungan sosial,
2.2. Skizofrenia suatu gangguan mental yang paling berat
Skizofrenia menimbulkan disfungsi sosial dan pekerjaan. Sejak awitan
penyakit, satu atau lebih fungsi utama seperti pekerjaan, hubungan
interpersonal dan perawatan diri secara bermakna berada di bawah tingkat
yang sebelumnya dapat diraih, atau apabila awitan pada usia anak dan remaja,
kegagalan untuk meraih tingkat yang diharapkan dari prestasi akademik,
interpersonal ataupun pekerjaan.14
2.2.1. Kriteria diagnostik
Kriteria diagnosis untuk skizofenia berdasarkan Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorder-Fourth Edition- Text Revision
(DSM-IV-TR) adalah sebagai berikut :
a. Gejala karakteristik : Dua (atau lebih) berikut, masing-masing ditemukan
untuk bagian waktu yang bermakna selama periode 1 bulan (atau kurang
jika diobati dengan berhasil):
15,16
1. Waham
2. Halusinasi
3. Bicara terdisorganisasi (kacau) (misalnya sering menyimpang atau
inkoheren)
4. Perilaku terdisorganisasi (kacau) atau katatonik yang jelas
5. Gejala negatif, yaitu pendataran afek, alogia, atau tidak ada kemauan
(avolition)
Catatan : Hanya satu gejala kriteria A yang diperlukan jika waham
terus-menerus mengomentari perilaku atau pikiran pasien, atau dua atau lebih
suara yang saling bercakap satu sama lain.
b. Disfungsi sosial atau pekerjaan : Untuk bagian waktu yang bermakna sejak
onset gangguan, satu atau lebih fungsi utama, seperti pekerjaan, hubungan
interpersonal, atau perawatan pribadi, adalah jelas dibawah tingkat yang
dicapai sebelum onset (atau jika onset pada masa anak-anak atau remaja,
kegagalan untuk mencapai tingkat pecapaian interpersonal, akademik, atau
pekerjaan yang diharapkan).
c. Durasi : Tanda gangguan terus-menerus menetap selama sekurangnya 6
bulan. Periode 6 bulan ini harus termasuk sekurangnya 1 bulan gejala (atau
kurang jika diobati dengan berhasil) yang memenuhi kriteria A (yaitu, gejala
fase aktif) dan mungkin termasuk periode gejala prodromal atau residual.
Selama periode prodromal atau residual, tanda gangguan mungkin
dimanifestasikan hanya oleh gejala negatif atau dua atau lebih gejala yang
dituliskan dalam kriteria A dalam bentuk yang diperlemah (misalnya,
keyakinan yang aneh, pengalaman persepsi yang tidak lazim).
d. Penyingkiran gangguan skizoafektif dan gangguan mood : Gangguan
skizoafektif dan gangguan mood dengan ciri psikotik telah disingkirkan
karena : (1) tidak ada episode depresif berat, manik, atau campuran yang
telah terjadi bersama-sama dengan gejala fase aktif ; atau (2) jika episode
mood telah terjadi selama gejala fase aktif, durasi totalnya adalah relatif
singkat dibandingkan durasi periode aktif dan residual.
e. Penyingkiran zat atau kondisi medis umum : Gangguan tidak disebabkan
oleh efek fisiologis langsung dari suatu zat (misalnya, obat yang
f. Hubungan dengan gangguan perkembangn pervasif : Jika terdapat riwayat
adanya gangguan autistik atau gangguan perkembangan pervasif lainnya,
diagnosis tambahan skizofrenia dibuat hanya jika waham atau halusinasi
yang menonjol juga ditemukan untuk sekurangnya satu bulan (atau kurang
jika diobati secara berhasil)
2.2.2. Dampak terhadap keluarga
Anggota keluarga dari penderita skizofrenia mengalami banyak stres
setiap hari. Pasien skizofrenia menjadi prioritas. Anggota keluarga selalu
khawatir akan kekambuhan dan berusaha menjaga orang yang mereka cintai
agar tetap sehat. Sayangnya, keluarga juga harus khawatir tentang keuangan
mereka karena mereka mungkin membiayai rumah sakit atau biaya
pengobatan yang tinggi. Keluarga dari pasien skizofrenia selalu waspada untuk
setiap perubahan dalam perilaku pasien. Karena terbebani dengan khawatir
tentang orang yang dicintai, anggota keluarga pasien skizofrenia dapat
mengabaikan kebutuhan mereka sendiri dan menjadi depresi dan cemas.
Dalam rangka untuk mencegah pengasuh yang "kelelahan," maka penting
bahwa anggota keluarga menemukan dukungan untuk mereka sendiri.4
Keluarga dari pasien skizofrenia mengalami pengalaman negatif oleh
efek dari stigma yang terkait dengan penyakit mental. Dalam masyarakat kita,
penyakit mental kadang-kadang ditafsirkan sebagai tanda kelemahan.
Beberapa orang masih percaya skizofrenia disebabkan oleh pengasuhan anak
yang buruk dan merupakan kesalahan keluarga. Lainnya berpikir bahwa sakit
mental hanya perlu untuk "mendapatkan lebih" dan melanjutkan hidup mereka.
yang dicintai. Penyakit mental berbeda dari penyakit fisik. Ketika anda melihat
orang-orang yang sakit secara fisik, anda akan menawarkan untuk membantu
mereka dengan membuka pintu atau membawa belanjaan mereka. Anda
berasumsi bahwa penyakit mereka bukan karena kesalahan mereka. Penyakit
mental, terutama skizofrenia, biasanya hanya menjadi jelas bagi orang lain
karena seseorang bertindak "ganjil". Bukannya mencoba untuk membantu,
kebanyakan orang malah menjaga jarak dan ingin mengabaikan orang dengan
skizofrenia. Akibatnya, perawat penderita skizofrenia dapat diasingkan dan
dibuat merasa bersalah dan sendirian.
Untuk menghindari kewalahan dengan tanggung jawab dari merawat
seseorang dengan skizofrenia, pengasuh mendesak untuk bergabung dengan
kelompok pendukung. Sebuah kelompok pendukung menyediakan forum untuk
anggota keluarga untuk berbagi perasaan mereka tentang memiliki seorang
keluarga penderita skizofrenia. Selain itu, pengasuh didorong untuk
mendapatkan waktu pribadi jauh dari keluarga mereka. Latihan, kunjungan rutin
keluar dari rumah, dan bahkan berpergian pada akhir pekan dapat memberikan
hiburan yang baik dari stres karena berurusan dengan seseorang dengan
penyakit mental. Ironisnya, merawat seorang keluarga penderita skizofrenia
dapat meningkatkan kemungkinan seorang pengasuh akan mengembangkan
gejala penyakit mental. Depresi, kecemasan, penyalahgunaan alkohol dan obat
adalah biasa untuk orang yang merawat keluarga dengan skizofrenia.
4
2. 3. Self Reporting Questionnaire (SRQ) 2.3.1. Latar belakang
Peneliti menunjukan gangguan mental umum terjadi diantara pasien
medis umum tapi sering tidak teridentifikasi, tidak diobati dan tidak dirujuk.
Diperkirakan setidaknya 500 juta orang di dunia menderita gangguan mental,
dan hanya sedikit yang mendapat penanganan yang baik. Pada banyak negara
berkembang, hanya sedikit terdapat tenaga terlatih dan dokter spesialis psikiatri
terbatas pada kota-kota besar.
2.3.2. Sejarah
4
Pada mulanya, SRQ terdiri dari 25 pertanyaan, 20 pertanyaan berhubungan
dengan gejala-gejala neurotik, 4 pertanyaan mengenai gejala-gejala psikotik
dan satu pertanyaan mengenai “serangan tiba-tiba”, ini disebut SRQ-25. Pada
SRQ-20 hanya terdapat butir-butir neurotik, alasannya adalah sebagai berikut:
a. Beberapa pasien dengan psikosis fungsional datang dengan sendirinya
ke fasilitas kesehatan primer untuk meminta bantuan;
4
b. Untuk menggapai pasien psikotik biasanya membutuhkan pencarian
kasus yang lebih aktif oleh tenaga kesehatan primer dalam masyarakat;
c. Kebutuhan untuk “butir psikotik” untuk mendeteksi psikosis diragukan
(sering, pasien mudah untuk dikenali sedang mengalami gangguan
psikotik, dan pada hampir semua keadaan, pasien psikotik tidak sadar
dengan kondisinya, karenanya menggunakan kuesioner mungin tidak
tepat);
d. Perlengkapan psikometrik dari kuesioner ini (sensitifitas dan
Self Reporting Questionnaire telah dikembangkan oleh WHO sebagai suatu
alat yang dirancang untuk menyaring gangguan psikiatri pada pusat pelayanan
kesehatan primer, terutama untuk negara berkembang. Penggunaaan SRQ
sebagai alat penyaring atau lebih tepatnya sebagai alat pencari kasus, tidak
terbatas pada pusat pelayanan kesehatan primer. Penggunaan SRQ bervariasi
dari penelitian pada orang lanjut usia di Afrika Selatan ke penelitian pada
keluarga penderita skizofrenia di klinik psikiatri di Malaisya.
Selain dalam bahasa Inggris, SRQ juga digunakan dalam bahasa Afrika,
bahasa Arab, bahasa Malaisya, bahasa Bengali, bahasa Filipina, bahasa
Perancis, bahasa Hindi, bahasa Italia, bahasa Portugis, bahasa Somali, bahasa
Spanyol dan lain-lain.
4
4
2.3.3. Skoring
Self Reporting Questionnaire terdiri dari 20 pertanyaan yang harus
dijawab dengan “ya” atau “tidak”. Ini bisa diisi sendiri atau dilakukan dengan
wawancara kepada responden. Berbagai pertanyaan tambahan telah
digunakan dengan SRQ-20, untuk menyaring gangguan psikotik dan
penyalahgunaan zat.4
Masing-masing dari 20 butir diberi skor 0 atau 1. Skor 1 menyatakan
bahwa gejala-gejala itu ada dalam sebulan terakhir, skor 0 menyatakan gejala
tersebut tidak ada. Skor maksimum adalah 20 Pada Self Reporting
Questionnaire (SRQ) mengandung butir pertanyaan mengenai gejala yang
lebih mengarah kepada neurosis. Gejala depresi terdapat pada butir nomor 6,
somatik pada butir nomor 1, 2, 7, 19; gejala kognitif pada butir nomor 8, 12, 13
dan gejala penurunan energi pada butir nomor 8, 11, 12, 13, 18, 20.
SRQ-20 merupakan suatu alat dengan 20 pertanyaan yang menanyakan
kepada responden tentang gejala-gejala dan masalah-masalah yang sering
muncul pada orang-orang dengan gangguan neurosis. Hasil dari semua
penelitian yang tersedia menggunakan SRQ-20 sejak tahun 1994. Selanjutnya,
para peneliti yang berencana untuk membuat penelitian menggunakan alat
penyaring gangguan mental mereka cendrung untuk tertarik untuk
menggunakan alat psikometrik. Sejak SRQ adalah alat yang telah terbukti
validitas dan reabilitasnya, ini menjadi bernilai bagi mereka.
4
4
2.3.4. Validitas
Uji validitas menunjukan seberapa baik suatu tes mengukur apa yang
ingin diukur. SRQ telah diuji untuk validitasnya pada rangkaian penelitian
antara tahun 1978 sampai dengan 1993. Aspek-aspek validitasnya antara lain:
1. Face validity (validitas muka)
4
2. Content validity (validitas isi)
3. Criterion validity (validitas ukuran/ kriteria)
4. Construct validity (validitas konsep)
2.3.5. Sensitivitas dan spesifisitas
Pendekatan yang umum untuk mengukur validitas ukuran pada alat uji
klinis adalah penggunaan indeks validitas seperti sensitivitas dan spesifisitas.
Dari beberapa penelitian sensitivitas SRQ berkisar antara 62.9% sampai 90%
indeks validitas ini menggaris-bawahi fakta bahwa alat skrining ini butuh untuk
divalidasi pada berbagai tempat dengan populasi yang berbeda.
Tabel 1.1. Pertanyaan Self Reporting Questionnaire (SRQ) 4
Dikutip dari: World Health Organization. User guides to the self reporting
2.4. Kerangka konseptual
Pasien skizofrenik
Ibu dari pasien skizofrenik
Faktor sosiodemografik
- Usia
- Status perkawinan
- Tingkat pendidikan
- Status pekerjaan
- Tempat tinggal
- Status sosioekonomi
Gejala gangguan mental emosional
• gejala somatik
• gejala depresi
• gejala ansietas
• gejala kognitif
• gejala penurunan energi
BAB 3. METODE PENELITIAN
3.1. Desain penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan cross
sectional.
3.2. Tempat dan waktu
1. Tempat penelitian: Poliklinik Psikiatri BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi
Sumatera Utara
2. Waktu penelitian : 1 September 2011 – 31 Oktober 2011
3.3. Populasi penelitian
1. Populasi target : Ibu dari pasien skizofrenik skizofrenik yang datang
membawa anaknya berobat ke BLUD RSJ Provinsi Sumut
2. Populasi terjangkau : Ibu dari pasien skizofrenik yang datang membawa
anaknya berobat ke BLUD RSJ Provinsi Sumut selama periode 1
September – 31 Oktober tahun 2011
3.4. Sampel dan cara pemilihan sampel
1. Sampel penelitian : Ibu dari pasien skizofrenik yang memenuhi kriteria
inklusi.
2. Cara pengambilan sampel dengan non probability sampling jenis
3.5. Perkiraan besar sampel
Besar sampel diukur dengan menggunakan rumus:
Keterangan:
18,19
�
=
� ∝
2��
�
2• n = jumlah sampel
• ∝
• z ∝ = nilai distribusi normal baku dari tabel Z yang besarnya tergantung
pada nilai α yang ditentukan; untuk nilai α = 0,05 Zα = 1,96 = kesalahan tipe I : 0,05 derajat kepercayaan 95%
• � = proporsi di populasi (proporsi gangguan mental emosional di
populasi adalah 11,6%
• � = 1-p
• d = presisi (kesalahan yang masih dapat di toleransi) 5 %
•
n =
1,962x0,116x0,8860,052
n = 157,9
Dengan menggunakan rumus diatas didapatkan jumlah sampel minimal
adalah: 158 orang.
3.6. Kriteria inklusi dan eksklusi Kriteria inklusi
1. Ibu kandung dari pasien yang didiagnosis skizofrenia sesuai dengan
kriteria DSM-IV-TR
2. Tinggal bersama pasien, menjaga dan merawat pasien
Kriteria eksklusi
1. Menderita penyakit medis umum
2. Gangguan psikiatri sebelumnya
3.7. Cara kerja
- Ibu dari pasien skizofrenik yang memenuhi kriteria inklusi mengisi
persetujuan secara tertulis setelah mendapatkan penjelasan yang
terperinci dan jelas untuk ikut serta dalam penelitian.
- Selanjutnya subyek penelitian akan diberikan kuesioner Self Reporting
Questionnaire (SRQ) yang terdiri dari 20 butir pertanyaan kemudian
subjek penelitian mengisi kuesioner tersebut, bagi subjek penelitian yang
tidak bisa baca tulis maka dilakukan wawancara langsung kepada subjek
penelitian dengan menggunakan kuesioner SRQ. Dan bagi subjek
penelitian yang tidak mengerti bahasa Indonesia akan di bantu oleh
paramedis yang mengerti bahasa daerah yang digunakan subjek
penelitian tersebut.
- Pada kuesioner juga terdapat isian mengenai karakteristik
sosiodemografik (usia, status perkawinan, status pekerjaan, tingkat
pendidikan, tempat tinggal dan status sosioekonomi) yang dapat diisi
langsung oleh subjek penelitian atau melalui wawancara.
- Setelah kuesioner diisi lengkap, kuesioner dikembalikan kepada peneliti.
- Jumlah kuesioner yang akan diisi adalah sebanyak 158 buah kepada
158 subjek penelitian sesuai dengan besar sampel penelitian.
- Dalam ini penelitian dilakukan penilaian terhadap jawaban pasien
dimana apabila menjawab minimal 6 jawaban “ya” maka pasien
- Selain itu diidentifikasi gejala-gejala gangguan mental emosional dimana
terdiri dari gejala somatik, gejala depresi, gejala ansietas, gejala kognitif
dan gejala penurunan energi.
- Setelah semua kuesioner diisi dilakukan pengolahan data dilakukan
editing, koding, histogram dan tabulasi.
3.8. Identifikasi variabel
Variabel penelitian adalah :
- usia, skala ukur: interval, alat ukur: kuesioner
- status perkawinan, skala ukur: nominal,alat ukur kuesioner
- status pekerjaan, skala ukur: nominal, alat ukur: kuesioner
- tingkat pendidikan, skala ukur: ordinal, alat ukur: kuesioner
- tempat tinggal, skala ukur: nominal, alat ukur: kuesioner
- status sosioekonomi, skala ukur: ordinal, alat ukur: kuesioner
- gangguan mental emosional Ibu dari pasien skizofrenik , skala ukur:
ordinal, alat ukur SRQ
- gejala gangguan mental emosinal, skala ukur: nominal, alat ukur:
3.9. Kerangka operasional
Self Reporting Questionaire Inklusi
Ibu dari pasien skizofrenik (Skizofrenia sesuai DSM – IV
–TR)
Eksklusi
Gangguan mental emosional
Faktor sosiodemografik
- Usia
- Status perkawinan
- Tingkat pendidikan
- Status pekerjaan
- Tempat tinggal
- Status sosioekonomi
Tidak Ya
Gejala gangguan mental emosional
• gejala somatik
• gejala depresi
• gejala ansietas
• gejala kognitif
3.10. Definisi operasional
• Gangguan metal emosional merupakan suatu keadaan yang
mengindikasikan individu mengalami suatu perubahan emosional yang
dapat berkembang menjadi keadaan patologis terus berlanjut sehingga
perlu dilakukan antisipasi agar kesehatan jiwa masyarakat tetap terjaga.
Istilah lain gangguan mental emosional adalah distres psikologik atau
distres emosional.
• Pasien yang didiagnosis skizofrenia sesuai dengan DSM-IV-TR
• Ibu pasien skizofrenik adalah ibu kandung pasien yang sehari-hari merawat,
menjaga dan tinggal bersama pasien
• Self Reporting Questionnaire (SRQ) merupakan adalah kuesioner yang
dikembangkan oleh WHO untuk skrining gangguan psikiatri dan keperluan
penelitian. SRQ terdiri dari 20 pertanyaan, apabila minimal menjawab 6
jawaban “ya” , maka responden diidentifikasi memililki gangguan mental
emosional.
- Ya : mengalami gangguan mental emosional (Jawaban Ya≥ 6)
- Tidak : tidak mengalami gangguan mental emosional (Jawaban Ya
< 6)
• Identifikasi gejala-gejala gangguan mental emosional menggunakan Self
Reporting Questionnaire (SRQ) yang terdiri 20 butir pertanyaan yang lebih
mengarah kepada neurosis, terdiri dari:
- Gejala depresi terdapat pada butir nomor 6, 9,10, 14, 15, 16, 17;
- Gejala ansietas terdapat pada butir nomor 3, 4, 5;
- Gejala somatik pada butir nomor 1, 2, 7, 19;
- Gejala penurunan energi pada butir nomor 8, 11, 12, 13, 18, 20.
• Status perkawinan : kawin, janda
• Pekerjaan : bekerja dan tidak bekerja • Tempat tinggal : di desa dan di kota
• Usia adalah lamanya hidup sejak lahir yang dinyatakan dalam satuan tahun.
Usia dibagi dalam :
- < 45
- 45 - < 50
- 50 - < 55
- 55 - < 60
- 60 - < 65
- ≥ 65
• Pendidikan : Jenjang pengajaran yang telah diikuti atau sedang dijalani
responden melalui pendidikan formal :
- Pendidikan tinggi: Tamat akademi atau perguruan tinggi
- Pendidikan sedang: Sekolah Menengah Atas (SMA)
- Pendidikan rendah: Tidak sekolah, tamat Sekolah Dasar (SD) atau
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
• Status sosioekonomi: rendah dan tinggi
- Rendah: pasien berobat menggunakan jamkesmas, askeskin dan
memenuhi batas kriteria miskin menurut BPS untuk daerah pedesaan
adalah Rp 72.780,00 /kapita/bulan sedangkan untuk daerah
perkotaan Rp 96.959,00 /kapita/bulan. Pendapatan perkapita adalah
jumlah pendapatan keluarga dalam satu bulan dibagi dengan jumlah
- Tinggi: pendapatan perkapita melebihi kriteria miskin menurut BPS.
3. 11. Izin subjek penelitian
Semua subjek penelitian akan diminta persetujuan dari keluarga terdekat
yang terlebih dahulu diberi penjelasan sebelum diikutsertakan sebagai subjek
penelitian.
3.12. Etika penelitian
Penelitian ini telah disetujui oleh Komite Etika penelitian di Fakultas
Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan.
3.13. Pengolahan data
Setelah data dikumpulkan, dilakukan pengolahan data dengan tahap-tahap
sebagai berikut :
a. Editing
13
Editing merupakan langkah untuk meneliti kelengkapan data yang
diperoleh melalui wawancara. Editing dilakukan pada setiap daftar pertanyaan
yang sudah diisi. Editing meliputi kelengkapan pengisian, kesalahan pengisian,
konsistensi, dan relevansi dari setiap jawaban yang diberikan. Editing dilakukan
di lapangan. Peneliti mengumpulkan dan memeriksa kembali kelengkapan
jawaban dari kuesioner yang diberikan. Hasil editing didapatkan semua data
terisi lengkap dan benar.
b. Koding
Adalah usaha untuk mengklasifikasikan jawaban yang ada menurut
dengan kode berupa angka. Selanjutnya kode tersebut dimasukkan dalam tabel
kerja untuk mempermudah dalam pembacaan.
d. Histogram
Adalah kegiatan memasukkan data-data hasil penelitian ke dalam
diagram berbentuk batang berdasarkan variabel yang diteliti yaitu tabel usia,
tingkat pendidikan, status perkawinan, status pekerjaan, tempat tinggal dan
status sosioekonomi, proporsi gangguan mental emosonal.
c. Tabulasi
Adalah kegiatan memasukkan data-data hasil penelitian ke dalam tabel
berdasarkan variabel yang diteliti yaitu tabel distribusi gangguan mental
emosional berdasarkan usia, tingkat pendidikan, status perkawinan, status
pekerjaan, tempat tinggal dan status sosioekonomi dan gejala-gejala gangguan
BAB 4. HASIL PENELITIAN
Telah dilakukan penelitian dengan kepada 158 orang ibu dari pasien
skizofrenik yang datang berobat ke Poliklinik Psikiatri BLUD RS Jiwa Provinsi
Sumatera Utara dari tanggal 1 September 2011 sampai tanggal 31 Oktober
2011.
4.1. Karakteristik demografik subjek penelitian
Karakteristik demografi subjek penelitian didapatkan:
Diagram 4.1. Distribusi karakteristik demografik subjek penelitian berdasarkan usia
Dari diagram di atas usia subjek penelitian terbanyak adalah usia 50-<55
tahun yaitu sebanyak 37 orang (23.4%).
Diagram 4.2. Distribusi karakteristik demografik subjek penelitian berdasarkan tingkat pendidikan
Dari diagram di atas tingkat pendidikan subjek penelitian terbanyak
adalah tingkat pendidikan rendah yaitu sebanyak 117 orang (74.1%).
Diagram 4.3. Distribusi karakteristik demografik subjek penelitian berdasarkan status pekerjaan
Dari diagram di atas status pekerjaan subjek penelitian terbanyak adalah
tidak bekerja yaitu sebanyak 96 orang (60.8%).
Diagram 4.4. Distribusi karakteristik demografik subjek penelitian berdasarkan status perkawinan
Dari diagram di atas status perkawinan subjek penelitian terbanyak
adalah janda yaitu sebanyak 83 orang (52.5%).
Diagram 4.5. Distribusi karakteristik demografik subjek penelitian berdasarkan tempat tinggal
Dari diagram di atas tempat tinggal subjek penelitian terbanyak adalah di
desa yaitu sebanyak 90 orang (57%).
Diagram 4.6. Distribusi karakteristik demografik subjek penelitian berdasarkan status ekonomi
Dari diagram di atas status sosioekonomi subjek penelitian terbanyak
adalah rendah yaitu sebanyak 138 orang (87.3%).
4.2. Proporsi gangguan mental emosional subjek penelitian
Dengan menggunakan kuesioner SRQ didapatkan proporsi gangguan
mental emosional subjek penelitian:
Dari diagram diatas dapat dilihat proporsi ganggauan mental emosional
pada subjek penelitian adalah adalah 105 orang (66.5 %).
4.3. Proporsi gejala-gejala gangguan mental emosional subjek penelitian
Table 4.1. Distribusi subjek penelitian yang mengalami gangguan mental emosional berdasarkan gejala yang banyak dialami
No Butir pertanyaan n
11 Merasa sulit menikmati kegiatan sehari-hari 31 29.5
12 Sulit untuk mengambil keputusan 39 37.1
13 Pekerjaan sehari-hari terganggu 29 27.6
14 Tidak mampu melakukan hal-hal yang
bermanfaat dalam hidup
28 26.7
15 Kehilangan minat pada berbagai hal 28 26.7
16 Merasa tidak berharga 42 40.0
17 Mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup 36 34.3
18 Merasa lelah sepanjang waktu 27 25.7
19 Mengalami rasa tidak enak di perut 59 56.2
20 Mudah lelah 89 84.8
Dari tabel di atas dapat dilihat gejala mental emosional yang paling
%), merasa hidup tidak bahagia (81.9%), mudah lelah (84.8%) mengalami rasa
tidak enak di perut (56.2%), sulit untuk berpikir jernih (54.8%), sering sakit
kepala (54.3%) dan sulit tidur (50.5%)., sedangkan gejala mental emosional
yang paling sedikit dialami responden adalah: merasa lelah sepanjang waktu
(25.7%) dan pencernaan terganggu (18.1%).
Dari tabel di atas dapat di dapatkan distribusi gejala gangguan mental
emosional garis sebagai berikut:
Diagram 4.8. Distribusi gejala gangguan mental emosional pada subjek penelitian
Dari diagram di atas kelompok gejala mental emosional terbanyak
adalah gejala depresi (50.6%).
50,6
( gejala gangguan mental emosional) frekuensi
4.4. Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian berdasarkan status sosiodemografik
Tabel 4.2. Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian berdasarkan usia
Gangguan mental emosional
Dari tabel di atas didapatkan proporsi gangguan mental emosional pada
ibu pasien skizofrenik terbanyak pada ibu berusia 60-<65 tahun yaitu 23 orang
(21.9%). Sedangkan proporsi terkecil gangguan mental emosional pada ibu
yang berusia <45 tahun yaitu 5 orang (4.8%).
Tabel 4.3. Distribusi gangguan mental emosional responden berdasarkan tingkat pendidikan
Gangguan mental emosional Total
ya % tidak % jumlah %
Dari tabel di atas didapatkan proporsi gangguan mental emosional pada
ibu pasien skizofrenik terbesar pada ibu dengan tingkat pendidikan rendah yaitu
75.2%. Sedangkan proporsi terkecil gangguan mental emosional pada ibu
Tabel 4.4 Distribusi gangguan mental emosional responden berdasarkan status pekerjaan
Dari tabel di atas didapatkan proporsi gangguan mental emosional pada
ibu pasien skizofrenik lebih besar pada ibu yang tidak bekerja yaitu 60.0 %
dibandingkan dengan ibu yang bekerja yaitu 40.0%.
Tabel 4.5 Distribusi gangguan mental emosional responden berdasarkan tempat tinggal
Dari tabel di atas didapatkan proporsi gangguan mental emosional pada
ibu pasien skizofrenik lebih besar pada ibu yang tinggal di desa yaitu 56.2 %
dibandingkan dengan ibu yang tinggal di kota yaitu 43.8%.
Tabel 4.6 Distribusi gangguan mental emosional responden berdasarkan status perkawinan
Gangguan mental emosional Total
ya % tidak % jumlah %
Gangguan mental emosional Total
ya % tidak % jumlah %
Tempat tinggal desa 59 56.2 31 58.5 90 57.0
kota 46 43.8 22 41.5 68 43.0
Total 105 100 53 100 158 100
Gangguan mental emosional Total
Dari tabel di atas didapatkan proporsi gangguan mental emosional pada
ibu pasien skizofrenik lebih besar pada ibu dengan status perkawinannya janda
yaitu 56.2 % dibandingkan dengan ibu dengan status perkawinannya kawin
yaitu 43.8%.
Tabel 4.7 Distribusi gangguan mental emosional responden berdasarkan status sosioekonomi
Dari tabel di atas didapatkan proporsi gangguan mental emosional pada
ibu pasien skizofrenik lebih besar pada ibu dengan status sosioekonomi rendah
yaitu 86.7 % dibandingkan dengan ibu dengan status sosioekonomi tinggi yaitu
13.3%.
Gangguan mental emosional Total
ya % tidak % jumlah %
Sosioekonomi rendah 91 86.7 47 88.7 138 87.3
tinggi 14 13.3 6 11.3 20 12.7
BAB 5. PEMBAHASAN
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan
cross-sectional. Didapatkan hasil penelitian yaitu proporsi gangguan mental
emosional pada ibu pasien skizofrenik yaitu 66.5 %. Hal ini lebih tinggi
dibandingkan hasil penelitian Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007
mendapatkan prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk
Indonesia yang berumur ≥ 15 tahun sebesar 11.6%.2
Gejala gangguan mental emosional yang paling banyak dialami ibu dari
pasien skizofrenik adalah mudah tegang, cemas dan kuatir (85.7%), merasa
hidup tidak bahagia (81.9%), mudah lelah (84.8%) mengalami rasa tidak enak
di perut (56.2%), sulit untuk berpikir jernih (54.8%), sering sakit kepala (54.3%)
dan sulit tidur (50.5%). Hasil ini hampir sama dengan gejala mental emosional
yang dialami penduduk Indonesia hasil penelitian oleh S.Idaiani dan
kawan-kawan tahun 2009, mendapatkan gejala mental emosional yang banyak dialami
oleh penduduk Indonesia antara lain sakit kepala, mudah lelah, sulit tidur, rasa
tidak enak di perut dan tidak nafsu makan. Juga hampir sama dengan hasil
Survei Kesehatan daerah (Surkesda) provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
mendapatkan gejala gangguan mental emosional terbanyak adalah sakit
kepala, mudah lelah, sulit tidur, merasa tidak enak di perut dan tidak nafsu Juga lebih tinggi
dibandingkan laporan World Health Organization (WHO) pada tahun 2000
memperoleh data gangguan mental pada populasi penduduk dunia adalah
sebesar 12% dan tahun 2001 meningkat menjadi 13%. Dan lebih tinggi
daripada prevalensi gangguan mental di negara Amerika Serikat 6-9%, Brazil
makan. Tetapi secara keseluruhan proporsi gejala gangguan mental emosional
yang dialami ibu dari pasien skizofrenik lebih tinggi dibandingkan proporsi
gejala gangguan mental yang dialami penduduk Indonesia umumnya.
Menurut S.Idaiani dan kawan-kawan tahun 2009, gejala yang banyak
memberikan kontribusi terhadap gangguan mental emosional antara lain
mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup, merasa tidak berharga, pekerjaan
sehari-hari terganggu, tidak mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam
hidup, merasa sulit menikmati kegiatan sehari-hari. Pada hasil penelitian
didapatkan proporsi gejala-gejala tersebut cukup besar yaitu mempunyai
pikiran untuk mengakhiri hidup (34,3%), merasa tidak berharga (40%),
pekerjaan sehari-hari terganggu (38,1%), tidak mampu melakukan hal-hal yang
bermanfaat dalam hidup (26,7%), merasa sulit menikmati kegiatan sehari-hari
(40%). Sedangkan gejala-gejala somatik seperti sakit kepala, tidak nafsu
makan, pencernaan terganggu, rasa tidak enak di perut tidak memberikan
kontribusi yang besar terhadap gangguan mental emosional. Semakin banyak
gejala yang dialami semakin besar kecendrungan mengalami gangguan mental
emosional.6
Pada penelitian ini Self Reporting Questionnaire (SRQ) yang digunakan
adalah murni 20 butir pertanyaan mengenai gejala yang lebih mengarah
kepada neurosis. Gejala depresi terdapat pada butir nomor 6, 9,10, 14, 15, 16,
17; gejala ansietas terdapat pada butir nomor 3, 4, 5; gejala somatik pada butir
nomor 1, 2, 7, 19; gejala kognitif pada butir nomor 8, 12, 13 dan gejala