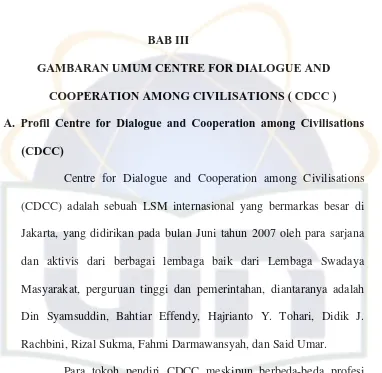PERANCENTRE FOR DIALOGUE AND COOPERATION AMONG CIVILISATIONS (CDCC) DALAM RANGKA PENGUATAN RUANG
PUBLIK YANG BEBAS
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Oleh : Amir Fiqi NIM: 105032201061
JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
ABSTRAK
Amir Fiqi, Peran Center for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC) Dalam Rangka Penguatan Ruang Publik Yang Bebas, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011.
Pasca keruntuhan Orde Baru yang otoriter dan terbentuknya era baru, yaitu era roformasi, ruang publik yang bebas terbuka bagi masyarakat dengan memberikan tempat bagi publik untuk mengekspresikan kebebasan dan otonomi mereka dengan wujud kebebasan pers, bebebasan berpartai, kebebasan berakal sehat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berunjuk rasa, kebebasan membela diri, kebebasan membela komunitas, otonomi daerah, independensi, dan kebebasan berkumpul untuk berdiskusi dan berdialog.
Pada skripsi ini penulis berusaha menjelaskan bagaimana peran Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC) dalam rangka penguatan ruang publik yang bebas khususnya dalam segmen dialog. Pada skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan mengamati data-data yang diperoleh di lapangan. Pada skripsi ini, penulis menggunakan observasi partisipasi, wawancara dan dokumen sebagai teknik mengumpulkan data.
Peran yang dilakukan oleh CDCC adalah memfasilitasi ruang publik yang bebas dan independent kepada warga yang berbeda latar belakang agama atau budaya
untuk berbicara, berdiskusi dan berdialog untuk membincangkan masalah-masalah agama bahkan masalah-masalah negara guna melakukan kritik dan kontrol terhadap pemerintah guna terbentuk good governancd.
Dalam melakukan dialog CDCC mengambil segmen masyarakat elit seperti tokoh-tokoh agama, kalangan pemerintahan, aktivis dan budayawan, bukan masyarakat akar rumput. Meskipun mengambil segmen elit akan tetapi mereka tidak bersikap elitis karena pertemuan-pertemuan (dialog) yang diadakan CDCC selalu mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat bawah yang selalu tersisihkan dengan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. CDCC juga konsen dalam dialog-dialog yang berkenaan dengan agama dan keyakinan dengan selalu melakukan pertemuan-pertemuan antar pemeluk agama yang berbeda guna terwujud masyarakat yang pluralis dan toleran.
KATA PENGANTAR
Puji syukur terhatur ke hadirat Dzat Yang Maha Ghofur, atas karunia, rahmat,
hidayah dan inayah-Nya, diri ini masih sempat menghirup udara segar dan
menatap juntai panorama yang indah. Atas kebesaran-Nya diri ini masih tabah
menghadang pongahnya kehidupan yang bertabur debu problematika. Atas
bimbingan-Nya, terbatik rasa sadar bahwa hidup ini adalah sebuah ujian bagi
hamba-hamba-Nya yang beriman. Syahdan, atas pertolongan-Nya, skripsi ini
dapat terselesaikan.
Salawat dan salam teriring mahabbah terindah semoga tercurahkan keharibaan
Nabi Agung Muhammad SAW, suri tauladan sepanjang hayat. Semoga kita semua
di padang mahsyar nanti termasuk ke dalam barisan yang berada di balik liwaul
hamdani, di bawah naungan syafa’ah uzma-Nya, sebagai hamba-hamba yang diberi inayah untuk mengikuti segenap petunjuk risalah-Nya.
Penulis sadar bahwa sepenuhnya diri ini berhutang budi kepada banyak pihak
yang telah memberikan dukungan, motifasi, bimbingan dan arahan untuk
terselesaikannya skripsi ini. Lebih dari itu, skripsi merupakan seteguk air segar
dalam kemarau studi yang penulis tempuh selama ini.
Sembah bakti, penulis haturkan kepada Ayah (Kasduri) dan Ibu (Suritah) yang
telah membesarkan dan membimbing penulis hingga sampai sekarang. Mohon
maaf jika anak Ayah dan Ibu belum bisa menjadi apa yang engkau harapkan.
Terimakasih Ayah, karena engkau penulis menjadi anak yang bertanggung jawab
dalam menghadapi masalah dalam hidup ini. Terima kasih Ibu, kasih sayang Ibu
terik mentari kehidupan dengan do’a-do’a yang selalu ibu panjatkan kepada Allah
SWT di sela-sela sholat mu.
Tak lupa, penulis juga menyampingkan terima kasih tak terhingga kepada
orang-orang yang telah menanamkan jasa dalam diri penulis antara lain:
1. Prof. Dr. Baktiar Efendi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Ahmad Abrori, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah sabar
membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta segenap dosen,
karyawan, dan seluruh staf yang telah banyak membantu dan memberikan
fasilitas bagi penulis dalam rentang waktu selama di kampus tercinta ini.
4. Terima kasih kepada kakak ku, mba Nur Hidayati yang selalu memberikan
bantuan baik moril dan finansial selama adikmu kuliah, semoga Allah
membalas kebaikan mba, adikmu janji tidak akan mengecewakan mu. Terima
kasih juga untuk mas Guntur, mas Rohidin, mba eti, mba Eli, mas Firman,
dan mba Fatimah, mas Wahyu (kakak ipar) dan adik ku Rifa, kau lah adalah
permata hati ku yang paling berharga dalam hidup ini.
5. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Ciputat:
terima kasih IMM, engkaulah adalah kampus kedua bagiku. Kerenamu, diri
ini mengerti arti penting dari organisasi. Terima kasih juga untuk teman
sejatiku Jajang dan Toto yang selalu menemananiku di kala susah dan senang,
walaupun kadang sengit kepada tingkah-tingkahmu, tapi rasa sengit itu
terkalahkan dengan rasa sayang sebagai sahabat. Terima kasih kepada teman
setia berjuang mengembangkan IMM dan teman-teman yang lain yang tidak
bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Adik-adikku yang sedang berjuang: Fahmi, Mayang, Amel, Farah, Rina,
Dimas, Beni dan seluruh Pengurus angkatan Fahmi. Jaga komitmen dan
kesolidan untuk kejayaan IMM.
7. Teman-teman mahasiswa Sosiologi Agama angkatan 2005: Jajang, Ade,
Alfan, Ariel, Rosidi, Oji, Wahyu, Iwes, Harum, Zakiyah, Sri, Nuri, Uli,
Nursakinah, dan teman-teman yang lain yang tak tercantum. Penulis bangga
dengan teman-teman, tetap jaga persahabatan kita.
8. Terimakasih yang tak terlupakan kepada Wahyu Ardila (Ia) yang selalu
membantu penulis dalam mencari buku dan selalu memberi motivasi dan
mengingatkan penulis agar cepat-cepat lulus kuliah. Dorongan dari mulah
penulis selalu semangat ketika diri ini lemah.
Akhirnya hanya kepada Allah jualah penulis memohon, semoga amal shalih yang
DAFTAR ISI
Lembar Persetujuan Abstrak
Kata Pengantar Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
A. ... Latar
Belakang Masalah ... 1
B. ... Pemb
atasan dan Perumusan Masalah ... 4
C. ... Tujua
n dan Manfaat Penelitian ... 5
D. ... Meto
dologi Penelitian ... 5
E. ... Liter
atur Review ... 8
F. ... Siste
matika Penulisan ... 9
Bab II Kajian Teori
A. Peran
1. ... Defin
2. ... Tinja
uan Sosiologis Tentang Peran ... 13
B. ... Ruan
g Publik dan Civil Society ... 16
C. ... Dialo
g Antar Umat Beragama
1. ... Defin
isi Dialog ... 27
2. ... Urge
nsi Dialog Antar Agama ... 30
3. ... Bent
uk-Bentuk Dialog ... 31
Bab III Gambaran Umum Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC)
A. Profile CDCC
1. ... Latar
Belakang CDCC ... 35
2. ... Misi
CDCC ... 36
3. ... Visi
4. ... Progr
am CDCC ... 37
5. ...
Nilai-Nilai Perjuangan CDCC ... 40
6. ... Struk
tur Organisasi ... 42
Bab IV Peran Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC) Dalam Rangka Penguatan Ruang Publik.
A. ... Latar
Belakang CDCC Membangun Dialog ... 45
B. ... Imple
mentasi Dialog CDCC Dalam Penguatan Ruang Publik ... 54
1. ... Mem
bangun Dialog Antar Umat Beragama ... 57
2. ... Mem
bangun Dialog Politik ... 67
3. ... Mem
bangun Dialog Budaya ... 74
4. ... Mem
bangun Dialog Ekonomi ... 81
Bab V Penutup
A. ... Kesi
B. ... Saran
93
Daftar Pustaka Lampiran-Lampiran
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Menurut Muhammad AS. Hikam, konsep Civil Society
merupakan wawasan yang berasal dari Eropa Barat. Menurutnya,
pengertian Civil Society (dengan memegang konsep de’ Tocquiville)
adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan
bercirikan antara lain kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self
generating), dan keswadayaan (self supporting) dan kemandirian
tinggi berhadapan dengan negara dan keterkaitan dengan norma-norma
atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya1.
Sebagai ruang politik, civil society merupakan suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya prilaku, tindakan, dan refleksi mandiri,
tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material dan tidak terserap
dalam jaring-jaring kelembagaan politik resmi. Oleh dari itu maka di
dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (the free
public sphere), tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa
1
dilakukan oleh warga masyarakat.2 Dalam penegakan civil
society pada suatu bangsa maka diperlukan pilar-pilar penegak untuk mewujudkan nya. Pilar penegak tersebut adalah institusi-institusi yang
menjadi bagian dari social control yang berfungsi mengkritiki
kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu
memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Dalam
penegakan Civil Society, pilar-pilar tersebut menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya kekuatan masyarakat. Pilar-pilar tersebut antara lain
adalah Lembaga Swadaya Masyarkat (LSM), Pers, Supremasi Hukum,
Perguruan Tinggi dan Partai Politik.3
Pada pembahasan ini kami hanya menekankan pada salah satu dari lima pilar penegak tersebut, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorang ataupun kelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari bahasa Inggris dikenal juga sebagai Organisasi non pemerintahan (bahasa Inggris: Non Governmental Organization; NGO).4
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam sebuah komunitas negara mempunyai fungsi mengimbangi dan mampu mengontrol kebijakan negara (Policy of State) yang cenderung memposisikan warganya sebagai subjek yang lemah. Untuk itu, maka diperlukannya penguatan masyarakat sebagai prasyarat untuk mencapai kekuatan bargaining
2 Dede Rosyada, dkk,
Pendidikan Kewarganegaraan (civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat (Jakarta: Kencana,2003), h. 141
3
Dede Rosyada , dkk. h. 250-252
4
masyarakat yang cerdas di hadapan negara tersebut. Oleh karena itu dengan adanya komponen yang penting berupa adanya
lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang mampu berdiri secara mandiri di hadapan negara, terdapat ruang publik dalam mengemukakan pendapat, menguatkan posisi kelas menengah dalam komunitas masyarakat.
Pada skripsi kali ini, penulis akan membahas sebuah tema, yaitu Peran Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC) Dalam Rangka Penguatan Ruang Publik Yang Bebas.
Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC)
adalah sebuah LSM yang didirikan pada bulan Juni tahun 2007 oleh
para sarjana dan aktivis dari berbagai lembaga baik dari Lembaga
Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan pemerintah. Centre for
Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC) bertujuan
untuk memajukan pemahaman yang lebih baik dan hubungan
perdamaian antara agama, budaya, bangsa dan peradaban yang luas.
Centre for dialogue and cooperation among Civilisations (CDCC)
dalam melihat perbedaan peradaban merupakan suatu ancaman dan
pertentangan, oleh karena itu CDCC berupaya menyatukan
pandangan yang berbeda itu menjadi sebuah kesempatan,
kesempurnaan dan penyatuan komponen untuk tumbuh, sehingga
tercapainya perdamaian dunia.
Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC)
menyediakan tempat yang lebih untuk berdialog antara elite dan forum
Cooperation among Civilisations (CDCC) juga menjembatani konflik
yang ada seperti mencegah beberapa kemungkinan konflik dengan
mempertemukan dan memfasilitasi ruang untuk melakukan dialog dan
diskusi berkenaan dengan masalah yang sedang dihadapi.
Sebagaimana disebutkan dalam profile CDCC, maka CDCC sebagai
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempunyai perhatian dalam
upaya memberikan ruang publik yang bebas untuk melakukan dialog
dan diskusi yang berkenaan dengan masalah-masalah yang relevan
untuk segera ditangani. Walaupun CDCC dalam pembentukan ruang
publik yang bebas menurut pandangan penulis lebih bersifat elitis akan
tetapi mempunyai peran, khususnya terhadap para tokoh agama,
aktivitis dan akademisi yang aktif dalam diskusi dan dialog.
Sesuai dengan tujuannya, yaitu berusaha mengupayakan
terwujudnya perdamaian dunia dengan menghilangkan sekat-sekat
yaitu berupa agama, kebudayaan dan peradaban, Centre for Dialogue
and Cooperation among Civilisations (CDCC) juga mengupayakan
terciptanya masyarakat yang toleran dan demokratis melalui segmen
dialog dan kerjasama dengan membuka ruang publik yang
seluas-luasnya bagi warga yang ingin melakukan dialog dan berdiskusi untuk
membicarakan masalah yang sedang mereka hadapi untuk segera
ditangani.
Dari penjelasan latar belakang masalah di atas maka penulis ingin
mengetahui bagaimana peran Centre for Dialogue and Cooperation
among Civilisations (CDCC) dalam rangka penguatan ruang publik
yang bebas. Agar pembahasan skripsi ini tidak terlalu melebar, maka
dalam skripsi ini penulis menekankan dalam sebuah pembatasan dan
perumusan masalah yaitu,
1. Bagaimana peran CDCC dalam rangka penguatan ruang publik yang bebas
terhadap masyarakat dengan mengedepankan sikap toleran dalam
kehidupan beragama melalui segmen dialog dan kerjasama.
2. Sejauh mana peran CDCC dalam melakukan kritik terhadap pemerintah.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana
peran yang dilakukan Centre for Dialogue and Cooperation among
Civilisations (CDCC) dalam rangka penguatan ruang publik yang
bebas terhadaap warga masyarakat guna terbentuknya masyarakat yang
toleran dan pluralis serta kritis terhadap pemerintah yang sesuai
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi para akademisi, dapat memberikan sumbangan teoritis untuk
menambah literatur atau bahan, referensi pada studi tentang LSM
2. Bagi para aktivis, khususnya aktivis LSM sebagai masukan atau saran
dalam mengembangkan program-program kegiatan dalam penguatan
ruang publik yang bebas.
D. Metodologi Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif
merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku
yang diamati.5 Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan, maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan
melalui proses penelitian lapangan. Pada pendekatan ini, penulis
menggunakan metode deskriptif. Dengan metode ini penulis akan
mengemukakan dan menggambarkan bagaimana peran Centre for
Dialogue and Cooperation among Civilisations dalam rangka
penguatan ruang publik yang bebas, yaitu dengan menjelaskan
bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh CDCC dan
cara-cara yang dilakukan CDCC dalam upaya menciptakan masyarakat
yang toleran, pluralis dan kritis terhadap pemerintah.
5 Bungin, B,
2. Unit Analisis.
Pada penelitian kali ini sebagai subjek dalam penelitian adalah
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu Centre for Dialogue and
Cooperation among Civilisations (CDCC) sebagai lembaga yang selulu
memfasilitasi ruang untuk berdialog dan berdiskusi guna terbentuknya
ruang publik yang bebas.
3. Teknik Pengumpulan Data.
A. Observasi Partisipasi.
Observasi partisipasi (participant observation) adalah metode
pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian
melalui pengamatan dan pengindraan di mana observer atau peneliti
terlibat dalam subjek yang akan diteliti.6 Pada penilitian ini, penulis melakukan pendekatan observasi partisipasi dengan cara mengikuti
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh CDCC yaitu berupa kegiatan
dialog dan diskusi yang diadakan oleh CDCC.
B. Interview
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan teknik
wawancara. Menurut Imam Suprayogo dan Tabroni wawancara
merupakan metode penggalian data yang paling banyak digunakan,
baik untuk tujuan praktis maupun ilmiah, terutama untuk penelitian
6
yang bersifat kualitatif.7 Pada penelitian kali ini, penulis akan mewawancari pengurus dari CDCC dan lembaga-lembaga lain yang
aktif dalam dialog dan diskusi yang diselenggarakan oleh CDCC.
C. Dokumentasi :
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang
berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah
berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, foto, dan
sebagainya. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan
dokumentasi guna untuk keberhasilan dan kevalidan data yang penulis
gunakan, yakni dengan menggunakan catatan-catatan yang telah ada
dan mencari artikel-artikel yang bisa membantu dalam penelitian kali
ini.
4. Analisis Data
Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data.
Analisis data adalah adalah rangkaian kegiatan penelaahan,
pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar
sebuah fenomena memilki nilai sosial, akademis dan ilmiah.8
Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan analisa kualitatif
dengan data-data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi
secara mendalam untuk mendapatkan data yang diharapkan dalam
penelitian ini. Wawancara yang peneliti lakukan, berdasarkan hal-hal
yang kami inginkan dan bersifat tidak terstuktur. Pengamatan yang
7
Suprayogo, Imam dan Tobrani, Metodologi Penelitian Sosial-Agama,(Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2003)
8 Suprayogo dan Tohorani,
peneliti lakukan adalah hanya mencari data yang berkaitan tentang
peran yang dilakukan Centre for Dialogue and Cooperation among
Civilisations (CDCC) dalam rangka penguatan ruang publik yang
bebas dan program kerja apa yang dilakukan untuk mencapai semua
itu baik di Indonesia mauapun di luar negeri. Setelah data-data yang
telah kami kumpulkan kemudian kami olah dalam narasi, kemudian
kami analisis dan disajikan secara deskriptif.
Sedangkan data-data dari buku, jurnal, artikel, makalah, dan
karya-karya ilmiah lainnya adalah data-data sekunder yang penulis gunakan
untuk mendukung dan melengkapi data-data primer. Dalam penelitian
yang penulis lakukan adalah análisis data dimulai dari penetapan
masalah, pengumpulan data, penyajian data sampai kepada penarikan
kesimpulan.
E. Literatur Review
Sepanjang penelusuran penulis, sudah ada skripsi yang
membahas tentang CDCC akan tetapi tidak terkait tentang penguatan
ruang publik yang bebas. Pada skripsi yang ditulis oleh Fauzia
Ningtyas, mahasiswi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam pada
Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul Skripsi “Perspektif
Komunikasi Antar Budaya Untuk Perdamaian Kasus The 2nd World
mengusung nilai-nilai perdamaian dan berusaha melawan berbagai
tindak kekerasan yang terjadi baik di Indonesia maupun di negara lain.
Skripsi yang ditulis oleh Fauzia Ningtyas lebih membahas
tentang peran CDCC sebagai penyelanggara Forum Perdamaian Dunia
(World Peace Forum) yang membahas tentang tindak kekerasan dan
konflik yang terjadi di berbagai negara, pada forum itu menyimpulkan
bahwa kekerasan dan konflik itu terjadi tidak hanya disebabkan oleh
satu faktor melainkan oleh beberapa faktor berbeda yang saling
mendukung, seperti faktor agama, politik, bangsa, budaya dan bahkan
faktor ideologi pribadi.
Pada penulisan skripsi kali ini, penulis akan membahas tentang
hal yang berbeda. Pada penulisan skripsi ini, Penulis akan
memposisikan tentang peran CDCC sebagai Lembaga Swadaya
Masyarakat dalam rangka penguatan ruang publik yang bebas bagi
masyarakat melalui segmen dialog dan kerjasama demi terciptanya
masyarakat yang toleran dan kritis terhadap pemerintah.
F. Sistematika Penulisan
Laporan hasil penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk karya tulis
skripsi dengan sistematika penulisan seperti dibawah ini :
1. Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menjelaskan hal- hal seputar
latar belakang yang menerangkan alasan utama kami mengangkat tema ini.
terlalu melebar dalam penulisan dan dapat menangkap isu dengan jelas
sehingga tidak menimbulkan pertanyaan pertanyaan yang keluar dari
konteks yang sedang kami bahas. Tujuan dan manfaat penelitian
menjelaskan tentang apa tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini.
Metodelogi penelitian menjelaskan tentang bagaimana cara penulis
mengumpulkan data-data yang untuk memperoleh data yang valid.
Diskripsi konsep menjelaskan tentang sekilar teori yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini. Pada bab I penulis juga mencantumkan Review studi
terdahu guna menentukan posisi penulis dalam penelitian ini. Dan
sistematika penulisan menjelaskan bagaimana penulis menjelaskan
bagaimana skripsi ini ditulis dari Bab I sampai Bab V
2. Bab II : Kajian Teori. Pada Bab ini penulis membahas tentang definis
peran, dan definisi civil society. Pada ini penulis juga menjelas tentang
ruang publik menurut habermas dan menjelaskan tentang dialog antar
umat beragama. Pada Bab II penulis gunakan sebagai pisau analis penulis
pada Bab IV.
3. Bab III : Gambaran Umum CDCC ( Centre for Dialogue and Cooperation
among Civilisations ). Pada pembahasan bab ini kami membahas tentang
latar belakang berdirinya CDCC, tujuan dan struktur CDCC, dan Visi dan
misi dari CDCC dalam rangka penguatan ruang publik yang bebas.
4. Bab IV: Bab IV ini penulis membahas tentang peran CDCC dalam rangka
penguatan ruang publik. Pada bab ini penulis akan menuangkan data-data
menjelaskan program- program kerja yang dilakukan oleh CDCC dalam
penguatan ruang publik.
5. Bab V : Penutup. Pada pembahasan bab ini kami akan menjelaskan hasil
dari penelitian yang kami lakukan, berupa kesimpulan. Pada bab ini kami
akan menuangkan berupa saran- saran yang mungkin harus kami
sampaikan dalam penelitian ini.
6. Terakhir kami mencantumkan daftar pustaka sebagai bahan acuan selama
kami menyusun skripsi ini, serta lampiran-lampiran berupa
pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan kepada responden untuk memperoleh
BAB II KAJIAN TEORI A. Peran
1. Definisi Peran
Dalam kamus Bahasa Indonesia, peran diartikan beberapa tingkah laku
yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat dan
harus dilaksanakan.9 Sedangkan menurut Gross, Mason dan A.W.MC, sebagaimana yang dikutip oleh David Barry mendefinisikan peran sebagai
perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati
kedudukan sosial tertentu.10
Sebagaimana yang telah diterangkan dalam definisi peran diatas, maka
penulis mengambil kesimpulan bahwa definisi peran adalah sesuatu yang lahir
dari interaksi dalam masyarakat, melalui partisipasi dalam memainkan peran
tertentu yang pada akhirnya ada proses penempatan status peranan seseorang
dalam keluarga, masyarakat dan sebagainya.
Seseorang dapat dikatakan berperan atau memiliki peran karena seseorang
tersebut mempunyai status dalam masyarakat, walaupun kedudukan ini
berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain, akan tetapi masing-masing diri
memiliki peran yang sesuai dengan statusnya. Tentunya peran tersebut tidak dapat
9 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kamus Besar Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 667
10
N. Gross W.S. Mason and A.W. Mc Eachern, Exploritations Role Analysis,
dipisahkan dengan status (kedudukan), walaupun keduanya berbeda, akan tetapi
saling berhubungan antara satu sama lainnya. Karena yang satu dengan yang
lainnya sangat bergantung, maka peran diibaratkan sebagai dua sisi mata uang
yang tidak mungkin bisa dipisahkan.
Dalam hal ini, Sarlito Wirawan Sarwono juga memberikan pengertian
bahwa harapan tentang peran itu adalah harapan-harapan lain yang pada
umumnya mengartikulasikan tentang prilaku-prilaku yang pantas, dan seyogyanya
ditentukan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.11
2. Tinjauan Sosiologis Tentang Peran
Manusia adalah makluk sosial yang tidak bisa dilepaskan dari sikap
ketergantungan pada manusia lain. oleh kerena itu pada posisi semacam ini peran
sangat menentukan kelompok sosial masyarakat tersebut, dalam artian diharapkan
masing-masing dari sosial masyarakat yang berkaitan agar menjalankan hak dan
kewajiban sesuai dengan kedudukan masyarakat dan lingkungan di mana mereka
tinggal.
Gross, Mason, dan Mc Eachern mendefinisikan peran sebagai seperangkat
harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial
tertentu.12 Dengan kata lain peranan-peranan tersebut ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat yang mempunyai makna setiap individu dalam setiap
pekerjaannya diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh
masyarakat, keluarga dan pada peranan-peranan yang lain.
11
Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial (CV. Rajawali: Jakarta,1984), Cet. Ke-1, h.235
12 David Berry,
Di dalam peran terdapat dua macam harapan, yaitu:13
1. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau
kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
2. Harapan-harapan yang dimilki oleh si pemegang peran terhadap
masyarakat atau terhadap orang yang berhubungan dengannya dalam
menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.
Sebagaimana penjelasan di atas terlihat suatu gambaran bahwa yang
dimaksud peran merupakan kewajiban-kewajiban dan keharusan yang dilakukan
seseorang kerena kedudukannya dalam status tertentu pada lingkungan di mana
dia berada. Dan setiap yang mempunyai peran itu biasanya bisa menyesuaikan
dengan peranan tersebut. Misalnya, seseorang ketika berada di rumah ia
mempunyai peran sebagai sebagai kepala rumah tangga, namun ketika di kantor ia
berperan sebagai karyawan dan sebagainya. Peran seperti ini sangat kompleks
tergantung pada mobilitas sosialnya.
Peran mencakup tiga hal, yaitu:14
1. Peran yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan
rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam
kehidupan bermasyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
13
Ibid., h. 101
14
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.
Perlu disinggung mengenai fasilitas-fasilitas bagi peran individu.
Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada invidu untuk dapat
menjalankan peran. Lembaga-lembaga kemasyarakatan atau organisasi
merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk
pelaksanaan peran. Kadang-kadang perubahan struktur suatu golongan
kemasyarakatan menyebabkan fasilitas-fasilitas bertambah.
Bertolak dari sudut-sudut pandang di atas, peran sosial dapat didefinisikan
sebagai bagian dari fungsi sosial masyarakat yang dilaksanakan oleh orang atau
kelompok tertentu, menurut pola kelakuan lahiriah dan batiniah yang telah
ditentukan.
Dari ganbaran di atas tentang peran, dapat disimpulkan beberapa aspek
yaitu:15
1. Peran sosial adalah bagian dari keseluruhan fungsi masyarakat. Fungsi
pada umumnya adalah suatu pengertian yang menunjukan pengaruh khas
dari satu bagian terhadap keseluruhan. Masyarakat sebagai keseluruhan
kesatuan hidup bersama mengemban tugas umu, ialah mencakupi
kepentingan umum yang berupa kesejahteraan spiritual dan material, tata
ketentraman dan keamanan.
2. Peran sosial mengandung sejumlah pola kelakuan yang telah ditentukan.
Jika peran sosial ditinjau dari sudut lain yakni bagaimana pelaksanaannya,
15 Hendropuspito,
peran sosial adalah seperangkat pola kelakuan lahiriah dan batiniah yang
harus diikuti oleh individu yang bersangkutan. Misalnya, bagaimana
seseorang pengurus lembaga sosial yang fokus terhadap permasalahan
anak jalanan dengan mampu memahami karakter anak-anak jalanan,
bagaimana harus bersikap terhadap mereka.
3. Peran sosial dilakukan oleh perorangan atau kelompok tertentu, misalnya
sebuah LSM atau Yayasan.
4. Pelaku peran sosial mendapatkan tempat tertentu dalam tangga
masyarakat. Seperti halnya dengan suatu pementasan sebuah drama,
pelaku-pelaku yang menjalankan peran sosial diberi tempat dalam tangga
masyarakat.
5. Dalam peran sosial terkandung harapan-harapan yang khas dari
masyarakat. Setiap peranan sosial adalah sejumlah harapan yang hendak
diwujudkan, juga harapan dari orang banyak yang realisasinya diserahkan
kepada seorang atau beberapa pelaku. Isi harapan dari masyarakat adalah
supaya peran (tugas) sosial tersebut dilakukan menurut norma dan
peraturan yang telah ditentukan.
6. Dalam peran sosial ada gaya khaas tertentu. Setiap peran yang dipegang
oleh individu atau kelompok memiliki harapan yang berbeda sesuai
dengan konsennya. Misalnya lembaga yang menangani masalah
kerukunan antar umat beragama, maka penjiwaannya harus seperti
karakterisik orang-orang yang menghargai toleransi dan pluralitas.
CDCC merupakan bagian dari civil society yang mempunyai peran dalam
penguatan ruang publik yang bebas. Oleh kerena itu pada kajian teori ini penulis
ingin membahas tentang Ruang Publik dan civil society guna membantu dalam
penulisan skripsi ini.
Menurut penulis untuk mewujudkan ruang publik yang bebas maka harus
terbentuknya dulu civil society. Dalam pengembangan konsep civil society dalam
sebuah bangsa akan sangat terkait dengan prakondisi-prakondisi atau modalitas
domestik yang bangsa itu miliki. Sejarah membuktikan, bangsa-bangsa di dunia
yang memiliki tradisi civil society bagus selalu didahului oleh pengalaman sejarah
yang panjang dalam mendefinisikan civil society sesuai dengan konteks ruang dan waktu masing-masing. Artinya, pengembangan tradisi kehidupan civil society
tidak mungkin dilakukan ditengah-tengah ruang historis yang kosong.
Pengaplikasian civil society pada hari ini akan terkait dengan kajadian historis
kemarin, dan pengaplikasian civil society kedepan akan sangat tergantung pada
pengembanagn konsep pada hari ini.16
Untuk mendefinisikan terma civil society sangat bergantung pada kondisi
sosial kultural suatu bangsa, karena bagaimanapun konsep civil society merupakan bangunan terma yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat.
Sebagai titik tolak, di sini akan penulis kemukakan beberapa definisi civil
society sebagaimana yang di paparkan Dede Rosyada.17
16 Masdar Hilmy,
Islam Profetik; Substansi Nilai-Nilai Agama Dalam Ruang Publik (Yogyakarta: Kanisius,2008), h. 41
17
pertama, definisi yang dikemukakan oleh Zbigniew Rau dengan latar
belakang kajiannya pada kawasan Eropa Timur dan Uni Sovyet. Ia mengatakan
bahwa yang dimaksud dengan civil society merupakan suatu masyarakat yang
berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang di mana individu dan
perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing, satu sama lain guna mencapai
nilai-nilai yang mereka yakini. Ruang ini timbul di antara hubungan-hubungan
yang menyangkut kewajiban mereka terhadap Negara. Oleh karenanya, maka
yang dimaksud civil society adalah sebuah ruang yang bebas dari pengaruh dan
kekuasaan Negara. Tiadanya pengaruh keluarga dan kekuasaan Negara dalam
masyarakat ini diekspresikan dalam gambaran masyarakat yang individualisme,
pasar dan pluralisme.
Kedua, yang digambarkan oleh Han Sung-Joo dengan latar belakang kasus
Korea Selatan. Ia mengatakan bahwa civil society merupakan sebuah kerangka
hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan
sukarela yang terbebas dari Negara, suatu ruang publik yang mampu
mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan warga Negara yang mampu
mengendalikan diri dan independen, yang secara bersama-sama mengkuti norma
dan budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada
akhirnya akan terdapat kelompok inti dalam civil society ini.
Ketiga, definisi yang dikemukakan oleh Kim Sunhyuk, juga dalam kontek
Korea Selatan. Ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan civil society adalah
suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri
otonom dari Negara, yang merupakan satuan-satuan dasar dari reproduksi dan
masyarakat politik yang mampu melakukan kegiatan politik dalam suatu ruang
publik, guna menyatakan kepedulian mereka dan menunjukan
kepentingan-kepentingan mereka menurut prinsip-prinsip pluralisme dan pengelolaan yang
mandiri.
Menurut Muhammad AS Hikam, pengertian civil society dengan
memegang konsep de Tocquiville adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang
terorganisir dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasembadaaan, dan
keswadayaan, kemandirian tinggi berhadapan dengan Negara dan keterkaitan
dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.18
Sejalan dengan penjelasan definisi civil society yang penulis paparkan di
atas, penulis akan menghubungkan dengan penulisan skripsi ini yang berkaitan
dengan penguatan ruang publik yang bebas. Definisi civil society dalam penelitian
ini adalah suatu lembaga yang murni dibentuk oleh masyarakat sipil yang
menyediakan ruang publik yang bebas dari pengaruh negara dan independent
untuk membicarakan atau mendiskusikan hal-hal yang relevan yang sedang
dihadapi oleh warga negara, baik dalam hal ekonomi, agama dan politik.
Sebagai ruang politik, civil society merupakan suatu wilayah yang
menjalin berlangsungnya prilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak
terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terperangkat di dalam
jaring-jaring kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu
ruang publik yang bebas, tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa
18
dilakukan oleh warga masyarakat. Hanya dalam ruang publik yang bebas, secara
normatif tiap individu dalam posisi yang setara dapat melakukan transaksi wacana
dengan dialog atau diskusi dan praksis politik secara sehat, tanpa distorsi dan
represi, baik fisik maupun psikis.
Ruang publik (public sphare) merupakan bagian dari karekteristik Civil
Society. Untuk merealisasikan wacana tersebut diperlukan prasyarat-prasyarat lain
yang menjadi nilai universal dalam penegakan Civil Society. Prasyarat ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain atau hanya mengambil salah satunya saja,
melainkan merupakan satu kesatuan yang integral yang menjadi dasar dan nilai
bagi eksistensi wacana tersebut. Karakteristik tersebut antara lain adalah adanya
Free Public Sphare, Demokrasi, Toleransi, Pluralisme, dan keadilan sosial.19 Tapi
pada pembahasan kali ini penulis lebih menekankan pada masalah ruang publik.
Gagasan ruang publik atau Public Sphere merupakan gagasan yang belum
cukup tua. Dalam hal ini filsuf Jerman Jurgen Habermas (lahir 1929) dianggap
sebagai pencetus gagasan tersebut, sekalipun sebagian orang menganggap
benih-benih pemikiran ruang publik sudah dikemukakan oleh sosilogis dan ekonomis
Jerman Maximilian Carl dan Emil Weber (1864-1920). Jurgen Habermas
mengenalkan gagasan ruang publik melalui bukunya Strukturwandel der
Öffentlichkeit; Untersuchungen zu einer Kategorie der Bürgerlichen Gesellschaft.
Edisi bahasa Inggris buku ini, The Structural Transformation of the Public Sphere:
an Inquiry into a Category of Bourgeois Society, diterbitkan pada 1989.
Sebenarnya apa arti dari publik itu? Apakah setiap kerumunan massa
dengan sendirinya dapat diidentifikasi sebagai publik? Apakah massa yang diam
dapat disebut publik? Apakah publik dilahirkan secara alamiah, ataukah perlu
dibangun?
Jawaban dari pertanyaan alenia di atas sebagai berikut, Publik adalah
warga negara yang memiliki kesadaran akan dirinya, hak-haknya,
kepentingan-kepentingannya. Publik adalah warga negara yang memiliki keberanian
menegaskan eksistensi dirinya, memperjuangkan pemenuhan hak-haknya, dan
mendesak agar kepentingan-kepentingannya terakomodasi. Sehingga publik
bukanlah kategori pasif, melainkan aktif. Publik bukan kerumunan massa yang
diam (mass of silent), dan publik itu tidak timbul secara alami, publik harus
dibangun dengan kesadaran warga yang kritis terhadap masalah yang dihadapi.20 Sedangkan ruang publik adalah tempat bagi publik untuk mengekspresikan
kebebasan dan otonomi mereka. Ruang publik bisa berwujud kebebasan pers,
kebebasan berpartai, kebebasan berakal sehat, kebebasan berkeyakinan,
kebebasan berunjuk rasa, kebebasan membela diri, kebebasan membela
komunitas, otonomi daerah, independensi, dan keadilan sistem hukum.
Konsep ruang publik dalam filsafat politik Habermas banyak mendapat
inspirasi dari konsep tindakan politiknya Hannah Arendt dalam bukunya The
Human Condition. Tetapi Habermas mengkritik Arendt bahwa konsep politiknya terlalu sempit. Kekuasaan seperti kata Arendt “terjadi di antara manusia-manusia,
20
jika mereka bertindak bersama, dan lenyap jika mereka bubar”.21 Kekuasaan komunikatif itu terbentuk dalam forum-forum diskusi publik, dalam
gerakan-gerakan sosial, dan juga di dalam DPR/MPR saat legislasi hukum. Di samping itu,
menurut Habermas, Arendt tidak sensitif terhadap kemungkinan adanya
manipulasi komunikasi di antara mereka yang mengaku berjuang demi kedaulatan
rakyat dan HAM. Menurut Habermas, kekuasaan komunikatif itu baru terbentuk
lewat pengakuan faktual atas klaim-klaim kesahihan yang terbuka terhadap kritik
dan dicapai secara diskursif. Dengan kata lain, legitimitas suatu keputusan publik
diperoleh lewat pengujian publik dalam proses deliberasi yang menyambungkan
aspirasi rakyat dalam ruang publik dan proses legislasi hukum oleh lembaga
legislatif dalam sistem politik.22
Ruang publik dalam pemikiran Habermas bertujuan untuk membentuk
opini dan kehendak (opinion and will formation) yang mengandung kemungkinan
generalisasi, yaitu mewakili kepentingan umum. Dalam tradisi teori politik,
kepentingan umum selalu bersifat sementara dan mudah dicurigai sebagai
bungkus kehendak kelompok elit untuk berkuasa. Generalisasi yang dimaksud
Habermas sama sekali bukan dalam arti statistik, melainkan filosofis karena
bersandar pada etika diskursus.23
Ruang publik dalam pemikiran Habermas lebih condong pada ruang
publik politik. Jurgen Habermas mengakui bahwa politik memang mengandung
21
Hannah Arendt, The Human Condition, (Chicago : The Chicaco University Press, 1958), h. 252
22 F. Budi Hardiman,
Menuju Masyarakat Komunikatif; Ilmu, Masyaraakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas, (Yogyakarta: Kanisius,2009) h. 140
23
ruang serba mungkin yang besar, tetapi ini tidak berarti bahwa politik hanya bisa
dilegitimasikan. Politik bisa dirasionalkan, sekurang-kurangnya dewasa ini
kecenderungan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan rasional bagi
keputusan kehendak politis itu menunjukan gejala yang disebutnya “pengilmiahan
politik”.24Habermas membaca kecenderuangan ini yang dituangkan dalam sebuah esai The Scientizition of Politics and Public Opinion. Yang menjadi keprihatinan
yang mendasari analisanya adalah terciptanya masyarakat yang demokrasi dan
rasional, artinya membangun masyarakat atas dasar hubungan antar pribadi yang
merdeka dan memulihkan kedudukan manusia sebagai subjek-subjek yang
mengelola sejarahnya.25
Berbicara mengenai “politik” demikian lazimnya anggapan orang, adalah
berbicara mengenai naluri kekuasaan yang dibenarkan secara sosial. Politik dalam
arti yang seluas-luasnya adalah dimensi kekuasaan yang mengatur dan
mengarahkan kehidupan sosial sebagai keseluruhan. Persoalan yang terus muncul
disini adalah siapakah yang berhak mengatur atau mengarahkan kehidupan sosial
itu, dan sebagaimana pengaturan dan pengarahan tersebut dilaksanakan. Secara
lebih mendasar, persoalannya adalah manakah politik yang diterima oleh semua
pihak dalam sebuah masyarakat. Ini menyangkut legitimasi. Sebuah kekuasaan
harus diligitimasi agar efektif pada semua pihak. Kekuasaan itu
sekurang-kurangnya harus tampak benar dihadapan pihak-pihak yang dikuasai.26
Mengapa politik harus dilegitimasikan? Ada banyak jawaban, akan tetapi
kita akan digiring ke sebuah jawaban mendasar bahwa politik itu irasional, dalam
24
Jurgen Habermas, Toward a Rational Socity, (London: Heinemann,1971) h.62
25
F. Budi Hardiman, Menuju Masyarakat Komunikatif; Ilmu, h. 145
artian unsur-unsur kehendak manusia mengatasi unsur pengetahuannya. Dalam
kehidupan sosial, ada segi kehidupan rutin yang bisa diantisipasi, terjadi dalam
pola-pola yang mapan dan diandaikan begitu saja, tapi ada juga segi kehidupan
yang menghadapkan manusia pada pilihan-pilihan yang serba mungkin untuk
mengubah atau mempertahankan kehidupan sosial itu. Karena serba mungkin,
maka segi politik kehidupan sosial ini menuntut keputusan kehendak. Supaya
keputusan kehendak ini memasuki segi kognitif yang dikuasai, dibutuhkan
legitimasi. Akan tetapi dengan legitimasi, politik bisa saja tetap irasional, sebab
bagaimanapun, ruang serba mungkin yang menuntut keputusan kehendak itu tetap
besar, dan keputusan kehendak tidak selalu didasari oleh pertimbangan rasional.
Rasionalisai kekuasaan pada gilirannya mengangkat isu demokrasi dalam
arti bentuk-bentuk komunikasi umum dan publik yang bebas dan terjamin secara
institusional. Dalam pandangan Habermas, hanya kekuasaan yang ditentukan oleh
diskusi publik yang kritislah yang merupakan kekuasaan yang dirasionalisasikan.
Diskusi semacam itu hanya mungkin dilakukan dalam suatu wilayah sosial yang
bebas dari sensor dan dominasi. Dalam esainya, The public Sphare, Habermas
melihat perkembangan wilayah sosial semacam itu dalam sejarah masyarakat
modern. Wilayah itu disebutnya “Ruang publik”. Semua wilayah kehidupan sosial
kita yang memungkinkan kita untuk membentuk opini publik dapat disebut ruang
publik.27
Dalam karya awalnya, Strukturwandel der Oeffentlichkeit (Perubahan
Struktur Ruang Publik), Juergen Habermas menjelaskan ruang publik politis
sebagai kondisi-kondisi komunikasi yang memungkinkan warga negara
membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursif.28 Pertanyaannya sekarang, kondisi-kondisi manakah yang diacu oleh Habermas?
Pertama, partisipasi dalam komunikasi politis itu hanya mungkin jika kita
menggunakan bahasa yang sama dengan semantik dan logika yang konsisten
digunakan. Semua warga negara yang mampu berkomunikasi dapat berpartisipasi
di dalam ruang publik politis itu.
Kedua, semua partisipan dalam ruang publik politis memiliki peluang yang
sama untuk mencapai suatu konsensus yang fair dan memperlakukan mitra
komunikasinya sebagai pribadi otonom yang mampu bertanggung jawab dan
bukanlah sebagai alat yang dipakai untuk tujuan-tujuan di luar diri mereka.
Ketiga, harus ada aturan bersama yang melindungi proses komunikasi dari
represi dan diskriminasi sehingga partisipan dapat memastikan bahwa konsensus
dicapai hanya lewat argumen yang lebih baik. Singkatnya, ruang publik politis
harus "inklusif", "egaliter", dan "bebas tekanan". Penulis dapat menambahkan
ciri-ciri lain: pluralisme, multikulturalisme, toleransi, dan seterusnya. Ciri ini
sesuai dengan isi konsep kepublikan itu sendiri, yaitu dapat dimasuki oleh siapa
pun.
Di manakah lokus ruang inklusif, egaliter, dan bebas tekanan itu di dalam
masyarakat majemuk? Jika penulis berfikir seperti analisis Habermas, penulis
membayangkan masyarakat kompleks dewasa ini sebagai tiga komponen besar,
yaitu sistem ekonomi pasar (kapitalisme), sistem birokrasi (negara), dan
28
solidaritas sosial (masyarakat). Lokus ruang publik politis terletak pada komponen
solidaritas sosial. Dia harus dibayangkan sebagai suatu ruang otonom yang
membedakan diri baik dari pasar maupun dari negara.
Pada era globalisasi pasar dan informasi dewasa ini, sulitlah
membayangkan adanya forum atau panggung komunikasi politis yang bebas dari
pengaruh pasar ataupun negara. Kebanyakan seminar, diskusi publik, demonstrasi,
dan seterusnya didanai, difasilitasi, dan diformat oleh kekuatan finansial besar,
entah kuasa bisnis, partai, atau organisasi internasional dan seterusnya. Hampir
tak ada lagi lokus yang netral dari pengaruh ekonomi dan politik. Jika demikian,
ruang publik politis harus dimengerti secara "normatif", yaitu ruang publik itu
berada tidak hanya di dalam forum resmi, melainkan di mana saja warga negara
bertemu dan berkumpul mendiskusikan tema yang relevan untuk masyarakat
secara bebas dari intervensi kekuatan-kekuatan di luar pertemuan itu. Kita
menemukan ruang publik politis, misalnya, dalam gerakan protes, dalam aksi
advokasi, dalam forum perjuangan hak-hak asasi manusia, dalam perbincangan
politis interaktif di televisi atau radio, dalam percakapan keprihatinan di
warung-warung, dan seterusnya.
Berbeda dari demokrasi dalam masyarakat yang berukuran relatif kecil dan
homogen, demokrasi di dalam masyarakat kompleks seperti yang berukuran
gigantis seperti masyarakat kita tidak dapat berfungsi secara memuaskan hanya
dengan mengandalkan kinerja para wakil rakyat dalam DPR/MPR. Subjek
kedaulatan rakyat dalam masyarakat majemuk tidak boleh dibatasi pada
politis, dan mereka adalah apa yang kita sebut masyarakat sipil. Mereka terdiri
atas perkumpulan, organisasi, dan gerakan yang terbentuk spontan untuk
menyimak, memadatkan, dan menyuarakan keras-keras ke dalam ruang publik
politis problem sosial yang berasal dari wilayah privat.
Masyarakat sipil bukan hanya pelaku, melainkan juga penghasil ruang
publik politis. Seperti diteliti oleh J Cohen dan A Arato, ruang publik politis yang
dihasilkan para aktor masyarakat sipil itu dicirikan oleh "pluralitas" (seperti
keluarga, kelompok nonformal, dan organisasi sukarela), "publisitas" (seperti
media massa dan institusi budaya), "privasi" (seperti moral dan pengembangan
diri), dan "legalitas" (struktur hukum dan hak-hak dasar).
C. Dialog Antar Umat Beragama.
Dalam rangka pengutan ruang publik yang bebas terhadap warga, CDCC
lebih mengambil segmen dialog dan kerjasama antara agama yang berbeda dan
kebudayaan yang berbeda. Oleh karena itu, pada kajian teori ini penulis
mengangkat tentang dialog antar umat beragama. Dengan melakukan dialog
maka ruang publik akan mudah terbentuk.
1. Definisi Dialog.
Dialog dapat diartikan sebagai komunikasi antara dua orang atau lebih atau
dua pihak yang berbeda pandangan.29 Dalam keperbedaannya masing-masing pihak saling belajar dan berbagai pengalaman satu terhadap yang lainnya.
Sedangkan menurut Swidler, dialog bukanlah debat, bukan pula saling
mengancam, tetapi merupakan suatu percakapan antara dua orang atau lebih
29 Sutan Rajasa,
tentang suatu masalah bersama namun memiliki pandangan yang berbeda yang
mempunyai tujuan pokok untuk saling mendengar, dan saling belajar satu sama
lain secara terbuka dan simpatik sehingga diharapkan terjadi perubahan sikap
kearah yang lebih positif.30
Mengacu pada definisi kata dialog diatas maka penulis mendefinisikan
dialog merupakan suatu cara dimana dua orang atau lebih (masyarakat) untuk
membicarakan perbedaan atau persamaan dari masing-masing dengan tujuan
untuk saling belajar dan mengetahui dengan cara damai sehingga tercipta
masyarakat yang toleran terhadap perbedaan.
Apabila penulis kaitkan dengan dialog antar umat beragma dari tujuan
dialog yang yang telah dijelaskan oleh Swidler, penulis bisa mengambil
kesimpulan bahwa dialog juga mempunyai tujuan yang lain, yaitu untuk
menunjukan rasa hormat terhadap agama yang berbeda dan perhatian terhadap
kepercayaan dan para pemeluk agama lainnya. Dengan cara ini, sebagai umat
beragama harus senantiasa bersikap hati-hati dalam menentukan
pemikiran-pemikiran apa saja berkenaan dengan pemahaman akan Tuhan yang serupa,
memilki kesamaan ataupun sama sekali berbeda.
Dari sinilah kehadiran forum dialog antar agama menjadi relevan dalam
kehidupan sosial masyarakat. Dialog sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup
ditengah pluralisme. Pluralisme itu muncul dalam berbagai macam ragam dan
bentuk yang meliputi: pluralisme kebutuhan, pluralisme keyakinan, pluralisme
keyakinan, pluralisme kepentingan, pluralisme etnis, pluralisme status sosial,
30
pluralisme agama dan lainnya. Dalam kontek pluralisme agama misalnya,
pluralisme ini juga berkaitan dengan pluralisme kebutuhan dan keyakinan yang
sesekali menampilkan pluralisme budaya sebagai latar belakang yang menjadi
basis pemahaman akan tuhan dan keyakinan keagamaan.31
Penulis dalam memahami pluralisme bukan sekedar bermakna statis, yaitu
dengan adanya kemajumukan atau keberagaman, melainkan juga bermakna
dinamis, yaitu adanya keterlibatan dalam upaya memahami perbedaan dan
kesamaan yang ada, dan sekaligus keterlibatannya dalam kebersamaan untuk
mencapai tujuan bersama. Pluralisme bukan mengingkari adanya perbedaan,
sebaliknya pluralisme mengakui adanya perbedaan namun tidak menjadikan
perbedaan tersebut sebagai penghalang terhadap kebersamaan dan harmoni
kehidupan.
Dari uraian diatas menghantarkan penulis pada salah satu sendi kehidupan
pluralis, yaitu adanya kesadaran kemajemukan (plural awareness) yaitu kesadaran
yang mendalam bahwa kita hidup dalam kemajemukan, dan ingkar kepada
kemajemukan berarti ingkar terhadap ciptaan Tuhan.
Kesadaran akan kemajemukan akan mengikis sikap kemutlakan, subjektif
dan ekslusif, dan akan menimbulkan sikap saling memahami. Berkembangnya
sikap ini akan memungkinkan lahirnya sendi kehidupan pluralis yang lain, yaitu
sikap saling percaya. Sesungguhnya modal trust ini bukan hanya menghindari timbulnya konflik, melainkan juga memungkinkan terjadinya sinergi antar
komunitas yang berbeda.
31
Ruslani, Masyarakat Kitab dan Dialog Antar Umat Beragama
Sendi dari kehidupan pluralis adalah dialog. Dialog merupakan instrument
utama dalam pengelolaan kehidupan plural yang sehat dan produktif, karena tanpa
ada dialog masing-masing komunitas yang berbeda sangat rentan untuk menjadi
eksklusif dan jatuh jatuh dalam fanatisme yang sempit. Dengan dialog dapat
melahirkan sikap toleran, saling percaya, dan saling menghormati.
Esensi dari dialog adalah adanya penghargaan dan pengenalan timbal balik
(reciprocal recognition) antara pihak yang berdialog . dengan adanya sikap saling
mengenal dan menghargai ini maka mereka benar-benar dapat memahami
pendapat, nilai-nilai kebenaran dan keyakinan mitra dialognya.32
2. Urgensi Dialog Antar Agama.
Dialog lebih memanisfetasikan dirinya sebagai suatu pendirian, orientasi,
atau penunjang komunikasi daripada sebagai suatu metode,teknik atau pola yang
spesifik.33
Ada hal yang harus diingat, kadang kala karakteristik dari dialog
disalahgunakan secara tidak bertanggung jawab. Kejujuran yang blak-blakan
dapat dilakukan untuk menghina orang lain dengan tujuan untuk memuaskan ego
sendiri dan perasaan mementingkan diri sendiri.
32 Ahmad Watik Pratinya, “Pluralisme,
Trust dan Dialog” dalam Ahmad Syafii Maarif, dkk., Ethics and Religious Dialogue In a Globalized World (Jakarta: The Habibie Centre,2010), h. 62
33
Apabila seseorang yang sadar akan nilai kemanusiaan, maka pasti dia tidak
akan mengganggu atau mengancam manusia lain. penulis teringat yang diutarakan
oleh filsuf moral Frans Magnis Suseno, bahwa “Humanisme tak pernah bisa
menjadi ancaman bagi humanisme lain” artinya, bahwa humanisme Kristiani tidak
mengancam humanisme Islam, begitu sebaliknya humanisme Islam tak
mengancam humanisme Kristiani.34 Demikian juga hal ini berlaku bagi humanisme yang lain yang ada dalam masing-masing agama, baik humanisme
yang terdapat dalam individu maupun kelompok. Konsekuensinya adalah agama
yang tidak humanis bisa menjadi ancaman bagi orang yang tidak beragama,
ancaman bagi orang yang beragama lain, dan bagi saudara-saudari seagama.
Dari sinilah kehadiran forum dialog antar agama menjadi relevan dalam
kehidupan masyarakat kita. Dialog sangat dibutuhkan dalam di tengah-tengah
pluralisme. Pluralisme ini muncul dalam berbagai macam ragam dan bentuk yang
meliputi: pluralisme kebutuhan, pluralisme keyakinan, pluralisme kepentingan,
pluralisme etnis, pluralisme status sosial, pluralisme agama, dan lainnya.
Berkaitan dengan pemahaman pluralisme, berkembanglah upaya-upaya
dialog dalam konteks agama-agama. Dialog antar agama, yang hakekatnya adalah
pertemuan hati dan pikiran antar berbagai macam agama, merupakan aktualisasi
sekaligus pelembagaan semangat pluralisme keagamaan.
Dialog antar agama menjadi ajang komunikasi dua orang atau lebih dalam
tingkatan agamis. Dengan dialog, jalan bersama menuju kebenaran semakin
34
terbuka.35 Dialog bukan debat, melainkan saling memberi informasi tentang agama masing-masing baik mengenai persamaan maupun perbedaannya.
Dialog sama sekali tidak mengurangi loyalitas dan komitmen seseorang
terhadap kebenaran keyakinan agama yang sudah ia pegang, akan tetapi lebih
memperkaya dan memperkuat keyakinan itu. Dialog juga jauh dari kemungkinan
orang untuk terjerumus ke dalam pandangan sinkretisme. Sebaliknya, dialog
mencegah orang dari sinkretisme karena dengan dialog seseorang akan semakin
mendalami pengetahuannya tentang agama atau kepercayaan lain, dan pada saat
yang sama keyakinannya terhadap kebenaran ajaran agama yang ia peluk akan
semakin teruji dan tersaring.
3. Bentuk-Bentuk Dialog
Dialog antar agama dapat berlangsung dalam beberapa bentuk diantaranya:
dialog kehidupan, dialog kerja sosial, dialog teologis (dialog iman), dan dialog
spritual.36Disamping itu juga ada dialog perbuatan, dialog kerukunan, dialog
sharing pengalaman agama, dialog doa bersama, interfaith dialogue, dialog terbuka, dialog tanpa kekerasan, dialog aksi dan sebagainya.37
Pertama, dialog kehidupan. Dialog kehidupan merupakan bentuk paling
sederhana dari pertemuan-pertemuan antar agama yang dilakukan oleh umat
beragama. Disini pemeluk agama yang berbeda-beda saling bertemu dalam
kehidupan sehari-hari, berbaur, dan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang
kegiatan sosial tanpa memandang identitas agama masing-masing.
35 Burhanuddin Daya,
Agama Dialogis; Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Antaragama, (Yogyakarta: Mataram-Minang Lintas Budaya,2004), h. 20
36
Mun’im A Sirry, Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-pluralis, (Jakarta: Paramadina,2004), h. 208
37 Burhanuddin Daya,
Kedua, dialog kerja sosial. Dialog kerja sosial merupakan kelanjutan dari
dialog kehidupan dan telah mengarah pada bentuk-bentuk kerjasama yang
dimotivasi oleh kesadaran keagamaan. Dasar sosiologisnya adalah pengakuan
akan pluralisme sehingga tercipta suatu masyarakat yang saling percaya. Dalam
konteks ini, pluralisme sebenarnya lebih sekedar pengakuan akan kenyataan
bahwa kita majemuk, melainkan juga terlibat aktif dalam kemajemukan itu.
Ketiga, dialog teologis atau dialog iman. Dialog teologis merupakan
pertemuan-pertemuan, baik reguler ataupun non reguler untuk membahas
persoalan-persoalan teologis. Tema yang diangkat misalnya pemahaman kaum
Muslim dan Kristen tentang Tuhan masing-masing atau tentang tradisi keagamaan
seseorang dalam konteks pluralisme dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk
membangun kesadaran bahwa diluar keyakinan dan keimanan dari tradisi
agama-agama selain kita. Jika dalam dialog sosial berangkat dari problem bagaimana kita
menempatkan agama kita di tengah-tengah agama-agama orang lain, maka dialog
teologis berusaha memposisikan iman kita di tengah-tengah iman orang lain.
Keempat, dialog spiritual. Dialog spiritual bertujuan untuk menyuburkan
dan memperdalam kehidupan spiritual di antara berbagai agama. Dialog ini
bergerak dalam wilayah esotoris yaitu sisi dalam agama-agama. oleh karena itu
para pesertanya melampaui sekat-sekat dan batas-batas formalisme agama.
Dialog antar agama paling tidak berlangsung dalam tiga level. Pertama,
dialog wacana, yaitu dialog yang membahas masalah-masalah teologis yang
muncul. Misalnya, konsep Tuhan Allah dengan paham Trinitas Kristen. Kedua,
menghayati kehidupan orang miskin. Ketiga, dialog dalam level aksi, yaitu dialog
yang para peserta dialog tanpa membeda-bedakan agamanya sama-sama
menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
Dapat digarisbawahi, muara dialog adalah memberi kesadaran secara
teologis bahwa perbedaan itu bukan buatan manusia tapi desain Tuhan. Oleh
karena itu, saling menghargai dalam perbedaan sangat diperlukan. Bertolak dari
pandangan inklusif-pluralis ini, para pemeluk agama yang berbeda dapat
menjalani kerja sama. Jadi pada prinsipnya dialog antar agama dengan kerja antar
agama adalah dua hal yang sambung-menyambung. Yang satu mengandaikan
yang lain. tidak ada kerja sama tanpa didahului oleh dialog, dan dialog berlanjut
pada kerja sama dan memberikan penguatan bagi kerja-kerja sosial. Aksi-aksi
kolaboratif melibatkan berbagai kalangan agama dalam merespon kebutuhan
BAB III
GAMBARAN UMUM CENTRE FOR DIALOGUE AND COOPERATION AMONG CIVILISATIONS ( CDCC ) A. Profil Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations
(CDCC)
Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations
(CDCC) adalah sebuah LSM internasional yang bermarkas besar di
Jakarta, yang didirikan pada bulan Juni tahun 2007 oleh para sarjana
dan aktivis dari berbagai lembaga baik dari Lembaga Swadaya
Masyarakat, perguruan tinggi dan pemerintahan, diantaranya adalah
Din Syamsuddin, Bahtiar Effendy, Hajrianto Y. Tohari, Didik J.
Rachbini, Rizal Sukma, Fahmi Darmawansyah, dan Said Umar.
Para tokoh pendiri CDCC meskipun berbeda-beda profesi
seperti Din Syamsudin sebagai akademisi dan sekaligus menjadi Ketua
Umum PP Muhammadiyah, Bahtiar Effendy sebagai akademisi dan
mantan Ketua Bidang Hikmah PP Muhammadiyah, Hajrianto Y.
Tohari sebagai Wakil Ketua MPR dan sebagai mantan ketua Pemuda
Muhammadiyah, Rizal Sukma Sebagai Wakil Direktur Eksekutif
Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS), Didik J. Racbani
sebagai politisi dari partai PAN (Partai Amanat Nasional) dan Fahmi
Darwansah dan Said Umar sebagai pengusaha akan tetapi mereka
semua mempunyai latar belakang organisasi yang sama, yaitu
Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations
(CDCC) bertujuan untuk memajukan pemahaman yang lebih baik dan
hubungan perdamaian antara agama, budaya, bangsa dan peradaban
yang luas, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan toleren
tarhadap sesama.
1. Latar Belakang CDCC
Berdirinya Centre for Dialogue and Cooperation among
Civilisations (CDCC) didasarkan oleh beberapa sebab. Sebab yang
paling mendasar adalah seiring dengan meningkatnya jumlah tindakan
kekerasan baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia
lainnya, yang disebabkan oleh faktor politik, agama, ekonomi, budaya,
dan lain-lain. Hal itu disebabkan karena ada alasan yang utama, yakni
bahwa tindakan kekerasan itu ada karena adanya benturan peradaban
yang berbeda antara satu masyarakat, budaya, dan agama yang satu
dengan yang lain nya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Samuel
Huntington. Tapi sebenarnya teori itu tidak sepenuhnya benar, karena
setiap peradaban memiliki nilai universalitas sendiri yang bisa diterima
oleh peradaban lainnya. Oleh karena alasan itulah CDCC kemudian
berusaha untuk memahami berbagai perbedaan tersebut dan berusaha
untuk mencari titik temunya. Dialog dan kerjasama pun dijadikan
CDCC sebagai jalan untuk mewujudkaan tata dunia yang damai.
Selama ini, berbagai dialog yang ada hanya bersifat
CDCC berusaha membuat dialog yang konseptual dan menjadi praktis,
sehingga berbagai kerja sama bisa diadakan untuk melawan tindak
kekerasan dan menghindari benturan-benturan peradaban, sehingga
dapat terwujud masyarakat dunia yang damai dan toleran terhadap
peradaban lain.
2. Misi CDCC
Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations
(CDCC) bertujuan untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik
dan hubungan damai antar agama, budaya, bangsa, dan peradaban pada
umumnya. Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations
(CDCC) berusaha untuk memediasi pemisahan yang selama ini ikut
didukung oleh adanya ketakutan dan ketidakpahaman pada dua belah
pihak.38 Maka dibentuklah beberarapa inisiatif untuk membangun dan memperluas dialog dan kerja sama antar agama, antar budaya,
internasional dan antar peradaban, serta memberikan prioritas tinggi
dalam menanggapi permasalahan-permasalahan utama mengenai
kesalahpahaman dan kekerasan melalui beberapa ketentuan studi
permasalahan yang terkait yang komprehensif, objektif, dan tepat.
3. Visi CDCC
Daripada memandang perbedaan sebagai suatu ancaman dan
selalu berbenturan, CDCC menganut sebuah pandangan bahwa
perbedaan adalah sebuah kesempatan, kekayaan dan sebuah komponen
integral yang tumbuh, dengan tujuan untuk menciptakan dunia yang
damai. Perbedaan harus diterima, tapi pada saat yang sama seseorang
tidak harus mempertahankan pandangan seperti yang selama ini dianut
oleh dunia Muslim dan Barat yang bisa menciptakan konflik yang
tiada henti-hentinya.
Bagaimanapun juga, usaha-usaha untuk menjembatani jurang
pemisah antar masyarakat, bangsa dan peradaban dunia seringkali
gagal jika tidak disertai oleh partisipasi, dialog dan kerja sama dari
komunitas internasional. Dewasa ini, sangatlah penting untuk
melakukan sebuah gerakan global untuk menjembatani jurang pemisah
itu dan mempromosikan dialog, pemahaman yang lebih luas dan saling
menghormati antar berbagai budaya dan peradaban.39
4. Program CDCC
CDCC berusaha untuk mencapai tujuannya melalui
aktifitas-aktifitas berikut:
a. Kuliah Umum (Public Lecture)
CDCC berusaha untuk mengadakan dialog-dialog antar
peradaban dengan mengumpulkan para elit dan masyarakat dalam
sebuah forum yang mendiskusikan isu-isu tentang antar agama, antar
39
V