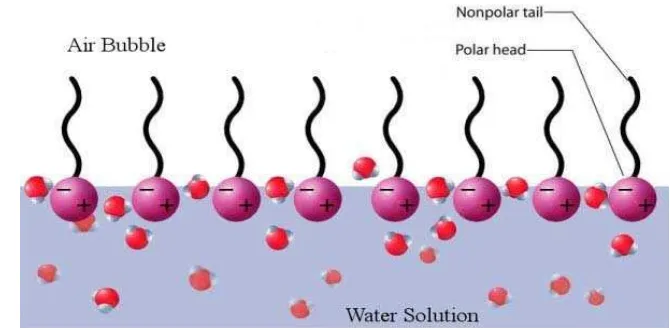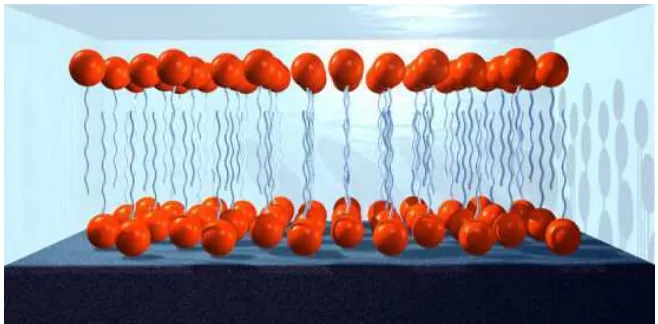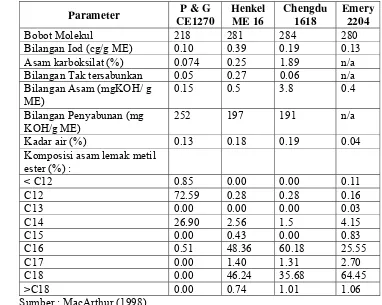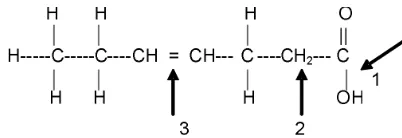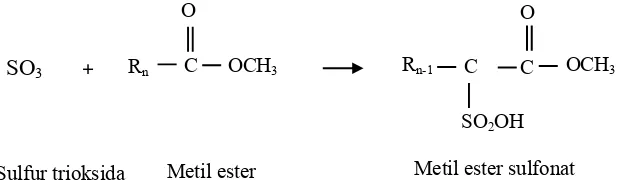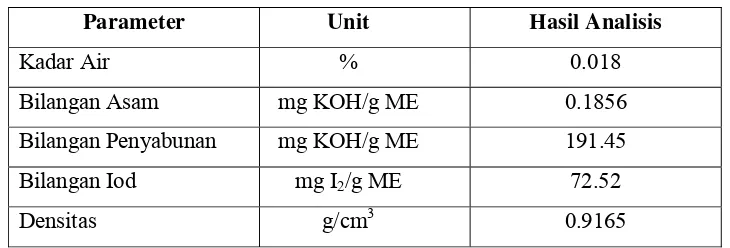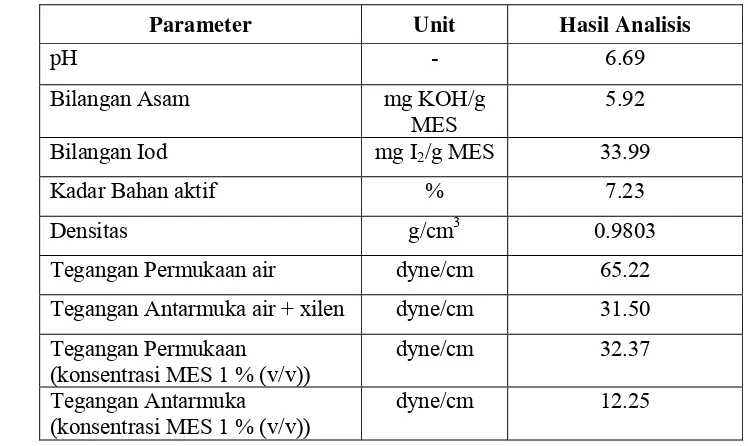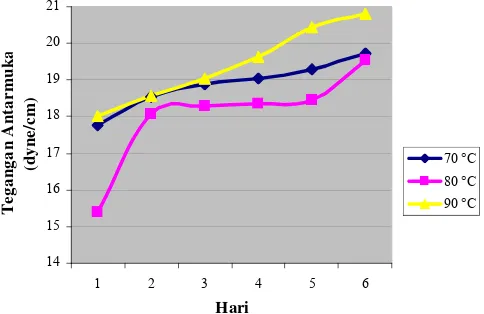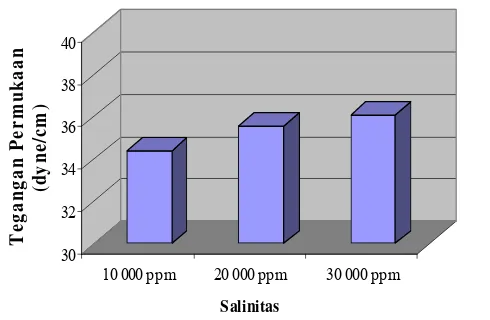I.
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Surfaktan merupakan suatu zat yang bersifat aktif permukaan yang dapat menurunkan tegangan antarmuka (interfacial tension)antara dua bahan baik berupa cairan-cairan, cairan-padatan atau cairan-gas. Sifat aktif permukaan yang dimiliki surfaktan memungkinkan dua atau lebih senyawa yang saling tidak bercampur pada kondisi normal menjadi bertedensi untuk saling bercampur homogen.
Surfaktan yang sering digunakan saat ini adalah surfaktan berbasis petroleum. Kelemahan surfaktan ini yaitu tidak dapat bertahan dalam kondisi kesadahan tinggi dan terbuat dari bahan baku yang tidak dapat diperbaharui. Bahan baku surfaktan yang dapat diperbaharui adalah minyak nabati.
Salah satu surfaktan yang mempunyai prospek untuk dikembangkan adalah surfaktan metil ester sulfonat (MES). Kelebihan surfaktan ini adalah dapat mempertahankan deterjensi pada air dengan tingkat kesadahan yang tinggi, tidak menggumpal pada air dengan tingkat salinitas yang tinggi dan memiliki laju biodegradasi yang lebih cepat dibandingkat surfaktan berbasis petroleum (Watkins, 2001).
Surfaktan dikelompokkan secara luas pada berbagai bidang industri seperti industri kimia, industri kosmetika, industri pangan, industri pertanian, dan industri farmasi serta industri perminyakan untuk Enhanced Oil Recovery (EOR). Surfaktan metil ester sulfonat (MES) adalah salah satu jenis surfaktan anionik yang dapat menurunkan tegangan permukaan dan tegangan antarmuka minyak dan air.
pohon industri minyak sawit yang disajikan pada Lampiran 1. Pada Tabel 1. disajikan perkembangan volume produksi minyak sawit di Indonesia.
Tabel 1. Perkembangan volume produksi minyak sawit di Indonesia Tahun Produksi minyak sawit (ton)
2000 5.094.855
Dalam rangka mengantisipasi melimpahnya produksi minyak sawit, maka diperlukan usaha untuk mengolah minyak sawit menjadi produk hilir. Pengolahan minyak sawit menjadi produk hilir memberikan nilai tambah tinggi. Produk olahan dari minyak sawit dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu produk pangan dan non pangan. Produk pangan terutama minyak goreng dan margarin. Produk non pangan terutama oleokimia yaitu ester, asam lemak, surfaktan, gliserin dan turunan-turunannya. Metil ester merupakan produk turunan minyak sawit yang diperoleh dengan reaksi esterifikasi. Metil ester menjadi bahan intermediet untuk bahan baku surfaktan seperti surfaktan metil ester sulfonat (MES).
Proses produksi surfaktan MES dapat dilakukan dengan menggunakan agen pensulfonasi diantaranya H2SO4, NaHSO3, oleum, dan gas SO3. Tim
peneliti dari SBRC-IPB telah memanfaatkan H2SO4 dan NaHSO3 dalam
Penggunaan gas SO3 sebagai agen pensulfonasi karena gas SO3 bersifat
reaktif dengan metil ester sehingga proses sulfonasi dapat berlangsung lebih cepat. Proses produksi surfaktan metil ester sulfonat dengan reaktan gas SO3
dapat menggunakan single tube falling film reactor. Metil ester yang masuk ke dalam reaktor memiliki ketebalan film tertentu dan bereaksi dengan gas SO3 dengan suhu dan waktu yang dapat ditentukan. Surfaktan MES sebagai
bahan yang akan diaplikasikan untuk menurunkan tegangan antarmuka, maka perlu dilakukan uji terhadap kinerjanya akibat pengaruh suhu pemanasan, lama pemanasan, tingkat salinitas dan tingkat kesadahan.
B. TUJUAN PENELITIAN
II.
TINJAUAN PUSTAKA
A. SURFAKTAN
Surfaktan adalah molekul organik yang jika dilarutkan ke dalam
pelarut pada konsentrasi rendah maka akan memiliki kemampuan untuk
mengadsorb (atau menempatkan diri) pada antarmuka, sehingga secara
signifikan mengubah karakteristik fisik antarmuka tersebut. Antarmuka adalah
batas antara dua sistem seperti cairan-cairan, padatan-cairan dan gas-cairan.
Suatu senyawa disebut sebagai surfaktan didasarkan pada kemampuannya
untuk membentuk lapisan tunggal (monolayer) yang terorientasi pada antarmuka (udara/air atau minyak/air), dan yang lebih penting adalah
kemampuannya untuk membentuk struktur misel atau gelembung pada suatu
fasa. Surfaktan memiliki aktivitas permukaan yang tinggi. Karena sifat
aktivitas permukaannya yang tinggi ini, seringkali surfaktan disebut sebagai
bahan aktif permukaan (surface-active agent). Bahan aktif permukaan ini mampu memodifikasi karakteristik permukaan suatu cairan atau padatan (Hui,
1996e).
Menurut Rieger (1985), surfaktan adalah suatu zat yang bersifat aktif
permukaan yang dapat menurunkan tegangan antarmuka (interfacial tension, IFT) minyak-air. Surfaktan memiliki kecenderungan untuk menjadikan zat
terlarut dan pelarutnya terkonsentrasi pada bidang permukaan. Sifat-sifat
surfaktan adalah mampu menurunkan tegangan permukaan, tegangan
antarmuka, meningkatkan kestabilan partikel yang terdispersi dan mengontrol
jenis formasi emulsi (misalnya oil in water (o/w) atau water in oil (w/o). Di samping itu, surfaktan akan terserap ke dalam permukaan partikel minyak atau
air sebagai penghalang yang akan mengurangi atau menghambat
penggabungan (coalescence) dari partikel yang terdispersi.
Umumnya bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan
surfaktan adalah minyak bumi, minyak nabati, karbohidrat dan hasil aktivitas
mikroorganisme. Penggunaan minyak bumi sebagai bahan baku surfaktan
semakin menipis karena persediaannya yang tidak dapat diperbaharui. Maka,
digunakan sebagai bahan baku surfaktan. Hal ini didukung dengan potensi
minyak sawit Indonesia yang terbesar di dunia sebagai negara pengekspor
minyak sawit.
Molekul surfaktan dapat digambarkan seperti berudu atau bola raket
mini yang terdiri dari bagian kepala dan ekor (Gambar 1). Bagian kepala dan
ekor memiliki sifat yang berbeda, disebabkan karena struktur molekulnya
yang tak seimbang (konfigurasi kepala-ekor). Bagian kepala yang bersifat
hidrofilik merupakan bagian yang sangat polar dan larut dengan air.
Sementara bagian ekor bersifat hidrofobik merupakan bagian nonpolar dan
lebih tertarik ke minyak atau lemak. Konfigurasi kepala-ekor tersebut
membuat surfaktan memiliki fungsi dan peranan yang beragam di industri
(Hui, 1996e).
Pada Gambar 2 disajikan tampilan visual orientasi bagian kepala
surfaktan pada media air. Sementara surfaktan yang saling berikatan hingga
membentuk satu lapisan disajikan pada Gambar 3.
Gambar 2. Tampilan orientasi bagian kepala surfaktan pada media air
Kepala (hidrofilik) Ekor (hidrofobik)
Gambar 3. Surfaktan yang membentuk satu lapisan
Surfaktan dapat dibagi atas empat kelompok, yaitu kelompok anionik,
nonionik, kationik dan amfoterik. Menurut Matheson (1996), kelompok
surfaktan terbesar yang diproduksi dan digunakan oleh berbagai industri
(dalam jumlah) adalah surfaktan anionik. Karakteristiknya yang hidrofilik
disebabkan karena adanya gugus ionik yang cukup besar, yang biasanya
berupa grup sulfat atau sulfonat. Beberapa contoh surfaktan anionik yaitu
linear alkilbenzen sulfonat (LAS), alkohol sulfat (AS), alkohol eter sulfat
(AES), alfa olefin sulfonat (AOS), parafin (secondary alkane sulfonate, SAS), dan metil ester sulfonat (MES).
Karakteristik utama surfaktan adalah pada aktivitas permukaannya.
Surfaktan mampu meningkatkan kemampuan menurunkan tegangan
permukaan dan antarmuka suatu cairan, meningkatkan kemampuan
pembentukan emulsi minyak dalam air, mengubah kecepatan agregasi partikel
terdispersi yaitu dengan menghambat dan mereduksi flokulasi dan
penggabungan (coalescence) partikel yang terdispersi, sehingga kestabilan partikel yang terdispersi makin meningkat. Surfaktan mampu
mempertahankan gelembung atau busa yang terbentuk lebih lama.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa surfaktan merupakan
bahan aktif permukaan yang dapat menurunkan tegangan permukaan air
dalam konsentrasi rendah. Surfaktan dapat menurunkan tegangan permukaan
air dari 73 dyne/cm menjadi 30 dyne/cm setelah ditambahkan surfaktan 0,005
B. SURFAKTAN METIL ESTER SULFONAT (MES)
Metil Ester Sulfonat (MES) yang merupakan golongan baru dalam
kelompok surfaktan anionik telah mulai dimanfaatkan sebagai bahan aktif
pada produk-produk pencuci dan pembersih (washing and cleaning products). Pemanfaatan surfaktan MES sebagai bahan aktif pada deterjen telah banyak
dikembangkan karena prosedur produksinya mudah, memperlihatkan
karakteristik dispersi yang baik, sifat detergensinya tinggi walaupun pada air
dengan tingkat kesadahan yang tinggi (hard water) dan tidak adanya fosfat,
mempunyai asam lemak C16 dan C18 yang mampu memberikan tingkat
detergensi yang terbaik, memiliki sifat toleransi terhadap ion Ca yang lebih
baik, memiliki tingkat pembusaan yang lebih rendah dan memiliki stabilitas
yang baik terhadap pH. Hasil pengujian di laboratorium memperlihatkan
bahwa laju biodegradasi MES serupa dengan alkohol sulfat (AS) dan sabun,
namun lebih cepat dibandingkan LAS. Hal tersebut menyebabkan metil ester
sulfonat pada masa mendatang diindikasikan akan menjadi surfaktan anionik
yang paling penting.
Surfaktan metil ester sulfonat (MES) merupakan salah satu jenis
surfaktan anionik, yaitu surfaktan yang bermuatan negatif pada gugus
hidrofiliknya atau bagian aktif permukaan. Minyak yang dapat digunakan
untuk produksi MES adalah minyak nabati sepert minyak sawit, minyak
kedelai, minyak jagung dan minyak rapeseed. Surfaktan MES memiliki kelemahan yaitu gugus ester pada struktur MES cenderung mengalami
hidrolisis baik pada kondisi asam maupun basa. Kecepatan reaksi hidrolisis
akan semakin cepat dengan meningkatnya suhu (Ketaren, 1986; Rosen, 2004).
Penelitian mengenai proses pembuatan MES dari minyak sawit sudah
dilakukan oleh Hapsari (2003) dan Mahardika (2003) tetapi MES yang
dihasilkan menggunakan reaktan NaHSO3. Setelah proses sulfonasi MES
yang dihasilkan perlu dimurnikan. Surfaktan MES yang belum dimurnikan
mengandung produk-produk hasil samping berupa garam (disalt) yang tidak larut sehingga akan mengganggu kinerja MES sebagai surfaktan. Disalt
mempunyai sensitivitas terhadap kesadahan air lebih tinggi daripada MES dan
fleksibilitas menurun terutama dalam fungsinya sebagai bahan aktif
permukaan penurun tegangan antarmuka.
Sintesis metil ester sulfonat merupakan proses kimiawi metil ester
sebagai bahan baku dengan gas SO3. Bahan baku metil ester yang digunakan
dalam proses sulfonasi merupakan produk turunan dari minyak sawit yang
tidak terhidrogenasi dengan karakteristik kualitas yang ditunjukkan dengan
nilai bilangan iod dan parameter lainnya (MacArthur, 1998). Karakteristik
metil ester yang digunakan untuk sulfonasi dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Karakteristik metil ester untuk bahan baku metil ester sulfonat
Parameter P & G
Bilangan Asam (mgKOH/ g ME)
Komposisi asam lemak metil ester (%) :
C18 0.00 46.24 35.68 64.45
>C18 0.00 0.74 1.01 1.06
Sumber : MacArthur (1998)
Metil ester merupakan suatu senyawa yang mengandung gugus –
COOR dengan R dapat membentuk alkil suatu ester. Suatu ester dapat
dibentuk langsung antara suatu asam lemak dengan alkohol yang dinamakan
dengan esterifikasi. Suatu asam karboksilat merupakan suatu senyawa
organik yang mengandung gugus karboksil –COOH. Gugus karboksil
mengandung sebuah gugus karbonildan sebuah gugus hidroksil (Fessenden
Proses sulfonasi untuk menghasilkan surfaktan MES dapat dilakukan
dengan mereaksikan reaktan seperti SO3, H2SO4, NaHSO3, NH2SO3H,
ataupun ClSO3H dengan minyak, asam lemak ataupun ester asam lemak (Kirk
dan Othmer, 1964; Bernardini, 1983; Foster, 1996). Menurut Foster (1996),
SO3 terlalu reaktif dan sangat eksotermik.
Metil ester sulfonat merupakan surfaktan yang dihasilkan melalui
proses sulfonasi metil ester (MacArthur et al., 1998). Metil ester atau biodiesel dihasilkan melalui reaksi transesterifikasi antar trigliserida berbahan
baku minyak sawit, minyak kelapa atau lemak hewan dengan metanol.
Gambar 4 menunjukkan reaksi transesterifikasi antara trigliserida dan metanol
menghasikan metil ester dan gliserol.
RCOOCH2 CH2OH
RCOOCH2 + 3 CH3OH Æ 3 RCOOCH3 + CHOH
RCOOCH2 CH2OH
Minyak Metanol Metil Ester Gliserol
Gambar 4. Reaksi transesterifikasi trigliserida dan metanol
Di industri, proses sulfonasi secara langsung dilakukan dengan cara
mereaksikan agen sulfonasi ke minyak pada suhu reaksi yang lebih tinggi dari
titik leleh minyak. Setelah sulfonasi, sisa pereaksi yang tidak bereaksi
dipisahkan dari produk hasil sulfonasi melalui proses pencucian
menggunakan air garam, kemudian dinetralisasi menggunakan larutan alkali.
Pencucian dan netralisasi dilakukan pada suhu antara 40 – 55 oC (Pore, 1976).
Reaksi sulfonasi molekul asam lemak dapat terjadi pada tiga sisi yaitu
(1) gugus karboksil; (2) bagian α-atom karbon; (3) rantai tidak jenuh (ikatan
rangkap) (Gambar 5). Pemilihan proses sulfonasi tergantung pada banyak
faktor yaitu: karakteristik dan kualitas produk akhir yang diinginkan, kapasitas
produksi yang disyaratkan, biaya bahan kimia, biaya peralatan proses, sistem
pengamanan yang diperlukan, dan biaya pembuangan limbah hasil proses.
Untuk menghasilkan kualitas produk terbaik, beberapa perlakuan penting
konsentrasi grup sulfat yang ditambahkan (SO3, NaHSO3, asam sulfit), waktu
netralisasi, pH dan suhu netralisasi (Foster, 1996).
Gambar 5. Kemungkinan terikatnya pereaksi kimia dalam proses sulfonasi
Bahan baku untuk surfaktan MES adalah metil ester yang diperoleh
dari proses esterifikasi minyak. Minyak yang akan dijadikan bahan untuk
produksi surfaktan harus diolah menjadi metil ester terlebih dahulu. Hal ini
karena minyak merupakan trigliserida yang mengandung gliserol. Dalam
proses transesterifikasi akan dihasilkan metil ester dan hasil samping gliserol
(Ketaren, 1986).
Distribusi asam lemak yang beragam sebagai penyusun minyak sawit
dan adanya ikatan rangkap dalam struktur karbon menyebabkan minyak sawit
menjadi tidak stabil terhadap pengaruh oksidasi. Hampir setengah bagian
komponen penyusun minyak sawit merupakan asam lemak tidak jenuh. Metil
ester sebagai produk turunan minyak sawit juga mengandung ikatan ester
tidak jenuh di dalamnya. Asam lemak yang telah diolah menjadi metil ester
akan menjadikan senyawa yang lebih stabil terhadap suhu rendah maupun
tinggi.
Metil ester mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan asam
lemak, diantaranya yaitu: 1) Pemakaian energi sedikit karena membutuhkan
suhu dan tekanan lebih rendah dibandingkan dengan asam lemak; 2) Peralatan
yang digunakan murah. Metil ester bersifat non korosif dan metil ester
dihasilkan pada suhu dan tekanan lebih rendah, oleh karena itu proses
pembuatan metil ester menggunakan peralatan yang terbuat dari karbon steel,
sedangkan asam lemak bersifat korosif sehingga membutuhkan peralatan
stainless steel yang kuat; 3) lebih banyak menghasilkan hasil samping gliserin
yaitu konsentrat gliserin melalui reaksi transesterifikasi kering sehingga
lemak menghasilkan gliserin yang masih mengandung air lebih dari 80%,
sehingga membutuhkan energi yang lebih banyak; 4) metil ester lebih mudah
didistilasi karena titik didihnya lebih rendah dan lebih stabil terhadap panas;
5) dalam memproduksi alkanolamida, ester dapat menghasilkan superamida
dengan kemurnian lebih dari 90% dibandingkan dengan asam lemak yang
menghasilkan amida dengan kemurnian hanya 65-70%; 6) metil ester mudah
dipindahkan dibandingkan asam lemak karena sifat kimianya lebih stabil dan
non korosif.
Proses sulfonasi metil ester dengan gas SO3 dapat dilakukan pada
skala laboratorium, skala pilot maupun skala industri. Peralatan sulfonasi yang
dilakukan pada skala laboratorium yaitu bejana gelas berbentuk silinder
dengan diameter bagian dalam 4 cm dan tingginya 45 cm. Gelas tersebut
dilengkapi dengan jaket pendingin, saluran masuk dan keluar gas, dan
termometer. Gas masuk melalui saluran atas dengan diameter saluran 8 mm.
Proses sulfonasi pada skala ini dapat berlangsung secara kontinyu dengan
lapisan film tipis pada reaktor. Untuk menghasilkan surfaktan metil ester
sulfonat dengan kapasitas besar dapat meningkatkan skala peralatan produksi
tersebut (Stein dan Baumann, 1974).
Menurut Stein dan Baumann (1974), lapisan metil ester bereaksi
dengan gas SO3 dari reaktor bagian atas. Pada reaktor dipasang saluran
pemisah antara fase gas dan fase cairan. Metil ester yang masuk ke dalam
reaktor dengan laju alir 600 gram/jam dan gas SO3 dengan konsentrasi 5 %.
Sulfonasi metil ester dilakukan pada suhu 70-90 °C dengan rasio mol metil
ester dan gas SO3 yaitu 1 : 1,3. Gas SO3 bersifat eksotermis dan reaksi terjadi
secara cepat dengan metil ester pada suhu yang lebih rendah akibat adanya
gugus karbonil dari ester, tetapi sulfonasi belum tercapai. Untuk itu diperlukan
suhu yang lebih tinggi agar sulfonasi berlangsung sempurna.
Penggunaan suhu 70-90 °C merupakan kondisi ideal dalam sulfonasi
pada falling film reactor. Pada awal reaksi, terjadi kontak bahan dengan gas SO3 secara cepat hingga mencapai keseimbangan reaksi. Pada suhu tersebut
dapat menghasilkan MES dengan bahan aktif 97 %. Metil ester sulfonat yang
dan tegangan antarmuka. Reaksi sulfonasi metil ester dengan gas SO3 dapat
digambarkan sebagai berikut.
Gambar 6. Reaksi sulfonasi untuk pembuatan MES (Watkins, 2001)
Sulfonasi metil ester terjadi dalam dua tahap. Pertama, adanya kontak
bahan secara cepat antara gas SO3 dengan metil ester. Tahap kedua reaksi
berlangsung lambat, suhu reaksi bergantung pada posisi gugus
α.
Untukmencapai sulfonasi 95 % membutuhkan waktu 50-60 menit dengan ekses gas
SO3 30 % mol dan suhu 80 °C. Tetapi, produk yang dihasilkan berwarna gelap
yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemucatan
terhadap metil ester sulfonat yang dihasilkan (Stein dan Baumann, 1974).
Sulfonasi metil ester untuk memproduksi MES lebih kompleks dari
pada sulfonasi dengan bahan baku yang lain. Karena dalam memproduksi
surfaktan anionik yang lain seperti linear alkilbenzen sulfonat (LAS), alkohol
sulfat (AS), alkohol eter sulfat (AES), alfa olefin sulfonat (AOS) tidak
membutuhkan proses pemucatan (bleaching). Berbeda dengan MES yang berwarna gelap sehingga memerlukan proses pemucatan (Roberts et al.,
2008). Beberapa tahapan penting dalam memproduksi metil ester sulfonat
antara lain;
1. Kontak antara metil ester dengan gas SO3
Jika rasio mol antara metil ester dengan gas SO3 kurang dari 1,2 maka
tidak akan tercapai konversi sempurna. Pada tahap ini biasanya
menggunakan falling film reactor. Jika netralisasi dilakukan pada tahap ini, maka metil ester tidak dapat terkonversi sempurna menjadi MES,
dengan nilai konversi sekitar 60-75%. Netralisasi produk pada tahap ini
menjadikan MES sangat sedikit dan sebagian besar akan terjadi disalt.
SO3 + Rn C OCH3
O
Sulfur trioksida Metil ester
C C OCH3
O
Rn-1
SO2OH
2. Tahapan penyempurnaan reaksi
Dalam hal ini perlu aging dengan suhu minimal 80 °C. dengan rasio mol 1,2 selama 45 menit pada suhu 90 °C atau 3,5 menit pada suhu 120
°C akan menghasikan konversi sebesar 98 %.
3. Tahap netralisasi
Jika reaksi menghasilkan asam dan tidak dinetralkan, maka akan
mengurangi kualitas MES yang dihasilkan seperti warna gelap, sangat
kental bahkan akan terbentuk endapan. Netralisasi dilakukan untuk
mencegah pH yang terlalu rendah dan mencegah hidrolisis yang
menyebabkan “disalt”.
Menurut MacArthur dan Sheat (2002), penelitian mengenai produksi
MES skala pilot plant secara sinambung telah dilakukan oleh Chemiton Corporation di Amerika Serikat. Produksi MES dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu tahap proses sulfonasi dimulai dengan pemasukan bahan baku
metil ester dan gas SO3 ke reaktor dan selanjutnya diikuti dengan tahap
pencampuran di digester, tahap pemucatan, tahap netralisasi, dan tahap pengeringan. Bahan baku metil ester dimasukkan ke reaktor pada suhu 40 -
56 oC, dengan konsentrasi gas SO3 adalah 7 % dan suhu gas SO3 sekitar 42
o
C. Nisbah mol antara reaktan SO3 dan metil ester sekitar 1,2 - 1,3. MES
segera ditransfer ke digester pada saat mencapai suhu 85oC, dengan lama waktu pencampuran adalah 0,7 jam (42 menit). Proses pemucatan dilakukan
dengan mencampurkan MES hasil digester dengan pelarut metanol sekitar 31
- 40 % (b/b, MES basis) dan H2O2 50 % sekitar 1 - 4 persen (b/b, MES basis)
pada suhu 95 - 100 oC selama 1 - 1,5 jam. Ditambahkan oleh Sheats dan
Foster (2003) bahwa bleached MES secara kontinyu dinetralisasi hingga mencapai nilai pH 6,5 – 7,5. Proses netralisasi dilakukan dengan
mencampurkan bleached MES dengan pelarut NaOH 50 % pada suhu 55 oC. Kemampuan surfaktan MES dalam menurunkan tegangan antarmuka
minyak-air disebabkan oleh kemampuan surfaktan MES dalam meningkatkan
gaya tarik menarik antara dua fasa yang berbeda polaritasnya. Hal ini terjadi
karena struktur dari surfaktan yang memiliki dua gugus fungsional yang
tension, IFT) memainkan peranan penting di dalam kinerja surfaktan. Bahan yang umum digunakan untuk memodifikasi tegangan antarmuka dan
tegangan permukaan suatu zat adalah surfaktan yang berasal dari istilah asing
surfactant (singkatan dari surface active agent).
C. OLEIN SAWIT
Salah satu dari beberapa tanaman golongan palm yang dapat
menghasilkan minyak adalah kelapa sawit (Elais guinensis JACQ). Tanaman kelapa sawit secara umum tumbuh dengan waktu rata-rata 20 – 25 tahun.
Pada tiga tahun pertama disebut sebagai kelapa sawit muda, hal ini
dikarenakan kelapa sawit tersebut belum menghasilkan buah. Kelapa sawit
mulai berbuah pada usia empat sampai enam tahun. Pada usia tujuh sampai
sepuluh tahun disebut sebagi periode matang (the mature periode), dimana pada periode tersebut mulai menghasilkan buah tandan segar ( fresh fruit bunch). Tanaman kelapa sawit pada usia sebelas sampai dua puluh tahun mulai mengalami penurunan produksi buah tandan segar. Daerah penanaman
tanaman sawit di Indonesia adalah daerah Jawa Barat (Lebak dan Tangerang),
Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh (Ketaren, 1986).
Kelapa sawit menghasilkan dua macam minyak yang berlainan
sifatnya, yaitu minyak yang berasal dari sabut (mesokarp) dan minyak yang
berasal dari biji (kernel). Minyak sawit yang dihasilkan dari sabut dikenal
dengan crude palm oil (CPO) dan dari inti (biji) disebut minyak inti sawit atau palm kernel oil (PKO).
Minyak sawit kasar (CPO) merupakan produk level pertama yang
dapat memberikan nilai tambah sekitar 30 % dari nilai tambah buah segar.
Pemisahan asam lemak penyusun trigliserida pada minyak sawit dapat
dilakukan dengan menggunakan proses fraksinasi. Secara umum fraksinasi
minyak sawit dapat menghasilkan 73 % olein, 21 % stearin, 5 % Palm Fatty Acid Distillate (PFAD), dan 0,5 % limbah. Olein sawit merupakan fase cair yang dihasilkan dari proses fraksinasi minyak sawit setelah melalui
pemurnian. Karakteristik fisik olein sawit bersifat cair pada suhu ruang,
berbeda dengan minyak sawit (CPO) yang bersifat semi solid. Komposisi
Tabel 3. Komposisi asam lemak beberapa produk sawit
Asam Lemak Jenis Bahan
CPOa) PKOb) Oleinc) Stearinc) PFADd)
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa olein sawit didominasi oleh
asam lemak C18:1. Surfaktan dari C18 mempunyai daya deterjensi yang
tinggi. Menurut Swern (1979), panjang molekul sangat kritis untuk
keseimbangan kebutuhan gugus hidrofilik dan lipofilik. Apabila rantai
hidrofobik terlalu panjang, akan terjadi ketidaksinambungan, terlalu besarnya
afinitas untuk gugus minyak atau lemak atau terlalu kecilnya afinitas untuk
gugus air. Hal ini akan ditunjukkan oleh keterbatasan kelarutan dalam air.
Demikian juga sebaliknya, apabila rantai hidrofobiknya terlalu pendek,
komponen tidak akan terlalu bersifat aktif permukaan (surface active) karena ketidakcukupan gugus hidrofobik dan akan memiliki keterbatasan kelarutan
dalam minyak. Pada umumnya panjang rantai terbaik untuk surfaktan adalah
asam lemak dengan 10-18 atom karbon.
Olein sawit baik digunakan sebagai bahan baku surfaktan metil ester
sulfonat (MES), hal ini dikarenakan olein sawit dominan mengandung asam
lemak C18 sebesar 40.7 – 43.9 % (Hui, 1996). Metil ester dari asam lemak
tidak jenuh sangat mudah untuk disulfonasi oleh gas SO3, sehingga reaksi
pada metil ester tidak jenuh akan lebih cepat dengan metil ester jenuh.
Olein merupakan fraksi cair dari minyak sawit, berwarna kuning
sampai jingga dan diperoleh dari hasil fraksinasi minyak dari daging buah
mengandung asam oleat dengan kadar yang lebih tinggi bila dibandingkan
dengan stearin (fraksi padat dari minyak sawit). Karakterisik mutu olein sawit
dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Karakteristik mutu olein sawit
Parameter Syarat
D. PENGARUH SUHU DAN LAMA PEMANASAN
Menurut Anwar (2003), suhu dapat mempercepat terjadinya reaksi
dengan memperluas distribusi energi dan memperbanyak jumlah
molekul-molekul yang memiliki energi kinetik lebih tinggi dari pada energi
aktivasinya. Pada kondisi tersebut memungkinkan semakin besarnya peluang
untuk terjadinya tumbukan sehingga mempercepat terjadinya reaksi
penguraian MES.
Kenaikan nilai tegangan antarmuka diduga akibat terjadinya degradasi
termal seperti yang terjadi pada surfaktan alfa olefin sulfonat yang diteliti oleh
Hui dan Tuvell (1998) dan surfaktan MES yang diteliti oleh Hidayati (2005)
dimana terjadi proses desulfonasi ikatan C-S pada struktur surfaktan MES
yang ditandai dengan berkurangnya tinggi peak gugus sulfonat. Proses
degradasi ini terjadi semakin cepat dengan meningkatnya suhu pemanasan.
Hui dan Tuvell (1998), menjelaskan bahwa gugus sulfonat yang
terurai kemudian membentuk asam sulfat. Asam sulfat yang terbentuk dalam
proses desulfonasi akan menjadi katalisator untuk terjadinya penguraian
ikatan C-S selanjutnya. Latifah et al (2001) menambahkan bahwa adanya katalisator dalam suatu reaksi kimia akan mengubah mekanisme reaksi
dengan membuat tahapan reaksi yang memiliki energi pengaktifan lebih
rendah sehingga reaksi berjalan lebih cepat dibandingkan reaksi dengan
E. PENGARUH SALINITAS
Salinitas adalah konsentrasi total ion-ion (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NO3-,
Cl-, HCO3-, SO42-) yang ada di air (Boyd, 1982). Salinitas merupakan jumlah
seluruh bahan-bahan yang terlarut dalam garam yang terkandung di dalam
satu kilogram air laut, dengan asumsi semua karbonat dikonversi menjadi
oksida, maka bromin dan iodin telah diganti diklorin dan seluruh bahan
organik telah teroksidasi.
Peningkatan salinitas akan menaikkan tegangan antarmuka yang
dihasilkan dalam pengujian. Penurunan efektifitas surfaktan MES dalam
menurunkan tegangan antarmuka seiring dengan peningkatan salinitas
dikarenakan kandungan natrium klorida yang merupakan senyawa garam
dengan ikatan ion. Senyawa garam apabila bercampur dengan air akan terurai
menjadi kation (Na+) dan anion (Cl-). Adanya ion-ion akan mengurangi
kinerja surfaktan MES yang disebabkan terikatnya kation pada senyawa aktif
(MacArthur, 1998).
F. PENGARUH KESADAHAN
Kesadahan pada dasarnya menggambarkan kondisi ion Ca2+, Mg2+,
dan ion-ion logam lainnya seperti Al3+, Fe2+, Mn2+, Sr2+, Zn2+, dan ion H- yang
terlarut dalam air. Kesadahan total berhubungan dengan alkalinitas total,
karena kation-kation kesadahan dan anion-anion alkalinitas bersumber dari
larutan mineral karbonat (Boyd, 1982). Kesadahan dinyatakan dalam
miligram per liter setara CaCO3.
Kesadahan terbagi menjadi dua kelompok yaitu kesadahan kalsium
dan kesadahan magnesium yang didasarkan atas ion logam, sedangkan yang
kedua adalah kesadahan karbonat dan bikarbonat, yang didasarkan atas anion
yang berasosiasi dengan ion logam. Pengelompokkan kesadahan kalsium dan
magnesium berdasarkan kesadahan pada perairan alami yang banyak
disebabkan oleh kation kalsium dan magnesium dibandingkan dengan kation
lainnya (Boyd, 1990).
Dua tipe kesadahan adalah kesadahan sementara dan kesadahan
permanen. Pada kesadahan sementara, ion-ion kalsium dan magnesium
1982). Sebagai kation kesadahan, ion kalsium selalu berhubungan dengan
anion yang terlarut khususnya alkalinitas CO2-, HCO3- dan OH-. Kesadahan
sementara dapat dihilangkan dengan pemanasan, pada kesadahan permanen,
ion kalsium dan magnesium berasosiasi dengan ion sulfat (SO42-), klor (Cl-),
dan nitrat (NO3-) atau disebut juga kesadahan non karbonat. Kesadahan ini
III.
METODOLOGI PENELITIAN
A. BAHAN DAN ALAT
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metil ester olein
dari minyak sawit. Bahan kimia yang digunakan untuk proses produksi dan
pemurnian surfaktan MES adalah gas SO3, metanol, H2O2 4 % dan NaOH 50
%. Sedangkan bahan-bahan untuk analisa antara lain larutan kloroform,
larutan KI 10 %, larutan Na2S2O3 0,1 N, alkohol netral 95%, indikator
penolphtalein 1%, KOH 0,1 N, NaCl, CaCl2.2H2O, NaOH 0.1 N, campuran 50
% tuluen – 50 % etanol 95 %, campuran sikoheksan – asam asetat glasial,
N-cetylpyridium chloride dan xylen.
Peralatan yang digunakan adalah reaktor sulfonasi single tube falling film reactor, Cole-parmer surface tensiometer, hotplate, termometer, piknometer, tabung reaksi, pH meter, timbangan analitik, peralatan gelas,
pipet, oven, block digester, vortex mixer, pipet dan hotplate stirer.
B. METODE PENELITIAN 1. Persiapan Sampel
1.1.Pembuatan Metil Ester
Bahan baku yang digunakan adalah olein dari minyak sawit.
Metil Ester Olein dibuat dengan proses transesterifikasi. Olein
dipanaskan sampai suhu 55 °C. Kemudian ditambahkan campuran
antara metanol 15 % dan KOH 1 %. Reaksi dilakukan selama 1 jam
dengan suhu 50 –60 °C. Selanjutnya dilakukan pemisahan antara
gliserol dan metil ester yang dihasilkan. Metil ester dianalisis untuk
bahan baku surfaktan MES.
1.2.Pembuatan Metil Ester Sulfonat
Tahap awal penelitian ini dilakukan dengan membuat
surfaktan metil ester sulfonat (MES) yang bersifat larut air. Surfaktan
MES dibuat dengan mereaksikan metil ester dengan pereaksi gas SO3
pada reaktor. Proses pembuatan dilakukan dengan menggunakan
SO3 dilakukan setelah suhu metil ester mencapai 80 °C. Proses
sulfonasi dilakukan selama 2 jam dengan kecepatan alir metil ester
yang masuk ke dalam reaktor adalah 100 ml/menit.
Metil ester sulfonat hasil reaksi ini umumnya gelap yang tidak
dapat dihindari dan memiliki derajat keasaman yang tinggi. Untuk itu
dilakukan proses pemucatan dan pemurnian pada MES untuk di uji
pada berbagai kondisi. Metil ester sulfonat dipanaskan sampai suhu
75 °C kemudian ditambahkan metanol 31 % dan H2O2 4 %. Reaksi
pemucatan dilakukan selama 1,5 jam. Netralisasi MES dilakukan
dengan menambahkan larutan NaOH 50 %. Selanjutnya dilakukan
penguapan metanol hingga didapatkan MES murni dengan pH netral.
Diagram alir proses pembuatan surfaktan MES dapat dilihat pada
Lampiran 2.
Produk MES yang dihasilkan selanjutnya dianalisa meliputi
uji kadar bahan aktif, bilangan asam, bilangan iod, pH, tegangan
permukaan, dan tegangan antar muka. Prosedur analisa dapat dilihat
pada Lampiran 3.
2. Penelitian Utama
2.1 Uji kinerja MES terhadap suhu dan lama pemanasan
Pada tahap penelitian ini dicoba pengaruh suhu dan lama
pemanasan terhadap kinerja surfaktan MES dalam menurunkan
tegangan permukaan dan tegangan antarmuka. Faktor suhu pemanasan
(A) yang digunakan terdiri dari 70, 80 dan 90 °C. Faktor lama
pemanasan (B) yang digunakan adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 hari.
Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak
lengkap faktorial dengan 2 faktor dengan model rancangan percobaan
Bj = Pengaruh faktor B pada taraf ke-j (j = 1, 2, 3)
(AB)ij = Pengaruh interaksi faktor A taraf ke-i dengan faktor B taraf
ke-j
εijk = Pengaruh kesalahan percobaan
Analisa yang dilakukan pengaruh suhu dan lama pemanasan
terhadap kinerja surfaktan MES adalah tegangan permukaan dan
tegangan antarmuka.
2.2 Uji kinerja MES terhadap pengaruh salinitas
Uji kinerja surfaktan MES dilakukan pada tingkat salinitas
dalam menurunkan tegangan permukaan dan tegangan antarmuka.
Faktor tingkat salinitas (C) untuk menguji kinerja surfaktan MES
pada kondisi salinitas terdiri dari 10.000 ppm, 20.000 ppm dan 30.000
ppm. Rancangan percobaannya adalah sebagai berikut.
Yij = µ + Ci+ εij
Keterangan :
Yijk = Nilai pengamatan dari tingkat salinitas ke-i, pada ulangan ke-j
µ = Nilai rata-rata
Ci = Pengaruh faktor C pada taraf ke-i (i = 1, 2,3)
εij = Pengaruh kesalahan percobaan
Analisa yang dilakukan pengaruh kondisi salinitas terhadap
kinerja surfaktan MES adalah tegangan permukaan dan tegangan
antarmuka.
2.3 Uji kinerja MES terhadap pengaruh kesadahan
Uji kinerja surfaktan MES dilakukan pada kondisi air sadah
dalam menurunkan tegangan permukaan dan tegangan antarmuka.
Faktor tingkat kesadahan (D) untuk menguji kinerja surfaktan MES
pada kondisi air sadah terdiri dari 100 ppm, 300 ppm dan 500 ppm.
Rancangan percobaannya adalah sebagai berikut.
Yij = µ + Di+ εij
Keterangan :
µ = Nilai rata-rata
Di = Pengaruh faktor D pada taraf ke-i (i = 1, 2,3)
εij = Pengaruh kesalahan percobaan
Analisa yang dilakukan pengaruh kondisi kesadahan terhadap
kinerja surfaktan MES adalah tegangan permukaan dan tegangan
IV.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. ANALISIS METIL ESTER
Metil ester yang digunakan dalam penelitian ini berbahan baku olein
sawit yang dihasilkan melalui reaksi transesterifikasi. Olein sawit yang
digunakan pada penelitian ini berasal dari PT. Asian Agri Group. Produksi
metil ester olein dilakukan pada skala 100 liter di pilot plant SBRC. Metil
ester olein yang dihasilkan dianalisis untuk persiapan bahan baku menjadi
surfaktan yang dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Hasil analisis metil ester olein minyak sawit
Parameter Unit Hasil Analisis
Kadar Air % 0.018
Bilangan Asam mg KOH/g ME 0.1856
Bilangan Penyabunan mg KOH/g ME 191.45
Bilangan Iod mg I2/g ME 72.52
Densitas g/cm3 0.9165
Dari hasil analisis metil ester olein diatas diketahui bahwa metil ester
olein sudah memenuhi standar kualitas untuk digunakan sebagai bahan baku
metil ester sulfonat.
B. ANALISIS SURFAKTAN MES
Proses pembuatan surfaktan metil ester sulfonat (MES) dilakukan
dengan mereaksikan metil ester dengan gas SO3 pada suhu reaksi 80 °C
dengan lama reaksi 2 jam. Proses reaksi ini dinamakan proses sulfonasi.
Proses sulfonasi pada penelitian ini menggunakan single tube falling film reaktor yang dapat dilihat pada Gambar 7.
Metil Ester yang masuk ke dalam reaktor memiliki lapisan 100
ml/menit, lapisannya cukup tipis sehingga gas yang masuk ke dalam reaktor
akan bereaksi dengan cepat untuk menjadi metil ester sulfonat. Proses
sulfonasi dilakukan secara kontinyu dengan memutarkan kembali ke dalam
Gambar 7. Single Tube Falling Film Reactor
Metil ester dialirkan ke dalam reaktor melalui saluran pada bagian atas
yang terdiri dari dua saluran. Lapisan metil ester akan terbentuk pada dinding
dalam reaktor. Setelah suhu mencapai 80 ºC, maka gas SO3 dialirkan melalui
saluran gas pada bagian atas reaktor. Gas SO3 akan bereaksi dengan lapisan
metil ester yang mengalir pada dinding. Semakin tipis lapisan metil ester,
reaksi sulfonasi akan semakin cepat. Sebaliknya, jika lapisan metil ester
smakin tebal maka sulfonasi akan terjadi secara lambat. Hal ini karena gas
SO3 yang bereaksi dengan metil ester harus lebih banyak. Laju alir metil ester
yang masuk ke dalam reaktor dalam penelitian ini adalah 100 ml/menit,
diduga memiliki lapisan yang tipis pada dinding reaktor.
Metil ester sulfonat yang dihasilkan dari reaktor cukup kental dan
berwarna gelap. Untuk meningkatkan kualitas surfaktan MES perlu dilakukan
pemurnian yang meliputi pemucatan dan netralisasi. Melalui proses
pemucatan, surfaktan akan lebih cerah seihingga memenuhi kriteria untuk
diaplikasikan dalam pembuatan deterjen. Metil ester sulfonat sebelum
pemucatan disajikan pada Gambar 8a dan sesudah pemucatan disajikan pada
a b
Gambar 8. Surfaktan Metil Ester Sulfonat sebelum pemucatan (8a)
dan setelah pemucatan (8b)
Surfaktan MES hasil pemucatan berwarna cerah seperti yang terlihat
pada Gambar 8b. sebelum dilakukan pemurnian dan pemucatan, surfaktan
MES cukup kental dan berwarna gelap. Surfaktan MES murni dianalisis
seperti yang disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Analisis surfaktan MES setelah proses pemurnian
Parameter Unit Hasil Analisis
pH - 6.69
Bilangan Asam mg KOH/g
MES
5.92
Bilangan Iod mg I2/g MES 33.99
Kadar Bahan aktif % 7.23
Densitas g/cm3 0.9803
Tegangan Permukaan air dyne/cm 65.22
Tegangan Antarmuka air + xilen dyne/cm 31.50
Tegangan Permukaan
Metil ester sulfonat hasil reaksi sulfonasi sebelum pemurnian dan
pemucatan memiliki keasaman yang tinggi dengan nilai bilangan asam 10.79
mg KOH/g MES. Setelah dilakukan pemurnian dan pemucatan, MES
berwarna lebih cerah dan derajat keasaman yang netral yaitu 6.69 dan nilai
bilangan asam 5.92 mg KOH/g MES. Proses netralisasi dilakukan pada
surfaktan MES semakin gelap yang tidak dapat dihindari, viskositas semakin
besar dan terbentuknya endapan MES. Derajat keasaman dari surfaktan MES
yang baik adalah pada pH netral. Apabila pH surfaktan MES rendah, maka
surfaktan bersifat semakin asam. Sementara jika pH melebihi netral, maka
dapat terjadi hidrolisis yang akan mementuk disalt. Hal ini akan
mengakibatkan keaktifan surfaktan MES berkurang.
Tegangan permukaan dirumuskan sebagai energi yang harus
digunakan untuk memperbesar permukaan suatu cairan sebesar 1 cm2.
Tegangan permukaan disebabkan adanya gaya tarik menarik dari molekul
cairan. Tegangan permukaan surfaktan MES dinyatakan dalam dyne per
centimeter (dyne/cm) atau miliNewton per meter (mN/m). Tegangan
permukaan timbul sebagai akibat ketidaksinambungan gaya tarik antar
molekul pada permukaan zat cair. Semakin besar ikatan antar
molekul-molekul dalam cairan maka semakin besar tegangan permukaan suatu
surfaktan (Bodner dan pardue, 1989).
Hasil pengukuran tegangan permukaan air sebelum penambahan
surfaktan MES sebesar 65.22 dyne/cm. Hasil pengukuran tegangan
permukaan air setelah penambahan surfaktan MES pada konsentrasi 1 %
sebesar 32.37 dyne/cm. Tegangan permukaan air mengalami penurunan 32.85
dyne/cm setelah penambahan surfaktan MES dari sebelumnya bernilai 65.22
dyne/cm. Dalam hal ini, surfaktan MES mampu menurunkan tegangan
permukaan air sebesar 50.36 %.
Pengukuran nilai tegangan permukaan dan tegangan antarmuka
surfaktan dilakukan pada suhu ruang pada konsentrasi surfaktan MES yang
ditambahkan 1 % (v/v). Jika pengukuran tegangan permukaan dan tegangan
antarmuka pada suhu tinggi akan menyebabkan kerusakan pada surfaktan
MES. Pada suhu tinggi, memungkinkan terjadinya oksidasi yang akan
menyebabkan surfaktan bersifat asam yang akan mempengaruhi kinerja dari
surfaktan MES. Konsentrasi surfaktan yang digunakan dalam pengujian
adalah 1 % (v/v). Pada konsentrasi lebih rendah dari 1 %, nilai tegangan
menurunkan tegangan permukaan dan tegangan antarmuka sampai bernilai
konstan pada konsentrasi 1 %.
Surfaktan adalah senyawa kimia yang memiliki aktivitas pada
permukaan cairan. Surfaktan memiliki struktur bipolar sehingga menyebabkan
surfaktan cenderung berada pada antarmuka antara fase yang berbeda derajat
polaritas dan ikatan hidrogen seperti air dan minyak.
Seperti dalam pengukuran tegangan permukaan, nilai tegangan
antarmuka juga diukur dengan alat cole parmer tensiometer. Dari hasil pengukuran, tegangan antarmuka air dan xilen sebelum penambahan surfaktan
MES sebesar 31.50 dyne/cm. Hasil pengukuran tegangan antarmuka air dan
xilen setelah penambahan surfaktan MES pada konsentrasi 1 % bernilai 12.25
dyne/cm. Tegangan antarmuka air dan xilen mengalami penurunan sebesar
19.25 dyne/cm. Dengan demikian dapat diketahui bahwa surfaktan MES
dapat menurunkan tegangan antarmuka air dan xilen 61,11 %.
C. PENGARUH SUHU DAN LAMA PEMANASAN
Penurunan tegangan permukaan dan tegangan antarmuka terjadi
karena struktur amphifilik surfaktan yang terdiri dari dua gugus dengan
derajat polaritas yang berbeda, yaitu gugus hidrofilik dan gugus hidrofobik.
Surfaktan dengan rumus kimia RSO3H dalam air akan terurai menjadi ion-ion
RSO3- dan H+.
Penelitian mengenai kinerja surfaktan MES dalam menurunkan
tegangan permukaan dan tegangan antarmuka akibat pengaruh suhu dan lama
pemanasan dilakukan pada suhu 70, 80 dan 90 °C dengan lama pemanasan 1,
2, 3, 4, 5 dan 6 hari.
Histogram nilai tegangan permukaan akibat pengaruh suhu pemanasan
70 ºC dapat dilihat pada Gambar 9. Nilai tegangan permukaan setelah
diberikan perlakuan pemanasan pada suhu 70 ºC mengalami kenaikan
dibandungkan sebelum pemanasn. Nilai tegangan permukaan meningkat dari
Gambar 9. Histogram nilai tegangan permukaan akibat pengaruh
suhu pemanasan 70 ºC
Kenaikan nilai tegangan permukaan juga terjadi pada suhu 80 ºC.
dimana nilai tegangan permukaan air setelah ditambahkan surfaktan MES 1 %
(v/v) meningkat dari 36.30 dyne/cm menjadi 37.60 dyne/cm. Hal ini berarti
bahwa kinerja surfaktan MES mengalami penurunan. Penyebabnya adalah
surfaktan MES mengalami degradasi akibat adanya pemanasan. Histogram
nilai tegangan permukaan akibat pengaruh suhu 80 ºC disajikan pada Gambar
10.
Gambar 10. Histogram nilai tegangan permukaan akibat pengaruh
suhu pemanasan 80 ºC
Pada suhu 90 ºC nilai tegangan permukaan bernilai 32.62 dyne/cm
terjadi pada suhu pemanasan 70 dan 80 ºC. Histogram nilai tegangan
permukaan akibat pengaruh suhu 90 ºC disajikan pada Gambar 11.
Gambar 11. Histogram nilai tegangan permukaan akibat pengaruh
suhu pemanasan 90 ºC
Dari hasil analisa ragam (ANOVA) menunjukkan adanya pengaruh
suhu dan lama pemanasan terhadap nilai tegangan permukaan yang dihasilkan
oleh metil ester sulfonat. Pada tingkat kepercayaan 99 %, suhu pemanasan dan
lama pemanasan berpengaruh sangat signifikan terhadap kenaikan tegangan
permukaan. Suhu dan lama pemanasan memberikan pengaruh positif terhadap
peningkatan nilai tegangan permukaan. Baik pada tingkat kepercayaan 99 %
maupun 95 %, interaksi antara suhu dan lama pemanasan tidak berpengaruh
signifikan terhadap kenaikan tegangan permukaan. Hasil analisa ragam
disajikan pada Lampiran 4B.
Hasil uji lanjut Duncan terhadap suhu pemanasan dengan tingkat
kepercayaan 95 % (α = 0.05) menunjukkan bahwa suhu pemanasan 70°C
memberikan pengaruh yang berbeda dengan suhu pemanasan 80 °C dan suhu
90 °C. Demikian juga suhu 80 °C memberikan pengaruh yang berbeda
terhadap suhu dan 90 °C. Masing-masing suhu pemanasan berbeda nyata satu
dengan lainnya pada tingkat kepercayaan 95 % (α = 0.05). Hasil uji lanjut
Duncan disajikan pada Lampiran 4C. Hasil uji lanjut Duncan terhadap lama
pemanasan menunjukkan bahwa lama pemanasan 1 hari berbeda nyata dengan
nyata dengan 3 hari. Sedangkan lama pemanasan 3 hari tidak berbeda nyata
dengan lama pemanasan 4 hari dan 5 hari. Lama pemanasan 6 hari berbeda
nyata satu dengan lainnya terhadap nilai tegangan permukaan dengan selang
kepercayaaan 95 % (α = 0.05) (Lampiran 4D).
Sementara itu, dalam uji kinerja surfaktan MES terhadap suhu dan
lama pemanasan menunjukkan bahwa kinerja surfaktan MES mengalami
penurunan terhadap nilai tegangan antarmuka air dan xilen. Tegangan
antarmuka setelah penambahan surfaktan MES dengan konsentrasi 1 %
berkisar 15.40 – 20.80 dyne/cm. Hal ini menunjukkan penurunan kinerja
surfaktan MES dimana sebelum dilakukan pemanasan, tegangan antarmuka
air dan xilen bernilai 12.25 dyne/cm.
Histogram hubungan antara suhu, lama pemanasan dan nilai tegangan
antarmuka disajikan pada Gambar 12. Kondisi perlakuan suhu 80 °C dengan
lama pemanasan 1 hari menghasilkan nilai tegangan antarmuka terendah
dengan nilai tegangan antarmuka sebesar 15.40 dyne/cm. Sedangkan nilai
tegangan antarmuka tertinggi dicapai pada perlakuan suhu 90 °C dengan lama
pemanasan 6 hari dengan nilai tegangan antarmuka sebesar 20.80 dyne/cm.
14
Gambar 12. Histogram nilai tegangan antarmuka akibat pengaruh
faktor suhu dan lama pemanasan
Setelah pemanasan pada suhu 70 °C, nilai tegangan antarmuka antara
air dan xilen meningkat dari 17.77 dyne/cm menjadi 19.72 dyne/cm. Kinerja
antarmuka akibat pemanasan pada suhu 80 °C yang dihasilkan dengan
penambahan surfaktan MES 1 % (v/v) mengalami kenaikan dari 15.40
dyne/cm menjadi 19.55 dyne/cm. Seperti yang terjadi pada suhu 70 dan 80 °C,
nilai tegangan antarmuka pada suhu 90 °C mengalami kenaikan dengan
bertambahnya lama pemanasan. Nilai tegangan antarmuka meningkat dari
18.02 dyne/cm menjadi 20.80 dyne/cm.
Suhu pemanasan berpengaruh terhadap nilai tegangan antarmuka
dikarenakan suhu dapat mempengaruhi kecepatan reaksi degradasi surfaktan
MES. Suhu dapat mempercepat terjadinya reaksi dengan memperluas
distribusi energi dan memperbanyak jumlah molekul yang mempunyai energi
kinetik lebih tinggi daripada energi aktivasinya. Dalam suhu yang lebih tinggi,
energi terdistribusi lebih luas sehingga semakin banyak jumlah
molekul-molekul yang memiliki energi kinetik melebihi energi aktivasinya. Dengan
demikian memungkinkan semakin besarnya peluang untuk terjadinya
tumbukan dan akan mempercepat terjadinya reaksi penguraian MES.
Hasil analisa ragam (ANOVA) menunjukkan adanya pengaruh suhu
dan lama pemanasan terhadap nilai tegangan antarmuka yang dihasilkan oleh
metil ester sulfonat. Baik pada tingkat kepercayaan 99 % (α = 0.01). maupun
95 % (α = 0.05), suhu pemanasan dan lama pemanasan berpengaruh sangat
signifikan terhadap kenaikan tegangan antarmuka. Suhu dan lama pemanasan
memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan nilai tegangan antarmuka.
Interaksi suhu pemanasan dan lama pemanasan memberikan pengaruh
signifikan terhadap nilai tegangan antarmuka pada selang kepercayaan 95 %
(α = 0.05) (Lampiran 7B).
Uji lanjut Duncan pada faktor suhu pemanasan menunjukkan semua
taraf suhu pemanasan (70, 80, dan 90 °C) berbeda nyata satu dan lainnya
terhadap nilai tegangan antarmuka air dan xilen pada tingkat kepercayaan 95
% (α = 0.05) (Lampiran 7C). Taraf suhu pemanasan 70 °C berbeda nyata
dengan taraf pemanasan 80 °C dan 90 °C dan sama halnya dengan taraf suhu
pemanasan 80 °C berbeda nyata dengan taraf pemanasan 70 °C dan 90 °C.
Perlakuan suhu pemanasan 90 °C memberikan nilai rataan tertinggi untuk
Hasil uji lanjut Duncan pada faktor lama pemanasan terhadap nilai
tegangan antarmuka pada tingkat kepercayaan 95 % (α = 0.05) (Lampiran 7D)
menunjukkan bahwa taraf lama pemanasan 1 hari berbeda nyata dengan taraf
lama pemanasan yang lainnya. Lama pemanasan 2 hari tidak berbeda nyata
dengan lama pemanasan 3 hari tetapi berbeda nyata dengan lama pemanasan
1, 3, 4, 5 dan 6 hari. Taraf lama pemanasan 3 hari tidak berbeda nyata dengan
4 hari tetapi berbeda nyata dengan lama pemanasan 1, 2, 5 dan 6 hari. Taraf
lama pemanasan 4 hari tidak berbeda nyata dengan lama pemanasan 5 hari
tetapi berbeda nyata dengan lama pemanasan 1, 2, 3 dan 6 hari. Taraf lama
pemanasan 6 hari berbeda nyata dengan lainnya. Perlakuan lama pemanasan 6
hari memberikan nilai rataan tertinggi untuk nilai tegangan antarmuka, yaitu
sebesar 20.05 dyne/cm.
Tegangan antarmuka yang rendah memiliki gaya tarik sesama molekul
sejenis (kohesi) yang akan berkurang, sedangkan gaya tarik antar molekul
yang tidak sejenis (adhesi) cenderung menguat. Penguatan gaya adhesi
mengakibatkan molekul surfaktan mampu membuat lapisan film yang
menyelimuti partikel dan akan mencegah penggabungan partikel sejenis.
Kenaikan nilai tegangan antarmuka diduga akibat terjadinya degradasi
termal seperti yang terjadi pada surfaktan alfa olefin sulfonat yang diteliti oleh
Hui dan Tuvell (1998) dan surfaktan yang diteliti oleh Hidayati (2005) dimana
terjadi proses desulfonasi ikatan C-S pada struktur surfaktan MES yang
ditandai dengan berkurangnya tinggi peak pada gugus sulfonat. Proses
degradasi terjadi semakin cepat seiring dengan meingkatnya suhu pemanasan
dan waktu pemanasan yang lama. Bertambahnya lama pemasanan
mengakibatkan nilai tegangan antarmuka surfaktan MES semakin meningkat.
Hui dan Tuvell (1998) menambahkan bahwa gugus sulfonat yang terurai
kemudian membentuk asam sulfat. Asam sulfat yang terbentuk dalam proses
desulfonasi akan menjadi katalisator untuk terjadinya penguraian ikatan C-S
selanjutnya. Ikatan C-S yang terurai menyebabkan surfaktan kehilangan
komponen aktifnya dan mengakibatkan surfaktan MES kurang bersifat aktif
D. PENGARUH TINGKAT SALINITAS
Penelitian mengenai kinerja surfaktan terhadap kondisi salinitas
dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh tingkat salinitas terhadap kinerja
surfaktan menurunkan tegangan permukaan dan tegangan antarmuka. Kadar
salinitas yang dicobakan dalam penelitian ini adalah 10.000 ppm, 20.000 ppm
dan 30.000 ppm NaCl (b/b). Tingkat salinitas ini menggambarkan kondisi air
di wilayah Indonesia. Surfaktan MES yang digunakan untuk aplikasi sebagai
bahan pencuci harus memiliki karakteristik deterjensi yang baik. Oleh karena
itu, pengujian surfaktan dilakukan pada rentang salinitas rendah sampai tinggi.
Hasil pengukuran tegangan permukaan pada kondisi salinitas
menunjukkan kisaran antara 34.42 dyne/cm hingga 36.10 dyne/cm (Lampiran
5A). Hal ini menunjukkan terjadi penurunan kemampuan surfaktan dalam
menurunkan tegangan permukaan air sebelumnya yaitu dai 32.37 dyne/cm
menjadi 36.10 dyne/cm. Dengan demikian, nilai tegangan permukaan
mengalami kenaikan dalam berbagai kondisi salinitas.
Berdasarkan analisa ragam terhadap nilai tegangan permukaan pada
tingkat kepercayaan 99 % maupun 95 % menunjukkan bahwa perlakuan
tingkat salinitas tidak memberikan pengaruh yang signifikan atau tidak
berbeda nyata (Lampiran 5B).
Histogram hubungan antara tingkat salinitas dengan nilai tegangan
permukaan disajikan pada Gambar 13. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa
nilai tegangan permukaan terendah terdapat pada perlakuan salinitas 10.000
ppm dengan nilai tegangan permukaan sebesar 34.42 dyne/cm. Sedangkan
nilai tegangan permukaan tertinggi dicapai oleh perlakuan salinitas 30.000
ppm dengan nilai tegangan permukaan sebesar 36.10 dyne/cm. Hal ini
menggambarkan bahwa dengan meningkatnya salinitas maka akan
meningkatkan nilai tegangan permukaan. Dengan bertambahnya ion-ion
garam dalam air, akan mempengaruhi kelarutan surfaktan MES dalam air.
Salinitas 30.000 ppm akan menghasilkan tegangan permukaan yang tinggi
karena pada kondisi ini, surfaktan MES menjadi sukar larut dalam air. Dengan
demikian kinerja surfaktan MES akan menurun dengan meningkatnya
30
Gambar 13. Histogram nilai tegangan permukaan akibat pengaruh
faktor salinitas
Pengukuran tegangan antarmuka pada kondisi salinitas setelah
penambahan surfaktan MES pada kondisi salinitas (10.000, 20.000 dan 30.000
ppm) menunjukkan kisaran rataan antara 16.25 dyne/cm hingga 19.17
dyne/cm (Lampiran 8A). Tegangan antarmuka pada kondisi salinitas
mengalami kenaikan daripada pada kondisi normal yaitu 12.25 dyne/cm.
Hasil analisa ragam (ANOVA) pada tingkat kepercayaan 95 % (α =
0.05) menunjukkan bahwa tingkat salinitas berpengaruh nyata terhadap nilai
tegangan antarmuka setelah penambahan surfaktan MES pada konsentrasi 1 %
(Lampiran 8B).
Uji lanjut Duncan pada faktor tingkat salinitas menunjukkan hasil
pada taraf salinitas 10.000 ppm berbeda nyata dengan taraf salinitas 20.000
dan 30.000 ppm terhadap nilai tegangan antar muka pada tingkat kepercayaan
95 %. Sedangkan taraf salinitas 20.000 tidak berbeda nyata dengan taraf
salinitas 30.000 ppm terhadap nilai tegangan antarmuka pada tingkat
kepercayaan 95 % (Lampiran 8C).
Pengaruh tingkat salinitas terhadap nilai tegangan antarmuka
ditunjukkan pada Gambar 14. Kondisi salinitas 10.000 ppm memiliki nilai
tegangan antarmuka terendah yaitu 16.25 dyne/cm. Sedangkan nilai tegangan
antarmuka tertinggi terdapat pada tingkat salinitas 30.000 ppm sebesar 19.17
CH3 CH COOCH3 + NaCl CH3 CH COONa + CH3Cl
SO3Na SO3Na
Gambar 15 . Reaksi pembentukan disalt 10
10000 ppm 20000 ppm 30000 ppm
Salinitas
Gambar 14. Histogram nilai tegangan antarmuka akibat pengaruh
faktor salinitas
Histogram nilai tegangan antarmuka menujukkan bahwa peningkatan
kondisi salinitas memberikan kecenderungan peningkatan nilai tegangan
antarmuka. Pada salinitas 30.000 ppm kandungan ion Na+ cukup banyak
sehingga menghambat kinerja surfaktan MES dalam menurunkan tegangan
antarmuka. Peningkatan salinitas akan menaikkan tegangan antarmuka yang
ditandai dengan semakin besarnya nilai tegangan antarmuka yang dihasilkan
dalam pengujian. Penurunan kinerja surfaktan MES dalam menurunkan
tegangan antarmuka seiring dengan meningkatknya salinitas. Hal ini
dikarenakan meningkatnya kandungan natrium klorida yang merupakan
senyawa garam dalam ikatan ion.
Senyawa garam jika dicampurkan dengan air akan terurai menjadi
kation (Na+) dan anion (Cl-). Dengan bertambahnya ion-ion ini akan
menurunkan kinerja surfaktan MES karena terikatnya kation natrium pada
senyawa aktif. Senyawa aktif yang mengikat dua kation natrium pada gugus
esternya akan membentuk senyawa disalt. Dengan terbentuknya senyawa
disalt ini akan menggurangi senyawa aktif pada surfaktan MES dalam
menurunkan tegangan antarmuka. Reaksi terbentuknya disalt dapat dilihat
E. PENGARUH TINGKAT KESADAHAN
Pengujian kinerja surfaktan MES pada kondisi kesadahan
dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kinerja surfaktan MES dari olein
sawit yang diaplikasikan sebagai penurun tegangan antarmuka dan tegangan
antarmuka dengan kondisi air sadah. Pengujian surfaktan MES dilakukan pada
kondisi sadah dengan taraf 100 ppm, 300 ppm dan 500 ppm.
Dalam air kondisi sadah yang ada adalah kesadahan umum, kesadahan
umum merupakan ukuran yang menunjukkan jumlah ion kalsium (Ca2+) dan
ion magnesium (Mg2+) dalam air. Pada umumnya, kesadahan dinyatakan
dalam satuan ppm (part per million /satu persejuta bagian) kalium karbonat, pada Tabel 7 dapat dilihat kriteria selang kesadahan.
Tabel 7. Kriteria selang kesadahan umum
No Kandungan Ca2+ / Mg2+) Golongan
Uji kinerja surfaktan pada kondisi kesadahan pada penelitian ini terdiri
dari tiga taraf yaitu 100 ppm, 300 ppm dan 500 ppm. Taraf ini diambil
berdasarkan pada kriteria selang kesadahan umum sehingga dapat mewakili
tingkat kesadahan rendah untuk 100 ppm, kesadahan sedang untuk 300 ppm
dan kesadahan tinggi untuk 500 ppm. Kemampuan deterjensi surfaktan MES
akibat kesadahan pada rentang kesadahan rendah tidak terlalu berpengaruh.
Oleh karena itu, pengujian surfaktan MES ini dilakukan pada rentang
kesadahan rendah sampai kesadahan tinggi.
Hasil analisa ragam (ANOVA) pada tingkat kepercayaan 95 % (α =
0.05) menunjukkan bahwa tingkat kesadahan berpengaruh nyata terhadap nilai
% (Lampiran 6B). Tingkat kesadahan memberikan pengaruh positif terhadap
peningkatan nilai tegangan permukaan.
Berdasarkan hasil uji lanjut Duncan pada faktor tingkat kesadahan
menunjukkan hasil pada taraf kesadahan 100 ppm berbeda nyata dengan taraf
kesadahan 300 ppm dan 500 ppm. Sedangkan taraf kesadahan 300 ppm tidak
berbeda nyata dengan taraf kesadahan 500 ppm terhadap nilai tegangan
permukaan pada tingkat kepercayaan 95 % (α = 0.05) (Lampiran 6C).
Pengaruh tingkat kesadahan terhadap nilai tegangan permukaan
ditunjukkan pada Gambar 16. Tingkat kesadahan 100 ppm memiliki nilai
tegangan permukaan terendah yaitu 35.12 dyne/cm. Sedangkan nilai tegangan
permukaan tertinggi terdapat pada tingkat kesadahan 500 ppm yaitu 37.32
dyne/cm. Sama halnya dengan surfaktan MES pada kondisi salinitas tinggi,
pada kondisi sadah tinggi surfaktan semakin sukar larut dalam air. Hal ini
karena banyaknya kation Ca2+ dari air sadah yang tinggi. Dengan menurunnya
kelarutan, maka surfaktan MES mengalami penurunan kemampuan dalam
menurunkan tegangan permukaan.
100 ppm 300 ppm 500 ppm
Ke sadahan
Gambar 16. Histogram nilai tegangan permukaan akibat pengaruh
faktor kesadahan
Berdasarkan analisa ragam terhadap nilai tegangan antarmuka pada
tingkat kepercayaan 99 % maupun 95 % menunjukkan bahwa perlakuan
tingkat kesadahan tidak memberikan pengaruh yang signifikan atau tidak
Dari hasil pengukuran terlihat bahwa tingkat kesadahan memberikan
hasil yang tidak berbeda nyata. Pada kesadahan rendah diduga bahwa pada
kesadahan 100 ppm yang dikategorikan kedalam kesadahan rendah, jumlah
kation Ca2+ dalam air masih berada pada batas toleransi sehingga kurang
berpengaruh terhadap kinerja surfaktan MES dalam menurunkan tegangan
antarmuka. Hal ini berarti bahwa surfaktan MES memiliki kinerja yang baik
dalam kondisi kesadahan.
Pengaruh tingkat kesadahan terhadap nilai tegangan antarmuka
ditunjukkan pada Gambar 17. Tingkat kesadahan 100 ppm memiliki nilai
tegangan permukaan terendah yaitu 17.40 dyne/cm. Nilai tegangan permukaan
tertinggi terdapat pada tingkat kesadahan 500 ppm yaitu 18.95 dyne/cm.
10
100 ppm 300 ppm 500 ppm
Ke sadahan
Gambar 17. Histogram nilai tegangan antarmuka akibat pengaruh
faktor kesadahan
Air yang memiliki sifat sadah mengandung kation Ca2+ atau Mg2+,
semakin tinggi tingkat kesadahan maka konsentrasi kation dalam air.semakin
tinggi. Surfaktan MES yang termasuk ke dalam kelompok surfaktan anionik
dengan gugus aktif yang bermuatan negatif, jika surfaktan ini bertemu dengan
air sadah maka gugus aktif tersebut akan membentuk ikatan dengan ion Ca2+
atau Mg2+. Dengan terbentuknya ikatan antara ion negatif pada surfaktan
dengan kation ini akan menurunkan kinerja surfaktan MES dalam
menurunkan tegangan antarmuka yang ditandai dengan besarnya nilai
Dari hasil penelitian menjukkan bahwa semakin tinggi tingkat
kesadahan maka nilai tegangan antarmuka semakin besar. Penyebabnya
adalah karena pada konsentrasi CaCl2 yang semakin meningkat maka jumlah
kalsium pada larutan akan semakin besar. Komponen tidak larut yang
terbentuk adalah (RCH(SO3Na)CO2Ca (Fessenden et al., 1998). Dengan adanya komponen tidak larut dalam larutan surfaktan akan mengurangsi sifat
kelarutan surfaktan dalam air sehingga kemampuan surfaktan MES dalam
V.
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Surfaktan metil ester sulfonat (MES) termasuk ke dalam kelompok surfaktan anionik dengan gugus aktifnya yang bermuatan negatif. Surfaktan MES dibuat dengan mereaksikan metil ester olein dengan reaktan gas SO3
dengan menggunakan single tube falling film reaktor dengan laju metil ester dengan ketebalan film 100 ml/menit. Surfaktan MES yang dihasilkan berwarna gelap dan memiliki nilai bilangan asam yang tinggi sehingga dilakukan proses pemurnian yang mencakup proses pemucatan dan netralisasi. Surfaktan MES hasil pemurnian berwarna cerah dengan pH netral.
Berdasarkan nilai tegangan permukaan dan tegangan antarmuka, dapat disimpulkan bahwa kinerja surfaktan MES dipengaruhi oleh suhu dan lama pemanasan. Faktor lama pemanasan memberikan pengaruh positif terhadap nilai tegangan permukaan dan tegangan antarmuka. Dimana, nilai tegangan permukaan meningkat dari 32.62 dyne/cm menjadi 41.00 dyne/cm dan nilai tegangan antarmuka dari 15.40 dyne/cm menjadi 20.80 dyne/cm. Demikian pula peningkatan salinitas dan kesadahan mempengaruhi kinerja surfaktan MES dalam menurunkan tegangan permukaan dan tegangan antarmuka. Pada faktor salinitas nilai tegangan permukaan meningkat dari 34.42 dyne/cm menjadi 36.10 dyne/cm dan nilai tegangan antarmuka dari 16.25 dyne/cm menjadi 19.17 dyne/cm. Kinerja surfaktan MES akibat faktor kesadahan cenderung mengalami penurunan. Dimana nilai tegangan pernukaan dan nilai tegangan antarmuka semakin besar. Nilai tegangan permukaan akibat kesadahan meningkat dari 35.12 dyne/cm menjadi 37.32 dyne/cm dan nilai tegangan antarmuka dari 17.40 dyne/cm menjadi 18.95 dyne/cm.
Secara umum, uji kinerja surfaktan MES yang diproduksi dengan menggunakan reaktan gas SO3 mengalami penurunan akibat pengaruh suhu
berakibat pada penurunan kinerja surfaktan MES dalam menurunkan tegangan permukaan dan tegangan antarmuka.
B. SARAN
1. Perlu dilakukan penelitian mengenai proses aging pada surfaktan MES setelah proses sulfonasi untuk penyempurnaan reaksi.
2. Perlu dilakukan penelitian mengenai produksi surfaktan MES pada skala yang lebih besar.
PENGARUH SUHU, LAMA PEMANASAN, SALINITAS DAN KESADAHAN TERHADAP KINERJA SURFAKTAN METIL ESTER
SULFONAT (MES) DARI OLEIN SAWIT
Oleh AANG ZEN
F34104088
2009
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DAFTAR PUSTAKA
Allen, T. O dan A.P.Roberts. 1993. Production Operation 2: Well Completions, Work over, and Stimulation. Oil and Gas Consultans International (OGCI) inc. Tulsa, Oklahoma.
Angstad, H.P., dan H. Tsao. 1982. Kinetics Study of Decomposition of Surfactant for Enhanced Oil Recovery. Tulsa, Oklahoma.
Anwar, N. 2003. Kimia Dasar II. Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
AOAC. 1995. Official Methods of Analysis of The Association of Official Analytical Chemistry. AOAC Inc., Washington.
ASTM D_1331.2000. Standard Test Methods Surface and Interfacial Tension of Surface Active Agents and Emulsion. Annual Book of ASTM Standard, Volume. 15 Easton MD, Philadelphia.
Badan Pusat Statistik. 2007. Statistik Indonesia 2000 – 2007. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
Basiron, Y. 1996. Bailey’s Industrial Oil and Fat Products. Vol.2 5th Edition. Hui, Y.H. (Ed.) John Willey and Sons, Inc. New York.
Bernardini, E. 1983. Vegetable Oils and Fats Processing. Volume II. Interstampa, Roma.
Bodner, G. M, dan H. L. Pardue. 1989. Chemistry An Experimental Science. John Willey and Sons. Inc, New York.
Boyd, C.E. 1982. Water Quality Management for Pond fish Culture. Elsevier Scientific Publishing Company, New York.
Boyd, C.E. 1990. Water Quality Management in Pond for Aquaculture. Elsevier Scientific Publishing Company, New York.
Fessenden, R.J dan Fessenden, J.S. 1982. Kimia Organik 2. Penerbit Erlangga, Jakarta.
Foster, N.C. 1996. Sulfonation and Sulfation Processes. In : Spitz, L. (Ed). Soap and Detergents : A Theoretical and Practical Review. AOCS Press, Champaign, Illinois.
Gomaa, E.E. 1997. Enhanced Oil Recovery : Modern Management Approach. Paper for IATMI-IWPL/MIGAS Conference, Surakarta, 28 Juli-1 Agustus 1997.
Hapsari, M. 2003. Kajian Pengaruh Suhu dan Kecepatan Pengadukan pada Psoses Produksi Surfaktan dari metil ester Minyak Inti Sawit dengan Proses Sulfonasi. Skripsi. Fateta IPB, Bogor.
Hidayati, S. 2005. Penentuan Gugus Sulfonat Hasil Degradasi Panas Pada Metil Ester Sulfonat Menggunakan Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Jurnal Sains dan Teknologi.
Hui, P.C., dan M. E. Tuvell. 1998. A Mechanistic Approach to the Thernal Degradation of Alfa Olefin Sulfonates. JAOAC,vo.65.page 1007.
Hui, Y.H. 1996e. Bailey’s Industrial Oil and Fat Products. 5th Edition. Volume 5. John Wiley & Sons, Inc., New York.
Kawauchi, A. 1997. Non Solvent Quantitation of Anionic Surfactant and Inorganic Ingredients in Laundry Detergent Product. JAOAC Press, Vol.74, No.7.
Ketaren, S.1986. Pengantar Teknologi Minyak dan Lemak. UI-Press, Jakarta.
Kirk, R.E. dan D.F. Othmer. 1964. Sulfonation and Sulfation. Di dalam : Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Vol. 19. Interscience Publisher, Inc., New York.
Latifah, K. 2001. Kimia Dasar I. Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Mahardika, A. D. 2003. Kajian Pengaruh Rasio Mol Reaktan dan Lama Reaksi Pada Proses Produksi Surfaktan Metil Ester Sulfonat. Skripsi. Fateta IPB, Bogor.
Matheson, K. L. 1996. Surfactant Raw Materials : Classification, Synthesis, and Uses. In : Soap and Detergents : A Theoritical and Practical Review. Spitz, L (Ed). AOCS Press, Champaign, Illionis.
MacArthur, B.W, Brooks B, Sheats W.B, dan Foster N.C. 1998. Meeting the Challenge of Methylester Sulfonation. Chemithon, USA.
McCune, C.V. 1980. Temperaturse in Well, Trans. AIME,vol 142., p. 15
Pore, J. 1976. Sulfated and Sulfonated Oils. Di dalam : Karlenskind, A. (Ed.). Oil and Fats. Manual Intercept Ltd., New York.
Dekker Inc., New York.
Roberts, D.W., Giusti, L., Forcella, A. 2008. Chemistry of Methyl Ester Sulfonates. Di dalam : Biorenewable Resources No.5. AOCS.
Rosen, J. M. 2004. Surfactant and Interfacial Phenomena. Third Edition. John Wiley & Sons, Inc.
Shaw, D.J. 1980. Introduction to Colloid Surface Chemistry. Butterworths,Oxford, England.
Standar Nasional Indonesia. 1998. Cara uji minyak dan lemak. Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
Stein, W.dan H. Baumann. 1975. α-Sulfonated Fatty Acids and Esters: Manufacturing Process, Properties, and Applications. JAOCS. Vol. 52: 323 – 329.
Suryani, A., I. Sailah dan E. Hambali. 2003. Pengantar Teknologi Emulsi. Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fateta IPB, Bogor.
Swern, D. 1979. Bailey’s Industrial Oil and Fat Products. Vol. I 4th Edition. John Willey and Son, New York.
Watkins, C. 2001. Surfactant and Detergent: All Eyes are on Texas. Inform 12 : 1152-1159.
www.o-fish.com. Kesadahan
PENGARUH SUHU, LAMA PEMANASAN, SALINITAS DAN KESADAHAN TERHADAP KINERJA SURFAKTAN METIL ESTER
SULFONAT (MES) DARI OLEIN SAWIT
Oleh AANG ZEN
F34104088
2009
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR