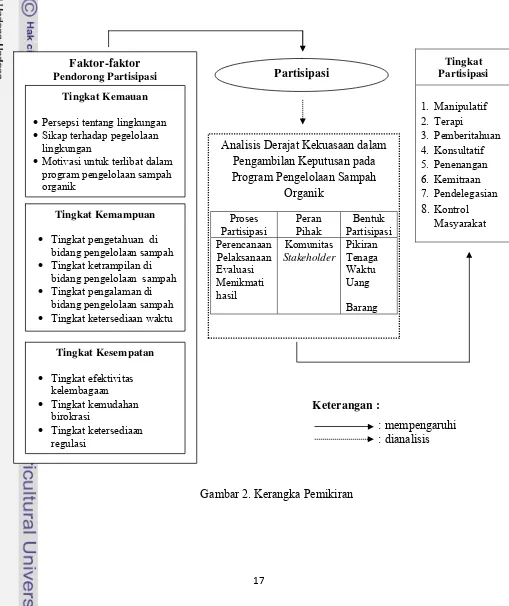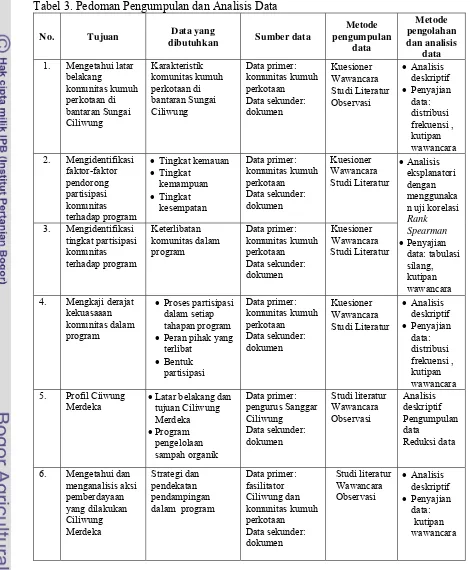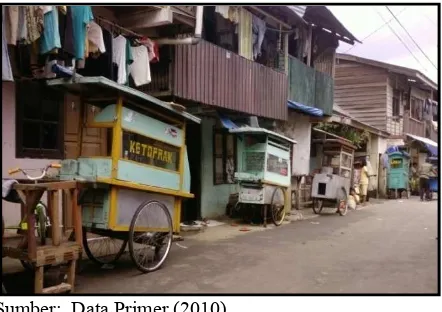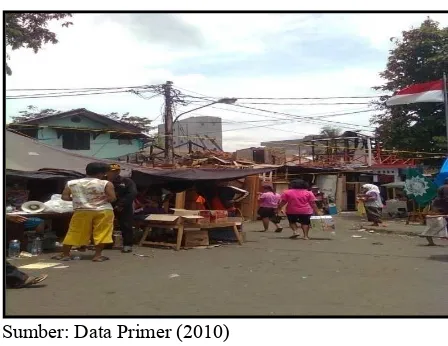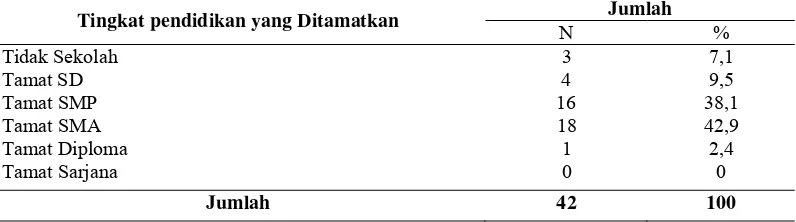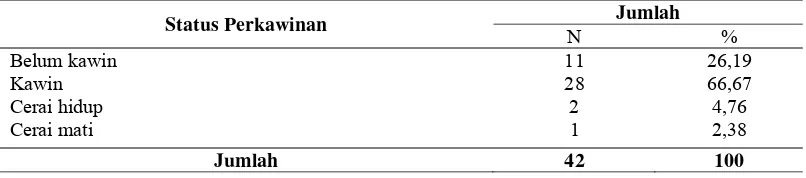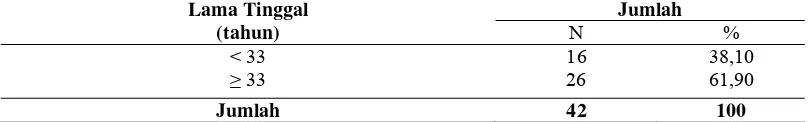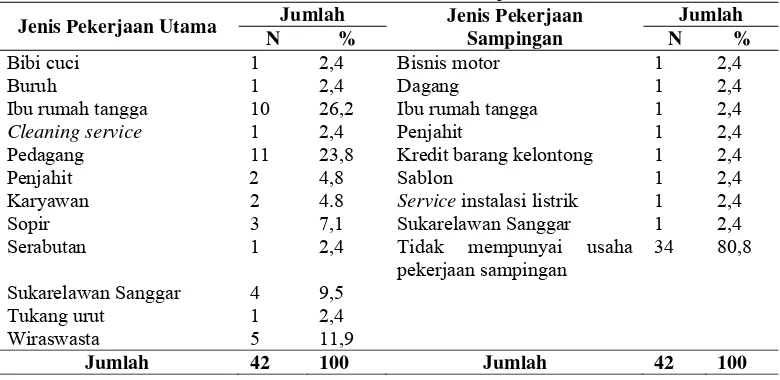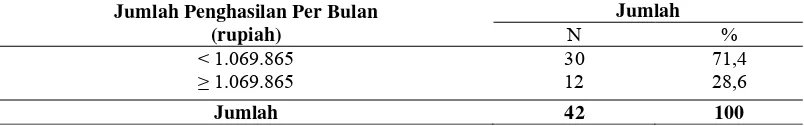PARTISIPASI PESERTA DALAM PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DI KOMUNITAS KUMUH PERKOTAAN
BANTARAN SUNGAI CILIWUNG
YUNITA PURBO ASTUTI I34070024
DEPARTEMEN
SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
ABSTRACT
This research aims to identify the factors that determine the level of marginal community participation in urban areas along the River Ciliwung on organic waste management programs. The second objective, to analyze the relationship between the factors that determine the participation level of participation. The third objective, knowing the extent of community participation in the program.
This research uses a quantitative approach and qualitative data supported. Analysis of data in the form of descriptive analysis and explanatory analysis. This research uses 42 respondents obtained by using the method of purposive.
The results showed a decisive factor is the participation of institutional effectiveness of Ciliwung Merdeka. All factors associated weakly with the level of participation. level of community participation in urban slums tokenisme stage. Stage indicates the level of information leading to the consultation. The community is only as beneficiaries of the program while Ciliwung Merdeka as a facilitator of the program. Ciliwung Merdeka only convey information and top-down direction of the community.
Keywords: marginal community, level of participation , degree of power
RINGKASAN
YUNITA PURBO ASTUTI. Partisipasi Komunitas Kumuh Perkotaan di Bantaran Sungai Ciliwung dalam Program Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Komunitas. Di bawah bimbingan TITIK SUMARTI.
Program pengelolaan sampah organik merupakan salah satu upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh sebuah organisasi masyarakat bernama Ciliwung Merdeka terhadap komunitas marginal di Kota Jakarta. Rangkaian kegiatan dalam program pengelolaan sampah organik melibatkan komunitas kumuh perkotaan di bantaran Sungai Ciliwung dalam mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang dimiliki komunitas. Dengan demikian proses pembelajaran yang diterapkan mengarah pada prinsip buttom up.
Tujuan penelitian adalah (1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi komunitas kumuh perkotaan terhadap program pengelolaan sampah organik; (2) Mengkaji hubungan antara tingkat kemauan, tingkat kemampuan, dan tingkat kesempatan yang dimiliki komunitas kumuh perkotaan terhadap tingkat partisipasi dalam program pengelolaan sampah organik; dan (3) Mengetahui sampai sejauh mana tingkat partisipasi (tipologi Arnstein) komunitas kumuh perkotaan dalam program pengelolaan sampah organik.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif. Metode yang digunakan adalah survei dengan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner, wawancara mendalam, analisis dokumen, serta observasi.
Responden berjumlah 42 orang yang diperoleh dengan metode pemilihan sampel secara purposif (purposive sampling) atau sengaja, yaitu warga yang mengetahui bahwa di RT nya terdapat program pengelolaan sampah organik yang difasilitasi Ciliwung Merdeka. Lokasi penelitian adalah RT 06 dan 07 RW 12 Kelurahan Bukit Duri dan RT 10 RW 03 Kelurahan Kampung Melayu dengan pertimbangan ketiga RT tersebut terdapat program pengelolaan sampah organik yang difasilitasi Ciliwung Merdeka. Jadi, dapat dikaji tingkat partisipasi komunitas kumuh perkotaan di bantaran sungai yang termarginal dalam program pemberdayaan di bidang pengelolaan lingkungan.
Teknik analisis data menggunakan (1) Analisis deskriptif untuk memaparkan faktor-faktor yang menentukan tingkat partisipasi dan tingkat partisipasi komunitas sebagai variabel tunggal; dan (2) Analisis eksplanatori untuk melihat hubungan antara faktor-faktor pendorong partisipasi dengan tingkat partisipasi.
sedangkan tingkat kemampuan dan tingkat kesempatan tidak berhubungan signifikan terhadap tingkat partisipasi.
Tingkat partisipasi komunitas dalam program jika dikaji dari derajat kekuasaan dalam pengambilan keputusan, berada pada tahap tokenisme yaitu tingkat information yang mengarah ke tingkat consultation. Metode pemberdayaan yang diterapkan Ciliwung Merdeka masih bersifat top down. Derajat kekuasaan komunitas dalam program masih lemah. Komunitas hanya sebagai penerima program yang disampaikan Ciliwung Merdeka secara searah, yakni sebatas pemberitahuan.
PARTISIPASI PESERTA DALAM PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DI KOMUNITAS KUMUH PERKOTAAN
BANTARAN SUNGAI CILIWUNG
Oleh:
YUNITA PURBO ASTUTI I34070024
SKRIPSI
Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
pada
Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
DEPARTEMEN
SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
DEPARTEMEN
SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh:
Nama : Yunita Purbo Astuti
NRP : I34070024
Judul : Partisipasi Peserta Program Pengelolaan Sampah Organik di
Komunitas Kumuh Perkotaan Bantaran Sungai Ciliwung
Dapat diterima sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut
Pertanian Bogor.
Menyetujui,
Dosen Pembimbing
Dr. Ir. Titik Sumarti, MS NIP. 19610927 198601 2 001
Mengetahui,
Ketua Departemen Sains
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS NIP. 19550630 198103 1 003
LEMBAR PERNYATAAN
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI YANG BERJUDUL
“PARTISIPASI PESERTA DALAM PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DI KOMUNITAS KUMUH PERKOTAAN BANTARAN SUNGAI CILIWUNG” BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI DAN TIDAK MENGANDUNG BAHAN-BAHAN YANG
PERNAH DITULIS ATAU DITERBITKAN OLEH PIHAK LAIN BAIK OLEH
PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN. KECUALI SEBAGAI
BAHAN RUJUKAN YANG DINYATAKAN DALAM NASKAH. DEMIKIAN
PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA DAN SAYA
BERSEDIA BERTANGGUNGJAWAB ATAS PERNYATAAN INI.
Bogor, Februari 2011
Yunita Purbo Astuti
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Pati pada tanggal 8 Juni 1989. Penulis merupakan
anak keempat dari empat bersaudara dari keluarga Bapak Suparwi dan Ibu Sarmi.
Penulis menamatkan pendidikan di TK Trisula 1 tahun 1995, SD Negeri 1
Kebonsawahan tahun 2001, SLTP Negeri 1 Juwana tahun 2004, SMA Negeri 1
Pati tahun 2007. Masuk universitas pada tahun 2007 ke Institut Pertanian Bogor
(IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) di Departemen
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (KPM) Fakultas Ekologi Manusia
(FEMA).
Prestasi yang pernah diraih yaitu lolos seleksi pemberian dana hibah Dikti
satu Program Kreativitas Mahasiswa bidang Pengembangan Masyarakat
(PKM-M) dan lolos menuju Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional (PIMNAS
XXIII) tahun 2010 yang berjudul “Pengembangan Metode Partisipatif Berbasis
Masyarakat Dalam Rangka Implementasi Agroforestri Di Dataran Tinggi Dieng
Melalui LEISA (Low External Input for Sustainable Agriculture)”. Pernah
bergabung di organisasi secara aktif selama duduk di bangku perkuliahan,
diantaranya dalam Forum Scientist IPB (FORCES) pada tahun 2007-2009 dan
Koran Kampus IPB pada tahun 2008-2010. Penulis juga memiliki minat pada
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Partisipasi Peserta dalam Program Pengelolaan Sampah Organik di Komunitas Kumuh Perkotaan Bantaran Sungai Ciliwung”. Penulis sangat bersyukur karena penyusunan skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya dan sesuai dengan yang direncanakan.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Dr. Ir. Titik Sumarti, MS sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, motivasi, dan segala bantuan selama penelitian hingga skripsi ini dapat terselesaikan
2. Ir. Fredian Tonny Nasdian, MS dan Ir. Nuraini W. Prasodjo, MS sebagai dosen penguji yang memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini
3. Martua Sihaloho, SP. MSi sebagai dosen penguji petik skripsi ini
4. Dr. Ir. Amir Djahi sebagai dosen pembimbing akademik yang membantu penulis apabila mendapat masalah di bidang akademik
5. Ciliwung Merdeka, warga RT 06 dan 07 RW 12 Kelurahan Bukit Duri, serta warga RT 10 RW 03 Kelurahan Kampung Melayu yang berpartisipasi dalam proses pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian
6. Keluarga tersayang, ayahanda dan ibunda, ketiga kakak kandung penulis, serta orang-orang tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan kepada penulis 7. Semua teman seperjuangan program akselerasi dan semua teman se-Departemen KPM
tercinta yang selalu memotivasi penulis sampai terselesaikannya skripsi ini tepat waktu 8. Semua teman di Koran Kampus dan kakak senior di UKM Seroja Putih yang memberikan
dukungan kepada penulis
9. Ibu kost dan semua teman satu kost yang telah memberikan doa dan dukungan sampai terselesaikannya skripsi ini
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI ... x
DAFTAR TABEL ... xv
DAFTAR GAMBAR ... xix
DAFTAR LAMPIRAN………..………...xix
BAB I.PENDAHULUAN ... 1
1.1. Latar Belakang ... 1
1.2. Masalah Penelitian ... 3
1.3. Tujuan Penelitian ... 4
1.4. Kegunaan Penelitian ... 4
BAB II.PENDEKATANTEORITIS ... 5
2.1. Tinjauan Pustaka ... 5
2.1.1. Pemberdayaan Masyarakat ... 5
2.1.2. Partisipasi ... 6
2.1.3. Komunitas ... 12
2.1.4. Kemiskinan ... 14
2.1.5. Pengelolaan Sampah ... 15
2.2. Kerangka Pemikiran ... 16
2.3. Hipotesis ... 18
2.4. Definisi Operasional ... 19
BAB III.PENDEKATAN LAPANG ... 24
3.1. Metode Penelitian ... 24
3.2. Lokasi dan Waktu ... 24
3.3. Metode Pengambilan Sampel ... 25
3.4. Metode Pengumpulan Data ... 26
3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Data ... 26
BABIV.GAMBARANUMUM ... 29
4.1. Gambaran Wilayah Pemukiman ... 29
4.1.1. Letak Geografis ... 29
4.1.4. Kondisi Fasilitas Umum ... 31
4.1.5. Kesejahteraan Warga ... 32
4.1.6. Kebersamaan Warga ... 32
4.2. Ciliwung Merdeka ... 33
4.2.1. Profil Organisasi ... 33
4.2.2. Ruang Lingkup Program Pengelolaan Sampah Organik ... 34
BAB V. KARAKTERISTIK RESPONDEN ... 37
5.1. Jenis Kelamin ... 37
5.2. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan ... 37
5.3. Status Perkawinan ... 37
5.4. Jumlah Anggota Keluarga yang Tinggal dalam Satu Rumah ... 38
5.5. Asal Usul Tempat Tinggal ... 39
5.6. LamaTinggal ... 40
5.7. Status Kepemilikan Tempat Tinggal ... 40
5.8. Status Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ... 41
5.9. Usia Angkatan Kerja ... 41
5.10. Jenis Pekerjaan ... 42
5.11. Status Pekerjaan ... 42
5.12. Jumlah Penghasilan ... 43
5.13. Lama Bekerja ... 43
5.14. Sumber Informasi tentang Program ... 44
5.15. Lama Terlibat dalam Program ... 45
5.16. Ikhtisar ... 46
BAB VI. FAKTOR-FAKTOR PENDORONGPARTISIPASI ... 47
6.1. Tingkat Kemauan ... 47
6.1.1. Persepsi terhadap Pengelolaan Lingkungan ... 47
6.1.2. Sikap terhadap Program Pengelolaan Sampah Organik ... 51
6.1.3. Motivasi untuk Terlibat dalam Program Pengelolaan Sampah Organik ... 52
6.2. Tingkat Kemampuan ... 53
6.2.2. Tingkat Ketrampilan di Bidang Pengelolaan Sampah Sebelum
Ada Program Pengelolaan Sampah Organik ... 54
6.2.3. Tingkat Pengalaman di Bidang Pengelolaan Sampah Sebelum Ada Program Pengelolaan Sampah Organik ... 54
6.2.4. Tingkat Ketersediaan Waktu ... 55
6.3. Tingkat Kesempatan ... 55
6.3.1. Tingkat Efektivitas Kelembagaan ... 55
6.3.2. Tingkat Kemudahan Birokrasi ... 57
6.3.3. Tingkat Ketersediaan Regulasi ... 58
6.4. Ikhtisar ... 59
6.4.1. Tingkat Kemauan ... 59
6.4.2. Tingkat Kemampuan ... 59
6.4.3. Tingkat Kesempatan ... 60
BAB VII.HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR PENDORONGPARTISIPASI DENGAN TINGKAT PARTISIPASI ... 61
7.1. Hubungan Antara Tingkat Kemauan dengan Tingkat Partisipasi ... 61
7.1.1. Hubungan Antara Persepsi tentang Lingkungan dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung Tahun 2010 ... 61
7.1.2. Hubungan Antara Sikap tentang Pengelolaan Lingkungan dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung Tahun 2010 ... 63
7.2. Hubungan Antara Tingkat Kemampuan dengan Tingkat Partisipasi ... 64
7.2.1. Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Sebelum Ada Program dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung Tahun 2010 ... 64
7.2.3. Hubungan Antara Tingkat Pengalaman Sebelum Ada Program
dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah
Organik di Bantaran Sungai Ciliwung Tahun 2010 ... 67
7.2.4. Hubungan Antara Tingkat Ketersediaan Waktu dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung Tahun 2010 ... 68
7.3. Hubungan Antara Tingkat Kesempatan dengan Tingkat Partisipasi . 69 7.3.1. Hubungan Antara Tingkat Efektivitas Kelembagaan dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung Tahun 2010 ... 69
7.3.2. Hubungan Antara Tingkat Kemudahan Birokrasi dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung Tahun 2010 ... 70
7.3.3. Hubungan Antara Tingkat Ketersediaan Regulasi dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung Tahun 2010 ... 71
7.4. Ikhtisar ... 73
7.4.1. Hubungan Antara Tingkat Kemauan dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung Tahun 2010 ... 73
7.4.2. Hubungan Antara Tingkat Kemampuan dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung Tahun 2010 ... 74
7.4.3. Hubungan Antara Tingkat Kesempatan dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung Tahun 2010 ... 75
BAB VIII. ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI ... 77
8.1. Tingkat Partisipasi dalam Program ... 77
8.1.1. Perencanaan ... 77
8.1.2. Pelaksanaan ... 81
8.1.3. Evaluasi ... 84
8.2. Ikhtisar ... 88
BAB IX.PENUTUP ... 90
9.1. Kesimpulan ... 90
9.2. Saran ... 91
DAFTAR PUSTAKA ... 93
LAMPIRAN ……….93
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Tingkat Partisipasi (Tipologi Arnstein)………... 9
Tabel 2. Economic-Environmrntal Typology of Cities……….. 13
Tabel 3. Pedoman Pengumpulan dan Analisis Data……… 28
Tabel 4. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan
Kelurahan Bukit Duri Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan,
Tahun 2010……… 37
Tabel 5. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan
Kelurahan Bukit Duri Menurut Status Perkawinan, Tahun 2010 …… 38
Tabel 6. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan
Kelurahan Bukit Duri Menurut Jumlah Anggota Keluarga yang Tinggal
dalam Satu Rumah, Tahun 2010……… 38
Tabel 7. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan
Kelurahan Bukit Duri Menurut Asal Usul Tempat Tinggal, Tahun
2010……… 39
Tabel 8. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan
Kelurahan Bukit Duri Menurut LamaTinggal, Tahun 2010……….. 40
Tabel 9. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan
Kelurahan Bukit Duri Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal,
Tahun 2010………. 40
Tabel 10. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan
Kelurahan Bukit Duri Menurut Usia Angkatan Kerja, Tahun 2010…….. 41
Tabel 11. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan
Kelurahan Bukit Duri Menurut Jenis Pekerjaan, Tahun 2010………... 42
Tabel 12. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan
Kelurahan Bukit Duri Menurut Status Pekerjaan, Tahun 2010…………. 42
Tabel 13. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan
Kelurahan Bukit Duri Menurut Jumlah Penghasilan, Tahun 2010…... 43
Tabel 14. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan
Tabel 15. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan
Kelurahan Bukit Duri Menurut Sumber Informasi tentang Program
Pengelolaan Sampah Organik yang Difasilitasi Ciliwung Merdeka…... 44
Tabel 16. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan
Kelurahan Bukit Duri, Tahun 2010 Menurut Lama Terlibat dalam
Program Pengelolaan Sampah Organik ………. 45
Tabel 17. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan
Kelurahan Bukit Duri Menurut Persepsi Cara Mengatasi Sampah……… 47
Tabel 18. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan
Kelurahan Bukit Duri Menurut Persepsi Tindakan Bagi Pelaku
Membuang Sampah di Sungai……… 48
Tabel 19. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan
Kelurahan Bukit Duri Menurut Persepsi Program Pengelolaan Sampah
Organik………... 49
Tabel 20. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan
Kelurahan Bukit Duri Menurut Persepsi Keterlibatan dalam Tahapan
Program Pengelolaan Sampah Organik………. 49
Tabel 21. Jumlah dan Presentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan
Kelurahan Bukit Duri Menurut Tingkat Aksesibilitas dalam Program
Pengelolaan Sampah Organik……… 56
Tabel 22. Jumlah dan Presentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan
Kelurahan Bukit Duri Menurut Tingkat Kemauan untuk Berpartisipasi
dalam Program Pengelolaan Sampah Organik……….. 59
Tabel 23. Jumlah dan Presentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan
Kelurahan Bukit Duri Menurut Tingkat Kemampuan untuk
Berpartisipasi dalam Program Pengelolaan Sampah Organik……… 59
Tabel 24. Jumlah dan Presentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan
Kelurahan Bukit Duri Menurut Tingkat Kesempatan untuk
Berpartisipasi dalam Program Pengelolaan Sampah Organik……… 60
Tabel 25. Hubungan Antara Jenis Kelamin dengan Tingkat Partisipasi Program
Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung, Tahun
Tabel 26. Hubungan Persepsi tentang Lingkungan dengan Tingkat Partisipasi
Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung,
Tahun 2010………. 62
Tabel 27. Hubungan Sikap terhadap Pengelolaan Lingkungan dengan Tingkat
Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai
Ciliwung, Tahun 2010……… 63
Tabel 28. Hubungan Tingkat Pengetahuan dalam Bidang Pengelolaan Sampah
Sebelum Ada Program dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan
Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung, Tahun 2010………….. 64
Tabel 29. Hubungan Tingkat Ketrampilan dalam Bidang Pengelolaan Sampah
Sebelum Ada Program dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan
Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung, Tahun 2010……… 66
Tabel 30. Hubungan Tingkat Pengalaman dalam Bidang Pengelolaan Sampah
Sebelum Ada Program dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan
Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung, Tahun 2010………….. 67
Tabel 31. Hubungan Tingkat Ketersediaan Waktu dengan Tingkat Partisipasi
Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung,
Tahun 2010………. 68
Tabel 32. Hubungan Tingkat Efektivitas Kelembagaan Ciliwung Merdeka dengan
Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran
Sungai Ciliwung, Tahun 2010……….. 69
Tabel 33. Hubungan Tingkat Kemudahan Birokrasi dengan Tingkat Partisipasi
Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung,
Tahun 2010………. 71
Tabel 34. Hubungan Tingkat Ketersediaan Regulasi tentang Pengelolaan Sampah
dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di
Bantaran Sungai Ciliwung, Tahun 2010……… 72
Tabel 35. Hubungan Tingkat Kemauan dengan Tingkat Partisipasi Program
Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung, Tahun 2010 73
Tabel 36. Hubungan Tingkat Kemampuan dengan Tingkat Partisipasi Program
Tabel 37. Hubungan Tingkat Kesempatan dengan Tingkat Partisipasi Program
Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung, Tahun 2010 75
Tabel 38. Jumlah dan Persentase Responden Menurut Tingkat Partisipasi Program
Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung, Tahun
2010……….. 77
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Kerangka Analisis Deskriptif Partisipasi……….. 7
Gambar 2. Kerangka Pemikiran……….. 17
Gambar 3. Rumah Susun Milik Warga……… 30
Gambar 4. Kegiatan Sarasehan Warga Bersama Ciliwung Merdeka di Jalan Utama Kampung………... 31
Gambar 5. Posko Bantuan Korban Kebakaran RT 05 RW 12 Bukit Duri….. 32
Gambar 6. Posisi Perilaku terhadap Lingkungan……….. 47
Gambar 7. Persepsi tentang Pengelolaan Lingkungan……… 50
Gambar 8. Sikap terhadap Pengelolaan Sampah Organik……….. 51
Gambar 9. Model Hierarki Kebutuhan Maslow………. 52
Gambar 10. Motivasi Komunitas untuk Berpartisipasi dalam Program Pengelolaan Sampah Organik……… 52
Gambar 11. Tingkat Pengetahuan Responden di Bidang Pengelolaan Sampah Sebelum Ada Program Pengelolaan Sampah Organik…………... 53
Gambar 12. Tingkat Ketrampilan Responden di Bidang Pengelolaan Sampah Sebelum Ada Program Pengelolaan Sampah Organik………….. 54
Gambar 13. Tingkat Pengalaman Responden di Bidang Pengelolaan Sampah Sebelum Ada Program Pengelolaan Sampah Organik………….. 54
Gambar 14. Tingkat Ketersediaan Waktu Responden untuk Mengikuti Program Pengelolaan Sampah Organik………. 55
Gambar 15. Tingkat Efektivitas Kelembagaan Ciliwung Merdeka………….. 57
Gambar 16. Tingkat Kemudahan Birokrasi……….. 57
Gambar 17. Tahap-Tahap Pengolahan Informasi……….. 65
Gambar 18. Tingkat Partisipasi Komunitas dalam Perencanaan Program….... 80
Gambar 19. Tingkat Partisipasi Komunitas dalam Pelaksanaan Program……. 82
Gambar 20. Tingkat Partisipasi Komunitas dalam Evaluasi Program………... 84
Gambar 21. Keterlibatan Komunitas dalam Menikmati Hasil Program……... 86
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Lokasi Penelitian
Lampiran 2. Struktur Organisasi Ciliwung Merdeka
Lampiran 3. Tahapan Program Pengelolaan Sampah Organik
Lampiran 4. Diagram Spiral Pendidikan Pemberdayaan Masyarakat
Lampiran 5. Hasil Uji Korelasi Rank Spearman
Lampiran 6. Kuesioner
Lampiran 7. Panduan Wawancara
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Banjir di Jakarta terjadi hampir setiap tahun. Pendangkalan sungai menjadi
salah satu faktor penyebab banjir yang melanda hilir Daerah Aliran Sungai (DAS)
Ciliwung. Banjir Jakarta tidak hanya disebabkan oleh faktor alam dengan
tingginya curah hujan, tetapi juga perilaku masyarakat dalam memperlakukan
alam baik di hulu, maupun di hilir DAS. Perilaku menebang pohon di hulu dan
tengah DAS dan perilaku membuang sampah sembarangan khususnya di sungai,
sampai saat ini masih dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat. Faktanya,
Sungai Ciliwung saat ini sangat keruh akibat terjadinya degradasi lahan di bagian
hulu dan tengah DAS Ciliwung. Selain itu, di bagian hilir diperparah dengan
banyaknya sampah di dalamnya. Sampai saat ini di sepanjang bantaran sungai di
Jakarta terdapat tumpukan sampah dan sampah-sampah tersebut hanyut terbawa
aliran air sungai. Oleh karena itu, Sungai Ciliwung diibaratkan sebagai selokan
terbesar karena tingginya pembuangan limbah yang merusak kelestarian DAS.
Menurut Dinas Kebersihan DKI Jakarta (2007) produksi sampah di DKI
Jakarta per harinya mencapai 26.945 m3 atau setara dengan 6.000 ton per hari,
yang terdiri dari 55 persen sampah organik dan 45 persen sampah anorganik.1 Hal
ini menunjukkan bahwa masalah sampah di Jakarta secara tersebar telah menjadi
permasalahan nasional. Keberadaan sampah yang dituding sebagai pemicu banjir,
memerlukan pengelolaan komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, agar
memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan. Pengelolaan sampah
tentunya dapat bersifat sustainable apabila masyarakat berpartisipasi dalam
pengelolaan sampah.
Inisisasi berbagai pihak seperti akademisi, LSM, wartawan, pemerintah,
turut andil dalam membangun kapasitas komunitas lokal untuk bangkit mengatasi
permasalahan banjir yang setiap tahun melanda Jakarta. Sebagaimana
pendampingan yang dilakukan oleh Ciliwung Merdeka terhadap komunitas di
Kampung Melayu dan Bukit Duri dekat bantaran sungai yang identik dengan
image Komunitas Kumuh Perkotaan atau kawasan slum area. Hal ini
menunjukkan bahwa ada ”pihak luar” yang masih peka terhadap permasalahan
yang dihadapi kaum termarginal (disadventaged groups) di negeri ini yang tak
lepas dari tudingan sebagai pihak yang turut andil menyebabkan banjir.
Tempat tinggal komunitas yang berada di bantaran sungai seringkali
dianggap sebagai penyebab menyempitnya lebar sungai yang memicu pada luapan
air sungai saat musim penghujan. Kondisi ini dipengaruhi semakin tingginya
pertumbuhan penduduk Kota Jakarta sebagai daerah urban dengan keterbatasan
lahan kosong dan sumber daya lainnya sebagai penyokong kehidupan komunitas
golongan lemah yang mencoba mengadu nasib di kota perantauaan. Semakin
padatnya pemukim di bantaran sungai berimpilkasi semakin susah ditemukannya
lahan sebagai tempat pembuangan sampah. Selain itu, sempitnya jalan
perkampungan turut menghambat akses kendaraan petugas kebersihan untuk
mengangkut sampah dari pemukiman. Akibatnya, komunitas slum area di
bantaran Sungai Ciliwung lebih mudah mengakases sungai sebagai tempat
pembuangan sampah.
Ciliwung Merdeka melakukan penguatan kapasitas komunitas melalui
program pemberdayaan di bidang pengelolaan sampah organik. Hal ini ditujukan
agar masyarakat yang tidak berdaya tersebut memiliki posisi tawar (bergaining
position) yang setara dengan masyarakat lainnya. Dengan demikian, komunitas
menjadi berdaya dengan mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapinya
serta mampu mencari solusi dari permasalahan pengelolaan sampah.
Kebijakan dan peraturan seperti larangan tinggal di sekitar bantaran
sungai, tidak membuang sampah di sungai, dan lain sebagainya telah dikeluarkan
oleh pemerintah dengan harapan tata kelola kota menjadi lebih baik. Namun, hal
ini tidak membawa perubahan yang signifikan. Kenyataanya, kebijakan yang
ditetapkan tersebut justru memarginalkan kaum minoritas yang tinggal di bantaran
sungai dengan keterbatasan kapasitas diri mereka. Dapat diibaratkan, bahwa
kebijakan sampai saat ini masih ”menyembunyikan komunitas slum area di
bawah karpet merah”. Artinya, kebijakan bersifat top down dan belum berupaya
meningkatkan kapasitas golongan marginal melainkan menutupi keberadaan
Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan ”Negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.
Ketidakberdayaan yang dialami kaum marginal di negeri ini salah satu
faktornya dipengaruhi adanya ketimpangan. Hal ini terlihat dari ketidakmerataan
redistribusi sumber daya berupa akses dan kontrol, khususnya dalam pengambilan
keputusan yang terkesan sepihak dan top down. Berdasar hasil analisis para
ekonom, menghitung bahwa 20 persen rakyat Indonesia menguasai 80 persen
kekayaan, sementara 80 persen rakyat Indonesia hanya menikmati 20 persen
kekayaan2 .
Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama ini merupakan
implementasi kebijakan “top-down” dengan tidak adanya keberlanjutan program.
Hal ini dikarenakan dalam penyusunan rencana sampai proses evaluasi program
masih kurang memperhatikan dan mengabaikan partisipasi masyarakat.
1.2. Masalah Penelitian
Menurut latar belakang yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah
dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah faktor-faktor yang menentukan tingkat partisipasi komunitas kumuh
perkotaan di bantaran Sungai Ciliwung terhadap program pengelolaan sampah
organik?
2. Bagaimana hubungan antara tingkat kemauan, tingkat kemampuan, dan
tingkat kesempatan yang dimiliki komunitas kumuh perkotaan di bantaran
Sungai Ciliwung terhadap tingkat partisipasi dalam program pengelolaan
sampah organik?
3. Sejauh mana tingkat partisipasi komunitas kumuh perkotaan di bantaran
Sungai Ciliwung dalam program pengelolaan sampah organik?
2
1.3. Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan rumusan permasalahan di atas, maka dalam penelitian
ini bertujuan:
1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan tingkat partisipasi komunitas
kumuh perkotaan terhadap program pengelolaan sampah organik;
2. Mengkaji hubungan antara tingkat kemauan, tingkat kemampuan, dan tingkat
kesempatan yang dimiliki komunitas kumuh perkotaan terhadap tingkat
partisipasi dalam program pengelolaan sampah organik; dan
3. Mengetahui sampai sejauh mana tingkat partisipasi (tipologi Arnstein)
komunitas kumuh perkotaan dalam program pengelolaan sampah organik.
1.4. Kegunaan Penelitian
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai
pihak yang tertarik serta terkait dengan program-program pemberdayaan
masyarakat, khususnya kepada:
1. Peneliti dan Civitas Akademika
Penelitian ini merupakan proses belajar bagi peneliti dalam
menganalisis program pemberdayaan masyarakat. Diharapkan penelitian ini
dapat memberikan informasi bagi penelitian sejenisnya serta dapat
mencetuskan strategi yang paling tepat sebagai upaya pemberdayaan
masyarakat marginal di negeri ini.
2. Masyarakat
Hasil penelitian ini semoga mampu meningkatkan kesadaran dan
pemahaman masyarakat akan kapasitas diri yang dimiliki dan peranan mereka
dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini tak terlepas dari akses dan kontrol
yang dapat dimiliki masyarakat dalam program pembangunan.
3. Instansi Terkait
Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam
merumuskan pedoman dan kebijakan untuk implementasi program-program
pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.
BAB II
PENDEKATAN TEORITIS
2.1. Tinjauan Pustaka
2.1.1. Pemberdayaan Masyarakat
Secara konseptual, pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata
‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Menurut Ife dalam Krisdyatmiko (2006),
pemberdayaan mengandung dua pengertian kunci yaitu kekuasaan dan kelompok
lemah. Dilihat dari perspektif kekuasaan, pemberdayaan bertujuan meningkatkan
kemampuan dari kelompok lemah. Jadi, pemberdayaan adalah proses membuat
orang cukup kuat untuk berpartisipasi dalam pengontrolan atas dan mempengaruhi
tindakan dan lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.”
Suharto (2005) menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses
dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat
kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat (khususnya
golongan yang tidak beruntung/tertindas baik oleh kemiskinan maupun
diskriminasi kelas sosial, gender). Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk
pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu
masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan tidak menempatkan masyarakat
sebagai obyek (penerima manfaat yang tergantung “pihak luar”) melainkan
subyek (partisipan yang bertindak secara mandiri). Kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan menurut Suharto (2005) tergantung pada dua hal (1)
Kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan
tidak mungkin terjadi apapun (2) Kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini
menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.
Pengembangan masyarakat menurut Sumarti (2008) bertumpu pada dua
elemen pokok, yaitu kemandirian dan partisipasi. Masyarakat mandiri karena
mempunyai daya menentukan pembangunannya dan berpartisipasi seutuhnya pada
seluruh prosesnya. Tanpa pemberdayaan, masyarakat akan selalu tergantung, dan
tanpa pemberdayaan, hanya partisipasi semu yang terjadi. Oleh karena itu,
pemberdayaan merupakan jalan menuju partisispasi “empowerment is road to
2.1.2. Partisipasi 2.1.2.1.Definisi
Parisipasi akan muncul ketika masyarakat mulai sadar akan masalah yang
dihadapi dan mampu mengidentifikasi kebutuhan mereka. Kesadaran yang
muncul dari diri sendiri itulah yang nantinya mendorong kepedulian masyarakat
untuk tergerak mencari penyelesaian masalah tersebut dan akhirnya kebutuhan
masyarakat bisa terpenuhi oleh upaya dan semangat mereka sendiri dan
melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait.
”Partisipasi ialah proses aktif, inisiatif yang diambil oleh warga komunitas,
dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan
proses (lembaga dan mekanisme) di mana mereka dapat menegaskan kontrol
secara efektif ”, Adiwibowo dkk. (2007). Cohen dan Serageldin (1994)
mendefinisikan partisipasi dalam empat hal “… participation in decision making,
participation in implementation, participation in benefit, and participation in
evaluation.” Berkaitan dengan pernyataan Cohen, Oakley dalam Hasim dan
Ramiswal (2009) menambahkan bahwa partisipasi juga menunjukkan keterlibatan
masyarakat secara bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan dari program
pembangunan.
2.1.2.2. Aspek Partisipasi
Menurut Oppenheim dalam Sumardjo (2009), ada dua hal yang
mendukung terjadinya partisipasi yaitu person inner determinant dan
environmental factors. Hal ini diperjelas oleh Sumardjo (2009) bahwa ada tiga
prasyarat terjadinya partisipasi yakni faktor kemauan (sikap positif terhadap
sasaran partisipasi), kemampuan (inisiatif untuk bertindak dengan komitmen dan
menikmati hasilnya), dan kesempatan (peluang berpartisipasi).
Sependapat dengan pernyataan Sumardjo (2009), dikemukakan juga oleh
Saharuddin (1987) agar masyarakat berpartisipasi dalam program, ada tiga syarat
(1) Adanya kesempatan untuk membangun; (2) Adanya kemampuan
1. Kemauan (aspek emosi dan perasaan/reaksi psikis yang dapat memotivasi
untuk bertindak, melaksankan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan
kesempatan yang ada).
2. Kemampuan (kesanggupan karena adanya ‘bekal’)
3. Kesempatan (peluang yang ada untuk dapat memanfaatkan kemampuan dan
kemauan yang dimiliki).
Kerangka analisis deskriptif terhadap fenomena partisipasi yang dijelaskan
oleh Uphoff, Cohen, dan Goldsmith (1979) sebagai dimensi partisipasi yang
menyangkut tiga pertanyaan pokok yaitu (1) What kind of participation
(partisipasi macam apa) (2) Who participates (siapa yang berpartisipasi) (3) How
participation occurs (bagaimana timbulnya partisipasi). Secara garis besar
kerangka analisis deskriptif terhadap fenomena partisipasi sebagai berikut:
Pengambilan keputusan
Apa Implementasi
Manfaat Evaluasi
Penduduk setempat Siapa Pemimpin setempat
Pegawai pemerintah Petugas asing
Dasar partisipasi Bagaimana Bentuk partisipasi
Lingkup partisipasi Akibat partisipasi
Sumber: Uphoff, Cohen, dan Goldsmith (1979)
Gambar 1. Kerangka Analisis Deskriptif Partisipasi
2.1.2.3. Bentuk Partisipasi
Krisdiyatmiko (2006) menyebutkan secara substantif, partisipasi
mencakup tiga hal. Pertama, suara (voice) setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan. Kedua, akses
pembuatan kebijakan, termasuk akses pada layanan publik dan akses pada arus
informasi. Ketiga, kontrol yakni setiap warga atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan (kontrol) terhadap
jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintah.
Keterlibatan atau keikutsertaan baik secara langsung maupun tidak
langsung dapat berupa tenaga, material (fisik) ataupun sumbangan pikiran (fisik
fisik) demi kelancaran pelaksanaan kegiatan, Hasim dan Ramiswal (2009).
2.1.2.4. Tingkat Partisipasi
Partisipasi masyarakat merupakan arti sederhana dari kekuasaan
masyarakat (citizen power). Hal ini ditunjukkan oleh terjadinya pembagian
kekuasaan yang adil (redistribution of power) antara penyedia kegiatan dan
kelompok masyarakat. Arnstein menggambarkan partisipasi adalah suatu pola
bertingkat (ladder patern) dengan delapan tingkatan partisipasi3 sebagai berikut:
Tabel 1. Tingkat Partisipasi (Tipologi Arnstein)
No. Tangga/tingkatan
partisipasi Hakekat kesertaan
Tingkatan pembagian kekuasaan 1. Manipulation
(Manipulasi)
Permaian oleh penyelenggara
program Tidak ada
partisipasi 2. Therapy
(Terapi)
Sekedar agar masyarakat tidak marah/mengobati
3. Information
(Pemberitahuan)
Sekedar pemberitahuan searah/sosialisasi
Degree of tokenism4
(Tokenisme/sekedar justifikasi) 4. Consultation
(Konsultasi)
Masyarakat didengar, tapi tidak selalu dipakai sarannya 5. Placation
(Penenangan)
Saran masyarakat diterima tetapi tidak selalu dilaksanakan 6. Partnership
(Kemitraan)
Timbal balik dinegosiasikan
Degree of citizen power
(Tingkat kekuasaan di masyarakat) 7. Delegated power
(Pendelegasian kekuasaan)
Masyarakat diberi kekuasaan (sebagian atau seluruh program) 8. Citizen control
(kontrol masyarakat)
Sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat
Sumber: Arnstein dalam Wicaksono (2010)
3.
Menurut J. Pretty et all. dalam Sumardjo (2009) menyebut tipologi partisipasi menjadi tujuh tingkatan, yakni pasif, informatif, konsultatif, insentif, fungsional, interaktif, dan mandiri.
4
Arnstein (1969) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan
kekuasaan masyarakat (citizen partisipation is citizen power). Partisipasi
masyarakat bertingkat sesuai dengan gradasi kekuasaan yang dapat dilihat dalam
proses pengambilan keputusan. Arnstein menggunakan metafora tangga
partisipasi di mana tiap anak tangga mewakili strategi partisipasi yang berbeda
yang didasarkan pada pola distribusi kekuasaan dan peran dominan stakeholder.
1. Manipulatif, yakni partisipasi yang tidak perlu menuntut respon partisipan
untuk terlibat banyak. Pengelola program akan meminta anggota komunitas
yaitu orang yang berpengaruh untuk mengumpulkan tanda tangan warga
sebagai wujud kesediaan dan dukungan warga terhadap program. Pada tangga
partisipasi ini relatif tidak ada komunikasi apalagi dialog.
2. Terapi (therapy), yakni partisipasi yang melibatkan anggota komunitas lokal
untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan tetapi jawaban
anggota komunitas tidak memberikan pengaruh terhadap kebijakan,
merupakan kegiatan dengar pendapat tetapi tetap sama sekali tidak dapat
mempengaruhi program yang sedang berjalan. Pada level ini telah ada
komunikasi namun bersifat terbatas. Inisiatif datang dari penyelenggara
program dan hanya satu arah.
Tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan sebagai derajat
tokenisme dimana peran serta masyarakat diberikan kesempatan untuk
berpendapat dan didengar pendapatnya, tapi mereka tidak memiliki
kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan
dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Peran serta pada jenjang ini
memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan
dalam masyarakat.
3. Pemberitahuan (informing) adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi
penyelenggara program sekedar melakukan pemberitahuan searah atau
sosialisasi ke komunitas sasaran program. Pada jenjang ini komunikasi sudah
mulai banyak terjadi tapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal
balik. Informasi telah diberikan kepada masyarakat tetapi masyarakat tidak
4. Konsultasi (consultation), anggota komunitas diberikan pendampingan dan
konsultasi dari semua pihak (stakeholder terkait program) sehingga
pandangan-pandangan diberitahukan dan tetap dilibatkan dalam penentuan
keputusan. Model ini memberikan kesempatan dan hak kepada wakil dari
penduduk lokal untuk menyampaikan pendangannya terhadap wilayahnya
(sistem perwakilan). Komunikasi telah bersifat dua arah, tapi masih bersifat
partisipasi yang ritual. Sudah ada penjaringan aspirasi, telah ada aturan
pengajuan usulan, telah ada harapan bahwa aspirasi masyarakat akan
didengarkan, tapi belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan
dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi.
5. Penenangan (placation), komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada
negosiasi antara masyarakat dan penyelenggara program. Masyarakat
dipersilahkan untuk memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan.
Namun penyelenggara program tetap menahan kewenangan untuk menilai
kelayakan dan keberadaan usulan tersebut. Pada tahap ini pula diperkenalkan
adanya suatu bentuk partisipasi dengan materi, artinya masyarakat diberi
insentif untuk kepentingan perusahaan atau pemerintah, ataupun instansi
terkait. Seringkali hanya beberapa tokoh di komunitas yang mendapat insentif,
sehingga tidak mewakilkan komunitas secara keseluruhan. Hal ini dilakukan
agar warga yang telah mendapat insentif segan untuk menentang program.
Tiga tangga teratas dikategorikan sebagai bentuk yang sesungguhnya
dari partisipasi dimana masyarakat memiliki pengaruh dalam proses
pengambilan keputusan.
6. Kerjasama (partnership) atau partisipasi fungsional di mana semua pihak baik
(masyarakat maupun stakeholder lainya), mewujudkan keputusan bersama.
Suatu bentuk partisipasi yang melibatkan tokoh komunitas dan atau ditambah
lagi oleh warga komunitas , “duduk berdampingan” dengan penyelenggara
dan stakeholder program bersama-sama merancang sebuah program yang
akan diterapkan pada komunitas.
7. Pendelegasian wewenang (delegated power), suatu bentuk partisipasi yang
aktif di mana anggota komunitas melakukan perencanaan, implementasi, dan
sebuah program dengan cara ikut memberikan proposal bagi pelaksanaan
program bahkan pengutamaan pembuatan proposal oleh komunitas yang
bersangkutan dengan program itu sendiri.
8. Pengawasan oleh komunitas (citizen control), dalam bentuk ini sudah
terbentuk independensi dari monitoring oleh komunitas lokal. Dalam tangga
partisipasi ini, masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk
kepentingannya sendiri, yang disepakati bersama, dan tanpa campur tangan
pihak penyelenggara program.
2.1.2.5. Hambatan Partisipasi
Oakley dalam Hasim dan Ramiswal (2009) mengemukakan tiga hal yang
dapat menghambat partisipasi, yaitu (1) Hambatan struktural, terkait dengan
redistribusi kekuasaan ekonomi politik, sistem politik terpusat sehingga hanya
mengarahkan masyarakat untuk melaksanakan keputusan yang telah diputuskan.
(2) Hambatan administrasi, ini erat kaitannya sengan hambatan struktural, dimana
sistem administrasi yang menguasai pengendalian pengambilan keputusan, alokasi
sumber, informasi dan pengetahuan yang dperlukan masyarakat untuk dapat
berperan dalam pembangunan secara efektif. (3) Hambatan sosial, berkaitan
dengan mental sebagai akibat dari pengalaman sejarah, seperti kesenjangan sosial,
relais gender yang timpang, pembiasaan untuk hanya melaksanakan inisiatif
atasan dan tidak pernah kreatif membuat keputusan.
Schrool dalam Saharuddin (1987) menjelaskan partisipasi timbul dari
kepincangan struktural yang terdapat dalam sistem sosial yakni kepincangan
antara kemampuan menyerap informasi dan kesempatan yang diharapkan untuk
menggunakan informasi, kepincangan tersebut timbul dari:
1. Kemampuan menyerap informasi bertambah, tetapi kesempatan relatif untuk
menerapkannya tidak ada.
2. Kemampuan dan kesempatan relatif keduanya bertambah tetapi tambahnya
kemampuan lebih cepat daripada tambahnya kesempatan
3. Kemampuan bertambah dan bersamaan dengan itu kesempatan relatif
Rusli dkk. (1995) menjelaskan “Semakin jauh suatu masyarakat terlibat
dalam penetrasi ‘pasar dan kenegaraan’ maka akan semakin jauh pula perbedaan
peluang partisipasi dalam kelembagaan-kelembagaan yang tersedia bagi tiap
warga masyarakatnya.”
Menurut Hasim dan Remiswal (2009) pengetahuan adalah kekuasaan.
Pengetahuan tumbuh dari proses dan hasil penelitian melalui partisipasi,
bersumber dari yang dimiliki oleh penduduk lokal. Melalui monopoli informasi
maka dapat digunakan untuk membuat perencanaan, mengelola keputusan.
2.1.3. Komunitas
Masyarakat dapat diartikan menurut dua konsep menurut Mayo dalam
Suharto (2005), yaitu (1) Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni
sebuah wilayah geografi yang sama. Misal, perumahan di daerah perkotaan atau
sebuah kampung di wilayah perkotaan. (2) Masyarakat sebagai “kepentingan
bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasar kebudayaan dan identitas.
Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas.
Komunitas menurut Cohen dan Serageldin (1994) mempunyai empat
komponen utama, yakni people, place of territory, social interaction, dan
psychological identification. Secara garis besar komunitas diartikan sekelompok
orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan membentuk kehidupan
sosial yang di dalamnya ditandai derajat hubungan sosial tertentu menurut
lokalitas, perasaan sewarga, dan solidaritas.
Menurut Sumardjo (1991) ”Karakteristik para pemukim di pemukiman
kumuh sebagian besar menyesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonomi
(pendapatannya) yang relatif rendah, sebagian besar bekerja di sektor informal
dan domisili mereka bersifat sementara sebagai tempat usaha dan pasar juga.
Menurut Adiwijaya dkk. (1991) perkampungan miskin dapat dianalisis dari
kondisi fisik kampung, pola kehidupan sosial, kondisi ekonomi keluarga. miskin
yaitu perkampungan yang memiliki kondisi lingkungan yang relatif rendah.
Cirinya diantaranya rumah-rumahnya tidak permanen, relatif buruk dan sempit
serta tidak teratur, tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi, fasilitas pemukiman
setiap rumah, jamban (WC) keluarga darurat dan sering berpindah-pindah karena
diantaranya banyak rumah tidak memiliki jamban, selokan pembuangan air
limbah sangat jarang. Permasalahan di lingkungan kumuh antara lain bersumber
dari sampah, pembuangan air besar, kepadatan ruang dan kurangnya air bersih.
Menurut Cohen dan Serageldin (1994), karakteristik ekonomi dan
lingkungan di daerah perkotaan dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 2 . Economic-Environmrntal Typology of Cities
Urban environment problem Lower-income countries (<$650/capital)
Access to basic services
• Water supply and sanitation Low coverage and poor quality, especially for urban poor
• Drainage Low coverage, frequent flooding
• Soild waste collection Low coverag, especially for urban poor Pollution
• Water pollution Problems from inadequate sanitation and raw domestic sewage
• Air pollution Severe problems in some cities using soft coal: indoor exposure for poor
• Salid waste disposal Open dumping, mixed wastes
• Hazardous waste management Non-existent capacity Rosource losses
• Land management Uncontrolled land development and use: pressure from squatter settlements
Environment hazards
Natural and hazards Recurrent disaster with severe damage and loss of life
Sumber: Cohen daan Serageldin (1994)
Kondisi lingkungan perkotaan mengalami penurunan carrying capacity
setiap terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk di perkotaan. Hal ini
mengakibatkan banyak munculnya permasalahan yang ada di perkotaan
khususnya dalam hal daya dukung lingkungan dan perekonomian masyarakat.
Berdasar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman, dijelaskan bahwa pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di
luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Prasarana lingkungan
pemukiman diartikan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan
lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana utama
meliputi jaringan jalan, jaringan air hujan, jaringan pengadaan air bersih, jaringan
2.1.4. Kemiskinan
Kemiskinan disebut Sayogyo dalam Rusli dkk. (1995) adalah sebagai ciri
dan dan akibat ketidaksamaan dalam masyarakat yang menjadikan sebagian
golongan tak mampu mencapai tingkat hidup layak, sesuai harapan dan cita-cita
hidup dalam masyarakat berdasar swadaya golongan itu. Secara politik,
kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (power).
Analisis terkecil dalam kemiskinan adalah keluarga dan bukan individu,
menurut Rusli dkk. (1995). Alasanya adalah keluarga merupakan satuan sosial
ekonomi terkecil dalam masyarakat.
Rusli dkk. (1995) menjelaskan pemahaman masalah kemiskinan perlu
membedakan indikator kemiskinan dalam kelompok (a) ‘input’ bagi proses
terjadinya kemiskinan. Merupakan faktor-faktor yang berpengaruh pada
kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dapat dilihat dari
ketersediaan sarana, penguasaan aset, kondisi aksesibilitas (tingkat isolasi daerah)
dll. (b) ‘proses’ terjadinya kemiskinan itu sendiri, isalnya orientasi usaha, tingkat
teknologi, dll. (c) ‘output’ yang berupa tingkat kemiskinan, menyangkut tingkat
pendapatan atau pengeluaran, daya beli, komposisi pengeluaran, kondisi rumah,
dll.
Kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua, yakni kemiskinan
struktural dan kultural. ”Kemiskinan struktural ialah kemiskinan yang diderita
oleh golongan dari masyarakat karena struktur sosial, masyarakat itu tidak dapat
ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi
mereka”, Sumardjan (1984). Teori budaya kemiskinan yang dicetuskan Lewis
dalam Krisdyatmiko (2006) memaparkan kemiskinan budaya muncul dari
teralienasinya orang-orang di lingkungan slum dari kehidupan kota yang
dikendalikan oleh kelas menengah di perkotaaan.
Berdasar hasil penelitian Rusli dkk. (1955), “…penyelenggaraan proyek di
perkotaan pada daerah kumuh (slum) yang dihuni orang-orang miskin dapat
diterapkan tanpa perlu bekerja melalui elit lokal, karena biasanya kelembagaan
sosial kelompok masyarakat kumuh relatif tidak terintegrasi dengan kelembagaan
formal perkotaan. Masyarakat seperti ini benar-benar mewakili suatu ciri
Untuk memahami permasalahan kemiskinan dapat juga menggunakan
analisis “pohon kemiskinan” menurut Rusli dkk. (1995), sebagai berikut:
Daun : gambaran ekosistem wilayah dimana kemiskinan itu ditemukan (kumuh,
terisolir, kritis, dll.)
Bunga : ciri-ciri kemiskinan yang dapat dikenali (rumah tak layak huni, kurang
pangan, pendidikan rendah, dan sebagainya).
Buah : akibat kemiskinan (gizi buruk dan dampak sosial ekonomi lainnya).
Batang : stuktur sosial (pola hubungan berbagai pihak/lapisan) yang menyebabkan
timbulnya masalah kemiskinan (tingkat upah, ketimpangan penguasaan
tanah, kelangkaan asset produksi, kesulitan modal, ijon, dll.).
Akar : penyebab kemiskinan, meliputi kondisi fisik/alam, sosial, ekonomi,
politik, pola budaya, infrastruktur, dll.
2.1.5. Pengelolaan Sampah
Sampah merupakan zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak lagi
digunakan lagi baik berupa bahan bangunan yang berasal dari rumah tangga,
“Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan”, Murbandono
(1993). Kebijakan pemerintah tentang Pengelolaan Sampah terdapat dalam UU
No. 18/2008. Tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan
kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai
sumberdaya.
Pengelolaan sampah Nainggolan dan Safrudin dalam Sasmita (2009), meliputi:
1. Pengomposan sampah, cara mengolah bahan padatan organik untuk menjadi
kompos melalui proses degradasi materi organik melalui reaksi biologi
mikroorganisme. Ketersediaan bahan organik dalam sampah kota 70-80%
2. Pembakaran sampah, pengurangan sampah mencapai 80% dari sampah yang
masuk, sedangkan sisanya yakni 20% dibuang ke TPA.
3. Daur ulang sampah, komponen sampah yang mempunyai nilai tinggi untuk
dimanfaatkan kembali.
Menurut Newman dan Paoletto (1999), pendekatan regulasi dan teknologi
dorongan inisiatif daur ulang yang berbasis masyarakat, perubahan sikap publik
terhadap konsumsi dan pembuangan sampah melalui informasi dan pendidikan
publik merupakan beberapa metodologi yang mengkombinasikan pendekatan
“atas ke bawah/top down” dan “ dan bawah ke atas/komunitarian/buttom up”.
2.2.Kerangka Pemikiran
Partisipasi merupakan elemen penting yang diharapkan terbentuk melalui
upaya pemberdayaan (empowerment is road to participation). “Munculnya
partisipasi komunitas dalam kegiatan pemberdayaan dapat dipengaruhi oleh faktor
eskternal maupun internal individu sebagai pelaku dan pelaksana program”,
Oppenheim dalam Sumardjo (2009).
Ada tiga faktor utama yang menjadi pendorong partisipasi yakni adanya
kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Ketiga faktor dijabarkan menjadi sepuluh
aspek yang menjadi prasyarat pendorong partisipasi. Pertama, tingkat kemauan
meliputi persepsi tentang lingkungan dan sikap terhadap pengelolaan lingkungan,
serta motivasi untuk berperan serta dalam program pengelolaan sampah organik.
Kedua, tingkat kemampuan meliputi tingkat pengetahuan, tingkat ketrampilan,
tingkat pengalaman di bidang pengelolaan sampah sebelum adanya pendampingan
program, dan ketersediaan waktu untuk terlibat dalam program. Ketiga, tingkat
kesempatan yang merupakan faktor luar diantaranya tingkat efektivitas
kelembagaan, tingkat kemudahan birokrasi untuk terlibat dalam program
pengelolaan sampah organik, serta tingkat ketersediaan regulasi tentang
pengelolaan sampah.
Komunitas kumuh perkotaan memiliki posisi termarginal di negeri ini
maka partisipasi komunitas dalam program pengelolaan sampah organik erat
kaitannya dengan derajat kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan.
Berdasar konsep tingkat partisipasi yang dijelaskan oleh Arnstein (1969) dan
kerangka deskriptif analisis partisipasi yang dijelasakan oleh Uphoff, Cohen, dan
Goldsmith (1979) mengenai “Kerangka Analisis Deskriptif Partisipasi”. Dalam
penelitian ini, tingkat partisipasi komunitas kumuh perkotaan di bantaran Sungai
Ciliwung dalam program pengelolaan sampah organik akan diketahui dengan
partisipasi dalam tahapan program; (2) Pihak-pihak yang terlibat dalam program;
dan (3) Bentuk partisipasi komunitas. Dengan demikian, akan diketahui sejauh
mana derajat kekuasaan komunitas menggunakan tipologi Arnstein, mulai dari
tingkat manipulatif, terapi, pemberitahuan, konsultatif, penenangan, kemitraan,
pendelegasian, sampai kontrol masyarakat. Untuk lebih jelasnya alur kerangka
pemikiran dalam penelitian ini tersaji pada Gambar 2.
Keterangan :
: mempengaruhi : dianalisis
Gambar 2. Kerangka Pemikiran
Tingkat Partisipasi
1. Manipulatif 2. Terapi
3. Pemberitahuan 4. Konsultatif 5. Penenangan
• Persepsi tentang lingkungan
• Sikap terhadap pegelolaan lingkungan
• Motivasi untuk terlibat dalam program pengelolaan sampah organik
Tingkat Kemampuan
• Tingkat pengetahuan di bidang pengelolaan sampah
• Tingkat ketrampilan di bidang pengelolaan sampah
• Tingkat pengalaman di bidang pengelolaan sampah
• Tingkat ketersediaanwaktu
Tingkat Kesempatan
• Tingkat efektivitas kelembagaan
• Tingkat kemudahan birokrasi
• Tingkat ketersediaan regulasi
Analisis Derajat Kekuasaan dalam Pengambilan Keputusan pada Program Pengelolaan Sampah
Organik Perencanaan Komunitas Pikiran Pelaksanaan Stakeholder Tenaga
2.3.Hipotesis
1. Ada hubungan nyata antara tingkat kemauan yang dimiliki komunitas terhadap
tingkat partisipasi dalam program pengelolaan sampah organik.
a. Ada hubungan signifikan antara persepsi tentang lingkungan terhadap tingkat
partisipasi
b. Ada hubungan signifikan antara sikap terhadap pengelolaan lingkungan
menentukan tingkat partisipasi
2. Ada hubungan signifikan antara tingkat kemampuan yang dimiliki komunitas
terhadap tingkat partisipasi dalam program
a. Ada hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan dalam bidang
pengelolaan sampah sebelum ada pendampingan program terhadap tingkat
partisipasi
b. Ada hubungan signifikan antara tingkat ketrampilan dalam bidang
pengelolaan sampah sebelum ada pendampingan program terhadap tingkat
partisipasi
c. Ada hubungan signifikan antara tingkat pengalaman dalam bidang
pengelolaan sampah sebelum ada pendampingan program terhadap tingkat
partisipasi
d. Ada hubungan signifikan antara tingkat ketersediaan waktu terhadap tingkat
partisipasi
3. Ada hubungan signifikan antara tingkat kesempatan yang disediakan dari
“lingkungan luar” terhadap tingkat partisipasi komunitas dalam program.
a. Ada hubungan signifikan antara tingkat efektivitas kelembagaan terhadap
tingkat partisipasi
b. Ada hubungan signifikan antara tingkat kemudahan birokrasi dalam program
terhadap tingkat partisipasi
c. Ada hubungan signifikan antara tingkat ketersediaan regulasi tentang
2.4. Definisi Operasional
Definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini
mengenai faktor pendorong partisipasi dan tingkat pertisipasi untuk mengukur
sejauh mana partisipasi komunitas terhadap program pengelolaan sampah organik.
A. Faktor pendorong partisipasi ialah faktor-faktor yang mempengaruhi
responden sehingga berparanserta dalam program, diantaranya:
1. Tingkat kemauan adalah keinginan responden untuk berpartisipasi dalam
program pengelolaan sampah organik. Tingkat kemauan diukur melalui
akumulasi skor dari aspek psikologis individu, meliputi persepsi dan sikap
responden terhadap program. Sedangkan motivasi berpartisipasi digunakan
untuk melihat alasan keterlibatan komunitas dalam program.
a. Persepsi tentang lingkungan adalah cara pandang terhadap pelestarian
lingkungan melalui program pengelolaan sampah organik dengan mengenali
dan memahami stimulus yang diterima responden.
Pengukuran :
1. Tidak tepat = skor 1
2. Tepat = skor 2
b. Sikap terhadap pengelolaan sampah organik adalah pernyataan evaluatif yang
mengindikasikan kecenderungan responden dalam menanggapi program,
berupa penerimaan atau penolakaan.
Dapat diukur dengan menggunakan skalalikert dari 1 (respon paling negatif)
sampai 5 (respon paling positif). Skala likert tersebut mencakup pilihan:
1. Sangat Tidak Setuju = skor 1
2. Tidak Setuju = skor 2
3. Ragu-ragu = skor 3
4. Setuju = skor 4
5. Sangat Setuju = skor 5
c. Motivasi terhadap program pengelolaan sampah organik adalah dorongan dari
dalam diri responden untuk terlibat dalam program pengelolaan sampah
organik. Motivasi mencakup faktor-faktor yang melatarbelakangi responden
Motivasi diukur dengan menggunakan metode rangking dari faktor yang
memotivasi warga untuk terlibat dalam program, mulai dari faktor motivasi
tertinggi dengan skor (5) sampai terendah dengan skor (1).
Penilaian terhadap tingkat kemauan yaitu dengan mengakumulasi jumlah skor
dari persepsi dan sikap.
Penentuan selang skor menurut rumus sebagai berikut:
Sehingga tingkat kemauan dapat dikategorikan menjadi:
1. Rendah, yaitu skor 24 < X ≤ 72
2. Tinggi, yaitu skor 72 < X ≤ 120
2. Tingkat kemampuan adalah daya yang dimiliki responden sehingga sanggup
berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah organik karena adanya
bekal pengetauan, ketrampilan, pengalaman dalam bidang pembuatan kompos
serta ketersediaan waktu yang dimiliki untuk berpartisipasi dalam program.
a. Tingkat pengetahuan adalah pemahaman responden tentang pengelolaan
sampah organik menjadi pupuk kompos sebelum adanya program.
Pengukuran:
1. Tidak punya = skor 1
2. Punya = skor 2
b. Tingkat ketrampilan adalah keahlian yang dimiliki responden dalam proses
pembuatan pupuk kompos sebelum dicanangkannya program.
Pengukuran:
1. Tidak punya = skor 1
2. Punya = skor 2
c. Tingkat pengalaman adalah responden pernah mengalami mengolah sampah
organik hingga menjadi pupuk kompos sebelum terlibat dalam program.
Pengukuran:
1. Tidak punya = skor 1
2. Punya = skor 2
d. Tingkat ketersediaan waktu adalah responden mempunyai waktu untuk
berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah organik.
Pengukuran:
1. Tidak punya = skor 1
2. Punya = skor 2
Penilaian terhadap tingkat kemampuan yaitu dengan mengakumulasi jumlah
skor dari tingkat pengetahuan, tingkat ketrampilan, tingkat pengalaman, dan
tingkat ketersediaan waktu. Tingkat kemampuan dapat dikategorikan menjadi:
1. Rendah, yaitu skor 4 < X ≤ 6
2. Tinggi, yaitu skor 6 < X ≤ 8
3. Tingkat kesempatan adalah faktor luar yang berasal dari lingkungan yang
mempengaruhi responden sehingga mempunyai peluang untuk berpartisipasi
dalam program pengelolaan sampah organik.
a. Tingkat efektivitas kelembagaan adalah sejauh mana akesibilitas yang
diberikan Ciliwung Merdeka kepada komunitas untuk mendapatkan sumber
daya yang dibutuhkan dalam program, berupa penyampaian saran dan kritik,
mengakses informasi terkait dengan program dan kesempatan untuk turut
berperan dalam proses pengambilan keputusan.
Pengukuran:
1. Tidak efektif = skor 1
2. Efektif = skor 2
b. Tingkat kemudahan birokrasi adalah adanya sistem yang mengatur
persyaratan responden untuk terlibat dalam program.
Pengukuran:
1. Tidak ada = skor 1
2. Ada = skor 2
c. Tingkat ketersediaan regulasi adalah responden tahu adanya
peraturan/kebijakan pemerintah yang mengatur pengelolaan sampah.
Pengukuran:
1. Tidak ada = skor 1
Penilaian terhadap tingkat kesempatan yaitu dengan menjumlah skor dari tingkat
efektivitas kelembagaan, tingkat kemudahan birokrasi, dan tingkat ketersediaan
regulasi. Sehingga tingkat kesempatan dapat dikategorikan menjadi:
1. Rendah, yaitu skor 5 < X ≤ 7,5
2. Tinggi, yaitu skor 7,5 < X ≤ 10
B. Tingkat partisipasi ialah tingkat keterlibatan anggota komunitas dalam tahapan
program pengelolaan sampah organik.
Pengukuran:
1. Tidak terlibat = skor 1
2. Terlibat = skor 2
Untuk menganalisis lebih lanjut tingkat partisipasi berdasar gradasi derajat
kekuasaan, maka tingkat partisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan program
pengelolaan sampah organik digolongkan sebagai berikut:
1. Tahap manipulasi, dinyatakan sebagai bentuk partisipasi yang tidak menuntut
respon partisipan untuk terlibat banyak dalam suatu kegiatan dan Ciliwung
Merdeka yang aktif karena ingin kepentingannya tercapai melalui program.
2. Tahap terapi ialah dengar pendapat, tetapi pendapat dari partisipan sama sekali
tidak dapat mempengaruhi kedudukan program yang sedang dilaksanakan.
3. Tahap pemberitahuan, sekedar pemeberitahuan searah atau sosialisasi dari
Ciliwung Merdeka kepada partisipan program yang bersifat top down.
4. Tahap konsultasi, komunitas diberikan pendampingan dan konsultasi dengan
Ciliwung Merdeka sehingga komunitas dilibatkan dalam penentuan keputusan
(dialog dua arah), tetapi dalam proses dialog hanya melibatkan “wakil warga”.
5. Tahap penenangan, dicirikan dalam komunikasi sudah ada negosiasi antara
pihak yang terlibat, dicirikan dengan pemberian insentif kepada warga tetapi
sebatas untuk meredam keinginan warga menolak program. (partisipasi semu).
6. Tahap kemitraan, dimana partisipan dan Ciliwung Merdeka bersama
stakeholder lainnya bertindak sebagai mitra sejajar sehingga dapat
mewujudkan keputusan bersama melalui negosiasi (partisipasi fungsional).
7. Tahap pendelegasian kekuasaan merupakan Ciliwung Merdeka sudah
perencanaan, implementasi dan mentoring terhadap program tetapi tetap
dipantau oleh Ciliwung Merdeka.
8. Tahap kontrol masyarakat, sudah terbentuk independensi dari warga untuk
mengelola program tanpa intervensi dari Ciliwung Merdeka.
Penilaian pada tingkat partisipasi yaitu akumulasi skor pertanyaan partisipasi.
Tingkat partisipasi dari keseluruhan rangkaian program (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasil) diperoleh dari jumlah dari
akumulasi skor pertanyaan partisipasi dan dapat dikategorikan:
1. Manipulasi (manipulative) skor 8 < X ≤ 14
2. Terapi (therapy) skor 14 < X ≤ 21
3. Pemberitahuan (informing) skor 21 < X ≤ 28
4. Konsultasi (consultation) skor 28 < X ≤ 35
5. Penenangan (placation) skor 35 < X ≤ 42
6. Kerjasama (partnership) skor 42 < X ≤ 49