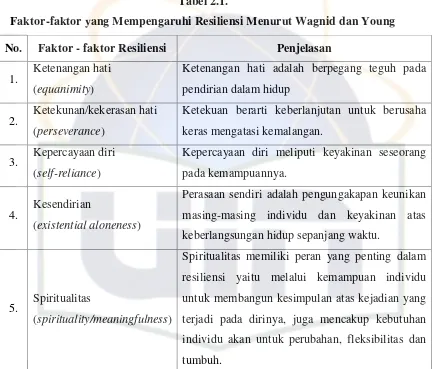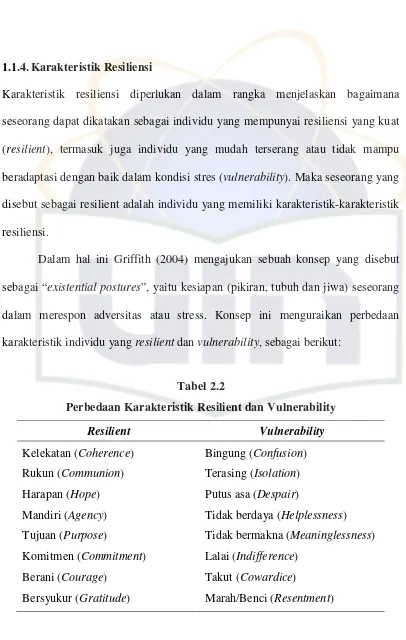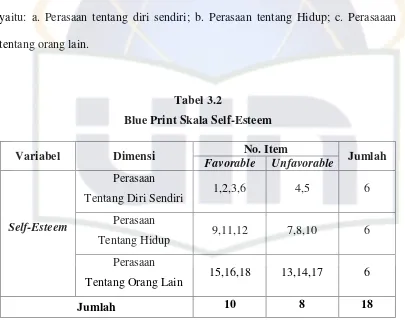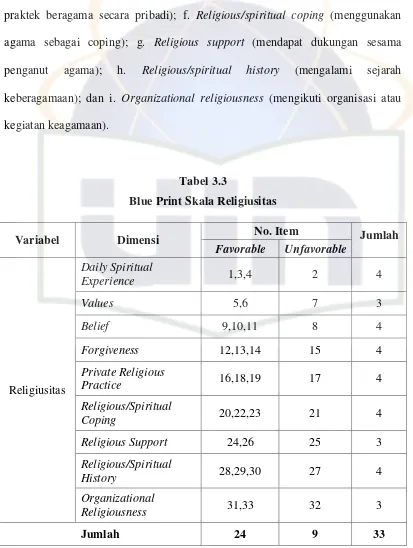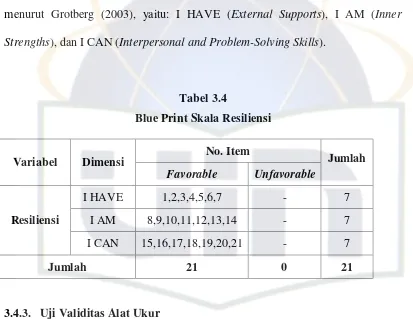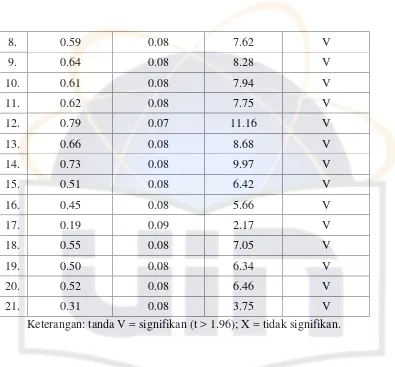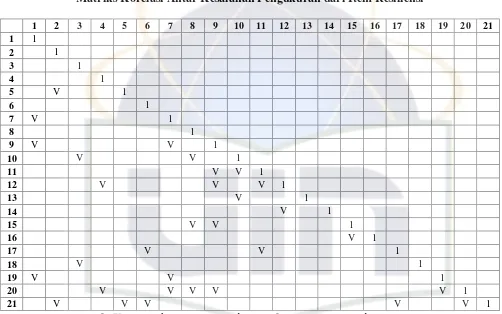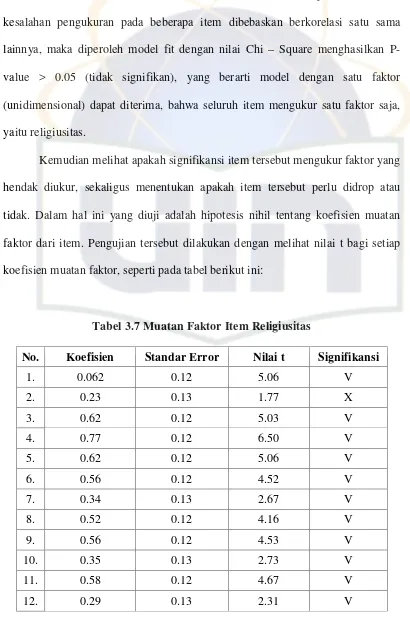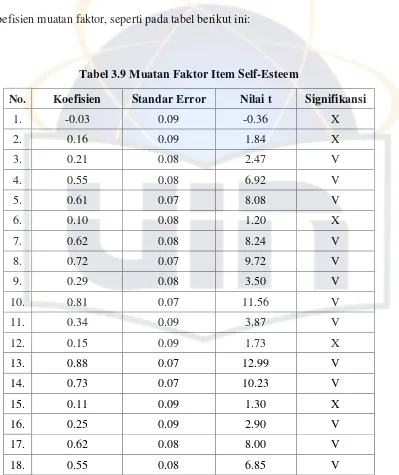Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Psikologi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi (S.Psi)
Oleh:
MUHAMMAD IQBAL
(106070002177)
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
HUBUNGAN ANTARA SELF-ESTEEM DAN
RELIGIUSITAS TERHADAP RESILIENSI PADA
REMAJA DI YAYASAN HIMMATA
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Psikologi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi (S.Psi)
Oleh:
MUHAMMAD IQBAL NIM: 106070002177
Di Bawah Bimbingan :
Pembimbing I
Ikhwan Lutfi, M.Psi
NIP. 19730710 200501 1 006
Pembimbing II
Zulfa Indira Wahyuni, M.Psi
NIP. 19810509 200901 2 012
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1432H/2011M
PENGESAHAN
Skripsi yang berjudul “HUBUNGAN ANTARA SELF-ESTEEM DAN RELIGIUSITAS TERHADAP RESILIENSI PADA REMAJA DI YAYASAN HIMMATA”, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 6 Desember 2011. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Fakultas
NIP. 19730710 200501 1 006
Zulfa Indira Wahyuni, M.Psi
NIP. 19810509 200901 2 012
PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : Muhammad Iqbal
NIM : 106070002177
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “HUBUNGAN ANTARA SELF-ESTEEM DAN RELIGIUSITAS TERHADAP RESILIENSI PADA REMAJA DI YAYASAN HIMMATA” adalah benar merupakan karya saya dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunan karya tersebut. Adapun kutipan-kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah dicantumkan sumber pengutipannya dalam skripsi. Saya bersedia untuk melakukan proses yang semestinya sesuai dengan undang-undang jika ternyata skripsi ini secara prinsip merupakan plagiat atau ciplakan dari karya orang lain.
Demikian pernyataan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.
Jakarta, 29 November 2011 Yang Menyatakan,
Muhammad Iqbal NIM: 106070002177
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO :
(
#q
Ł
=t«¡ sø @dr&ł
.ˇe
%!
$# b˛
) OGY. wt
b qHs>Łs?
“Maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan
jika kamu tidak mengetahui”. (An-Nahl: 43)
Persembahan:
Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, B apak M .
Syamsuddin dan I bu D. Sholihati yang telah mendoakan, mendidik dan
membentuk karakter saya hingga saat ini.
ABSTRAK
A) Fakultas Psikologi
B) November 2011
C) Muhammad Iqbal
D) Hubungan Antara Self-Esteem dan Religiusitas Terhadap Resiliensi Pada
Remaja di Yayasan HIMMATA
E) xiv + 126 halaman + lampiran
F) Persaingan dunia global saat ini, telah menciptakan kelompok masyarakat
yang hidup dengan status sosioekonomi yang rendah, kaum miskin kota, kelompok marginal, anak jalanan, dan masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. Dalam konteks remaja sebagai individu yang tengah dihadapkan pada pencarian jati diri dan status sebagai orang dewasa, hal tersebut menjadi suatu ancaman baru bagi perkembangan psikologis mereka, karena secara alami remaja mudah tertekan dengan beragam resiko (Goldstein, 2005). Data Badan Pusat Statistik (2010), menyebutkan terdapat 110.978.00 warga miskin yang hidup di kota, dan 19.925.600 warga miskin lainnya hidup di desa. Lalu data DEPSOS RI (2010), menyebutkan jumlah anak jalanan pada tahun 2008 sebanyak 109.454 jiwa. Remaja yang berhasil menghadapi tantangan-tantangan dan kesengsaraan adalah remaja yang mampu mengembangkan kerangka
berpikir untuk menjadi resilient. Yaitu mereka yang mampu berkembang
dengan baik (Gordon, 1993), adaptif dan tak terkalahkan (Werner & Smith, 1982), tidak mudah terserang (Garmezy, 1985), berhasil beradaptasi dengan keadaan yang merugikan (Norman, 2000), dan mereka yang mampu menghadapi, mengatasi, mempelajari, dan berubah melalui kesulitan-kesulitan yang tak terhindarkan (Grotberg, 2003). Untuk menjadi
resilient atau memiliki resiliensi yang baik, banyak faktor yang
menentukan, salahsatunya adalah self-esteem (perasaan tentang diri
sendiri, perasaan tentang hidup, dan perasaan tentang orang lain) dan
religiusitas (daily spiritual experience, values, beliefs, forgiveness, private
religious pratices, religious/spiritual coping, religious support, religious/spiritual history, organizational religiousness). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara self-esteem dan religiusitas dengan resiliensi pada remaja di Yayasan HIMMATA. HIMMATA atau Himpunan Pemerhati Masyarakat Marginal Kota) adalah sekolah bagi remaja dengan latar belakang sosioekonomi yang rendah (miskin), termasuk juga remaja yatim piatu, dan remaja yang menjadi anak jalanan. Sampel yang berjumlah 146 orang diambil dengan
teknik simple random sampling dan diberikan angket untuk mengukur
self-esteem, religiusitas dan resiliensi responden. Analisa data pada
penelitian ini menggunkan metode Statistic Multiple Regression Analysis
pada taraf signifikansi 0,05.
Hasil penelitian menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara self-esteem dan religiusitas dengan resiliensi pada remaja, dimana jika remaja memiliki self-esteem yang tinggi, maka resiliensinya akan tinggi pula, begitu juga dengan religiusitas. Sebaliknya, jika self-esteem dan religiusitas remaja rendah maka resiliensinya akan rendah pula. Pada pengujian dimensi masing-masing variabel dari self-esteem dan religiusitas sebagai variabel minor, menunjukkan bahwa hanya variabel
daily spiritual experience, values, forgiveness, private religious practice,
dan perasaan tentang diri sendiri yang signifikan terhadap resiliensi. Hasil penelitian juga menunjukkan proporsi varians dari resiliensi yang jelaskan
oleh semua indepent variable adalah sebesar 53,8%, sedangkan 46,2%
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.
Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian adalah pengadministrasian alat ukur, serta sampel penelitian yang lebih representatif dan homogen.
G) Bahan Bacaan: 33 Buku, 11 Jurnal, dan 2 Int enet . (1961-2011)
KATA PENGANTAR
Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia, hidayah, dan pencerahan-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan kesungguhan dan kerja keras. Penelitian ini adalah manifestasi pemahaman peneliti atas studi Ilmu Psikologi yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, khususnya studi Psikologi Sosial yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Penelitian ini diajukan sebagai prasyarat kelulusan pendidikan sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti telah melibatkan banyak pihak yang secara langsung maupun tidak telah memberikan konstribusi nyata bagi peneliti dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Termasuk juga pelajaran dan hikmah baik selama penyusunan skripsi, maupun selama peneliti menghabiskan berkuliah di Fakultas Psikologi. Terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan kepada:
1. Kedua orang tua, yang selalu mendukung, membantu dan memberikan
nasihat dengan sabar dan kerja keras selama peneliti menyelesaikan penelitian ini. Keempat saudaraku, t’Duha, Ismah, Jadid dan Fiah yang telah mendukung secara emosional selama peneliti mengerjakan skripsi dan umumnya selama masa perkuliahan.
2. Jahja Umar, Ph.D, Dekan Fakultas Psikologi UIN Jakarta, dan Dra.
Fadhilah Suralaga, M.Si, Pembantu Dekan I, beserta seluruh jajaran dekanat lainnya, yang secara totalitas dan kesungguhan telah memfasilitasi pendidikan kepada mahasiswa dalam rangka menciptakan lulusan-lulusan Fakultas Psikologi yang baik dan berkualitas.
3. Sitti Evangeline I. Suaidy, M.Si, Psi., selaku pembimbing akademik yang
selalu membantu, mendukung, dan memberikan masukan kepada peneliti baik selama masa perkuliahan maupun selama peneliti melaksanakan
penelitian. Terimakasih untuk support yang luar biasa.
4. Ikhwan Lutfi, M.Psi. dan Zulfa Indira Wahyuni, M.Psi, dosen pembimbing
peneliti yang dengan kesabaran dan kesungguhan telah memberikan banyak saran dan kritik kepada peneliti selama masa penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah meluangkan waktu yang begitu berharga untuk berdiskusi dan memberikan masukan.
5. Dosen-dosen peneliti, Mrs. Yunita, Mrs. Rena Latifa, Mr. Avicena, Mr
Abdul Mujib, dan seluruh dosen di Fakultas Psikologi yang telah membimbing, memberikan masukan, dan bertukar ide dengan peneliti selama penyusunan skripsi maupun masa perkuliahan. Terimakasih untuk dedikasi yang luar biasa, dosen-dosen yang mendidik dengan kejujuran
dan kesungguhan, dosen-dosen yang mengatakan tahu jika mengetahui, dan tidak tahu jika tidak mengetahui. Terimakasih.
6. Pak Sarkono, kepala Yayasan HIMMATA, terimakasih telah memberikan
izin dan memfasilitasi peneliti selama peneliti melaksanakan penelitian di Yayasan HIMMATA.
7. Roni, pengajar di Yayasan HIMMATA yang telah banyak membantu dan
memfasilitasi peneliti selama masa penelitian, khususnya selama masa pengambilan data di Yayasan HIMMATA. Terimakasih untuk kemurahan hati dan keikhlasannya membantu peneliti mendapatkan banyak pengalaman dan pelajaran berharga selama berada di HIMMATA.
8. Para responden peneliti di Yayasan HIMMATA, siswa/I SMP dan SMA
yang telah bersedia memberikan informasi dan mengisi angket penelitian sehingga peneliti dapat melaksanakan penelitian ini dengan hasil yang maksimal. Terimakasih untuk pelajaran berarti yang peneliti dapatkan. Kalian telah menunjukkan bagaimana menjadi individu yang resilient ditengah keterbatasan dan kesulitan hidup.
9. Adiyo dan ka Via, sahabat peneliti yang telah banyak membantu peneliti
dalam pengolahan dan analisa data selama penyusunan Bab 3-5. Terimakasih untuk kesungguhan dan kesediaannya sob.
10.Terakhir, terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan yang telah banyak
mendukung dan memberikan masukan baik selama penyusunan skripsi ini
maupun selama masa perkuliahan, Kharubi, Ade, agan Reza, agan Dimas,
agan Vita, Hani Istifa, Firanti, Cut, dan Tsauroh.
Penelitian ini tidak akan berarti tanpa kehadiran dan kontribusi dari seluruh pihak yang telah peneliti sebutkan di atas. Peneliti sangat berharap penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang dan bisa memberi manfaat bagi siapa saja yang membaca, serta menjadi kontribusi nyata sebagai wacana baru dalam diskursus kajian Ilmu Psikologi, khususnya Psikologi Sosial. Peneliti juga berharap siapapun yang membaca penelitian ini dapat memberikan masukan dan kritik yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Amin.
Jakarta, 29 November 2011
Peneliti
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ... i
HALAMAN PERSETUJUAN ... ii
HALAMAN PENGESAHAN ... iii
HALAMAN PERNYATAAN ... iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... v
ABSTRAK ... vi
KATA PENGANTAR ... vii
DAFTAR ISI ... x
DAFTAR TABEL ... xiii
DAFTAR LAMPIRAN ... xv
BAB 1 PENDAHULUAN ... 1-16 1.1 Latar Belakang Masalah ... 1
1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah ... 12
1.2.1 Perumusan Masalah ... 12
1.2.2 Pembatasan Masalah ... 13
1.3 Tujuan Penelitian ... 14
1.4 Manfaat Penelitian ... 14
1.5 Sistematika Penulisan ... 16
BAB 2 KAJIAN TEORITIS ... 17-70 2.1 Resiliensi ... 17
2.1.1 Pengertian Resiliensi ... 17
2.1.2 Protective Factors dan Risk Factors ... 24
2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Resiliensi ... 27
2.1.4 Karakteristik Resiliensi ... 33
2.2 Self-Esteem ... 38
2.2.1 Pengertian Self-Esteem ... 38
2.2.2 Dimensi-Dimensi Self-Esteem ... 42
2.3 Religiusitas ... 46
2.3.1 Pengertian Religiusitas ... 46
2.3.2 Dimensi-Dimensi Religiusitas ... 48
2.4 Remaja ... 54
2.4.1 Pengertian Remaja ... 54
2.4.2 Resiliensi pada Remaja ... 56
2.4.3 Self-Esteem pada Remaja ... 58
2.4.4 Religiusitas pada Remaja ... 60
2.5 Kerangka Berpikir ... 62
2.6 Hipotesis Penelitian ... 67
BAB 3 METODE PENELITIAN ... 71-92 3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian ... 71
3.2 Variabel Penelitian ... 72
3.2.1 Definisi Konseptual ... 72
3.2.2 Definisi Operasional ... 73
3.3 Pengambilan Sampel ... 74
3.3.1 Populasi dan Sampel ... 74
3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel ... 74
3.4 Pengumpulan Data ... 75
3.4.1 Teknik Pengumpulan Data ... 75
3.4.2 Instrumen Penelitian ... 76
3.4.3 Uji Validitas Alat Ukur ... 78
3.4.3.1 Uji Validitas Skala Resiliensi ... 79
3.4.3.2 Uji Validitas Skala Religiusitas ... 82
3.4.3.3 Uji Validitas Skala Self-Etsem ... 86
3.5 Analisa Data ... 89
3.6 Prosedur Penelitian ... 91
BAB 4 HASIL PENELITIAN ... 93-110 4.1 Analisis Deskriptif ... 93
4.2 Uji Hipotesis Penelitian ... 99
4.2.1 Analisis Korelasional Variabel Penelitian ... 99
4.2.2 Analisis Regresi Variabel Penelitian ... 100
4.2.3 Pengujian Proporsi Varians Independent Variable ... 105
BAB 5 KESIMPULAN, DISKUSI DAN SARAN ... 111-120 5.1 Kesimpulan ... 111
5.2 Diskusi ... 112
5.3 Saran ... 117
5.3.1 Saran Metodologis ... 118
5.3.2 Saran Praktis ... 119
DAFTAR PUSTAKA ... 121-126 LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Karakteristik Remaja di Yayasan HIMMATA
Tabel 1.2 Alasan Pentingnya Penelitian Resiliensi
Tabel 2.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Resiliensi Menurut Wagnid dan
Young
Tabel 2.2 Perbedaan Karakt erist ik Resilient dan Vulnerabilit y
Tabel 3.1 Skor untuk Setiap Pernyataan Pada Skala
Tabel 3.2 Blue Print Skala Self-Esteem
Tabel 3.3 Blue Print Skala Religiusitas
Tabel 3.4 Blue Print Skala Resiliensi
Tabel 3.5 Muatan Faktor Item Resiliensi
Tabel 3.6 Matriks Korelasi Antar Kesalahan Pengukuran dari Item Resiliensi
Tabel 3.7 Muatan Faktor Item Religiusitas
Tabel 3.8 Matriks Korelasi Antar Kesalahan Pengukuran dari Item
Religiusitas
Tabel 3.9 Muatan Faktor Item Self-Esteem
Tabel 3.10 Matriks Korelasi Antar Kesalahan Pengukuran dari Item
Self-Esteem
Tabel 4.1 Distribusi Populasi Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 4.2 Distribusi Resiliensi Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 4.3 Distribusi Populasi Berdasarkan Usia
Tabel 4.4 Distribusi Resiliensi Berdasarkan Usia
Tabel 4.5 Signifikansi Perolehan Mean Berdasarkan Usia
Tabel 4.6 Distribusi Populasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 4.7 Distribusi Resiliensi Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 4.8 Signifikansi Perolehan Mean Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 4.9 Perolehan Skor Variabel Secara Kategorik
Tabel 4.10 Matriks Korelasi Antar Variabel
Tabel 4.11 Tabel Anova
Tabel 4.12 Tabel R Square
Tabel 4.13 Tabel Proporsi Varians Self-Esteem terhadap Resiliensi
Tabel 4.14 Tabel Proporsi Varians Religiusitas terhadap Resiliensi
Tabel 4.15 Tabel Koefisien Regresi
Tabel 4.16 Penghitungan Proporsi Varians Resiliensi
Tabel 4.17 Residual Plot Resiliensi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Item-item Skala Variabel Penelitian
Lampiran 2 Angket Penelitian
Lampiran 3 Skor-skor Variabel Resiliensi
Lampiran 4 Skor-skor Variabel Religiusitas
Lampiran 5 Skor-skor Variabel Self-Esteem
Lampiran 6 Gambar Analisis Konfirmatorik Resiliensi
Lampiran 7 Gambar Analisis Konfirmatorik Religiusitas
Lampiran 8 Gambar Analisis Konfirmatorik Self-Esteem
Pada bab ini berisi latar belakang mengapa perlu dilakukan penelitian tentang
resiliensi, tujuan dan manfaat penelitian, dan pembatasan masalah serta
sistematika penulisan.
1.1. Latar Belakang Masalah
Dalam menghadapi persaingan dunia global saat ini, dan di antara perkembangan
teknologi yang pesat, telah menciptakan kelompok masyarakat yang hidup dengan
kondisi sosioekonomi yang rendah, kaum miskin kota, kelompok-kelompok
marginal, anak jalanan, dan masyarakat yang hidup dalam keterbatasan.
Dalam konteks remaja, dimana menurut Beyth, Marom & Fischoff (dalam
Diclemente, Santelli, & Crosby, 2009),
Remaja adalah suatu periode kehidupan yang ditandai dengan
perubahan fisik, kognitif, sosial dan emosional yang terjadi secara cepat.
Secara normatif perkembangan remaja ditunjukkan dengan meningkatnya
kemandirian, perubahan dalam hubungan keluarga, prioritas hubungan
dengan teman sebaya, pembentukan identitas, meningkatnya kesadaran
moral dan nilai, kematangan kognitif, dan semua yang berangkat dari
perubahan fisiologis yang cepat. Namun dalam pertumbuhan positif yang
sangat pesat tersebut, masa perkembangan remaja juga membawa
peningkatan eksplorasi dan perilaku mengambil resiko yang
membahayakan.
Secara alami remaja menjadi mudah tertekan dengan beragam resiko yang
mengancam perkembangan psikologis mereka. Bahkan dewasa ini tidak ada
seorang anak pun yang terbebas dari tekanan, perubahan yang terjadi secara cepat
dan lingkungan yang memberi pengaruh stress telah menciptakan resiko baru bagi
anak-anak dan remaja (Goldstein, Brooks, 2005). Adriana Feder (dalam Reich,
Zautra & Hall, 2010) juga menyatakan bahwa kebanyakan orang sangat rentan
terhadap kejadian traumatis dalam kehidupan mereka, dan sebagian besar lainnya
memikul beban stres secara persisten sepanjang waktu.
Menurut Schilling, Aseltine & Gore (dalam Reich, et.al., 2010), terdapat
hubungan yang nyata antara kondisi kesehatan psikologis yang dialami remaja
berusia antara 18-22 tahun secara partikular dengan kemunduran dalam kondisi
sosioekonomi, dimana remaja dalam kondisi sosioekonomi yang rendah akan
mudah menghadapi masalah-masalah psikologis. Hal ini menggambarkan bahwa
remaja yang menghadapi tekanan baik karena kondisi sosioekonomi yang rendah,
lingkungan, maupun sikap diskriminasi atau remaja yang berada dalam
kesenjangan sosial, akan menghadapi ancaman serius dalam tahap perkembangan
yang sedang dijalani.
Salah satu kelompok remaja yang memiliki resiko tinggi dalam tahap
perkembangan tersebut adalah remaja yang bersekolah di Yayasan HIMMATA,
Plumpang, Jakarta Utara, dimana secara umum remaja yang bersekolah di
yayasan ini adalah remaja dengan latar belakang keluarga dengan status
sosioekonomi yang rendah (miskin). HIMMATA atau Himpunan Pemerhati
dengan tujuan memberikan pendidikan yang layak dan setara dengan lembaga
pendidikan lainnya bagi remaja berusia antara 12-21 tahun dengan latar belakang
keluarga tidak mampu, remaja yatim piatu atau ditinggalkan orang tua, dan remaja
yang hidup atau tinggal di jalanan.
Seperti pada kebanyakan yayasan sosial lainnya, Yayasan HIMMATA
tumbuh dan berkembang dari swadaya masyarakat dan donatur, termasuk
pemerintah. Oleh karenanya setiap remaja yang bersekolah di yayasan ini tidak
dipungut biaya sama sekali, dengan syarat mereka berasal dari keluarga miskin
(dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari RT, RW, dan kelurahan di mana
mereka tinggal). Latar belakang geografis dan sosiologis masyarakat Jakarta Utara
yang perkembangannya tidak sebaik di Jakarta Selatan maupun Jakarta Pusat,
dimana masyarakat marginal kota di Jakarta Utara menjadi sangat ketara dan
kental dengan potret sosial kemiskinan, menjadikan yayasan seperti HIMMATA
strategis bagi perkembangan pendidikan dan sosial masyarakat miskin kota.
Program pendidikan yang disediakan oleh HIMMATA adalah program
pendidikan paket C bagi SMP dan SMA, walaupun para siswa di yayasan ini tidak
dipungut biaya sama sekali sampai mereka lulus tahap ahkir Sekolah Menengah
Atas (SMA), namun kurikulum dan sistem pendidikan yang diterapkan sama
dengan penyelenggaran sekolah pada umumnya, termasuk program
ekstrakulikuler seperti marawis, futsal dan lain-lain. Sebagai nilai tambah yang
ada pada yayasan ini adalah program yang berkaitan dengan peningkatan
berjamaah di mushola jika waktu shalat telah tiba, diikuti dengan berdo’a dan
dzikir bersama.
Remaja dengan latar belakang keluarga tidak mampu, ditinggalkan orang
tua (yatim piatu), dan remaja yang tinggal di pemukiman yang kurang layak, serta
hidup di jalanan seperti yang terdapat di Yayasan HIMMATA, secara alami
menurut Goldstein dan Brooks (2005), menjadi mudah tertekan dengan beragam
resiko yang mengancam perkembangan psikologis mereka. Tetapi Goldstein dan
Brooks (2005), menekankan bahwa yang menjadi keyakinan adalah setiap
individu (remaja) mampu mengembangkan kerangka berpikir untuk menjadi
resilient. Mereka akan mampu mengurai stress dan tekanan secara lebih efektif,
mampu mengatasi setiap tantangan, mampu kembali dari kekecewaan,
kesengsaraan dan trauma, mengembangkan tujuan yang jelas dan realistis, mampu
memecahkan masalah, dan mampu berhubungan dengan orang lain secara
nyaman, serta mampu menyikapi dirinya dan orang lain dengan penghargaan.
Individu yang resilient sebagaimana dipaparkan di atas adalah individu
yang memiliki resiliensi yang baik, dimana resiliensi menurut Gordon, 1993
(dalam Gordon & Other, 1994), didefinisikan sebagai kemampuan untuk
berkembang dengan baik, matang dan bertambahnya kompetensi dalam
menghadapi keadaan-keadaan dan rintangan-rintangan yang sulit. Dalam rangka
untuk berkembang dengan baik, matang dan bertambahnya kompetensi tersebut,
seseorang harus menerapkannya pada semua sumber daya mereka; biologis,
Sementara menurut Ruther (dalam Mccubbin, 2001), resiliensi adalah
suatu hasil yang positif (dari proses adaptasi) dalam menghadapi kesengsaraan
seperti kemiskinan. Maka individu yang resilient adalah mereka yang adaptif; tak
terkalahkan dan tidak mudah terserang. Menurut Luthar (dalam MacDermid,
Samper, Schwarz, Nishida & Nyaronga, 2008), resiliensi didefinisikan sebagai
suatu fenomena atau proses yang secara relatif mencerminkan adaptasi positif saat
mengalami ancaman atau trauma yang signifikan. Resiliensi adalah konstruk yang
lebih tinggi yang menggolongkan dua dimensi yang berbeda, yaitu; ancaman yang
signifikan dan adaptasi positif, dan ini tidak pernah secara langsung diukur,
melainkan secara tidak langsung dapat disimpulkan berdasarkan bukti dua
penggolongan konstruk tersebut.
Werner & Smith (dalam Diclemente, et.al., 2009) menjelaskan bahwa
penelitian tentang resiliensi baru dimulai pada tahun 1954 ketika Emmy Werner
menerbitkan hasil penelitian tentang resiliensi yang melibatkan sekelompok
remaja yang lahir di pulau Kauai, Hawaii selama hampir 5 dekade. Werner
memulai penelitiannya dengan sebuah pertanyaan sederhana:
“Why some children did well socially and emotionally in the face of
adversity?”
Kemudian pada awal tahun 1950an terdapat sejumlah penelitian yang
dilakukan untuk bertujuan menjawab pertanyaan serupa yang diajukan oleh
Werner. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Norman Garmezy,
dimana ia membangun kerangka berpikir penelitian dengan sebuah pertanyaan
“What causes strength to overcome what causes harm?”
Pada intinya, penelitian tentang resiliensi fokus pada pertanyaan mengapa
seseorang yang hidup dalam kesengsaraan dan tekanan dapat kembali sehat,
sementara yang lain tidak. Penelitian resiliensi menurut Cutuli & Masten (dalam
Lopez, 2009) kemudian berkembang sebagai penelitian pada individu yang
memiliki resiko atas masalah perkembangan, termasuk anak-anak yang memiliki
resiko karena latar belakang keluarga mereka (seperti, memiliki orang tua dengan
beberapa gangguan mental), dan pengalaman hidup (seperti, kemiskinan atau
kekerasan lingkungan).
Sementara para peneliti lain yang mengembangkan resiliensi pada tahun
1970an dan 1980an, yaitu Lois Murphy, Michael Rutter, dan Garmezy, mereka
menilai pentingnya perkembangan positif yang tidak diduga-duga dan mulai
mencari penjelasan atas resiliensi. Dari permulaan tersebut, para pelopor teori
resiliensi memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan untuk mengembangkan
hasil yang lebih baik diantara individu-individu dengan resiko tinggi pada
permasalahan hidup (Cutuli & Masten dalam Lopez, 2009). Penelitian resiliensi
lebih banyak dikembangkan pada anak-anak dan remaja, karena anak-anak dan
remaja adalah populasi utama dimana resiliensi terjadi pada rentang waktu
tersebut (Ahern et al., dalam Resnick, Gwyther & Roberto, 2011).
Goldstein & Brooks (2005) dalam Handbook of Resilience in Children,
menjelaskan bahwa resiliensi mengurangi tingkat faktor-faktor resiko (risk
factors), dan meningkatkan level faktor-faktor pelindung (protective factors),
mudah terserang (vulnerabilities) dan meningkatkan kompetensi dan kekuatan
individu dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, Merubah derajat kondisi
faktor resiko dan faktor pelindung yang muncul untuk dihubungkan dengan
kelemahan dan kekuatan individu untuk melawan serangan dari gangguan dan
untuk menghasilkan resiliensi dalam menghadapi tantangan yang serius.
Alasan lainnya dikemukakan oleh Benard, Burgoa dan Wheldon (dalam
Goldstein dan Brooks, 2005), bahwa penelitian resiliensi penting dalam rangka
membangun komunitas yang mendukung pada pengembangan manusia
berdasarkan pada hubungan saling membantu, juga menunjukkan remaja pada
kebutuhan akan stabilitas psikologis dan rasa memiliki, dan penelitian resiliensi
penting karena resiliensi telah lama dikenal oleh para peneliti psikologi dan
menjadi konstribusi yang baik bagi psikologi, serta karena resiliensi mengarah
pada kebijaksanaan hati dan intuisi sebagai panduan bagi intervensi klinis,
Menurut Masten dan Coatsworth (dalam Goldstein & Brooks, 2005) ada
dua hal utama yang perlu diperhatikan dalam mempelajari resiliensi. Pertama,
adanya ancaman yang signifikan. Seseorang tidak dapat dikatakan sebagai
individu yang resilient jika ia tidak menghadapi ancaman atau kesengsaraan yang
signifikan yang mengancam perkembangan psikologisnya. Kedua, hasil yang
baik. Yaitu seseorang dikatakan resilient jika ia berhasil menghadapi ancaman
atau kesengsaraan dengan baik.
Resiliensi sendiri saat ini telah menjadi payung istilah untuk mencakupi
banyak perbedaan aspek individu dalam menghadapi kesulitan (adversity)
menjelaskan bahwa istilah “resiliensi” telah diadopsi sebagai pengganti dari istilah
sebelumnya yang digunakan untuk mendeskripsikan fenomena (seperti kondisi
tidak mudah terancam, tak terkalahkan, dan ketabahan), karena usaha pengenalan
istilah ini melibatkan proses individu untuk menjadi resilient.
Istilah resiliensi secara umum merujuk pada faktor-faktor yang membatasi
perilaku negatif yang dihubungkan dengan stress dan hasil yang adaptif meskipun
dihadapkan dengan kemalangan atau kesengsaraan”. (Waxman, et.al. 2003). Maka
resiliensi terkait sangat erat dengan stress, dan keduanya adalah konstruk yang
tidak dapat dipisahkan, karena resiliensi hanya bisa dijelaskan ketika ada kondisi
kesengsaraan/tekanan yang dihadapi seseorang, sementara kondisi kesengsaraan
atau tekanan tersebut memicu stress; dan manajemen stres yang mengarah pada
adaptasi yang positif adalah resiliensi (Blum & Blum, dalam Diclemente, Santelli
& Crosby, 2009).
Sementara itu, kesengsaraan atau tekanan yang dihadapi individu bisa
beragam bentuknya, diantaranya adalah individu yang mengalami masalah medis
(Brown & Harris dalam Goldstein & Brooks, 2005), keluarga yang memiliki
resiko (Beardslee, Beardslee & Podorefsky, Hammen, Worsham, Compas, & Ey,
dalam Goldstein & Brooks, 2005), masalah-masalah psikologis (Hammen dalam
Goldstein & Brooks, 2005), orang tua yang bercerai (Sandler, Tein, & West,
dalam Goldstein & Brooks, 2005), kehilangan atau ditinggalkan orang tua
(Lutzke, Ayers, Sandler, & Barr, dalam Goldstein & Brooks, 2005),
masalah-masalah yang terjadi di sekolah (Skinner & Wellborn dalam Goldstein & Brooks,
Faktor-faktor dalam skala yang luas seperti kondisi pasca perang atau
bencana alam, dipastikan dapat menyebabkan stress, tetapi faktor yang lebih
umum pada level makro adalah faktor-faktor seperti kemiskinan, diskriminasi, dan
ketidakadilan (Cicchetti & Dawson, dalam Diclemente, et.al., 2009).
Sebagai contoh, kemiskinan menurut Lerner & Steinberg (dalam
Diclemente, et.al. 2009), menjadi faktor resiko yang signifikan bagi kehidupan
jutaan remaja, dimana faktor tersebut menetap sejak mereka kanak-kanak hingga
remaja. Sementara menurut Furstenberg (Diclemente, et.al., 2009), kemiskinan
pada remaja berkembang dari keadaan keluarga dan lingkungan sekitar yang
miskin yang kemudian menjadi faktor resiko. Meskipun dampak kemiskinan lebih
spesifik terjadi pada perkembangan masa kanak-kanak, tetapi kemiskinan menjadi
salah satu faktor negatif yang paling signifikan bagi kondisi kesehatan mental dan
fisik remaja. Sejumlah penelitian menunjukkan hubungan yang nyata antara
kemiskinan dan permasalahan psikologis pada remaja, dan remaja yang tumbuh
dalam kemiskinan memiliki resiko lebih tinggi menghadapi masalah-masalah
psikologis.
Para peneliti resiliensi yang terdiri dari psikolog dan psikiatri, selama
tahun 1970-an telah mendapati fakta bahwa sejumlah anak-anak yang hidup
dalam kondisi sosioekonomi yang rendah seperti kemiskinan, cenderung akan
menghadapi hambatan dalam perkembangan psikologis (Garmezi, 1991; Murphy
& Morarty, 1976; Rutter, 1979; Werner, 1995, dalam Reich, Zautra & Hall,
Berdasarkan data dari Kementrian Sosial Republik Indonesia (2011), pada
tahun 2008 terdapat 6.767.159 warga miskin di Indonesia, hampir miskin sejumlah
7.561.831 dan warga yang sangat miskin sejumlah 2.989.038 jiwa. Sementara
menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2010) jumlah total penduduk miskin di
Indonesia yang berada di kota sebanyak 11.097.800 jiwa, dan yang terdapat di
desa sebanyak 19.925.600 jiwa. Lalu untuk data mengenai anak jalanan, jumlah
anak jalanan berdasarkan data Departemen Sosial Republik Indonesia (2011),
pada tahun 2007 terdapat 104.497 jiwa, dan pada tahun 2008 sebanyak 109.454
jiwa.
Berdasarkan data tersebut, maka dapat dipahami bahwa masyarakat miskin
Indonesia sangat memungkinkan untuk menjadi populasi sosial dalam penelitian
terkait ketahanan psikologis yang tercakup dalam resiliensi, karena sebagaimana
dijelaskan sebelumnya bahwa kemiskinan memiliki resiko lebih tinggi
menghadapi masalah-masalah psikologis.
Dalam resiliensi, banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah
self-esteem dan religiusitas. Self-esteem menurut Santrock dalam Educational
Psychology (2009), mengacu pada suatu gambaran menyeluruh dari individu.
Self-esteem juga berarti harga diri (self-worth) atau gambaran diri (self-image).
Sebagai contoh, seorang anak dengan self-esteem yang tinggi mungkin merasa
bahwa dirinya bukan hanya seorang anak, melainkan seorang anak yang baik.
Menurut Nicholson (dalam Guindon, 2010), self-esteem khususnya pada
remaja, adalah prediktor yang paling signifikan bagi resiliensi. Burns dan
Self-esteem diargumentasikan sebagai pelindung individu dari
pengaruh sakit dan mencegah dari berbagai macam permasalahan hidup.
Dasar pemikiran ini mengasumsikan bahwa individu dengan self-esteem
yang tinggi (yang berlawanan dengan individu dengan self-esteem yang
rendah), memiliki sikap yang secara sosial lebih dapat diterima dan
bertanggungjawab. Bagaimanapun individu tersebut menjadi lebih resilient
dalam menghadapi perubahan dalam hidup, dan secara umum menunjukkan
pencapaian yang lebih tinggi, dan pada akhirnya secara sosioemosional
lebih baik.
Sementara religiusitas (religiousness) adalah seberapa kuat individu
penganut agama merasakan pengalaman beragama sehari-hari (daily spiritual
experience), mengalami kebermaknaan hidup dengan beragama (meaning),
mengekspresikan keagamaan sebagai sebuah nilai (values), meyakini ajaran
agama (beliefs), memaafkan (forgiveness), melakukan praktek beragama secara
pribadi (private religious practices), menggunakan agama sebagai coping
(religious/spiritual coping), mendapat dukungan sesama penganut agama
(religious support), mengalami sejarah keberagamaan (religious/spiritual history),
komitmen beragama (commitment), mengikuti organisasi atau kegiatan
keagamaan (organizational religiousness) dan meyakini pilihan agamanya
(religious preference) (dalam Fetzer, 2003).
Pargament dan Cummings dalam “Handbook of Adult Resilience” (2010),
menyatakan bahwa faktor resiliensi yang signifikan bagi banyak orang adalah
religiusitas (religiousness). Para peneliti tersebut mengidentifikasi bagaimana
religiusitas membantu banyak orang dalam menahan pengaruh krisis dalam hidup.
pengaruh yang unik bagi resiliensi. (dalam Reich, 2010). Studi-studi empiris juga
telah menunjukkan hubungan yang nyata antara kejadian stress dengan berbagai
bentuk keterlibatan keberagamaan. (Bearon, Koeing, Bjorck, Cohen, Ellison,
Taylor, Lindenthal et.al., dalam Lopez, 2003).
Dari pemaparan beberapa faktor yang mempengaruhi resiliensi di atas,
peneliti menggunakan self-esteem dan religiusitas sebagai faktor yang
mempengaruhi resiliensi pada remaja di Yayasan HIMMATA. Dimana penelitian
kedua faktor tersebut akan diukur berdasarkan pada dimensi masing-masing
variabel dan signifikansinya terhadap resilensi. Dengan asumsi bahwa jika
self-esteem dan religiusitas remaja tinggi, maka resiliensi yang mereka miliki juga
tinggi, yang artinya kemampuan beradaptasi remaja terhadap berbagai macam
ancaman dan kesengsaraan juga tinggi. Maka melalui resiliensi ini akan terukur
kemampuan adaptasi, kompetensi, perkembangan dan kematangan psikologis
remaja di Yayasan HIMMATA dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan
tantangan hidup yang mereka hadapi.
1.2. Perumusan dan Pembatasan Masalah
1.2.1.Perumusan Masalah
Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengajukan
perumusan masalah yang akan dijadikan dasar dalam penelitian dan pengumpulan
data, yang dirumuskan sebagai berikut:
Apakah ada hubungan antara self-esteem dan religiusitas terhadap resiliensi
1.2.2.Pembatasan Masalah
Kajian dalam penelitian ini dibatasi pada hal sebagai berikut:
1. Self-esteem adalah nilai yang dilekatkan pada diri kita. Self-esteem juga
berarti penilaian atas ‘harga diri’ kita sebagai manusia, berdasarkan pada
persetujuan atau pengingkaran atas diri dan perilaku kita (Jerry
Minchinton, 1993).
2. Religiusitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seberapa kuat
individu penganut agama merasakan pengalaman beragama sehari-hari
(daily spiritual experience), mengekspresikan keagamaan sebagai
sebuah nilai (value), meyakini ajaran agama (belief), memaafkan
(forgiveness), melakukan praktek beragama secara pribadi (private
religious practice), menggunakan agama sebagai coping
(religious/spiritual coping), mendapat dukungan sesama penganut
agama (religious support), mengalami sejarah keberagamaan
(religious/spiritual history), dan mengikuti organisasi atau kegiatan
keagamaan (organizational religiousness) (dalam John E. Fetzer, 2003).
3. Resiliensi (resilience) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
kemampuan seseorang untuk menghadapi, mengatasi, mempelajari, atau
berubah melalui kesulitan-kesulitan yang tak terhindarkan (Grotberg,
2003).
4. Remaja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah individu yang
berusia antara 12 sampai 19 tahun yang sekolah di Yayasan
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui hubungan
antara self-esteem dan religiusitas terhadap resiliensi pada remaja.
1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat berupa:
a) Secara teoritik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
khazanah Ilmu Psikologi khususnya Psikologi Sosial, dan menambah
wawasan baru bagi pembaca tentang resiliensi pada remaja kaitannya
dengan self esteem dan religiusitas.
b) Secara praktis,
• Bagi subjek: Penelitian ini diharapkan secara praktis akan
bermanfaat dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada
remaja yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman psikologis,
bahwa tekanan dan ancaman yang diterima tidak akan
mempengaruhi kondisi psikologis mereka ketika self-esteem dan
religiusitas masih tinggi.
• Bagi lembaga atau yayasan sosial: Penelitian ini diharapkan dapat
menjadi masukan bagi lembaga/yayasan sosial yang menaungi
anak jalanan atau remaja yang memiliki resiko tinggi terhadap
ancaman psikologis, bahwa pembinaan yang dilakukan dapat
dilakukan melalui pendekatan resiliensi dimana anak perlu dididik
hidup yang dihadapi melalui peningkatan self-esteem dan
religiusitas, (intervensi dengan pendekatan community based).
• Bagi orang tua: Diharapkan dapat memberikan informasi dan
pemahaman kepada orang tua yang memiliki remaja dengan
tingkat resiko tinggi tentang resiliensi remaja yang dibangun
melalui peningkatan self-esteem dan religiusitas. Orang tua
diharapkan dapat menjadi lingkungan yang stabil dan kondusif
bagi remaja, sehingga keluarga dapat mendukung perkembangan
psikologis remaja dan melindunginya dari gangguan dan ancaman
psikologis (family asprotective factor).
• Bagi praktisi klinis: Diharapkan hasil penelitian ini dapat
memberikan wawasan baru bagi para praktisi klinis sebagai
panduan intervensi klinis tentang resilensi pada remaja, kaitannya
dengan peningkatan self-esteem dan religiusitas individu.
• Pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait remaja yang
memiliki resiko tinggi (remaja jalanan, atau remaja yang berada
dalam kemiskinan), bahwa pengambilan kebijakan dalam
menyikapi anak-anak atau remaja yang beresiko tinggi menghadapi
ancaman psikologis, penting dilakukan dengan menggunakan
pendekatan psikologi, yaitu bahwa kebijakan (pembinaan atau
mereka. Dampak psikologis tersebut tergantung pada seberapa kuat
resiliensi yang dimiliki oleh para remaja.
1.5. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dalam pembahasan tema yang diteliti, penulis membagi
penelitian ini dalam 5 (lima) bab dengan sistematikan sebagai berikut:
Bab 1 Pendahuluan, yang berisi latar belakang mengapa perlu dilakukan
penelitian resiliensi, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian,
pembatasan masalah serta sistematikan penulisan.
Bab 2 Landasan Teoritis, berisi teori yang menjelaskan masing-masing
variabel dalam penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi, dimensi-dimensi
pada tiap variabel, dan kerangka berpikir serta hipotesis penelitian.
Bab 3 Metodologi Penelitian, membahas tentang pendekatan dan metode
penelitian, variabel penelitian, yaitu definisi konseptual dan definisi operasional,
populasi dan sampel termasuk teknik pengambilan sampel, dan pengumpulan data
serta analisis data.
Bab 4 Hasil Penelitian, membahas mengenai hasil penelitian meliputi
pengolahan statistik dan analisis terhadap data
Bab 5 Kesimpulan, Diskusi dan Saran, berisi rangkuman keseluruhan isi
BAB 2
KAJIAN TEORITIS
Pada bab ini akan dibahas teori yang menjelaskan masing-masing variabel dalam
penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi, dimensi-dimensi pada tiap variabel,
dan kerangka berpikir serta hipotesis penelitian.
1.1.Resiliensi
1.1.1. Pengertian Resiliensi
Resiliensi telah menjadi salah satu konsep psikologi yang integratif dan heuristic
yang muncul pada abad ke-21 dalam kajian ilmu sosial. Meskipun banyak
terdapat variasi dalam definisi dan karakteristik, resiliensi muncul menjadi dua
domain utama dalam arus berpikir manusia yang kemudian menjadi pokok dari
arti konsep ini, yaitu:
Pertama: sebagai respon atas stress, resiliensi fokus pada pemulihan (recovery),
yaitu kemampuan untuk kembali dari kondisi stress, atau suatu
kapasitas untuk mendapatkan kembali keseimbangan (equilibrium)
secara cepat, serta mampu kembali pada kondisi kesehatan semula.
Kedua: sebagai dimensi pokok yang sama, yaitu ketahanan, yang menyatakan
keberlangsungan pertumbuhan dan peningkatan fungsi sebagai hasil
reaksi kesehatan atas stress. (Reich et.al. 2010).
Sementara Waxman, Gray dan Padron (2003), menjelaskan bahwa dalam
literatur psikologi, konsep resiliensi digunakan untuk menggambarkan tiga
kategori pokok fenomena:
Kategori pertama: mencakup kajian-kajian mengenai perbedaan individu
dalam pemulihan pasca trauma.
Kategori kedua: dibentuk untuk individu dari kelompok dengan resiko
tinggi untuk memperoleh hasil yang lebih baik daripada hasil yang secara
khusus diharapkan individu tersebut.
Kategori ketiga: mengacu pada kemampuan individu untuk beradaptasi
dalam kondisi stress.
Lopez (2009), menjelaskan bahwa resiliensi secara umum mengacu pada
adaptasi secara positif dalam konteks resiko (risk) dan kesengsaraan (adversity).
Resiliensi adalah konsep yang luas yang menekankan pada fenomena yang luas,
termasuk kapasitas sistem untuk menahan dan mengatasi tantangan-tantangan
yang signifikan. Dalam perkembangan manusia, penelitian resiliensi fokus pada
tiga situasi yang berbeda:
a. Berfungsi selama mengalami kesengsaraan yang signifikan (stress
resistance)
b. Mengembalikan fungsi yang baik pada tingkat sebelumnya menyusul
trauma yang beberapa kali mengganggu pengalaman (bouncing back)
c. Mencapai tingkatan baru pada adaptasi yang normal atau positif ketika
Sementara McCubbin (2001) menjelaskan, bahwa terdapat empat hal yang
saling berhubungan tetapi memiliki perspektif yang berbeda dalam memahami
resiliensi:
a. Sebagai akibat (outcomes) atas kesengsaraan/ancaman
b. Sebagai kompetensi yang menopang (sustained competence) saat terjadi
stress
c. Sebagai pemulihan (recovery) setelah trauma.
d. Sebagai hubungan antara protective factors dan risk factors
Beberapa definisi resiliensi menurut beberapa tokoh:
Menurut Grotberg (1996) dalam The International Resilience Project
Findings from the Research and the Effectiveness of Interventions, “Resiliensi
adalah kapasitas universal yang memungkinkan individu, kelompok atau
komunitas untuk mencegah, meminimalisir atau mengatasi pengaruh merugikan
atas kesengsaraan atau kesulitan.
Masih menurut Grotberg (2003) dalam sumber berbeda, Resilience for
today: Gaining strength from adversity, “Resiliensi adalah kemampuan seseorang
untuk menghadapi, mengatasi, mempelajari, atau berubah melalui
kesulitan-kesulitan yang tak terhindarkan”.
Luthar (dalam MacDermind et.al 2008), menyatakan bahwa resiliensi
didefinisikan sebagai suatu fenomena atau proses yang secara relatif
mencerminkan adaptasi positif meskipun saat mengalami ancaman atau trauma
menggolongkan dua dimensi yang berbeda, yaitu; ancaman yang signifikan dan
adaptasi positif, dan ini tidak pernah secara langsung diukur, melainkan secara
tidak langsung dapat disimpulkan berdasarkan bukti dua penggolongan konstruk
tersebut.
Menurut Charney (dalam Reich et.al. 2010), konstruk resiliensi mengacu
pada kemampuan individu untuk beradaptasi secara sukses dalam menghadapi
stres akut, trauma, atau kesengsaraan yang kronis, untuk memperoleh kembali
kesehatan psikologis dan keseimbangan fisiologis.
Menurut Goldstein dan Brooks (2001), “Resiliensi adalah kekuatan dari
dalam diri untuk berhadapan secara kompeten dan sukses, hari ke hari, dengan
tantangan dan tuntutan yang mereka hadapi”.
Menurut Luthar, Cicchetti dan Becker (dalam McCubbin, 2001), resiliensi
mengacu pada sebuah proses dinamis yang mencakup adaptasi yang positif dalam
konteks kesengsaran atau kemalangan.
Wolin & Wolin’s (dalam Hooper, n.d), resiliensi adalah kemampuan
mengatasi tantangan-tantangan yang signifikan dalam masa perkembangan dan
secara konsisten dapat pulih kembali untuk menyelesaikan tugas-tugas
perkembangan pada masa selanjutnya.
Gordon (dalam Gordon & Other., 1994), resiliensi adalah:
Gordon et.al., (1994), menjelaskan bahwa resiliensi adalah fenomena yang
beraneka segi yang mencakup dua faktor: personal dan lingkungan. Berdasarkan
kerangka tersebut, terdapat empat hal yang dapat menjelaskan resiliensi, yaitu:
1. Menghilangkan stressor
2. Memberikan jalan alternatif untuk sukses
3. Memutus rantai negatif dari kejadian
4. Meningkatkan self-esteem (self-concept).
Wolin & Wolin (dalam Waxman, et.al. 2003), menjelaskan bahwa istilah
“resilient” telah diadopsi sebagai pengganti dari istilah sebelumnya yang
digunakan untuk mendeskripsikan fenomena (seperti kondisi tidak mudah
terancam, tak terkalahkan, dan ketabahan), karena usaha pengenalan istilah ini
melibatkan proses untuk menjadi resilient. Istilah resiliensi secara umum merujuk
pada fator-faktor dan proses-proses yang membatasi perilaku negatif yang
dihubungkan dengan stress dan hasil yang adaptif meskipun dalam kondisi
kemalangan/kesengsaraan.
Dalam Review of Research on Educational Resilience (2003), dijelaskan
bahwa perbedaan di antara definisi-definisi resiliensi seringkali berakar pada
pendekatan yang spesifik atau konteks dimana resiliensi dikaji (Waxman, et.al.
2003). Dan tantangan dalam menjabarkan konstruk resiliensi berhubungan dengan
kondisi kritis itu sendiri yang dinamis (seperti: resiko atau kesengsaraan dan
kompetensi atau adaptasi). Apa yang mungkin bisa dipertimbangkan adalah
faktor-faktor resiko atau stressor pada masa kecil mungkin sangat berbeda
kemampuan mengatasi dan beradaptasi pada kondisi stress dapat berubah
sepanjang waktu sebagai akumulasi dari pengalaman dan pengetahuan (Mc
Cubbin, 2001).
Cicchetti & Garmezy (1993), mencatat bahwa resiliensi tidak statis dan
mungkin berubah sepanjang waktu. Oleh karena itu, aspek yang dinamis
menjadikan resiliensi konstruk yang unik dibandingkan dengan konstruk yang
lain, dan ini adalah tantangan yang besar. Maka untuk mendefinisikan resiliensi,
seseorang perlu mempertimbangkan usia atau kapasitas psikologis yang
mengembangkan keterampilan tertentu atau perilaku dalam mengatasi adversitas
(dalam McCubbin, 20010). Kaufman, Cook, Arny, Jones & Pittinsky (1994),
menyepakati bahwa mendefinisikan resiliensi adalah suatu permasalahan yang
akan terus berkelanjutan. Oleh karenanya tidak mengherankan terjadi beragam
pendapat dalam mendefinisikan konsep resiliensi.
Hal ini bahkan dijabarkan lebih jauh dalam “Challenges to the Definition
of Resilience” oleh McCubbin (2001), tentang beberapa faktor yang
mempengaruhi perbedaan dalam mendefinisikan resiliensi, yaitu:
a. Pertama: Hubungan antara resiliensi dan faktor-faktor akibat (outcomes
factors).
Seperti: Mendefinisikan resiliensi sebagai variabel penengah
(moderator variable) dalam menguji hubungan antara kesengsaraan dan
akibat yang dimunculkan.
b. Kedua: Perbedaan dalam konseptualisasi resiliensi sebagai seperangkat
Seperti: Resiliensi didefinisikan sebagai pertambahan keterampilan
sosial, perkembangan emosional atau pencapaian akademis. Atau
outcome yang negatif yaitu penggunaan narkoba dan meningkatnya
aktivitas seksual.
c. Ketiga: Mendefinisikan dan mengoperasionalisasikan unsur resiliensi
yang tampak untuk mempengaruhi akibat/hasil yang akan dimunculkan.
Seperti: Variabel-variabel yang mempengaruhi keterampilan coping,
sikap-sikap menghadapi rintangan, atau faktor-faktor lingkungan seperti
dukungan keluarga dan keterlibtan komunitas.
d. Keempat: Resiliensi dilihat sebagai sekelompok faktor-faktor resiko
(risk factors) yang memberikan arti bagi respon manusia bertahan dan
pulih kembali dari kesengsaraan, seperti:
• Mengukur signifikansi kejadian dalam kehidupan seseorang.
Contohnya, kelahiran anak, pernikahan (positif), atau kematian
keluarga dan sakit (negatif)
• Mengukur stress yang spesifik seperti bencana alam atau kejadian
yang khusus seperti perceraian atau kehilangan keluarga.
• Memperhatikan stress yang kronis atau stres yang beruntun dan
konstelasi.
Berdasarkan pemaparan beberapa definisi di atas, serta uraian tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam mendefinisikan konstruk
resiliensi, penulis dapat menyimpulkan bahwa resiliensi adalah, “kemampuan
kemampuan dalam mengatasi berbagai bentuk ancaman, tekanan dan kesulitan
dalam hidup dalam rangka memperoleh keseimbangan psikologis.”
1.1.2.Protective Factors dan Risk Factors
Dalam kajian resiliensi, terdapat dua istilah yang terkait erat dengan konstruk
resiliensi, yaitu protective factors (faktor-faktor pencegah) dan risk factors
(faktor-faktor resiko). Protective factors adalah faktor-faktor yang menjaga
individu dari masalah perilaku. Sementara risk factor adalah faktor-faktor yang
menyebabkan individu dengan resiko permasalahan tinggi mengalami
permasalahan dalam perilaku. Menurut Kraemer (1997) istilah resiko (risk
factors) mengacu pada meningkatnya kemungkinan mendapatkan hasil yang
negatif (dari proses adaptasi) pada suatu populasi yang spesifik. Risk factors
disebutjugasebagai risk characteristics atau karakteristik resiko (dalam Glantz &
Johson, 2002).
Para peneliti bersepakat bahwa faktor-faktor resiko (risk factors)
berkonstribusi pada keadaan psikologis yang membahayakan, sementara
faktor-faktor pencegah (protective factors) mengurangi pengaruh dari kondisi kesulitan
atau kemalangan yang dihadapi (Benard, Constantine, Benard, & Diaz, Grotberg,
Masten, Tusaie & Dyer, dalam McCubbin, 2001). Interaksi antara faktor-faktor
resiko dan fakor-faktor pencegah penting untuk menguji variabel hasil (outcome
variable) yang mungkin berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada sifat
rangka memperbaiki dan melindungi seseorang dari hasil perkembangan yang
buruk (dalam McCubbin, 2001).
Terdapat tiga bentuk protective factors, yaitu: pertama, karakteristik
individu yang memunculkan respon positif dari lingkungan (seperti, anak-anak
yang memiliki temperamen yang baik dalam keluarga yang sedang menghadapi
kondisi stress yang signifikan). Kedua, praktek sosialisasi di dalam keluarga yang
mendorong kepercayaan, otonomi, inisiatif dan hubungan baik dengan orang lain.
Ketiga, sistem dukungan eksternal pada lingkungan sekitar atau komunitas yang
memperkuat self-esteem dan self-efficacy (dalam Goldstein & Brooks, 2005). Hal
serupa juga dipaparkan oleh Wyman (dalam Miller, 2005), tentang tiga bentuk
protective factors, yaitu, temperamen yang positif pada anak-anak, dukungan dari
lingkungan keluaga, dan adanya dukungan dari orang yang lebih dewasa atau
keluarga secara lebih luas.
Protective factors telah diuji dalam hubungannya dengan variabel resiko
dan variabel hasil dalam berbagai cara yang berbeda. Protective factors dapat
menjadi lawan penahan dari faktor-faktor resiko dan yang dapat menengahi
faktor resiko, serta melindungi hasil-hasil yang buruk (Jessor, 1999 Kumpfer,
1993; Masten et al, 1990; dan Rutter, 1987, sebagaimana dikutip dalam Norman,
2000). Bagaimanapun beberapa peneliti setuju bahwa protective factors hanya
dapat didefinisikan dalam hubungannya dengan faktor-faktor resiko karena
Risk factors
Outcomes
Protective factors
Beavias dan Oetting (1999), membedakan antara protective factors dan
konsep resiliensi. Protective factors berperan seiring meningkatnya kesempatan
perilaku prososial dan norma secara konsisten sepanjang waktu. Sementara
resiliensi hanya berfungsi ketika suatu permasalahan atau kesengsaraan muncul.
Beavias dan Oetting (1999) juga menyatakan, protective factors menjaga
seseorang dari bencana, sementara resiliensi mengembalikan kondisi seseorang
pasca bencana. Pembedaan antara protective factors dan resiliensi ini perlu
dipertimbangkan untuk menguji penelitian dan konstruk seseorang (dalam
McCubbin, 2001).
Protective factors dibagi menjadi dua kategori, yaitu:
1. Internal protective factors
Seperti: Harga diri (self-esteem), kemampuan diri (self-efficacy) dan
kejujuran (honesty). Internal protective factors memiliki dua sub-kategori,
yaitu:
a. Kejujuran
b. Tanggungjawab
c. Kemampuan mengendalikan seseorang atau kemampuan mengambil
2. External protective factors
Seperti: Dukungan keluarga dan keterlibatan komunitas. External
protective factors dibagi menjadi dua sub-kategori, yaitu:
a. Dukungan
b. Pemberdayaan
c. Batasan dan Harapan
d. Pemanfaatan waktu
1.1.3.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Resiliensi
Menurut Resnick, Gwyther & Roberto (2011), terdapat empat faktor yang
mempengaruhi resiliensi pada individu, yaitu: self-esteem, dukungan sosial,
spiritualitas atau keberagamaan dan emosi positif.
1. Self-Esteem
Memiliki self-esteem yang baik pada usia lanjut dapat membantu individu
dalam menghadapi kesengsaraan. Dua data dari hasil penelitian yang lebih
luas yang dilakukan oleh Collins & Smyer (2005), bertujuan menggali
self-esteem sepanjang rentang kehidupan manusia (yang dilakukan selama
periode 3 tahun), pada individu yang mengalami stres pada usia lanjut
(memiliki beban finansial). Para partisipan menyelesaikan alat ukur
self-esteem, nilai dan perasaan kehilangan. Hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa terjadi sedikit penurunan self-esteem pada individu
meskipun mereka menghadapi kehilangan. Kemudian, ketika mereka
mengurangi self-esteem yang dimiliki, meskipun individu tersebut
teridentifikasi sebagai individu yang sehat, begitu juga yang memiliki
penyakit, tidak menghasilkan perubahan yang berarti pada self-esteem.
2. Dukungan Sosial (Social Support)
Dukungan sosial sering dihubungkan dengan resiliensi (Hildon et al. 2009;
Maddi et al. 2006). Penelitian lain menunjukkan bahwa resiliensi dan
dukungan emosional (bukan dukungan instrumen) menghasilkan kualitas
hidup yang lebih tinggi pada individu usia lanjut (Netuveli & Blane,
2008). Penelitian pada orang dewasa di New York, Poindexter dan Shippy
(2008), yang dilakukan pada partisipan yang mengalami positif HIV,
menunjukkan bahwa jaringan dukungan sosial yang unik berkonstribusi
pada resiliensi. Para peneliti juga melakukan penelitian pada lima
kelompok yang memiliki jaringan dukungan sosial informal yang terdiri
atas individu-individu yang kebanyakan mengidap positif HIV.
Meskipun upaya untuk memperoleh dukungan sosial menurun
karena ketakutan dan stigma yang dialami, namun mereka mampu
merelokasi sumber daya dan mengisi dukungan melalui sumber daya HIV
positif pada komunitas mereka. Para partisian menunjukkan bahwa
kehilangan anggota kelompok karena kematian menyediakan kesempatan
bagi para anggota untuk memperkuat ikatan dukungan.
3. Spiritualitas (Spirituality)
Faktor lain yang mempengaruhi resiliensi dalam menghadapi tekanan dan
(religiousness) serta spiritualitas (spirituality) (Maddi et al. 2006).
Spiritualitas membutuhkan suatu pencarian di alam semesta, suatu
pandangan bahwa dunia lebih luas daripada diri sendiri, spiritualitas juga
berarti ketaatan pada suatu ajaran (agama) yang spesifik. Penelitian
tentang ketabahan, keberagamaan dan spiritualitas menunjukkan
kualitas-kualitas yang membantu individu dalam mengatasi kondisi stres dalam
hidup dan menyediakan perlindungan pada individu dalam menghadapi
depresi dan stres (Maddi et al. 2006).
Aspek positif dari spiritualitas juga turut membantu individu dalam
memulihkan perasaan kontrol diri saat sakit, dan membantu perkembangan
adaptasi saat sakit kronis dan tidak seimbang (Crowther et al. 2002). Pada
suatu hasil penelitian, spiritualitas memiliki hubungan dengan resiliensi
pada orang yang selamat dari penyakit kanker; meskipun individu tersebut
memiliki resiko lebih dalam mengembangkan depresi dan kecemasan,
tetapi tingkat spiritualitas dan personal mereka tumbuh lebih baik setelah
pemulihan (Costanzo et al. 2009)
4. Emosi Positif (Positive Emotions)
Bereaksi dengan emosi yang positif saat mengalami krisis dapat menjadi
cara dalam menurunkan dan mengatasi respon stres secara lebih efektif
(Davis et al. 2007). Kemudian, emosi positif juga dapat menjadi pelindung
dalam menghadapi ancaman terhadap ego. Perangkat teori ini dibangun
dan dikembangkan oleh Fredrickson (1998) yang menyatakan bahwa
beradaptasi pada situasi-situasi stres. Secara spesifik, respon negatif
terhadap stres (respon melawan atau menghindar) adalah sifat yang
terbatas, karena memilih respon positif selama mengalami stres
memungkinkan beragam respon yang lebih luas.
Dalam serangkaian penelitian, Tugade dan Fredrickson (2004),
menemukan bahwa respon positif saat mengalami stres berhubungan
dengan menurunnya tegangan secara fisiologis, dan mendukung adanya
hubungan antara pikiran dan tubuh. Kemudian, coping stres diketahui
lebih tinggi saat individu diinstruksikan untuk melihat situasi stres sebagai
suatu tantangan yang dapat membantu mereka tumbuh dengan lebih baik
daripada sebagai suatu ancaman yang merugikan. Kerangka kognitif
tersebut dapat menjadi cara untuk meningkatkan resiliensi. Studi
berikutnya menunjukkan suatu bukti adanya hubungan antara emosi positif
dan penilaian positif atas situasi. Melalaui beberapa penelitian tersebut,
menunjukkan bahwa individu yang memiliki resiliensi lebih baik, lebih
memungkinkan untuk mengalami emosi positif dan memanfaatnya untuk
mengatasi stres.
Wagnid dan Young (dalam Reich, et.al, 2010), mengembangkan suatu
skala resiliensi secara psikometri yang dikembangkan melalui wawancara pada
individu yang resilient. Skala tersebut dibangun melalui analisis faktor yang
mempengaruhi resiliensi, yaitu: ketenangan hati, ketekunan/kekerasan hati,
Tabel 2.1.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Resiliensi Menurut Wagnid dan Young
No. Faktor - faktor Resiliensi Penjelasan
1. Ketenangan hati
(equanimity)
Ketenangan hati adalah berpegang teguh pada
pendirian dalam hidup
2. Ketekunan/kekerasan hati
(perseverance)
Ketekuan berarti keberlanjutan untuk berusaha
keras mengatasi kemalangan.
3. Kepercayaan diri
(self-reliance)
Kepercayaan diri meliputi keyakinan seseorang
pada kemampuannya.
4. Kesendirian
(existential aloneness)
Perasaan sendiri adalah pengungakapan keunikan
masing-masing individu dan keyakinan atas
keberlangsungan hidup sepanjang waktu.
5. Spiritualitas
(spirituality/meaningfulness)
Spiritualitas memiliki peran yang penting dalam
resiliensi yaitu melalui kemampuan individu
untuk membangun kesimpulan atas kejadian yang
terjadi pada dirinya, juga mencakup kebutuhan
individu akan untuk perubahan, fleksibilitas dan
tumbuh.
Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Werner dan Smith (dalam
Reich, et.al. 2010), dengan longitudial study selama 40 tahun, menyimpulkan
bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi resilience outcome
yaitu:
(1) Karakteristik individual, seperti self-esteem dan purpose in life;
(2) Karakteristik keluarga, seperti kasih sayang ibu dan dukungan
keluarga; dan
(3) Lingkungan sosial yang lebih luas, khususnya yang mempunyai
Faktor-faktor umum diantara populasi seperti memiliki peran yang berarti
pada suatu komunitas, self-efficacy, self-esteem, hubungan yang aman, keamanan,
dan optimisme, berkonstribusi terhadap resiliensi (Kirby & Fraser, 1997 dalam
Reich, et.al. 2010)
Faktor-faktor lingkungan juga berkonstribusi bagi resiliensi, kualitas
pengasuhan dan keterbukaan keluarga (Bradley, Tellegen, Pellegrini, Larkin &
Larsen, Rutter), tugas sehari-hari dan kekokohan spiritualitas (Clark, Gordon),
meningkatkan kemungkinan resiliensi dalam konteks keadaan-keadaan yang
menantang (dalam Gordon, 1994).
Garmezy, Greef & Ritman, Rutter, dan Shinner (dalam Reich, et.al.,
2010), menjelaskan bahwa kepribadian resilient ditandai oleh sifat (trait) yang
merefleksikan suatu kekuatan, dapat dibedakan dengan baik, kepribadian yang
terintegrasi (self structed), dan sifat-sifat yang menunjukkan kekuatan dan
hubungan interpersonal timbal balik dengan orang lain. Kekuatan diri tersebut
dibuktikan oleh:
• Harga Diri (Self esteem)
• Kepercayaan Diri (Self-confidence/self efficacy)
• Pemahaman Diri (Self understanding)
• Orientasi Masa Depan yang Positif (A positive future orientation)
• Kemampuan untuk mengelola perilaku-perilaku dan emosi-emosi
1.1.4.Karakteristik Resiliensi
Karakteristik resiliensi diperlukan dalam rangka menjelaskan bagaimana
seseorang dapat dikatakan sebagai individu yang mempunyai resiliensi yang kuat
(resilient), termasuk juga individu yang mudah terserang atau tidak mampu
beradaptasi dengan baik dalam kondisi stres (vulnerability). Maka seseorang yang
disebut sebagai resilient adalah individu yang memiliki karakteristik-karakteristik
resiliensi.
Dalam hal ini Griffith (2004) mengajukan sebuah konsep yang disebut
sebagai “existential postures”, yaitu kesiapan (pikiran, tubuh dan jiwa) seseorang
dalam merespon adversitas atau stress. Konsep ini menguraikan perbedaan
karakteristik individu yang resilient dan vulnerability, sebagai berikut:
Tabel 2.2
Perbedaan Karakteristik Resilient dan Vulnerability
Resilient Vulnerability
Tidak berdaya (Helplessness)
Tidak bermakna(Meaninglessness)
Lalai (Indifference)
Takut (Cowardice)