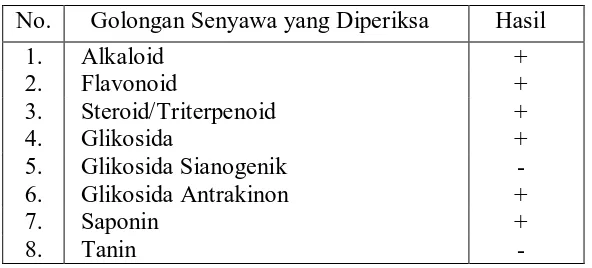BAHAN SKRIPSI
ISOLASI DAN KARAKTERISASI SENYAWA ALKALOID DARI UMBI BAWANG SABRANG (Eleutherinae bulbus)
OLEH :
DINA MARIANI PURBA NIM 060804061
FAKULTAS FARMASI
HALAMAN PENGESAHAN
ISOLASI DAN KARAKTERISASI SENYAWA ALKALOID DARI UMBI BAWANG SABRANG (Eleutherinae bulbus)
OLEH :
DINA MARIANI PURBA NIM 060804061
Medan, September 2010
Disetujui oleh : Disahkan oleh :
Pembimbing I, Dekan Fakultas Farmasi,
Prof. Dr. Siti Morin Sinaga, M.Sc., Apt Prof. Dr. Sumadio Hadisahputra, Apt NIP. 195008281976032002 NIP. 195311281983031002
Pembimbing II,
Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Alkaloid dari Umbi Bawang Sabrang (Eleutherinae bulbus)
Abstrak
Tumbuhan bawang sabrang (Eleutherine palmifolia (L.) Merr.) merupakan salah satu tumbuhan yang dapat digunakan untuk pengobatan sembelit, disuria, radang usus, disentri, luka, bisul, peluruh muntah, penyakit kuning, kanker payudara, diabetes melitus, hipertensi, menurunkan kolesterol, antimelanogenesis dan sebagai antioksidan. Salah satu kandungan kimia dari umbi bawang sabrang yaitu alkaloid. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengekstraksi dan mengisolasi senyawa alkaloid dari umbi bawang sabrang dan melakukan karakterisasi isolat dengan spektrofotometer ultraviolet (UV) dan inframerah (IR).
Serbuk simplisia dikarakterisasi dan diskrining fitokimia kemudian diekstraksi secara maserasi menggunakan pelarut etanol 80% yang dilanjutkan dengan prosedur pengocokan asam basa. Ekstrak alkaloid kasar dianalisa secara KLT dengan fase gerak kloroform-metanol-amonia, toluen-etilasetat, benzen-etilasetat dengan beberapa perbandingan, sebagai penampak bercak digunakan pereaksi Bouchardat. Selanjutnya dilakukan pemisahan dengan KLT preparatif menggunakan fase gerak toluen-etilasetat (9:1). Kemudian isolat dikarakterisasi dengan spektrofotometer UV dan IR.
Hasil makroskopik umbi bawang sabrang segar adalah berbentuk bulat telur memanjang, berwarna merah, tidak berbau serta berasa pahit. Umbi lapis terdiri dari 5-6 lapisan, dan panjang umbi 4-5 cm dan diameter 1-3 cm. Hasil mikroskopik serbuk simplisia umbi bawang sabrang dijumpai adanya kristal Ca-oksalat, parenkim, xylem dengan penebalan dinding sel berupa tangga (skalariform) dan butir amilum. Hasil penetapan kadar air diperoleh 8, 98%, kadar sari yang larut dalam air 8,03%, kadar sari yang larut dalam etanol 9,63%, kadar abu total 4,32%, kadar abu yang tidak larut dalam asam 0,84%. Hasil skrining fitokimia diperoleh senyawa golongan alkaloid, flavonoid, steroid/triterpenoid, glikosida, glikosida antrakinon, dan saponin. Hasil isolasi dari ekstrak alkaloid kasar diperoleh dua isolat murni yaitu isolat A (Rf 0,51) dan isolat B (Rf 0,57). Isolat A memberikan absorbansi maksimum pada panjang gelombang 270 nm, dan isolat B 271 nm. Hasil spektrofotometri inframerah menunjukkan adanya gugus C-H alifatis, CH2, C=O, C=C, C-N, C-O (isolat A) dan gugus C-H alifatis,
CH2, CH3, C=C, C-N dan C-O (isolat B).
Kata kunci : umbi bawang sabrang, alkaloid, skrining fitokimia, isolasi,
Isolation and Characterization Alkaloids Compound from Bawang Sabrang bulb (Eleutherinae bulbus)
Abstract
Bawang sabrang (Eleutherine palmifolia (L.) Merr.) is one plant that can be used for the treatment of constipation, dysuria, cancer, colitis, dysentery, wounds, ulcers, vomiting, jaundice, breast cancer, diabetes mellitus, hypertension, lower cholesterol, antimelanogenesis and as an antioxidant. One of the chemical constituents of bawang sabrang namely alkaloids. The purpose of this research is to extract and isolate the alkaloid compounds from bawang sabrang bulb and to do the characterization of isolate by ultraviolet (UV) and infrared (IR) spectrophotometer.
Simplex characterization and phytochemical screening were done to the simplex powder then the powder was extracted by maceration using ethanol 80%, and then the isolation of alkaloids from the ethanol by acid-base shuffle method. Crude alkaloid extract was analyzed by TLC with mobile phase chloroform-methanol-ammonia, toluene-ethyl acetate, benzene-ethylacetate with some comparisons, as the spray reagent used Bouchardat reagent. Next was separated by preparative TLC using mobile phase toluene-ethyl acetate (9:1). After that the isolate was characterized with ultraviolet and infrared spectrophotometer. The results of macroscopic examination of fresh bawang sabrang bulb is elongated oval-shaped, red in color, no smell and taste bitter. Bulb consists of 5-6 layers, and tubers 4-5 cm long and 1-3 cm in diameter. The results of microscopic of the simplex powder detected Ca-oxalate crystals, parenchyma, xylem with thickening cell walls of the stairs (skalariform) and amylum grains. The water content of the simplex powder is 8,98%, levels of water-soluble extract 8,03%, the concentration of ethanol-soluble extract 9,63%, total ash content 4,32% and the acid insoluble ash content is 0,84 %. The result of phytochemical screening showed the presence of alkaloids, flavonoids, steroids / triterpenoids, glycosides, anthraquinone glycosides, and saponins. The isolation of the crude alkaloid extract obtained two pure isolates, they are isolates A (Rf 0,51) and isolate B (Rf 0,57). Isolate A gives a maximum absorbance at 270 nm wavelength and isolate B at 271 nm. The results of infrared spectrophotometry showed the presence of aliphatic CH, CH2, C=O, C=C, C-N, C-O (isolate A) and aliphatic CH, CH2, CH3,
C=C, C-N, C-O (isolate B).
Keywords: Bawang sabrang bulb, alkaloids, phytochemical screening, isolation,
DAFTAR ISI
Halaman
JUDUL ... i
HALAMAN PENGESAHAN ... ii
ABSTRAK ... iii
ABSTRACT ... iv
DAFTAR ISI ... v
DAFTAR TABEL ... viii
DAFTAR LAMPIRAN ... ix
BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang ... 1
1.2 Perumusan masalah ... 2
1.3 Hipotesis ... 2
1.4 Tujuan ... 3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ... 4
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Alat-alat ... 18
3.2 Bahan-bahan ... 18
3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Tumbuhan 3.3.1 Pengumpulan Bahan Tumbuhan ... 18
3.3.2 Identifikasi Tumbuhan ... 19
3.3.3 Pengolahan Bahan Tumbuhan ... 19
3.5 Karakterisasi Simplisia ... 21
3.5.1 Pemeriksaan Makroskopik ... 21
3.5.2 Pemeriksaan Mikroskopik ... 21
3.5.3 Penetapan Kadar Air ... 21
3.5.4 Penetapan Kadar Sari yang Larut dalam Air ... 22
3.5.5 Penetapan Kadar Sari yang Larut dalam Etanol ... 22
3.5.6 Penetapan Kadar Abu ... 23
3.5.7 Penetapan Kadar Abu yang Tidak Larut dalam Asam.. 23
3.6 Skrining Fitokimia 3.6.1 Pemeriksaan Alkaloid ... 23
3.6.2 Pemeriksaan Flavonoid ... 24
3.6.3 Pemeriksaan Glikosida ... 25
3.6.4 Pemeriksaan Glikosida Antrakinon ... 25
3.6.5 Pemeriksaan Glikosida Sianogenik ... 26
3.6.6 Pemeriksaan Saponin ... 26
3.6.7 Pemeriksaan Steroid ... 26
3.6.8 Pemeriksaan Tanin ... 26
3.7 Pembuatan Ekstrak ... 27
3.8 Isolasi Senyawa Alkaloid dari Ekstrak Etanol dengan Metode Pengocokan Asam Basa ... 27
3.9 Analisis Ekstrak Alkaloid Kasar Secara KLT ... 28
3.10 Pembuatan Plat KLT ... 29
3.12 Pemurnian Kristal Hasil Preparatif ... 29
3.13 Uji Kemurnian Isolat Hasil Preparatif dengan KLT Satu Arah dan Dua Arah ... 30
3.14 Karakterisasi Isolat ... 31
3.14.1 Karakterisasi Isolat dengan Spektrofotometri Ultraviolet ... 31
3.14.2 Karakterisasi Isolat dengan Spektrofotometri Inframerah ... 31
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 32
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 38
5.1 Kesimpulan ... 38
5.2 Saran ... 38
DAFTAR PUSTAKA ... 39
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Hasil Karakterisasi Serbuk Simplisia Umbi Bawang Sabrang
(Eleutherinae bulbus) ... 33
Tabel 2. Hasil Skrining Fitokimia Serbuk Simplisia Umbi Bawang
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1. Hasil Identifikasi Tumbuhan ... 42
Lampiran 2. Gambar Tumbuhan dan Umbi Bawang Sabrang ... 43
Lampiran 3. Gambar simplisia umbi bawang sabrang ... 44
Lampiran 4. Gambar Mikroskopik Serbuk Simplisia ... 45
Lampiran 5. Perhitungan Kadar Air Serbuk Simplisia Umbi Bawang Sabrang ... 46
Lampiran 6. Perhitungan Kadar Sari Larut dalam Air ... 47
Lampiran 7. Perhitungan Kadar Sari Larut dalam Etanol ... 48
Lampiran 8. Perhitungan Kadar Abu Total ... 49
Lampiran 9. Perhitungan Kadar Abu Tidak Larut dalam Asam ... 50
Lampiran 10. Bagan Ekstraksi Serbuk Simplisia Umbi Bawang Sabrang .. 51
Lampiran 11. Bagan Isolasi Senyawa Alkaloid dari Ekstrak Etanol dengan Metode Pengocokan Asam Basa ... 52
Lampiran 12. Bagan Isolasi Senyawa Alkaloid dari Ekstrak Alkaloid Kasar ... 53
Lampiran 13. Kromatogram Hasil KLT Ekstrak Alkaloid Kasar Umbi Bawang Sabrang (Eleutherinae bulbus) ... 54
Lampiran 14. Kromatogram Hasil KLT Preparatif Ekstrak Alkaloid Kasar Umbi Bawang Sabrang (Eleutherinae bulbus) ... 57
Lampiran 15. Kromatogram Hasil KLT Satu Arah Isolat A ... 58
Lampiran 16. Kromatogram Hasil KLT Satu Arah Isolat B ... 59
Lampiran 18. Kromatogram Hasil KLT Dua Arah Isolat B ... 61
Lampiran 19. Gambar Spektrum Ultraviolet Isolat A ... 62
Lampiran 20. Gambar Spektrum Ultraviolet Isolat B ... 63
Lampiran 21. Gambar Spektrum Inframerah Isolat A ... 64
Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Alkaloid dari Umbi Bawang Sabrang (Eleutherinae bulbus)
Abstrak
Tumbuhan bawang sabrang (Eleutherine palmifolia (L.) Merr.) merupakan salah satu tumbuhan yang dapat digunakan untuk pengobatan sembelit, disuria, radang usus, disentri, luka, bisul, peluruh muntah, penyakit kuning, kanker payudara, diabetes melitus, hipertensi, menurunkan kolesterol, antimelanogenesis dan sebagai antioksidan. Salah satu kandungan kimia dari umbi bawang sabrang yaitu alkaloid. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengekstraksi dan mengisolasi senyawa alkaloid dari umbi bawang sabrang dan melakukan karakterisasi isolat dengan spektrofotometer ultraviolet (UV) dan inframerah (IR).
Serbuk simplisia dikarakterisasi dan diskrining fitokimia kemudian diekstraksi secara maserasi menggunakan pelarut etanol 80% yang dilanjutkan dengan prosedur pengocokan asam basa. Ekstrak alkaloid kasar dianalisa secara KLT dengan fase gerak kloroform-metanol-amonia, toluen-etilasetat, benzen-etilasetat dengan beberapa perbandingan, sebagai penampak bercak digunakan pereaksi Bouchardat. Selanjutnya dilakukan pemisahan dengan KLT preparatif menggunakan fase gerak toluen-etilasetat (9:1). Kemudian isolat dikarakterisasi dengan spektrofotometer UV dan IR.
Hasil makroskopik umbi bawang sabrang segar adalah berbentuk bulat telur memanjang, berwarna merah, tidak berbau serta berasa pahit. Umbi lapis terdiri dari 5-6 lapisan, dan panjang umbi 4-5 cm dan diameter 1-3 cm. Hasil mikroskopik serbuk simplisia umbi bawang sabrang dijumpai adanya kristal Ca-oksalat, parenkim, xylem dengan penebalan dinding sel berupa tangga (skalariform) dan butir amilum. Hasil penetapan kadar air diperoleh 8, 98%, kadar sari yang larut dalam air 8,03%, kadar sari yang larut dalam etanol 9,63%, kadar abu total 4,32%, kadar abu yang tidak larut dalam asam 0,84%. Hasil skrining fitokimia diperoleh senyawa golongan alkaloid, flavonoid, steroid/triterpenoid, glikosida, glikosida antrakinon, dan saponin. Hasil isolasi dari ekstrak alkaloid kasar diperoleh dua isolat murni yaitu isolat A (Rf 0,51) dan isolat B (Rf 0,57). Isolat A memberikan absorbansi maksimum pada panjang gelombang 270 nm, dan isolat B 271 nm. Hasil spektrofotometri inframerah menunjukkan adanya gugus C-H alifatis, CH2, C=O, C=C, C-N, C-O (isolat A) dan gugus C-H alifatis,
CH2, CH3, C=C, C-N dan C-O (isolat B).
Kata kunci : umbi bawang sabrang, alkaloid, skrining fitokimia, isolasi,
Isolation and Characterization Alkaloids Compound from Bawang Sabrang bulb (Eleutherinae bulbus)
Abstract
Bawang sabrang (Eleutherine palmifolia (L.) Merr.) is one plant that can be used for the treatment of constipation, dysuria, cancer, colitis, dysentery, wounds, ulcers, vomiting, jaundice, breast cancer, diabetes mellitus, hypertension, lower cholesterol, antimelanogenesis and as an antioxidant. One of the chemical constituents of bawang sabrang namely alkaloids. The purpose of this research is to extract and isolate the alkaloid compounds from bawang sabrang bulb and to do the characterization of isolate by ultraviolet (UV) and infrared (IR) spectrophotometer.
Simplex characterization and phytochemical screening were done to the simplex powder then the powder was extracted by maceration using ethanol 80%, and then the isolation of alkaloids from the ethanol by acid-base shuffle method. Crude alkaloid extract was analyzed by TLC with mobile phase chloroform-methanol-ammonia, toluene-ethyl acetate, benzene-ethylacetate with some comparisons, as the spray reagent used Bouchardat reagent. Next was separated by preparative TLC using mobile phase toluene-ethyl acetate (9:1). After that the isolate was characterized with ultraviolet and infrared spectrophotometer. The results of macroscopic examination of fresh bawang sabrang bulb is elongated oval-shaped, red in color, no smell and taste bitter. Bulb consists of 5-6 layers, and tubers 4-5 cm long and 1-3 cm in diameter. The results of microscopic of the simplex powder detected Ca-oxalate crystals, parenchyma, xylem with thickening cell walls of the stairs (skalariform) and amylum grains. The water content of the simplex powder is 8,98%, levels of water-soluble extract 8,03%, the concentration of ethanol-soluble extract 9,63%, total ash content 4,32% and the acid insoluble ash content is 0,84 %. The result of phytochemical screening showed the presence of alkaloids, flavonoids, steroids / triterpenoids, glycosides, anthraquinone glycosides, and saponins. The isolation of the crude alkaloid extract obtained two pure isolates, they are isolates A (Rf 0,51) and isolate B (Rf 0,57). Isolate A gives a maximum absorbance at 270 nm wavelength and isolate B at 271 nm. The results of infrared spectrophotometry showed the presence of aliphatic CH, CH2, C=O, C=C, C-N, C-O (isolate A) and aliphatic CH, CH2, CH3,
C=C, C-N, C-O (isolate B).
Keywords: Bawang sabrang bulb, alkaloids, phytochemical screening, isolation,
BAB I PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat merupakan warisan nenek moyang
sejak dahulu kala dan telah digunakan dalam kurun waktu cukup lama hampir
seluruh negara di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil
tanaman obat yang potensial dengan keanekaragaman hayati yang dimilikinya.
Upaya pencarian tumbuhan berkhasiat obat telah lama dilakukan, baik untuk
mencari senyawa baru ataupun menambah keanekaragaman senyawa yang telah
ada. Pencarian tersebut dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti cara
empiris, etnobotani, dan etnofarmakologi. Selanjutnya dilakukan upaya untuk
pengisolasian senyawa murni dan turunannya sebagai bahan dasar obat modern
atau pembuatan ekstrak untuk obat fitofarmaka (Hernani dan Djauhariya, 2004).
Salah satu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat yaitu bawang
sabrang (Eleutherine palmifolia (L.) Merr.), termasuk tumbuhan terna, dengan
tinggi 25-50 cm, bunga putih, umbi lapisnya berwarna merah (Ogata, 1995).
Tumbuhan bawang sabrang ini mengandung senyawa kimia aktif berupa alkaloid,
flavonoid, steroid, glikosida dan fenolik (Galingging, 2007). Umbi tumbuhan ini
dapat digunakan untuk pengobatan sembelit, disuria, radang usus, disentri, luka,
bisul, peluruh muntah, penyakit kuning (Ogata, 1995; Heyne, 1987), kanker
payudara, diabetes melitus, hipertensi, menurunkan kolesterol (Galingging, 2009),
Senyawa alkaloid banyak mempunyai kegiatan fisiologi yang menonjol
sehingga digunakan secara luas dalam bidang pengobatan (Harbone, 1987).
Senyawa aktif ini dapat berperan sebagai analgesik, sedatif, bioinsektisida,
stimulan pada syaraf otonom, obat malaria, obat kanker (Putra, 2007; Tjay 2002),
antiinflamasi, antidiabetes dan diuretik (Dineshkumar, 2010).
Berdasarkan hal di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti salah satu
kandungan kimia umbi bawang sabrang yaitu senyawa alkaloid dan melakukan
karakterisasi simplisia untuk mengetahui apakah simplisia yang digunakan
memenuhi syarat sesuai dengan Materia Medika Indonesia.Melakukan skrining
fitokimia dan mengekstraksi senyawa alkaloid dari umbi tumbuhan bawang
sabrang menggunakan metode pengocokan asam basa dan isolasi dengan bantuan
kromatografi lapis tipis (KLT) dan KLT preparatif serta melakukan karakterisasi
isolat hasil isolasi secara spektrofotometri ultraviolet dan spektrofotometri
inframerah.
1.2 Perumusan Masalah
1. Apakah senyawa alkaloid yang terdapat pada umbi bawang sabrang
(Eleutherinae bulbus) dapat diisolasi dengan KLT dan KLT preparatif
menggunakan campuran pelarut yang sesuai?
2. Apakah senyawa alkaloid hasil isolasi dapat dikarakterisasi secara
spektrofotometri ultraviolet dan spektrofotometri inframerah?
1.3Hipotesis
1. Senyawa alkaloid yang terdapat pada umbi bawang sabrang (Eleutherinae
bulbus) dapat diisolasi dengan KLT dan KLT preparatif menggunakan
2. Senyawa alkaloid hasil isolasi dapat dikarakterisasi secara spektrofotometri
ultraviolet dan spektrofotometri inframerah.
1.4Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah untuk :
1. Mengisolasi senyawa alkaloid dari umbi bawang sabrang (Eleutherinae
bulbus)
2. Melakukan karakterisasi senyawa alkaloid hasil isolasi dari umbi bawang
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Uraian Tumbuhan 2.1.1 Habitat
Tumbuhan bawang sabrang merupakan tumbuhan yang berasal dari
Amerika tropis, di Jawa dipelihara sebagai tanaman hias dan di beberapa tempat
tumbuh jalang antara 600 dan 1500 m di atas permukaan laut; kadang-kadang
didapati dalam jumlah besar di pingg ir-pinggir jalan yang berumput dan di dalam
kebun-kebun teh, kina dan karet (Heyne, 1987).
2.1.2 Morfologi luar
Tumbuhan ini merupakan tumbuhan terna yang merumpun sangat kuat,
akhirnya merupakan rumpun-rumpun besar, tinggi 26 hingga 50 cm. Umbinya
berbentuk bulat telur memanjang dan berwarna merah (Heyne, 1987). Daun
tunggal, letak daun berhadapan, warna daun hijau muda, bentuk daun sangat
panjang, dan meruncing (acicular), tepi daun halus tanpa gerigi (entire), pangkal
daun berbentuk runcing (acute) dan ujung daun meruncing (acuminate)
permukaan daun atas dan bawah halus (glabrous) tulang daun paralel/sejajar
(Krismawati dan M. Sabran, 2006).
2.1.3 Sistematika Tumbuhan
Sistematika dari tumbuhan bawang sabrang adalah sebagai berikut:
Kingdom: Plantae
Super Divisi: Spermatophyta
Ordo: Liliales
Famili: Iridaceae
Genus: Eleutherine
Spesies: Eleutherine palmifolia (L.) Merr. (Anonim, 2010).
2.1.4 Nama Daerah
Nama daerah dari tumbuhan bawang sabrang adalah sebagai berikut:
bawang kapal (Sumatera); brambang sabrang, luluwan sapi, teki sabrang,
bebawangan beureum, bawang siem (Jawa) ( Ditjen POM, 1985).
2.1.5 Sinonim
Sinonim dari tumbuhan bawang sabrang : Sisyrinchium palmifolium L.
(Anonim, 2010).
2.1.6 Kandungan Kimia dan Khasiat
Bawang sabrang mengandung senyawa-senyawa yang meliputi alkaloid,
steroid, glikosida, tanin, fenolik, dan flavonoid (Galingging, 2007). Tumbuhan ini
dapat digunakan untuk pengobatan sembelit, disuria, peradangan poros usus,
disentri, penawar racun ikan, luka, bisul, peluruh muntah dan penyakit kuning
(Ogata, 1995; Heyne, 1987).
2.2 Alkaloida
Alkaloid, sekitar 5500 telah diketahui, merupakan golongan zat tumbuhan
sekunder yang terbesar. Banyak sekali alkaloid yang khas pada suatu suku
tumbuhan atau beberapa tumbuhan sekerabat. Jadi, nama alkaloid sering kali
diturunkan dari sumber tumbuhan penghasilnya. Uji sederhana, tetapi yang sama
sekali tidak sempurna untuk alkaloid dalam daun atau buah segar adalah rasa
sebenarnya biosintesis kebanyakan alkaloid lebih rumit. Secara kimia, alkaloid
merupakan suatu golongan heterogen. Alkaloid banyak yang mempunyai kegiatan
fisiologi yang menonjol, jadi digunakan secara luas dalam bidang pengobatan
(Harbone, 1987).
2.2.1 Defenisi
Alkaloida adalah senyawa kimia yang secara khas diperoleh dari
tumbuhan dan hewan, bersifat basa, mengandung satu atau lebih atom nitrogen
(biasanya dalam cincin heterosiklik), dibiosintesis dari asam amino, banyak
diantaranya memiliki aktivitas biologis pada manusia dan hewan (Trease dan
Evans, 1983). Alkaloid merupakan senyawa yang berpengaruh terhadap susunan
syaraf pusat, mempunyai atom nitrogen heterosiklis dan disintesis oleh tumbuhan
dari asam amino atau turunannya (Waller dan Nowacki, 1978).
2.2.2 Sifat
Alkaloid sebagai golongan dibedakan dari sebagian besar komponen
tumbuhan lain berdasarkan sifat basanya (kation). Oleh karena itu senyawa ini
biasanya terdapat dalam tumbuhan sebagai garam berbagai asam organik dan
sering ditangani di laboratorium sebagai garam dengan asam hidroklorida dan
asam sulfat. Garam ini, dan sering alkaloid bebas, berupa senyawa padat
berbentuk kristal tanwarna. Beberapa alkaloid berupa cairan, dan alkaloid yang
berwarna pun langka (berberina dan serpentina berwarna kuning) (Robinson,
1995).
2.2.3 Klasifikasi
Alkaloid dibagi menjadi dua golongan berdasarkan letak atom nitrogennya
A. Non heterosiklis disebut juga protoalkaloida. Contohnya efedrin yang terdapat
pada tumbuhan Ephedra sinica.
B. Heterosiklis, dibagi dalam 12 golongan berdasarkan struktur cincinnya yaitu :
1. Alkaloid golongan pirol dan pirolidin, yaitu alkaloid yang mengandung inti
pirol dan pirolidin dalam struktur kimianya. Contohnya higrin pada tumbuhan
Erythtroxylon coca.
2. Alkaloid golongan pirolizidin, yaitu alkaloid yang mengandung inti pirolizidin
dalam struktur kimianya. Contoh retronesin pada tumbuhan Senecio jacobaea.
3. Alkaloid golongan piridin dan piperidin, yaitu alkaloid yang mengandung inti
piridin dan piperidin dalam struktur kimianya. Contohnya nikotin pada
tumbuhan Nicotiana tabaccum yang mempunyai inti piridin.
4. Alkaloid golongan tropan, yaitu alkaloid yang mengandung inti tropan dalam
struktur kimianya. Contohnya atropin pada tumbuhan Atropa belladonna.
5. Alkaloid golongan kuinolin, yaitu alkaloid yang mengandung inti kuinolian
dalam struktur kimianya. Contohnya kuinin pada tumbuhan Cinchona
officinalis.
6. Alkaloid golongan isokuinolin, yaitu alkaloid yang mengandung inti
isokuinolin dalam struktrur kimianya. Contohnya papaverin pada tumbuhan
Papaver somniferum.
7. Alkaloid golongan aporfin, yaitu alkaloid yang mengandung inti aporfin
dalam struktrur kimianya. Contohnya boldin pada tumbuhan Peumus boldus.
8. Alkaloid golongan norlupinan, yaitu alkaloid yang mengandung inti
norlupinan dalam struktrur kimianya. Contohnya sitisin pada tumbuhan
9. Alkaloid golongan indo l atau benzopirol, yaitu alkaloid yang mengandung inti
indol dalam struktrur kimianya. Contohnya psilosin pada tumbuhan Psilocybe
sp.
10.Alkaloid golongan imidazol atau glioksalin, yaitu alkaloid yang mengandung
inti imidazol dalam struktrur kimianya. Contohnya pilokarpin pada tumbuhan
Pilocarpus jaborandi.
11.Alkaloid golongan purin, yaitu alkaloid yang mengandung inti purin dalam
struktrur kimianya. Contohnya kafein pada tumbuhan Coffea arabica.
12.Alkaloid steroida, yaitu alkaloid yang mengandung inti steroida (siklopentano
perhidrofenantren) dalam struktrur kimianya. Contohnya solanidin pada
tumbuhan Lycopersicon esculentum.
Menurut Hegnauer, alkaloid dikelompokkan sebagai:
(a). Alkaloid sesungguhnya
Alkaloid sesungguhnya adalah racun, senyawa tersebut menunjukkan
aktivitas phisiologi yang luas, hampir tanapa terkecuali bersifat basa; lazim
mengandung nitrogen dalam cincin heterosiklis; diturunkan dari asam amino;
biasanya terdapat dalam tanaman sebagai garam asam organik. Beberapa
perkecualian terhadap aturan tersebut adalah kolkhisin dan asam aristolokhat yabg
bersifat bukan basa dan tidak memiliki cincin heterosiklis dan alkaloid kuartener,
yang bersifat agak asam daripada basa.
(b). Protoalkaloid
Protoalkaloid merupakan amin yang relatif sederhana dimana nitrogen
berdasarkan biosintesis dari asam amino yang bersifat basa. Contoh, adalah
meskalin, ephedin, dan N,N-dimetiltriptamin.
(c). Pseudoalkaloid
Pseudoalkaloid tidak diturunkan dari precursor asam amino. Senyawa
biasanya bersifat basa. Ada dua seri alkaloid yang penting dalam klas ini, yaitu
alkaloid steroidal (contoh konessin) dan purin (contoh kaffein) (Sastrohamidjojo,
1996).
2.3 Ekstraksi
Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut
sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair (Ditjen
POM, 2000). Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya
dengan menggunakan pelarut. Jadi, ekstrak adalah sediaan yang diperoleh dengan
cara ekstrasi tanaman obat dengan ukuran partikel tertentu dan menggunakan
medium pengekstraksi yang tertentu pula (Goeswin, 2007).
Metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut :
- Maserasi
Maserasi adalah proses pengekstraksian simplisia dengan menggunakan
pelarut dengan dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada
temperatur ruangan (kamar). Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk
simplisia dalam cairan penyari yang akan menembus dinding sel dan masuk ke
dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena
adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif yang ada di dalam dengan di
luar sel maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang
Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan
penyaringan maserat pertama, dan seterusnya (Ditjen POM, 1986).
- Perkolasi
Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai
sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Proses terdiri dari
tahapan pengembangan bahan, tahap perkolasi sebenarnya(penetesan/
penampungan ekstrak), terus-menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang
jumlahnya 1-5 kali bahan.
- Refluks
Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya,
selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan
adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu
pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna.
- Soklet
Soklet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang
umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan
jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik.
- Digesti
Digesti adalah cara maserasi dengan menggunakan pemanasan lemah,
yaitu pada suhu 40º-50º C. Cara ini hanya dapat dilakukan untuk simplisia yang
zat aktifnya tahan terhadap pemanasan. Daya melarutkan cairan penyari akan
meningkat sehingga pemanasan tersebut mempunyai pengaruh yang sama dengan
- Infus
Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air
(bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 96-98ºC)
selama waktu tertentu (15-20 menit) (Ditjen POM, 2000).
- Dekok
Dekok adalah penyarian menggunakan simplisia dengan perbandingan dan
derajat kehalusan tertentu. Cairan penyari air digunakan pada suhu 90-95ºC
selama 30 menit (Goeswin, A., 2007).
2.4 Kromatografi
Kromatografi merupakan suatu metode pemisahan berdasarkan
perbedaan migrasi dari komponen-komponen senyawa diantara dua fase yaitu fase
diam dan fase gerak (Depkes, 1995). Cara-cara kromatografi dapat digolongkan
sesuai dengan sifat-sifat dari fase diam, yang dapat berupa zat padat atau zat cair,
Jika fase diam berupa zat padat maka cara tersebut dikenal sebagai kromatografi
serapan (adsorpsi), jika zat cair dikenal sebagai kromatografi partisi (pembagian).
Saat ini kromatografi merupakan teknik pemisahan yang paling umum dan paling
sering digunakan, baik untuk analisis kualitatif, kuantitatif atau preparatif dalam
bidang farmasi, industri dan sebagainya (Rohman, 2007).
2.4.1 Kromatografi Lapis Tipis
Kromatografi lapis tipis termasuk kromatografi adsorpsi, dimana sebagai
fase diam digunakan zat padat yang disebut adsorben (penyerap) dan fase gerak
adalah zat cair yang disebut sebagai larutan pengembang (Gritter dkk., 1991).
Kromatografi lapis tipis merupakan jenis kromatografi dimana fase diamnya
didukung oleh lempeng kaca, pelat aluminium, atau pelat plastik (Rohman,
2007). Bila KLT dibandingkan denngan KKt, kelebihan khas KLT ialah
keserbagunaan, kecepatan dan kepekaannya (Harbone, 1987).
Pada kromatografi lapis tipis , sifat yang penting dari penyerap adalah
besar partikel dan homogenitasnya karena adhesi terhadap penyokong sangat
tergantung pada dua sifat tersebut. Besar partikel yang biasa digunakan adalah
1-21 mikron. Partikel yang butirannya sangat kasar tidak akan memberikan hasil
yang memuaskan dan salah satu alasan untuk menaikkan hasil pemisahn adalah
menggunakan penyerap yang butirannya halus. Beberapa contoh penyerap yang
digunakan untuk pemisahan-pemisahan dalam kromatografi lapis tipis antara lain
silika gel, alumina, kieselguhr, bubuk selulose dan pati (Sastrohamidjojo, 1985).
Fase gerak ialah medium angkut yang terdiri atas satu atau beberapa
pelarut dan bergerak di dalam fase diam karena ada gaya kapiler. Bila diperlukan
sistem pelarut multi komponen, harus berupa suatu campuran sesederhana
mungkin yang terdiri atas maksimum tiga komponen (Stahl, 1985). Sistem pelarut
untuk KLT dapat dipilih dari pustaka, tetapi lebih sering dengan mencoba-coba
karena waktu yang diperlukan hanya sebentar (Gritter, 1991). Pemilihan sistem
pelarut yang dipakai didasarkan atas prinsip like dissolves like, artinya untuk
memisahkan sampel yang bersifat nonpolar digunakan sistem pelarut yang
bersifat nonpolar juga (Adnan, 1997).
Jarak pengembangan senyawa pada kromatogram biasanya dinyatakan
Angka Rf berjangka antara 0,00 dan 1,00 dan hanya dapat ditentukan dua
desimal. Angka hRf ialah Rf dikalikan faktor 10 (h), menghasilkan nilai berjangka
0 sampai 100 (Stahl, 1985).
Faktor-faktor yang mempengaruhi harga Rf pada KLT, antara lain:
a. Struktur kimia dari senyawa yang dipisahkan.
b. Sifat dari penyerap dan derajat aktivitasnya.
c. Tebal dan kerataan lapisan penyerap.
d. Derajat kemurnian fase gerak.
e. Derajat kejenuhan uap pengembang dalam bejana.
f. Jumlah cuplikan.
g. Suhu (Sastrohamidjojo, 1991).
2.4.2 KLT Preparatif
Salah satu metode pemisahan senyawa bahan alam yang memakai peralatan
yang paling dasar ialah kromatografi lapis tipis preparatif. KLT preparatif dapat
memisahkan bahan alam dalam jumlah gram, sebagian besar pemakaian hanya
dalam jumlah milligram. Ukuran pelat yang biasa digunakan yaitu 20 x 20 cm
atau 20x 40 cm. Penjerap yang paling umum ialah silika gel dan dipakai untuk
pemisahan senyawa lipofil maupun campuran senyawa hidrofil. Cuplikan sampel
dilarutkan dalam sedikit pelarut sebelum ditotolkan pada pelat KLTP dimana
konsentrasinya sekitar 5-10%. Penotolan dapat dilakukan dengan tangan (pipet)
ataupun dengan penotol otomatis.
Pilihan pelarut ditentukan berdasarkan pemeriksaan pendahuluan memakai
KLT analitik. Karena ukuran partikel penjerap kira-kira sama, pelarut yang
penjerap KLTP mengandung indicator fluoresensi yang membantu mendeteksi
kedudukan pita yang terpisah sepanjang senyawa yang dipisahkan menyerap sinar
UV. Untuk senyawa yang tidak menyerap sinar UV, ada beberapa pilihan :
a. Menyemprot dengan air (misalnya saponin)
b. Menutup pelat dengan sepotong kaca kemudian menyemprot salah satu sisi
dengan pereaksi semprot
c. Menambahkan senyawa pembanding (Hostettmann, 1995).
2.5 Spektroskopi
2.5.1 Spektrofotometri Ultra Violet
Spektrofotometer UV pada umumnya digunakan untuk:
1. Menentukan jenis kromofor, ikatan rangkap yang terkonjugasi dan
auksokrom dari suatu senyawa organik.
2. Menjelaskan informasi dari struktur berdasarkan panjang gelombang
maksimum suatu senyawa.
3. Mampu menganalisis senyawa organic secara kuantitatif dengan
menggunakan hokum Lambert-Beer (Dachriyanus, 2004).
Sinar ultraviolet memberikan energi yang cukup untuk terjadinya transisi
elektronik sehingga disebut sebagai spektra elektronik. Keadaan energi yang
paling rendah disebut dengan keadaan dasar (ground state). Apabila suatu
molekul menyerap radiasi ultraviolet, di dalam molekul tersebut terjadi
perpindahan tingkat energi elektron-elektron ikatan di orbital molekul paling luar
dari tingkat energi yang lebih rendah ke yang lebih tinggi (Noerdin, 1986).
Istilah-istilah yang sering digunakan di dalam membicarakan spektra
Kromofor : Suatu gugus kovalen tidak jenuh yang bertanggung jawab untuk
serapan elektronik.
Auksokrom : Suatu gugus jenuh dengan elektron tidak terikat dimana bila
menempel kepada suatu kromofor dapat mengubah panjang gelombang dan
intensitas serapan.
Pergeseran batokromik : Pergeseran serapan ke panjang gelombang yang lebih
panjang karena sisipan atau pengaruh pelarut (geseran merah).
Pergeseran hipsokromik : Pergeseran serapan ke panjang gelombang yang lebih
pendek disebabkan substitusi atau pengaruh pelarut (geseran biru).
Efek hiperkromik : Kenaikan dalam intensitas serapan.
Efek hipokromik : Penurunan dalam intensitas serapan (Silverstein, 1986).
2.5.2 Spektrometri Infra Merah
Spektra inframerah mengandung banyak serapan yang dihubungkan
dengan sistem vibrasi yang berinteraksi dalam molekul, dan karena mempunyai
karakteristik yang unik untuk setiap molekul maka dalam spektrum memberikan
pita-pita serapan yang karakteristik juga (Sastrohamidjojo, 1985).
Spektrofotometer inframerah pada umumnya digunakan untuk:
1. Menentukan gugus fungsi suatu senyawa organik
2. Mengetahui informasi struktur suatu senyawa organik dengan
membandingkan daerah sidik jarinya.
Pengukuran pada spektrum inframerah dilakukan pada daerah cahaya inframerah
tengah (mid-infrared) yaitu pada panjang gelombang 2,5-50 µm atau bilangan
gelombang 4000-200 cmˉ 1. Energi yang dihasilkan oleh radiasi ini akan
khas dan spesifik untuk setiap tipe ikatan kimia atau gugus fungsi. Metoda ini
sangat berguna untuk mengidentifikasi senyawa organik dan organometalik.
Jika suatu frekuensi tertentu dari radiasi inframerah dilewatkan pada sampel suatu
senyawa organik maka akan terjadi penyerapan frekuensi oleh senyawa tersebut.
Detektor yang ditempatkan pada sisi lain dar senyawa akan mendeteksi frekuensi
yang dilewatkan pada sampel yang tidak diserap oleh senyawa. Banyaknya
frekkuensi yang melewati senyawa (yang tidak diserap) akan diukur sebagai
persen transmitan (Dachriyanus, 2004).
Adapun langkah-langkah umum untuk memeriksa pita serapan
adalah sebagai berikut (Pavia, 1988):
1. Apakah terdapat gugus karbonil? Gugus C=O memberikan puncak pada
daerah 1820-1660 cm-1. Puncak ini biasanya merupakan yang terkuat dengan
lebar medium pada spektrum.
2. Jika gugus C=O ada, periksalah gugus-gugus berikut (jika tidak ada, langsung
ke nomor 3).
Asam : Apakah ada gugus O-H? Serapan lebar di daerah 3300-2500 cm-1.
(biasanya tumpang tindih dengan C-H).
Amida : Apakah ada N-H? Serapan medium di dekat 3500 cm-1, kadang-
kadang muncul dengan puncak rangkap.
Ester : Apakah ada C-O? Serapan medium di daerah 1300-1000 cm-1.
Anhidrida: Mempunyai dua serapan C=O di daerah 1810 dan 1760 cm-1.
Aldehida : Apakah ada C-H dari aldehid? Dua serapan lemah di daerah 2850-
2750 cm-1 yaitu di sebelah kanan serapan C-H.
3. Bila gugus C=O tidak ada.
Alkohol/fenol: Periksa gugus O-H, serapan lebar di daerah 3600-3300 cm-1
yang diperkuat adanya serapan C-O di daerah 1300-1000 cm-1.
Amina : Periksa gugus N-H,yaitu serapan medium di daerah 3500 cm-1
Eter : Periksa gugus C-O (serapan O-H tidak ada), yaitu dekat
1300-1000 cm-1.
4. Ikatan rangkap dua dan/atau cincin aromatik.
- C=C mempunyai serapan lemah di daerah 1650 cm-1.
- Serapan medium sampai kuat pada daerah 1650-1450 cm-1 sering
menunjukkan adanya cincin aromatik.
- Buktikan kemungkinan di atas dengan memperhatikan serapan pada
daerah C-H aromatik di sebelah kiri 3000 cm-1, sedangkan C-H alifatis
terjadi di sebelah kanan daerah tersebut.
5. Ikatan rangkap tiga.
- C≡N mempunyai serapan medium dan tajam di daerah 2250 cm-1.
- C≡C mempunyai serapan lemah tapi tajam di daerah 2150 cm-1. Periksa
juga CH asetilenik di dekat 3300 cm-1.
6. Gugus nitro.
Dua serapan kuat di daerah 1600-1500 cm-1 dan 1390-1300 cm-1.
7. Hidrokarbon.
- Apabila keenam kemungkinan di atas tidak ada.
- Serapan utama di daerah CH dekat 3000 cm-1.
- Spektrum sangat sederhana, hanya terdapat serapan lain di daerah 1450
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1Alat-alat
Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat
gelas laboratorium, blender (National), eksikator, hairdryer (Fransen), krus
porselin, lampu UV 366 nm (Diamond), mikroskop (Olympus), neraca listrik
(Vibra AJ), neraca kasar, oven (Memmert), penangas air (Yenaco), penguap
vakum putar (Haake D1 Fisons), seperangkat alat KLT, seperangkat alat
penentuan kadar air, spektrofotometer inframerah (IRPrestige21 Shimadzu),
spektrofotometer ultraviolet (UV1800 Shimadzu) dan tanur.
3.2 Bahan-bahan
Bahan tumbuhan yang digunakan pada penelitian ini adalah umbi bawang
sabrang (Eleutherinae bulbus). Bahan kimia yang digunakan kecuali dinyatakan
lain berkualitas proanalisis, yaitu amonium hidroksida, asam asetat anhidrid, asam
klorida, asam sulfat, benzen, bismut (III) nitrat, etanol, eter, eter minyak tanah,
etilasetat, besi (III) klorida, iodium, isopropanol, kalium iodida, kloralhidrat,
kloroform, metanol, n-heksan, natrium hidroksida, natrium sulfat anhidrat, raksa
(II) klorida, serbuk Mg, serbuk Zn, timbal (II) asetat, toluen, α-naftol. Plat
pralapis silika gel GF254, silika gel GF254 dan air suling.
3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Tumbuhan 3.3.1 Pengumpulan Bahan Tumbuhan
Bahan tumbuhan yang digunakan dalam penelitian ini adalah umbi
Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Medan, Sumatera
Utara. Bagian tumbuhan yang digunakan adalah umbi segar yang berwarna
merah. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif tanpa membandingkan
dengan tumbuhan serupa dari daerah lain.
3.3.2 Identifikasi Tumbuhan
Identifikasi tumbuhan dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengembangan
Biologi, LIPI, Bogor.
3.3.3 Pengolahan Bahan Tumbuhan
Umbi dari bawang sabrang yang baru diambil dibersihkan dari kotoran,
dicuci dengan air bersih, ditiriskan di atas kertas perkamen, dirajang, lalu
ditimbang berat basahnya. Kemudian dikeringkan di lemari pengering hingga
kering dan rapuh, lalu ditimbang berat keringnya. Selanjutnya simplisia kering
diserbuk dengan blender dan disimpan dalam wadah yang kering.
3.4 Pembuatan Pereaksi
3.4.1 Pereaksi Asam Klorida 2 N
Sebanyak 17 ml asam klorida pekat diencerkan dengan air suling hingga
100 ml (Depkes, 1979).
3.4.2 Pereaksi Natrium Hidroksida 2 N
Sebanyak 8,002 g natrium hidroksida dilarutkan dalam air suling bebas
karbon dioksida hingga 100 ml (Depkes, 1979).
3.4.3 Pereaksi Bouchardat
Sebanyak 2 g iodium dan 4 kalium iodida dilarutkan dalam air suling
3.4.4 Pereaksi Mayer
Sebanyak 1,569 g raksa (II) klorida dilarutkan dalam air suling hingga 60
ml. Pada wadah lain dilarutkan 5 g kalium iodida dalam 10 ml air suling.
Kemudian keduanya dicampurkan dan ditambahkan air suling hingga diperoleh
larutan 100 ml ( Depkes,1989).
3.4.5 Pereaksi Dragendorff
Sebanyak 0,85 g bismut (III) nitrat dilarutkan dalam 100 ml asam asetat
glasial, lalu tambahkan 40 ml air suling. Pada wadah lain dilarutkan dalam 8 g
kalium iodida dalam 20 ml air suling, kemudian campurkan kedua larutan sama
banyak, lalu ditambahkan 20 ml asam asetat glasial dan diencerkan dengan air
suling hingga volume 100 ml (Zweig, 1987).
3.4.6 Pereaksi Besi (III) Klorida 1%
Sebanyak 1 g besi (III) klorida dilarutkan dalam air suling hingga 100 ml
(Depkes RI,1989).
3.4.7 Pereaksi Liebermann-Burchard
Sebanyak 20 bagian asam asetat anhidrid dicampurkan dengan 1 bagian
asam sulfat pekat (Harborne, 1987).
3.4.8 Pereaksi Molish
Sebanyak 3 g α-naftol dilarutkan dalam asam nitrat 0,5 N secukupnya
hingga diperoleh 100 ml larutan (Depkes, 1979).
3.4.9 Pereaksi Kloralhidrat
Sebanyak 50 g kloralhidrat ditimbang dan dilarutkan dalam 20 ml air
3.4.10 Pereaksi Timbal (II) Asetat 0,4 N
Sebanyak 15,17 g timbal (II) asetat dilarutkan dalam air suling bebas
karbon dioksida secukupnya hingga 100 ml (Depkes, 1989).
3.5 Karakterisasi Simplisia
Pemeriksaan karakteristik simplisia dilakukan menurut World Health
Organization (1992) (penetapan kadar air) dan Depkes (1989) (pemeriksaan
makroskopik, mikroskopik, penetapan kadar sari yang larut dalam air, penetapan
kadar sari yang larut dalam etanol, penetapan kadar abu total, penetapan kadar abu
yang tidak larut dalam asam).
3.5.1 Pemeriksaan Makroskopik
Pemeriksaan makroskopik dilakukan dengan mengamati bentuk luar dari
umbi bawang sabrang.
3.5.2 Pemeriksaan Mikroskopik
Pemeriksaan mikroskopik dilakukan terhadap serbuk simplisia umbi
bawang sabrang. Serbuk simplisia diletakkan pada kaca objek yang telah ditetesi
larutan kloralhidrat kemudian ditutup dengan kaca penutup, dipanaskan dan
diamati di bawah mikroskop. Untuk melihat pati, serbuk simplisia ditaburkan
pada kaca objek yang telah ditetesi air suling kemudian ditutup dengan kaca
penutup dan diamati di bawah mikroskop.
3.5.3 Penetapan Kadar Air
Penetapan kadar air dilakukan dengan metode Azeotropi (destilasi toluen).
Cara kerja :
Ke dalam labu alas bulat dimasukkan 200 ml toluena dan 2 ml air suling,
dan volume air pada tabung penerima dibaca. Kemudian ke dalam labu
dimasukkan 5 g serbuk simplisia yang telah ditimbang seksama, lalu dipanaskan
hati-hati selama 15 menit. Setelah toluen mendidih, kecepatan tetesan diatur 2
tetes per detik, sampai sebagian air terdestilasi. Kemudian kecepatan destilasi
dinaikkan hingga 4 tetes per detik. Setelah semua air terdestilasi, bagian dalam
pendingin dibilas dengan toluen. Destilasi dilanjutkan selama 5 menit, kemudian
tabung penerima dibiarkan dingin sampai suhu kamar. Setelah air dan toluen
memisah sempurna, volume air dibaca dengan ketelitian 0,05 ml. Selisih kedua
volume air dibaca dengan kandungan air yang terdapat dalam bahan yang
diperiksa. Kadar air dihitung dalam persen.
3.5.4 Penetapan Kadar Sari yang Larut dalam Air
Sebanyak 5 g serbuk yang telah dikeringkan di udara dimaserasi selama 24
jam dalam 100 ml air-kloroform (2,5 ml kloroform dalam air sampai 1 liter)
dalam labu bersumbat sambil sesekali dikocok selama 6 jam pertama, kemudian
dibiarkan selama 18 jam, lalu disaring. Sejumlah 20 ml filtrat diuapkan sampai
kering dalam cawan dangkal berdasar rata yang telah ditara, dan sisa dipanaskan
pada suhu 105º C sampai bobot tetap. Kadar sari larut dalam air dihitung terhadap
bahan yang telah dikeringkan.
3.5.5 Penetapan Kadar Sari yang Larut dalam Etanol
Sebanyak 5 g serbuk yang telah dikeringkan di udara dimaserasi selama 24
jam dalam 100 ml etanol 96% dalam labu bersumbat sambil sesekali dikocok
selama 6 jam pertama, kemudian dibiarkan selama 18 jam. Kemudian disaring
cepat untuk menghindari penguapan etanol. Sejumlah 20 ml filtrat diuapkan
dipanaskan pada suhu 105ºC sampai bobot tetap. Kadar sari larut dalam etanol
dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan.
3.5.6 Penetapan Kadar Abu
Sebanyak 2 g serbuk yang telah digerus dan ditimbang seksama
dimasukkan dalam krus porselin yang telah dipijar dan ditara, kemudian
diratakan. Krus dipijarkan pada suhu 600ºC sampai arang habis, kemudian
didinginkan dan ditimbang sampai diperoleh bobot tetap. Kadar abu dihitung
terhadap bahan yang telah dikeringkan.
3.5.7 Penetapan Kadar Abu yang Tidak Larut dalam Asam
Abu yang telah diperoleh dalam penetapan kadar abu total dididihkan
dalam 25 ml asam klorida 2 N selama 5 menit, bagian yang tidak larut dalam
asam dikumpulkan, disaring melalui kertas saring bebas abu kemudian dicuci
dengan air panas. Residu dan kertas saring dipijarkan pada suhu 600ºC sampai
bobot tetap, kemudian didinginkan dan ditimbang. Kadar abu tidak larut dalam
asam dihitung terhadap bahan yang dikeringkan.
3.6 Skrining Fitokimia
Skrining fitokimia serbuk simplisia dilakukan menurut Depkes (1989)
(alkaloid, flavonoid, glikosida, glikosida antrakinon, glikosida sianogenik,
saponin) dan Farnsworth (1966) (steroid/triterpenoid, tanin).
3.6.1 Pemeriksaan Alkaloid
Serbuk ditimbang sebanyak 0,5 g, ditambahkan 10 ml asam klorida 0,2 N,
dipanaskan di atas penangas air selama 10 menit, didinginkan dan disaring. Filtrat
yang diperoleh dipakai untuk uji alkaloid. Ke dalam 4 tabung reaksi dimasukkan
Pada masing-masing tabung reaksi :
1. ditambahkan 2 tetes pereaksi Mayer
2. ditambahkan 2 tetes larutan Iodium
3. ditambahkan 2 tetes pereaksi Dragendorff
4. ditambahkan 2 tetes pereaksi Bouchardat
Alkaloid positif jika terjadi endapan atau kekeruhan pada dua dari empat pereaksi
di atas.
3.6.2 Pemeriksaan Flavonoid
Serbuk ditimbang sebanyak 0,5 g, lalu ditambahkan 10 ml metanol,
direfluks selama 10 menit, disaring panas-panas melalui kertas saring. Filtrat
diencerkan dengan 10 ml air suling. Setelah dingin ditambahkan 5 ml eter minyak
tanah, dikocok hati-hati, lalu diamkan sebentar. Lapisan metanolnya diambil,
diuapkan pada temperatur 40ºC, sisanya dilarutkan dalam 5 ml etilasetat, disaring.
Filtratnya digunakan untuk uji flavonoida dengan cara berikut:
a. Sebanyak 1 ml filtrat diuapkan sampai kering, sisa dilarutkan dalam 2 ml
etanol 96 %, lalu ditambah 0,5 g serbuk Zn dan 2 ml asam klorida 2 N,
didiamkan selama 1 menit. Kemudian ditambahkan 10 tetes asam klorida
pekat. Jika dalam waktu 2-5 menit terjadi warna merah intensif menunjukkan
adanya flavonoid.
b. Sebanyak 1 ml filtrat diuapkan sampai kering, sisa dilarutkan dalam 2 ml
etanol 96 %, lalu ditambah 0,1 g serbuk Mg dan 10 tetes asam klorida pekat.
Jika terjadi warna merah jingga sampai warna merah ungu menunjukkan
adanya flavonoid, warna kuning jingga menunjukkan adanya flavon, kalkon
3.6.3 Pemeriksaan Glikosida
Serbuk ditimbang sebanyak 3 g, lalu disari dengan 30 ml campuran etanol
96% dengan air (7:3) dan 10 ml asam klorida 2 N, direfluks selama 2 jam,
didinginkan dan disaring. Diambil 20 ml filrat ditambahkan 25 ml air suling dan
25 ml timbal (II) asetat 0,4 M, dikocok, didiamkan 5 menit lalu disaring. Filtrat
disari dengan 20 ml campuran isopropanol dan kloroform (2:3), dilakukan
berulang sebanyak 3 kali. Sari air dikumpulkan dan diuapkan pada temperatur
tidak lebih dari 50 C. Sisanya dilarutkan dalam 2 ml metanol. Larutan sisa
digunakan untuk percobaan berikut :
1. 0,1 ml larutan percobaan diuapkan, ditambahkan 5 ml asam asetat anhidrid dan
10 tetes asam sulfat pekat.
2. 0,1 ml larutan percobaan dimasukkan dalam tabung reaksi dan diuapkan diatas
penangas air. Pada sisa ditambahkan 2 ml air dan 5 tetes pereaksi Molish.
Kemudian secara perlahan-lahan ditambahkan 2 ml asam sulfat pekat melalui
dinding tabung. Terbentuknya cincin berwarna ungu pada batas kedua cairan
menunjukkan glikosida.
3. Serbuk sampel direbus dalam air, didinginkan, disaring. Pada filtrat
ditambahkan fehling A dan fehling B (1:1), dipanaskan. Terbentuknya endapan
merah bata menunjukkan adanya gula pereduksi.
3.6.4 Pemeriksaan Glikosida Antrakinon
Serbuk ditimbang sebanyak 0,2 g, ditambahkan 5 ml asam sulfat 2 N,
dipanaskan sebentar, setelah dingin ditambahkan 10 ml benzen, dikocok dan
dengan 2 ml NaOH 2 N, didiamkan. Lapisan air berwarna merah dan lapisan
benzen tidak berwarna menunjukkan adanya antrakinon.
3.6.5 Pemeriksaan Glikosida Sianogenik
Sebanyak 0,5 g serbuk dimasukkan ke dalam erlenmeyer, dilembabkan
dengan air. Diselipkan kertas saring yang telah dibasahi natrium pikrat pada mulut
erlenmeyer, ditutup, dibiarkan terkena sinar matahari. Jika kertas saring
memberikan warna merah, menunjukkan adanya sianogenik glikosida.
3.6.6 Pemeriksaan Saponin
Serbuk ditimbang sebanyak 0,5 g dan dimasukan ke dalam tabung reaksi,
lalu ditambahkan 10 ml air panas, dinginkan kemudian dikocok kuat-kuat selama
10 detik. Terbentuk busa setinggi 1-10 cm yang stabil tidak kurang dari 10 menit
dan tidak hilang dengan penambahan 1 tetes asam klorida 2 N menunjukkan
adanya saponin.
3.6.7 Pemeriksaan Steroid
Serbuk ditimbang sebanyak 1 g, dimaserasi dengan 20 ml n-heksana 2
jam, disaring, filtrat diuapkan dalam cawan penguap, dan pada sisanya
ditambahkan pereaksi Liebermann-Burchard. Terbentuknya warna ungu atau
merah yang berubah menjadi biru ungu atau biru hijau menunjukkan adanya
triterpenoid/steroid.
3.6.8 Pemeriksaan Tanin
Serbuk daun ditimbang sebanyak 1 g, dididihkan selama 3 menit dalam
100 ml air suling lalu didinginkan dan disaring. Pada filtrat ditambahkan 1- 2 tetes
pereaksi besi (III) klorida 1%. Jika terjadi warna biru kehitaman atau hijau
3.7 Pembuatan Ekstrak
Pembuatan ekstrak dilakukan dengan cara maserasi menggunakan pelarut
etanol 80%.
Cara kerja:
Sebanyak 1,3 kg serbuk simplisia dimasukkan ke dalam wadah bertutup,
dimaserasi dengan pelarut etanol 80% sampai serbuk terendam sempurna, ditutup,
dibiarkan selama 120 jam terlindung dari cahaya sambil sesekali diaduk, disaring.
Diperoleh filtrat hasil maserasi (maserat). Ampas dimaserasi kembali
menggunakan prosedur yang sama selama 48 jam. Pengerjaan dilakukan
berulangkali hingga maserat hampir tidak memberikan warna. Maserat yang
diperoleh digabungkan, kemudian diuapkan dengan bantuan penguap vakum putar
pada suhu ± 400C sampai diperoleh ekstrak kental. Bagan ekstraksi serbuk
simplisia umbi bawang sabrang dapat dilihat pada lampiran 10 halaman 51.
3.7 Isolasi Senyawa Alkaloid dari Ekstrak Etanol dengan Metode Pengocokan Asam Basa
Alkaloid yang terdapat dalam ekstrak etanol diisolasi dengan kloroform
memakai metode pengocokan asam basa sampai diperoleh ekstrak alkaloid kasar
dalam fase kloroform. Bagan isolasi alkaloid dapat dilihat pada lampiran 11
halaman 52.
Cara kerja :
Sebanyak 80 g ekstrak etanol kental hasil maserasi ditambahkan HCl 2 N
hingga pH antara 2-3, disaring. Filtrat dibasakan dangan NH4OH, hingga pH
antara 9-10, kemudian disari dengan 100 ml kloroform dengan cara pengocokan
dalam corong pisah, lapisan air dan lapisan kloroform dipisahkan. Perlakuan ini
disaring. Volume kloroform yang ada diuapkan menjadi sepertiganya dengan
penguap vakum putar pada suhu tidak lebih dari 40ºC. Lalu kepada sari kloroform
ditambahkan HCl 2 N sama banyak, dikocok dalam corong pisah, lalu lapisan
asam dan lapisan kloroform dipisahkan. Perlakuan ini diulangi sebanyak tiga kali.
Larutan asam dikumpulkan dan disaring. Larutan asam kemudian dibasakan
dengan NH4OH hingga pH 9-10. Disari dengan 100 ml kloroform dan kedua
lapisan dipisahkan dengan corong pisah. Perlakuan ini diulangi tiga kali. Sari
kloroform dikumpulkan dan diuapkan dengan penguap vakum putar bertekanan
rendah sampai diperoleh ekstrak alkaloida kasar yang kental.
3.8 Analisis Ekstrak Alkaloid Kasar Secara KLT
Terhadap ekstrak alkaloida kasar dilakukan KLT untuk melihat profil
kromatogram alkaloidnya menggunakan plat pra lapis silika gel GF254 dengan fase
gerak kloroform-metanol-amonia (90:10:1), (85:15:1), (80:20:1), benzen-etilasetat
(7:3), (5:5), toluen-etilasetat (9:1), (8:2), (7:3), (6:4).
Cara kerja :
Ke dalam chamber dimasukkan campuran pengembang kemudian ekstrak
etanol ditotolkan pada plat pra lapis silika gel GF254, setelah kering dimasukkan
ke dalam chamber yang telah jenuh dengan uap pengembang dan ditutup rapat.
Sesudah elusi selesai plat dikeluarkan dari chamber dan dikeringkan di udara,
kemudian plat disemprot dengan larutan penampak bercak Bouchardat, warna
3.9 Pembuatan Plat KLT
Plat KLT untuk preparatif dibuat dengan cara menimbang 7 g silika gel
GF254 kemudian ditambahkan air suling dengan perbandingan 1:2, dihomogenkan
dengan cara diaduk kemudian dituang ke atas plat kaca ukuran 20 x 20 cm yang
telah dibebaslemakkan dengan pelarut metanol dan diratakan kemudian dibiarkan
hingga kering. Pengaktifan plat dilakukan dengan cara pemanasan dalam oven
pada suhu 100ºC selama 1 jam.
3.10Pemisahan Ekstrak Alkaloid Kasar dengan KLT Preparatif
Ekstrak alkaloid kasar dipisahkan dengan KLT preparatif menggunakan
fase diam silika gel GF254, fase gerak toluen-etilasetat (9:1) dan penampak bercak
pereaksi Bouchardat.
Cara kerja :
Ekstrak alkaloid kasar ditotolkan berupa pita pada plat KLT berukuran
20x20 cm lalu dimasukkan ke dalam chamber yang telah jenuh dengan uap fase
gerak. Setelah elusi selesai, plat dikeluarkan dari bejana dan dikeringkan
kemudian bagian ujung plat disemprot dengan pereaksi Bouchardat. Bagian plat
silika yang memberikan harga Rf sama dengan noda yang positif terhadap
pereaksi Bouchardat dikerok kemudian dielusi dengan pelarut metanol, filtrat
diuapkan kemudian dimasukkan ke dalam lemari pendingin.
3.11Pemurnian Kristal Hasil Preparatif
Kristal hasil KLT preparatif dimurnikan dengan cara dicuci
3.12 Uji Kemurnian Isolat Hasil Preparatif dengan KLT Satu Arah dan Dua Arah
Terhadap isolat A dan B hasil KLT preparatif dilakukan uji kemurnian
dengan KLT satu arah menggunakan berbagai macam fase gerak yaitu n-heksan-
etilasetat (9:1), toluen-etilasetat (9:1), dan kloroform-metanol-amonia (85:15:1).
Fase diamnya adalah plat pra lapis silika gel GF254 dan sebagai panampak bercak
digunakan Bouchardat.
Cara kerja :
Isolat ditotolkan pada plat pra lapis silika gel GF254, setelah kering
dimasukkan ke dalam chamber yang telah jenuh dengan uap fase gerak. Setelah
pengembangan selesai plat dikeluarkan dari chamber, diamati bercaknya
kemudian disemprot dengan penampak bercak Bouchardat. Warna bercak yang
terjadi diamati dan dihitung harga Rf-nya. Kromatogram hasil KLT satu arah
dapat dilihat pada lampiran 15-16 halaman 43-44. Uji kemurnian isolat A dan B
selanjutnya dilakukan dengan KLT dua arah menggunakan dua sistem
pengembang yang berbeda yaitu fase gerak I kloroform- metanol-ammonia
(85:15:1) dan fase gerak II toluen-etilasetat (9:1). Isolat ditotolkan pada plat KLT
berukuran 20 x 20 cm lalu dimasukkan ke dalam chamber yang telah jenuh
dengan uap fase gerak I. Setelah elusi selesai, plat dikeluarkan dari chamber dan
dikeringkan. Setelah kering, plat dimasukkan kembali ke dalam chamber yang
telah jenuh dengan uap fase gerak II dan dielusi kembali. Setelah mencapai garis
batas pengembangan, plat dikeluarkan dan dikeringkan, diamati bercaknya
kemudian disemprot dengan penampak bercak Bouchardat. Warna bercak yang
terjadi diamati dan dihitung harga Rf-nya. Kromatogram hasil KLT dua arah
3.13Karakterisasi Isolat
Karakterisasi senyawa hasil isolasi dilakukan dengan spektrofotometri
ultraviolet dan inframerah.
3.13.1 Karakterisasi Isolat dengan Spektrofotometri Ultraviolet
Karakterisasi isolat dengan spektrofotometri ultraviolet dilakukan dengan
cara melarutkan zat hasil isolasi dengan kloroform kemudian diukur
absorbansinya pada panjang gelombang 200-400 nm. Spektrum ultraviolet dari
isolat A dan B dapat dilihat pada lampiran 19-20 halaman 62-63.
3.14.2 Karakterisasi Isolat dengan Spektrofotometri Inframerah
Karakterisasi isolat dengan spektrofotometri inframerah dilakukan dengan
cara mencampur isolat dengan kalium bromida menggunakan alat mixture vibrate
kemudian dicetak menjadi pellet dan dimasukkan ke dalam alat spektrofotometer
inframerah, lalu diukur absorbansinya pada frekuensi 4000-500 cm-1. Spektrum
inframerah dari isolat A dan B dapat dilihat pada lampiran 21-22 halaman 64-65.
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi tumbuhan dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengembangan
Biologi, LIPI, Bogor, hasilnya disebutkan tumbuhan yang digunakan adalah
bawang sabrang (Eleutherine palmifolia (L.) Merr.) suku Iridaceae. Hasil
identifikasi tumbuhan dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 42. Gambar
tumbuhan pada lampiran 2 halaman 43.
Pada pengolahan bahan tumbuhan, berat basah sampel setelah sortasi
basah diperoleh 5190 g. Sampel dikeringkan di lemari pengering untuk mencegah
kerusakan simplisia dan setelah sortasi kering diperoleh berat kering 2270 g.
Susut pengeringan yang dialami sampel adalah sebesar 56,26% dan rendemen
43,74%.
Hasil pemeriksaan makroskopik umbi bawang sabrang segar secara
organoleptis, umbi berbentuk bulat telur memanjang, berwarna merah dan tidak
berbau, serta berasa pahit. Umbi lapis terdiri dari 5-6 lapisan, dengan panjang
umbi 4-5 cm dan diameter 1-3 cm. Simplisia umbi bawang sabrang berwarna
merah pucat. Hasil pemeriksaan mikroskopik serbuk simplisia dijumpai adanya
kristal Ca-oksalat berbentuk jarum dan letaknya tidak beraturan, parenkim yang
terdiri dari beberapa lapis sel dengan bentuk tidak beraturan, xylem dengan
penebalan dinding sel berupa tangga (skalarifom), butir amilum dengan satu hilus
Hasil karakterisasi simplisia dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 1. Hasil karakterisasi serbuk simplisia umbi bawang sabrang
No. Uraian Hasil (%) Persyaratan MMI (%)
1. Kadar air 8,98 ≤ 10
2. Kadar sari yang larut dalam air 8,03 ≥ 4 3. Kadar sari yang larut dalam etanol 9,63 ≥ 2
4. Kadar abu total 4,32 ≤ 1
5. Kadar abu yang tidak larut dalam asam 0,84 ≤ 1,5
Tujuan pemeriksaan kadar air simplisia umbi bawang sabrang yaitu untuk
mengetahui batasan minimal kandungan air simplisia karena air merupakan media
yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Kadar sari larut dalam air dilakukan untuk
mengetahui senyawa polar yang larut dalam air. Kadar sari larut dalam etanol
dilakukan untuk mengetahui senyawa yang terlarut dalam etanol, baik polar
maupun nonpolar. Kadar abu total dilakukan untuk mengetahui kandungan
mineral dan juga cemaran logam pada simplisia. Kadar abu yang tidak larut dalam
asam dilakukan untuk mengetahui bahan-bahan yang tidak larut dalam asam.
Perhitungan hasil karakterisasi simplisia dapat dilihat pada lampiran 5-9 halaman
46-50.
Hasil skrining fitokimia serbuk simplisia umbi bawang sabrang dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2. Hasil Skrining Fitokimia Serbuk Simplisia Umbi Bawang Sabrang
(Eleutherinae bulbus)
Keterangan: + = mengandung golongan senyawa No. Golongan Senyawa yang Diperiksa Hasil
1. Alkaloid +
2. Flavonoid +
3. Steroid/Triterpenoid +
4. Glikosida +
5. Glikosida Sianogenik -
6. Glikosida Antrakinon +
7. Saponin +
[image:45.595.114.410.587.721.2]Pemeriksaan golongan alkaloid dengan penambahan pereaksi Mayer
terjadi kekeruhan dan endapan putih, dengan pereaksi iodium terjadi kekeruhan,
Bouchardat terbentuk endapan yang berwarna kuning kecoklatan, dan dengan
Dragendorff terbentuk warna jingga kecoklatan. Apabila paling sedikit dua dari
reaksi di atas positif maka menunjukkan adanya senyawa alkaloid (Depkes, 1989).
Pemeriksaan senyawa flavonoid dengan serbuk Mg dan asam klorida pekat serta
dengan serbuk Zn dan asam klorida pekat terbentuk warna merah. Pemeriksaan
senyawa steroid/triterpenoid dengan Liebermann-Burchard memberikan warna
ungu yang menunjukkan adanya senyawa triterpenoid. Golongan senyawa
glikosida dengan pereaksi Molish dan asam sulfat pekat terbentuk cincin berwarna
ungu dan penambahan pereaksi Fehling A dan Fehling B sama banyak terbentuk
endapan berwarna merah bata, hal ini menunjukkan glikosida positif. Glikosida
sianogenik diperiksa dengan pereaksi natrium pikrat, hasilnya tidak terbentuk
warna merah yang menunjukkan tidak adanya golongan senyawa glikosida
sianogenik. Pemeriksaan senyawa glikosida antrakinon yang dikocok dengan
larutan benzen dan NaOH, terbentuk warna merah pada lapisan NaOH yang
menunjukkan adanya senyawa glikosida antrakinon. Senyawa saponin
memberikan reaksi positif dengan uji busa yang dengan penambahan HCl 2 N
busa yang terbentuk tidak hilang, hal ini menunjukkan adanya senyawa golongan
saponin. Senyawa tanin dengan larutan FeCl3 10% tidak terbentuk warna hijau
maupun biru yang menunjukkan tidak adanya senyawa tanin.
Ekstraksi serbuk simplisia dilakukan dengan cara maserasi menggunakan
pelarut etanol 80%, diperoleh ekstrak etanol sebanyak 129,796 g dari 1300 g
dengan metode pengocokan asam basa dengan pelarut kloroform maka diperoleh
0,425 g ekstrak alkaloid kasar.
Analisa KLT ekstrak alkaloid kasar menggunakan fase diam plat pralapis
silika gel GF254, fase gerak kloroform-metanol-amonia (90:10:1), (85:15:1),
(80:20:1), benzen-etilasetat (7:3), (5:5) dan toluen-etilasetat (9:1), (8:2), (7:3)
(6:4). Hasilnya diperoleh fase gerak yang terbaik adalah toluen-etilasetat dengan
perbandingan (9:1) yang memberikan bercak noda yang paling banyak dan
dengan menggunakan penampak bercak Bouchardat menunjukkan adanya
senyawa alkaloid. Kromatogram dapat dilihat pada lampiran 13 halaman 54-56.
Pemisahan ekstrak alkaloid kasar dengan KLT preparatif menggunakan
fase gerak toluen-etilasetat (9:1), fase diam silika gel GF254, dan penampak bercak
Bouchardat. Hasilnya diperoleh 5 pita pada plat KLT berukuran 20 x 20 cm
setelah disemprot dengan penampak bercak Bouchardat. Selanjutnya plat
dikeluarkan dari bejana dan dikeringkan, kemudian bagian ujung plat disemprot
dengan pereaksi Bouchardat. Bagian plat silika yang memberikan harga Rf sama
dengan noda yang positif terhadap pereaksi Bouchardat dikerok, kemudian dielusi
dengan pelarut metanol, filtrat diuapkan dan dimasukkan ke dalam lemari
pendingin. Kristal yang diperoleh dimurnikan dengan cara dicuci berulang-ulang
menggunakan metanol dingin hingga diperoleh kristal bentuk jarum. Hasil
pemisahan diperoleh pita 1,2 dan 5 jumlahnya sangat sedikit sehingga untuk
analisis selanjutnya hanya dilakukan terhadap pita 3 dan 4. Kromatogram hasil
KLT preparatif dapat dilihat pada lampiran 14 halaman 57.
Terhadap pita 3 dan 4 dilakukan kembali uji kemurnian dengan KLT satu
toluen-etilasetat (9:1), dan kloroform-metanol-amonia (85:15:1). Hasilnya
ternyata tetap memberikan satu bercak berwarna jingga dengan penampak bercak
Bouchardat, hasilnya diperoleh harga Rf secara berturut-turut 0,34, 0,51, 0,86
(pita 3 selanjutnya disebut isolat A) dan 0,41, 0,6, 0,9 (pita 4 selanjutnya disebut
isolat B). Selanjutnya dilakukan KLT dua arah dengan fase gerak I
kloroform-metanol-amonia (85:15:1) dan fase gerak II toluen-etilasetat (9:1) memberikan
satu bercak dengan Rf 0,51 (isolat A) dan 0,57 (isolat B).
Hasil pemeriksaan spektrofotometri ultraviolet dari isolat A dan B
memberikan absorbansi maksimum pada panjang gelombang (λ) 270 nm (isolat
A) dan 271 nm (isolat B). Ini menunjukkan adanya gugus kromofor yang
mengalami transisi n→л*
Hasil pemeriksaan spektrofotometri inframerah dari isolat A menunjukkan
adanya ikatan C-H alifatis yang ditunjukkan oleh dua puncak tajam yang
berdekatan pada bilangan gelombang 2922,16 cm-1 dan 2850,79 cm-1, ini
diperkuat oleh adanya puncak pada bilangan gelombang 1462,04 yang
menunjukkan adanya gugus metilen (CH2). Puncak lemah pada bilangan
gelombang 1724,36 cm-1 menunjukkan adanya gugus C=O dari ester. Puncak
yang tajam pada bilangan gelombang 1587,42 menunjukkan adanya gugus C=C.
Puncak sedang pada bilangan gelombang 1355,96 cm-1 menunjukkan adanya
gugus C-N. Puncak pada bilangan gelombang 1097,50 cm-1 menunjukkan adanya
gugus C-O. Pada spektrum tidak ditemukan adanya puncak N-H pada bilangan
gelombang sekitar 3500 cm-1 sehingga diduga bahwa alkaloid pada isolat A
Hasil pemeriksaan spektrofotometri inframerah dari isolat B menunjukkan
adanya ikatan C-H alifatis yang ditunjukkan oleh dua puncak yang berdekatan
pada bilangan gelombang 2922,16 cm-1 dan 2852, 72 cm-1, ini diperkuat oleh
adanya puncak yang tajam pada bilangan gelombang 1462,04 yang menunjukkan
adanya gugus metilen (CH2) dan adanya puncak pada bilangan gelombang
1379,10 cm-1 menunjukkan adanya gugus metil (CH3). Puncak yang sedang pada
bilangan gelombang 1589,34 menunjukkan adanya gugus C=C. Puncak sedang
pada bilangan gelombang 1355,96 cm-1 menunjukkan adanya gugus C-N. Puncak
pada bilangan gelombang 1097,50 cm-1 menunjukkan adanya gugus C-O dari eter.
Pada spektrum tidak ditemukan adanya puncak N-H pada bilangan gelombang
sekitar 3500 cm-1 sehingga diduga bahwa alkaloid pada isolat B merupakan
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1Kesimpulan
1. Hasil analisis KLT ekstrak alkaloid kasar dari umbi bawang sabrang diperoleh toluen-etilasetat (9:1) sebagai fase gerak terbaik. Hasil kromatografi preparatif
diperoleh dua isolat yaitu isolat A dengan harga Rf 0,51 dan B 0,57.
2. Hasil spektrofotometri ultraviolet isolat A diperoleh panjang gelombang maksimum (λ) 270 nm dan B 271 nm. Hasil spektrofotometri inframerah menunjukkan adanya gugus C-H alifatis, CH2, C=O, C=C, C-N, C-O (isolat
A) dan gugus C-H alifatis, CH2, CH3, C=C, C-N dan C-O (isolat B).
5.2Saran
DAFTAR PUSTAKA
Adnan, M. (1997). Teknik Kromatografi Untuk Analisis Bahan Makanan. Yogyakarta: Penerbit Andi. Halaman 10, 15-16.
Anonim. (2010). Eleutherine palmifolia (L.) Merr. http://www.biologie.uni-ulm.de
Arung, et al. (2009). Evaluation of Medicinal Plants From Central Kalimantan
for Antimalanogenesis. J Nat Med 63:473-480.
Dachriyanus. (2004). Analisis Struktur Senyawa Organik Secara Spektroskopi. Cetakan Pertama. Padang : Andalas University Press. Halaman 1, 21-23.
Depkes. (1979). Farmakope Indonesia. Edisi III. Jakarta. Halaman 744.
Depkes. (1995). Farmakope Indonesia. Edisi IV. Jakarta. Halaman 1002.
Depkes. (1985). Tanaman Obat Indonesia. Jilid II. Jakarta : Departemen Kesehatan RI. Halaman 47.
Depkes. (1986). Sediaan Galenik. Jakarta : Departemen Kesehatan RI. Halaman 10-12.
Depkes. (1989). Materia Medika Indonesia. Jilid V. Jakarta : Departemen Kesehatan RI. Halaman 536, 540, 549-553.
Depkes. (1995). Materia Medika, Indonesia. Jilid VI. Jakarta : Departemen Kesehatan RI. Halaman 300.
Dineshkumar, et al. (2010). Antidiabetic and Hypolipidemic Effects of
Mahanimbine (Carbazole Alkaloid) From Murraya koenigii (Rutaceae) Leaves. International Journal of Phytomedicine 2:22-30.
Ditjen POM. (2000). Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat. Cetakan Pertama. Jakarta : Departemen Kesehatan RI. Halaman 1, 10-11.
Galingging, R. Y. (2007). Potensi Plasma Nutfah Tanaman Obat Sebagai Sumber Biofarmaka di Kalimantan Tengah. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Vol 10, No. 1 Halaman 82.
Galingging, R. Y. (2009). Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia) Sebagai Tanaman Obat Multifungsi. Warta Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembanga