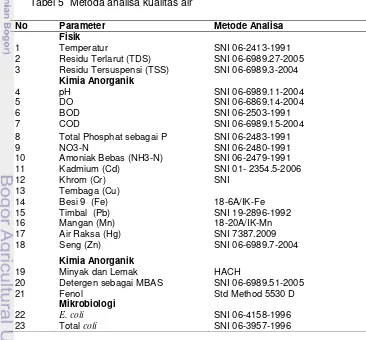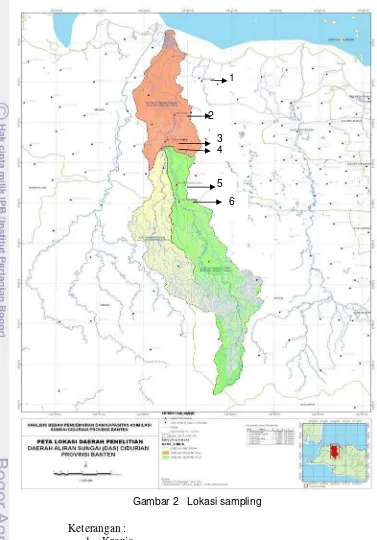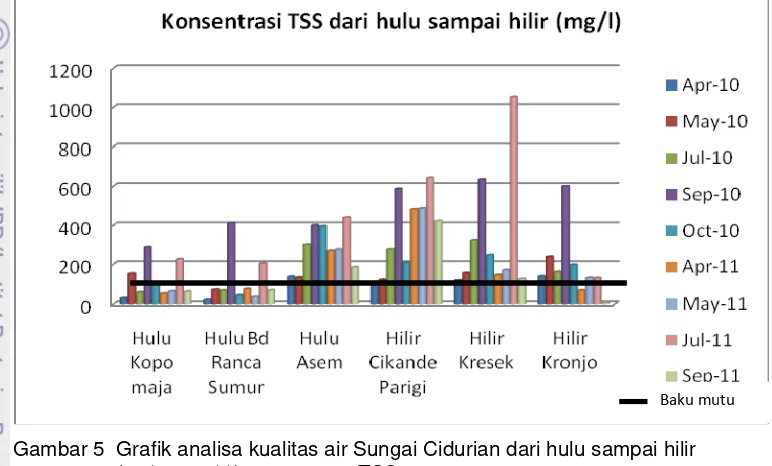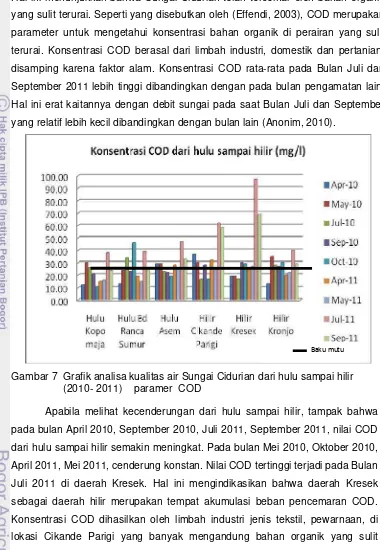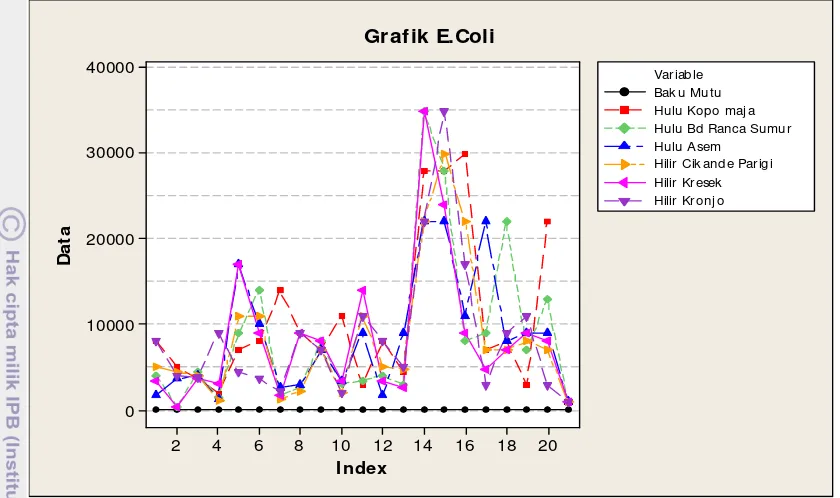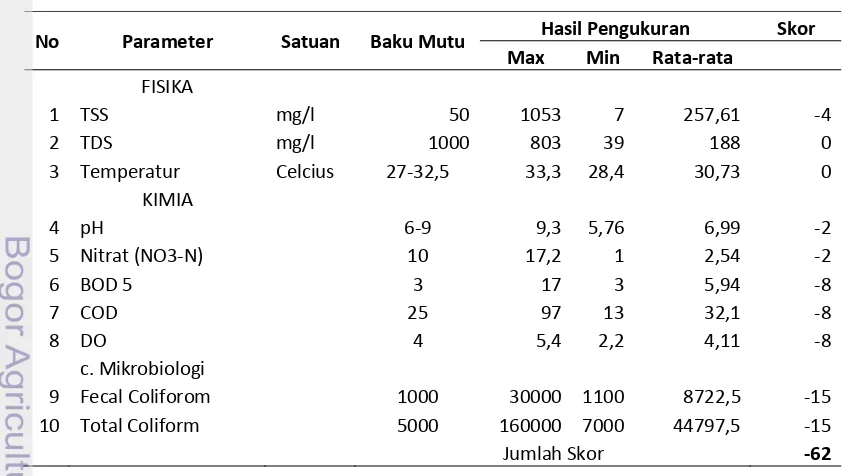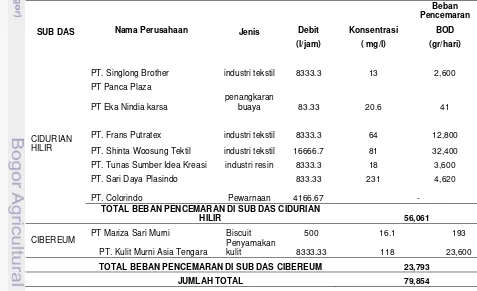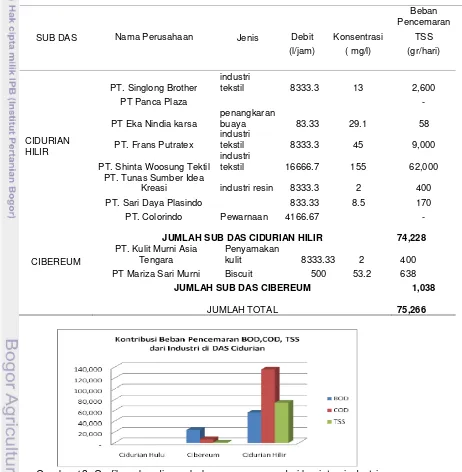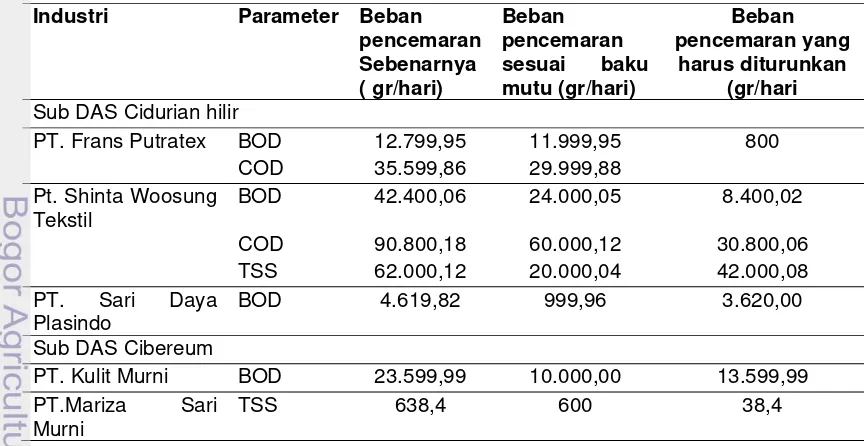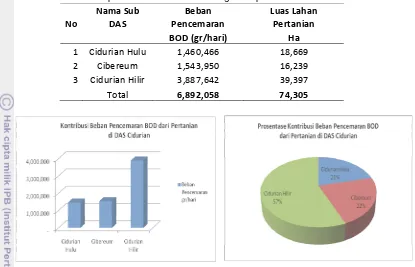PROVINSI BANTEN
ISTIANA WINDU KARTIKA
SEKOLAH PASCA SARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Analisa Beban Pencemaran
dan Kapasitas Asimilasi Sungai Cidurian Provinsi Banten adalah karya saya
dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk
apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau
dikutip dari karya yang diterbitkan maupun sudah diterbitkan dari penulis lain
telah disebutkan dalam tesis dan dicantumkan dalam daftar pustaka bagian
akhir tesis ini.
Bogor, April 2012
Istiana Windu Kartika
ISTIANA WINDU KARTIKA, Pollution Burden Analysis and Assimilation Capacity of Cidurian River Banten Province, under direction of ETTY RIANI and BUDI KURNIAWAN.
The river has the ability to clean itself of the burden of pollution naturally which is known as the capacity of assimilation. Incoming load exceeds the capacity of assimilation would lead to a decrease in the quality of the river until the river functions decline. This research aims to analyze the water quality of Cidurian River, analyze the contribution of pollution loads entering River Cidurian, and knowing the assimilation capacity of the stream. Research results show that the water quality, starting from the upstream to downstream concentrations of BOD, TSS, COD and
E. coli
are likely to exceed the standard of quality. Contribution to the total burden of polluters from certain sources (point source) in DAS Cidurian 2,4 tons/month BOD, COD 4,3 tons/month, TSS 2,26 tons/month. The contribution burden of polluters undefinable (non point source) based on the analysis of land use from agricultural sector BOD 206,76 tons/month,TSS 24,13 ton/month, based on the analysis of the population of each sub DAS, domestic sector have 1.374 tons/month of BOD, COD 1.890 tons/month, TSS 1.305 tons/month and E.coli 1,02 E 16 tons/month. Total contribution burden of polluters undefinable (non point source) parameters BOD 1.580 tons/month, COD 1.890 tons/month, TSS 1.324 tons/month, more dominant compared to certain sourced (point source). Capacity of assimilation to the parameters of TSS 22.901,55 tons/month, BOD 2.347,83 tons/month, COD 24.208,33 tons/month, E.coli 424.629,90 tons/month. Overall value of assimilation capacity is smaller compared to the burden of pollution of the river, resulting in the organic matter pollution experienced TSS, BOD, COD andE.coli
. The high contribution to the burden of domestic source of polluters and agriculture, as well as the capacity of assimilation to consider in an attempt to control water pollution.Sungai Cidurian Provinsi Banten, dibimbing oleh ETTY RIANI dan BUDI
KURNIAWAN
Sungai merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan baik ekologi, ekonomi maupun sosial. Namun sungai juga digunakan manusia sebagai tempat pembuangan limbah. Berbagai aktifitas di bidang industri, domestik serta pertanian berpotensi menghasilkan limbah yang di buang ke sungai baik secara langsung maupun tak langsung. Hal ini mengakibatkan sungai menerima beban pencemaran yang melebihi kemampuannya dalam membersihkan diri atau dikenal sebagai kapasitas asimilasi. Kondisi dimana beban pencemaran yang diterima ke sungai melebihi kapasitas asimilasi dikatakan sebagai kondisi tercemar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air Sungai Cidurian,, menganalisis potensi beban pencemaran yang masuk Sungai Cidurian, serta mengetahui nilai kapasitas asimilasi.
Lokasi penelitian adalah DAS Cidurian, dengan meninjau wilayah ekosistem maupun administrasi. Ekosistem DAS Cidurian meliputi sub DAS Cidurian Hulu, sub DAS Cibereum, serta sub DAS Cidurian Hilir. Wilayah administratif yang dilintasi DAS Cidurian antara lain ; Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang serta Kabupaten Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penentuan status mutu air menggunakan metode storet dan indeks pencemar, analisa kualitas air dengan membandingkan baku mutu menurut kelas II Peraturan Pemerintah no 82 tahun 2001. Sedangkan metode analisis beban pencemaran dilakukan melalui analisis terhadap beban pencemaran dari sumber tertentu (point source) serta sumber tak tentu (non point
source), untuk setiap sub DAS maupun wilayah administratif, serta analisis sektor
Parameter yang dominan antara lain TSS, BOD, COD dan
E.coli
. Hasil penentuan status mutu air menunjukkan Sungai Cidurian berada dalam kondisi tercemar sedang sampai berat, sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup no 115 tahun 2003.Kontribusi beban pencemar dari sumber tertentu, dari sektor industri untuk parameter BOD sebesar 2,4 ton/bulan, COD sebesar 4,3 ton/bulan, TSS sebesar 2,26 ton/bulan, Berdasarkan analisa ekosistem tiap sub DAS, diperoleh hasil bahwa kontribusi beban pencemaran tertinggi dari sumber pertanian untuk parameter BOD adalah sub DAS Cidurian Hilir sebesar 116,63 ton/bulan, untuk parameter TSS adalah sub DAS Cibereum sebesar 21,12 ton/bulan. Hal ini berkaitan dengan penggunaan lahan di daerah hilir banyak didominasi oleh sawah yang mempunyai faktor emisi dari pembusukan jerami sebesar 18 gr/ha/musim tanam. Sub DAS Cibereum penggunaan lahannya lebih bervariasi, untuk sawah, palawija dan perkebunan lain. Kontribusi beban pencemar dari sumber domestik yang paling dominan adalah sub DAS Cidurian Hulu, dengan nilai
E.coli
, TSS, BOD, COD berturut - turut sebesar; 0,56 ton/bulan, 0,59 ton/bulan dan 0,81 ton/bulan. Sub DAS Cidurian Hilir jumlah penduduknya lebih tinggi dibandingkan sub DAS Cidurian Hulu. Namun beban pencemaran sub DAS Cidurian Hilir dari sumber domestik lebih kecil dari sub DAS Cidurian Hilir. Hal ini disebabkan penduduk di sub DAS Cidurian Hulu sebagian besar pemukimannya berdekatan dengan sungai, yang berpeluang membuang limbah secara langsung ke sungai.Berdasarkan analisa wilayah, diperoleh hasil wilayah yang dominan terhadap kontribusi beban pencemaran, dari sektor pertanian dan domestik, sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pengendalian pencemaran air. Total kontribusi beban pencemar dari sumber tak tentu (non point source) parameter BOD 1.580 ton/bulan, COD 1.890 ton/bulan, TSS 1.329 ton/bulan. Secara umum diperoleh gambaran bahwa kontribusi beban pencemaran dari sumber tak tentu (non point source) lebih besar dibandingkan dengan sumber tertentu (point source).
Nilai kapasitas asimilasi masing masing parameter yang diamati berturut-turut TSS 22.901,55 ton/bulan, BOD 2.347,83 ton/bulan, COD 24.208,33 ton/bulan,
E.coli
424.629,90 ton/bulan. Secara umum diperoleh gambaran, beban pencemaran TSS, BOD, COD,E.coli
melebihi kapasitas asimilasi, sehingga Sungai Cidurian dalam kondisi tercemar.DAN KAPASITAS ASIMILASI SUNGAI CIDURIAN
PROVINSI BANTEN
ISTIANA WINDU KARTIKA
Tesis
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains pada
Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
SEKOLAH PASCA SARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Penguji luar komisi pada ujian tesis :
Puji syukur yang tak hingga kami sampaikan kehadirat Allah SWT yang
telah memberikan rahmat dan karunia Nya, sehingga kami dapat
menyelesaikan tesis ini. Judul yang dipilih adalah Analisis Beban Pencemaran
dan Kapasitas Asimilasi Sungai Cidurian Provinsi Banten. Penelitian dilakukan
selama Bulan Agustus 2011 sampai dengan Desember 2011.
Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr.Ir.Etty Riani, MS dan
Bapak Dr. Budi Kurniawan, M.Eng, selaku dosen pembimbing. Kami juga
menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada rekan rekan
Badan Lingkungan Hidup serta Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi
Banten , serta semua pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data
serta penyelesaian tesis ini. Tak lupa kami sampaikan terima kasih yang tak
terhingga kepada rekan-rekan PSL kelas khusus angkatan kedua, atas
dukungannya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Orangtua kami,
suami, anak-anak tercinta serta seluruh keluarga besar atas doa, dukungan dan
pengorbanannya.
Penulis dilahirkan di Malang pada tanggal 7 Oktober 1969 dari ayah H.Faisal
Munieb dan Ibu Solichah Ashadi. Penulis merupakan anak kedelapan dari delapan
bersaudara. Penulis lulus dari Sekolah Dasar di Malang tahun 1982, dan melanjutkan di
SMP Negeri 1 Malang. Setelah tamat tahun 1985, penulis melanjutkan studi ke SMA
Negeri 3 Malang, dan tamat tahun 1988. Pada tahun 1988 penulis melanjutkan studi ke
Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) Jurusan Teknik Lingkungan, dan
tamat tahun 1993.
Pada tahun ajaran 2009 – 2010 penulis melanjutkan studi ke Sekolah Pasca
Sarjana Institut Pertanian Bogor, Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
DAFTAR TABEL………...
DAFTAR GAMBAR………
DAFTAR LAMPIRAN………
BAB I. PENDAHULUAN………
1.1 Latar Belakang……… 1
1.2 Kerangka Pemikiran………. 2
1.3 Perumusan Masalah……….. 4
1.4 Tujuan Penelitian……….. 5
1.5 Manfaat Penelitian……….. 5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kualitas Air Sungai……… 6
2.2 Beban Pencemaran……… 7
2.3 Kapasitas Asimilasi………... 14
2.4 Sungai Cidurian……… 15
2.5 Pengendalian Pencemaran Air Sungai……… 18
BAB III. METODE PENELITIAN 3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian………... 20
3.2 Jenis dan Sumber Data……… 20
3.3 Metode Sampling……….. 3.4 Metode Analisis Potensi Beban Pencemaran……….. 20 23 3.5 Metode Analisis Kapasitas Asimilasi Beban Pencemaran………. 27
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Analisa Kualitas Air Sungai Cidurian……….. 29
4.2 Analisa Beban Pencemaran Sungai Cidurian……… 44
4.2.1 Analisa Ekosistem……… 44
4.2.2 Analisa Wilayah ……… 58
4.2.3 Analisa Sektoral……….. 78
5.1 Kesimpulan………
5.2 Saran………..
94
94
DAFTAR PUSTAKA………....
LAMPIRAN………...
96
Halaman
1. Emisi air limbah domestik………. 12
2. Klasifikasi emisi BOD di Indonesia………. 12
3. Emisi dari kegiatan pertanian……….. 13
4. Pembagian lokasi sampling berdasarkan sub DAS……….. 21
5. Metode analisa kualitas air……… 21
6. Lokasi sampling logam berat……… 23
7. Hasil pemantauan kualitas air Sungai Cidurian parameter TSS………. 30
8. Hasil pemantauan kualitas air Sungai Cidurian parameter COD……… 32
9. Hasil pemantauan kualitas air Sungai Cidurian parameter BOD……… 34
10. Hasil pemantauan kualitas air Sungai Cidurian parameter DO……… 37
11. Hasil pemantauan kualitas air Sungai Cidurian parameter E.coli………... 38
12. Hasil pemantauan logam berat Sungai Cidurian……….. 40
13. Hasil pehitungan status mutu air metode storet bagian hulu……….. 41
14. Hasil perhitungan status mutu air metode storet bagian tengah……… 41
15. Hasil perhitungan status mutu air metode storet bagian hilir……….. 42
16. Rekapitulasi hasil perhitungan status mutu air metode storet……… 42
17. Hasil perhitungan status mutu air metode indeks pencemaran……….. 43
18. Perhitungan beban pencemaran BOD dari kegiatan industri……… 44
22. Rekapitulasi penggunaan lahan di DAS Cidurian………. 50
23. Beban pencemaran TSS dari kegiatan pertanian di DAS Cidurian……… 53
24. Beban pencemaran domestik berdasarkan analisa ekosistem……….. 54
25. Penggunaan lahan di Kabupaten Lebak………. 55
26. Kontribusi beban pencemaran dari pertanian di Kabupaten Lebak…………... 56
27. Kontribusi beban pencemaran dari pertanian di Kabupaten Serang………… 58
28. Kontribusi beban pencemaran dari pertanian di Kabupaten Tangerang…….. 59
29. Kontribusi beban pencemaran dari pertanian di Kabupaten Bogor……… 61
30. Beban pencemaran dari kegiatan domestik di Kabupaten Lebak……….. 64
31. Beban pencemaran dari kegiatan domestik di Kabupaten Serang……… 66
32. Beban pencemaran dari kegiatan domestik di Kabupaten Tangerang……….. 69
33. Beban pencemaran dari kegiatan domestik di Kabupaten Bogor……….. 72
34. Perbandingan beban pencemaran dari sektor domestik dan pertanian di
Kabupaten Lebak………
74
35. Perbandingan beban pencemaran dari sektor domestik dan pertanian di
Kabupaten Serang……….
77
36. Perbandingan beban pencemaran dari sektor domestik dan pertanian di
Kabupaten Tangerang………..
79
37. Perbandingan beban pencemaran dari sektor domestik dan pertanian di
Kabupaten Bogor………
38. Fungsi hubungan beban pencemaran sungai dan kualitas sungai bagian hilir
80
Kabupaten Bogor………..
1. Kerangka pemikiran analisis beban pencemaran dan kapasitas asimilasi 3
2. Lokasi sampling……….. 22
3. Grafik analisa kualitas air Sungai Cidurian periode pengamatan (2010-2011) parameter TSS……….
30
4. Grafik analisa kualitas air Sungai Cidurian dari hulu sampai hilir (2010-2011) parameter TSS………
31
5. Grafik analisa kualitas air Sungai Cidurian periode pengamatan (2010-2011) parameter COD………..
32
6. Grafik analisa kualitas air Sungai Cidurian dari hulu sampai hilir (2010-2011) parameter COD………..
33
7. Grafik analisa kualitas air Sungai Cidurian periode pengamatan (2010-2011) parameter BOD………..
35
8. Grafik analisa kualitas air Sungai Cidurian dari hulu sampai hilir (2010-2011) parameter BOD………..
35
9. Grafik analisa kualitas air Sungai Cidurian periode pengamatan (2010-2011) parameter DO……….
37
10. Grafik analisa kualitas air Sungai Cidurian dari hulu sampai hilir (2010-2011) parameter E. coli ………...
39
11. Grafik status mutu air berdasarkan nilai indeks pencemar……… 43
12. Grafik perbandingan beban pencemaran dari kegiatan industri di DAS Cidurian………..
48
13. Prosentase penggunaan lahan untuk sawah dan palawija di DAS
Cidurian….………..
51
14. Prosentase penggunaan lahan untuk perkebunan lain di DAS Cidurian… 52
15. Kontribusi beban pencemar dan prosentase BOD dari pertanian…………. 53
16. Grafik perbandingan penggunaan lahan di DAS Cidurian……….. 54
17. Kontribusi beban pencemaran TSS dari kegiatan pertanian di DAS Cidurian………..
19. Kontribusi beban pencemaran dari domestic berdasarkan analisa
ekosistem………
57
20. Jumlah penduduk di tiap sub DAS Cidurian dan prosentase jumlah penduduk………
57
21. Penggunaan lahan DAS Cidurian di Kabupaten Lebak……….. 58
22. Kontribusi beban pencemaran BOD dan prosentase kontribusi beban pencemaran BOD dari pertanian di Kabupaten Lebak………
59
23. Hubungan antara beban pencemaran BOD dari pertanian dengan luas penggunaan lahan………
59
24. Kontribusi beban pencemaran TSS dan prosentase kontribusi beban pencemaran TSS dari pertanian di Kabupaten Lebak………
60
25. Hubungan antara luas lahan pertanian dengan beban pencemaran TSS dari pertanian di Kabupaten Lebak………
61
26. Kontribusi beban pencemaran BOD dan prosentase kontribusi beban pencemaran BOD dari pertanian………
62
27. Hubungan antara luas lahan pertanian dengan kontribusi beban
pencemaran BOD dari pertanian di Kabupaten Serang………..
62
28. Kontribusi beban pencemaran TSS dan prosentase kontribusi beban pencemaran TSS dari pertanian di Kabupaten Serang………..
63
29. Hubungan antara luas lahan pertanian dengan beban pencemaran TSS dari pertanian di Kabupaten Serang………
63
30. Kontribusi beban pencemaran BOD dan perbandingan luas lahan pertanian di Kabupaten Tangerang………....
31. Kontribusi beban pencemaran TSS dan prosentase kontribusi beban pencemaran TSS dari pertanian di Kabupaten Tangerang…………
65
66
32. Penggunaan lahan DAS Cidurian serta prosentase kontribusi beban pencemar BOD dari pertanian di Kabupaten Bogor………
67
33. Kontribusi beban pencemar TSS serta prosentase kontribusi beban pencemar TSS dari pertanian di Kabupaten Bogor……….
35. Kontribusi dan prosentase beban pencemaran COD dari domestik di
Kabupaten Lebak……….
70
36. Kontribusi dan prosentase beban pencemaran TSS dari domestik di
Kabupaten Lebak………..
70
37. Kontribusi dan prosentase beban pencemaran E. coli dari domestik di Kabupaten Lebak………..
71
38. Kontribusi dan prosentase kontribusi beban pencemaran BOD, COD, TSS dari domestik di Kabupaten Serang………
73
39. Kontribusi dan prosentase kontribusi beban pencemaran
E coli
dari domestik di Kabupaten Serang………...73
40. Kontribusi dan prosentase kontribusi beban pencemaran BOD, COD, TSS dari domestic di Kabupaten Tangerang……….
75
41. Kontribusi dan prosentase kontribusi beban pencemaran E coli dari domestik di Kabupaten Tangerang……….
76
42. Prosentase kontribusi beban pencemar dari domestik di Kabupaten Tangerang………..
76
43. Prosentase jumlah penduduk di DAS Cidurian wilayah Kabupaten Bogor..
44. Kontribusi beban pencemar dari domestik di Kabupaten Bogor………
77
78
45. Perbandingan kontribusi beban pencemaran BOD dan TSS dari domestik dan pertanian di Kabupaten Lebak………
79
46. Prosentase pola penyebaran penduduk di DAS Cidurian wilayah
Kabupaten Lebak……….
47. Perbandingan kontribusi beban pencemaran BOD dan TSS dari domestik dan pertanian di Kabupaten Serang……….
80
81
48. Prosentase pola penyebaran penduduk di DAS Cidurian Kecamatan Tanara Kabupaten Serang……….
dan pertanian di Kabupaten Tangerang………...
50. Prosentase pola penyebaran penduduk di DAS Cidurian wilayah
Kabupaten Tangerang……….
51. Perbandingan kontribusi beban pencemaran BOD dan TSS dari domestik dan pertanian di Kabupaten Bogor………
84
85
52. Prosentase pola penyebaran penduduk di DAS Cidurian wilayah
Kabupaten Bogor………..
53. Analisa regresi antara beban pencemaran TSS dengan konsentrasi TSS Sungai Cidurian pada bulan pengamatan Oktober sampai Desember 2011……….
54. Analisa regresi antara beban pencemaran BOD dengan konsentrasi BOD Sungai Cidurian pada bulan pengamatan Oktober sampai Desember .2011………
55. Analisa regresi antara beban pencemaran COD dengan konsentrasi COD Sungai Cidurian pada bulan pengamatan Oktober sampai Desember 2011……….
56. Analisa regresi antara beban pencemaran
E. coli
dengan konsentrasiE. coli Sungai Cidurian pada bulan pengamatan Oktober sampai
Desember 2011……….
85
88
89
90
1. Matrik luas penggunaan lahan berdasarkan sub DAS dan administrasi wilayah dari metode GIS………..
82
2. Perhitungan beban pencemaran kegiatan pertanian parameter BOD berdasarkan analisa ekosistem……….
89
3. Perhitungan beban pencemaran kegiatan domestik berdasarkan jumlah penduduk per sub DAS ( analisa ekosistem )………
91
4. Perhitungan beban pencemaran kegiatan pertanian parameter BOD berdasarkan analisa wilayah………
97
5. Perhitungan beban pencemaran kegiatan domestik berdasarkan jumlah penduduk per kecamatan per Kabupaten ( analisa wilayah )………
98
6. Perhitungan beban pencemaran Sungai Cidurian pada bulan
pengamatan Oktober 2011 sampai dengan Desember 2011………
102
7. Beban pencemaran total dan kualitas air di hilir untuk menentukan kapasitas asimilasi………
8. PETA batas sub DAS Cidurian………
103
104
9. PETA penggunaan lahan……….
10. PETA zona koefisien transfer beban………..
105
1.1 Latar belakang
SungaiCidurian merupakan salah satu sungai strategis di Provinsi Banten
yang mengalir dari hulu di Kabupaten Bogor, dan melewati Kabupaten Lebak,
perbatasan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang serta bermuara di
Laut Jawa. Keberadaan sungai ini sangat penting bagi masyarakat khususnya
yang tinggal di bantaran DAS Cidurian. Berbagai aktifitas di sekitar wilayah
sungai seperti pertanian, industri, penambangan pasir, serta aktifitas masyarakat
berdampak terhadap pelestarian fungsi sungai sebagai penyedia sumber daya
air. Dampak yang sangat potensial adalah terjadinya pencemaran sungai yang
mengakibatkan penurunan kualitas air sungai, sehingga tidak dapat
dimanfaatkan sesuai peruntukkan kelas sungai .
Sungai Cidurian kualitas airnya termasuk ke dalam kelas III dan IV
(BLHD Banten, 2009), berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Kualitas Air peruntukkan
tersebut tidak sesuai untuk air baku air minum. Kondisi tersebut, mendorong
untuk dilakukan upaya pengendalian pencemaran Sungai Cidurian, sehingga
Sungai Cidurian dapat berfungsi sesuai peruntukan kelas I khususnya sebagai
penyedia air bersih untuk masyarakat, industri dan aktifitas lainnya.
Pengendalian pencemaran sungai yang ada saat ini baru pada tingkat
pengendalian pada sumber efluennya melalui pendekatan kebijakan penetapan
baku mutu air limbah dari industri. Kebijakan ini mendorong industri melakukan
pendekatan teknologi seperti produksi bersih, end of pipe instalasi pengolahan air limbah, pemberlakuan prinsip 3 R (reuse, reduce, recycle). Namun pengendalian pencemaran belum mencapai hasil yang optimal. Terbukti masih
tingginya tingkat pencemaran di Sungai Cidurian. Hal ini mengindikasikan bahwa
ada sumber pencemar dari kegiatan lain yang belum mampu dikendalikan, serta
belum diketahui kemampuan Sungai Cidurian dalam melakukan pembersihan
alami terhadap beban pencemaran yang diterima, yang disebut dengan
kapasitas asimilasi.
Bertitik tolak dari hal tersebut, perlu dilakukan analisis beban pencemaran
secara alamiah, sungai memiliki kapasitas asimilasi. Namun kemampuannya
terbatas, untuk itu diperlukan suatu analisis mengenai kapasitas asimilasi sungai.
Limbah cair yang dibuang ke Sungai Cidurian berasal dari berbagai macam
sumber. Sampai saat ini analisis beban pencemaran dan kapasitas asimilasi
Sungai Cidurian belum diketahui bahkan belum pernah dilakukan penelitian
secara khusus. Analisis beban pencemaran dan kapasitas asimilasi badan air
(sungai) yang benar-benar riil sebenarnya sangat sulit dilakukan. Hal ini
dikarenakan banyaknya variabel yang mempengaruhi kemampuan air sungai
untuk melakukan kapasitas asimilasi, diantaranya debit sungai, kecepatan, jenis
dan jumlah pencemar, suhu, cuaca, musim, bentuk aliran dan oksigen terlarut.
Oleh karena itu maka pada penelitian ini dilakukan estimasi analisis beban
pencemaran dan kapasitas asimilasi
1.2 Kerangka Pemikiran
Masalah yang dihadapi Sungai Cidurian Provinsi Banten saat ini adalah
penurunan kualitas air sungai, sehingga sungai tidak berfungsi sesuai dengan
peruntukannya. Penurunan kualitas air disebabkan oleh faktor alamiah dan
pengaruh aktifitas manusia. Sumber pencemar yang alami berasal dari erosi dan
tanah longsor yang menyebabkan peningkatan kandungan bahan tersuspensi.
Sumber pencemar yang berasal dari aktifitas manusia adalah dari kegiatan
domestik, pertanian yang telah menggunakan bahan pestisida dan herbisida,
serta industri yang tidak diolah atau melebihi baku mutu air limbah yang
ditetapkan. Data dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten (BLHD
2009) menunjukkan adanya penurunan status mutu air menurut Peraturan
Pemerintah No 82 tahun 2001 dari kelas II menjadi kelas III dan IV. Berdasarkan
Pearaturan Pemerintah tersebut, mutu Kelas III dan IV adalah kelas air untuk
kepentingan pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi
tanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama
dengan kegunaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka kelas III dan IV tidak
layak digunakan sebagai air baku air minum. Penurunan status mutu air,
disebabkan oleh tingginya beban pencemaran pada Sungai Cidurian. Menurut
data dari BLHD Provinsi Banten ada tiga buah Perusahaan Daerah Air Minum
dan sepuluh industri yang mengambil air baku dari Sungai Cidurian, selain
Sampai saat ini pengendalian pencemaran air pada Sungai Cidurian
dilakukan dengan monitoring dan evaluasi kualitas air rutin setiap bulan oleh
Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten. Namun belum pernah
dilakukan penelitian mengenai analisis beban pencemar dan kapasitas asimilasi
di Sungai Cidurian. Bertitik tolak dari hal tersebut, perlu dilakukan upaya
pendekatan sistem pengendalian pencemaran air yang tepat, dengan
mempertimbangkan beban pencemaran dari sumber tertentu (point source) dan sumber tak tentu (non point source) serta perlu melihat kemampuan sungai dalam mereduksi beban pencemaran atau kapasitas asimilasi. Kerangka
pemikiran ini disajikan pada Gambar 1.
1.3 Perumusan Masalah
Pencemaran yang terjadi pada Sungai Cidurian berasal dari sumber
tertentu (point source) seperti efluen dari limbah industri maupun sumber tak tentu (non point source) seperti domestik, pertanian. Sumber polutan dari domestik cukup besar karena jumlah penduduk di DAS Cidurian berjumlah ±
1.656.769 orang (BPS Banten 2010), dan rata-rata penduduknya memanfaatkan
Sungai Cidurian sebagai sumber kehidupan. Saat ini pengendalian pencemaran
Sungai Cidurian belum mengakomodir pencemaran dari limbah domestik dan
pertanian. Faktor penyebabnya adalah kesulitan dalam menentukan beban
pencemaran dari limbah domestik dan pertanian. Oleh karena itu dilakukan
pendekatan melalui metode estimasi beban pencemaran. Pengendalian
pencemaran dari sumber industri telah dilakukan melalui pengaturan limbah yang
masuk ke sungai agar tidak melebihi baku mutu, namun belum mencapai hasil
yang diharapkan. Terbukti kualitas air Sungai Cidurian masih dibawah baku mutu
yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan tinggginya beban pencemaran dari
sumber domestik dan pertanian yang belum dapat dikendalikan.
Secara teoritis air limbah baik yang diolah ataupun yang tidak diolah
apabila masuk ke badan air akan mengalami tekanan oleh ekosistem air.
Tekanan tersebut berupa pengurangan atau penghilangan bahan pencemar oleh
berbagai proses yang ada dalam air. Proses ini meliputi pengenceran secara
fisik, penyebaran dan pengendapan, reaksi kimia, adsorbsi, penguraian secara
biologis dan stabilisasi. Proses-proses tersebut pada dasarnya merupakan sifat
alamiah air yang memiliki kemampuan untuk membersihkan atau
menghancurkan berbagai kontaminan dan pencemar yang dibawa air limbah.
Kemampuan air untuk membersihkan diri secara alamiah dari berbagai
kontaminan dan pencemar dikenal sebagai kapasitas asimilasi. Namun kapasitas
asimilasi ada batasnya. Beban pencemar yang masuk ke Sungai Cidurian,
apabila melebihi kapasitas asimilasi menyebabkan penurunan kualitas air.
Analisis beban pencemaran dan kapasitas asimilasi diharapkan dapat
digunakan sebagai dasar dalam mengendalikan pencemaran berdasarkan
potensi beban pencemar maupun kondisi kualitas perairan alami. Oleh
karenanya muncul beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana kualitas air Sungai Cidurian saat ini?
source)?
3. Berapa kapasitas asimilasi Sungai Cidurian saat ini?
1.4 Tujuan Penelitian
1. Menganalisis kualitas air Sungai Cidurian ditinjau dari kelas air menurut
Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 dan status mutu air menurut
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.115 thun 2003
2. Menganalisis potensi kontribusi beban pencemaran pada Sungai Cidurian dari
sumber titik (point source) maupun sumber menyebar (diffuse source).
3. Menganalisis kapasitas asimilasi Sungai Cidurian terhadap beban pencemaran.
1.5 Manfaat penelitian
1. Pemanfaat dapat mengetahui kualitas air Sungai Cidurian sesuai dengan
peruntukan kelas sungai ditinjau dari kelas air menurut Peraturan Pemerintah
No.82 Tahun 2001 serta status mutu air menurut Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup No.115 thun 2003
2. Pemerintah mendapatkan informasi potensi beban pencemaran pada Sungai
2.1 Kualitas Air Sungai
Kualitas air adalah kondisi kualitatif air yang diukur dan atau diuji
berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003). Kualitas air dapat
dinyatakan dengan parameter kualitas air. Parameter ini meliputi parameter fisik,
kimia, dan mikrobiologis. Parameter fisik menyatakan kondisi fisik air atau
keberadaan bahan yang dapat diamati secara visual/kasat mata, Parameter fisik
meliputi kekeruhan, kandungan partikel/padatan, warna, rasa, bau, suhu, dan
sebagainya. Pengelolaan kualitas air menurut Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 adalah upaya pemeliharaan air
sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk
menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiah. Peruntukan badan air
masing-masing kelas menurut PP No 82 Tahun 2001. Pasal 8 adalah sebagai
berikut;
• Kelas satu, adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama
dengan kegunaan tersebut.
• Kelas dua, adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air prasarana/ sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air
untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan
mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
• Kelas tiga, adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan
atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan
kegunaan tersebut.
• Kelas empat, adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air
2.2 Beban Pencemaran
Definisi pencemaran menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No
01 Tahun 2010 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,
dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga
melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan. Beban pencemaran
adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau limbah .
Beban pencemaran juga merupakan besaran satuan berat zat pencemar dalam
satuan waktu, misal 1 ton BOD/hari (Anonim, 2010).
2.2.1 Sumber dan Jenis Beban Pencemaran
Sumber pencemar (polutan) dapat berupa suatu lokasi tertentu (point source) dan tak tentu/tersebar (non-point/diffuse source) Sumber pencemar point source misalnya knalpot mobil, cerobong asap pabrik, dan saluran limbah industri. Pencemar yang berasal dari point source bersifat lokal. Efek yang ditimbulkan dapat ditentukan berdasarkan karakteristik spasial kualitas air.
Volume pencemar dari point source biasanya relatif tetap. Sumber pencemar non - point source bersifat menyebar dalam jumlah yang banyak Misalnya limpasan dari daerah pemukiman dan domestik dan limpasan dari daerah perkotaan
(Effendi, 2003).
Bahan pencemar (polutan) adalah bahan-bahan yang bersifat asing
bagi alam atau bahan yang berasal dari alam itu sendiri yang memasuki suatu
tatanan ekosistem sehingga mengganggu peruntukan ekosistem tersebut.
Berdasarkan cara masuknya ke dalam lingkungan, polutan dikelompokkan
menjadi dua, yaitu polutan alamiah dan polutan antropogenik. Polutan alamiah
adalah polutan yang memasuki suatu lingkungan (misalnya badan air) secara
alami, misalnya akibat letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, dan
fenomena alam yang lain. Polutan yang memasuki suatu ekosistem secara
alamiah sukar dikendalikan. Polutan antropogenik adalah polutan yang masuk ke
badan air akibat aktifitas manusia, misalnya kegiatan domestik (rumah tangga),
kegiatan urban (perkotaan), maupun kegiatan industri. Intensitas polutan
antropogenik dapat dikendalikan dengan cara mengontrol aktifitas yang
menyebabkan timbulnya polutan tersebut (Effendi, 2003).
Menurut Effendi (2003) polutan yang memasuki perairan terdiri atas
polutan, maka kombinasi pengaruh yang ditimbulkan oleh beberapa jenis polutan
tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga sebagai berikut :
1. Additive; pengaruh yang ditimbulkan oleh beberapa jenis polutan merupakan penjumlahan dari pengaruh masing-masing polutan. Misalnya, pengaruh
kombinasi zinc dan kadmium terhadap ikan
2. Synergism; pengaruh yang ditimbulkan oleh beberapa jenis polutan lebih besar daripada penjumlahan pengaruh dari masing-masing polutan. Misalnya ,
pengaruh kombinasi copper dan klorin atau pengaruh kombinasi copper dan surfaktan
3. Antagonism; pengaruh yang ditimbulkan oleh beberapa jenis polutan saling mengganggu sehingga pengaruh secara kumulatif lebih kecil atau mungkin
hilang. Misalnya pengaruh kombinasi kalsium dan timbal atau zinc atau
aluminium.
Rao (1991) dalam (Hefni, 2003) mengelompokkan bahan pencemar di
perairan menjadi beberapa kelompok, yaitu :
1. Limbah yang menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut
Semua limbah yang dioksidasi, terutama limbah domestik, termasuk
dalam kategori limbah penyebab penurunan kadar oksigen terlarut (oxygen demanding waste). Oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup organisme pada ekosistem perairan. Kadar oksigen terlarut di perairan dipengaruhi oleh
proses aerasi, fotosintesis, respirasi dan oksidasi limbah. Aerasi adalah proses
transfer oksigen dari atmosfer ke perairan melalui proses difusi. Apabila kadar
oksigen terlarut di perairan mencapai saturasi dan berada dalam kesetimbangan
dengan kadar oksigen di atmosfer maka proses aerasi tidak akan berlangsung.
Transfer oksigen dari udara ke dalam air berlangsung apabila kadar oksigen
pada badan air belum mencapai tingkat jenuh (saturasi), dan sebaliknya. Pada
siang hari, proses fotosintesis menghasilkan oksigen di perairan. Sebaliknya,
pada malam hari oksigen justru dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk
keperluan respirasi. Penurunan kadar oksigen di perairan juga diakibatkan oleh
keberadaan limbah organik yang membutuhkan oksigen untuk melakukan
perombakan atau dikenal dengan istilah dekomposisi (Anonim, 2007).
2. Limbah yang mengakibatkan timbulnya penyakit
Air mudah tercemar oleh mikroorganisme berbahaya (patogen) yang
masuk melalui limbah. Berbagai metode untuk mengidentifikasi bakteri patogen
bakteri patogen membutuhkan waktu dan biaya yang besar, sehingga penentuan
grup bakteri coliform dianggap sudah cukup baik dalam menilai tingkat higienitas
perairan. Escherichia coli adalah salah satu bakteri coliform total tidak berbahaya yang ditemukan dalam tinja manusia. Keberadaan E. coli secara berlimpah menggambarkan bahwa perairan tersebut tercemar oleh kotoran manusia, yang
mungkin juga disertai dengan cemaran bakteri patogen.
3. Limbah yang merupakan senyawa organik
Bahan organik baik yang alami maupun sintesis masuk ke badan air,
sebagai hasil dari aktifitas manusia. Penyusun utama bahan organik biasanya
berupa polisakarida (karbohidrat), polipeptida (protein), lemak (fats), asam nukleat (nucleid acid). Setiap bahan organik memiliki karakteristik fisika, kimia, dan toksisitas yang berbeda. Limbah organik juga mengandung bahan-bahan
organik sintesis yang toksik. Beberapa contoh bahan organik yang bersifat toksik
terhadap organisme akuatik adalah minyak, fenol, pestisida, surfaktan, dan
polychlorinated biphenyl (PCBs). Berbeda dengan limbah organik alami yang relatif mudah diurai secara biologis, senyawa organik sintetik pada umumnya
tidak dapat diurai secara biologis (non biodegradable). Senyawa organik sintesis juga bersifat persisten atau bertahan dalam waktu yang lama di dalam badan air
serta bersifat kumulatif. Bahan buangan organik pada umumnya berupa limbah
yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme, sehingga hal ini
dapat mengakibatkan semakin berkembangnya mikroorganisme dan mikroba
patogen pun ikut juga berkembang baik dimana hal ini dapat mengakibatkan
berbagai macam penyakit. Limbah pertanian dari penggunaan pestisida jenis
klorotalonil maupun pestisida golongan klor-organik lainnya, susah larut dalam
air. Senyawanya dapat berikatan dengan senyawa organik lain yang bersifat
asam (Manuaba ,2007).
4. Limbah yang merupakan senyawa anorganik dan mineral
Senyawa anorganik terdiri atas logam dan logam berat yang pada
umumnya bersifat toksik. Davis dan Cornwell (1991) dalam Hefni (2003)
mengemukakan, bahan anorganik yang dianggap toksik adalah arsen (As),
barium (Ba), kadmium (Cd), kromium (Cr), timbal (Pb), air raksa (Hg), selenium
(Se) dan perak (Ag). Senyawa anorganik dapat berasal dari limbah domestik,
dan industri. Limpasan perkotaan merupakan sumber utama timbal (Pb) dan
anorganik pada umumnya berupa limbah yang tidak dapat membusuk dan sulit
didegradasi oleh mikroorganisme. Dalam perairan, buangan anorganik
menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah ion logam di dalam air, sehingga
hal ini dapat mengakibatkan air menjadi bersifat sadah, karena mengandung ion
kalsium (Ca) dan ion yang bersifat toksik.
5. Sedimen
Sedimen meliputi tanah dan pasir yang masuk ke badan air akibat
erosi atau banjir. Pada dasarnya, sedimen tidak bersifat toksik. Sedimen berupa
bahan-bahan tersuspensi di dalam air. Keberadaan sedimen dalam badan air air
mengakibatkan terjadinya peningkatan kekeruhan perairan, yang selanjutnya
menghambat penetrasi cahaya dan transfer oksigen dari atmosfer ke perairan.
Peningkatan kekeruhan akan menghambat daya lihat (visibilitas) dan
terganggunya kehidupan organisme akuatik.
6. Minyak
Minyak tersebar di perairan dalam bentuk terlarut, lapisan film yang
tipis yang terdapat di permukaan, emulsi dan fraksi yang terserap. Di perairan,
interaksi dari bentuk minyak ini sangat kompleks, dipengaruhi oleh nilai specific gravity, titik didih, tekanan permukaan, viskositas, kelarutan dan penyerapan. Kadar minyak mineral dan produk-produk petroleum yang diperkenankan
terdapat dalam air minum berkisar antara 0,01 – 0,1 mg/liter. Kadar yang
melebihi 0,3 mg/liter bersifat toksik terhadap beberapa jenis ikan air tawar
(UNESCO/WHO/UNEP, 1992).
2.2.2 Penentuan Beban Pencemaran
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 1 tahun
2010 tentang tata laksana pengendalian pencemaran air, metode untuk
menentukan beban pencemaran dikelompokkan berdasarkan sumber
pencemar tertentu (point source) dan sumber tak tentu (non point source).
Penentuan beban pencemar dari sumber tertentu (point source) berdasarkan data primer dari lapangan maupun data sekunder hasil pemantauan
instansi yang berwenang. Data kuantitas dan kualitas pencemar air dari sumber
tertentu dievaluasi dan dikaji dengan menggunakan metode estimasi sebagai
berikut :
I,j = Ci x V x OpHrs/1.000.000
I,i = Besar beban/emisi pencemar atau parameter i, kg/tahun
C,i = Konsentrasi jneis pencemar i dalam buangan air limbah, mg/l
(data pemantauan lapangan)
V = Laju alir buangan air limbah liter/jam
OpHrs =Jumlah jam operasi per tahun, jam/tahun
1 000. 000 = faktor konversi, mg/kg
(Sumber : Permen LH no 01 tahun 2010)
Beban pencemar dari sumber tak tentu (non point source) diperkirakan dengan terlebih dahulu menentukan faktor emisi yang bersifat spesifik untuk
masing-masing kategori kegiatan. Metode estimasi untuk setiap kelompok
kegiatan yang menghasilkan air limbah kategori sumber tak tentu (non Point source) sebagai berikut :
Kegiatan dan penggunaan barang konsumsi menghasilkan emisi berupa :
a. Emisi polutan dari proses sanitasi dan pencucian
b. Emisi yang berkaitan dengan kepadatan penduduk
Hasil penelitian Irianto dan Iskandar, 2007 emisi air limbah domestik seperti
Tabel 1
Tabel 1. Emisi air limbah domestik
No Parameter Faktor Emisi (gr/hari)
1. TSS 38
Sumber : Irianto dan Iskandar, 2007 dalam Puslitbang SDA
Anonim (2010) mengatakan bahwa emisi BOD untuk limbah domestik seperti
Tabel 2. Klasifikasi emisi BOD di Indonesia
No Daerah Klasifikasi Rentang Beban
gr BOD/orang/hari
Sumber : Balai Lingkungan Keairan Pusat Litbang Sumber Daya air
Beban pencemar dapat diestimasi dengan beberapa rumus berikut :
(1) Beban pencemar = faktor emisi x kepadatan populasi x rasio ekivalen kota
(Iskandar, 2007)
(2) Beban pencemar = jumlah penduduk x x faktor emisi (tabel 1)
(Anonim, 2010)
(3) Beban pencemar = Luas daerah pemukiman x kepadatan penduduk x
faktor emisi
(PerMenLH no 01 tahun 2010)
Keterangan:
: koefisien transfer beban, (0,3 – 0,8), yang merupakan pendekatan dari estimasi
air limbah yang masuk ke sungai berdasarkan jarak pemukiman terhadap sungai.
Asumsi yang digunakan adalah semakin dekat dengan sungai semakin besar
peluang membuang limbah langsung ke sungai. Sebaliknya semakin jauh dari
sungai masyarakat semakin rendah peluang membuang limbah secara langsung
ke sungai (Kurniawan, 2003)
Sumber pencemar kegiatan pertanian berasal dari sisa pemakaian pupuk
dan jerami yan merupakan sisa hasil panen. Pupuk yang dipakai per Ha sawah
terdiri dari komposisi 200 kg Nitrogen, 100 kg Phospor, 100 kg kalium, selain itu
digunakan hanya 80 % yang efektif diserap, sedangkan sisanya 20% terbawa
aliran terutama pada saat musim hujan. Jerami padi merupakan produksi
sampingan pada saat musim panen. Setiap ha sawah menghasilkan 3 ton jerami
padi, dan setiap tonnya menghasilkan 30 kg BOD. Emisinya diperkirakan
sebanyak 20% dari jerami tersebut terbawa ke dalam aliran sungai (Anonim,
2010). Emisi dari kegiatan pertanian untuk setiap parameter dapat dilihat pada
Tabel 3.
Tabel 3. Emisi dari kegiatan pertanian
Sumber : Balai Lingkungan Keairan Pusat Litbang Sumber Daya air
2.3 Kapasitas Asimlasi
Kapasitas asimilasi didefinisikan sebagai kemampuan badan air dalam
menerima beban pencemar, tanpa menyebabkan terjadinya penurunan kualitas
air yang ditetapkan sesuai peruntukannya (Quano, 1993). Kapasitas asimilasi
atau kapasitas homeostatis merupakan kemampuan badan air dalam menetralisir
atau membersihkan sendiri (self purification) terhadap beban pencemar sampai kondisi tidak tercemar.
Sungai dikatakan berada dalam kondisi tercemar, apabila mengalami
perubahan karakteristik fisik, kimia dan biologi. Perubahan karakteristik disebabkan adanya tekanan ekologis yang berkaitan dengan fungsi sungai
sebagai badan air penerima limbah. Pada awalnya limbah yang masuk ke sungai
dapat secara alami dinetralisir sampai pada kondisi tidak tercemar. Namun apabila konsentrasi limbah yang masuk lebih besar daripada kemampuan sungai
dalam menetralisir lmbah, maka akan terjadi pencemaran. Bahan pencemar
(polutan) dapat berupa gas, bahan-bahan terlarut, dan partikulat. Pencemar
memasuki badan air dengan berbagai cara, misalnya melalui atmosfer, tanah,
No Jenis Pertanian Parameter Limbah Pertanian
BOD N P TSS Pestisida
Kg/ha/musim tanam ;/ha/musim tanam
1. Sawah (jerami padi yang membusuk
18 20 10 0,04 0,16
2. Palawija (humus yang terkikis) 9 10 5 2,4 0,08
3. Perkebunan lain (humus yang terkikis)
limpasan (run off) pertanian, limbah domestik dan perkotaan, pembuangan limbah industri, dan lain-lain (Effendi, 2003).
Konsentrasi dari partikel polutan yang masuk ke perairan akan
mengalami tiga macam fenomena yaitu pengenceran (dilution), penyebaran (dispersion) dan reaksi penguraian (decay of reaction). Pengenceran terjadi pada arah vertical ketika air limbah sampai di permukaan perairan, sedangkan
penguraian merupakan pengenceran pada permukaan perairan ketika limbah
tercampur karena arus (Quano, 1993).
Metode yang digunakan untuk menentukan nilai kapasitas
asimilasi dikemukakan oleh Quano (1993), sebagai berikut :
- Metode hubungan antara kualitas air dan beban pencemaran
Kapasitas asimilasi ditentukan dengan cara memplotkan nilai-nilai kualitas air
suatu perairan pada kurun waktu tertentu dengan beban pencemaran dalam
suatu grafik. Selanjutnya direferensikan dengan nilai baku mutu air kelas II
Peraturan Pemerintah no 82 tahun 2001.
- Metode arus bermuatan partikel
Kapasitas asimilasi ditentukan dengan cara membandingkan konsentrasi limbah
dengan konsentrasi air sungai yang menerima limbah, dengan memperhitungkan
kecepatan aliran, perbedaan konsentrasi dan debit sungai.
- Metode penurunan oksigen dari streeter dan phelps
Kapasitas asimilasi ditentukan dengan cara mengamati pengurangan nilai
oksigen terlarut. Faktor yang diperhitungkan dalam metode ini antara lain waktu
perjalanan limbah di sungai.
Kapasitas asimilasi juga merupakan kemampuan sungai dalam menerima
bahan organik bersifat mudah terurai secara biologis (biodegradable) yang banyak membutuhkan oksigen untuk proses dekomposisi, sehingga menurunkan
kadar oksigen dalam badan air. Sungai mampu melakukan asimilasi
penambahan oksigen dari atmosfer melalui proses reaerasi sehingga kandungan
oksigen terlarut dalam perairan mencukupi untuk kehidupan organisme (Hasham,
2004).
Ada dua konsep yang berhubungan dengan kapasitas asimilasi
Penentuan kapasitas asimilasi sangat sulit karena ada beberapa sifat dari
organisme yang berbeda. Misalnya organisme yang bersifat mudah terurai
secara biologis dan yang sulit terurai secara biologis. Penentuan kapasitas
asimilasi sangat penting sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan
pengendalian pencemaran air (Lee et al. 2008).
2. 4 SUNGAI CIDURIAN
2.4.1 Kondisi geografis Daerah Penelitian
Provinsi Banten merupakan lokasi keberadaan Sungai Cidurian. Agar
diperoleh gambaran tentang daerah penelitian, berikut ini diuraikan tentang
kondisi umum wilayah yang dilalui Sungai Cidurian.
Secara geografis letak Sungai Cidurian antara 106°00’30” BT dan
6°40’ LS. Luas Sungai Cidurian ± 815 km dengan panjang sungai 81,5 km,
mempunyai dua anak sungai, yaitu Sungai Cimandaya dan Sungai Cibeureum
(Anonim, 2010).
Wilayah aliran Sungai Cidurian ini dibatasi oleh Laut Jawa di bagian
Utara , wilayah aliran Sungai Ciujung di bagian Barat, wilayah aliran Sungai
Cisadane-Ciliwung di bagian timur, wilayah aliran sungai Cibaliung-Cibareno di
bagian selatan. Sungai Cidurian mengalir dari sumber mata air yang berada di
komplek G. Gede ke Laut Jawa dengan melewati empat kabupaten yaitu
Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten
Tangerang. Sungai Cidurian ini mempunyai tiga anak sungai utama, yaitu Sungai
Cidurian Hulu, Sungai Cibeureum dan Sungai Cipangaur terletak pada daerah
Cilaang dan pertemuan sungai Cidurian dan Sungai Cibeureum pada daerah
Cikande.
Topografi Sungai Cidurian yang merupakan daerah dataran dengan
kemiringan antara 0,00012 – 0,00025 (satuan ) terletak pada daerah muara
sungai sampai dengan daerah pertemuan dengan Cibeureum dan Sungai
Cidurian dan untuk topografi yang landai ke arah terjal (daerah pegunungan)
terletak pada daerah pertemuan Sungai Cidurian dengan Sungai Cipangaur
sampai ke arah hulu dengan kemiringan 0,0004 – 0,0007 (Anonim, 2009).
Lahan yang ada di kiri kanan Daerah Aliran Sungai Cidurian secara
umum merupakan daerah perbukitan, perkebunan, hutan, sawah, pemukiman,
industri dan sebagainya. Jenis lahan yang ada sangat dipengaruhi oleh
Secara rinci, lahan yang ada di kiri kanan sungai dapat diuraikan
sebagai berikut :
a. Daerah bagian hulu sungai : hutan, perkebunan, galian golongan C (pasir),
persawahan, perkotaan, pemukiman
b. Daerah bagian tengah sungai : kebun, persawahan, pemukiman, galian golongan
C (pasir), jaringan irigasi, industri
c. Daerah bagian hilir sungai : kebun, pemukiman, galian golongan C (pasir),
industri, perkotaan, tambak
2.4.2 Peuntukan Sungai Cidurian
Berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 34 tahun 1996, dari hulu Sungai Cidurian beserta anak-anak sungainya
sampai dengan muara sungai Cidurian di Desa Tenjoayu Kec. Tirtayasa Kab.
Serang, termasuk golongan B, C, dan D, yaitu untuk pemanfaatan air baku air
minum, perikanan, peternakan, pertanian, dll.
Berdasarkan Peraturan pemerintah No 82 th 2001, tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air, Sungai Cidurian
masuk dalam klasifikasi mutu air kelas II, III dan IV, yaitu untuk peruntukkan
prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, pertanian dan
peternakan.
Pemanfaatan lahan di DAS Cidurian terbesar adalah sebagai kawasan
budi daya pertanian. Hanya sebagian kecil yang merupakan kawasan lindung,
berada pada wilayah Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Menurut data dari
Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Banten, Sungai Cidurian
dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan irigasi. Perusahaan Daerah Air Minum
memanfaatkan Sungai Cidurian untuk penyediaan kebutuhan air bersih bagi
masyarakat.
2.4.3. Debit Sungai Cidurian
Debit maksimum bulanan Sungai Cidurian yang diamati di Stasiun
Bendung Ranca Sumur mulai dari tahun 2001 sampai tahun 2010 sebesar
602,189 m³/detik yang terjadi pada Bulan Mei tahun 2001 dan debit minimum
2010). Rasio terbesar antara debit rata-rata pada saat musim hujan terjadi pada
tahun 2007 yaitu 1 : 2,90.. Debit rata-rata bulanan Sungai Cidurian yang diamati
di stasiun pengamatan Bendung Ranca Sumur dapat dilihat pada Lampiran 9.
Debit Sungai Cidurian bagian hulu sebesar 272,9 m³/detik dan bagian hilir 536,61
m³/detik berdasarkan data dari Status Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang
(Anonim, 2010).
2.4.4 Permasalahan di Sungai Cidurian
Permasalahan utama yang dialami Sungai Cidurian adalah
pencemaran air sungai dan kerusakan DAS Cidurian. Indikator kerusakan DAS
Cidurian adalah adanya fluktuasi debit yang sangat tinggi antara musim hujan
dan musim kemarau. Selain itu adanya lahan kritis di daerah hulu yang
mengakibatkan terjadinya erosi dan sedimentasi di daerah hilir.
Pencemaran di Sungai Cidurian disebabkan oleh pencemaran limbah
domestik, industri, pertanian dan peternakan. Sumber polutan dari domestik
adalah aktifitas penduduk yang memanfaatkan Sungai Cidurian untuk MCK.
Jumlah penduduk di DAS Cidurian berjumlah ± 1.656.769 orang (BPS Banten
2010) orang. Sumber polutan dari industri adalah aktifitas perusahaan yang air
limbahnya belum memenuhi Baku Mutu Lingkungan. Berdasarkan data dari
BLHD Provinsi Banten, tahun 2009 (Laporan Pemantauan Kualitas Sungai
Cidurian), industri yang membuang limbahnya di Sungai Cidurian adalah ; PT.
Tunas Sumber Idea Kreasi Kimia, PT. Kulit Murni Asia Tenggara, PT. Frans
Putratex, PT. Sari Daya Plasindo, , PT. Shinta Woo Sung, PT. Panca Plaza Indo
Textile, PT. Singlong Brother Industri, PT. Eka Nindya Karsa, Pt. Platinum Resin,
PT. Mariza Sari Murni.
Hasil pemantauan dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Serang, kualitas air Sungai Cidurian cenderung mengalami
penurunan, dari 18 parameter yang dipantau, empat parameter berada diatas
baku mutu, yaitu COD, nitrit, H₂S dan kekeruhan. Hasil pemantauan dari BLHD
Provinsi Banten, 2009, diketahui beberapa parameter yang melebihi baku mutu
berdasarkan PP 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air kelas II yaitu COD, BOD, Zn, E coli dan total coli. Kelas air Sungai Cidurian adalah kelas III dan IV.
2.5 Pengendalian Pencemaran Air Sungai
Manajemen pengelolaan kualitas air dapat dilakukan dengan beberapa
pendekatan yaitu :
1. Pendekatan dari sumber titik (point source) melalui teknologi pengolahan limbah Pemerintah melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup, menetapkan Baku
Mutu Bagi Limbah untuk berbagai kegiatan, mulai dari industri, rumah sakit,
perhotelan. Baku Mutu yang dimaksud dalam KepMenLH No 55 Tahun 1995,
tentang baku mutu limbah industri.
2. Pendekatan dari pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
menurut PP 82 tahun 2001, antara lain penetapan status mutu air sesuai dengan
Pasal 14 (1) PP 82 Tahun 2001. Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan: a.
kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air; b. kondisi baik,
apabila mutu air memenuhi baku mutu air. dan pedoman penentuan status mutu
air ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Sejalan dengan hal diatas
Pasal 15 (1) PP 82 Tahun 2001. Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi
cemar, maka Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan upaya penanggulangan
pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
(2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik, maka pemerintah dan
pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan
masing-masing mempertahankan dan meningkatkan kualitas air, pemantauan
kualitas air sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran menyatakan bahwa
untuk menjamin kualitas air yang dinginkan sesuai peruntukannya agar tetap
dalam kondisi alamiahnya, maka perlu dilakukan upaya pengelolaan kualitas air.
3. Pendekatan daya tampung beban pencemaran dengan memadukan antara
potensi beban pencemaran dari berbagai sumber dengan kualitas air.
Dasar hukum penetapan daya tampung beban pencemaran, diatur dalam
Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, dalam pasal 1,8,12,16,17 dan 19. Secara tegas disebutkan
dalam undang-undang tersebut, pentingnya pertimbangan daya tampung dan
daya dukung lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan
Pemerintah no 82 Tahun 2001 pasal 20 dan 23 juga mengatur penetapan daya
tampung, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup no 110 Tahun 2003 tentang
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Waktu dan lokasi penelitian
Penelitian dilakukan mulai Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2011
Lokasi penelitian adalah Sungai Cidurian Provinsi Banten yang meliputi 3 sub
daerah aliran sungai (DAS) yaitu sub DAS Cidurian Hulu, sub DAS Cidurian Hilir
serta sub DAS Cibereum.
3.2 Jenis dan sumber data
zData yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data
sekunder. Data primer berupa data pengukuran kualitas fisik, kima dan biologis
yang diperoleh langsung di lapangan.
Data sekunder diambil dari berbagai sumber, seperti hasil penelitian
terdahulu, laporan ataupun kajian dari berbagai instansi yang berkaitan dengan
Sungai Cidurian. Instansi tempat pengambilan data meliputi :
1. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten
2. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Provinsi Banten
3. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciujung, Cidurian, Cidanau
4. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten
5. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.
3.3 Metode Sampling
A. Pengambilan sampel kualitas air
Tujuan pengambilan sampel adalah untuk mendapatkan gambaran tentang sifat
fisik, kimia dan biologi Sungai Cidurian. Penentuan lokasi dilakukan secara
(purposive). Lokasi sampling (Gambar 2) ditetapkan berdasarkan titik sampling yang mewakili kondisi kualitas air di DAS Cidurian. Lokasi sampling diambil
berdasarkan wilayah sungai yang representative, di titik 6 titik pantau yang
lokasinya tersebar di setiap sub DAS. Lokasi dimaksud adalah Sub DAS Cidurian
Hulu, Sub DAS Cibereum dan Sub DAS Cidurian Hilir. Adapun pembagian lokasi
Tabel 4 Pembagian lokasi sampling berdasarkan Sub DAS
Sub DAS Kabupaten/Kota Segmen Titik Pantau
Cidurian Hulu Kab. Lebak 1 Kopo Maja
Cidurian Hulu Kab. Lebak 2 Bendung Ranca Sumur
Cibereum Kab. Serang 3 Cikande Hulu Asem
Cidurian Hilir Kab. Serang 4 Cikande Hilir Parigi
Cidurian Hilir Kab. Serang 5 Kresek
Cidurian Hlir 6 Kronjo
Pengambilan sampel air berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)
Pengambilan sampel air dilakukan secara komposit.
B. Penentuan parameter sampling
Parameter fisika, kimia, biologi yang diukur dalam penelitian didasarkan pada
parameter kelas I Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001, yaitu air yang
digunakan untuk air baku air minum. Penentuan analisa kualitas air
menggunakan metode seperti pada Tabel 5.
Tabel 5 Metoda analisa kualitas air
No Parameter Metode Analisa
Fisik
1 Temperatur SNI 06-2413-1991 2 Residu Terlarut (TDS) SNI 06-6989.27-2005 3 Residu Tersuspensi (TSS) SNI 06-6989.3-2004
Kimia Anorganik
4 pH SNI 06-6989.11-2004
5 DO SNI 06-6869.14-2004
6 BOD SNI 06-2503-1991
7 COD SNI 06-6989.15-2004
8 Total Phosphat sebagai P SNI 06-2483-1991
9 NO3-N SNI 06-2480-1991
10 Amoniak Bebas (NH3-N) SNI 06-2479-1991 11 Kadmium (Cd) SNI 01- 2354.5-2006
12 Khrom (Cr) SNI
20 Detergen sebagai MBAS SNI 06-6989.51-2005 21 Fenol Std Method 5530 D
Mikrobiologi
22 E. coli SNI 06-4158-1996
Gambar 2 Lokasi sampling
Keterangan : 1. Kronjo 2. Kresek
3. Cikande Parigi 4. Cikande Asem
5. Bendung Ranca Sumur 6. Kopo Maja
1
3 4
5
C. Sampling logam berat untuk sedimen atau perairan dasar dilakukan di empat titik
sampling seperti pada Tabel 6.
Tabel 6 Lokasi sampling logam berat
SUB DAS Lokasi Keterangan
Cidurian Hulu Bendung Ranca
Sumur
Sebelum Industri
Cibereum Cikande Hilir
Perbatasan
Di depan Industri
Cidurian Hilir Di depan Industri PT. Frans Putratex
Cidurian Hilir Kresek Di Hilir
D. Waktu sampling di lapangan.
Pengambilan sampel dilakukan sebanyak enam kali dengan interval waktu 1
bulan, mulai Bulan Oktober sampai Bulan Desember 2011.
3.4 Metode Analisis Potensi Beban Pencemaran
Analisis kontribusi beban pencemaran, ditujukan untuk mengetahui
potensi beban pencemar dari berbagai sumber yaitu, sumber tertentu (point source) dan sumber tak tentu (domestik dan pertanian). Metode yang digunakan antara lain :
1. Beban pencemar dari sumber tertentu (point source)
Metode perhitungan langsung menggunakan data hasil pemantauan, misalnya
untuk (outlet air limbah industri, instalasi pengolah air limbah komunal domestik).
Variabel yang harus diamati seperti dalam matrik dibawah ini :
- Nama perusahaan
- Jenis kegiatan
- Kapasitas produksi
- Debit air limbah yang dibuang (m3/hari)
- Nama anak sungai tempat pembuangan akhir
- Titik koordinat outlet IPAL
- Karakteristik limbah
- Waktu operasi per tahun (jam/tahun)
Perhitungan beban pencemar menggunakan rumus berikut :
I,i = Ci x V x Ophrs/1000000
keterangan
I,i = Besar beban/emisi pencemar atau parameter i, kg/tahun
C,i = Konsentrasi jneis pencemar i dalam buangan air limbah, mg/l
(data pemantauan lapangan)
V = Laju alir buangan air limbah liter/jam
OpHrs =Jumlah jam operasi per tahun, jam/tahun
1 000. 000 = faktor konversi, mg/kg
2. Beban pencemar dari sumber tak tentu (non point source)
Beban pencemar dari sumber tak tentu (non point source) dititikberatkan pada kegiatan domestik dan pertanian.
Metode penentuan beban pencemar dari sumber tak tentu (non point source) menggunakan alat bantu PETA GIS (geographic information system) dan melalui pendekatan faktor emisi. Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemar Air,
besaran dari sumber pencemar air tak tentu diperkirakan dengan terlebih dahulu
menentukan faktor emisi yang bersifat spesifik untuk masing-masing kategori
kegiatan.
Beberapa informasi yang dapat diperoleh dari PETA GIS meliputi :
- Peta penggunaan lahan untuk menentukan beban pencemaran dari kegiatan
pertanian
- Peta Sub DAS untuk menentukan kepadatan penduduk di setiap Sub DAS dan
menentukan pola penyebaran penduduk di sepanjang DAS Cidurian.
Kelompok kegiatan dari sumber tak tentu yang potensial menghasilkan air limbah
antara lain :
a. Kegiatan domestik
b. Kegiatan pertanian dan peternakan
Metode yang digunakan untuk mengetahui beban pencemaran dari
PBP = jumlah penduduk x faktor emisi x
Keterangan
PBP : Potensi beban pencemaran
Faktor emisi : (dapat dilihat dalam tabel faktor emisi limbah
domestik tabel 1 dan faktor emisi limbah pertanian
tabel 3)
: nilai koefisien yang menggambarkan jarak
pemukiman penduduk terhadap sungai.
Koefisien merupakan nilai yang merepresentatifkan dampak air limbah
terhadap beban pencemaran sungai. Diasumsikan semakin dekat penduduk
yang tinggal dekat sungai, semakin besar kontribusinya terhadap beban
pencemaran sungai, sehinnga nilai koefisien nya juga semakin besar. Untuk mendapatkan nilai , digunakan metode GIS
Beberapa data yang dapat diperoleh dari GIS meliputi :
1. Data Peta Kepadatan Penduduk
2. Data Pola Penyebaran Penduduk terhadap sungai
3. Data buffer (pembatasan) berdasarkan jaraknya terhadap sungai, sehingga
diperoleh nilai (Kurniawan, 2003):
Jarak 0 - 100 m ; nilai = 1
Jarak 100 m - 500 m ; nilai = 0,85
Jarak 500 m – 1 km ; nilai = 0,5
Jarak 1 km ; nilai = 0,3
Kontribusi beban pencemar dari kegiatan domestik, dilakukan pada setiap sub
DAS, yang meliputi sub DAS Cidurian Hulu, sub DAS Cibereum, dan sub DAS
Cidurian Hilir. Wilayah administrasi untuk masing-masing sub DAS diketahui
dengan menggunakan PETA GIS.
Beban Pencemar untuk parameter BOD, N,P, TSS dari kegiatan pertanian
dihitung berdasarkan produksi per luas tanam per musim tanam (kg/ha/musim
tanam). Sesuai dengan persamaan :
Beban pencemar = luas lahan x faktor emisi x musim tanam per tahun
Keterangan
Luas lahan : luas lahan untuk sawah, palawija dan perkebunan
dengan metode GIS (geographic information system)
Satuan ha
Faktor emisi : Merupakan emisi dari kegiatan penggunaan lahan
untuk sawah, palawija dan perkebunan lain (tabel
3)
Musim tanam
per tahun
: Jumlah musim tanam dalam satu tahun
Misalnya untuk padi 3 kali dalam satu tahun
3. Parameter yang digunakan untuk menentukan beban pencemaran merupakan
parameter yang melebihi baku mutu, dari hasil analisa kualitas air.
4. Penentuan kontribusi beban pencemar yang termasuk kategori sumber tertentu
dan sumber tak tentu untuk setiap parameter yang melebihi baku mutu.
5. Beban Pencemaran dari kegiatan domestik dibatasi hanya untuk parameter BOD, COD, TSS, dan E. coli
6. Beban Pencemaran dari kegiatan pertanian dibatasi hanya untuk parameter
BOD, TSS
7. Inventarisasi dan rekapitulasi data beban pencemaran meliputi :
a. Beban pencemaran dari sumber tertentu (point source): sektor industri
b. Beban pencemaran dari sumber tak tentu (non point source): sektor domestik dan pertanian.
8. Analisis data beban pencemaran meliputi :
a. Analisis terhadap DAS (daerah aliran sungai) yang meliputi: sub DAS Cidurian
Hulu, sub DAS Cibereum, serta sub DAS Cidurian Hilir
b. Analisis terhadap wilayah administratif yang dilalui DAS Cidurian meliputi
Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang serta Kabupaten
Tangerang
c. Analisis terhadap sektor kegiatan yang berkontribusi terhadap beban
pencemaran dari sumber domestik dan pertanian
d. Analisis terhadap parameter dominan yang ada di setiap sub DAS maupun
wilayah administratif.
3.5 Metode Analisis Kapasitas Asimilasi Beban Pencemaran
Nilai Kapasitas asimilasi didapatkan dengan cara membuat grafik
hubungan antara konsentrasi masing-masing parameter limbah di Sungai
Cidurian dengan total beban pencemaran yang masuk ke sungai. selanjutnya
dianalisa dengan memotongkan garis status peruntukkan air sesuai Peraturan
Pemerintah No. 82 tahun 2001, yaitu kelas II, sebagaimana pada Gambar 3 .
Beban Pencemaran
Scatterplot of Konsentrasi parameter vs Beban Pencemaran
Gambar 3 Grafik untuk mencari kapasitas asimilasi
Nilai kapasitas asimilasi didapat dari titik perpotongan dengan nilai baku mutu
yang berlaku untuk setiap parameter. Selanjutnya dianalisis seberapa besar
peran masing-masing parameter terhadap beban pencemarannya.
Secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :
Y = f(X)
Secara matematis persamaan regresi linier dapat dituliskan sebagai berikut :
Y = a + bX
Y = nilai konsentrasi parameter
X = Beban Pencemaran
a = nilai tengah/ rataan umum
b = Koefisien regresi untuk parameter di sungai
Analisis kapasitas asimilasi beban pencemaran dilakukan dengan melihat grafik
hubungan antara konsentrasi parameter dengan beban pencemar. Jika beban
pencemaran di atas nilai kapasitas asimilasi maka perairan tercemar, atau dapat
dikatakan beban pencemaran melebihi daya tampung perairan. Kapasitas
asimilasi mempunyai nilai yang berbeda untuk masing-masing parameter