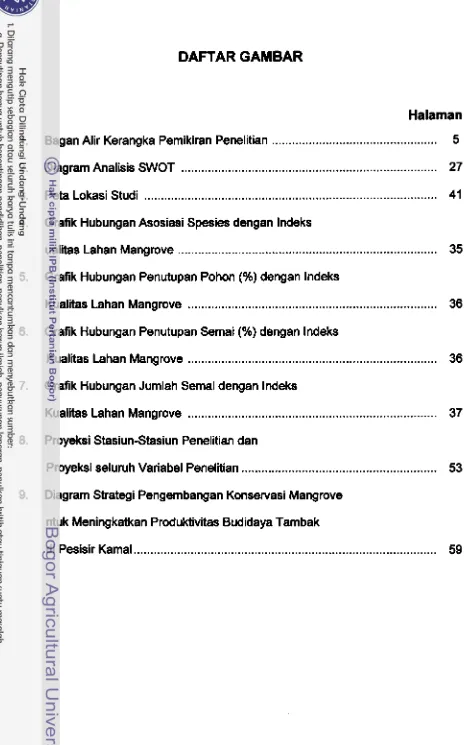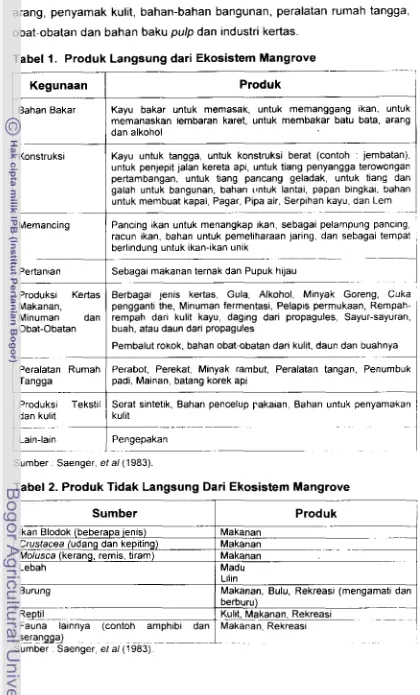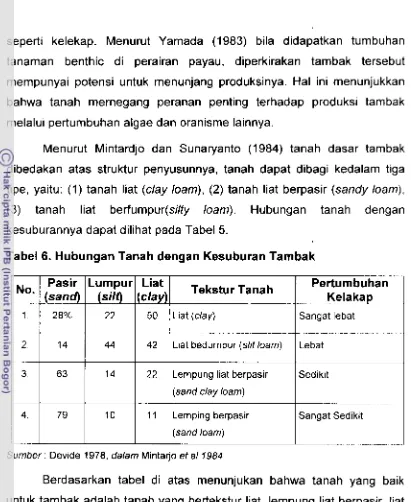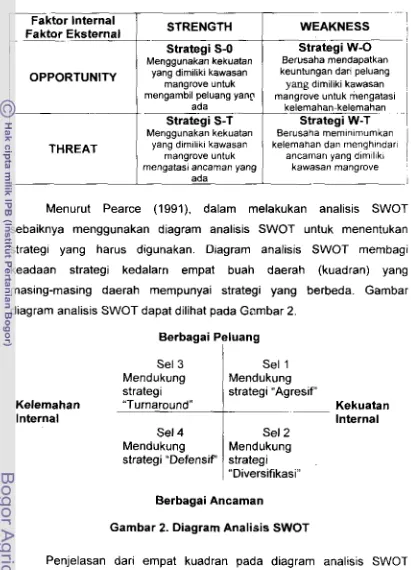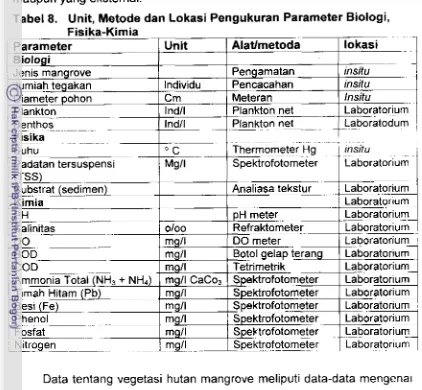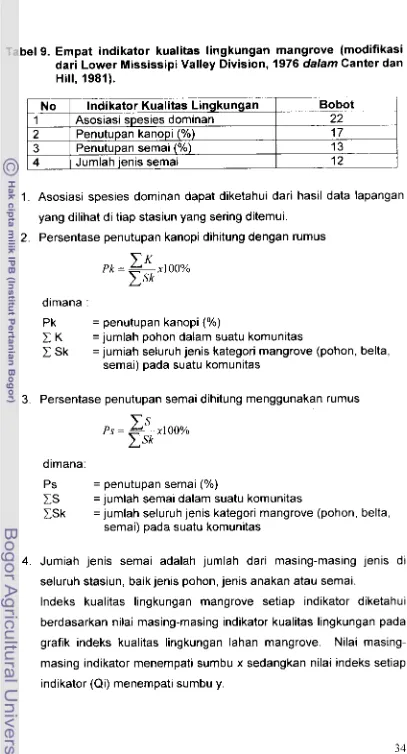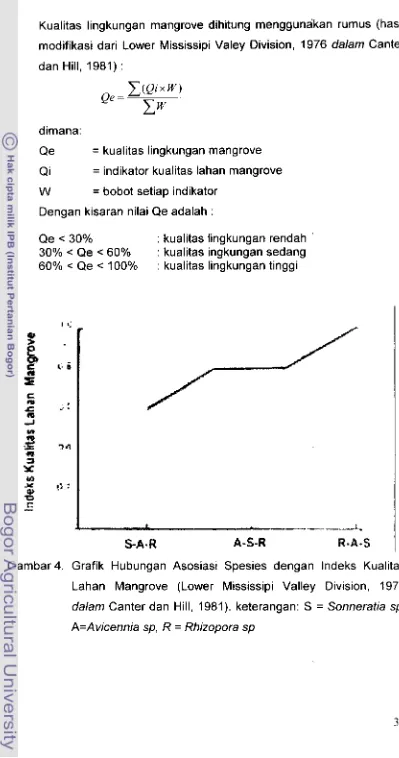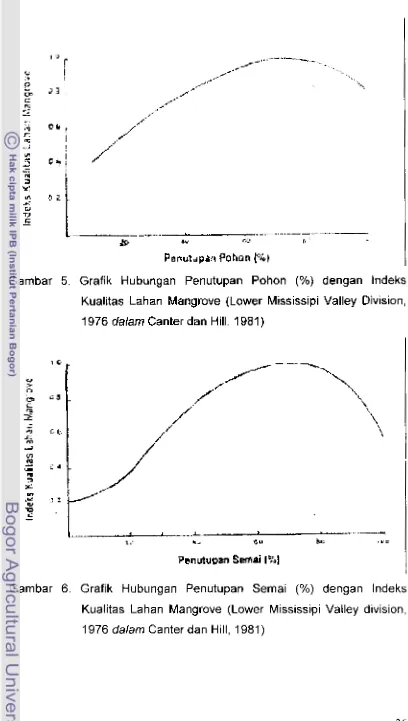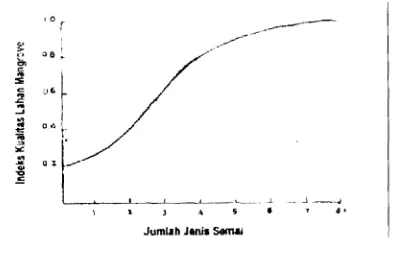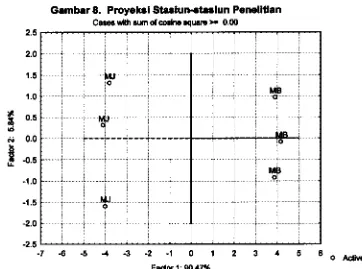KAJlAN KETERKAITAN
MANGROVE DAN
PRODUKTIVITAS
BUDIDAYA
TAMBAK DI KELURAHAN KAMAL,
JAKARTA UTARA
Oleh
:
Upik Mardamti, SP.SEKOLAH
PASCASARJANA
ABSTRAK
Upik Mardawati. Kajian Keterkaitan Mangrove dan Produktivitas Budidaya Tambak di Kelurahan Kamal, Jakarta Utara. Dibawah bimbingan DlETRlECH G. BENGEN dan KUKUH NIRMALA.
Wilayah Pesisir Kamal merupakan bagian Teluk Jakarta yang terletak di Kelurahan Kamal, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Pesisir Kamal memiliki hutan lindung mangrove yang telah banyak dikonversi menjadi peruntukkan lain seperti pembukaan lahan tambak, jalan, pemukiman dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui faktor-faktor biofisik kimia yang lebih dominant mempengaruhi produktivitas tambak ikan, kedua, untuk mengetahui
korelasi yang terjadi antara eksistensi hutan lindung mangrove dengan peningkatan atau penurunan produktivitas tambak dan
tujuan
yang ketiga, adalah untuk mengetahui strategi yang optimal untuk pengembangan rehabilitasi mangrove yang dapat diterapkan di pesisir Kamal.Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder yaitu mengenai kualitas air, vegetasi mangrove dan produktivitas tambak.
(parameter biofisik kimia, sosekbud dan kelembagaan). Data dianalisis dengan menggunakan regresi sederhana, Principle Component Analysis dan SWOT.
Hasil yang didapat adalah sebagai berikut: I) dari 21 parameter yang diuji terdapat 19 parameter yang berpengaruh nyata terhadap produktivitas tambak yaitu: suhu, salinitas, eo, bod, cod, ammoniak, pb, phenol, phospat, nitrogen, ph, tss, benthos, plankton, pasir, hat, debu,
volume ganti air dan kualitas lingkungan mangrove(Qe) ; 2) parameter
yang memiliki korelasi
sangat
erat (r=
0,999) adalah kualitas lingkungan lingkungan mangrove (Qe), nitrogen, volume ganti air, benthos, plankton dan COD; 3) strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan rehabilitasi mangrove untuk meningkatkan produktivitas budidaya tambakSURAT PERNYATAAN
Dengan
ini saya Menyatakan:KAJlAN KETERKAITAN MANGROVE DAN PRODUKTIVITAS
BUDIDAYA TAMBAK Dl KELURAHAN KAMAL,
JAKARTA UTARA
Adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan, semua sumber data dan informasi yang telah digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.
Bogor, Oktober 2004
W l A N
KETERKNTAN MANGROVE DAN PRODUKTIVITAS
BUMDAYA
TAMBAK Dl
KELURAHAN KAMAL,
JAKARTA UTARA
Uplk Mardawati, SP. @@799
Sebagai Sahh Saw Syamt Untuk Mempemleh Gelar Magkter
Satns
h k m
Bldang Pengelohan Sumbrdaya Peslsir dan LautanPada Sekolah Pascasarjana Inutltut Pertanian Bogor
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTCTUT
PERTANlAN
BOGOR
Judui Thesis
Nama N I M
: Kajian Keterkaitan Mangrove dan
Produktivitas Budidaya Tambak di
Kelurahan Karnal, Jakarta Utara
: Upik Mardawati,SP
: 99799
Disetujui,
1. Komisi Pembimbing
Dr. Ir. Kukuh Nirmala, MSc.
Ketua Ang g ota
Diketahui,
2. Ketua Program Studi 3. Dekan Sekolah Pascasarjana 1PB Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Lautan
Manuwoto, M.Sc.
Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggat 31 Agustus 1971 dari pasangan H. Abdul Gani dan Hj. Uni Sukaesih, sebagai anak kelima dari
enam bersaudara.
Pada tahun 1985 penulis lulus dari SD Negeri 01 pagi Jakarta
Barat, 1988 lulus dari SMP Negeri 45 Jakarta Barat dan pada tahun 1991
lulus dari SMU Negeri 33 Jakarta Barat. Pendidikan sarjana ditempuh di
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, lnstitut Pertanian
Bogor pada tahun 1991 hingga 1997.
Pada tahun 1999, penulis di terima di Program Studi Pengelolaan
Sumberdaya Pesisir dan Laut pada Sekolah Pascasarjana lnstitut
Bismillahirahrnannirahiim
Alharndullilah, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala lirnpahn rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan thesis ini.
Terwujudnya tulisan ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan semua pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-
besarnya dan semoga Allah rnernberikan pahala yang berlimpah kepada: 1. Prof. Dr. Ir. Dietriech
G.
Bengen, DEA dan Dr. Ir. Kukuh Nirmala M.Sc.selaku dosen pembimbing yang banyak memberikan masukan dan saran.
2. Bapak dan Mama atas doa dan restu yang selalu rnenyertai
3. Suamiku Yaris lkhsan dan ananda tercinta Nabiilah atas pengertian
dan dukungannya.
4. Bapak E. Batubara, Bapak Suwandi, Herning, Pawit, Eno atas semua bantuannya.
5. Rekan-rekan SPL angkatan IV atas kekornpakannya selama ini.
PENOArmWAN
...
1Latar Selakang
...
1-usan M w l a h
...
2Hipoeesw P e d i a n
...
3TMuan Penelitian
...
3...
Manfaat
Penelitian 4...
Bagan Alir Kerang ka Penelitian 5 W A U A N PUSTAKA...
.
.
.
...
6Batasan dan ~a&teristik WIlayah Pesisir
...
6-an Wilayah Pesisir yang Serkelanjutan
...
6...
hnpmbmgan Tambak di Kawasan pesisir 7...
Ekoehm Mangrove 8 Fun@ Ekobgi Ekosisbm Mangrove...
9...
Fwrgsi Ekonomi E kosistem Mangrove 12 Produktivitas Tambak...
14F m
Bid@.
Fwikadan
Kimia Lingkungan...
yangmempmgaruhi
Produ ktivitas Budidaya Tam bak 14...
Tekstur Tanah 22 Padat Tebar. . Pakan. Perkrmbuhandan
Survival Rate...
23KeWkaiin Sumberdaya lkan dengan Ekosistem Mangrove
...
24MET- P E N ~ ~ ~ A N
...,,.,,,...
29...
Waktu dan Lokasi Penelitian 29
...
k h a n dan
Alat
29-tan Data
dan
Informasi...
29Analisis Data
...
31,...
...
HASL DAM W A N
.
.
.
.
.
42...
Keadaan Umum Lokasi Penelitian 42
A n a l i Kuaiii Perairan dan Mangrove terhadap Produ k-
ti- Tambak lkan Bandeng dengan menggunakan
h a M s Regresi Sederhana dan Principle Component
Arratyscs
...,...
43W i Fisik
...
43
Analisis Stmbegi Pengembangan Hutan Mangrove untuk Meningkatkan Produktivibs Budidaya Tam bak
di W s i r
Kamal
...~...
54DAFTAR TABEL
Halaman
Produk Langsung dari Ekosistem Mangrove
...
.
.
.
.
. . .
13Produk Tdak Langsung dari Ekosistem Mangrrove
...
13Pengaruh pH terhadap Budidaya Perikanan
...
17Kriteria Kualitas Air Berdasarkan Kandungan Total
...
Partikel Tersuspensi 19 Jenis Plankton yang Sering Dijumpai di Tambak dan Wama Airyang
DitimbulkanHubungan Tanah dengan Kesuburan Tambak...
21Hubungan Tanah dengan Kesuburan Tambak
...
23
MatriksSWOT
...
27Unit. Metoda dan Lokasi Pengukuran Parameter Fisika dan Kimia
...
30Empat lndikator Kualitas Lingkungan Mangrove
...
34Faktor Strategis Internal
dan
Eksternal HutanMangrove
...
54Faktor Strategis Ekstemal dan Internal Hutan Mangrove dengan nilai bobotnya
...
55DAFTAR GAMBAR
[image:11.566.40.505.42.787.2]Halaman
Bagan Alir Kerangka Pemikiran Penelitian...
5...
Diagram
Analisis SWOT
27Peta Lokasi Studi
...
41Grafik Hubungan Asosiasi Spesies dengan lndeks
ualitas Lahan Mangrove
...
.
.
...
35Grafik Hubungan Penutupan Pohon (%) dengan lndeks
Kualitas La han Mangrove
...
36Gmfik Hubungan Penutupan Semai (016) dengan Indeks
Kualitas La han Mangrove
...
36Grafik Hubungan Jumlah Semai dengan lndeks
Kualitas La han Mangrove
...
.
.
...
37 Proyeksi Stasiun-Stasiun Penelitian danProyeksi seluruh Variabel Penelitian
...
..
..
...
53 Diagram Strategi Pengembangan Konsenrasi Mangroventuk Meningkatkan ProduMiitas Budidaya Tambak
...
*
.
...
1. p d h n 69
...
2
.
a n
m u k u r a n
Parameter 79...
.
3 Maw( Kodasi 82
Latar Belakang
Pengembangan wilayah pesisir berlangsung sangat cepat dan pesat. Berbagai aktivitas pembangunan dari berbagai sektor, terjadi turnpang tindih di wilayah pesisir. Hal ini mengakibatkan degradasi lingkungan dan terancamnya kelestarian sumberdaya alam wilayah pesisir. Salah satu sumberdaya alam wilayah pesisir yang terancam kelestariannya akibat dari tidak terpadunya pengelolaan di wilayah pesisir
adalah hutan mangrove.
Kerusakan ekosistem hutan mangrove di wilayah pesisir di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Selama periode 1982 - 1993 telah terjadi penurunan luas hutan mangrove dari
5,21 juta ha menjadi sekitar 2,5 juta ha (Dahuri, 2000). Penurunan luasan
hutan mangrove hampir merata terjadi di seluruh kawasan pesisir di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya konversi lahan mengrove menjadi peruntukkan lain,
seperti
pembukaan lahan tambak, pemukiman, pengembangan kawasan industri serta eksploitasi kayu mengrove yangterus meningkat.
Kerusakan ekosistem hutan mangrove dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem lain di wilayah pesisir. Karena, secara empiris,
keterkaitan antara beberapa ekosistem yang berada di wilayah pesisir sangat tinggi sehingga dampak yang timbul sebagai akibat dari adanya
pemanfaatan satu sumberdaya akan sangat mempengaruhi kondisi sumberdaya lain di wilayah tersebut.
Hutan mangrove yang merupakan ekosistem penyangga antara lautan dan daratan, mernegang
peranan
penting dalam mendukung produktivitas perairan pesisir dan sekitarnya. Peran yang sangat penting dari ekosistem mangrove yang berkaitan dengan produktivitas perairan pesisir adalah bahwa secara biologi ekosistem mangrove merupakanHal ini dibuktikan dengan adanya berbagai hasil penelitian yang
menunjukkan adanya korelasi positif antara luas hutan mangrove dengan produksi tangkapan ikan, udang, kepiting di perairan pesisir. Semakin luas hutan mangrove, maka produksi ikan, kepiting, tiram dan udang semakin tinggi.
Wilayah pesisir Kamal merupakan bagian Teluk Jakarta yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Aktivitas e konomi penduduk yang terdapat di wilayah pesisir ini meliputi budidaya kerang hijau, budidaya ikan bandeng dan nelayan. Penduduk yang berrnukim di sekitar pesisir Kamal sebagian besar adalah pendatang (suku Bugis, Makasar, Bone) yang bermata pencaharian sebagai nelayan.
Kondisi hutan lindung di pesisir Kamal sebagian telah dikonversi menjadi peruntukkan lain, seperti pembukaan lahan tambak, jalan dan pemukiman, sedangkan sebagian lainnya oleh Dinas Kehutanan dipertahankan menjadi hutan lindung dan dijadikan hutan wisata. Namun, beberapa tahun terakhir, pada wilayah pesisir yang hutan mangrovenya telah dikonversi, terjadi abrasi pantai yang mengakibatkan hilangnya
sempadan pantai, hancurnya tambak ikan yang diiringi menurunnya produktivitas tambak. Sebaliknya, tambak ikan yang terdapat di hutan lindung mangrove memiliki produktivitas yang tinggi. Maka berdasarkan
ha!-ha1 tersebut, untuk menciptakan pengembangan wilayah konservasi mangrove serta lahan budidaya tambak ikan yang berkelanjutan dan
memiliki produktivitas yang tinggi, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor
yang
mempengaruhi produktivitas tambak dipesisir Kamal kaitannya dengan keberadaan
hutan
mangrove sertastrategi pengembangan konservasi mangrove pada lahan budidaya tambak di wilayah pesisir
yang
dapat diterapkan di pesisir Kamal.Perurnusan Masalah
sosial berupa pembukaan lahan tambak. Jika ha1 tersebut dibiarkan maka kerusakan hutan mangrove akan meluas sehingga diduga hutan mangrove tidak dapat berfungsi sebagai biofilter untuk perairan khususnya perairan tambak disekitarnya sehingga kualitas lingkungan perairan di pesisir Kamal menu run, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas tambak yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu perlu diketahui korelasi yang terjadi antara kualitas lingkungan hutan mangrove dengan peningkatanlpenurunan produktivitas tambak di pesisir Kamal. Selain itu
faktor-faktor biofisik-kimia apa saja yang mempengaruhi produktivitas tambak di pesisir Kamal, serta strategi yang bagaimana yang dapat
diterapkan untuk pengembangan konservasi mangrove untuk meningkatkan produktivitas budidaya tambak di pesisir Kamal.
Hipotesis Penelitian
1. Semakin baik kualitas lingkungan perairan tarnbak rnaka sernakin
tinggi produktivitas tambak
2. Semakin tinggi kualitas lingkungan mangrove maka semakin tinggi
produktivitas tambak
Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui faktor-faktor biofisik-kimia apa saja yang lebih dominan mempengaruhi produktivitas tambak ikan di pesisir Kamal. 2. Untuk mengetahui korelasi yang terjadi antara kualitas lingkungan
hutan mangrove dengan peningkatanlpenurunan produktivitas tambak
di pesisir Kamal.
Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah :
1 . Secara akademik penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai proses belajar, memenuhi persyaratan dalam penyelesaian program magister sains di Sekolah Pascasarjana IPB, serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.
Garnbar 1. Bagan Alir Kerangka Pikir
Kondisi Lingkungan di Pesisir Kamal
Kerusakan Hutan Mangrove Produktivitas Tambak
Menurun
a
Biofisik Sosial Ekonomi Kelembagaan Eksternal . (dlasumsikan sama)
Internal Internal Internal Internal SDM
Kualltas a ~ r Kepem~l~kan Jasa llngkungan UU No 4111999
yang buruk (ke~ndahan) ttg kehutanan
Jen~s Pohon Ekstetnal Fungsl Farmakologi dar~ SK Menter~ In
yang t~dak Aturanlsanksi yg hutan mangrove Kehutanan No Kualitas Lingkungan
tahan ombak lernah Fungsl ekonomr dar~ 6671Kpts11995 Perairan yang rendah
Eksternal 4 Lama tlnggal hutan mangrove ber!sl larangan (pH, Suhu, Salinitas, dll)
Sampah Pemaharnan Eksternal membuat empang
Angln rnasyarakat rendah Perm~ntaan Kayu Pasal 18, UU No
Ombak Pend~d~kan rendah 4 Keuntungan jangka 41 11 999
pendek opt~mal~sas~
Konversl lahanlal~h fungsl manfaat dan Uji Statistik
- Eksternal penataaan zona
Lemahnya
pengawasan
Kurangnya PC A
pemblnaan
u
Analisa SWOT Strategi Pengembangan Konservasi Mangrove
b
Untuk Meningkatkan Produktivitas Budidaya Tambakdi Pesisir Kamal
TINJAUAN PUSTAKA
Batasan dan Karakteristik Wilayah Pesisir
Defenisi wilayah pesisir hingga saat ini belum ada yang baku. Namun demikian terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah
pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daerah daratan dan lautan. Untuk kepentingan pengelolaan, penetapan batas fisik suatu wilayah pesisir didasarkan atas faktor yang mernpengaruhi pembangunan dan pengelolaan ekosistim pesisir dan lautan beserta segenap sumberdaya
yang ada didalamnya, serta dari tujuan pengelolaan itu sendiri (Dahuri, 1997).
Dalam penyusunan tata guna lahan pesisir, ada lima karakteristik utama dari ekosistem kawasan pesisir, yaitu : 1) Keterkaitan ekologis antar ekosistim di dalam wilayah pesisir bagian atas dan laut lepas, 2) terdapat lebih dari dua macam sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang dapat dikembangkan, 3) terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat yang memiliki keterampilan dan kesenangan (preference)
bekerja yang berbeda, 4) pemanfaatan suatu wilayah pesisir secara monokuttur
(single
use) secara ekologis maupun ekonomis adalah sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternalyang
menjuruspada kegagalan usaha. 5) wilayah pesisir merupakan sumber daya rnilik bersama yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang (Dahuri dan
Arumsyah, 1994).
Pembangunan Wilayah Pesisir Yang Berkelanjutan
Menurut Dahuri, et al. (1997) pembangunan berkelanjutan adalah pernbangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa rnerusak
tiga persyaratan yang dapat menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan, yaitu: keharmonisan spasial, kapasitas asimitasi dan pemanfaatan berkelanjutan. Keharmonisan spasial mensyaratkan bahwa dalam suatu wilayah pembangunan hendaknya tidak seluruhnya diperuntukkan bag; zona pemanfaatan tetapi harus dialokasikan juga
untuk zona preservasi dan konservasi. Dimensi ekologis seperti ini pada
dasarnya menyajikan informasi daya dukung sistem alam wilayah pesisir dalarn menopang segenap kegiatan pembangunan dan kehidupan manusia.
Menurut Scones (1993) daya dukung lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daya dukung ekologis (ecological carrying capacity)
dan daya dukung ekonomi. Daya dukung ekologis adalah jumlah maksimum hewan-hewan pada suatu lahan yang dapat didukung tanpa menga ki batkan kematian karena faktor kepadatan maupu n terjad inya kerusakan lingkungan secara permanen (irreversible). Hal ini ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan. Daya dukung ekonomi adalah tingkat produksi (skala usaha) yang memberikan keuntungan maksimum dan
ditentukan oleh tujuan usaha secara ekonomi. Dalam hal ini digunakan parameter-parameter kelaya kan usa ha secarn ekonomi.
Pengembangan Tambak di Kawasan Pesisir
Pengembangan dapat dipandang sebagai suatu proses yang
membawa peningkatan kemampuan penduduk mengenai lingkungan
sosial yang disertai dengan meningkatnya taraf hidup mereka sebagai akibat dari penguasaan mereka. Dengan dernikian pengembangan adalah suatu proses yang menuju pada suatu kemajuan (Manurung, et al., 1 998).
budidaya perikanan dapat berkelanjutan dan optimal maka pemilihan lokasi harus di lakukan secara benar dan menurut kaidah ekologis dan ekonomis (Dahuri et al. 1 997).
Kegiatan budidaya tarnbak dalam pengembangannya di kawasan
pantai dalam realisasinya harus memperhatikan UU No. 511 990
(Alifuddin, 2001 ), yakni:
(a) perlindungan sistem penyangga kehidupan
(b) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta
ekosistemnya.
(c) Pemanfaatan secara lestari sumberdaya
alam
hayati dan e kosistemnya.Perkembangan pertambakan yang tidak terkendali telah membawa dampak negative terhadap mutu lingkungan. Mutu air secara fisik, kimiawi
dan mikrobiologis merosot tajam. Gejala ini diperburuk oleh
perkembangan pemukiman, pencemaran, perindustrian dan penebangan hutan mangrove penyangga (BPPT, 1995).
Ekosistem Mangrove
Menurut Manan (1 986) ekosistem mangrove merupakan ekosistem utama penyusun ekosistem wilayah pesisir. Hutan mangrove adalah formasi tumbuhan ritoral yang karakteristik terdapat di daerah tropika dan
subtropika, terhampar di sepanjang pesisir. Sedangkan
menu
rut Koesoebiono (1 997) hutan mangrove disebut juga hutan bakau yang mempunyai karakteristik ekosistem yang khas, mengingat hidupnya berada di darah ekotone yaitu perairan dan daratan. Karakteristik mangrove ini terutama dalah mampu berada pada kondisi salim dantawar. Masih menurut Koesoebiono (1 997) dalam pertumbuhannya mangrove memerlukan kondisi lingkungan tertentu. Kondisi lingkungan ini
sangat mempengaruhi komposisi dan distribusi serta bentuk pertumbuhan mangrove. Kondisi lingkungan tersebut adalah gerakan air yang minim, sirkulasi air dalam hutan mangrove dan pasang surut air laut.
(1 997) pada kebanyakan spesies terdapat ciri-ciri khas yang memberikan kemampuan untuk bertahan hidup dan berkembang pada substrat yang
terdiri dari sedimen halus yang sering anoksis dan bersifat asam. Sehingga kebanyakan spesies mangrove dilengkapi dengan struktur perakaran yang khas, yang terdiri dari dua tipe perakaran yaitu tipe cakar ayam bercabang yang terdapat pneumatofora yang menernbus permukaan substrat dan tipe penyangga perakaran ganda dimana
beberapa akar penyangga tumbuh dari batang pohon menem bus substrat,
membentuk suatu struktur yang rnenyerupai payung. Dari akar-akar penyangga utama tersebut tumbuh akar-akar penyangga sekunder
menembus permukaan substrat
.
Ekosistem mangrove merupakan sumberdaya alam pesisir yang mempunyai peranan penting bagi kelangsungan hidup ekosistem lainnya.
Hal ini karena ekosistem mangrove mempunyai lokasi yang strategis, dan dengan potensi yang terkandung didalamnya, serta fungsi perlindungannya secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi keberadaan dan berfungsinya sumberdaya alam lainnya. Ekosistem mangrove di Indonesia memiliki keragaman hayati yang tert~nggi didunia
dengan jumlah total kurang lebih 89 spesies, yang terdiri dari 35 spesies
tanaman, 9 spesies perdu, 9 spesies liana, 29 spesies epifit, dan dua spesies parasitik (Nontji, 1 987). Beberapa jenis yang umum dijumpai di
wilaya h pesisir l ndonesia adala h bakau (Rhirophora), Api-api (Avicennia), Pedada (Sonneratia), Tanjang
(Bruguiera),
Nyiri h (Xyl~carpus), Tengar(Ceriops) dan Buta-buta (Exoecaria). Oleh sebab itu didalam
perencanaan pembangunan ekosistem mangrove harus dianut pula azas
kelestarian fungsi dan manfaat yang optimal. Ekosistem mangrove secara garis besar mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi ekologis dan
fungsi sosial ekonomi.
Fungsi Ekologis Ekosistem Mangrove
ekologis. Fungsi ekologis ekosistem hutan mangrove dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain aspek fisika, kimia dan biologi. Fungsi ekologis ditinjau dari aspek fisika adalah (1) Terjadinya mekanisme hubungan antara komponen-komponen dalam ekosistem mangrove serta
hubungan antara ekosistem mangrove dengan jenis-jenis ekosistem lainnya seperti padang lamun dan terumbu karang;
(2.)
Oengan sistem perakaran yang kuat dan kokoh ekosistem hutan mangrove mempunyaikemampuan meredam gelombang, menahan lurnpur dan melindungi pantai dari erosi, gelombang pasang dan angin topan; dan (3) Sebagai
pengendali banjir. Hutan mangrove yang banyak turnbuh di daerah
estuaria juga dapat berfungsi untuk mengurangi bencana banjir. Fungsi ini
akan hilang apabila hutan mangrove ditebang.
Apabila dilihat dari aspek kimia, maka hutan mangrove dengan kemampuannya melakukan proses kimia dan pemulihan (Self purification)
memiliki beberapa fungsi, yaitu (I) Hutan mangrove dapat berfungsi sebagai penyerap bahan pencemar (Envimnmentle service), khususnya bahan-bahan organik; (2) sebagai sumber energi bagi lingkungan perairan sekitarnya. Ketersed iaan berbagai jenis ma kanan yang terdapat pada
ekosistem hutan mangrove telah menjadikannya sebagai sumber energi berbagai jenis biota yang bernaung didalamnya, seperti crustacea, udang,
kepiting, burung, kera dan lain-lain telah menjadikan rantai makanan yang
sangat komplek sehingga terjadi pengalian energi dari tingkat tropik yang
lebih rendah ke tingkat tropik yang lebih tinggi; dan (3) Pensuplai bahan organik bagi lingkungan perairan. Pada ekosistem hutan mangrove terjadi mekanisme hubungan memberikan sumbangan berupa bahan organik
Masih menurut Snedaker et al., (1985) selain fungsi diatas, ekosistem mangrove juga memiliki fungsi-fungsi fisik, yaitu (a) mencegah terjadinya intrusi air asin ke daratan dan (b) sebagai pelindung pantai dari
abrasi. Dengan adanya kawasan mangrove, air pasang masih dapat terhalang oleh pepohonan mangrove, sehingga tidak akan masuk jauh ke
arah daratan, yang sekaligus mencegah intrusi air asin ke tanah. Jika
terjadi intrusi air asin ke daerah perkebunan, dapat mengakibatkan penurunan produksi perkebunan rakyat di luar tambak. Kerugian lainnya dari intrusi air asin adalah terpengaruhnya sumber air tawar penduduk
oleh air asin. Jika ha! tersebut terjadi, rnasyarakat akan sangat terganggu kehidupannya.
Hutan mangrove dari aspek biologis sangat penting untuk tetap
menjaga kestabilan produktivitas dan ketersediaan sumberdaya hayati wilayah pesisir. Hal ini mengingat hutan mangrove juga merupakan
daerah asuhan (nursery ground) dan pemijahan (spawning ground)
beberapa biota perairan seperti udang, ikan dan kerang-kerangan. Beberapa fungsi ekologis hutan mangrove memang
sangat
ditunjang olehkarakteristik hutan mangrove itu sendiri seperti yang telah diuraikan di atas. Mementingkan fungsi ekologis bukan berarti meniadakan fungsi ekonomis yang dimiliki oleh hutan mangrove, tetapi bagaimana menempatkan kepentingan ekonomis tidak merusak fungsi ekologis hutan mangrove itu sendiri.
White dalam Naamin, (1991) menyatakan bahwa ekosistem mangrove memiliki produktivitas yang tinggi. Nontji (1987) dalarn laporannya menyatakan bahwa kurang lebih 80 spesies dari crustacea, dan 65 spesies Mollusca terdapat di ekosistem mangrove di Indonesia. Tanaman mangrove, termasuk bagian batang, akar dan daun yang berjatuhan memberikan habitat bagi spesies akuatik yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove. Ekosistem ini juga berfungsi sebagai tempat
Ekosistem mangrove merupakan produsen primer melalui serasah
yang dihasilkannya. Serasah hutan melalui proses dekomposisi oleh sejumlah mikroorganisme, menghasilkan detritus dan berbagai jenis fitoplankton yang akan dimanfaatkan oleh konsumer primer yang terdiri dari zooplankton, i kan dan crustacea (udang, kepiting , dan lain-lain) sampai akhirnya dimangsa oleh rnanusia sebagai konsumer utama
(Sumarna, 1985). Vegetasi hutan mangrove juga merupakan pendaur ulang hara tanah yang diperlukan bagi tanaman. Hasil penelitian di Florida menunjukkan bahwa 90% kotoran hutan menghasilkan 35-60% unsur hara yang terlarut di pantai. Selain itu daun bakau-bakau (Rhizophora
spp) pada awal pembusukannya mengandung kadar protein 3,1% dan setelah satu tahun meningkat menjadi 21 %. Kadar N daun kering adalah sekitar 0,5%, dan diperkirakan setelah satu tahun menghasilkan sekitar 47
kg N. Satu hektar lahan hutan mangrove serasah ' yang dihasilkan mencapai 7,l
-
8,8 ton per tahun. Menurut Odum (1 982), pasokan nutrien bagi ekosistem mangrove ditentukan oleh berbagai proses yang saling terkait, meliputi inputlekspor dari ion-ion m~neral anorganik dan bahan organik serta pendaur ulangan nutrien secara internal rnelalui jaringanmakanan berbasis detritus. Konsentrasi relatif dan nisbah (ratio) optimal dari nutrien yang diperlukan untuk pemeliharaan produktivitas ekosistem mangrove dan ditentukan oleh; I) Frekuensi, jumlah dan lamanya penggenangan oleh air asin atau air tawar; dan 2) Dinamika sirkulasi internal dari kompleks detritus.
Fungsi Ekonomis Ekosistem Mangrove
Ekosistem hutan mangrove merupakan hutan tropika yang khas turnbuh di sepanjang pantai atau muara sungai. Hutan mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif dengan berbagai fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan yang penting. Hamilton dan Snedaker (1 984) telah mengidentifikasi lebih dari 70 nilai pakai dari ekosistem hutan
arang, penyamak kulit, bahan-bahan bangunan, peralatan rumah tangga, obat-obatan dan bahan baku pulp dan industri kertas.
Tabel I. Produk Langsung dari Ekosistem Mangrove
-. . . . - - - . . .
r ~ e ~ u n s s n
I
Produ kI
Peralatan Tang g a
I Produksi
- -
Cdan
kulitjSahan
Bakar - Konstru ksiL
. . . -i Memancing
I
Pertaman
Produksi Kertas
Makanan,
Minuman dan
Obat-Obatan
Kayu bakar untuk memasak, untuk memanggang ikan, untuk memanaskan lembaran karet, untuk rnernbakar batu bata, arang dan alkohol
Kayu untuk tangga, untuk konstruksi berat (contoh : jembatan). untuk penjepit jalan kereta api, untuk tiang penyangga terowongan pertarnbangan, untuk tiang pancang geladak, untuk tiang dan galah untuk bangunan, bahan ilntuk lantai, papan bingka~, bahan untuk membuat kapal, Pagar, Pipa air, Serpihan kayu, dan Lem
I
I Pancing ikan untuk menangkap ~kan, sebagai pelampung panclng, racun ikan, bahan untuk pemeliharaan jaring, dan sebagai tempat , berlindung untuk ikan-ikan unik
- .-
Sebagai makanan ternak dan Pupuk hijau
- .. . . .
Berbaga~ ]enis kertas, Gula< Alkohol, Minyak Goreng, Cuka '
pengganti the, Minuman fermentasi, Pelap~s permukaan, Rempah- i rempah dari kulit kayu, daging dari propagules, Sayur-sayuran, buah, atau daun dari propagules
. .-
Rumah
Pengepakan
1
- ..Pembalut rokok, bahan obat-obatan dari kulit, daun dan buahnya
.. - -- Perabot, Perekat, Minyak rarnbut, Peralatan tangan, Penumbuk padi, Mainan, batang korek api
--
Tekstil
Sumber . Saenger, et ai { I 983).
Serat sintetik, Bahan pencelup yakaian, Bahan untuk penyamakan kulit
Tabel 2. Produk Tidak Langsung Dari Ekosistem Mangrove
I
1
Produk/ Sumber i
C
--lkan Blodok (beberapa jenis)
Crustacea (udang dan kepiting) -#olusca (kerang, remis, tiram)
Lebah
Burung
- - - -. - -. . , . - - - , REP!!!
Fauna lainnya (contoh amphibi dan seranga]
. -- -. .
- - - . - - - - - - - -. . . -
-
Makanan . -
Makanan -
Makanan . .
Madu Lilin
Makanan, Bulu, Rekreasi (mengamati dan berburu) - - - - - - - . . . -.
- . Kulit, Makanan, Rekreasi
- . - - . . . . . .
Makanan, Rekreasi
- - . . . . . .
[image:25.570.79.499.82.777.2]Produ ktivitas Tambak
Menurut Chapman dalarn Tanggo (1990) yang di maksud dengan
produksi biomassa adalah besarnya pertambahan berat organisme pada
suatu periode tertentu. Produksi biomassa ditandai dengan laju pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup individu. Beberapa faktor
yang berpengaru h terhadap produksi biomasa suatu individu adalah kualitas lingkungan, makanan, hama dan penyakit, predator dan kompetitor dan kepadatan populasi.
Menu rut Dahuri (2000) dalam ha1 budidaya perikanan (tambak) faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas, ketidak menentuan hasil produksi (termasuk kegagalan panen) adalah sebagai berikut:
(1) Kemampuan teknologi budidaya (mencakup pernilihan induk,
pemija han, penetasan pembuahan, pemeliharaan larva, pendederan, pembesaran, manajemen kualitas air, manajemen
pemberian pakan, genetic (breeding), manajemen kesehatan ikan dan teknik perkolaman sebagian besar petani ikan masih rendah.
(2) Kompetisi penggunaan ruang (lahan perairan) antara usa ha
budidaya perikanan dan kegiatan pembangunan lainnya
(pemukiman industri, pertambangan dan lainnya) pada umumnya
atau selalu mengalahkan usaha budidaya perikanan.
( 3 ) Semakin memburuknya kualitas air sumberdaya untuk budidaya
perikanan
khususnya
di kawasan padat penduduk atau tinggi intensitas pembangunannya.Faktor Biologi
-
Fisika-
Kimia Lingkungan Yang Mempengaruhi Produ ktivitas Usaha Budidaya TambakSelain faktor teknik pemeliharaan budidaya ikan dalam tambak
Kualitas Perairan
Kualitas lingkungan seperti suhu air berpengaruh terhadap kelangsungan aktivitas fisiologis hewan peliharaan dan sifat fisik dan kimia perairan. Kualitas suatu perairan sangat ditentukan oleh pengaruh yang
diterima oleh wilayah di sekitarnya. Kualitas perairan secara luas dapat
diartikan sebagai faktor fisika
-
kimia dan biologi. Yang mempengaruhi kehidupan ikan dan organisme perairan lainya baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Menurut Wardoyo (1981) bahwa perairanyang ideal bagi kehidupan ikan dan organisme lainya dalam rangka menyelesaikan daur hidupnya serta mendukung kehidupan makanan ikan
diperlukan pada setiap stadia daur hidup. Beberapa parameter kunci dari kualitas suatu perairan dalam penelitian ini yaitu : Salinitas, suhu, padatan tersuspensi (TSS), pH, DO, BOD, COD, Pb, Fe, Nitrogen dan Phenol.
Salinitas
Salinitas didefinisikan sebagai jumlah total garam terlarut dalam satuan gram yang terdapat dalam satu kilogram air laut, dengan
asumsi
semua karbonat telah teroksidasi, sedangkan brom dan yod diubah menjadi klor dan semua unsur organic telah teroksidasi. Menurut Stickney
(1979), salinitas dari air tawar biasanya kurang dari 0,5%0 , dan air mulai
terasa asin pada salinitas sekitar 2%0. Salinitas bukan merupakan hal
yang menjadi pertimbangan pada budidaya air tawar namun sangat
penting bagi budidaya laut
(rnariculture).
Afrianto dan Liviawaty (1991) menyatakan bahwa salinitas air yang cocok untuk digunakan mengisi tambak budidaya udang windu berkisar antara 1 5-20%0, sedangkan untukikan bandeng berkisar antara
5-25%0 (Soeseno,l983).
Air dengansalinitas demikian dapat diperoleh di perairan yang terletak di sekitar pantai yang dipengaruhi adanya masukan air sungai.
Perubahan salinitas pada perairan bebas adalah relatif kecil bita dibandingkan dengan yang terjadi di perairan dekat pantai. Hal ini disebabkan perairan pantai banyak mendapatkan masukan air tawar dari
(1 990) menjelaskan bahwa goncangan salinitas air ditentukan oleh suplai air tawar maupun air laut dan laju evaporasi. Untuk mencegah ha1 tersebut hendaknya kontruksi tata letak dan lokasi tambak sedemikian rupa
sehingga penggantian air dapat di lakukan dengan mudah.
Suhu
Su hu air pada suatu perairan dipengaruhi oleh komposisi substrat, kekeruhan air hujan, luas permukaan perairan yang langsung terkena sinar matahari serta suhu perairan yang menerima air hujan limpahan (Perkins, 1974). Sedangkan menurut Welcomme (1 985), hal-ha1 yang
mempengaruhi suhu di sungai antara lain letak pada garis Iintang, ketinggian dari permukaan, komposisi substrat, kekeruhan, masukan dari
air tanah dan air hujan, angin dan penutupan oleh vegetasi. Suhu air sangat berkaitan erat dengan konsentrasi oksigen terlarut dalam air dan
laju konsumsi oksigen hewan air. Suhu air berbanding terbalik dengan konsentrasi jenuh oksigen terlarut, tetapi berbanding lurus dengan !aju
konsumsi oksigen hewan air dan laju reaksi kimia dalam air (Ahmad et a / . , 1999). Suhu air yang baik bagi kepentingan perikanan adalah suhu air normal (k 27°C untuk daerah tropic) dengan fluktuasi sekitar 3°C (Haryadi
et a/., 1992). Menurut Poernomo (19881, kisaran suhu yang
diperbolehkan dalam pemeliharaan udang windu adalah
26'C
-32'C
, sedangkan untuk pemeliharaan benih bandeng di tambak bervariasi antara 34'C-38,5"C
(Bardach et a/. , 1973). Sedangkan berdasarkanpengalaman di Filipina suhu air yang layak untuk pemeliharaan ikan
bandeng adalah antara 25
-
35'C (Kinne 1964) dalam Tanggo (1990).Derajat Keasaman
(pH)
Derajat keasaman diduga sangat berpengaruh terhadap tingkat toksisitas bahan beracun. Menurut Hawkes (1 979) bahwa pH antara 5 - 9,
pengaruh bahan beracun sangat kecil. Perairan yang netral mempunyai
pH 7, pH lebih kecil dari 7 maka perairan bersifat asam dan apabila pH lebih besar dari 7 maka perairan bersifat basa. Menurut Blanco (1 970)
berkisar antara 7.8
-
9.5 dengan salinitas air antara 10 - 50 01,,,Poernomo (1976) dalam Tanggo dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pH air yang baik untuk budidaya ikan bandeng di Indonesia berkisar antara 7.0 - 8.0 . Sedangkan Swingle (1969) dalam Boyd (1990), mengatakan bahwa pH optimum di tambak berkisar antara 6,5-
9,O. Hubungan antara pH dengan budidaya perikanan dapat dilihat pada
table berikut.
Lu-
6,5-91
Pertumbuhan baik - , . -. - - ,Tabel 3. Pengaruh pH terhadap Budidaya Perikanan
.
PH.
.L:
% -1 5-6.5
>11
1
Kematian -- -- .. . ,1
Pengaruh terhadap ikan
Kematian
Pertumbuhan lambat, tidak terjadi reproduksi -.
--
~ e r t u m bu han lambat
-.
--q
I9-9,5
9,5-11
Sumber Swingle (1 969) dalam Boyd (1 982)
Pertumbuhan lambat
Pertumbuhan lambat, tidak terjadi reproduksi
Oksigen Terlarut (DO)
Oksigen merupakan unsur penunjang kehidupan. Pada air laut, oksigen di manfaatkan oleh organisme perairan untuk proses respirasi dan
untuk menguraikan zat organik oleh mikroorganisme (Harvey, 1976 ).
Menurut Muchtar (1982) oksigen terlarut di laut atau DO (Dissolved
Oxygen) sangat penting artinya bagi kehidupan organisme dan keseimbangan kimia di dalam air laut. Proses fotosintesis di laut
merupakan salah satu faktor yang menentukan konsentrasi oksigen dalam air laut. Oksigen juga dapat masuk dari udara melalui proses difusi. Proses larutnya oksigen dari udara di pengaruhi oleh sifat-sifat fisika dari
gas yang ada di dalam air laut dan yang ada di udara.
Menu rut Pescod (1 973) konsentrasi oksigen terlarut yang aman
bagi kehidupan harus berada diatas titik kritis dan tidak terdapat bahan
perikanan dianjurkan > 3mgfl. Perairan dalarn kadar oksigen terlarut rendah mengakibatkan nafsu makan ikan berkurang dan efisiensi pakan jadi turun.
BOD (Biochemical Oxygen Demand)
Kebutuhan oksigen Biokimia atau BOD
(Biochemical
OxygenDemand) adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh
mikroorganisme dalarn proses dekomp~sisi bahan-bahan organik mikroorganisme yang terjadi di perairan. Menurut Prasetyo (1979) pelepasan limbah yang berupa bahan-bahan organik ke dalarn perairan dengan konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan kekurangan oksigen. Hal ini sangat berbahaya karena dapat mengubah proses dekomposisi
aerobik menjadi dekomposisi anaerobik yang dapat meng hasilkan gas-gas beracun seperti CH4 dan H2S
COD (Chemical Oxygen Demand)
Kebutu han oksigen kirnia atau COD (Chemical Oxygen Demand)
menyatakan jumlah total oksigen yang dibutu hkan untuk rnengoksidasi semua bahan organik yang terdapat di perairdn menjadi karbondioksida di
air. Nilai COD akan meningkat seiring dengan meningkatnya nilai bahan
organik di perairan (Widigdo et al., 1992). Menurut prasetyo (1979) nilai COD perlu diketahui dalarn menduga pencemaran oleh rninyak bumi. Hal
ini disebabkan oleh banyaknya senyawa-senyawa organik yang tidak atau
sukar sekali terdekornposisi secara biologis.
Padatan Tersuspensi Total (Total Suspended Solid)
Total Suspended Solid (TSS) adala h bahan-bahan tersuspensi yang tidak larut dalarn air. Bahan-bahan ini baik organik maupun
Berdasarkan kandungan total bahan tersuspensi di air, maka kualitas air dikelompokan dalarn beberapa kriteria yaitu :
Tabel 4. Kriteria Kualitas Air Berdasarkan Kandungan Total Partikel
Tersuspensi
Sumber: Canter and Hill, 1981
Total Fosfat
Kandungan Total Parti kel Tersuspensi (mgll) < 4
4-1 0
70 -15 1 5-20
20-35
Total fosfat menunjukkan kandungan P (fosfor) baik yang berupa
senyawa organik maupun anorganik. Mereduksi P dalam bentuk senyawa organik dilakukan disgestion yaitu yaitu air sampel yang diberi asam kuat (H2S04) (Widigdo et al., 1992). Kandungan fosfat yang tinggi menyebabkan terjadinya eutrofikasi di perairan.
Kriteria Kualitas Air
Sangat Baik Baik Sedang
Miskin
Jelek
Fosfat dibutuhkan algae dan plankton untuk keperluan tumbuh dan reproduksi, sehingga seringkali fosfat terserap dalam jumlah besar dalam plankton dan alga tersebut. Fosfat yang terserap tidak sernuanya
langsung dimanfaatkan, tapi disimpan sebagai cadangan. Apabila plankton tersebut mati maka fosfat yang belum termanfaatkan diendapkan bersama jasad renik tersebut. Proses sedimentasi jasad renik yang terus menerus, menyebabkan-fosfat bersenyawa dengan unsur yang ada di tanah. Total konsentrasi fosfat di sistem perairan berkisar 0.01 - 200 mgA
Amoniak
Amoniak-nitrogen khususnya amoniak bebas (NH3) sangat beracun bagi hewan air (Boyd, 1991). Akumulasi ion amonium (NH4'} dalm tubuh ikan atau udang dalam jumlah banyak dapat menimbulkan gangguan
rnetabolisme yang mengarah pada penurunan laju perturnbuhan bahkan
kematian. Tingginya amoniak juga akan meningkatkan konsurnsi oksigen
oleh jaringan, kerusakan insang dan menurunnya kernampuan darah
dalam mentransportasikan oksigen ke tubuh (Boyd, 1991).
Pada konsentrasi subletal amoniak dapat menyebabkan perubahan histologis pada ginjal, limpa, tyroid, dan darah serta menurunnya daya ta han terhadap penyakit (Boyd, 1982). Boyd (1 982)' mengemu kakan bahwa konsentrasi subletal amoniak ialah 0.0006 - 0.34 mgll NH3, sedangkan konsentrasi letal (dalam 24 - 72 jam) amoniak adalah antara
0.4 mgll dan 2.0 mgll. Menurut Ahmad (1992) menyataka bahwa konsentrasi amoniak total di tambak tidak boleh lebih dari 0.5 mgll, karena
dengan konsentrasi sebesar itu mampu menurunkan laju perturnbuhan
udang sampai 50%.
Phenol
Phenol termasuk grup hidroksil yang gugus fungsinya dihubungkan dengan cincin aromatik, yang dihasilkan dengan formula Ar-OH (Brown, 1 976). Phenol dapat ditemukan dalam lirnbah cair dari' industri gas dan
coke, pabrik resin sintetis, pernurnian minyak bumi, industri tekstil, pabrik kimia dan pabrik lilin. Phenol mudah larut dalam air, alkohol, benzena, naftalena daan berbagai pelarut organik. Zat ini dalarn lingkungan memberikan dampak yang bermacam-macam, namun secara umum
menimbulkan bahaya racun bagi kehidupan. Batas ambang phenol yang aman bagi lingkungan adalah 15 mgll.
Nitrogen
Senyawa nitrogen terdapat dalam keadaan terlarut dan tersuspensi.
Senyawa
ini sangat penting dalam air karena rnemegang peranan yangnitrogen anorganik utama dalam air adalah ion nitrat (NO3-) dan
ammonium (NH4
'1.
Sebagian besar dari nitrogen total dalam air berupa nitrogen organic yang berasal dari bahan-bahan yang berprotein. Sumbernitrogen bahan organic berasal dari limbah domestik, limbah industri, limbah peternakan dan pupuk. Nitrogen di perairan adalah penyebab
utama pertumbuhan ganggang yang sangat pesat (Alaerts dan Santika,
1 984).
Pada perairan tropis yang masih alami, kandungan ammoniak tidak lebih dari 1 ppm. Pada tingkat konsentrasi tersebut akan aman bagi
kehidupan ikan. Perairan yang banyak mengandung ammonia akan berdampak bahaya terhadap daya tahan tubuh organisme akuatik (Pescod, 1973)
Nitrogen diperlukan oleh semua organisme sebagai komponen penting dari protein dan zat-zat biokimia lainnya. Nitrogen diserap dari air oleh organisme nabati akuatik dalarn bentuk nitrat (Pond, 1978).
Plankton
Pertumbuhan plankton ditandai oleh berubahnya wama air di
tambak. Karena terjadinya percampuran antara beberapa jenis plankton
serta kepadatan yang berbeda, timbul percampuran warna dengan intensitas yang juga berbeda (Poernomo, 1988). Beberapa plankton yang
sering terdapat di tambak dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Jenis Plankton Yang Sering Dijumpai di Tambak dan Warna Air Yang Ditimbulkan
.--
I Warna air
Coklat muda - - - -. - . - . - - . -A Coklat tua .. . --
- Coklattua .
. . .-
Coklat kemerahan - -- -
~oklaF- . . .
L .
Coklat kehitaman jernih
Jenis plankton
Diatome
Na vicufa
Nitzschia Coscinodiscus Chaefoceros Meios!ra Zooplankton Brachionus- ~h~toflagellata
~ehdtnium .
Diatorne Phytoflage fla fa
."
Asam organik -.
Keterangan
Baik dipertahankan '
.--
.. .. .-
Bak, air perlu diencerkan - . . . - . . - - - - -.
. . -
-. -. - . . - -. . . .
tidak baik, air.di@nt~ . -. . . . - - - -. . ,
Bahaya, . air dibuang d G d~ganti . . - - . . . i
- - -- . . . . - - - -. . - -
Kurang baik, airjerlu diencerkan - - -. . - - - - . . .
. I
.. - . -- .- . -. -- . . .I
PhormidiumI
1
I [ Anabaena !
i
.- . .. [ Ana baenapsis
I
C h f o r o c o c- c. . - - . - -
Balk, dlpertahankan - I - - --
Kurang balk, air perlu - - d~enierkan - -- Tidak bak alr banyak dlencerkan -
--
--
Tldak bak air dlbuang dan dkantl
-
4
- 1
Hl'au daun muda
*I..
-HI au - kekun~ngan --
-- -
Hljau tua Hljau kebiruan
Sumber: Poernomo, 1988
- .-
. -chlorophyta -
Chlorococcum
Pianktosp haetra
Crusgena --
Phytoflagellata dhlamrdomonas Chllomonas Dl~nakella Cryptomonas Qyanophyceae Oscilatona
Logam Berat
Logam berat bersifat akumulatif dalam tubuh organisme, pada
konsentrasi tertentu dapat rnenyebabkan efek letal atau subletal. Menurut
Pescod (1973) logam berat yang bersifat toksik terhadap ikan dan organisme air lainnya adalah Cu, As, Pb, Cr, Cd dan Se, sedangkan yang
bersifat toksik dalam air minum adalah Cu, Fe, Pb, As, Cr, Se dan Zn. Daya tahan organisme terhadap logam berat tidak sama antar satu dengan lainnya. Logam berat merupakan zat pencema; yang tahan urai (non biodegradable
pollutants).
Senyawa-senyawa ini sukar terurai atau terurai secara lambat, disamping juga bisa terakumulasi melalui rantai makanan dalam siklus biogeokimia (Hamidah, 1980).Menurut Schuster, 1960 dalam Tanggo (1990) pada kondisi tanah
yang sangat asam, kandungan konsentrasi Al, Fe, Mg merupakan toksik
bagi ikan, udang dan organisme lainnya. Beberapa elemen terutama Fe dan Al dilepaskan ke dalam perairan akan mengikat fosfat sehingga terjadi terjadi defisiensi fosfor bagi algae. Sebaliknya pada kondisi alkalis, perairan kaya akan garam-garam Na dan unsur-unsur biogenik lain sehingga memungkinkan organisme nabati dapat tumbuh seperti kelakap.
Tekstur Tanah
seperti kelekap. Menurut Yamada (1 983) bila didapatkan
turn
buhantanaman benthic di perairan payau, diperkirakan tambak tersebut mempunyai potensi untuk rnenunjang produksinya. Hal ini menunjukkan bahwa tanah mernegang peranan penting terhadap praduksi tambak melalui pertumbuhan algae dan oranisme lainnya.
Menurut Mintardjo dan Sunaryanto (1984) tanah dasar tambak dibedakan atas struktur penyusunnya, tanah dapat dibagi kedalarn tiga tipe, yaitu: (1) tanah liat (clay loam), (2) tanah liat berpasir (sandy loam),
[image:35.566.86.497.51.553.2](3) tanah liat berFumpur(si1ty loam). Hubungan tanah dengan kesuburannya dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 6. Hubungan Tanah dengan Kesuburan Tambak
Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa tanah yang baik untuk tambak adalah tanah yang bertekstur liat, lempung liat berpasir, liat berpasir dan lempung liat. Tanah ini sangat keras dan mengalami retak-retak bila dalarn keadaan kering sedangkan dalam keadaan basah marnpu menahan, dengan kata lain tidak mudah menimbulkan kebocoran.
Pasir Lumpur
silt)
Padat Tebar, Pakan, Pertumbuhan dan Survival Rate
Sumber Dev~de 1978, dalam Mlntarjo et a1 7984
Liat
(clay)
Padat Tebar, Pertumbu han dan Survival Rate berpengaru h terhadap produksi tambak udang ataupun ikan. Pada budidaya intensif kepadatan tebar relatif tinggi, sifat dan tingkah laku udang atau ikan, jenis
22
44
14
10 1
1
28%dan stadia maupun daya dukung perairan tambak menentukan kepadatan
Tekstur Tanah
- 2 3 4
1
L -- - . Pertumbuhan Kelakap 14 63 79 Sangat lebat - -. - . - - - . Lebat -- Sedlklt - - - . - Sangat Sedik~t - . .-. -- - 50'
Llat (clay)42
22
11
.- . -. - - -
L~at bedurnpur (slrt loam)
-. --
Lempung hat berpasir
(sand clay loam)
Lemping berpaslr
udang atau ikan yang di pelihara (Hidayat, 1992). Turunan dari kepadatan yang tinggi ialah perubahan pakan per harinya rnenjadi lebih tinggi,
demikian pula kebutuhan oksigen perlu ditingkatkan. Pemberian pakan
harus disesuaikan dengan nafsu makan ikan. Pakan harus dikelola dengan baik untuk menarnbah atau mempercepat pertumbuhan yang dapat meningkatkan produksi tambak tersebut.
Keterkaitan Sum berdaya lkan dengan Ekosistem Mangrove
Secara ekologis, ekosistem mangrove memiliki peran utarna
sebagai daerah pemijahan (spawning ground), daerah asuhan
[nursery
ground) dan tempat mencari makan (feeding ground) sebagian besar jenis
biota laut (ikan, udang,
moluska)
yang bernilai ekonomi penting. Ekosistem mangrove juga berperan besar dalam pemeliharaan kualitas pesisir melalui: (1) penjebakan sedimen yang terdapat di kolarn air dan (2) pengeluaran nutrien dalam keadaan seirn bang (steady-state equilibrium) (Darovec (1975) dalam Kawaroe (2000)). Dan menurut Snedaker (1978)dalarn Kawaroe (2000), bahwa sekitar 90% dari jenis-jenis ikan laut
daerah tropika menghabiskan masa hidupnya paling tidak satu fase dalam
daur hidupnya, di daerah pesisir berhutan mangrove. Berarti ekosistem mangrove berfungsi sebagai plasma nuffah dan biodiversity. Selain ~ t u
hutan mangrove juga berfungsi sebagai pelindung daerah pesisir dari gempuran ombak (abrasi), gelombang tsunami dan angin taufan.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruslan (1986) di pantai Tirnur
Aceh menyatakan bahwa lebar jalur hijau di wilayah pesisir mempunyai hubungan yang nyata (signifikan) dengan produksi udang dari tambak tradisional dan produksi udang dari hasil tangkapan nelayan disekitarnya. Berdasarkan penelitian Fahrudin (1996) menunjukkan perubahan pemanfaatan lahan pesisir yang merusak hutan mangrove (misainya untuk tambak) dapat rnengakibatkan hilangnya karnponen surnberdaya hayati lain yang terkandung di dalamnya dan sumberdaya perikanan di wilayah
perairan sekitarnya. Komponen sumberdaya tersebut memiliki nilai
mengakibatkan hilangnya nilai ekonomi dari komponen hayati yang terkandung di dalamnya dan nilai ekonomi sumberdaya perikanan di
wilayah perairan sekitarnya.
Analisis SWOT
Untuk menganalisis strategi pengembangan mangrove untuk meningkatkan produktivitas budidaya tambak yang optimal di pesisir Kamal diperlukan suatu alat analisis. Sscara garis besa;, pengembangan konservasi mangrove untuk meningkatkan produktivitas budidaya tambak
dalam penelitian ini dipengaruhi oleh lingkungan yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Untuk kawasan mangrove, lingkungan ekstemal dapat menimbulkan ancaman dan memberikan peluang, sedangkan lingkungan internal dapat rnemberikan kekuatan dan
kelemahan.
Lingkungan ekstemal kawasan mangrove terdiri dari beberapa faktor yaitu pencemaran kualitas perairan berupa limbah padat maupun
cair, abrasi yang terjadi dan pembukaan lahan tambak yang tak terkendali
akan menjadi ancaman. Sedangkan produktivitas tambak yang tinggi serta harga ikan yang cukup baik dan stabil akan menjadi peluang. Lingkungan internal kawasan mangrove terdiri dari faktor yang akan memberi kekuatan seperti fungsi ekologis hutan mangrove yaitu sebagai daerah asuhan (nursery ground), pemijahan (spawning ground) dan pembesaran beberapa biota perairan, fungsi fisik hutan mangrove yaitu dapat menahan angin dan ornbak serta dominansi jenis mangrove tertentu sepeti
avicennia dan rhizopora yang cenderung lebih mudah hidupllebih tahan dibanding jenis lain. Sedangkan lingkungan peratran yang buruk, sampah, lemahnya pengawasan, pembinaan kawasan dan masyarakat dan tidak adanya sanksi yang tegas oleh instansi terkait serta pemahaman masyarakat yang kurang mengenai status kepemilikan lahan akan menjadi kelemahan pada penentuan strategi.
yang baik. Salah satu metode untuk melakukan pengkajian tersebut adalah rnenggunakan analisis SWOT.
Analisis SWOT adalah strategi deskriptif (kualitatif) berdasarkan hasil analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE). Tujuan analisis ini adalah untuk rnenguji ketepatan strategi yang
dijalankan dan mencari alternatif strategi baru. Menu rut Assael (1 990),
analisis SWOT dibagi menjadi dua analisis yang terpisah yaitu :
I. Strength and Weakness Analysis
Analisis ini mengevaluasi kemampuan kawasan mangrove untuk mengekploitasi kesernpatan-kesempatan dan kelemahan potensial yang dapat mengganggu dalam upaya pengelolaan kawasan. Analisis
ini berhubungan dengan analisis lingkungan internal (ALI) kawasan.
2. Opportunity and Threat Analysis
Analisis ini mengevaluasi bagaimana perubahan-perubahan lingkungan eksternal kawasan mangrove akan mempengaruhi kebijakan kawasan. Analisis ini berhubungan dengan analisis lingkungan eksternal (ALE)
kawasan .
Menurut Kinner dan Taylor (1993), keterkaitan faktor eksternal dan
internal yang dihadapi kawasan mangrove dapat digambarkan dalam matrik SWOT. Matrik SWOT adalah alat untuk meringkas faktor-faktor
strategis kawasan mangrove
yang
mengilustrasikan bagaimanaTabel 7. Matriks SWOT
Menurut Pearce (1 991), dalam melakukan analisis SWOT
Faktor Internal
STRENGTH WEAKNESS
!
Faktor - Eksternal ..
-!
1
Strategi S-0 strat-egi W - 0
Menggunakan kekuatan Berusaha mendapatkan
OPPORTUNlN yang dimiliki kawasan mangrove untuk keuntungan dari peluang yang dimiliki kawasan
sebaiknya rnenggunakan diagram analisis SWOT untuk menentukan
I__-
THREAT
strategi yang harus digunakan. Diagram analisis SWOT membagi keadaan strategi kedalarn empat buah daerah (kuadran)
yang
mengambil peluang yanp
ada Strategi S-T-
Menggunakan kekuatan yang dimiliki kawasan
mangrove untuk mengatasi ancaman yang
ada
masing-masing daerah mempunyai strategi yang berbeda. Garnbar
mangrove untuk mengatasi kelemahan-kelemahan . --
Strategi W-T
Berusaha meminimumkan kelemahan dan mengh~ndar~
I
I
ancaman yang dirn~l~kb
I
kawasan mangrove .I
diagram analisis SWOT dapat dilihat pada Gnmbar 2.
Berbagai Peluang
I
Sel 3
Mendukung strategi
Sel 1 Mendukung strategi "Agresif'
Kelemahan "Turnaround"
Internal
Berbagai Ancaman
-. .- Kekuatan
Internal Sel4
Mendukung strategi "Defensif'
Gambar 2. Diagram Analisis SWOT
Sel2
Mendukung
strateg i "Diversifikasi"
Penjelasan dari empat kuadran pada diagram analisis SWOT
Kuadran 1
Kawasan mangrove berada pada situasi yang sangat menguntungkan. Kawasan mangrove memiliki peluang dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan. Strategi yang harus ditetapkan adalah mendukung kebijakan pertum bu han yang agresif (growth oriented strategy).
Kuadran 2
Kawasan mangrove mulai mendapatkan ancaman tetapi masih
mempunyai kekuatan untuk meng hadapinya. Strategi yang harus diterapkan pada keadaan ini adalah menggunakan kekuatan untuk
memanfaaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi
diversifikasi.
Kuadran 3
Kawasan mangrove menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi dilain pthak juga dihadapkan pada beberapa kendala dan kelemahan internal. Strategi yang dapat digunakan pada keadaan ini adalah meminimalkan masalah internal kawasan mangrove sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik.
Kuadran 4
Kawasan mangrove dihadapkan pada situasi yang sangat tidak
menguntungkan. Kawasan mangrove harus menghadapi berbagai
Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2003 di kawasan Hutan Lindung Angke Kapuk, wilayah pesisir Kamal, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Lokasi penelitian in; ditentukan berdasarkan keberadaan hutan mangrove di kawasan tersebut. Tambak bandeng yang merupakan
lokasi penelitian adalah dua area tambak bandeng, lokasi yang pertama
adalah tambak bandeng yang berada di area hutan mangrove yang kondisinya relatif masih baik dan lokasi yang kedua adalah tambak bandeng yang hutan mangrovenya telah dikonversi. Lokasi penelitian
dapat dilihat pada Gambar 3. Bahan dan Alat
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan- bahan kimia kualitas air. Sedangkan peralatan yang digunakan terdiri dari:
Peralatan untuk mengambil contoh air (Kemmerer Water Sampler), Peralatan analisis kualitas air (pH
meter,
alat titrasi, labu takar, gelas ukur dan pipet),Peralatan untuk menghitung vegetasi mangrove (meteran, tali, spidol) Salinometer, Termometer.
4 Plankton
net
KuesionerPengambilan contoh air serta pengukuran parameter fisika, kimia dan biologi dilakukan di lokasi pengamatan. Metode, unit parameter terukur
dan lokasi pengukuran disajikan dalam Tabel 8. Pengumpulan Data dan lnformasi
Data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan yaitu data tentang vegetasi
hutan mangrove, dan kualitas air (parameter biologi, fisika dan kimia)
yang mempengaruhi kerusakan hutan mangrove baik yang internal maupun yang eksternal.
Data tentang vegetasi hutan mangrove meliputi data-data mengenai Tabel 8. Unit, Metode dan Lokasi Pengukuran Parameter Biologi,
Fisika-Kimia
jenis, jumlah tegakan dan diameter pohon, untuk data mangrove
mengambil 3 (tiga) stasiun dengan masing-masing stasiun diambil 3 (tiga) lokasi
- -insitu insitu
Insitu . .
Laboratoriurn ~abaratodum
,
plot yang disesuaikan dengan luasan mangrove yang ada. Plot-plot yang
~latlmetoda
Pengamatan Pencacahan
Meteran Plankton net
-- planktonjet . . _ _ - --
Parameter Biologi
Jenis mangrove
Jumiah tegakan Diameter pohon
Plankton , --
Benthos -. -.
digunakan berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 10 m x 10
rn
untukFisika
Unit
lndividu Cm l ndll '"dl1 .
. . . . -. . -. -. . . -
~ u h u - .. -..
;Padatan tersuspensi
- .-
+ NH4)
-
sampel jenis pohon, 5 m x 5 m untuk jenis
anakan,
d a n , 2 m x 2 m untuk jenis semai. Pembagian masing-masing kelas, yaitu kelas pohon memiliki.- -
.- - -
Lmrosen_-_.
. - I mgt~ . . . . - , , - . . - - - . . -" C -.
Mgll 0100 mgll mgll mgll mgll CaCo, mgll
diameter > 4 cm; Anakan rnerniliki diameter < 4
cm
dan tinggi > 1 m; dan semai memiliki tinggi < 1 m., . - . . . -. . -. . .-.... - - - .
Thermometer Hg insitu
~~ektrofotometer ~aboratoriuh . -
Analiasa tekstur Laboratorium
Data tentang kualitas air pada tambak diperoleh dengan melakukan H meter
Eefraktometer ..
DO meter
Botol gelapkrang Tetrimetrik
~~ektrofotorneter' Spektrofotometer
sampling dan mengambil contoh air pada masing-masing lokasi. Laboratorium ~a boratonum-! ~aboratoriurn i
~ahoratorium Laboratoriuy Laboratorium Laboratorium
Pengarn bilan contoh air serta pengukuran parameter fisika, kimia dan
[image:42.570.78.500.116.506.2]pengambilan sampel air dilakukan di 2 (dua) stasiun pantai yang menghadap mangrove yang kondistnya buruk dan yang kondisinya bag us. Dua stasiun
lainnya
ditempatkan pada tambak yang sumber airnyamelewati mangrove yang kondisinya buruk dan bag us.
lnformasi mengenai faktor-faktor sosial, ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi kerusakan hutan mangrove baik yang internal maupun yang eksternal didapat melalui wawancara dengan responden dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya.
Wawancara dilakukan terhadap 32 responden yang terdiri dari 28 petani
tambak tradisional, satu orang pejabat instansi Departemen Kelautan dan Perikanan setempat, satu orang pejabat Dinas Kehutanan DKI
Jakarta, satu orang petugas jagawana dan satu orang petugas penyuluh perikanan. Metode penentuan pengambilan responden dilakukan secara purposive sampling. Defenisi petani tambak tradisional dalam penelitian
ini adalah petani yang dalam mengelola tambaknya tidak menggunakan teknologi, seperti kipas, mesin pompa air dan lain-lain.
Data sekunder
yang
diperlukan dalam penelitian ini adalah data produksi tambak per satu kali panen pada dua lokasi tambak yangmenjadi lokasi penelitian. Data produksi yang diperlukan adalah data selama beberapa periode panen. Data sekunder yang mendukung penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, baik hasil-hasil penelitian terdahulu maupun tulisan-tulisan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, data-data tersebut diperoleh dari:
Balai Penelitian Perikanan laut (BPPL), Dinas Perikanan DKI Jakarta
Dinas Kehutanan DKI Jakarta
Kantor Kecamatan Penjaringan
Kantor Kelurahan Karnal
Analisis Data
Analisis data dilakukan
dengan
beberapa tahap mulai dari analisis parameter biologi, fisika dan kimia perairan.a. Kerapatan Jenis
Kerapatan jenis (Di) yaitu jumiah Jenis tegakan jenis I dalam suatu
unit area (Bengen,2000)
Di = nilA
Dimana: Di = Kerapatan jenis ke-i
ni = Jurnlah total individu dari jenis I
A =
Luas
total pengambilan contohb.
Kerapatan RelatifMenurut Bengen (2000) kerapatan relatif (RDi), yaitu perbandingan antara jumlah tegakan jenis ke-i (ni) dan tegakan seluruh jenis (En) :
Rdi
=
(niEn) x 100%Dimana: Rdi = Kerapatan relatif
( I n ) = Kerapatan seluruh jenis
c. Frekuensi
Frekuensi (Fi), yaitu peluang ditemukannya suatu jenis ke-t dalam semua petak contoh yang dibuat (Bengen, 2000):
Fi = piEp
Dimana: Fi = Frekuensi relatif
PI = Jumlah petak contoh dimana ditemukan jenis ke-i Cpi = jumlah total petak contoh yang dibuat
d. Frekuensi Relatif
Menurut Bengen (2000), frekuensi relatif adalah perbandingan antara frekuensi
jenis (Fi) dan jumiah frekuensi untuk seluruh jenis (CF) : Fri = (FiICF) x 100%
Dimana : FRi = Frekuensi relatif
Fi = Frekuensi jenis ke-i
e. Penutupan Jenis
Penutupan jenis (Ci) adalah luas penutupan jenis ke-i delam suatu unit area tertentu Bengen, 2000)
Ci = CBNA
Dimana: Ci = Penutupanjenis
BA = nd214 (d
=
diameter batang setinggi dada, n(3.14)konstanta)
A = Luas total area pengambilan contoh. f. Penutupan Relatif
Penutupan relatif (RCi), yaitu perbandingan antara penutupan jenis
ke-I (Ci) dengan luas total penutupan untuk seluruh jenis (CC) Bengen
(2000)
RCi = (CiEC) x 100%
Dimana RCi = Penutupan relatif
Ci = Penutupan jenis ke-i
XC
= Penutupan total untuk seluruh jenisg. lndeks Nilai Penting
Jumlah nilai kerapatan relam (RDi), frekuensi relatif (FRi) dan
penutupan relatif jenis (RCi) untuk jenis ke-i dari mangrove disebut lndeks
Nilai Penting (INP) menurut Bengen(2000):
INP
=
RDi+
RFi + RCiNilai penting suatu jenis berkisar antar
0
sampai 300. Nilai penting inimemberikan gambaran mengenai pengaruh atau
peranan
suatu jenis mangrove dalam ekosistem.Pada vegetasi mangrove akan ditentukan kualitas lingkungan
mangrove. Kualitas lingkungan mangrove dihitung berdasarkan 6 indikator (Lower Mississipi Valley Division dalam Canter dan Hill, 1981). lndikator tersebut adalah asosiasi spesies, penutupan kanopi ( O h ) , penutupan semai
(%), jumlah jenis semai, jumlah hari tergenang dan luasan daerah yang terkena pengaruh pasang surut air laut. Pada penelitian ini hanya