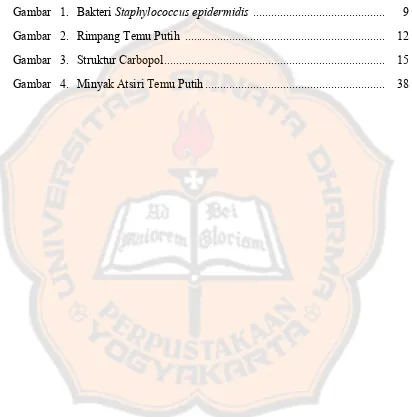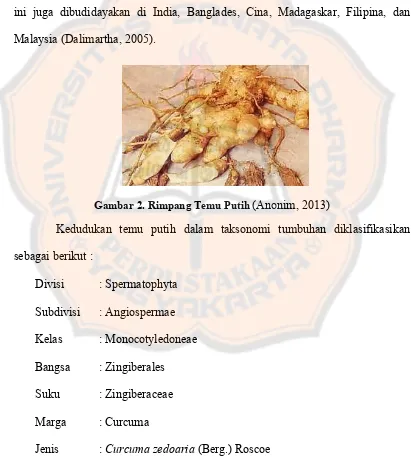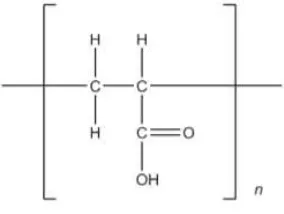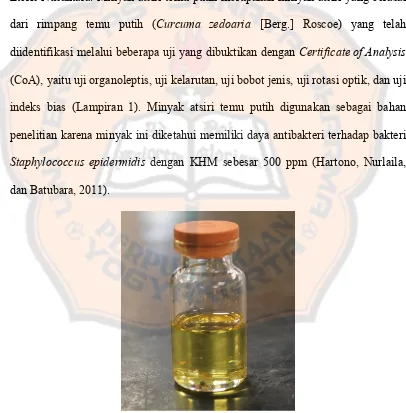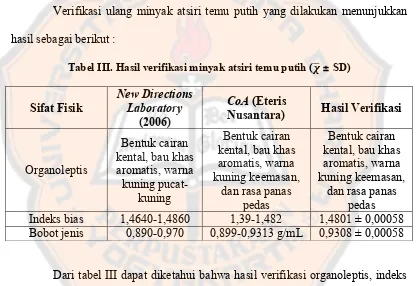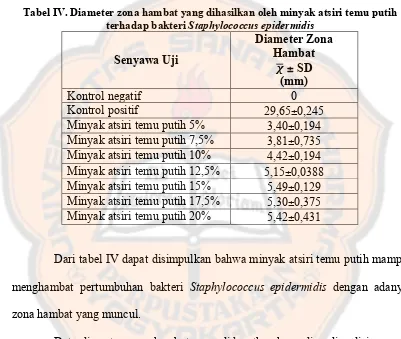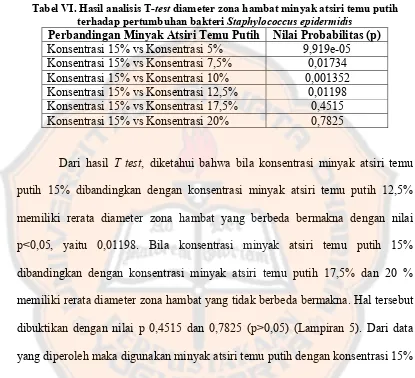FORMULASI SEDIAAN EMULGEL MINYAK ATSIRI TEMU PUTIH (Curcuma zedoaria [Berg.] Roscoe) DENGAN VARIASI CARBOPOL 940 SEBAGAI GELLING AGENT DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERINYA
TERHADAP BAKTERI Staphylococcus epidermidis ATCC 12228
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S. Farm.)
Program Studi Farmasi
Oleh :
Felicia Aniska
NIM : 108114090
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
i
FORMULASI SEDIAAN EMULGEL MINYAK ATSIRI TEMU PUTIH (Curcuma zedoaria [Berg.] Roscoe) DENGAN VARIASI CARBOPOL 940 SEBAGAI GELLING AGENT DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERINYA
TERHADAP BAKTERI Staphylococcus epidermidis ATCC 12228
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S. Farm.)
Program Studi Farmasi
Oleh :
Felicia Aniska
NIM : 108114090
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
HALAMAN PERSEMBAHAN
Good things come to those who believe, better things come to those who are patient, and the best things come to those who don’t give up.
My life isn’t perfect but I’m thankful for everything I have.. ♥ Today is a perfect day to start living your dreams. Make it happened!!
vii
PRAKATA
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan
Bunda Maria atas berkat, rahmat, dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Formulasi Sediaan Emulgel Minyak Atsiri
Temu Putih (Curcuma zedoaria [Berg.] Roscoe) dengan Variasi Carbopol 940 sebagai Gelling Agent dan Uji Aktivitas Antibakterinya terhadap Bakteri
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228” ini dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Farmasi (S. Farm.)
program studi Farmasi.
Penulis menyadari bahwa selama proses perkuliahan menempuh masa
studi S1 sampai penyusunan skripsi ini selesai, penulis telah menerima dukungan
baik dalam doa, bimbingan, arahan, saran, maupun kritik yang membangun dari
berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Ipang Djunarko, M. Sc., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ibu Christofori Maria Ratna Rini Nastiti, M. Pharm., Apt., selaku Kaprodi
Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, sekaligus Dosen Pembimbing
Skripsi yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, pengarahan,
masukan, semangat serta motivasi kepada penulis dari pembuatan proposal
3. Ibu Dr. Erna Tri Wulandari, M. Si., Apt., selaku dosen penguji yang telah
memberikan waktu, masukan, kritik dan saran kepada penulis.
4. Ibu Damiana Sapta Candrasari, M. Sc., selaku dosen penguji yang telah
memberikan waktu, masukan, kritik dan saran kepada penulis.
5. Ibu Maria Dwi Budi Jumpowati, S. Si., atas masukan dan arahan dalam
bidang Mikrobiologi kepada penulis.
6. Segenap dosen Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma yang telah
mengajar dan membimbing penulis selama perkuliahan.
7. Bapak Mukmin, Bapak Musrifin, Bapak Agung, Bapak Iswandi, serta
laboran-laboran lain yang telah membantu penulis selama penelitian.
8. Orang tua penulis, yang telah memberikan doa, cinta, kasih sayang, dukungan,
semangat, dan motivasi yang luar biasa kepada penulis dari kecil hingga saat
ini.
9. Adik penulis, Yovan, atas semangat, dukungan, dan doa yang diberikan.
10.Teman-teman skripsi senasib seperjuangan, Angga, Wulan, Dian, Odil,
Tomas, dan Samuel atas kerbersamaan dan kerjasama baik suka maupun duka,
dari awal hingga selesainya penyusunan skripsi.
11.Sahabat-sahabatku, Lulu, Stephanie, dan Maria, atas doa, semangat,
dukungan, dan kebersamaan yang telah diberikan.
12.Teman-teman Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma atas kebersamaan
ix
13.Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu karena keterbatasan
penulis atas segala doa, bantuan, dan dukungan selama proses penelitian dan
penyusunan skripsi.
Penulis menyadari bahwa laporan akhir skripsi ini masih memiliki
banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis.
Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari
berbagai pihak. Penulis berharap semoga laporan akhir skripsi ini dapat berguna
bagi seluruh pihak dalam kepentingan akademik, terutama dalam bidang farmasi.
Yogyakarta, 29 Mei 2014
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ………... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ………... ii
HALAMAN PENGESAHAN ………... iii
HALAMAN PERSEMBAHAN ……… iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ……….. v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ……… vi
PRAKATA ………. vii
B. Bakteri Staphylococcus epidermidis ………..… 9
C. Minyak Atsiri ………. 10
D. Minyak Atsiri Temu Putih ………...….. 12
E. Emulgel ……….. 13
F. Carbopol ………. 15
xi
BAB III. METODE PENELITIAN ………... 24
A. Jenis dan Rancangan Penelitian ………... 24
B. Variabel Penelitian ………... 24
C. Definisi Operasional ……….. 25
D. Bahan Penelitian ……… 27
E. Alat Penelitian ……… 27
F. Tata Cara Penelitian ………... 27
1. Verifikasi Minyak Atsiri Rimpang Temu Putih ……….. 27
2. Uji Antibakteri Minyak Atsiri Temu Putih terhadap Bakteri Staphylococcus epidermidis ……… 29
3. Formula Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih ………. 32
4. Pembuatan Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih ……..………... 33
5. Pembuatan Kontrol Positif Emulgel Clindamycin 0,2% ……… 33
6. Uji pH Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih ……… 34
7. Uji Sifat Fisik Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih ……… 34
8. Uji Daya Antibakteri Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih terhadap Bakteri Staphylococcus epidermidis dengan Metode Difusi Sumuran ………... 35
G. Analisis Hasil ………... 37
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ……….. 38
A. Identifikasi dan Verifikasi Minyak Atsiri Temu Putih ……….. 38
B. Uji Daya Antibakteri Minyak Atsiri Temu Putih terhadap Bakteri Staphylococcus epidermidis ………... 40
D. Uji Sifat Fisik Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih ………... 50
E. Uji Stabilitas Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih ………. 54
F. Uji Daya Antibakteri Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih terhadap Bakteri Staphylococcus epidermidis ………... 55
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ………... 60
A. Kesimpulan ………...………... 60
B. Saran ………...………... 60
DAFTAR PUSTAKA ………...………... 61
LAMPIRAN ………...………... 66
xiii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel I. Formula basis emulgel (200 g) ... 32
Tabel II. Formula emulgel minyak atsiri temu putih dengan perbandingan
komposisi carbopol 940 (100 g) ... 32
Tabel III. Hasil verifikasi minyak atsiri temu putih ... 39
Tabel IV. Diameter zona hambat yang dihasilkan oleh minyak atsiri temu
putih terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis ... 43 Tabel V. Nilai probabilitas uji Shapiro-Wilk diameter zona hambat minyak
atsiri temu putih terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus
epidermidis ... 44 Tabel VI. Hasil analisis T-test diameter zona hambat minyak atsiri temu
putih terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis .. 45 Tabel VII. Hasil uji pH emulgel minyak atsiri temu putih ... 51
Tabel VIII. Hasil uji viskositas dan daya sebar emulgel atsiri minyak temu
putih ... 53
Tabel IX. Nilai probabilitas uji Kruskal-Wallis stabilitas viskositas emulgel minyak atsiri temu putih ... 54
Tabel X. Diameter zona hambat yang dihasilkan oleh emulgel minyak atsiri
temu putih terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis ... 56 Tabel XI. Nilai probabilitas uji Shapiro-Wilk diameter zona hambat emulgel
minyak atsiri temu putih terhadap pertumbuhan bakteri
Staphylococcus epidermidis ... 57 Tabel XII. Nilai probabilitas T-test diameter zona hambat minyak atsiri temu
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Bakteri Staphylococcus epidermidis ... 9
Gambar 2. Rimpang Temu Putih ... 12
Gambar 3. Struktur Carbopol ... 15
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1. Certificate of Analysis Zedoaria Oil ... 66 Lampiran 2. Sertifikat Hasil Uji Staphylococcus epidermidis ATCC
12228 ... 67
Lampiran 3. Verifikasi Minyak Atsiri Temu Putih ... 68
Lampiran 4. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Minyak Atsiri Temu Putih ... 69
Lampiran 5. Hasil Analisis Statistik Data Diameter Zona Hambat Minyak
Atsiri Temu Putih terhadap Bakteri Staphylococcus
epidermidis ... 72 Lampiran 6. Konversi Minyak Atsiri Temu Putih ... 92
Lampiran 7. Hasil Uji Sifat Fisik dan Stabilitas Emulgel Atsiri Minyak
Temu Putih ... 94
Lampiran 8. Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih ... 102
Lampiran 9. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Emulgel Atsiri Minyak Temu
Putih ... 104
Lampiran 10. Hasil Analisis Statistik Data Diameter Zona Hambat Emulgel
Minyak Atsiri Temu Putih terhadap Bakteri Staphylococcus epidermidis ... 107 Lampiran 11. Hasil Analisis Statistik Data Diameter Zona Hambat Minyak
Atsiri Temu Putih terhadap Bakteri Staphylococcus
INTISARI
Kandungan minyak atsiri rimpang temu putih (Curcuma zedoaria [Berg.] Roscoe) telah terbukti memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri
Staphylococcus epidermidis. Berdasarkan hal tersebut, minyak atsiri temu putih berpotensi untuk diformulasikan menjadi sediaan topikal emulgel. Emulgel dibuat dalam tiga formula dengan variasi komposisi carbopol 940 sebagai gelling agent. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan emulgel minyak atsiri temu putih sesuai dengan kriteria, mengetahui ada tidaknya aktivitas antibakteri emulgel minyak atsiri temu putih terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis, dan mengetahui pengaruh variasi komposisi carbopol 940 dalam sediaan emulgel minyak atsiri temu putih terhadap sifat fisik dan kemampuannya sebagai antibakteri pada bakteri Staphylococcus epidermidis.
Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimental murni rancangan acak lengkap pola searah. Sifat fisik emulgel yang diamati meliputi organoleptis, pH, viskositas, daya sebar, dan stabilitas emulgel, yaitu mengamati viskositas 48 jam dan tiap minggu selama 1 bulan. Analisis data menggunakan ANOVA satu arah dengan taraf kepercayaan 95%, selanjutnya dilakukan T-test dengan menggunakan aplikasi program R versi 3.0.1.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa emulgel minyak atsiri temu putih FI dan FII memiliki sifat fisik sesuai kriteria, sedangkan FIII tidak. Emulgel minyak atsiri temu putih memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus epidermidis. Penambahan konsentrasi carbopol 940 pada sediaan emulgel minyak atsiri temu putih berbanding terbalik dengan aktivitas antibakteri yang diukur melalui diameter zona hambat terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis.
xvii
ABSTRACT
The content of zedoaria oil (Curcuma zedoaria [Berg.] Roscoe) had been shown to have antibacterial activity against Staphylococcus epidermidis. Based on this, zedoaria oil had the potential to be formulated into topical emulgel preparations. Emulgel was made in three formulas with compositional variation of carbopol 940 as a gelling agent. This research aimed to ensure the emulgel of zedoaria oil according to the criteria, to determine whether there was antibacterial activity in emulgel of zedoaria oil against Staphylococcus epidermidis, and to determine the effect of variations in the composition of Carbopol 940 in emulgel of zedoaria oil on physical properties and its ability as antibacterial.
This research was a pure experimental research with completely randomized one-way design. The physical properties of the emulgel of zedoaria oil that observed was organoleptic characteristics, pH, viscosity, spreadability, and stability of emulgel, by observing the viscosity at 48 hours and every week for 1 month. Analysis of data was using one-way ANOVA with a confidence level of 95%, and then followed by T-test using application program R version 3.0.1.
The results showed the emulgel of zedoaria oil in FI and FII had physical properties which matched the criteria, while FIII did not. Emulgel of zedoaria oil had antibacterial activity against Staphylococcus epidermidis. The increase of carbopol 940 concentration in emulgel of zedoaria oil was inversely proportional to the antibacterial activity which was measured by inhibition zone diameter against Staphylococcus epidermidis.
BAB I PENGANTAR
A. LATAR BELAKANG
Bau kaki merupakan salah satu masalah yang biasanya menggangu
kehidupan sehari-hari seseorang. Bau kaki seringkali membuat orang merasa
kurang percaya diri karena aroma yang ditimbulkan dapat mengganggu orang di
sekitarnya. Aroma yang kurang sedap ini biasanya akan muncul ketika seseorang
mulai berkeringat. Pada dasarnya keringat tidak bau, biasanya bau yang tidak
sedap timbul oleh aktivitas bakteri Staphylococcus epidermidis. Bakteri ini akan mendegradasi leusin dalam keringat menjadi asam isovaleric yang menjadi penyebab bau kaki (Ara, et al., 2006).
Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam,
merupakan negara yang sangat potensial dalam penyediaan bahan baku alami
untuk pembuatan obat maupun kosmetik. Ribuan jenis tumbuhan yang diduga
berkhasiat sudah sejak lama secara turun-temurun dimanfaatkan oleh masyarakat
kita. Sesuai dengan perkembangan ilmu dalam dunia kefarmasian, banyak orang
yang memanfaatkan tanaman karena dianggap lebih aman dan memiliki resiko
efek samping yang lebih rendah. Dalam setiap tanaman pasti mengandung suatu
senyawa yang dapat berguna dan memiliki efektivitas farmakologis tertentu, oleh
Temu putih (Curcuma zedoaria [Berg.] Roscoe) merupakan salah satu tanaman yang dapat dikembangkan dalam dunia kefarmasian. Menurut berbagai
penelitian eksperimental menunjukkan bahwa temu putih berkhasiat sebagai
antijamur, antineoplastik, antibakteri, dan antitrombotik (Chang and But, 1987). Rimpang temu putih mengandung minyak atsiri. Minyak atsiri rimpang temu
putih memiliki daya antibakteri terhadap beberapa jenis bakteri patogen, salah
satunya adalah Staphylococcus epidermidis yang merupakan salah satu flora alami pada kulit manusia yang dapat menimbulkan bau kaki. Melalui penelitian yang
dilakukan oleh Hartono, Nurlaila, dan Batubara (2011), diketahui bahwa pada
konsentrasi 500 ppm, minyak atsiri rimpang temu putih sudah bisa menghambat
pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis.
Sediaan topikal emulgel minyak atsiri temu putih dapat menjadi salah
satu alternatif pengatasan bau kaki yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus epidermidis. Emulgel merupakan suatu sediaan kombinasi emulsi dan gel, yaitu campuran emulsi baik tipe M/A maupun A/M, dengan gelling agent sebagai agen pembentuk gel dengan konsentrasi tertentu (Suryarini, 2011). Bentuk sediaan
topikal emulgel tipe M/A ini digunakan untuk formulasi minyak atsiri rimpang
temu putih yang bersifat lipofil. Bentuk sediaan ini perlu dilakukan uji dan
evaluasi agar tercapai bentuk sediaan yang diharapkan sehingga mampu
melepaskan zat aktif dengan baik.
polimer sintesis dengan bobot molekul tinggi dari ikatan silang asam akrilat
dengan alil eter dari sukrosa lain atau alil eter dari pentaerythritol (Stephenson
and Karsa, 2000). Carbomer dapat meningkatkan viskositas. Viskositasnya lebih tinggi pada pH 6-11 dan viskositasnya akan berkurang pada pH kurang dari 3 atau
lebih dari 12 (Rowe, Sheskey, and Quinn, 2009). Bila carbomer memiliki viskositas yang baik, maka pelepasan zat aktif yang diberikan baik pula (Patil,
2005).
1. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ada adalah
sebagai berikut :
a. Apakah sediaan emulgel minyak atsiri rimpang temu putih memiliki sifat
fisik yang memenuhi kriteria?
b. Apakah sediaan emulgel minyak atsiri rimpang temu putih memiliki
aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis?
c. Bagaimana pengaruh variasi komposisi carbopol 940 sebagai gelling agent dalam sediaan emulgel minyak atsiri rimpang temu putih terhadap sifat fisik dan kemampuannya sebagai antibakteri pada bakteri
2. Keaslian Penelitian
Adapun penelitian terkait yang telah dilakukan oleh Maiyani Hartono,
Nurlaila, Irmanida Batubara (2011), yaitu “Potensi Temu Putih (Curcuma zedoaria) sebagai Antibakteri dan Kandungan Senyawa Kimia”. Dalam penelitian ini, yang dilakukan adalah menganalisis kandungan yang terdapat
dalam minyak atsiri temu putih dan menguji aktivitasnya terhadap bakteri
Bacillus subtilis dan Staphylococcus epidermidis.
Pada penelitian Lai, et al. (2004) berjudul “Antimicrobial Activity and Cytotoxicity of The Essential Oil of Curcuma zedoaria”, yang dilakukan adalah menguji sitotoksisitas dan daya antibakteri minyak atsiri rimpang temu
putih dengan konsentrasi 500 ppm terhadap pertumbuhan beberapa bakteri.
Dari penelitian ini diperoleh bahwa minyak atsiri temu putih memiliki
aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram positif seperti Staphylococcus aureus, Bacillus cereus dan bakteri gram negatif sepert Escherechia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Vibrio parahaemolyticus, dan Salmonella typhimurium.
Pada penelitian Angel, Vimala, and Nambisan (2012), “Antioxidant and Antimicrobial Activity of Essential Oils from Nine Starchy Curcuma Species”, membandingkan aktivitas antioksidan dan antibakteri minyak atsiri yang
terkandung dari sembilan tumbuhan genus Curcuma, diperoleh bahwa minyak atsiri rimpang temu putih memiliki kandungan fenol paling banyak
memiliki daya antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, dan Escherichia coli.
Pada penelitian Kurniawan, Wijayanto, and Sobri (2012) berjudul “Formulation and Effectiveness of Antiseptic Hand Gel Preparations
Essential Oils Galanga (Alpinia galanga)”. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh sediaan gel yang sesuai dengan kriteria sifat fisik
dan stabil selama penyimpanan, serta efektif sebagai antiseptik. Formulasi gel
dibuat dengan variasi carbopol 940 (FI = 0,5%, FII = 1,25%, dan FIII = 2%).
Hasil yang diperoleh yaitu ketiga formula gel stabil dalam penyimpanan,
viskositas semakin turun dan daya sebar semakin meningkat selama
penyimpanan. Formula gel FI menjadi formula yang paling baik karena
memiliki efektivitas yang lebih besar bila dibandingkan dengan FII dan FIII.
Pada penelitian Agustina (2013) berjudul “Formulasi Emulgel Minyak
Cengkeh (Oleum caryophylli) sebagai Antibau Kaki : Pengaruh Carbopol 940 dan Sorbitol Terhadap Sifat Fisik dan Stabilitas Fisik”. Peneliti
memformulasikan minyak cengkeh menjadi sediaan topikal emulgel karena
merupakan salah satu pembawa yang baik bagi zat aktif yang bersifat
hidrofobik. Penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh dari carbopol 940
dan sorbitol pada level yang diteliti terhadap sifat fisik dan stabilitas fisik
emulgel minyak cengkeh. Dari penelitian tersebut didapat bahwa carbopol
940 berpengaruh pada viskositas dan daya sebar dari sediaan. Semakin tinggi
konsentrasi carbopol 940, semakin tinggi viskositas dan semakin rendah daya
Sejauh penelusuran pustaka yang telah dilakukan oleh penulis, penelitian
dengan judul “Formulasi Sediaan Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih
(Curcuma zedoaria [Berg.] Roscoe) dengan Variasi Carbopol 940 sebagai
Gelling Agent dan Uji Aktivitas Antibakterinya terhadap Bakteri
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228” belum pernah dilakukan sebelumnya.
3. Manfaat Penelitian a. Manfaat teoretis
Manfaat teoretis dalam penelitian ini adalah untuk menambah
pengetahuan mengenai potensi aktivitas antibakteri dari sediaan emulgel
minyak atsiri rimpang temu putih terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis.
b. Manfaat praktis
Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan sediaan
topikal emulgel minyak atsiri rimpang temu putih dengan sifat-sifat fisik
yang diharapkan dan efektif memiliki aktivitas antibakteri terhadap
bakteri Staphylococcus epidermidis.
B. TUJUAN PENELITIAN 1. Tujuan Umum
Tujuan umum dalam penelitian ini adalah membuat sediaan emulgel dengan
2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Memastikan bahwa sediaan emulgel minyak atsiri rimpang temu putih
memiliki sifat fisik yang memenuhi kriteria.
b. Mengetahui ada tidaknya aktivitas antibakteri dari sediaan emulgel
minyak atsiri rimpang temu putih terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis.
c. Mengetahui pengaruh variasi komposisi carbopol 940 sebagai gelling agent dalam sediaan emulgel minyak atsiri rimpang temu putih terhadap sifat fisik dan kemampuannya sebagai antibakteri pada bakteri
8
BAB II
PENELAAHAN PUSTAKA
A. Bau Kaki
Bau kaki merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat
mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang. Bau kaki disebabkan karena
adanya kelebihan keringat dan aktivitas bakteri pada kaki. Bakteri tumbuh di
telapak kaki yang sebenarnya menghasilkan gas-gas serupa dengan yang
dihasilkan bakteri untuk memproduksi bau seperti keju (cheesy feet) (Podiatrivic,
2002).
Aroma yang kurang sedap ini biasanya muncul ketika kaki mulai
berkeringat. Keringat pada kaki berasal dari kelenjar eccrine. Keringat ini cenderung menguap cukup cepat dan biasanya tidak menimbulkan bau. Namun,
kaki manusia memiliki sekitar 1 juta sampai 5 juta kelenjar keringat di tubuh,
sehingga ada konsentrasi yang lebih tinggi dari keringat di badan (Freeman, 2012).
Bau kaki disebabkan karena pertumbuhan bakteri yang menggunakan
hasil sekresi dari apocrine (keringat apokrin berasal dari kelenjar apokrin yang
terdiri dari protein, asam amino, lipid, karbohidrat dan air), eccrine(keringat ekrin
dari kelenjar ekrin terdiri dari NaCl, asam asetat, asam propionat, asam kaproat,
asam kaprionat, asam laktat, asam sitrat, urea dan air), dan sebaceous gland
Dalam penelitian Kobayashi (1990), ditemukan bahwa Staphylococcus epidermidis, yang merupakan flora normal kulit, memainkan peran utama dalam menimbulkan bau kaki. Di dalam keringat terdapat kandungan asam amino,
seperti leusin, valin, dan isoleusin. Bakteri ini akan mendegradasi leusin dalam
keringat dengan bantuan enzim leusin dehidrogenase menghasilkan isovaleric acid yang diketahui menjadi penyebab bau kaki. Isovaleric acid merupakan suatu senyawa asam lemak rantai pendek (Ara, et al., 2006).
B. Bakteri Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus epidermidis adalah salah satu spesies bakteri dari genus
Staphylococcus yang diketahui dapat menyebabkan infeksi oportunistik (menyerang individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah). Beberapa
karakteristik bakteri ini adalah fakultatif, koagulase negatif, katalase positif, gram
positif, berbentuk kokus, dan berdiameter 0,5-1,5 µm (Jawetz, Melnick, and
Adelberg, 1996).
Lingkungan hidup bakteri Staphylococcus epidermidis adalah kulit
manusia. Bakteri ini biasanya hidup pada kulit dan merupakan patogen
nosokomial (penyebab infeksi silang yang diperoleh dari pasien lain).
Staphylococcus epidermidis adalah staphylococcus paling umum di kulit manusia
(Mack, Davies, Harris, Rohde, Horstkotte, and Knobloch, 2007).
Berikut adalah klasifikasi dari bakteri Staphylococcus epidermidis : Kerajaan : Bacteria
Spesies : Staphylococcus epidermidis
(Jawetz, Melnick, and Adelberg, 1996).
C. Minyak Atsiri
Minyak atsiri adalah senyawa aromatik yang terdapat dalam berbagai
jenis tanaman karena mudah menguap ketika dibiarkan terbuka di udara, maka
disebut volatile oil, minyak eteris atau minyak essensial. Minyak atsiri biasanya tidak bewarna, segar, tetapi dalam jangka waktu yang lama dapat teroksidasi dan
mengalami pendamaran yang menyebabkan warna menjadi gelap. Bagi tumbuhan,
minyak atsiri merupakan produk metabolisme sekunder tanaman yang bersifat
Minyak atisiri merupakan senyawa minyak berasal dari tumbuhan dan
terdistribusi pada bagian bagian tumbuhan seperti daun, bunga, dan akar serta
batang. Minyak atsiri sangat mudah menguap pada suhu kamar. Minyak atsiri
memiliki bau khas seperti tanaman aslinya dan dapat teroksidasi oleh matahari
sehingga warnanya menjadi gelap. Minyak atsiri juga mengalami pendamaran
(Harborne, 1996).
Komponen minyak atsiri dapat dibagi menjadi 2 golongan besar
didasarkan pada biosintesisnya sebagai berikut :
1. Derivat terpen yang dibentuk melalui jalur asam asetat mevalonat.
2. Komponen aromatik yang dibentuk melalui jalur sikimat fenil propanoid
(Tyler, Brady, and Robbers, 1988).
Sifat antibakteri dari minyak atsiri dan komponennya telah ditinjau,
namun mekanisme kerja belum diteliti dengan sangat rinci. Karena banyaknya
konstituen, minyak atsiri tampaknya tidak memiliki target seluler tertentu. Dengan
sifat lipofil yang sama, mereka melewati dinding sel dan membran sitoplasma,
mengganggu struktur dari lapisan pada polysaccharides, fatty acids dan
phospholipid. Pada bakteri, permeabilitas dari membran dikaitkan dengan hilangnya ion-ion dan reduksi potensial membran, terganggunya pompa proton,
dan berkurangnya ATP. Minyak atsiri mengentalkan sitoplasma, merusak lipid
dan protein. Kerusakan pada dinding sel dan membran dapat menyebabkan
kebocoran (leakage) makromolekul dan lisis (Tripathi, Chawla, Upadhyay, and
D. Minyak Atsiri Temu Putih
Temu putih ditanam sebagai tanaman obat dan dapat ditemukan tumbuh
liar pada tempat-tempat terbuka yang tanahnya lembab pada ketinggian 0-1000
meter di atas permukaan laut. Temu putih banyak ditemukan di Indonesia seperti
di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, Ambon, hingga Irian. Selain itu, tanaman
ini juga dibudidayakan di India, Banglades, Cina, Madagaskar, Filipina, dan
Malaysia (Dalimartha, 2005).
Gambar 2. Rimpang Temu Putih (Anonim, 2013)
Kedudukan temu putih dalam taksonomi tumbuhan diklasifikasikan
sebagai berikut :
Jenis : Curcuma zedoaria (Berg.) Roscoe
Menurut berbagai penelitian eksperimental, temu putih berkhasiat
sebagai antijamur, antineoplastik, antibakteri, dan antitrombotik (Chang and But, 1987). Rimpang temu putih mengandung 1-2,5% minyak menguap dengan
komposisi utama sesquiterpene. Minyak menguap tersebut mengandung lebih dari 20 komponen seperti curzerenone (zedoarin) yang merupakan komponen terbesar,
1,8-cineole, germacrone, curzerene, Epicurzerenone, cymene, α-phellandrene, β
-eusdesmol, curcumin, furanodiene, furanodienone, zederone, curzeone,
13-hydroxygermacrone, dihydrocurdione, curcumenone, zedoaronediol, curcumenol,
zedoarol, curcumanolide-A, curcumanolide-B, ethyl para-methoxycinnamate,
b-turmerone, zingiberene, dihydrocurcumin, curdione, neocurdione (Lobo, Prabhu, Shirwaikar, and Shirwaikar, 2009).
Minyak atsiri rimpang temu putih memiliki daya antibakteri terhadap
beberapa jenis bakteri patogen, salah satunya adalah Staphylococcus epidermidis
yang dapat menimbulkan bau kaki. Melalui penelitian diketahui bahwa pada
konsentrasi 500 ppm, minyak atsiri rimpang temu putih sudah bisa menghambat
pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis (Hartono, Nurlaila, dan Batubara, 2011).
E. Emulgel
Gel merupakan sistem semipadat yang terdiri dari suspensi yang dibuat
dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar dan
terpenetrasi oleh suatu cairan (Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan,
keterbatasan sebagai penghantar obat-obat yang bersifat hidrofobik (Khullar,
Kumar, and Saini, 2011). Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, maka dilakukan
pendekatan berbasis emulsi. Ketika gel dan emulsi dikombinasikan bersama
menjadi suatu sediaan, sediaan tersebut dikenal sebagai emulgel. Emulgel
membantu mengatasi masalah tersebut, droplet-droplet minyak akan terdispersi
dalam fase air menghasilkan emulsi tipe oil in water (O/W). Kemudian emulsi ini yang akan dicampur dalam basis gel. Hal ini dapat meningkatkan stabilitas dan
pelepasan obat (Panwar, Upadhyay, Bairagi, Gujar, Darwhekar, and Jain, 2011). Menurut Voigt (1994), gel pada penggunaan topikal memiliki beberapa
kelebihan, yaitu kemampuan penyebaran pada kulit baik, efek dingin yang
dijelaskan melalui penguapan lambat dari kulit, kemudahan pencucian dengan air,
dan pelepasan obat yang baik. Emulsi memiliki kemampuan penetrasi yang tinggi
ke dalam kulit (Bhanu, Shanmugam, and Lakshmi, 2011). Emulsi diaplikasikan untuk pemberian minyak dan obat cair bersama, dengan tujuan menyamarkan rasa,
bau, dan penampilan yang tidak menyenangkan, bahkan kadang untuk
mendukung absorpsi pada obat-obat tertentu (Allen Jr., 2002).
Emulgel (emulsion in gel) merupakan emulsi baik tipe oil-in-water
maupun water-in-oil yang dimodifikasikan dengan gelling agent. Emulgel
memiliki tingkat penerimaan yang tinggi sebagai sediaan topikal sebab memiliki
gabungan kelebihan dari gel dan emulsi (Bhanu, Shanmugam, and Lakshmi, 2011). Emulgel memiliki sifat-sifat menguntungkan, antara lain dapat
melembabkan, mudah penyebarannya, mudah dihilangkan, larut dalam air, dan
Emulgel dibuat dengan cara mencampurkan emulsi dan gel pada
perbandingan tertentu. Pada formula emulgel terdapat bahan tambahan yang
digunakan agar membentuk bentuk sediaan yang stabil, yaitu :
1. Emulsifying agent untuk menghasilkan emulsi yang stabil, dengan menurunkan tegangan muka antar fase pendispersi dan fase terdispersi, yang
pada umumnya memiliki perbedaan polaritas sehingga tidak dapat bercampur
(Pena, 1990).
2. Gelling agent digunakan membentuk tiga ikatan dimensional yang akan membatasi gerak kinetik dari fase pendispersi, dengan ini maka akan
meningkatkan viskositas dari suatu sediaan (Rowe, Sheskey, and Quinn, 2009).
F. Carbopol
Carbopol atau carbomer merupakan gelling agent yang sering digunakan untuk menghasilkan gel ataupun emulgel dengan karakteristik yang diinginkan.
Carbomer berasal dari polimer sintesis dengan bobot molekul tinggi dari ikatan
silang asam akrilat dengan alil eter dari sukrosa lain atau alil eter dari
Mekanisme pembentukan gel tergantung pada netralisasi gugus asam
karboksilat ke bentuk garamnya sehingga menghasilkan gel yang jernih dengan
viskositas optimum pada pH 7 (Conteras and Sanchez, 2001). Carbomer dapat
meningkatkan viskositas. Viskositasnya lebih tinggi pada pH 6-11, sedangkan
pada pH kurang dari 3 atau lebih dari 12 maka viskositasnya akan berkurang.
Penambahan basa akan memutuskan lebih banyak gugus karboksil sehingga gaya
tolak menolak elektrostatis lebih besar, sehingga membuat polimer mengembang
dan lebih rigid (Rowe, Sheskey, and Quinn, 2009). Bila carbomer memiliki viskositas yang baik, maka pelepasan zat aktif yang diberikan baik pula (Patil,
2005).
Carbopol 940 dapat digunakan sebagai gelling agent dalam memformulasikan obat yang bersifat hidrofobik seperti minyak atsiri ke dalam
sediaan emulgel. Minyak atsiri akan lebih mudah digunakan bila diformulasikan
ke dalam suatu sediaan seperti emulgel yang terdiri dari kombinasi dua sistem,
yaitu sistem emulsi dan sistem gel. Pada sistem emulsi, minyak atsiri yang
bersifat hidrofobik dapat bercampur dengan fase minyak dan fase air karena
terdapat emulsifying agent (menurunkan tegangan permukaan). Setelah sistem emulsi terbentuk, gelling agent ditambahkan untuk membentuk emulsi menjadi emulgel dengan membentuk sistem gel dan meningkatkan konsistensi sediaan
G. Uji Sifat Fisik Sediaan Topikal
Uji sifat sediaan yang meliputi pH, viskositas, daya sebar, dan ukuran
droplet bertujuan untuk mengetahui pH sediaan, penyebaran pada kulit,
pengeluaran sediaan dari wadah atau kemasan, pelepasan obat dari basisnya, dan
kestabilan sediaan (Martin, Swarbrick, dan Cammarata, 1993).
1. pH
Pada pembuatan sediaan topikal diharapkan sediaan memiliki pH yang
sama atau sedekat mungkin dengan pH kulit normal agar terhindar dari resiko
iritasi kulit. Kulit normal relatif memiliki pH yang berkisar antara 4-6,5
(Baranoski andAyello, 2008).
2. Viskositas
Pada pembuatan sediaan semisolid, reologi berpengaruh pada
penerimaan pasien, stabilitas fisika dan ketersediaan hayati, salah satunya
adalah viskositas. Viskositas adalah suatu pertahanan dari suatu cairan untuk
mengalir pada suatu tekanan yang diberikan, semakin tinggi viskositas maka
semakin besar tahanannya sehingga semakin besar pula gaya yang diperlukan
untuk membuat cairan tersebut dapat mengalir (Sinko, 2006). Viskositas (η) digambarkan dengan persamaan matematika :
𝜂 =!! =!!!!"#!!"# !"#$!!
!"#$ (1)
Dari persamaan itu dapat diketahui bahwa peningkatan gaya geser (shear stress) sebanding dengan kecepatan geser (shear rate). Namun hal ini hanya berlaku untuk senyawa dengan tipe Newtonian seperti air, alkohol, gliserin,
dan larutan polimer umumnya termasuk tipe Newtonian. Pada tipe
non-Newtonian, viskositas tidak berbanding lurus dengan kecepatan geser. Tipe
non-Newtonian meliputi plastis, pseudoplastis, dan dilatan (Liebermann,
Rieger, and Banker, 1996).
Pengujian viskositas dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai
jenis viskometer berdasarkan kebutuhan formulator (Garg, Aggarwal, Garg,
and Singla, 2002). 3. Daya sebar
Daya sebar adalah kemampuan dari suatu sediaan untuk menyebar di
tempat aplikasi, dan merupakan salah satu karakteristik penting yang
bertanggung jawab dalam keefektifan atau transfer dosis yang tepat ke tempat
target, kemudahan aplikasi pada substrat, pengeluaran dari kemasan, dan
penerimaan konsumen dalam menggunakan sediaan semi solid. Faktor-faktor
yang mempengaruhi daya sebar, yaitu viskositas sediaan, lama tekanan,
temperatur tempat aksi (Garg, Aggarwal, Garg, and Singla, 2002).
Metode yang paling sering digunakan dalam pengukuran daya sebar
adalah metode parallel-plate. Keuntungan metode ini yaitu sederhana, mudah untuk dilakukan, dan tidak memerlukan banyak biaya. Namun, metode ini
kurang tepat dan sensitif karena data yang dikumpulkan harus dihitung lagi
secara manual (Garg, Aggarwal, Garg, and Singla, 2002). 4. Uji ukuran droplet
Ukuran droplet merupakan parameter untuk mengukur kestabilan suatu
sediaan pada object glass kemudian diamati ukuran droplet menggunakan mikroskop. Diameter terjauh dari tiap droplet dicatat sejumlah 500 droplet,
kemudian dihitung rata-ratanya (Mantyas, 2013).
H. Uji Antibakteri
Uji antibakteri memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui kemampuan
suatu agen dalam menghambat maupun membunuh bakteri tertentu. Ada beberapa
metode dalam melakukan pengujian daya antibakteri, yaitu :
1. Metode Dilusi
Metode dilusi dapat digunakan untuk menentukan Kadar Hambat
Minimal (KHM), yaitu konsentrasi terendah yang dapat menghambat
pertumbuhan bakteri dan menentukan Kadar Bunuh Minimal (KBM), yaitu
konsentrasi terendah yang dapat membunuh bakteri (Pratiwi, 2008).
2. Metode Difusi
Metode difusi mengukur aktivitas antibakteri berdasarkan pengamatan
diameter zona jernih yang dihasilkan pada media karena adanya agen
antibakteri yang berdifusi dari tempat awal pemberian. Metode ini dilakukan
dengan menempatkan agen antibakteri pada media padat yang telah
diinokulasikan biakan bakteri (Jawetz, Melnick, and Adelberg, 1996). Ada beberapa cara dalam melakukan metode difusi ini, yaitu :
a. Cara sumuran.
Cara ini dilakukan dengan menginokulasikan bakteri ke media kemudian
lurus dengan permukaan media, selanjutnya ke dalam sumuran ini
dimasukkan agen antibakteri. Daya antibakteri yang diukur adalah
diameter zona jernih yang dihasilkan di sekitar sumuran (Pratiwi, 2008).
b. Cara paper disc.
Cara ini dilakukan dengan menginokulasikan bakteri ke media kemudian
setelah memadat, paper disc diletakkan di atas media yang telah memadat, dan ditetesi dengan agen antibakteri, sehingga agen antibakteri
meresap ke dalam paper disc. Daya antibakteri yang diukur adalah diameter zona jernih yang dihasilkan di sekitar disc (Pratiwi, 2008).
I. Landasan Teori
Bau kaki merupakan salah satu masalah yang mengganggu kehidupan
sehari-hari seseorang. Bau kaki ini timbul ketika kaki mulai berkeringat.
Penyebab terjadinya bau kaki ini adalah bakteri Staphylococcus epidermidis, yang merupakan salah satu flora normal pada kulit manusia. Bakteri ini akan
mendegradasi leusin dalamkeringat yang diproduksi menjadi isovaleric acid yang diketahuimenjadi penyebab bau kaki.
Menurut berbagai penelitian, rimpang temu putih dapat digunakan
sebagai antibakteri, antijamur, antineoplastik, antibakteri, dan antitrombotik.
Rimpang temu putih mengandung 1-2,5% minyak menguap dengan komposisi
utama sesquiterpene. Minyak menguap tersebut mengandung lebih dari 20 komponen seperti curzerenone (zedoarin) yang merupakan komponen terbesar,
-eusdesmol, curcumin, furanodiene, furanodienone, zederone, curzeone,
13-hydroxygermacrone, dihydrocurdione, curcumenone, zedoaronediol, curcumenol,
zedoarol, curcumanolide-A, curcumanolide-B, ethyl para-methoxycinnamate,
b-turmerone, zingiberene, dihydrocurcumin, curdione, neocurdione.
Minyak atsiri rimpang temu putih memiliki daya antibakteri terhadap
beberapa jenis bakteri patogen, salah satunya adalah Staphylococcus epidermidis
yang merupakan salah satu flora alami pada kulit manusia yang dapat
menimbulkan bau kaki. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Maiyani Hartono,
Nurlaila, Irmanida Batubara (2011), menunjukkan bahwa pada konsentrasi 500
ppm, minyak atsiri rimpang temu putih sudah bisa menghambat pertumbuhan dari
bakteri Staphylococcus epidermidis. Berdasarkan efektivitas minyak atsiri temu putih dalam menghambat pertumbuhan bakteri penyebab terjadinya bau kaki,
maka minyak atsiri temu putih dapat diformulasikan ke dalam bentuk sediaan
topikal sebagai penghilang bau kaki.
Emulgel merupakan formula modifikasi gabungan dari emulsi dan gel.
Emulgel ini akan membantu mengatasi masalah yang dimiliki oleh gel, yaitu
keterbatasan sebagai penghantar obat-obat yang bersifat hidrofobik. Selain itu,
kelebihan emulgel yaitu terdiri dari emulsi yang mempunyai kemampuan
penetrasi yang tinggi dan terdapat dalam sistem gel yang memiliki kandungan air
tinggi, sehingga memberikan sensasi dingin di kulit dan membuat kulit terasa
meningkatkan viskositas. Carbopol 940 sebagai gelling agent memiliki range kadar 0,5-2,0%. Viskositas dari carbopol 940 sangat tergantung pada pH. Bila pH
carbopol tidak dinetralkan, viskositasnya akan turun karena ikatan hidrogen pada
strukturnya mudah putus. Penambahan basa akan memutuskan lebih banyak
gugus karboksil sehingga gaya tolak-menolak elektrostatik lebih besar,
memperbesar volume, membuat gel mengembang dan lebih rigid. Carbopol 940
dapat mempengaruhi sifat fisik, meliputi viskositas, daya sebar dan stabilitas dari
sediaan emulgel yang dihasilkan. Penambahan gelling agent akan meningkatkan stabilitas dari sistem emulsi yang terbentuk karena meningkatnya viskositas dari
sediaan. Bila carbopol 940 memiliki viskositas yang optimum, maka pelepasan
zat aktif yang diberikan baik pula. Bila carbopol 940 memiliki viskositas yang
terlalu tinggi (terlalu kental/rigid), maka pelepasan zat aktif akan semakin
menurun karena zat aktif akan semakin sulit untuk keluar berdifusi.
Salah satu metode yang digunakan dalam menguji aktivitas antibakteri,
yaitu metode difusi. Metode difusi dilakukan berdasarkan pengamatan diameter
zona jernih atau zona hambat yang dihasilkan pada media yang telah
diinokulasikan bakteri karena adanya agen antibakteri yang berdifusi dari tempat
awal pemberian. Metode difusi yang digunakan adalah sumuran. Difusi sumuran
dilakukan dengan menginokulasikan bakteri ke media. Kemudian setelah
memadat, dibuat sumuran dengan diameter tertentu dan tegak lurus dengan
permukaan media. Selanjutnya ke dalam sumuran ini dimasukkan agen antibakteri.
Daya antibakteri yang diukur adalah diameter zona jernih yang dihasilkan di
J. Hipotesis
1. Sediaan emulgel minyak atsiri rimpang temu putih memiliki sifat fisik yang
memenuhi kriteria.
2. Sediaan emulgel minyak atsiri rimpang temu putih memiliki aktivitas
antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis.
3. Sediaan emulgel minyak atsiri rimpang temu putih dengan variasi komposisi
24
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian eksperimental
murni dan rancangan acak lengkap pola searah.
B. Variabel Penelitian 1. Variabel Utama
a. Variabel bebas.
Konsentrasi gelling agent (carbopol 940) yang akan digunakan. b. Variabel tergantung.
Sifat fisik emulgel yang meliputi organoleptis, viskositas, daya sebar, dan
pH. Stabilitas emulgel meliputi pergeseran viskositas setelah
penyimpanan selama 48 jam, 7 hari, 14 hari, 21 hari dan 28 hari, serta
diameter zona hambat terhadap Staphylococcus epidermidis.
2. Variabel Pengacau
a. Variabel Pengacau Terkendali.
Kecepatan, lama, dan suhu pengadukan dalam pembuatan sediaan
emulgel minyak atsiri rimpang temu putih, wadah penyimpanan, lama
penyimpanan, kondisi penyimpanan, suhu inkubasi, lama inkubasi,
b. Variabel Pengacau Tak Terkendali.
Suhu ruangan dan kelembaban ruangan saat pembuatan dan pengujian
emulgel minyak atsiri rimpang temu putih, serta kemungkinan
penguapan minyak atsiri rimpang temu putih.
C. Definisi Operasional
1. Minyak atsiri temu putih adalah minyak atsiri yang berasal dari rimpang tanaman temu putih yang diperoleh dari Eteris Nusantara dengan ciri
organoleptis berbentuk cairan kental, berbau khas aromatis, dan berwarna
kuning keemasan.
2. Emulgel minyak atsiri temu putih adalah sediaan topikal semisolid dengan bahan aktif minyak atsiri temu putih yang digunakan untuk menghilangkan
bau kaki yang dibuat sesuai dengan formula yang tercantum pada penelitian
ini.
3. Gelling agentadalah suatu zat yang dapat membentuk suatu massa gel, yang
berfungsi untuk mengentalkan dan menstabilkan emulgel minyak atsiri temu
putih. Pada penelitian ini menggunakan carbopol 940.
4. Pelarut adalah campuran dari gliserin, tween 80, span 80, dan air yang digunakan untuk melarutkan minyak atsiri temu putih pada uji antibakteri
minyak atsiri temu putih terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis.
5. Sifat fisik sediaan topikal antibakteri temu putih adalah parameter yang digunakan untuk mengetahui kualitas fisik sediaan topikal antibakteri emulgel
viskositas 48 jam setelah pembuatan serta stabilitas viskositas 48 jam dan
setiap minggu selama 1 bulan penyimpanan.
6. Viskositas adalah suatu pertahanan dari emulgel minyak atsiri temu putih untuk mengalir setelah adanya pemberian gaya. Semakin besar viskositas,
maka emulgel minyak atsiri temu putih akan makin tidak mudah untuk
mengalir.
7. Daya sebar adalah diameter penyebaran tiap 1 gram emulgel minyak atsiri temu putih pada alat uji daya sebar yang diberi beban total 125 gram dan
didiamkan selama 1 menit.
8. Pergeseran viskositas adalah stabilitas dari emulgel minyak atsiri temu putih dilihat viskositas setelah 48 jam, 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari
penyimpanan yang dianalisis dengan statistik.
9. Daya antibakteri emulgel minyak atsiri temu putih adalah kemampuan sediaan topikal antibakteri emulgel minyak atsiri temu putih untuk
menghambat atau membunuh Staphylococcus epidermidis penyebab bau kaki, yang ditunjukan melalui diameter zona hambat yang dihasilkan.
10.Zona hambat adalah zona jernih di mana tidak dijumpai pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis atau terdapat pertumbuhan sedikit sekali dibandingkan dengan kontrol pertumbuhan.
D. Bahan Penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah minyak atsiri rimpang
temu putih, carbopol 940 (kualitas farmasetis), gliserin (kualitas farmasetis),
Tween 80 dan Span 80 (kualitas farmasetis), parafin cair (kualitas farmasetis),
TEA (kualitas farmasetis), metil paraben (kualitas farmasetis), propil paraben
(kualitas farmasetis), aquadest steril, etanol 70%, bakteri uji Staphylococcus epidermidis, media Muller-Hinton Agar (Merck), Muller-Hinton Broth (Merck).
E. Alat Penelitian
Glasswares merek pyrex Japan, neraca analitik, waterbath, mixer, pipet
ukur, cawan petri, tabung reaksi, termometer, indikator pH universal, vortex,
viscotester seri VT 04 (RION-JAPAN), stopwatch, alat pengukur daya sebar,
refractometer ABBE, piknometer, pipet mikro 5-100 µL, jarum ose, alat pembuat sumuran, autoclave, inkubator, jangka sorong.
F. Tata Cara Penelitian 1. Verifikasi Minyak Atsiri Rimpang Temu Putih
Verifikasi sifat fisik minyak atsiri rimpang temu putih yang dilakukan
pada penelitian ini, meliputi:
a. Pengamatan organoleptis.
Pengamatan organoleptis meliputi pengamatan bentuk, warna, dan bau
b. Verifikasi indeks bias minyak atsiri rimpang temu putih.
Indeks bias minyak atsiri rimpang temu putih diukur dengan
menggunakan hand refractometer. Minyak atsiri rimpang temu putih diteteskan pada prisma utama, kemudian prisma ditutup dan ujung
refraktometer diarahkan ke arah cahaya terang, sehingga melalui lensa
skala dapat dilihat dengan jelas dan ditentukan nilai indeks biasnya.
Refraktometer dialiri air mengalir dan diatur suhunya menjadi 20°C.
Nilai indeks bias minyak atsiri rimpang temu putih ditunjukkan oleh
garis batas yang memisahkan sisi terang dan sisi gelap pada bagian atas
dan bawah. Dilakukan replikasi sebanyak 3 kali (Kusuma, 2010).
Perhitungan :
c. Verifikasi bobot jenis minyak atsiri temu putih.
Bobot jenis minyak atsiri rimpang temu putih diukur dengan
menggunakan piknometer yang telah dikalibrasi, dengan menetapkan
bobot piknometer kosong dan bobot air, pada suhu 25°C. Piknometer
diisi dengan minyak atsiri rimpang temu putih, dan kondisikan suhu
hingga 25°C, kemudian piknometer ditimbang. Bobot piknometer yang
piknometer kosong. Bobot jenis minyak atsiri rimpang temu putih
merupakan perbandingan antara bobot minyak atsiri rimpang temu putih
dengan bobot air dalam piknometer pada suhu 25°C. Dilakukan replikasi
sebanyak 3 kali.
Perhitungan :
Bobot jenis minyak atsiri temu putih = !"!"# !"#$%& !"#$%$ !"#$ !"#$!
!"!"# !"# !"#" !"!! !"°!
(Kusuma, 2010).
2. Uji Antibakteri Minyak Atsiri Temu Putih terhadap Bakteri Staphylococcus epidermidis
a. Penentuan konsentrasi minyak atsiri temu putih.
Minyak atsiri temu putih dibuat dalam beberapa seri konsentrasi, yaitu 5,
7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, dan 20% v/v dengan pelarut (campuran gliserin,
tween 80, span 80, dan air).
b. Pembuatan stok bakteri Staphylococcus epidermidis.
Media Muller-Hinton Agar (MHA) suhu 45-50°C dimasukkan ke dalam
tabung reaksi sejumlah 7 ml, kemudian disterilkan dengan menggunakan
autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Pada suhu 45-50°C, tabung
reaksi dimiringkan dan dibiarkan memadat. Diambil 1 ose biakan murni
Staphylococcus epidermidis dan diinokulasikan secara goresan, inkubasi
c. Pembuatan suspensi bakteri.
Suspensi bakteri dibuat dengan mengambil 1 ose koloni bakteri
Staphylococcus epidermidis dari stok bakteri, dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi media Muller-Hinton Broth (MHB) steril,
inkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C dalam inkubator, selanjutnya
kekeruhan suspensi bakteri Staphylococcus epidermidis disesuaikan dengan standar Mac Farland 0,5 (1,5 x 108 CFU/mL).
d. Pembuatan kontrol media.
Media MHA steril dituang ke dalam cawan petri, biarkan memadat,
kemudian diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37°C. Setelah
diinkubasi, diamati dan dibandingkan dengan perlakuan.
e. Pembuatan kontrol pertumbuhan bakteri uji Staphylococcus epidermidis.
Media MHA steril dengan suhu 45-55°C, diinokulasikan suspensi bakteri
uji dengan kepadatan dan jumlah yang sama dengan suspensi bakteri uji
pada perlakuan, kemudian tuang ke cawan petri steril dan digoyang
sehingga pertumbuhan bakteri dapat merata. Cawan petri tersebut
kemudian diinkubasi 24 jam, dengan suhu 37°C. Setelah diinkubasi,
diamati pertumbuhan bakteri uji melalui kekeruhan media dibandingkan
dengan perlakuan.
f. Pembuatan kontrol positif.
labu ukur 10 mL dan diperlukan sebanyak 20 mg serbuk clindamycin,
sehingga dihitung penimbangan clindamycin 0,2% :
!" !"
!"# !"× rata-rata isi 20 kapsul clindamycin
g. Uji daya antibakteri minyak atsiri temu putih terhadap Staphylococcus epidermidis dengan metode difusi sumuran.
Cawan petri steril diisi hingga 1/3 tinggi cawan petri dengan media MHA
steril dan biarkan memadat, layer ini merupakan layer pertama. Layer
kedua dituang di atas lapisan pertama, hingga 3/4 tinggi cawan petri
dengan media MHA yang telah diinokulasikan dengan suspensi bakteri.
Selanjutnya, dibuat 9 lubang sumuran dengan diameter 8 mm pada
cawan petri yang telah berisi media MHA double layer yang telah padat. Ketujuh sumuran masing-masing diisi dengan 50 µl minyak atsiri
rimpang temu putih dengan konsentrasi yang berbeda (5, 7,5, 10, 12,5,
15, 17,5, 20%). Satu sumuran diisi oleh pelarut sebagai kontrol negatif
dan satu sumuran diisi oleh clindamycin 0,2% sebagai kontrol positif. Cawan petri dilapisi dengan menggunakan plastic wrap, kemudian
diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C, dan diamati serta diukur
diameter zona hambat yang dihasilkan. Konsentrasi dengan daya
antibakteri yang maksimal dipakai untuk pengujian daya antibakteri
sediaan topikal antibakteri temu putih. Penelitian ini dilakukan 3 kali
replikasi sesuai dengan replikasi dari sediaan topikal antibakteri temu
3. Formula Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih
Formula yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada formula basis
emulgel (Wijayanti, 2013) dalam 200 g adalah sebagai berikut.
Tabel I. Formula basis emulgel (200 g)
Bahan Satuan (g)
Dari formula tersebut, dilakukan modifikasi sebagai berikut :
Tabel II. Formula emulgel minyak atsiri temu putih dengan perbandingan komposisi carbopol 940 (100 g)
Bahan FI (g) FII (g) FIII (g) Minyak atsiri temu putih 13,77 13,77 13,77
Parafin cair 17,25 17,25 17,25
Keterangan : FI = Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih (carbopol 940 0,5 %)
FII = Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih (carbopol 940 0,75 %)
4. Pembuatan Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih
Carbopol 940 dikembangkan dengan menggunakan 35 mL aquadest dari formula selama 24 jam, kemudian semua bahan yang termasuk dalam fase
minyak (parafin cair, propil paraben dan Span 80) dicampur terlebih dahulu
pada suhu 50°C di atas waterbath demikian halnya dengan fase air (gliserin,
aquadest, metilparaben dan Tween 80). Campuran fase minyak dicampurkan dengan fase air menggunakan mixer dengan kecepatan 300 rpm selama 1 menit pada suhu 50°C. Setelah sistem emulsi dingin (suhu ruangan), minyak
atsiri temu putih dimasukkan, dicampur menggunakan mixer dengan
kecepatan 300 rpm selama 1,5 menit.
Emulsi selanjutnya dicampurkan dengan carbopol 940 yang sebelumnya
telah dikembangkan dengan 35 mL aquadest dari formula menggunakan
mixerdengan kecepatan putar 300 rpm selama 2,5 menit pada suhu ruangan.
Kemudian trietanolamin (TEA) ditambahkan ke dalam campuran, dan
campuran diaduk kembali menggunakan mixer dengan kecepatan 300 rpm
selama 1,25 menit.
5. Pembuatan Kontrol Positif Emulgel Clindamycin 0,2%
Carbopol 940 dikembangkan dengan menggunakan 35 mL aquadest dari formula selama 24 jam, kemudian semua bahan yang termasuk dalam fase
minyak (parafin cair, propil paraben dan Span 80) dicampur terlebih dahulu
pada suhu 50°C di atas waterbath demikian halnya dengan fase air (gliserin,
dengan fase air menggunakan mixer dengan kecepatan 300 rpm selama 1 menit pada suhu 50°C. Setelah sistem emulsi dingin (suhu ruangan),
clindamycin dimasukkan, dicampur menggunakan mixer dengan kecepatan 300 rpm selama 1,5 menit.
Emulsi selanjutnya dicampurkan dengan carbopol 940 yang sebelumnya
telah dikembangkan dengan 35 mL aquadest dari formula menggunakan
mixerdengan kecepatan putar 300 rpm selama 2,5 menit pada suhu ruangan.
Kemudian trietanolamin (TEA) ditambahkan ke dalam campuran, dan
campuran diaduk kembali menggunakan mixer dengan kecepatan 300 rpm
selama 1,25 menit.
6. Uji pH Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih
Pengukuran pH ini menggunakan indikator universal, yaitu dengan
memasukkan indikator pH universal (pH strips) ke dalam emulgel minyak
atsiri temu putih yang telah dibuat. Kemudian menentukan pHnya dengan
membandingkan warna yang dihasilkan dengan standar (Wijayanti, 2013).
7. Uji Sifat Fisik Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih
Sifat fisik sediaan emulgel minyak atsiri temu putih yang diuji pada
penelitian ini meliputi :
a. Organoleptis.
Pemeriksaan orhanoleptis meliputi bentuk, warna dan bau yang diamati
b. Uji Viskositas.
Pengukuran viskositas menggunakan alat Viscometer Rion seri VT 04.
Emulgel dimasukkan ke dalam wadah hingga penuh dan dipasang pada
portable viscotester. Viskositas emulgel diketahui dengan mengamati
gerakan jarum penunjuk viskositas (Instruction Manual Viscotester
VT-04E) (Tiran, 2014). Uji ini dilakukan 48 jam setelah pembuatan untuk
mengetahui efek faktor terhadap viskositas, sedangkan untuk mengetahui
stabilitas emulgel dilakukan setelah 48 jam, 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan
28 hari penyimpanan. Dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Viskositas
yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah antara 200-350 d.Pa.s.
c. Uji Daya Sebar.
Sediaan emulgel ditimbang seberat 1 gram dan diletakkan di tengah kaca
bulat berskala. Di atas emulgel diletakkan kaca bulat lain dan beban
dengan berat total 125 gram, didiamkan selama 1 menit, kemudian
dicatat penyebarannya (Garg, Aggarwal, Garg, and Singla, 2002). Pengujian daya sebar dilakukan 48 jam setelah emulgel selesai dibuat.
Dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Daya sebar yang dikehendaki di
dalam penelitian ini yaitu 3-5 cm.
8. Uji Daya Antibakteri Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih terhadap Bakteri Staphylococcus epidermidis dengan Metode Difusi Sumuran
Pada uji ini dibuat kontrol media dan kontrol pertumbuhan di
kontrol media, yaitu media yang tidak diberi bakteri Staphylococcus
epidermidis, kemudian satu petri lainnya dibuat kontrol pertumbuhan, yaitu
media yang diberi 1 mL bakteri Staphylococcus epidermidis ke dalam MHA
hangat (suam-suam kuku) setelah sterilisasi, kemudian diinkubasikan terbalik
selama 24 jam pada suhu 37°C dalam inkubator.
Selanjutnya pada pengujian ini dibuat tiga petri besar yang diisi hingga
1/3 tinggi cawan petri dengan media MHA steril (36 mL) dan dibiarkan
memadat, layer ini merupakan layer pertama. Layer kedua dituang di atas lapisan pertama, hingga 3/4 tinggi cawan petri (61 mL) dengan media MHA
yang telah diinokulasikan dengan suspensi bakteri dengan perlakuan sama
seperti kontrol pertumbuhan diberi masing-masing 2,5 mL suspensi bakteri
Staphylococcus epidermidis dan diberi 9 lubang sumuran sampai pada layer
atas dengan diameter 8 mm pada cawan petri yang telah berisi MHA steril
double layer yang telah memadat. Dalam masing-masing cawan petri, ke dalam sumuran diberi ketiga formula basis emulgel, ketiga formula emulgel
minyak atsiri temu putih 15%, dan ketiga formula kontrol positif emulgel
antibakteri (clindamycin 0,2%). Kemudian dilakukan replikasi sebanyak tiga kali. Setelah itu cawan petri dilapisi dengan menggunakan plastic wrap, diinkunbasikan terbalik selama 24 jam pada suhu 37°C dalam inkubator.
G. ANALISIS HASIL
Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data sifat fisik sediaan
topikal antibakteri emulgel minyak atsiri temu putih yang meliputi organoleptis,
viskositas, daya sebar, pH, serta data daya antibakteri sediaan topikal antibakteri
emulgel minyak atsiri temu putih, kontrol basis sediaan topikal emulgel, dan
kontrol positif sediaan topikal emulgel antibakteri. Hasil pengujian aktivitas
sediaan emulgel antibakteri minyak atsiri temu putih dan uji sifat fisik sediaan
dianalisis secara statistik dengan uji Shapiro-Wilk untuk melihat distribusi data. Jika distribusi data normal, dilanjutkan dengan Levene’s Test untuk melihat kehomogenan data. Jika data sudah homogen dilanjutkan dengan menggunakan
38
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Identifikasi dan Verifikasi Minyak Atsiri Temu Putih
Penelitian ini menggunakan minyak atsiri temu putih yang berasal dari
Eteris Nusantara. Minyak atsiri temu putih merupakan minyak atsiri yang berasal
dari rimpang temu putih (Curcuma zedoaria [Berg.] Roscoe) yang telah diidentifikasi melalui beberapa uji yang dibuktikan dengan Certificate of Analysis
(CoA), yaitu uji organoleptis, uji kelarutan, uji bobot jenis, uji rotasi optik, dan uji
indeks bias (Lampiran 1). Minyak atsiri temu putih digunakan sebagai bahan
penelitian karena minyak ini diketahui memiliki daya antibakteri terhadap bakteri
Staphylococcus epidermidis dengan KHM sebesar 500 ppm (Hartono, Nurlaila, dan Batubara, 2011).
Gambar 4. Minyak Atsiri Temu Putih
Tahap awal yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu dengan uji
indeks bias, dan bobot jenis. Uji organoleptis minyak atsiri temu putih meliputi
bau, warna, dan rasa. Peneliti melakukan verifikasi ulang terhadap minyak atsiri
temu putih dengan tujuan untuk lebih memastikan apakah minyak atsiri yang akan
digunakan dalam penelitian ini adalah benar minyak atsiri temu putih yang sesuai
dengan literatur yang digunakan. Hasil yang semakin mendekati literatur
menunjukkan keaslian minyak atsiri yang semakin tinggi pula.
Verifikasi ulang minyak atsiri temu putih yang dilakukan menunjukkan
hasil sebagai berikut :
Tabel III. Hasil verifikasi minyak atsiri temu putih (𝝌 ± SD)
Sifat Fisik Indeks bias 1,4640-1,4860 1,39-1,482 1,4801 ± 0,00058 Bobot jenis 0,890-0,970 0,899-0,9313 g/mL 0,9308 ± 0,00058
Dari tabel III dapat diketahui bahwa hasil verifikasi organoleptis, indeks
bias, dan bobot jenis minyak atsiri temu putih sesuai dengan literatur dan
Certificate of Analysis (CoA) (Lampiran 1). Berdasarkan hasil verifikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa minyak atsiri temu putih yang diperoleh dari Eteris
B. Uji Daya Antibakteri Minyak Atsiri Temu Putih terhadap Bakteri Staphylococcus epidermidis
Dalam penelitian Kobayashi (1990), ditemukan bahwa Staphylococcus epidermidis, yang merupakan flora normal kulit, memainkan peran utama dalam menimbulkan bau kaki. Di dalam keringat terdapat kandungan asam amino,
seperti leusin, valin, dan isoleusin. Bakteri ini akan mendegradasi leusin dalam
keringat dengan bantuan enzim leusin dehidrogenase menghasilkan isovaleric acid yang diketahui menjadi penyebab bau kaki. Isovaleric acid merupakan suatu senyawa asam lemak rantai pendek (Ara, et al., 2006).
Bahan aktif yang digunakan pada formulasi sediaan topikal emulgel
antibakteri pada penelitian ini adalah minyak atsiri temu putih yang berasal dari
rimpang tanaman temu putih. Pada penelitian yang dilakukan oleh Maiyani
Hartono, Nurlaila, Irmanida Batubara (2011), menunjukkan bahwa pada
konsentrasi 500 ppm, minyak atsiri rimpang temu putih sudah bisa menghambat
pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis.
Uji ini merupakan uji pendahuluan yang dilakukan sebelum
memformulasikan minyak atsiri temu putih ke dalam sediaan emulgel untuk
memastikan bahwa minyak atsiri temu putih memiliki daya antibakteri terhadap
bakteri Staphylococcus epidermidis. Kualitas atau kadar dalam minyak atsiri temu putih yang digunakan dalam setiap penelitian pasti berbeda-beda. Hal ini dapat
dipengaruhi oleh faktor klimatik (iklim), faktor edafik (kondisi tanah), faktor
fisiografi, dan faktor biotik. Perbedaan kualitas (kadar) minyak atsiri temu putih