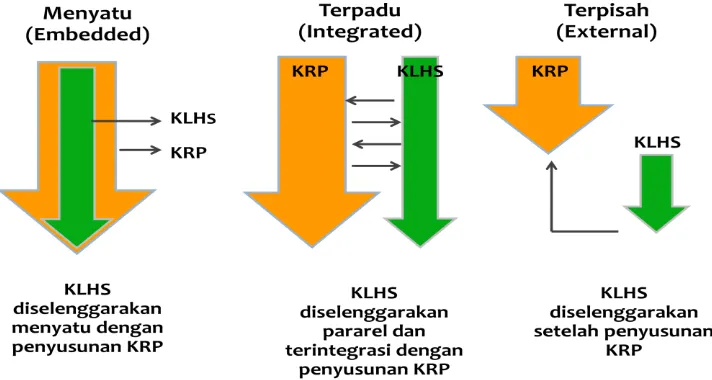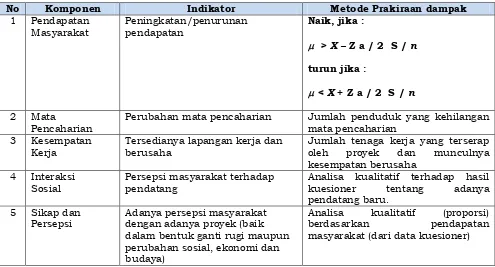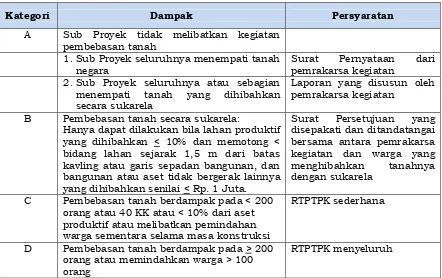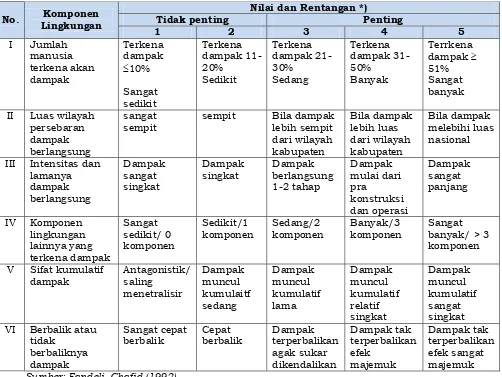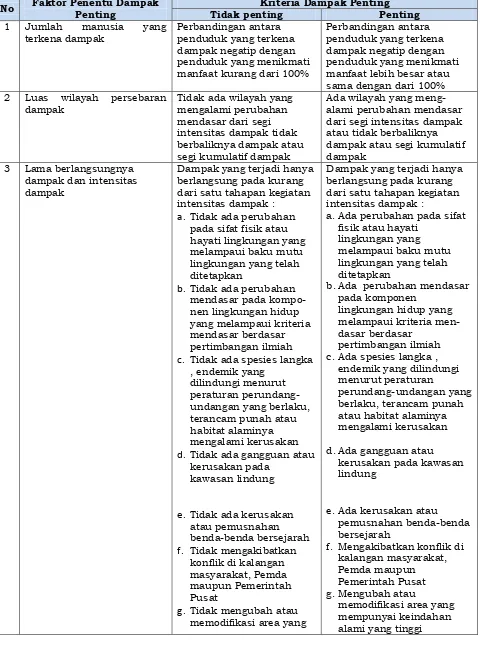8.1.
Analisis Perlindungan Lingkungan dan Sosial
8.1.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
A. Kaidah KLHS
Prinsip dalam penyusunan KLHS agar tercapai tujuan yang ingin dicapai
untuk mengukur dampak terhadap lingkungan yaitu:
• Keterkaitan (interdependency) • Keseimbangan (equilibrium)
• Keadilan (justice)
Keterkaitan (interdependency) menekankan pertimbangan keterkaitan antara
satu komponen dengan komponen lain, antara satu unsur dengan unsur lain, atau
antara satu variabel biofisik dengan variabel biologi, atau keterkaitan antara lokal
dan global, keterkaitan antar sektor, antar daerah, dan seterusnya.
Keseimbangan (equilibrium) menekankan aplikasi keseimbangan antar aspek,
kepentingan, maupun interaksi antara makhluk hidup dan ruang hidupnya, seperti
diantaranya adalah keseimbangan laju pembangunan dengan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup, keseimbangan pemanfaatan dengan perlindungan dan
pemulihan cadangan sumber daya alam, keseimbangan antara pemanfaatan ruang
dengan pengelolaan dampaknya,dan lain sebagainya.
Keadilan (justice) untuk menekankan agar dapat dihasilkan kebijakan,
rencana dan program yang tidak mengakibatkan pembatasan akses dan kontrol
terhadap sumber-sumber alam, modal dan infrastruktur, atau pengetahuan dan
informasi kepada sekelompok orang tertentu.
Atas dasar kaidah diatas, maka penerapan KLHS terhadap KRP bertujuan
untuk mendorong pembuat dan pengambil keputusan atas KRP menjawab
pertanyaan-pertanyaan berikut :
ASPEK
• Apa manfaat langsung atau tidak langsung dari usulan sebuah KRP?
• Bagaimana dan sejauh mana timbul interaksi antara manfaat KRP dengan
lingkungan hidup dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam?
• Apa lingkup interaksi tersebut? Apakah interaksi tersebut akan menimbulkan
kerugian atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup? Apakah interaksi
tersebut akan mengancam keberlanjutan dan kehidupan masyarakat?
• Dapatkah efek-efek yang bersifat negatif diatasi, dan efek-efek positifnya
dikembangkan?
• Apabila KRP mengintegrasikan seluruh upaya pengendalian atau mitigasi atas
efek-efek tersebut dalam muatannya, apakah masih timbul pengaruh negatif KRP
tersebut terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan secara umum?
B. Metode Penyusunan KLHS
Ruang lingkup yang menjadi kajian dalam penyusunan KLHS harus meliputi
hal hal sebagai berikut :
a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
KLHS adalah proses untuk mempengaruhi penentuan pilihan-pilihan
pembangunan yang diusulkan dalam KRP yang terutama dilakukan melalui kegiatan
konsultasi dan dialog secara tepat dan relevan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan
KLHS harus sesuai dengan kebutuhan tanpa terpaku dalam metoda dan prosedur
yang baku. Melalui penyusunan KLHS maka semua kebijakan, rencana dan program
yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten akan mendorong lahirnya
pemikiran untuk alternatif –alternatif baru pembangunan melalui tahapan atau proses
sebagai berikut :
a. Identifikasi isu-isu utama lingkungan atau pembangunan berkelanjutan yang
perlu dipertimbangkan dalam KRP;
isu-isu yang relevan dan memberikan masukan untuk optimalisasi;
c. Mengkaji paling tidak dampak kumulatif yang mendasar dari KRP dan memberi
masukan untuk optimalisasi.;
d. Memaparkan proses KLHS, kesimpulan dan usulan rekomendasi kepada para
pengambil keputusan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan KLHS
adalah sebagai berikut :
a. Melakukan seluruh persiapan dan mobilisasi sumberdaya yang diperlukan.
b. Melakukan pengumpulan data, peta dan informasi terkait
c. Melakukan pekerjaan yang terkoordinasi untuk menjaring masukkan mengenai
pengembangan infrastruktur di Kota Banjarbaru
d. Melakukan survey dan observasi untuk kelengkapan data.
e. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap hasil survey dan observasi.
f. Menyelenggarakan presentasi hasil evaluasi dan analisisnya.
Mekanisme penyusunan KLHS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
dilakukan dengan tahapan atau proses sebagai berikut :
1. Penapisan;
Penapisan adalah rangkaian langkah-langkah untuk menentukan apakah suatu
KRP perlu dilengkapi dengan KLHS atau tidak. Penentuan KRP telah memenuhi
kriteria pelaksanaan KLHS dilakukan melalui kesepakatan pihak-pihak yang
berkepentingan.
2. Pelingkupan;
Pelingkupan adalah rangkaian langkah-langkah untuk menetapkan nilai penting
KLHS, tujuan KLHS, isu pokok, ruang lingkup KLHS, kedalaman kajian dan
kerincian penulisan dokumen, pengenalan kondisi awal, dan telaah awal
kapasitas kelembagaan. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan sistematis
dan metodologis yang memenuhi kaidah ilmiah. Mengingat terbatasnya waktu
dan sumber daya yang tersedia, dalam kajian ini tidak dilakukan proses
konsultasi publik.
Pengkajian adalah rangkaian langkah-langkah untuk melakukan kajian ilmiah,
pemetaan kepentingan, dialog dan konsultasi serta penemuan pilihan-pilihan
alternatif rumusan maupun perbaikan dan penyempurnaan terhadap rumusan
yang sudah ada. Tim kajian melakukan serangkaian diskusi dan konsultasi
dengan para pihak (stakeholders) terkait, khususnya dengan instansi pemerintah
dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
4. Perumusan dan pengambilan keputusan
Perumusan dan pengambilan keputusan adalah rangkaian langkah-langkah
persetujuan rekomendasi hasil KLHS dan interaksi antar pihak berkepentingan
dalam rangka mempengaruhi hasil akhir KRP.
Keseluruhan hasil pengkajian ini secara lengkap dituangkan dengan jelas dan
sistematis sehingga dapat dijadikan pedoman pembangunan berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan.
Gambar 8.1. Mekanisme Penyelenggaraan KLHS
Pada tahap analisa atau pengkajian, harus dilakukan serangkaian kajian
dengan menerapkan daftar uji pada setiap langkah proses KRP, meliputi :
1. Uji Kesesuaian Tujuan dan Sasaran KRP.
Kepentingan pengujian adalah untuk memastikan bahwa :
a) tujuan dan sasaran umum KRP memang jelas,
b) berbagai isu keberlanjutan maupun lingkungan hidup tercermin dalam tujuan
c) sasaran terkait dengan keberlanjutan akan bisa dikaitkan langsung dengan
indikator-indikator pembangunan berkelanjutan,
d) keterkaitan KRP dengan KRP-KRP lain bisa dijelaskan dengan baik,
e) konflik kepentingan antara KRP dengan KRP-KRP lain segera bisa
teridentifikasi.
2. Uji Relevansi Informasi yang Digunakan.
Kepentingan utama pengujian ini adalah bukan menilai kelengkapan dan validitas
data, tetapi identifikasi kesenjangan antara data yang dibutuhkan dengan yang
tersedia serta cara mengatasinya. Hal ini terasa penting ketika KRP diharuskan
memperhatikan kesatuan fungsi ekosistem dan wilayah-wilayah rencana selain
wilayah administratifnya sendiri.
Selanjutnya pengujian juga lebih mengutamakan relevansi informasi dan
sumbernya agar proses kerja bisa efektif namun tetap memperhatikan
kendala-kendala setempat.
3. Uji Pelingkupan Isu-isu Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan dalam KRP.
Pengujian ini ditujukan untuk memandu penyusun KRP memperhatikan isu-isu
lingkungan hidup maupun keberlanjutan di tingkat lokal, regional, nasional,
maupun internasional, dan melihat relevansi langsung isu-isu tersebut terhadap
wilayah perencanaannya.
4. Uji Pemenuhan Sasaran dan Indikator Lingkungan Hidup dan Pembangunan
Berkelanjutan.
Pengujian ini efektif bila konsep rencana sudah mulai tersusun, sehingga dapat
dilakukan penilaian langsung atas arahan-arahan rencana terhadap
indikator-indikator teknis lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Uji ini
sebenarnya merupakan iterasi atau pengembangan dari uji yang dilakukan di
awal proses penyusunan KRP sebagaimana dijelaskan pada nomor 1.
5. Uji Penilaian Efek-efek yang Akan Ditimbulkan.
Pengujian ini membantu penyusun KRP untuk dapat memperkirakan dimensi
besaran dan waktu dari efek-efek positif maupun negatif yang akan ditimbulkan.
Bentuk pengujian ini dapat disesuaikan dengan kemajuan konsep maupun
ketersediaan data, sehingga pengujian dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif.
dengan verifikasi berupa proses konsultasi maupun diskusi dengan pihak-pihak
yang terkait.
6. Uji Penilaian Skenario dan Pilihan Alternatif.
Pengujian ini membantu penyusun KRP untuk memperoleh pilihan alternatif yang
beralasan, relevan, realistis dan bisa diterapkan. Keputusan pemilihan alternatif
bisa dilakukan dengan sistem pengguguran (memilih satu opsi dan menggugurkan
yang lainnya) atau mengkombinasikan beberapa pilihan dengan penyesuaian.
7. Uji Identifikasi Timbulan Efek atau Dampak dampak Turunan maupun Kumulatif.
Pengujian ini merupakan pengembangan dari jenis pengujian nomor 5, dimana
jenis-jenis KRP tertentu diperkirakan juga akan menimbulkan efek-efek atau
dampak-dampak lanjutan yang lahir dari dampak langsung yang ditimbulkan,
maupun akumulasi efek dalam jangka waktu panjang dan pada skala ruang yang
besar.
Kelompok-kelompok pengujian ini bisa dilakukan dengan cara :
• mengemasnya dalam berbagai model daftar pertanyaan, misalnya model
daftar uji untuk menilai mutu dokumen, model daftar uji untuk menilai
konsistensi muatan KRP terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan, model daftar
uji untuk menuntun pengambil keputusan mempertimbangkan kriteria-kriteria
dan opsi-opsi yang mendukung keberlanjutan, dan lain sebagainya
• melakukannya secara berurut sejalan dengan proses persiapan, pengumpulan
data, kompilasi data, analisis dan penyusunan rencana
• melakukannya secara berulang/iteratif
• mengembangkan atau memodifikasi jenis pertanyaan-pertanyaannya sesuai
Gambar 8.2. Kerangka Kerja dan Metodologi KLHS
Dalam pelaksanaannya, penyusunan KLHS dilakukan terhadap 3 kondisi KRP,
yaitu KRP yang sudah disusun atau dilaksanakan sebelumnya, KRP yang masih
dalam proses perencanaan atau penyusunan dan yang terakhir adalah KRP yang
sedang dalam proses penyusunan. Pendekatan pelaksanaan KLHS terhadap ketiga
kondisi KRP tersebut berbeda satu dengan lainnya, dengan skema pendekatan
sebagai berikut :
Gambar 8.4. Skema Alternatif Pelaksanaan Integrasi KLHS
8.1.2 Amdal, UKL UPL dan SPPLH
Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) rencana kegiatan
pembangunan merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah,
mengendalikan, dan menanggulangi dampak lingkungan hidup yang bersifat negatif
dan meningkatkan dampak positip yang timbul sebagai akibat dari rencana suatu
kegiatan tersebut. Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan merupakan upaya
peduli serta rasa tanggung-jawab pemrakarsa untuk mengupayakan pelestarian
lingkungan dan mengembangkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan.
Dampak-dampak yang muncul tersebut perlu dikelola oleh pemrakarsa
sehingga keseimbangan ekosistem lingkungan tetap terjaga dan kualitas daya
dukung lingkungan akan meningkat.
Upaya pengelolaan lingkungan hidup mencakup empat kelompok aktivitas yaitu :
1. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah
dampak negatif lingkungan hidup melalui pemilihan alternatif, tata letak lokasi
dan rancang bangun proyek.
2. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimasi
atau mengendalikan dampak dampak negatip baik yang timbul di saat usaha
atau kegiatan beroperasi maupun hingga saat usaha atau kegiatan tersebut
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat meningkatkan dampak positip
sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik
kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut
menikmati dampak positip tersebut.
4.
Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat memberikan pertimbanganekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas
sumber daya tidak dapat pulih, hilang atau rusak sebagai dasar untuk
memberikan kompensasi sebagai akibat usaha atau kegiatan.
8.1.3 Perlindungan Sosial
Komponen safeguard sosial dalam hal ini terkait pengadaan tanah dan
keresahan masyarakat karena rencana investasi tidak sesuai dengan harapan
masyarakat. Pengadaan tanah biasanya terjadi jika kegiatan investasi berlokasi di
atas tanah yang bukan milik pemerintah atau telah ditempati oleh
swasta/masyarakat selama lebih dari satu tahun. Prinsip utama pengadaan tanah
adalah bahwa semua langkah yang diambil harus dilakukan dengan kesepakatan
kedua belah pihak terutama terkait dengan ganti rugi atau ganti untung dan
bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan standar kehidupan warga yang
terkena dampak akibat kegiatan pengadaan tanah ini.
Pengadaan tanah dan permukiman kembali atau land acquisition and
resettlement untuk kegiatan RPIJM mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Transparan : Sub proyek dan kegiatan yang terkait harus diinformasikan
secara transparan kepada pihak-pihak yang akan terkena dampak. Informasi
harus mencakup, antara lain, daftar warga dan aset (tanah, bangunan, tanaman,
dan lainnya) yang akan terkena dampak.
b. Partisipatif : Warga yang berpotensi terkena dampak/dipindahkan (DP) harus
terlibat dalam seluruh perencanaan proyek, seperti: penentuan batas lokasi
proyek, jumlah dan bentuk kompensasi, serta lokasi tempat permukiman
kembali.
c. Adil : Pengadaan tanah tidak boleh memperburuk kondisi kehidupan
masyarakat. Masyarakat tersebut memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi
dengan harga pasar tanah dan asetnya. Biaya terkait lainnya, seperti biaya
pindah, pengurusan surat tanah, dan pajak, harus ditanggung oleh pemrakarsa
kegiatan. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengkaji rencana
pengadaan tanah ini secara terpisah di antara mereka sendiri dan menyetujui
syarat-syarat dan jumlah ganti rugi dan/atau permukiman kembali.
Untuk masalah ketidaksetujuan atau tidak sesuainya rencana investasi
dengan harapan masyarakat harus segera diselesaikan melalui sosialisasi mengenai
pentingnya proyek, keuntungan dan manfaat proyek bagi kesehatan lingkungan dan
kesehatan masyarakat setempat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui tercapainya kebutuhan sanitasi dasar bagi masyarakat.
Untuk aspek sosial ekonomi dan budaya prakiraan besarnya dampak
dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan metode formal dan dengan metode
informal. Metode formal digunakan untuk memprakirakan besarnya perubahan dari
variabel-variabel yang dapat terukur secara kuantitatif, diantaranya keresahan
masyarakat, konflik sosial, perubahan pendapatan, adanya kesempatan kerja,
perubahan mata pencaharian.
Sedangkan metode informal yang digunakan adalah teknik analogi. Metode ini
digunakan untuk memprakirakan besarnya dampak dari variabel-variabel yang
bersifat kualitatif misalnya, keresahan masyarakat. Berikut ini disajikan cara yang
Tabel 8.1. Metode Prakiraan Dampak Komponen Sosial
No Komponen Indikator Metode Prakiraan dampak
1 Pendapatan
Perubahan mata pencaharian Jumlah penduduk yang kehilangan mata pencaharian
3 Kesempatan Kerja
Tersedianya lapangan kerja dan berusaha
Analisa kualitatif terhadap hasil
kuesioner tentang adanya
pendatang baru. 5 Sikap dan
Persepsi
Adanya persepsi masyarakat dengan adanya proyek (baik dalam bentuk ganti rugi maupun perubahan sosial, ekonomi dan budaya)
Analisa kualitatif (proporsi)
berdasarkan pendapatan
masyarakat (dari data kuesioner)
Secara khusus prosedur pelaksanaan safeguard untuk kegiatan pembebasan
tanah dan perolehan permukiman kembali terdiri dari beberapa kegiatan utama yang
meliputi:
a. Penyiapan awal dari usulan kegiatan untuk melihat apakah kegiatan yang
bersangkutan memerlukan pembebasan tanah atau kegiatan permukiman
kembali atau tidak;
b. Pengklasifikasian/kategorisasi dampak pembebasan tanah dan
permukiman kembali dari sub proyek yang diusulka;
c. Perumusan surat pernyataan bersama (jika melibatkan hibah sebidang
tanah secara sukarela) atau perumusan Rencana Tindak Pembebasan
Tanah dan Permukiman Kembali (RTPTPK) sederhana atau menyeluruh
sesuai kebutuhan didukung SK Gubernur/Bupati/Walikota.
Pembebasan tanah dan perolehan permukiman kembali yang telah
dilaksanakan sebelum usulan sub proyek disampaikan, harus diperiksa kembali
dengan tracer study. Tracer study ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa proses
pembebasan tanah telah sesuai dengan standar yang berlaku, tidak mengakibatkan
kondisi kehidupan masyarakat yang terkena dampak menjadi lebih buruk, dan
Tabel 8.2. Kategori Pendugaan Dampak Pembebasan Tanah dan
Permukiman Kembali
Kategori Dampak Persyaratan
A Sub Proyek tidak melibatkan kegiatan pembebasan tanah
1.Sub Proyek seluruhnya menempati tanah negara
Surat Pernyataan dari pemrakarsa kegiatan
2.Sub Proyek seluruhnya atau sebagian menempati tanah yang dihibahkan secara sukarela
Laporan yang disusun oleh pemrakarsa kegiatan
B Pembebasan tanah secara sukarela:
Hanya dapat dilakukan bila lahan produktif yang dihibahkan < 10% dan memotong < bidang lahan sejarak 1,5 m dari batas kavling atau garis sepadan bangunan, dan bangunan atau aset tidak bergerak lainnya yang dihibahkan senilai < Rp. 1 Juta.
Surat Persetujuan yang disepakati dan ditandatangai bersama antara pemrakarsa kegiatan dan warga yang menghibahkan tanahnya dengan sukarela
C Pembebasan tanah berdampak pada < 200 orang atau 40 KK atau < 10% dari aset produktif atau melibatkan pemindahan warga sementara selama masa konstruksi
RTPTPK sederhana
D Pembebasan tanah berdampak pada > 200 orang atau memindahkan warga > 100 orang
RTPTPK menyeluruh
Sedangkan metode pendugaan dampak lingkungan dapat diuraikan sebagai
berikut, untuk memprakirakan pentingnya dampak maka diperlukan batasan kriteria
dampak penting sebagai berikut:
a. Jumlah manusia yang terkena dampak,
b. Luas persebaran dampak,
c. Intensitas dampak dan lamanya dampak berlangsung,
d. Komponen lingkungan yang terkena dampak,
e. Sifat kumulatif dampak,
f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.
Dampak penting suatu komponen lingkungan hidup ditentukan oleh :
a. Jumlah manusia yang terkena dampak.
Pengertian manusia yang akan terkena dampak mencakup aspek yang
luas, maka kriteria penting dikaitkan dengan sendi-sendi kehidupan yang di
usaha/kegiatan yang penentuannya didasarkan pada sendi-sendi kehidupan
pada masyarakat dan jumlah manusia yang terkena dampak menjadi penting
bilamana : “manusia di wilayah proyek yang terkena dampak lingkungan
tetapi tidak menikmati manfaat dari usaha/kegiatan, jumlahnya sama atau
lebih besar dari jumlah manusia yang menikmati manfaat dari usaha/kegiatan
di wilayah studi”.
b. Luas wilayah penyebaran dampak
Dampak lingkungan dari rencana usaha/kegiatan bersifat penting
bilamana ”rencana usaha/kegiatan mengakibatkan adanya wilayah yang
mengalami perubahan mendasar dari segi intensitas dampak, atau tidak
berbalik dampak atau segi kumulatif dampak
c. Lamanya dan intensitas dampak berlangsung
Dampak kegiatan dapat berlangsung lama atau dalam waktu singkat pada
setiap tahap pembangunan rencana kegiatan. Atas dasar pengertian ini maka
dampak lingkungan bersifat penting apabila rencana usaha/kegiatan
mengakibatkan timbulnya perubahan mendasar dari segi lamanya dan
intensitas dampak.
d. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak
Dikarenakan dampak terhadap komponen lingkungan akan berdampak
lanjut terhadap komponen lingkungan lainnya, sehingga atas pengertian ini
dampak tergolong penting bila : rencana usaha/kegiatan menimbulkan
dampak sekunder dan dampak lanjutan lainnya yang jumlah komponennya
lebih atau sama dengan komponen yang terkena dampak primer.
e. Sifat kumulatif dampak tersebut
Dampak suatu usaha/kegiatan tergolong berdampak penting bilamana :
Dampak lingkungan berlangsung berulang kali dan terus menerus
sehingga pada kurun waktu tertentu tidak dapat diasimilasi oleh
lingkungan alam atau sosial yang menerimanya.
Beragam dampak lingkungan bertumpuk dalam suatu ruang tertentu
sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam atau sosial yang
Dampak lingkungan dari berbagai sumber kegiatan menimbulkan efek
yang saling memperkuat (sinergis).
f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak
Dampak bersifat penting bilamana : perubahan yang akan dialami oleh
suatu komponen lingkungan tidak dapat dipulihkan kembali walaupun dengan
intervensi manusia”.
Tabel 8.3.Batasan Kriteria Penentuan Dampak Penting
No. Komponen Lingkungan
Nilai dan Rentangan *)
Tidak penting Penting
1 2 3 4 5
sempit Bila dampak
lebih sempit
III Intensitas dan lamanya
V Sifat kumulatif dampak
Tabel 8.4.
Batasan Kriteria Penentuan Dampak Penting(Kep. Ka.Bapedal No.056/1994)
No Faktor Penentu Dampak Penting
Kriteria Dampak Penting Tidak penting Penting 1 Jumlah manusia yang manfaat kurang dari 100%
Perbandingan antara penduduk yang terkena dampak negatip dengan penduduk yang menikmati manfaat lebih besar atau sama dengan dari 100% 2 Luas wilayah persebaran
dampak
Tidak ada wilayah yang mengalami perubahan dari segi intensitas dampak atau tidak berbaliknya dampak atau segi kumulatif dampak
3 Lama berlangsungnya dampak dan intensitas dampak
Dampak yang terjadi hanya berlangsung pada kurang dari satu tahapan kegiatan intensitas dampak :
a. Tidak ada perubahan pada sifat fisik atau hayati lingkungan yang melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan
b. Tidak ada perubahan mendasar pada kompo-nen lingkungan hidup yang melampaui kriteria mendasar berdasar pertimbangan ilmiah c. Tidak ada spesies langka
, endemik yang d. Tidak ada gangguan atau
kerusakan pada kawasan lindung
e. Tidak ada kerusakan atau pemusnahan
g. Tidak mengubah atau memodifikasi area yang
Dampak yang terjadi hanya berlangsung pada kurang dari satu tahapan kegiatan intensitas dampak :
a.Ada perubahan pada sifat fisik atau hayati
lingkungan yang melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan
b.Ada perubahan mendasar pada komponen
d.Ada gangguan atau kerusakan pada kawasan lindung
e.Ada kerusakan atau pemusnahan benda-benda bersejarah
No Faktor Penentu Dampak Penting
Kriteria Dampak Penting Tidak penting Penting mempunyai keindahan
alami yang tinggi 4 Komponen lain yang terkena
dampak
Tidak menimbulkan dam-pak sekunder dan damdam-pak lanjutan lainnya yang
lanjutan lainnya yang jumlah komponennya lebih atau sama dengan komponen lingkungan yang terkena dampak primer
5 Sifat kumulatif dampak Tidak kumulatif Bersifat kumulatif, tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan dan bersifat sinergetik
6 Berbalik atau tidak berbaliknya dampak
Dapat dipulihkan Tidak dapat dipulihkan
8.1.3.1 Perlindungan Sosial Pada Tahap Perencanaan Pembangunan
a. Survey Lapangan
Keresahan Masyarakat
Keresahan pada masyarakat berpotensi timbul karena adanya kekhawatiran
masyarakat akan kemungkinan dampak negatif akibat pembangunan proyek
seperti tergusurnya lahan masyarakat, kemacetan lalu lintas, debu, bising
dan lainnya.
Persepsi Positif
Persepsi positif dapat timbul di masyarakat karena adanya harapan
meningkatnya kualitas lingkungan dan berkurangnya daerah genangan saata
musim penghujan tiba karena saluran drainase menjadi bersih serta
meningkatnya kesehatan karena lingkungan menjadi lebih bersih karena
terbangunnya infrastruktur lingkungan.
b. Perencanaan Dan perijinan
Persepsi Positif
Persepsi positif dapat timbul di masyarakat karena adanya perencanaan
dilakukan secara seksama dan memperhatikan aspek lingkungan. Persepsi
positif juga dapat timbul karena proses perijinan dilakukan sesuai peraturan
perundangan yang berlaku.
Persepsi Negatif
Persepsi negatip dapat timbul karena adanya kekhawatiran masyarakat akan
kemungkinan dampak negatif akibat pembangunan sub proyek investasi
seperti terganggunya lingkungan dan persepsi kemungk inan adanya
pengenaan biaya dan kenaikan pungutan atau retribusi sampah bahkan air
limbah apabila infrastruktur tersebut telah beroperasi.
c. Penyampaian Informasi pada masyarakat
Persepsi Positif
Persepsi positif dapat timbul di masyarakat setelah mendapatkan
informasi yang memadai tentang rencana pembangunan sub proyek serta
jika didukung adanya kesepakatan bersama antara pemrakarsa dengan
warga
Keresahan Masyarakat
Keresahan masyarakat masih mungkin terjadi jika informasi yang
diberikan tidak memadai atau tidak sesuai dengan harapan / keinginan
warga setempat atau bila ada pembebasan lahan maka belum tercapai
kata sepakat untuk kompensasinya.
Gangguan Kamtibmas
Gangguan kamtibmas dapat terjadi apabila keresahan yang timbul di
masyarakat tidak ditanggulangi dengan baik atau tidak adanya solusi yang
dapat diterima oleh masing-masing pihak, baik pemrakarsa maupun
warga setempat (terjadi kebuntuan) atas masalah yang dihadapi.
Gangguan kamtibmas dapat berupa protes atau aksi yang mengancam
kelancaran kegiatan pembangunan proyek.
8.1.3.2 Perlindungan Sosial Pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan
a. Mobilisasi Tenaga Kerja
Peningkatan Kesempatan Kerja
Peningkatan kesempatan kerja disebabkan oleh adanya kebutuhan tenaga
kerja untuk melaksanakan kegiatan pembangunan proyek terutama
Kecemburuan sosial
Kecemburuan sosial dapat timbul jika pihak kontraktor proyek lebih
mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari luar wilayah proyek dalam
perekrutan pekerja proyek.
Gangguan kamtibmas
Gangguan kamtibmas dapat terjadi jika kecemburuan sosial yang ada di
masyarakat dibiarkan berlarut-larut tanpa diantisipasi dengan baik akan
dapat mengancam kelancaran kegiatan pembangunan proyek. Selain itu,
gangguan kamtibmas dapat terjadi apabila tenaga kerja proyek tidak
dapat berbaur dengan masyarakat setempat atau melakukan tindakan
kriminalitas.
b. Mobilisasi Peralatan dan Material
Penurunan kualitas udara
Penurunan kualitas udara disebabkan oleh tingginya kadar polutan
kendaraan bermotor yang digunakan untuk pengangkutan material.
Penurunan kualitas udara terjadi terutama pada jalan-jalan yang dilalui
kendaraan pengangkut yang umumnya akan melewati daerah padat
penduduk.
Peningkatan kebisingan
Peningkatan kebisingan berasal dari suara bising kendaraan
pengangkut yang digunakan terutama jika mobilisasi alat berat dan
material dilakukan dalam jumlah besar dan bersamaan serta melewati
wilayah penduduk padat.
Peningkatan volume lalu lintas
Peningkatan volume lalu lintas dapat terjadi pada ruas-ruas jalan yang
menjadi rute pengangkutan terutama di jalan-jalan yang padat atau jika
mobilisasi alat berat dan material dilakukan pada jam-jam sibuk
Kerusakan Jalan
Kerusakan Jalan dapat terjadi pada ruas-ruas jalan yang menjadi rute
pengangkutan terutama di jalan-jalan yang padat atau jika mobilisasi
alat berat dan material dilakukan menggunakan kendaraan besar dan
c. Pembangunan dan Pengoperasian Base Camp
Peningkatan volume air buangan
Peningkatan volume air buangan terjadi karena adanya penggunaan
KM/WC di base camp oleh pekerja proyek. Air sisa dari kegiatan di
KM/WC tersebut akan menimbulkan air limbah, dan bila hanya dibuang
langsung ke saluran akan memberikan peningkatan pencemaran.
Peningkatan volume sampah
Peningkatan volume sampah diprakirakan timbul dari kegiatan
manajemen dan aktivitas pekerja proyek yang tinggal di base camp.
Sampah yang dihasilkan sebagian besar berupa sampah yang dapat didaur
ulang seperti kertas, lapak dan lain-lain dan sisanya adalah sampah yang
mudah terurai (sisa-sisa makanan).
Gangguan kamtibmas
Gangguan kamtibmas dapat terjadi apabila terdapat konflik antara
masyarakat sekitar dengan tenaga kerja proyek atau pekerja proyek
melakukan tindakan kriminalitas di lokasi proyek dan sekitarnya.
d.Pekerjaan Penyiapan Lahan
Keresahan masyarakat
Keresahan Masyarakat dapat timbul dari penyiapan lahan. Karena
masyarakat khawatir lahan mereka akan tergusur, timbul bau, jumlah
sampah meningkat, timbulnya debu dan bising.
Persepsi positif
Persepsi Positif dapat timbul karena sampah dalam saluran drainase
berkurang serta air limbah dan sistem drainase dapat ditangani dengan
baik
Peningkatan volume sampah hasil dari pengerukan di pinggir saluran
drainase
Peningkatan volume sampah dapat timbul dari kegiatan penyaringan
sampah dan pengerukan endapan pada saluran drainase pada saat
kegiatan normalisasi saluran. Terutama jika sampah tidak segera
dikelola dengan baik.
Berkurangnya Jumlah Sampah dalam Saluran Drainase dapat timbul
karena kegiatan penyaringan sampah dan pengerukan endapan pada
saluran drainase yang akan dinormalisasi.
Penurunan kualitas udara
Penurunan kualitas udara disebabkan karena adanya Bau yang berasal
dari kegiatan penyaringan sampah dan pengerukan endapan pada
saluran drainase serta peningkatan debu akibat kegiatan peralatan
berat untuk penyiapan lahan
Peningkatan kebisingan
Peningkatan kebisingan berasal dari suara bising alat berat yang
digunakan dalam kegiatan penyiapan lahan terutama jika alat berat
tersebut digunakan bersamaan.
Penurunan vegetasi di sepanjang saluran drainase
Penurunan Jumlah Pohon di wilayah proyek dapat terjadi karena
pelebaran drainase atau penyiapan lahan untuk TPST, peningkatan
kualitas TPA, maupun jaringan limbah atau jamban komunal/IPAL
komunal, yang memerlukan penebangan pohon.
e. Pembongkaran aspal dan Penggalian Tanah
Penurunan kualitas udara
Penurunan kualitas udara disebabkan oleh tingginya kadar polutan
akibat adanya emisi dari alat berat yang digunakan dalam kegiatan
pembongkaran aspal dan penggalian tanah untuk kegiatan pemasangan
sistem sewerage atau normalisasi dan pembuatan saluran drainase serta
untuk pemasangan pipa transmisi maupun pipa distribusi.
Peningkatan kebisingan
Peningkatan kebisingan berasal dari suara bising alat berat yang
digunakan dalam kegiatan pembongkaran aspal dan penggalian tanah
terutama jika alat berat tersebut digunakan bersamaan.
Penurunan K3
Penurunan K3 timbul karena adanya penurunan kualitas udara yang
berdampak terhadap kesehatan. Hal ini akan banyak dialami oleh
proyek. Disamping itu, dampak negatif ini juga bisa terjadi jika ada
pekerjaan proyek yang rawan bahaya bagi tenaga kerja proyek atau
terabaikannya sistem K3 sehingga dapat menyebabkan kecelakaan
kerja.
Keresahan masyarakat
Keresahan masyarakat dapat terjadi karena adanya kekhawatiran
masyarakat jika nantinya kegiatan pembongkaran aspal dan penggalian
tanah dapat menyebabkan kerusakan bangunan milik warga yang
berdekatan dengan lokasi proyek dan terganggunya kenyamanan
lingkungan.
f. Pembangunan Bak Kontrol dan Manhole
Penurunan kualitas udara
Penurunan kualitas udara disebabkan oleh tingginya kadar polutan
akibat adanya emisi dari alat berat yang digunakan dalam kegiatan
pembangunan bak kontrol dan manhole sebagai pelengkap pembangunan
sistem jaringan air limbah.
Peningkatan kebisingan
Peningkatan kebisingan berasal dari suara bising alat berat yang
digunakan dalam kegiatan pembangunan bak kontrol dan manhole
terutama jika alat berat tersebut digunakan bersamaan.
Penurunan K3
Penurunan K3 timbul karena adanya penurunan kualitas udara yang
berdampak terhadap kesehatan. Hal ini akan banyak dialami oleh
tenaga kerja proyek dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi
proyek. Disamping itu, dampak negatif ini juga bisa terjadi jika ada
pekerjaan proyek yang rawan bahaya bagi tenaga kerja proyek atau
terabaikannya sistem K3 sehingga dapat menyebabkan kecelakaan
kerja.
g. Pengurugan Pasir, Tanah dan Pengaspalan Kembali (finishing jalur SPAB
dan perpipaan air bersih)
Penurunan kualitas udara disebabkan oleh tingginya kadar polutan baik
debu maupun gas dari proses kegiatan pengaspalan dan akibat adanya
emisi dari alat berat yang digunakan dalam kegiatan Pengurugan Pasir,
Tanah dan Pengaspalan Kembali (finishing jalur SPAB dan perpipaan air
bersih).
h.Pembangunan Jamban beserta Septictank Komunal
Penurunan kualitas udara
Penurunan kualitas udara disebabkan oleh tingginya kadar polutan
akibat adanya emisi dari alat berat yang digunakan dalam kegiatan
Pembangunan Jamban beserta Septictank Komunal.
Peningkatan kebisingan
Peningkatan kebisingan berasal dari suara bising alat berat yang
digunakan dalam kegiatan Pembangunan Jamban beserta Septictank
Komunal terutama jika alat berat tersebut digunakan bersamaan.
Penurunan K3
Penurunan K3 timbul karena adanya penurunan kualitas udara yang
berdampak terhadap kesehatan. Hal ini akan banyak dialami oleh
tenaga kerja proyek dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi
proyek. Disamping itu, dampak negatif ini juga bisa terjadi jika ada
pekerjaan proyek yang rawan bahaya bagi tenaga kerja proyek atau
terabaikannya sistem K3 sehingga dapat menyebabkan kecelakaan
kerja.
Keresahan masyarakat
Keresahan masyarakat dapat terjadi karena adanya kekhawatiran
masyarakat jika nantinya kegiatan Pembangunan Jamban beserta
Septictank Komunal dapat menyebabkan kerusakan bangunan milik warga
yang berdekatan dengan lokasi proyek ataupun dapat menimbulkan
masalah lainnya apabila nantinya bangunan tersebut tidak dikelola
i. Pekerjaan Pondasi
Penurunan Kualitas Udara
Penurunan kualitas udara disebabkan oleh adanya peningkatan debu
serta kadar polutan akibat adanya emisi dari alat berat yang digunakan
dalam kegiatan pekerjaan pondasi bangunan TPST, bangunan IPA dan
IPAL serta bangunan untuk peningkatan kualitas TPA.
Peningkatan Kebisingan
Peningkatan kebisingan berasal dari suara bising alat berat yang
digunakan dalam kegiatan pekerjaan pondasi terutama jika alat berat
tersebut digunakan bersamaan.
Penurunan K3
Penurunan K3 timbul karena adanya penurunan kualitas udara yang
berdampak terhadap kesehatan. Hal ini akan banyak dialami oleh
tenaga kerja proyek dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi
proyek. Disamping itu, dampak negatif ini juga bisa terjadi jika ada
pekerjaan proyek yang rawan bahaya bagi tenaga kerja proyek atau
terabaikannya sistem K3 sehingga dapat menyebabkan kecelakaan
kerja.
Keresahan Masyarakat
Keresahan masyarakat dapat terjadi karena adanya kekhawatiran
masyarakat akan adanya kerusakan bangunan saat pondasi dibuat.
j. Pekerjaan Struktur Bangunan IPAL dan IPA serta sistem jaringan drainase
dan Pelengkapnya
Peningkatan Kebisingan
Peningkatan kebisingan berasal dari suara bising alat berat yang
digunakan dalam Pekerjaan Struktur Bangunan IPA, IPAL, TPST, T PA
dan Pelengkapnya terutama jika alat berat tersebut digunakan
bersamaan.
Penurunan K3
Penurunan K3 timbul kegiatan konstruksi dapat menyebabkan
k. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
Keresahan Masyarakat
Keresahan masyarakat dapat terjadi karena adanya kekhawatiran
masyarakat jika nantinya kegiatan Pembangunan TPST akan
menimbulkan bau dan timbulnya penyebaran bibit penyakit.
Penurunan Kualitas Udara
Penurunan kualitas udara disebabkan oleh adanya peningkatan debu
serta kadar polutan akibat adanya emisi dari alat berat yang digunakan
dalam kegiatan pekerjaan pembangunan TPST.
Peningkatan Kebisingan
Peningkatan kebisingan berasal dari suara bising alat proyek yang
digunakan dalam kegiatan pekerjaan pembangunan TPST .
l. Demobilisasi Peralatan dan Material
Penurunan kualitas udara
Penurunan kualitas udara disebabkan oleh tingginya kadar polutan dari
emisi yang dihasilkan kendaraan pengangkut pengembalian alat berat dan
sisa material. Penurunan kualitas udara terutama terjadi di jalan-jalan
yang dilalui kendaraan pengangkut alat berat.
Peningkatan kebisingan
Peningkatan kebisingan berasal dari suara bising kendaraan
pengangkut yang digunakan.
Peningkatan volume lalu lintas
Peningkatan volume lalu lintas dapat terjadi pada ruas-ruas jalan yang
menjadi rute pengangkutan kegiatan demobilisasi alat berat dan sisa
material, terutama di jalan-jalan yang padat atau pada jam-jam sibuk.
m. Demobilisasi Tenaga Kerja
Penurunan lapangan pekerjaan
Menurunnya lapangan pekerjaan dapat terjadi di akhir masa konstruksi
karena selesainya masa kontrak kerja antara pekerja proyek dengan
Khusus untuk peningkatan kualitas TPA, maka dampak yang terjadi
pada tahap konstruksi adalah :
a. Pembangunan jalan akses ke TPA dan jalan operasional dilakukan
dengan konstrusi berupa jalan beton bertulang belakang. Kegiatan
perkerasan beton tersebut dilakukan dengan menggunakan alat-alat
berat yang dapat menimbulkan penurunan kualitas udara berupa
peningkatan emisi gas buang kendaraan dan debu di udara.
b. Pada kegiatan recovery sampah lama dengan penataan kembali
operasional sel-sel sampah di atasnya, dilakukan pemadatan sampah
lama mamakai buldozer sehingga terdapat dampak adanya penurunan
sampah sehingga perataan sampah dalam setiap sel dalam proses
penataan memerlukan kecermatan dan kehati-hatian karena
kemungkinan masih ada gas yang terperangkap yang menyebabkan
penurunan kualitas udara. Sedangkan pada pemanfaatan sampah lama
yang digunakan sebagai biogas dapat memberikan peluang usaha
namun kegiatan ini juga dapat berisiko akan terjadi penumpukan gas
landfill yang menyebabkan terjadinya gangguan K3 akibat
kemungkinan ledakan gas di dalam sampah.
c. Kegiatan pembangunan saluran drainase sebagai saluran untuk
mengalirkan limpasan dari TPA dapat menyebabkan terjadinya
perubahan pola aliran dan potensi banjir. Pada pembangunan tanggul
penahan sampah dapat menyebabkan terjadinya potensi longsor pada
timbunan sampah.
d. Kegiatan pemasangan pipa ventilasi gas dan pipa lindi dilakukan
setelah tanah di areal sel sampah diratakan. Pipa ventilasi gas
merupakan jalan keluarnya gas metahana yang terperangkap dalam
timbunan sampah, sehingga terjadi peningkatan produksi gas methan
atau tertangkapnya gas methana. Pemasangan pipa lindi sebagai jalan
keluarnya air lindi menuju saluran lindi berdampak pada
tertangkapnya cairan lindi dan menghindari meresapnya lindi ke
e. Kegiatan Pagar keliling TPA memberikan dampak positip terjadinya
penurunan gangguan kamtibmas karena keleluasaan masuknya
masyarakat ke dalam TPA sudah terbatasi karena adanya pemagaran.
8.1.3.3 Perlindungan Sosial Pada Tahap Pasca Pelaksanaan Pembangunan
a. Operasional dari saluran drainase, Pipa Jalur SPAB, Jamban dan
Septicktank Komunal, IPAL, pompa dan TPST
Peningkatan fungsi saluran
Karena saluran drainase sudah dibersihkan dan saluran juga sudah
diperbaiki sehingga fungsi saluran drainase lebih maksimal. Dan saluran
drainase dan SPAB sudah terpisah sehingga saluran drainase tidak
bercampur dengan air limbah sehingga lebih bersih dan sehat.
Peningkatan kualitas air saluran
Kualitas air pada seluruh badan air akan meningkat karena kondisi
perairan lebih bersih dan air dapat mengalir dengan baik serta sistem
penyaluran air limbah tertata secara jaringan.
Peningkatan kesempatan kerja
Meningkatnya lapangan pekerjaan disebabkan oleh adanya kebutuhan
tenaga kerja sebagai tenaga operator dan sebagai pemelihara dari semua
fasilitas yang telah di bangun.
Kecemburuan sosial
Kecemburuan sosial dapat timbul jika pihak pemrakarsa lebih
mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari luar wilayah proyek dalam
perekrutan tenaga kerja.
Berkurangnya volume sampah pada saluran drainase
Volume sampah akan berkurang sejalan dengan adanya pengoperasian
TPST dan sarana lain yang mendukung.
Penurunan Banjir
Karena saluran drainase telah ternormalisasi dan mengalir sesuai
fungsinya, maka diharapkan tidak akan terjadi genangan/banjir di
kawasan proyek.
Perilaku masyarakat akan lebih baik karena seluruh infrastruktur sanitasi
lingkungan telah terbangun dan difungsikan terutama masyarakat
diharapkan tidak membuang sampah dan air limbah ke badan air dan tidak
melakukan aktivitas apapun untuk membuang limbah ke badan air.
Peningkatan Estetika lingkungan
Estetika lingkungan akan meningkat dengan beroperasinya seluruh
sarana dan prasarana proyek. Peningkatan Estetika lingkungan ditandai
dengan semakin bersihnya kawasan dimana proyek dilakukan.
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Kesehatan masyarakat diprakirakan akan menjadi lebih baik karena
sarana sanitasi telah terbangun dan lingkungan menjadi lebih sehat.
b.Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
Peningkatan Kualitas dan Estetika Lingkungan
Dengan beroperasinya proyek sesuai fungsinya maka volume sampah
berkurang dan air limbah tidak dibuang langsung ke saluran. Dengan
berkurangnya sampah dan air limbah maka secara tidak langsung
meningkatkan kualitas dan estetika lingkungan.
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Peningkatan kesehatan masyarakat disebabkan membaiknya kondisi
estetika lingkungan. Hal ini akan banyak meningkatkan kesehatan
masyarakat di kawasan proyek dan sekitarnya.
Khusus untuk kegiatan peningkatan TPA maka dampak yang terjadi adalah
sebagai berikut :
Kegiatan operasional TPA dimulai dari proses pengangkutan sampah dari
TPS ke TPA, Kegiatan pengangkutan sampah dapat memberikan prioritas
dampak penting hipotesis adanya penurunan kualitas udara, peningkatan
kecelakaan, penurunan kesehatan masyarakat.
Pada kegiatan operasional sel harian (bongkar muat sampah) terjadi
proses penyortiran sampah dahulu yang berdampak Penurunan Kualitas
Udara (Bau). Hal ini juga bisa menyebarkan peningkatan vektor penyakit
yang berdampak pada penurunan Kesehatan masyarakat sebelum
keresahan pada pemulung karena kesempatan mendapatkan barang bekas
semakin kecil.
Pada kegiatan pengoperasian sampah selalu dilakukan perataan dan
pemadatan sampah dengan peralatan buldozer dimana pada akhir
operasional sampah diurug dan dipadatkan dengan tanah urug. Hal in
berdampak menyebabkan penurunan populasi lalat dan penurunan
kualitas udara.
Kegiatan pengoperasian IPAL Lindi, lindi disalurkan ke IPAL dan diolah
secara biologis. Pemilihan teknologi yang tidak tepat akan
mengakibatkan adanya dampak penurunan kualitas air pemukaan dan
peningkatan bau.
Kegiatan pengoperasian pipa gas berupa pengoperasian saluran ventilasi
dilakukan untuk pengendalian gas pengamanan pada timbunan sampah
dan adanya tangkapan gas ini menyebabkan adanya potensi kebakaran
dan keresahan pada masyarakat.
Kegiatan pengolahan sampah akan memberikan dampak adanya
penurunan volume sampah di TPA, kesempatan kerja karena terdapat
diversifikasi usaha dari sampah dan persepsi positip masyarakat.
Kegiatan pemeliharaan lingkungan TPA dilakukan terhadap semua sarana
dan fasilitas fisik pada TPA sehingga berdampak pada peningkatan