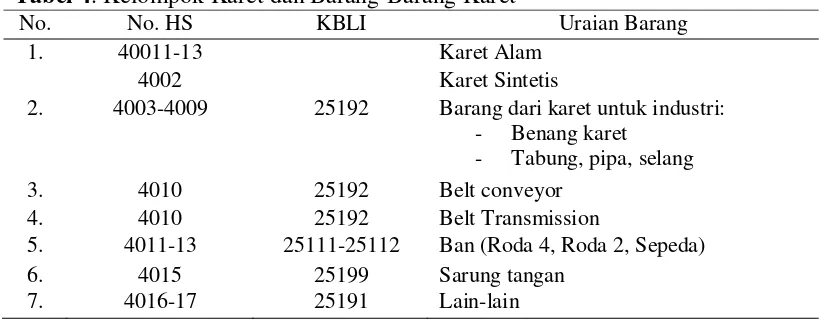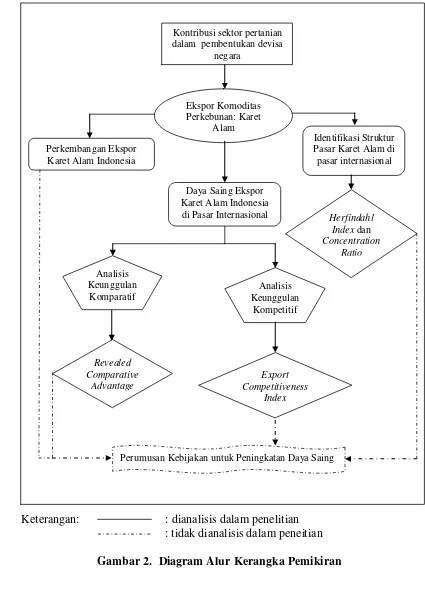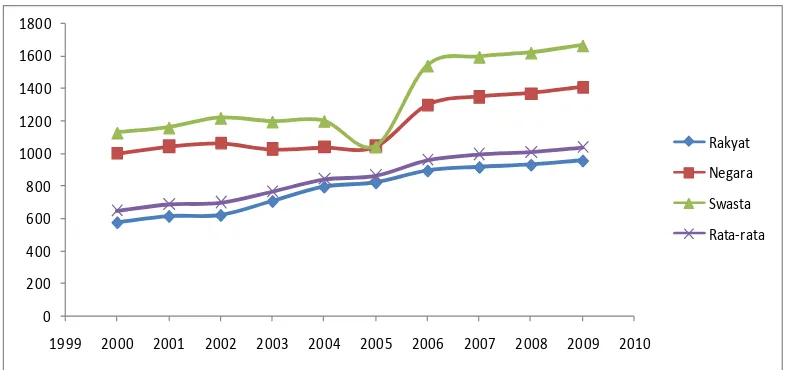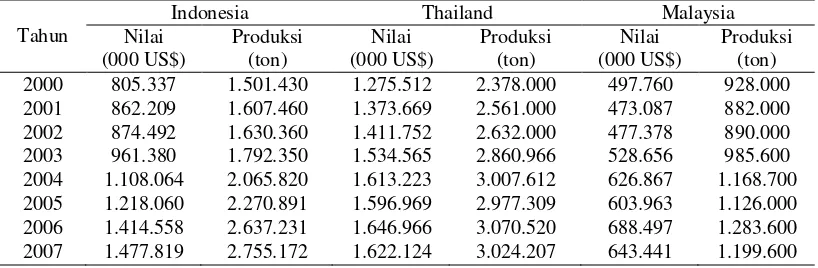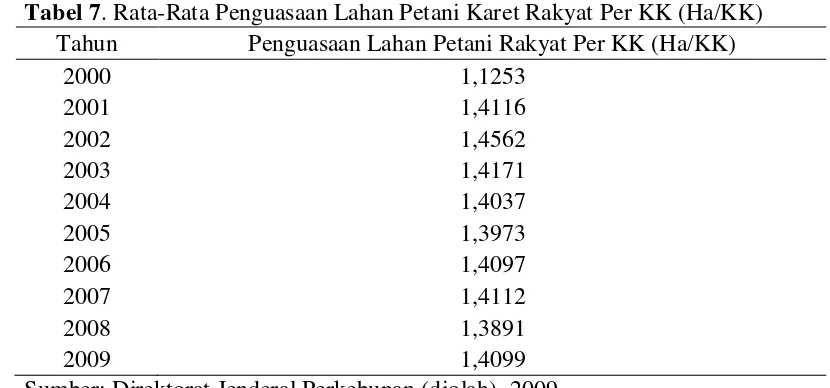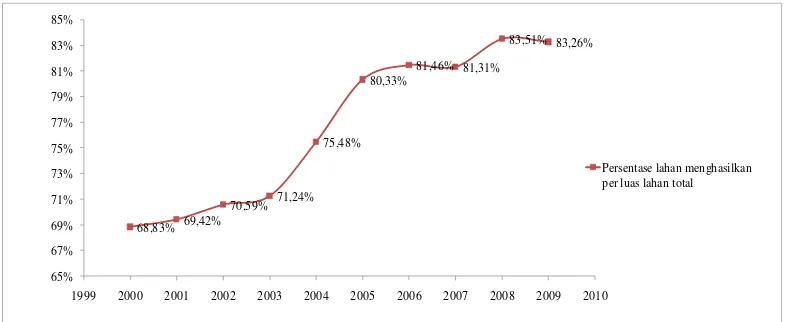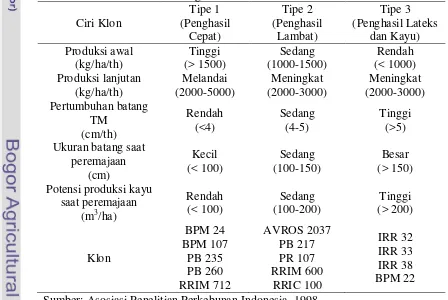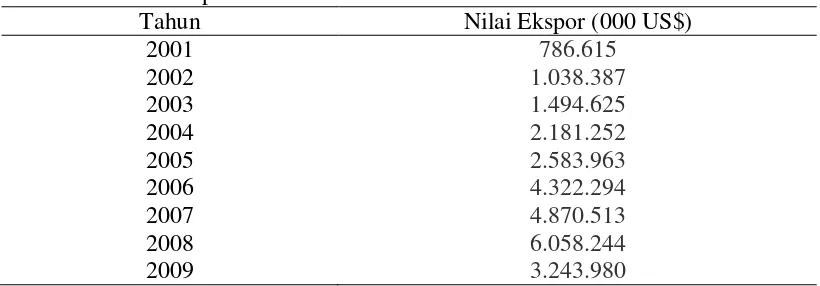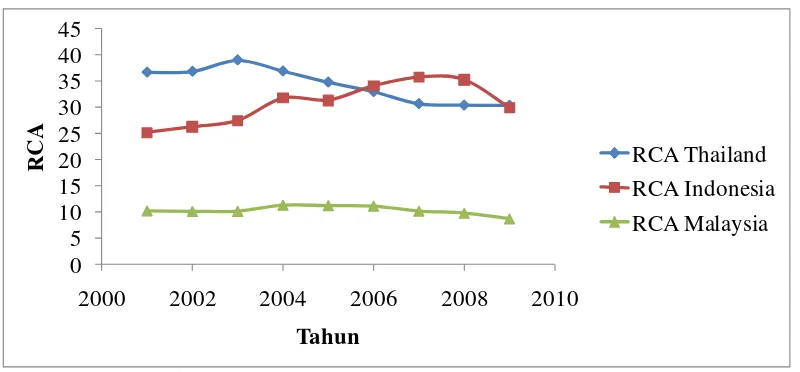ANALISIS DAYA SAING EKSPOR KARET ALAM
INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL
EKA RATNAWATI
DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
QS. Al Hujuraat (49): 10
RINGKASAN
EKA RATNAWATI. Analisis Daya Saing Ekspor Karet Alam Indonesia di Pasar Internasional. Dibimbing Oleh ADI HADIANTO
Menghadapi era perdagangan bebas saat ini penting artinya untuk melihat keunggulan dan daya saing yang dimiliki setiap negara, mengingat globalisasi menuntut adanya persaingan. Karet alam merupakan salah satu produk andalan ekspor Indonesia. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki areal karet alam terbesar didunia. Meskipun demikian, Indonesia hanya menjadi eksportir terbesar kedua setelah Thailand.
Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan ekspor karet alam Indonesia serta untuk mengetahui struktur pasar yang terbentuk pada komoditas karet alam di pasar internasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apakah Indonesia, sebagai salah satu negara pengekspor karet alam terbesar memiliki keunggulan untuk produk tersebut, baik secara komparatif maupun kompetitif. Struktur pasar yang terbentuk pada perdagangan karet alam di pasar internasional dilakukan dengan menggunakan analisis
Herfindahl Index (HI) dan Concentration Ratio (CR), sedangkan analisis daya saing ekspornya dilakukan dengan menggunakan analisis Revealed Comparative Advantage (RCA) untuk melihat status keunggulan komparatif dan Export Competitiveness Index (ECI) untuk melihat status keunggulan kompetitif negara eksportir karet alam.
Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menyatakan bahwa struktur pasar yang terbentuk pada perdagangan karet internasional adalah struktur pasar yang berbentuk oligopoly, yang mana pasar dikuasai oleh tiga eksportir utama karet alam, yaitu Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Pangsa pasar rata-rata yang dikuasai oleh ketiga negara ini dalam kurun waktu 2001-2009 adalah sebesar 78%, yang mana hal ini berarti dalam kurun waktu tersebut, ketiga negara eksportir utama karet alam internasional menguasai 78% pasar karet alam internasional. Perhitungan mengenai keunggulan komparatif negara-negara eksportir karet alam menyatakan bahwa masing-masing negara eksportir utama tersebut memiliki keunggulan komparatif. Hal ini terlihat dari nilai RCA yang lebih besar dari 1. Berbeda dengan perhitungan tersebut, perhitungan mengenai keunggulan kompetitif negara ekspotir utama karet alam dengan menggunakan analisis ECI menyatakan bahwa hingga tahun 2008, hanya Indonesia yang memiliki keunggulan kompetitif, sedangkan Thailand dan Malaysia tidak memiliki keunggulan ini. Hal tersebut dilihat dari nilai ECI yang lebih kecil dari 1. Perhitungan tersebut memberikan gambaran bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam perdagangan (ekspor) karet alam. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari keunggulan yang dimiliki Indonesia dalam perdagangan karet alam, sehingga daya saing yang dimiliki Indonesia perlu untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan.
PERNYATAAN
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI YANG BERJUDUL
“ANALISIS DAYA SAING EKSPOR KARET ALAM INDONESIA DI PASAR
INTERNASIONAL” BELUM PERNAH DIAJUKAN PADA PERGURUAN
TINGGI LAIN ATAU LEMBAGA LAIN MANAPUN UNTUK TUJUAN
MEMPEROLEH GELAR AKADEMIK TERTENTU. SAYA JUGA
MENYATAKAN SKRIPSI INI BENAR-BENAR HASIL KARYA SENDIRI
DAN TIDAK MENGANDUNG BAHAN-BAHAN YANG PERNAH DITULIS
ATAU DITERBITKAN OLEH PIHAK LAIN KECUALI SEBAGAI RUJUKAN
YANG DINYATAKAN DALAM NASKAH.
Bogor, Januari 2011
ANALISIS DAYA SAING EKSPOR KARET ALAM
INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL
EKA RATNAWATI H44061590
Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada
Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
Judul Skripsi : Analisis Daya Saing Ekspor Karet Alam Indonesia di Pasar Internasional
Nama : Eka Ratnawati
NIM : H44061590
Menyetujui, Pembimbing,
Adi Hadianto, SP, M.Si NIP: 19790615 200501 1 004
Mengetahui, Ketua Departemen,
Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT NIP: 19660717 199203 1 003
RIWAYAT HIDUP
Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan resmi ibu Titi Ariyati dan ayah M. Jamhari. Penulis dilahirkan dengan selamat di Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 15 Juli 1987.
PRAKATA
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan umat, Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi umatnya dan membawa perubahan menuju peradaban yang lebih baik.
Skripsi yang berjudul “Analisis Daya Saing Ekspor Karet Alam Indonesia di Pasar Internasional” ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat penyelesaian studi jenjang Strata 1 (S1) di Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat kerja keras, do’a, dorongan, dan bantuan yang luar biasa dari berbagai pihak.
Terimakasih utamanya penulis sampaikan kepada mama tercinta, Titi Ariyati yang senantiasa berjuang dengan kesabaran serta do’a yang tiada putus -putusnya, dan adikku, Nur Ratih atas dorongan dan semangat yang diberikan. Tak lupa penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Pemda Kutai Kartanegara atas bantuan dana yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 dengan baik. Terimakasih kepada bapak dan seluruh keluarga besar, baik yang berada di Sangasanga, Samarinda, Balikpapan, maupun di Haruai yang senantiasa memberikan do’a dan dukungan, Ninuk dan keluarga di Tenggarong yang terus memberikan do’a dan secercah harapan. Kepada seluruh guru yang telah mengajar penulis sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan jenjang Perguruan Tinggi (apresiasi dan terimakasih yang tiada habisnya pada bapak dan ibu semua).
utama, Bapak Ujang Sehabudin, serta kepada dosen penguji wakil departemen, Bapak Novindra atas masukan yang diberikan. Kepada pengurus perpustakaan balai penelitian karet penulis juga mengucapkan terimakasih atas informasi-informasi yang telah diberikan. Juga kepada mba Aam atas bantuan yang diberikan.
Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada sahabat seperjuangan di Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Riana Ekawati (terus semangat untuk mengukir kembali mimpi kita bu), sahabat 99, Yunita Mukti Noor Yanti, Harli Septian, Rafik Albar, Hairika Maulani, Agustya Lutfiani, dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu (semoga persahabatan tetap menyatukan kita). Kepada teman-teman di Pondok RIZQI, Yanti (yanti???), mba Ummi (begadang lagi mba?), mba Peni, mba Wage, Isma, Reni, dan semuanya atas bantuan dan semangat yang diberikan. Tak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada para sahabat dan semua teman semasa TK, SD, SLTP, SMA, TPB (B01_ers), teman-teman di FM BUD KUKAR, organisasi, kepanitiaan, serta teman-teman di Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu (kalian semua telah memberikan warna dalam hidup saya).
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pengetahuan bagi semua pihak yang berkepentingan.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Bogor, Januari 2011
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR TABEL ... xi
DAFTAR GAMBAR ... xii
DAFTAR LAMPIRAN ... xiii
I. PENDAHULUAN ... 1
1.1. Latar Belakang ... 1
1.2. Perumusan Masalah ... 7
1.3. Tujuan Penelitian... 9
1.4. Manfaat Penelitian ... 9
1.5. Ruang Lingkup Penelitian ... 9
II. TINJAUAN PUSTAKA ... 11
2.1. Peran Sektor Pertanian... 11
2.2. Perkebunan ... 12
2.3. Konsep Keunggulan dan Daya Saing Ekspor ... 15
2.4. Ekspor sebagai Sumber Devisa ... 16
2.5. Karet Alam ... 18
2.5.1. Perbedaan Karet Alam dengan Karet Sintetis ... 20
2.5.2. Jenis-Jenis Karet Alam ... 21
2.5.3. Manfaat Karet ... 25
2.6. Bentuk Kerjasama Antar Negara Produsen Karet Alam ... 27
2.7. Penelitian Terdahulu ... 29
III. KERANGKA PEMIKIRAN ... 33
IV. METODOLOGI PENELITIAN ... 39
4.1. Jenis dan Sumber Data ... 39
4.2. Metode Pengolahan dan Analisis Data ... 39
4.2.1. Analisis Struktur Pasar ... 40
4.2.2. Analisis RCA ... 43
4.2.3. Analisis ECI ... 44
V. GAMBARAN UMUM KARET ALAM ... 46
5.1. Sejarah Karet Dunia dan Indonesia ... 46
5.2. Permintaan dan Penawaran Karet Alam ... 49
5.3. Perkembangan Produksi Karet Alam Indonesia dibandingkan Thailand dan Malaysia sebagai Produsen Utama Karet Alam Dunia ... 51
5.4. Sentra Produksi Karet Indonesia ... 58
5.5. Kemajuan Pemuliaan Karet Indonesia ... 62
5.5.1. Produktivitas Karet ... 62
x
5.5.3. Pertumbuhan Tanaman Menghasilkan (TM) ... 64
5.5.4. Tipe Keunggulan Klon ... 65
VI. PERKEMBANGAN EKSPOR KARET ALAM INDONESIA ... 67
6.1. Perkembangan Nilai dan Volume Ekspor Karet Alam Indonesia ... 67
6.2. Tujuan Ekspor Karet Alam Indonesia ... 70
6.3. Perkembangan Ekspor Karet Alam Negara Pesaing ... 73
VII. STRUKTUR PASAR KARET ALAM DI PASAR INTERNASIONAL ... 77
7.1. Pangsa Pasar Karet Alam ... 77
7.2. Herfindahl Index dan Concentration Ratio ... 79
VIII. DAYA SAING EKSPOR KARET ALAM ... 82
8.1. Analisis Revealed Comperative Advantage ... 83
8.2. Analisis Export Competitiveness Index ... 86
IX. KESIMPULAN DAN SARAN ... 90
9.1. Kesimpulan ... 90
9.2. Saran ... 91
DAFTAR PUSTAKA ... 93
xi
DAFTAR TABEL
Nomor Halaman
1. Kontribusi Ekspor Sektor Pertanian terhadap Ekspor NonMigas
Tahun 2000-2009 (Juta US$) ... 2
2. Kontribusi Ekspor Karet Alam terhadap Ekspor NonMigas (Juta US$) ... 3
3. Ranking Global Competitiveness Indeks (GCI) ... 5
4. Kelompok Karet dan Barang-Barang Karet... 20
5. Standard Indonesian Rubber (SIR) ... 24
6. Perkembangan Nilai dan Produksi Karet Alam Negara Eksportir Utama... 56
7. Rata-Rata Penguasaan Lahan Petani Karet Rakyat per KK (Ha/KK) ... 60
8. Pengelompokkan Klon Karet berdasarkan Laju Pertumbuhan TBM ... 63
9. Pengelompokkan Klon Karet berdasarkan Pertumbuhan Batang TM ... 64
10.Tipe Klon Unggul berdasarkan Pola Produksi Karet Kering dan Laju Pertumbuhan Batang ... 65
11.Nilai Ekspor Karet Alam Dunia ... 67
12.Nilai Ekspor Karet Alam Indonesia ... 68
13.Volume Ekspor Karet Alam Indonesia ... 69
14.Kuantitas Ekspor Karet Alam Indonesia ke Negara Tujuan Ekspor Utama ... 70
15.Nilai Ekspor Karet Alam Indonesia ke Negara Tujuan Ekspor Utama... 72
16.Kuantitas Ekspor Negara Pesaing Utama Karet Alam Dunia ... 73
17.Nilai Ekspor Negara Pesaing Utama Karet Alam Dunia ... 74
18.Harga Ekspor Karet Alam Negara Eksportir Utama (US$/ton) .... 75
xii
DAFTAR GAMBAR
Nomor Halaman
1. World Economic Forum: 12 Pillars of Competitiveness ... 6 2. Diagram Alur Kerangka Pemikiran ... 38
3. Perbandingan Luas Areal Tanam dan Produktivitas Karet Alam Negara Produsen Utama ... 53 4. Perkembangan Produktivitas Lahan Karet alam Indonesia
berdasarkan Status Pengusahaan ... 55 5. Perkembangan Luas Lahan Tanaman Menghasilkan terhadap
Luas Lahan Total Karet Alam Indonesia ... 61 6. Persentase Volume Ekspor Karet Alam Indonesia ke Beberapa
Negara Tujuan Ekspor Utama ... 71 7. Penguasaan Pasar Eksportir Utama Karet Alam ... 78
8. Perbandingan Nilai RCA Negara Eksportir Utama Karet Alam... 83
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Halaman
1. Luas Areal Karet Perkebunan Rakyat Menurut Provinsi di Indonesia (Ha) ... 100
2. Produksi Karet Perkebunan Rakyat Menurut Provinsi di Indonesia (ton) ... 101
3. Perhitungan Penguasaan Pasar Negara Eksportir Karet Alam Dunia ... 103
I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya
berusaha di bidang pertanian. Dengan tersedianya lahan dan jumlah tenaga kerja
yang besar, diharapkan sektor ini dapat mendorong pertumbuhan perekonomian
nasional. Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat rata-rata penyerapan tenaga
kerja di sektor pertanian periode 2003-2010 sebesar 42,75%, meskipun kontribusi
sektor ini terhadap PDB nasional hanya sekitar 15% (Badan Pusat Statistik, 2010).
Kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan devisa negara tergolong
cukup besar, terutama subsektor perkebunan Sektor pertanian Indonesia pada
neraca perdagangan periode 2006-2008 menunjukkan nilai yang positif (surplus).
Menurut data BPS (2009), pada tahun 2006 neraca perdagangan sektor pertanian
mengalami surplus sebesar 8,9 juta US$. Nilai ini meningkat pada tahun 2007
menjadi 13,3 juta US$ dan tahun 2008 sebesar 12,4 juta US$.
Surplus yang terjadi pada neraca perdagangan sektor pertanian
dikarenakan nilai ekspor komoditas pertanian yang cenderung mengalami
peningkatan, yaitu dari sebesar 2,7 milyar US$ pada tahun 2000 menjadi 4,6
milyar US$ pada tahun 2008. Besaran nilai ekspor sektor pertanian periode
2000-2008 diperlihatkan pada Tabel 1. Peningkatan nilai ekspor ini mengindikasi
perbaikan yang terjadi di bidang pertanian terhadap ekspor nonmigas. Pada Tabel
1 terlihat kontribusi ekspor sektor pertanian terhadap ekspor nonmigas selama
2
Tabel 1. Kontribusi Ekspor Sektor Pertanian terhadap Ekspor Nonmigas Tahun 2000-2008 (Juta US$)
Tahun Ekspor Pertanian
Ekspor Nonmigas
Kontribusi Ekspor Pertanian terhadap Ekspor Nonmigas
2000 2 709,1 47 757,4 5,67%
2001 2 438,5 43 684,6 5,58%
2002 2 568,3 45 046,1 5,70%
2003 2 526,2 47 406,6 5,33%
2004 2 496,2 55 939,3 4,46%
2005 2 880,3 66 428,5 4,34%
2006 3 364,9 78 589,1 4,28%
2007 3 657,8 92 012,3 3,98%
2008 4 584,6 107 894,1 4,25%
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2003-2009
Melihat besaran kontribusi ekspor sektor pertanian terhadap ekspor
nonmigas di atas, maka pengembangan sektor pertanian diharapkan dapat menjadi
pendorong pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang. Hal ini salah
satunya dapat dilakukan dengan pengembangan komoditas unggulan pertanian.
Dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 terdapat 39
komoditas pertanian yang ingin dipacu produksinya. Dari jumlah tersebut terdapat
14 komoditas yang pengembangannya bukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan
tetapi lebih kepada substitusi impor, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri
dalam negeri, serta pengembangan ekspor. Karet merupakan salah satu komoditas
unggulan yang menjadi target pengembangan karena memiliki potensi pasar yang
cukup luas, terutama di pasar ekspor.
Pengutamaan ekspor bagi Indonesia sudah digalakkan sejak tahun 1983
(Basri, 2002). Bahkan sejak tahun 1988, sumber utama perolehan devisa
Indonesia bertumpu pada penerimaan ekspor nonmigas (Dumairy, 1996). Dalam
perkembangannya, ekspor memiliki peranan yang penting dalam perekonomian
nasional, terlebih sejak digulirkannya perundingan WTO menuju perdagangan
3 yang menimbulkan guncangan sosial dan politik dapat terselamatkan salah
satunya oleh kinerja ekspor pertanian (Basri, 2002).
Kinerja ekspor pertanian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang
cukup baik, khususnya hasil perkebunan. Salah satu ekspor komoditas yang
menjadi andalan Indonesia adalah komoditas karet dan barang karet, di samping
CPO yang tetap menjadi primadona ekspor Indonesia. Kontribusi nilai ekspor
karet alam Indonesia terhadap ekspor nonmigas diperlihatkan pada Tabel 2.
Persentase ekspor karet alam Indonesia terhadap ekspor non migas cenderung
meningkat, yaitu dari 1,8% pada tahun 2001 menjadi 5,61% pada tahun 2008
(Badan Pusat Statistik, 2009). Pertumbuhan yang secara signifikan mengalami
peningkatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja yang cukup baik
dari komoditas ini (Parhusip, 2008).
Tabel 2. Kontribusi Ekspor Karet Alam terhadap Ekspor Nonmigas (Juta US$)
Tahun Ekspor Nonmigas
Ekspor Karet Alam
Persentase Ekspor Karet Alam Thd Ekspor Non Migas
2001 43 684,6 787 1,80%
2002 45 046,1 1 038 2,31%
2003 47 406,6 1 495 3,15%
2004 55 939,3 2 181 3,90%
2005 66 428,5 2 584 3,89%
2006 78 589,1 4 322 5,50%
2007 92 012,3 4 871 5,29%
2008 107 894,1 6 058 5,61%
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009
Indonesia merupakan negara dengan luas areal perkebunan karet terbesar
di dunia (Food and Agriculture Organization, 2010). Meskipun demikian, hal
tersebut tidak menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor karet terbesar.
Indonesia menduduki posisi kedua produksi dan ekspor karet alam setelah
Thailand (United Nation Comtrade, 2010). Pentingnya komoditas karet alam
4 ekspor sehingga komoditas ini kemudian dapat dijadikan sebagai salah satu
penopang perekonomian nasional.
Dalam rangka menjalin hubungan dagang secara internasional, Indonesia
turut serta dalam penerapan kebijakan-kebijakan dagang. Awal pelaksanaan
pembangunan jangka panjang kedua banyak tantangan yang dihadapi oleh
Indonesia. Tantangan tersebut antara lain keikutsertaan Indonesia dalam
organisasi perdagangan dunia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994
tentang Pengesahan Agreement on Establishing WTO (World Trade Organization)
(Sukarmi, 2002). Indonesia yang termasuk dalam anggota ASEAN membuka
jalan perdagangannya dengan berpartisipasi dalam perjanjian perdagangan bebas
dengan anggota-anggota ASEAN lain. Bentuk hubungan kerjasama ini dikenal
dengan nama AFTA (ASEAN Free Trade Area). AFTA dibentuk pada KTT
ASEAN IV di Singapura pada tahun 1992. Pembentukan ini didasarkan tujuan
membentuk kawasan bebas perdagangan ASEAN dalam upaya meningkatkan
daya saing ekonomi regional ASEAN.
Kondisi globalisasi yang terjadi menyebabkan perlunya perhatian lebih
terhadap daya saing produk domestik mengingat bahwa globalisasi menuntut
adanya persaingan. Konsep daya saing tidak saja dilihat dari keunggulan
komparatif tetapi lebih didasarkan pada keunggulan kompetitif produk.
Globalisasi membuat pasar antarnegara menjadi semakin luas. Negara yang
memiliki keunggulan kompetitif cenderung semakin dapat memperkaya
negaranya dan negara yang tidak siap dalam menghadapi persaingan di pasar
global akan semakin terpuruk (Oktaviani dan Novianti, 2009). World Economic
5 mendefinisikan daya saing sebagai himpunan kelembagaan, kebijakan, dan
faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara (Daryanto, 2009).
Laporan Daya Saing Global atau Global Competitiveness Report yang
merupakan laporan tahunan dari WEF membahas mengenai masalah kemampuan
negara-negara untuk menyediakan kemakmuran tingkat tinggi bagi warga
negaranya. Tabel 3 memperlihatkan perbandingan peringkat keunggulan
kompetitif beberapa negara pada periode 2010-2011 dan perbandingan dengan
tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan pada tabel tersebut terlihat bahwa pada
periode 2010-2011, Indonesia berada pada peringkat 44 dari 139 negara yang
disurvei, meningkat 10 peringkat dari periode sebelumnya.
Tabel 3. Ranking Global Competitiveness Indeks (GCI)
No Negara GCI 2010-2011 Rank
GCI 2009-2010 Rank
GCI 2008-2009 Rank
GCI 2007-2008 Rank
1 Indonesia 44 54 55 54
2 Thailand 38 36 34 28
3 Singapore 3 3 5 7
4 Vietnam 59 75 70 68
5 Malaysia 26 24 21 21
6 India 51 49 50 48
7 China 27 29 30 34
8 Philippines 85 87 71 71
Sumber: Schwab, 2010
Peningkatan terhadap posisi daya saing global Indonesia dipengaruhi oleh
berbagai indikator. Pendorong utama dalam peningkatan ini adalah perbaikan
pada pilar makroekonomi1. WEF mencatat perbaikan Indonesia terhadap kondisi
makroekonominya relatif baik, yang mana hal ini ditunjukkan oleh peningkatan
peringkat daya saing pada indikator tersebut sebanyak 17 peringkat sejak
terjadinya krisis moneter (Schwab, 2010).
6 Penentuan indeks daya saing global tersebut menggunakan 12 pilar utama
yang mempengaruhi daya saing, yang mana penentunya terbagi atas tiga
kelompok besar, yaitu kelompok persyaratan dasar, kelompok peningkat efisiensi,
serta kelompok inovasi dan kecanggihan. Pengelompokan pilar-pilar tersebut
terlihat sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1. Pilar makroekonomi menjadi
salah satu penilaian dalam kelompok persyaratan dasar.
Sumber: Schwab, 2010 (World Economic Forum: Global Competitiveness Report 2010-2011) Gambar 1. World Economic Forum: 12 Pillars of Competitiveness
Dalam indeks makroekonomi, kinerja ekspor merupakan salah satu
variabel utama. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa
peningkatan daya saing suatu negara sangat ditentukan oleh kinerja ekspornya
(Hadianto, 2010). Atas dasar konsep ini maka analisis terhadap daya saing ekspor
karet alam sebagai salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia penting untuk
dilakukan. Hal ini sebagai salah satu faktor yang diharapkan dapat meningkatkan
Basic requirements
Institution
Infrastructure
Macroeconomic stability
Helth and primary education
Key for Factor-driven
economies
Eficiency Enhancers
Higher education and training
Goods market efficiency
Labor market efficiency
Financial market sophistication
Technological readiness
Market size
Innovation and sophistication factors
Business sophistication
innovation
Key for Efficiency-driven
economies
Key for Innovation-driven
7 posisi daya saing Indonesia di lingkup global, mengingat prospek pengembangan
ekspor karet alam Indonesia masih sangat besar.
1.2. Perumusan Masalah
Pertumbuhan produksi karet alam Indonesia mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari tumbuhnya produksi karet dari 1,63 juta ton
pada tahun 2002 menjadi 2,77 juta ton pada 2010 (Direktorat Jenderal
Perkebunan, 2010). Angka ini merupakan angka produksi terbesar ke dua dunia
setelah Thailand (Food and Agriculture Organization, 2010). Jumlah produksi
yang demikian besar kemudian dihadapkan pada kondisi penetrasi pasar di mana
Indonesia harus bersaing dengan negara-negara produsen lain, serta adanya
fluktuasi harga (Parhusip, 2008).
Harga karet alam pada perdagangan internasional cenderung fluktuatif
(International Rubber Concortium Limited, 2010). Hal ini merupakan salah satu
ciri yang berkelanjutan. Fluktuasi harga tersebut berdampak pada arus
perdagangan karet alam dan upaya pengembangan ekspor karet alam Indonesia
dalam rangka meningkatkan devisa negara yang memiliki konsekuensi pada
perubahan lingkungan ekonomi atau kebijakan perdagangan yang secara
signifikan mempengaruhi distribusi pendapatan.
Dalam era perdagangan bebas, pengembangan komoditas karet
menghadapi berbagai tantangan. Semakin terbukanya pasar mengakibatkan
persaingan (kompetisi) yang terjadi terhadap ekspor komoditas karet alam
menjadi semakin ketat. Kondisi pasar terbuka menyebabkan semakin minimnya
8 masuknya pesaing-pesaing baru dalam perdagangan. Sebagai gambaran,
pertumbuhan ekspor karet alam oleh negara Vietnam yang semakin baik
mempengaruhi jumlah penawaran karet alam global. Peningkatan jumlah
penawaran ini pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pembentukan harga
(International Trade Statistics, 2010).
Atas dasar tersebut analisis terhadap perkembangan ekspor karet alam
menjadi sangat penting sebagai informasi awal untuk menjelaskan kondisi daya
saing komoditas karet alam Indonesia di pasar ekspor. Untuk mengetahui posisi
daya saing karet alam Indonesia, perlu juga diketahui perkembangan komoditas
tersebut pada negara lain yang menjadi pesaing dalam pasaran internasional.
Informasi-informasi ini berguna untuk melihat seberapa besar penguasaan pasar
oleh eksportir karet alam di lingkup global yang pada akhirnya akan menentukan
kondisi pasar yang terbentuk dari pangsa pasar tersebut.
Kondisi struktur pasar yang terbentuk secara langsung memiliki pengaruh
terhadap daya saing produk. Tingkat daya saing suatu negara penting diketahui
untuk dapat menilai kinerja suatu komoditas dalam perkembangannya di dunia
perdagangan. Dengan mengetahui kondisi struktur pasar yang terbentuk pada
komoditas karet alam, maka kebijakan yang akan diterapkan terhadap komoditas
tersebut akan dapat dirumuskan secara tepat guna pengembangan daya saing
ekspor komoditas terkait di pasaran internasional. Berdasarkan hal tersebut,
masalah-masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana perkembangan ekspor komoditas karet alam Indonesia?
2. Bagaimana struktur pasar karet alam di pasar internasional?
9
1.3. Tujuan Penelitian
Perumusan masalah yang telah disebutkan di atas kemudian melahirkan
tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari
perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis perkembangan ekspor komoditas karet alam Indonesia.
2. Mengidentifikasi struktur pasar karet alam di pasar internasional.
3. Menganalisis daya saing karet alam Indonesia di pasar internasional.
1.4. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi:
1. Bahan informasi dasar dalam penyusunan dan penentuan arah kebijakan
perkaretan nasional.
2. Tambahan informasi mengenai posisi daya saing ekspor karet alam Indonesia
di pasar internasional.
3. Tambahan bagi khasanah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
1.5. Ruang Lingkup Penelitian
Lingkup penelitian dari studi mengenai “Analisis Daya Saing Ekspor
Karet Alam Indonesia di Pasar Internasional” ini adalah sebagai berikut:
1. Komoditas karet alam yang dimaksud dalam penelitian ini berdasarkan pada
komoditas karet alam dengan kode HS 4001, yaitu kelompok karet alam,
balata, getah perca, guayule, chicle dan getah alam semacam itu, dalam
bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip.
10 3. Analisis daya saing ekspor karet alam dilakukan pada tiga negara eksportir
utama karet alam, yaitu Indonesia, Thailand, dan Malaysia.
4. Identifikasi struktur karet alam di pasar internasional dilakukan dengan
metode Herfindahl Index (HI) dan Concentration Ratio (CR), sedangkan analisis daya saing dilakukan dengan metode Revealed Comparative
11
II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Peran Sektor Pertanian
Sektor pertanian merupakan salah satu penopang perekonomian suatu
negara, khususnya di negara agraris seperti Indonesia. Peranan sektor ini dapat
dikatakan cukup besar bagi perkembangan perekonomian negara yang
bersangkutan. Mengikuti analisis klasik dari Kuznets (1964) dalam Tambunan (2003), pertanian di LDCs dapat dilihat sebagai suatu sektor ekonomi yang sangat
potensial dalam empat bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi nasional, yaitu sebagai berikut:
1) Ekspansi dari sektor-sektor ekonomi lainnya sangat tergantung pada
pertumbuhan output di sektor pertanian, baik dari sisi permintaan sebagai sumber pemasokan makanan yang kontinu mengikuti pertumbuhan
penduduk, maupun dari sisi penawaran sebagai sumber bahan baku bagi
keperluan produksi di sektor-sektor lain seperti industri manufaktur (misalnya
industri makanan dan minuman) dan perdagangan. Kuznets menyebut ini
sebagai kontribusi produk.
2) Di negara-negara agraris seperti Indonesia, pertanian berperan sebagai
sumber penting bagi pertumbuhan permintaan domestik bagi produk-produk
dari sektor-sektor ekonomi lainnya. Kuznets menyebutnya kontribusi pasar.
3) Sebagai suatu sumber modal untuk investasi di sektor-sektor ekonomi
lainnya. Selain itu, menurut teori penawaran tenaga kerja (L) tak terbatas dari
Arthur Lewis dan telah terbukti dalam banyak kasus, bahwa dalam proses
12 industri dan sektor-sektor perkotaan lainnya. Kuznets menyebutnya
kontribusi faktor-faktor produksi.
4) Sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan (sumber devisa),
baik lewat ekspor hasil-hasil pertanian maupun dengan peningkatan produksi
pertanian dalam negeri menggantikan impor (substitusi impor). Kuznets
menyebutnya kontribusi devisa.
2.2. Perkebunan
Perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004
didefinisikan sebagai segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada
tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan
memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Pelaksanaan
perkebunan diselenggarakan antara lain dengan tujuan untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara, penyedia lapangan
kerja, pemenuhan kebutuhan konsumsi, serta pengoptimalan sumberdaya secara
berkelanjutan. Pada pasal 4 disebutkan bahwa usaha perkebunan memiliki fungsi
secara ekonomi, ekologi, dan sosial budaya.
Tanaman perkebunan merupakan pendukung utama sektor pertanian dalam
menghasilkan devisa. Ekspor komoditas pertanian kita yang utama adalah
hasil-hasil perkebunan. Hasil-hasil-hasil komoditas perkebunan yang selama ini telah
menjadi komoditas ekspor konvensional terdiri atas karet, kelapa sawit, teh, kopi
13 perkebunan yang diekspor, namun porsinya relatif kecil. Dalam beberapa tahun
terakhir ini, kakao telah berkembang menjadi salah satu komoditas penting di
dalam jajaran ekspor komoditas perkebunan. Meskipun demikian, penghasil
devisa utama dari subsektor perkebunan masih dipegang oleh komoditas karet dan
kopi.
Pengusahaan tanaman perkebunan di Indonesia berlangsung dualitis.
Sebagian besar diselenggarakan oleh rakyat secara orang perorangan, dengan
teknologi produksi dan manajemen usaha yang tradisional. Sebagian lagi
diusahakan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan, baik milik pemerintah
maupun swasta, dengan teknologi produksi yang modern serta manajemen usaha
yang profesional. Karena tanaman perkebunan didominasi oleh perkebunan
rakyat, maka kondisi perkebunan Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan
perkebunan negara lain.
Pembangunan perkebunan dilaksanakan melalui empat pola
pengembangan, yaitu (Dumairy, 1996):
1) Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR)
2) Pola Unit Pelayanan Pengembangan (UPP)
3) Pola Swadaya; dan
4) Pola Perusahaan Perkebunan Besar
Pola PIR dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan usaha antara
perkebunan rakyat sebagai plasma dan perkebunan besar sebagai inti, dalam suatu
sistem pengelolaan yang menangani seluruh rangkaian kegiatan agribisnis.
Pelaksanaannya dilakukan dengan memanfaatkan perkebunan besar untuk
14 pola pengembangan atas asas pendekatan terkonsentrasi pada lokasi tertentu, yang
menangani keseluruhan rangkaian proses agribisnis. Pelaksanaan pola ini
ditempuh melalui pengembangan perkebunan rakyat oleh suatu unit organisasi
proyek yang beroperasi di lokasi perkebunan yang sudah ada. Pola swadaya
ditujukan untuk mengembangkan swadaya masyarakat petani/pekebun yang sudah
ada di luar wilayah kerja PIR dan UPP. Sedangkan pola perkebunan besar
diarahkan untuk meningkatkan peranan pengusaha untuk mengembangkan
perusahaan perkebunan besar, baik berupa perusahaan negara (BUMN),
perusahaan swasta nasional maupun swasta asing.
Peningkatan produksi perkebunan diupayakan terutama melalui
peningkatan produktivitas lahan serta perbaikan efisiensi pengolahan. Sasaran
utamanya adalah peningkatan produksi perkebunan rakyat, mengingat
produktivitas per hektar dan mutu hasilnya masih rendah, padahal sebagian besar
hasil perkebunan berasal dari perkebunan rakyat. Untuk menunjang kenaikan
produksi perkebunan rakyat dimaksud, dibangun unit-unit pelayanan
pengembangan (UPP). Unit-unit ini memberikan pembinaan dalam hal teknik
agronomi, membantu pembiayaan, pemasaran, dan pengembangan fasilitas
pengolahannya. Sementara itu usaha ekstensifikasi perkebunan dilaksanakan
melalui pola PIR, dimana perusahaan inti bertugas membina plasma-plasmanya
(pekebun-pekebun rakyat) dalam hal teknik agronomi, pengolahan, dan
pemasaran hasil.
Sejalan dengan usaha-usaha tersebut, produksi beberapa tanaman
perkebunan utama meningkat secara cukup berarti. Kenaikan produksi terutama
15 perluasan, serta upaya rehabilitasi dan intensifikasi. Ekspor berbagai jenis
tanaman perkebunan juga berkembang, antara lain berkat dilaksanakannya Proyek
Rehabilitasi dan Peremajaan Tanaman Ekspor (PRPTE).
2.3. Konsep Keunggulan dan Daya Saing Ekspor
Daya saing ekspor memiliki pengertian kemampuan suatu komoditi untuk
memasuki pasar luar negeri dan kemampuan untuk bertahan dalam pasar itu. Daya
saing suatu komoditi dapat diukur atas dasar perbandingan pangsa pasar komoditi
tersebut pada kondisi pasar yang tetap. Dalam hal ini berarti suatu produk
dikatakan memiliki daya saing apabila produk tersebut mampu bertahan dalam
suatu pasar meskipun dengan mengalami guncangan (Amir, 2004).
Untuk dapat melakukan perdagangan antar negara, maka suatu komoditas
perlu memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Ricardo
menyatakan bahwa manfaat dari perdagangan akan tetap dapat diperoleh oleh
suatu negara meskipun negara tertentu tidak memiliki keunggulan apapun, selama
rasio harga antarnegara masih berbeda (Hady, 2004). Jika tidak ada perdagangan,
setiap negara akan memiliki keunggulan komparatif, yaitu kemampuan untuk
menemukan barang-barang yang dapat diproduksi pada tingkat biaya
ketidakunggulan relatif yang lebih rendah (dimulai dari awal dibukanya
perdagangan) daripada barang lainnya. Barang-barang inilah yang seharusnya
diekspor untuk ditukar dengan barang lainnya. Hukum keunggulan komparatif
Ricardo menyatakan bahwa setiap negara memiliki keunggulan komparatif dalam
sesuatu dan memperoleh manfaat dengan memperdagangkannya untuk ditukar
16 Menurut Porter (1998) dalam Abdmoulah dan Laabas (2010) keunggulan bersaing suatu negara sangat tergantung pada tingkat sumberdaya yang
dimilikinya. Keunggulan kompetitif dapat dilihat dari sumberdaya lokal yang
dimiliki suatu negara/wilayah. Keunggulan ini dapat dibuat dan dipertahankan
melalui suatu proses internal yang tinggi. Perbedaan dalam struktur ekonomi
nasional, nilai kebudayaan, kelembagaan dan sejarah turut serta dalam
menentukan keberhasilan kompetitif.
2.4. Ekspor sebagai Sumber Devisa
Setiap negara berbeda dengan negara lainnya, baik ditinjau dari sudut
sumber alam, iklim, letak geografis, penduduk, keahlian, tenaga kerja, tingkat
harga, serta keadaan struktur ekonomi dan sosialnya. Perbedaan itu menimbulkan
pula perbedaan barang yang dihasilkan, biaya yang diperlukan, serta mutu atau
kualitasnya. Hal inilah yang kemudian mendorong suatu negara untuk menjalin
hubungan dagang dengan negara lain guna memenuhi kebutuhan dalam negeri
yang belum ataupun tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri.
Kelebihan produksi dalam negeri akan mendorong terjadinya ekspor.
Pengertian ekspor menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor adalah
kegiatan mengeluarkan barang dan jasa dari daerah kepabeanan suatu negara.
Adapun daerah kepabeanan sendiri didefinisikan sebagai wilayah Republik
Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta
tempat-tempat tertentu di zona ekonomi ekslusif dan landas kontinen yang
17 (1997) dalam Novianti dan Hendratno (2008) menyatakan bahwa ekspor penting dalam dua hal utama yaitu: a) bersama-sama dengan impor dalam menghasilkan
neraca pembayaran (balance of payment) dari suatu negara; b) ekspor
menghasilkan devisa yang memberikan peningkatan pendapatan nasional dan
pendapatan riil. Secara matematis, ekspor dapat dituliskan sebagai fungsi berikut:
���= − � + −1
Dimana:
Xt = Jumlah ekspor komoditas tahun t
Qt = Jumlah produksi domestik tahun t
Ct = Jumlah konsumsi domestik tahun t
St-1 = Stok tahun sebelumnya (t-1)
Pembelian barang ataupun pembayaran jasa dari luar negeri yang
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mengharuskan setiap negara
berusaha untuk memiliki atau menguasai alat-alat pembayaran luar negeri. Alat
pembayaran luar negeri, atau juga disebut sebagai Foreign Exchange Currency
atau devisa dapat dianggap sebagai tagihan terhadap luar negeri yang dapat
dipergunakan untuk melunasi hutang yang terjadi dengan luar negeri. Sumber
devisa dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Umumnya sumber
devisa dari suatu negara adalah sebagai berikut (Amir, 1984):
1) Hasil-hasil dari ekspor barang maupun jasa;
2) Pinjaman yang diperoleh dari luar negeri, baik dari pemerintah suatu negara,
badan-badan keuangan internasional, ataupun dari swasta;
3) Hadiah atau Grant dari negara asing;
4) Keuntungan dari penanaman modal di luar negeri;
18
2.5. Karet Alam
Karet adalah polimer hidrokarbon yang terbentuk dari emulsi kesusuan
(dikenal sebagai latex), di getah pada beberapa jenis tumbuhan tetapi dapat juga
diproduksi secara sintetis. Sumber utama barang dagang dari latex yang
digunakan untuk menciptakan karet adalah pohon karet Para, Hevea brasiliensis
(Euphorbiaceae). Pengambilan getah dilakukan dengan cara melukai kulit pohon sehingga pohon akan memberikan respon yang menghasilkan lateks lebih banyak
(Departemen Perindustrian, 2007). Pohon tersebut menurut Undri (2004) pertama
kali ditemukan di lembah Amazone oleh tim ekspedisi dari Perancis. Kemudian
ekspedisi tersebut berhasil menemukan pohon karet yang dapat diambil getahnya
tanpa harus menebang pohonnya, cukup dengan melukai kulit batang tanaman
karet tersebut. Penemuan tersebut menyebabkan pengembangan penggunaan
lateks semakin pesat, apalagi setelah ditemukannya proses vulkanisasi oleh Good
Year tahun 1839, maka pengembangan perkebunan karet mulai berkembang secara komersil. Setelah percobaan berkali-kali oleh Henry Wickham, pohon
tersebut berhasil dikembangkan di Asia Tenggara, dimana sekarang ini tanaman
ini banyak dikembangkan. Menjelang tahun 1940, Indonesia dan Malaysia
akhirnya menjadi produsen utama karet dunia. Upaya pengembangan tanaman
karet secara perkebunan baru mulai pada akhir abad ke-19 (Undri, 2004). Lebih
dari setengah karet yang digunakan sekarang ini adalah sintetik, tetapi beberapa
juta ton karet alami masih diproduksi setiap tahun dan masih merupakan bahan
penting bagi beberapa industri termasuk otomotif dan militer (Suciati, 2006).
Saat ini, karet alam merupakan komoditi perkebunan yang sangat penting
19 Indonesia bahkan pernah menjadi produsen karet alam nomor satu di dunia.
Sebagian besar tanaman ini diusahakan oleh perkebunan rakyat.
Kedudukan Indonesia sebagai produsen utama karet alam dunia kini telah
digeser oleh Thailand, akibat areal luas yang dimiliki tidak diiringi dengan
produksi besar dan mutu yang baik. Namun demikian, karet masih merupakan
penghasil devisa utama di jajaran komoditas ekspor perkebunan. Produksi karet
alam Indonesia pada tahun 2007 sebesar 2,76 juta ton dimana 2,44 juta ton atau
88,4% dari produksi karet alam tersebut diekspor dengan nilai US$ 4,36 milyar,
hanya 13,3% atau 355.717 ton yang digunakan untuk kebutuhan industri dalam
negeri (Association of Natural Rubber Producing Countries, 2010). Pasar utama
ekspor karet alam tertuju ke Amerika Serikat (40%) dan Singapura (30%).
Selebihnya ke Jepang dan Eropa Barat, serta beberapa negara lain dalam porsi
kecil (International Trade Statistics, 2010). Jenis yang diekspor terdiri atas lateks,
karet sheets, karet crepe, dan karet SIR (Standard Indonesia Rubber). Jenis yang paling banyak diekspor adalah karet SIR. Selain getah karet yang berguna sebagai
bahan baku berbagai produk industri, kayu karet juga layak ekspor. Jepang,
Taiwan, dan beberapa negara Eropa mengimpor kayu karet dari Indonesia.
Karet dan barang karet dapat diklasifikasikan menurut The Harminized
Commodity Descreption and Coding System (HS) dan kelompok barang lapangan industri (KBLI). Pengelompokkan tersebut sebagaimana yang dapat diperlihatkan
20
Tabel 4. Kelompok Karet dan Barang-Barang Karet
No. No. HS KBLI Uraian Barang 1. 40011-13 Karet Alam
4002 Karet Sintetis
2. 4003-4009 25192 Barang dari karet untuk industri: - Benang karet
- Tabung, pipa, selang 3. 4010 25192 Belt conveyor
4. 4010 25192 Belt Transmission
5. 4011-13 25111-25112 Ban (Roda 4, Roda 2, Sepeda) 6. 4015 25199 Sarung tangan
7. 4016-17 25191 Lain-lain
Sumber: Departemen Perindustrian, 2009
2.5.1 Perbedaan Karet Alam dengan Karet Sintetis
Karet alam memiliki keunggulan-keunggulan jika dibandingkan dengan
karet sintetis. Keunggulan-keunggulan tersebut antara lain (Nazaruddin dan
Paimin, 2006):
Memiliki daya elastik atau daya lenting yang sempurna;
Memiliki plastisitas yang baik sehingga pengolahannya mudah;
Mempunyai daya aus yang tinggi;
Tidak mudah panas (low heat build up); dan
Memiliki daya tahan yang tinggi terhadap keretakan (groove cracking
resistance).
Meski demikian, karet sintetis juga memiliki kelebihan seperti tahan
terhadap berbagai zat kimia, dan harganya yang cenderung dapat dipertahankan
sehingga tetap stabil. Hal ini berbeda dengan karet alam yang mana harganya
selalu mengalami fluktuasi, yang terkadang bahkan bergejolak (International
Rubber Concortium Limited, 2010). Suatu kebijakan politik entah dari pihak
pengusaha maupun pemerintah memiliki pengaruh yang besar terhadap usaha
21
2.5.1. Jenis-Jenis Karet Alam
Jenis karet alam yang dikenal luas adalah (Nazaruddin dan Paimin, 2006) :
Bahan olah karet (lateks kebun, sheet angin, slab tipis, dan lumb segar),
Karet konvensional (ribbed smoked sheet, white crepes, dan pale crepe, estate
brown crepe, compo crepe, thin brown crepe remills, thick blanked crepe ambers, flat bark crepe, pure smoke blanket crepe, dan off crepe),
Lateks pekat,
Karet bongkah atau block rubber,
Karet spesifikasi teknis atau crumb rubber,
Karet siap olah atau tyre rubber, dan
Karet reklim atau reclaimed rubber.
1) Bahan Olah Karet
Bahan olah karet adalah lateks kebun serta gumpalan lateks kebun yang
diperoleh dari pohon karet Havea brasiliensis. Beberapa kalangan menyebutkan
bahwa bahan olah karet bukan produksi perkebunan besar, melainkan merupakan
bokar (bahan olah karet rakyat) karena biasanya diperoleh dari petani yang
mengusahakan kebun karet. Menurut pengolahannya bahan olah karet dibagi
menjadi 4 macam: lateks kebun, sheet angin, slap tipis, dan lump segar.
a. Lateks kebun adalah cairan getah yang didapat dari bidang sadap pohon
karet. Cairan getah ini belum mengalami penggumpalan.
b. Sheet angin adalah bahan olah karet yang dibuat dari lateks yang sudah
disaring dan digumpalkan dengan asam semut, berupa karet sheet yang
22 c. Slap tipis adalah bahan olah karet yang terbuat dari lateks yang sudah
digumpalkan dengan asam semut.
d. Lump segar adalah bahan olah karet yang bukan berasal dari gumpalan
lateks kebun yang terjadi secara alamiah dalam mangkuk penampung.
2) Karet Alam Konvensional
Terdapat beberapa macam karet olahan yang tergolong karet alam
konvensional. Jenis itu pada dasarnya hanya terdiri dari golongan karet sheet dan
crepe. Jenis karet alam olahan yang tergolong konvensional adalah sebagai
berikut.
a. Ribbed smoked sheet atau RSS adalah jenis karet berupa lembaran sheet
yang mendapat proses pengasapan dengan baik. RSS terdiri dari
beberapa kelas, yaitu X RSS, RSS 1, RSS 2, RSS 3, RSS 4, dan RSS 5.
b. White crepe dan pale crepe merupakan crep yang berwarna putih atau muda. White crepe dan pale crepe juga ada yang tebal dan tipis.
c. Estate brown crepe merupakan crepe yang berwarna coklat. Disebut
estate brown crepe karena banyak dihasilkan oleh perkebunan-perkebunan besar atau estate. Jenis ini dibuat dari bahan yang kurang
baik seperti yang digunakan untuk pembuatan off crepe serta dari sisa lateks, lump atau koagulum yang berasal dari prakoagulasi, dan scrap
atau lateks kebun yang sudah kering di atas bidang penyadapan. Brown
crepe yang tebal disebut thick brown crepe dan yang tipis disebut thin
brown crepe.
23 e. Thin brown crepe remills merupakan crepe cokelat yang tipis karena jenis ini merupakan jenis karet yang digiling ulang. Bahan yang
digunakan sama dengan jenis brown crepe yang lain, hanya saja dalam
prosesnya jenis ini mengalami penggilingan ulang untuk memperoleh
ketebalan seperti yang telah ditetapkan.
f. Thick blanket crepes ambers merupakan jenis crepe blanket yang berwarna cokelat dan tebal, dan biasanya terbuat dari slab basah, sheet
tanpa proses pengasapan, dan lumb serta scrap dari perkebunan atau
kebun rakyat yang baik mutunya.
g. Flat bark crepe merupakan jenis karet tanah atau earth rubber, yaitu
jenis crepe yang dihasilkan dari scrap karet alam yang belum diolah,
termasuk scrap tanah yang berwarna hitam.
h. Pure smoked blanket crepe merupakan crepe yang diperoleh dari penggilingan karet asap yang khusus berasal dari RSS, termasuk
didalamnya block sheet atau sheet bongkah atau sisa dari potongan RSS.
i. Off crepe yang tidak tergolong dalam bentuk baku atau standar. Biasanya dibuat dari contoh sisa penentuan kadar karet kering, lembaran RSS yang
tidak bagus penggilingannya sebelum diasapi, busa-busa dari lateks,
bekas air cucian yang banyak mengandung lateks, serta bahan-bahan lain
yang tidak bagus, bukan dari proses pembekuan langsung dari bahan
24 3) Lateks Pekat
Lateks pekat adalah jenis karet yang berbentuk cairan pekat. Lateks pekat
yang diperdagangkan di pasar ada yang dibuat melalui proses pendadihan
(creamed lateks) dan melalui proses pemusingan (centrifuged lateks). Jenis ini biasanya banyak digunakan untuk pembuatan bahan-bahan karet yang tipis dan
bermutu tinggi.
4) Karet Bongkah atau Block Rubber
Karet bongkah adalah jenis karet remah yang telah dikeringkan dan
dikilang menjadi bandela-bandela dengan ukuran yang telah ditetapkan. Karet
bongkah ada yang berwarna muda dan setiap kelasnya mempunyai kode warna
tersendiri. Standar mutu jenis ini tercantum dalam SIR (Standard Indonesian
Rubber) sebagaimana disajikan pada Tabel 5 berikut..
Tabel 5. Standard Indonesian Rubber (SIR)
SIR 5L SIR 5 SIR 10 SIR 20 SIR 50
Kadar kotoran maksimum 0,05% 0,05% 0,10% 0,20% 0,50%
Kadar abu maksimum 0,50% 0,50% 1,75% 1,00% 1,50%
Kadar zat asiri maksimum 1.0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
PRI minimum 60 60 50 40 30
Plastisitas-Po minimum 30 30 30 30 30
Limit warna (skala livibond)
maksimum 6 - - - -
Kode warna Hijau Hijau - Merah Kuning
Sumber: Thio Goan Loo, 1980 dalam Nazaruddin dan Paimin, 2006 5) Karet Spesifikasi Teknis atau Crumb Rubber
Karet spesifikasi teknis adalah karet alam yang dibuat khusus sehingga
terjamin mutu teknisnya. Penetapan mutunya juga didasarkan pada sifat-sifat
teknisnya. Warna atau penilaian visual yang menjadi dasar penentuan golongan
mutu pada jenis karet sheet, crepe, maupun lateks pekat tidak berlaku untuk jenis
25 6) Tyre Rubber
Tyre rubber adalah bentuk lain dari dari karet alam yang dihasilkan sebagai barang setengah jadi sehingga bisa langsung digunakan oleh konsumen,
baik untuk pembuatan ban atau barang lain yang menggunakan bahan baku karet
alam. Tyre rubber sudah dibuat di Malaysia sejak tahun 1972. Pembuatannya
dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing karet alam terhadap karet sintetis.
Jika dibandingkan dengan karet konvensional, tyre rubber adalah bahan pembuat yang lebih baik untuk ban atau produk karet lain. Kelebihan yang dimiliki karet
jenis ini adalah memiliki daya campur yang baik sehingga mudah digabung
dengan karet sintesis.
7) Karet Reklim atau Reclaimed Rubber
Karet reklim merupakan jenis karet yang diolah kembali dari
barang-barang karet bekas, terutama ban-ban mobil bekas. Karena itu dapat dikatakan
bahwa karet reklim adalah suatu hasil pengolahan scrap yang sudah divulkanisir.
2.5.2. Manfaat Karet
Karet banyak digunakan dalam kehidupan. Penggunaan bahan baku karet
telah dikembangkan dengan basis industri. Umumnya alat-alat yang dibuat dari
bahan karet sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari maupun dalam industri
seperti penggunaannya pada mesin-mesin penggerak.
Barang yang dapat dibuat dari karet alam antara lain adalah ban kendaraan
(mulai dari sepeda, motor, traktor, hingga pesawat terbang), sepatu karet, sabuk
penggerak mesin besar dan mesin kecil, pipa karet, kabel, isolator, serta
26 membuat perlengkapan seperti sekat. Pembuatan jembatan pun menggunakan
karet sebagai penahan getarannya.
Manfaat karet sangat beragam. Pemanfaatannya melingkupi hampir
seluruh dari kegiatan kehidupan manusia. Peralatan rumah tangga kebanyakan
terbuat dari bahan dasar karet. Begitupun dengan peralatan kantor, seperti kursi,
lem perekat barang, selang air, kasur busa, serta peralatan tulis menulis seperti
karet penghapus. Tambang-tambang besar yang mengolah bijih besi dan batubara
menggunakan belt yang sangat panjang dan terbuat dari karet untuk
pengangkutannya. Bangunan-bangunan besar semakin banyak yang menggunakan
bahan karet. Tak hanya itu, bahkan peralatan dan kendaraan perang juga banyak
bagiannya yang terbuat dari bahan dasar karet.
Selain karet alam, karet sintetis juga banyak digunakan dalam pembuatan
berbagai jenis barang. Hal ini dikarenakan karet sintetis memiliki beberapa
kelebihan yang tidak dimiliki oleh karet alam. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa
manfaat karet bagi kehidupan manusia jauh lebih banyak lagi dibanding dengan
yang telah disebutkan. Karet memiliki pengaruh besar terhadap bidang
transportasi, komunikasi, industri, pendidikan, kesehatan, hiburan, dan banyak
bidang kehidupan lain yang vital bagi kehidupan manusia. Manfaat secara tidak
langsung pun banyak yang dapat diperoleh dari barang yang dibuat dari karet.
Hingga saat ini, pengembangan usaha perkebunan karet tidak hanya fokus
pada prospek pengembangan dan produksi lateks saja, tetapi lebih terhadap nilai
lain yang lebih tinggi dan mulia. Perkembangan karet sintetis dewasa ini
mengakibatkan perlunya melihat manfaat lain dari karet alam. Berbeda dengan
27 karet alam justru menghasilkan oksigen. Menurut data yang diperoleh dari IRSG,
dalam sehari produksi O2 pada perkebunan karet mencapai 1000 ton (Bastari,
1998). Selain itu, biji karet juga dapat menghasilkan minyak yang berguna bagi
industri, disamping kayu karet yang juga memiliki prospek cerah kedepannya.
2.6. Bentuk Kerjasama Antar Negara Produsen Karet Alam
Perdagangan multilateral yang mana saat ini mengarah ke dalam
perdagangan yang lebih terbuka menawarkan peluang sekaligus tantangan bagi
tiap negara untuk meningkatkan daya saing bagi produk yang dimilikinya maupun
membentuk berbagai jenis kerjasama multilateral antar negara. Kepentingan
Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar dari karet alam memberikan
landasan yang cukup besar untuk berpartisipasi aktif menjadi salah satu anggota
kerjasama dunia yang mengelola permasalahan tersebut. Berbagai organisasi
multilateral telah terbentuk sejak lama yang mana hal ini mendorong para
produsen untuk juga membentuk organisasi yang menangani masalah karet alam
dunia.
Organisasi multilateral karet alam yang pertama kali didirikan pada tahun
1980 dengan nama International Natural Rubber Organization (INRO), yang tujuan utamanya adalah untuk menstabilkan harga karet alam. Anggota dari INRO
terdiri dari negara-negara produsen karet alam (eksportir) yaitu Malaysia,
Indonesia, Thailand, Sri Lanka, dan Nigeria, serta negara konsumen (importir)
yaitu China, Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. INRO kemudian
dibubarkan secara resmi pada tanggal 13 Oktober 1999. Sejak itu, tidak ada lagi
28 pada saat itu, INRO tidak dapat mengatasi kemerosotan harga. Association of
Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) yang berdiri sejak tahun 1970 dan terdiri dari negara-negara produsen karet alam, yang diharapkan dapat berfungsi
sebagai pengganti sebagian dari fungsi INRO tidak dapat berjalan sebagaimana
yang diharapkan.
Bubarnya INRO membawa dampak psikologi terhadap pasar. Hal ini dapat
dilihat dari semakin merosotnya harga karet alam di pasar internasional.
Berdasarkan pada latar belakang pemerosotan harga karet alam sejak terjadinya
krisis moneter tahun 1997 dan dibubarkannya INRO, maka tiga negara produsen
utama karet alam yaitu Thailand, Indonesia, dan Malaysia sepakat mengadakan
kerjasama di bidang perdagangan karet alam. Dalam upaya mengatasi merosotnya
harga karet alam, pemerintah Thailand, Indonesia, dan Malaysia sepakat
mendirikan perusahaan patungan karet alam yang bernama “International Rubber
Consortium Limited (IRCo)”. Kesepakatan pendirian perusahaan patungan IRCo
ini telah tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yng
ditandatangani oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI, Menteri
Agriculture and Cooperatives Thailand, dan Menteri Primary Industries Malaysia
pada tanggal 8 Agustus 2002 di Bali. IRCo berfungsi sebagai pelengkap dari
skema penstabil harga yang lain, yaitu Supply Managemant Scheme (SMS) dan
Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) sebagaimana yang telah disepakati dalam “Joint Ministerial Declaration (Bali Declaration) 2001”, yaitu
melaksanakan kegiatan strategic marketing yang meliputi pembelian dan
29
2.7. Penelitian Terdahulu
Penelitian terkait komoditas karet alam telah banyak dilakukan. Soekarno
(2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Keunggulan Komparatif
Karet Alam Indonesia Tahun 2003-2007” menyatakan bahwa pertumbuhan daya
saing karet alam Indonesia di pasar dunia semakin mengalami peningkatan. Hal
ini dapat dilihat dari nilai Revealed Comparative Advantage (RCA) yang mengalami peningkatan dari 28,403 pada tahun 2003 menjadi 37,388 pada tahun
2007. Peningkatan nilai RCA ini tidak terlepas dari semakin besarnya nilai ekspor
karet alam Indonesia di pasar dunia. Selain itu, Soekarno juga menyatakan bahwa
hal tersebut terkait dengan semakin gencarnya program revitalisasi perkebunan
karet di Indonesia yang membawa harapan pemerintah untuk menjadikan
Indonesia sebagai penghasil karet alam terbesar di dunia pada tahun 2010.
Karet sintetik yang merupakan produk komplementer maupun substitusi
dari karet alam semestinya memiliki peranan dalam pembentukan harga karet
alam. Atas dasar pemikiran ini, maka dalam analisis yang menggunakan metode
impulse response function dan variance decompotition, Zebua (2008) memakai harga karet sintetis dan nilai tukar Rupiah dalam menelusuri respon variabel
dependent terhadap guncangan variabel independent sebesar satu standar deviasi.
Hasil yang didapat menyatakan bahwa pengaruh dari guncangan harga karet
sintetik terhadap harga karet RSS dan TSR20 pada jangka pendek memberikan
dampak yang positif terhadap harga ekspor karet RSS di Indonesia, sedangkan
dampak nilai tukar Rupiah adalah negatif. Hal ini mencerminkan bahwa
keragaman harga ekspor karet alam Indonesia, khususnya RSS dan TSR20
30 sintetik dan nilai tukar Rupiah hanya memberikan kontribusi yang berkisar 0-12%
saja.
Penelitian yang dilakukan oleh Sunandar (2007) mengenai analisis daya
saing dan dampak kebijakan pemerintah terhadap pengusahaan komoditi tanaman
karet alam di Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan dengan
menggunakan metode analisis PAM (Policy Analysis Matrix) memperoleh hasil bahwa usahatani yang dijalankan oleh petani karet alam Kecamatan Cambai
mempunyai daya saing. Ini terlihat dengan indikator keunggulan kompetitif dan
keunggulan komparatif (PCR dan DCR) yang lebih kecil dari satu (<1), serta
keuntungan sosial dan juga keuntungan privat (finansial) yang positif. Hasil yang
diperoleh untuk nilai PCR (Private Cost Ratio) sebesar 0,43% dan keuntungan finansial sebesar Rp 6.903,94/kg. sedangkan nilai DRC (Domestic Resource Cost
Ratio) sebesar 0,77% dan keuntungan sosial sejumlah Rp 2.791,39/kg. Hasil dari nilai PCR yang lebih kecil dari DCR merupakan indikator yang memiliki arti
bahwa komoditi usahatani karet alam (bokar) terhadap kebijakan pemerintah yang
meningkatkan efisiensi dalam berproduksi. Dampak kebijakan yang diberlakukan
pemerintah terhadap output menyebabkan nilai transfer output bernilai negatif
(Rp 2.094,94/kg bokar) sehingga harga output di pasar domestik Kecamatan
Cambai lebih rendah dibandingkan harga di pasar internasional. Analisis
sensitivitas yang digunakan yaitu dengan menurunkan harga output sebesar 6%,
kenaikan input (pupuk) sebesar 6%, dan analisis gabungan dengan faktor lain
tidak berpengaruh, menunjukkan hasil bahwa perhitungan dengan menggunakan
Matriks Analisis Kebijakan pada komoditi tanaman karet alam menunjukkan
31 tersebut dilihat dari nilai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang
menunjukkan nilai lebih kecil dari satu, sedangkan dampak kebijakan pemerintah
terhadap input-output yang dilihat dengan nilai EPC yang terjadi mengalami
perubahan menjadi 1 (EPC=1).
Prabowo (2006) menggunakan model ekonometrika dinamis untuk
menganalisis tren perdagangan karet alam antara Indonesia dengan negara-negara
importir utama karet alam yaitu Amerika Serikat dan Jepang. Penelitian tersebut
menghasilkan suatu kesimpulan bahwa pada kurun waktu 1995-2003 produksi
karet alam Indonesia cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 1.467 juta ton
menjadi 1.798 juta ton atau meningkat sebesar 22,56%. Namun peningkatan
tersebut kurang berarti jika dibandingkan dengan Thailand dan India yang dapat
meningkatkan produksinya hingga dua kali lipat lebih besar dari Indonesia. Hal
yang sama terjadi pada ekspor karet alam. Ekspor karet alam Indonesia meningkat
dari 1.324 juta ton pada tahun 1995 menjadi 1.453 juta ton di tahun 2001.
Meskipun demikian, nilai tersebut kontras dengan persentase ekspor terhadap
ekspor dunia, dimana pangsa ekspor karet alam justru mengalami penurunan dari
31,2% terhadap ekspor dunia pada tahun 1995 menjadi 28,2% pada tahun 2001.
Sebaliknya, Thailand mengalami peningkatan pangsa pasar dari 38,5% pada tahun
1995 menjadi 39,6% pada tahun 2001. Hasil analisis yang dilakukan
menunjukkan bahwa ekspor dan produksi karet alam dunia masih didominasi oleh
Thailand, Indonesia, dan Malaysia, serta Vietnam yang mulai diperhitungkan
dalam jajaran eksportir utama karena terus mengalami peningkatan produksi dan
ekspor. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa faktor dominan yang
32 domestik brutonya dengan respon yang elastik. Hal tersebut berbeda dengan
Jepang yang permintaannya terhadap karet alam tidak responsif terhadap
perubahan pendapatan domestik bruto maupun perubahan harga impor karet alam.
Namun, secara umum distorsi pasar akibat kebijakan perdagangan dan perubahan
33
III. KERANGKA PEMIKIRAN
Ekonomi Internasional pada umumnya diartikan sebagai bagian dari ilmu
ekonomi yang mempelajari dan menganalisis transaksi dan permasalahan
ekonomi internasional (ekspor dan impor) yang meliputi perdagangan dan
keuangan/moneter serta organisasi (swasta/pemerintah) dan kerjasama ekonomi
antar negara (internasional). Permasalahan pokok yang dihadapi dalam ekonomi
internasional juga tidak berbeda dengan yang dihadapi oleh ekonomi pada
umumnya, yaitu masalah kelangkaan (scarcity) produk dan masalah pilihan
(choice) produk. Masalah tersebut muncul karena adanya permintaan atau demand
serta adanya penawaran atau supply yang berasal dari dalam maupun luar negeri
(Hady, 2004).
Oktaviani dan Novianti (2009) mendefinisikan perdagangan internasional
sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan
penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud
dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antar individu dengan
pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara
lain. Perdagangan internasional yang tercermin dari kegiatan ekspor dan impor
suatu negara menjadi salah satu komponen dalam pembentukan PDB (Produk
Domestik Bruto) dari sisi pengeluaran suatu negara. Peningkatan ekspor bersih
suatu negara menjadi faktor utama dalam peningkatan PDB negara tersebut.
Konsep perdagangan internasional pada hakikatnya telah terjadi selama
ribuan tahun (seperti Jalur Sutra dan Amber Road). Meskipun demikian,
dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan
34 industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan
multinasional (Oktaviani dan Novianti, 2009).
Dalam perdagangan domestik, para pelaku ekonomi bertujuan untuk
memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonomi yang dilakukannya. Demikian
juga halnya dengan perdagangan internasional. Suatu negara terlibat dalam
perdagangan internasional, menurut Krugman da Obstfeld (2000) dalam Prabowo
(2006) didasarkan pada dua alasan, yang mana setiap alasan tersebut memberikan
kontribusi dalam mendatangkan manfaat bagi negara yang melakukan
perdagangan. Pertama, suatu negara terlibat dalam perdagangan karena setiap
negara berbeda dengan negara lainnya. Sebagaimana layaknya individu, suatu
negara dapat memperoleh manfaat dari perbedaan dengan melakukan kesepakatan
untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dihasilkan dengan baik, dengan kata lain
melakukan spesialisasi. Kedua, suatu negara melakukan perdagangan untuk
mencapai skala ekonomi dalam produksi. Jika setiap negara hanya menghasilkan
beberapa jenis produk tertentu, maka setiap negara dapat menghasilkan produk
dalam skala yang lebih besar dan lebih efisien dari pada jika mencoba untuk
menghasilkan semua produk.
Saat ini kajian mengenai perdagangan internasional semakin penting
karena pengaruh globalisasi ekonomi dunia yang dicirikan oleh hal-hal sebagai
berikut (Hady, 2004):
1) Keterbukaan ekonomi terutama dengan adanya liberalisasi pasar dan arus