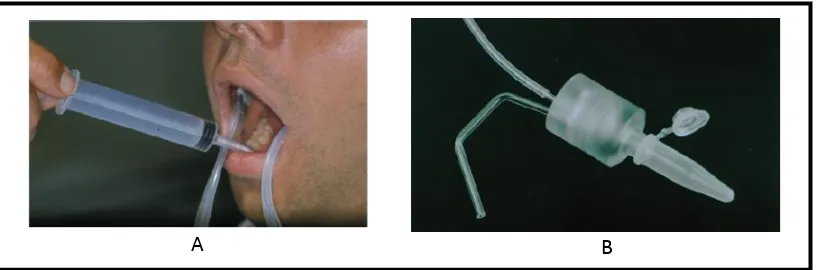BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penyakit Paru Obstruktif Kronik
Penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) merupakan penyakit paru kronik
progresif yang tidak menular, ditandai dengan adanya hambatan aliran udara di
saluran napas yang bersifat reversibel parsial. Penyakit PPOK berhubungan dengan
respon inflamasi abnormal paru terhadap partikel berbahaya atau gas racun.11
Kebiasaan merokok merupakan faktor risiko utama penyakit PPOK. Selain itu,
terdapat faktor-faktor risiko lainnya seperti riwayat terpajan polusi udara di
lingkungan dan tempat kerja, hiperaktivitas bronkus, riwayat infeksi saluran napas
bawah berulang dan defisiensi antitripsin alfa-1 yang sangat jarang terjadi di
Indonesia.6,11
Diagnosis PPOK ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik,
pemeriksaan penunjang seperti foto toraks dan uji faal paru.8,12 Gejala awal PPOK
berupa batuk produktif yang sebagian besar terjadi diantara perokok berusia 40-50
tahun, sementara dyspnea (sesak napas) merupakan gejala lanjutan pada usia 50-60
tahun.12 Penyakit paru obstruktif kronik terdiri dari bronkitis kronik dan emfisema
atau sering merupakan gabungan keduanya.7,8,12
Bronkitis kronik adalah kelainan saluran napas dimana penderita mengalami
batuk kronis dan produksi sputum berlebihan yang terjadi minimal selama tiga bulan
dalam dua tahun berturut-turut, disertai rasa kelelahan dan rasa tidak nyaman pada
penderita.8,12,20 Gejala-gejala pada bronkitis kronik seperti batuk kronik dan
produktif, obstruksi jalan napas dan gangguan pertukaran gas merupakan akibat
perubahan patologi struktur paru. Perubahan struktur paru yang disebabkan oleh
proses inflamasi kronik tersebut berupa peningkatan ukuran epitel-epitel kelenjar,
hipertrofi otot polos dan jaringan penunjang pada dinding jalan napas, serta
degenerasi tulang rawan jalan napas. Perubahan bronkiolus dan gangguan pertukaran
tidak sesuai (mismatched), dimana sebagian tempat (alveoli) terdapat aliran darah
yang adekuat, tetapi sangat sedikit aliran udara dan sebaliknya pada sebagian tempat
lain. Selain itu, juga terjadi penurunan kerja otot-otot respirasi dan penyempitan jalan
napas yang menimbulkan hipoventilasi dan tidak cukupnya udara ke alveoli, hingga
akhirnya menyebabkan peningkatan karbondioksida dalam darah dan kekurangan
oksigen. Sementara itu, mediator-mediator inflamasi yang didominasi oleh sel T
limfosit (CD8+), makrofag dan neutrofil mengakibatkan hipertrofi kelenjar-kelenjar
yang memproduksi mukus dan peningkatan jumlah sel goblet, sehingga terjadi
hipersekresi mukus.20
Emfisema adalah suatu kelainan anatomis paru ditandai oleh pelebaran rongga
udara distal bronkiolus terminal dan kerusakan dinding alveoli.8 Pada emfisema
terjadi penurunan elastisitas alveoli dan berkurangnya permukaan pertukaran gas
sehingga pernapasan menjadi susah. Merokok adalah penyebab utama selain polusi
dan faktor herediter.21,22 Gejala awal emfisema berupa sesak napas dan batuk yang
disertai penurunan aktivitas menjadi sangat terbatas, hingga akhirnya terjadi
kerusakan alveoli yang permanen dan hilangnya kemampuan pertukaran gas oleh
seluruh bagian paru. Emfisema tidak dapat disembuhkan, tetapi perubahan sikap
dengan berhenti merokok dan perawatan dapat menurunkan degenerasi paru dan
mengatasi simtom. 21
2.2 Obat Bronkodilator
Obat bronkodilator merupakan obat utama perawatan PPOK.13 Bronkodilator
menyebabkan relaksasi otot-otot saluran pernapasan sehingga saluran bertambah
lebar dan pernapasan menjadi lebih mudah.23 Bronkodilator diberikan dalam
perawatan reguler untuk mendapat efek bronkodilatasi dan juga digunakan untuk
meredakan gejala eksaserbasi PPOK.7,12 Jenis obat bronkodilator yang digunakan
dalam merawat PPOK yaitu obat golongan agonis beta 2 dan antikolinergik.13 Obat
bronkodilator dapat diberikan secara tunggal ataupun dikombinasi, sesuai dengan
klasifikasi derajat berat penyakit.8 Pemilihan bentuk obat diutamakan bentuk inhalasi
2.2.1 Agonis beta 2
Obat golongan agonis beta 2 merupakan obat yang umumnya digunakan
dalam perawatan penyakit asma dan PPOK.24 Efek farmakologi utama agonis beta 2
adalah sebagai bronkodilator yaitu untuk merelaksasi otot polos pernapasan melalui
stimulasi reseptor adrenergik beta 2 yang banyak terdapat pada otot polos saluran
napas.15,24 Stimulasi reseptor adrenergik beta 2 pada tingkat sel akan meningkatkan
siklik adenosin monofosfat intraselular (cAMP) yang berperan dalam mengatur tonus
otot polos pernapasan, sehingga terjadi bronkodilatasi. Selain itu, agonis beta 2 yang
juga menstimulasi reseptor adrenergik beta 2 pada presinaptik ganglia parasimpatis
saluran napas, menghambat pelepasan asetilkolin yang merupakan bronkokonstriktor
sehingga menyebabkan bronkodilatasi.15,24,25
Berdasarkan lama kerjanya, agonis beta 2 dibedakan menjadi agonis beta
berefek singkat/SABAs (Short Acting Beta Agonists) dan agonis beta berefek
panjang/LABAs (Long Acting Beta Agonists). SABAs digunakan sebagai obat pereda
simtom akut (reliever) karena memiliki onset kerja yang cepat (1-5 menit) walaupun
tidak bertahan lama (4-6 jam).13,15,23 LABAs mempunyai efek bronkodilator yang
bertahan sekitar 12 jam hingga 24 jam sehingga lebih efektif penggunaanya dalam
pengobatan reguler penyakit PPOK.23
Agonis beta 2 dapat menimbulkan efek samping tremor, takikardia, gagal
jantung kronik dan efek samping di rongga mulut berupa xerostomia.26,27
Tabel 1. Macam-macam obat agonis beta 215,18
Agonis Beta 2 Macam Obat
SABAs Salbutamol (albuterol), terbutaline, pirbuterol
LABAs Salmeterol, formoterol, vilanterol, indacaterol
2.2.2 Antikolinergik
Pada PPOK, antikolinergik digunakan untuk mengurangi tonus otot yang
menyebabkan hambatan aliran udara dan untuk menekan sekresi mukus.28 Sistem
normal, rangsangan asetilkolin pada saraf parasimpatis reseptor muskarinik paru akan
menyebabkan bronkokonstriksi, yaitu pada reseptor muskarinik M1 dan M3,
sementara pada reseptor muskarinik M2 memiliki efek feedback untuk membatasi
pelepasan asetilkolin. Selain itu, rangsangan asetilkolin pada reseptor muskarinik M3
di kelenjar submukosa saluran napas akan menyebabkan peningkatan sekresi
mukus.13,28 Antikolinergik atau antimuskarinik bronkodilator merupakan antagonis
reseptor muskarinik kolinergik non selektif yang bekerja dengan menghambat
asetilkolin padasaraf parasimpatis sehingga menimbulkan bronkodilatasi.28
Bronkodilator antikolinergik terdiri dari antikolinergik berefek singkat/SAMA
(Short acting muscarinic antagonist) seperti ipratropium bromida dan antikolinergik
berefek panjang/LAMA (Long acting muscarinic antagonist) yaitu tiotropium
bromida. SAMA bersifat non selektif dan menghambat ketiga reseptor muskarinik,
menyebabkan bronkodilatasi dan sedikit supresi mukus, sedangkan LAMA bersifat
lebih selektif terhadap reseptor M3.29 Seperti fungsi SABA, SAMA juga digunakan
untuk mengatasi simtom akut bronkospasme, sementara LAMA digunakan dalam
pengobatan reguler.15 Akan tetapi, jika dibandingkan dengan agonis beta 2,
antikolinergik memiliki onset kerja yang lebih lama sehingga kurang efektif
digunakan sebagai obat pereda simtom (reliever).23,28 Ipratropium bromida (SAMA)
bekerja dalam 15 menit dan bertahan selama 6-8 jam, sementara tiotropium (LAMA)
membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bekerja (20 menit), walaupun dapat
bertahan selama 24 jam.23
Bronkodilator antikolinergik memiliki lebih sedikit efek samping dibanding
agonis beta 2. Xerostomia dan retensi urin merupakan efek samping yang paling
sering dijumpai.23 Tiotropium menyebabkan xerostomia pada 6-13% pasien.27
2.3 Xerostomia
2.3.1 Definisi
Xerostomia berasal dari kata xeros (kering) dan stoma (mulut) yang artinya
mulut kering. Xerostomia bukan merupakan penyakit, melainkan merupakan sensasi
hiposalivasi.3 Dasar terjadinya xerostomia adalah perubahan kuantitatif atau kualitatif
fungsi kelenjar saliva.30 Perubahan komposisi dan kualitas saliva dapat menyebabkan
xerostomia, walaupun tanpa terjadi penurunan aliran saliva.3,31
Xerostomia sering ditemukan pada usia lanjut dan prevalensinya tinggi pada
wanita postmenopause. Prevalensi xerostomia juga meningkat seiring pertambahan
umur, dengan estimasi sekitar 30% populasi yang berumur 65 tahun ke atas menderita
xerostomia. Akan tetapi, dalam keadaan sehat/tanpa masalah medis dan tanpa
mengkonsumsi obat-obatan, aliran saliva dan komposisi saliva bersifat stabil dan
tidak berhubungan dengan peningkatan umur.3
2.3.2 Etiologi
Xerostomia dapat disebabkan oleh banyak faktor diantaranya akibat merokok,
penggunaan obat-obatan, proses penuaan, penyakit sistemik, penyakit kelenjar saliva,
efek radioterapi kepala leher dan akibat bernapas dari mulut.1-3,30,32 Selain
faktor-faktor tersebut, xerostomia juga dapat terjadi akibat perubahan inervasi saraf autonom
pada kelenjar saliva. Perubahan inervasi saraf yang didominasi rangsangan simpatis,
seperti pada episode stres dan cemas akut mengakibatkan perubahan komposisi saliva
yang menyebabkan sensasi mulut kering/xerostomia. Kondisi psikologis seperti
depresi dan insomnia juga dapat menyebabkan xerostomia.3 Beberapa penyebab
xerostomia dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Obat-obatan
Obat-obatan sering menyebabkan efek samping di rongga mulut berupa
xerostomia. Lebih dari 500 jenis obat menyebabkan xerostomia dan dari obat yang
sering diresepkan, 80% menyebabkan efek samping xerostomia. Obat-obatan yang
menyebabkan xerostomia diantaranya obat golongan antikolinergik, antidepresan,
antihistamin, obat diuretik, obat antihipertensi, bronkodilator dan opioid.3,27
Efek samping obat-obatan terhadap terjadinya xerostomia juga dipengaruhi
oleh kombinasi obat, dosis obat dan lama penggunaan obat. Semakin banyak
seseorang mengkonsumsi obat-obatan (polifarmasi) atau semakin tinggi dosis obat
2. Penyakit kelenjar saliva
Beberapa penyakit kelenjar saliva dapat menyebabkan hiposalivasi dan
xerostomia. Penyakit kelenjar saliva yang menyebabkan hiposalivasi/xerostomia
diantaranya seperti parotitis, sialolithiasis, mukokel, obstruksi kelenjar saliva,
adenoma dan karsinoma.1
3. Penyakit sistemik
Sejumlah besar penyakit sistemik dapat menyebabkan xerostomia, baik
sebagai efek samping penyakit maupun yang secara langsung mempengaruhi kelenjar
saliva dan menyebabkan berkurangnya sekresi saliva. Beberapa penyakit sistemik
yang menyebabkan xerostomia diantaranya sindrom Sjogren’s, diabetes, sarkoidosis, sistemik lupus eritematosus, infeksi HIV, hepatitis C, penyakit
Graft-versus-host-disease, tuberkulosis dan penyakit ginjal kronik.1-3,30
Sindrom Sjogren’s merupakan penyakit autoimun yang ditandai dengan
inflamasi kelenjar eksokrin, sehingga menyebabkan kekeringan permukaan mukosa,
terutama pada mukosa mata dan mukosa mulut. Infiltrasi limfosit yang progresif
merusak asini sekretori kelenjar saliva mayor dan kelenjar saliva minor secara
perlahan, mengakibatkan hiposalivasi dan xerostomia. Selain itu, hipofungsi kelenjar
juga diakibatkan adanya gangguan stimulus pada kelenjar saliva.3
Selain sindrom Sjogren’s, penyakit autoimun yaitu kronik
Graft-versus-host-disease (cGVHD) juga menimbulkan manifestasi oral dan xerostomia merupakan
keluhan yang paling sering ditemukan. Penyakit cGVHD menyebabkan fibrosis
kelenjar saliva dan perubahan komposisi saliva (berkurangnya konsentrasi Na+ dan
meningkatnya konsentrasi K+) sehingga terjadi penurunan aliran saliva. Pada tahap
lanjut, penyakit cGVHD akan merusak fungsi kelenjar saliva mayor dengan
menyerang reseptor muskarinik, transporter air dan ion kalsium.2,33
Keadaan xerostomia juga menjadi salah satu komplikasi oral penyakit
diabetes mellitus. Sebesar 38,5% anak-anak dan 53% dewasa penderita diabetes
mellitus tipe 1 mengalami xerostomia dan 14%-62% penderita diabetes mellitus tipe
2 mengalami xerostomia.30 Xerostomia terjadi terutama pada penderita penyakit
dengan keadaan poliuri dan dehidrasi yang dialaminya.30,33,34 Pada penderita dengan
kontrol diabetes buruk, pemeriksaan laju aliran saliva stimulasi pada kelenjar parotid
menunjukkan nilai terendah dibandingkan dengan kelompok diabetes terkontrol.
Sekitar 24%-48% penderita diabetes mengalami pembesaran kelenjar parotid.2
Penurunan laju sekresi saliva dan perubahan komposisi saliva terjadi sebagai akibat
komplikasi kronis penyakit diabetes mellitus berupa neuropati, kelainan
mikrovaskular dan disfungsi endotelial yang menyebabkan gangguan
mikrosirkulasi.34
4. Usia
Xerostomia sering menjadi keluhan saat usia lanjut dan diperkirakan sekitar
12-47% individu usia lanjut mengalami mulut kering.30 Proses penuaan
mengakibatkan berkurangnya sekresi saliva total saat istirahat.4,27 Sekitar 70% saliva
total saat istirahat berasal dari kelenjar saliva submandibular dan sublingual sehingga
berkurangnya aliran saliva yang berkaitan dengan usia disebabkan berkurangnya
aliran saliva kelenjar submandibula dan sublingual dan sedikit dipengaruhi oleh
kelenjar parotid.27 Pemeriksaan histomorfometrik pada jaringan kelenjar saliva
menunjukkan berkurangnya volume asinar, meningkatnya volume duktus, dan
terjadinya penggantian sel-sel asinar oleh jaringan adiposa dan jaringan fibrotik.4
Keadaan xerostomia pada manula dapat diperparah apabila manula menderita
penyakit sistemik maupun mengkonsumsi obat-obatan akibat penyakit sistemik yang
dideritanya.3,4 Penggunaan obat-obatan meningkat seiring bertambahnya umur. Lebih
dari 75% individu berusia 65 tahun ke atas mengkonsumsi minimal satu obat,
sehingga prevalensi xerostomia akibat obat-obatan tinggi pada usia lanjut.35
5. Terapi radiasi kepala dan leher
Radioterapi kepala dan leher dapat menyebabkan komplikasi akut dan
komplikasi kronis pada kelenjar saliva, menyebabkan perubahan komposisi saliva
dan akhirnya menyebabkan xerostomia.3 Pada tahap awal, ionisasi kelenjar saliva
mengakibatkan inflamasi dan degenerasi pada parenkim kelenjar saliva, terutama
sel-sel asinar, perubahan duktus epitelium, fibrosis dan degenerasi jaringan adiposa
kelenjar saliva.36
Kelenjar saliva yang paling radiosensitif yaitu kelenjar parotid, diikuti
kelenjar submandibula, sublingual dan kelenjar saliva minor. Efek akut radioterapi
pada fungsi salivasi berlangsung pada minggu pertama radioterapi. Radiasi pada
minggu pertama menyebabkan penurunan saliva sebesar 50%-60% dan setelah tujuh
minggu mengalami penurunan sebesar 20%.3 Fungsi salivasi terus menurun hingga
beberapa bulan setelah radioterapi (1-3 bulan).3,36 Jumlah dosis, durasi dan lamanya
radioterapi berhubungan dengan keparahan xerostomia.3
2.3.3 Tanda dan Gejala
Tanda dan gejala klinis xerostomia yaitu sebagai berikut:
1. Tanda
Mukosa oral terlihat kering dan eritema, dorsal lidah terlihat berlobus dan
fisur, yang disertai dengan atrofi papila filiformis.32,37 Xerostomia mengakibatkan
mukosa menjadi rentan terhadap trauma, kandidiasis, terjadinya sindrom mulut
terbakar dan halitosis.3 Prevalensi kandidiasis dan angular cheilitis meningkat akibat
menurunnya aktivitas cleansing dan antimikroba saliva.37 Penderita xerostomia juga
akan rentan terhadap karies servikal, karies rekuren, erosi enamel dan penyakit
periodontal.3,32,37
2. Gejala
Penderita xerostomia akan mengalami kesulitan berbicara, mengunyah dan
menelan serta mengalami perubahan pengecapan. Berkurangnya lubrikasi saliva saat
makan, bahkan dapat menyebabkan makanan melekat dengan membran oral. Selain
itu, penderita mengeluh adanya ketidaknyamanan oral dan pada yang memakai gigi
tiruan, xerostomia akan menyebabkan retensi gigi tiruan yang buruk. Penderita
xerostomia juga mengeluh adanya peningkatan kebutuhan untuk minum terutama
2.3.3 Diagnosis
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis xerostomia,
diantaranya:
1. Anamnesis dan Kuesioner
Xerostomia merupakan keluhan subjektif mulut kering, sehingga diagnosis
xerostomia dapat ditegakkan dengan hanya melakukan anamnesis, menanyakan
pertanyaan-pertanyaan yang detail tentang keluhan mulut kering yang dialami
seseorang.4
Kuesioner juga dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis xerostomia.
Pertanyaan dalam kuesioner meliputi gejala xerostomia dan perilaku dalam
mengatasinya.4,38
Tabel 2. Kuesioner untuk mendiagnosis xerostomia38
1 Apakah mulut anda terasa kering saat ini?
2 Apakah saat mengkonsumsi makanan mulut anda juga terasa kering?
3 Apakah anda mengalami kesulitan dalam mengkonsumsi makanan yang kering? 4 Apakah anda mengalami kesulitan saat menelan makanan?
5 Apakah mulut anda membutuhkan air minum saat menelan makanan? 6 Apakah anda mengisap permen untuk meringankan mulut kering? 7 Apakah pada malam hari anda bangun untuk minum?
8 Apakah bibir anda terasa kering? 9 Apakah kulit wajah anda terasa kering? 10 Apakah mata anda terasa kering? 11 Apakah hidung anda terasa kering?
2. Pemeriksaan klinis rongga mulut
Pemeriksaan klinis meliputi pemeriksaan tanda-tanda kekeringan mukosa
seperti bibir pecah, mukosa bukal yang pucat, lidah yang licin, eritema dan disertai
atrofi papila. Kandidiasis sering ditemukan dan berkontribusi menyebabkan mukosa
yang sensitif. Selain itu, lakukan pemeriksaan kelenjar saliva yaitu memeriksa apakah
terjadi pembesaran, perubahan tekstur dan rasa sakit, serta memeriksa kuantitas dan
Xerostomia juga ditandai oleh sarung tangan dan kaca mulut yang terasa lengket
dengan permukaan mukosa saat dilakukan pemeriksaan.3
3. Pemeriksaan laboratorium
Pemeriksaan fungsi kelenjar saliva dan laju sekresi saliva dapat dilakukan
secara objektif menggunakan metode sialometri.3 Pemeriksaan dapat dilakukan
terhadap saliva total (campuran cairan rongga mulut) maupun terhadap saliva
individu, baik dalam keadaan tanpa stimulasi/istirahat atau dalam keadaan
terstimulasi.27,33 Saliva total lebih banyak digunakan sebagai indikator mulut kering
dan penyakit sistemik yang bersangkutan, sementara pemeriksaan saliva individu
lebih bermanfaat dalam mendiagnosis penyakit kelenjar saliva.27
Teknik pengumpulan saliva dalam keadaan tanpa stimulasi diantaranya
dengan metode draining/drooling, metode spitting, metode swabbing dan metode
suction.40 Pengumpulan saliva yang terstimulasi dapat dilakukan dengan metode
mengunyah parafin ataupun dengan mengaplikasikan asam sitrat pada lidah.40 Total
waktu pengumpulan saliva sekitar 5-15 menit.27 Untuk melakukan pengumpulan
saliva istirahat, individu yang akan diukur salivanya, diinstruksikan untuk tidak
makan, minum, merokok atau melakukan stimulasi apapun (termasuk tindakan
higiene oral) selama 90 menit sebelum dilakukan pengukuran.33
a. Saliva total tanpa stimulasi
Dalam keadaan tanpa stimulasi, laju alir saliva total normalnya sekitar
0,5 ml/menit dan dikatakan hiposalivasi jika laju alir saliva total kurang dari
0,1 ml/ menit.35,39 Pengumpulan saliva total istirahat dapat dilakukan dengan metode
draining, spitting, suction dan absorbent (swab).3 Pada metode draining, saliva
dibiarkan mengalir dari mulut ke dalam suatu wadah, sementara metode spitting yaitu
mengumpulkan saliva dalam mulut yang kemudian ditampung dalam suatu
wadah/sialometer 1-2 kali setiap menit. Metode suction menggunakan saliva ejector,
sementara pada metode swab caranya menggunakan cotton roll/sponge yang
sebelumnya diukur beratnya, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan dibiarkan
saliva mengalir membasahinya. Cotton roll/sponge tersebut kemudian diukur kembali
untuk memperkirakan derajat salivasi pasien dengan keadaan xerostomia yang
parah.27
b. Saliva total terstimulasi
Pada keadaan terstimulasi, laju alir saliva meningkat menjadi 1,5-2 ml/menit
dan dikatakan hiposalivasi jika kurang dari 0,7 ml/menit.33 Pengumpulan saliva total
stimulasi dapat menggunakan metode mastikasi dengan parafin wax, metode
rangsangan dengan asam sitrat dan metode absorbent dengan sponge. Pada metode
mastikasi, individu diberi parafin wax untuk dikunyah selama 5 menit. Setelah itu,
saliva yang terakumulasi dalam mulut ditampung setiap menit dalam suatu wadah.
Metode rangsangan dengan asam sitrat yaitu dengan mengaplikasikan asam sitrat
pada lateral lidah setiap 30 detik selama 5 menit, kemudian saliva dikumpulkan
dalam suatu wadah setiap menit. Pada metode absorbent/swab, sponge diletakkan di
dalam mulut setelah sebelumnya ditimbang beratnya. Kemudian individu diinstruksi
untuk mengunyah sponge tersebut. Sponge kemudian diukur kembali beratnya dan
dicari hasil selisihnya.27
c. Saliva individu kelenjar parotid
Pengumpulan saliva individu kelenjar parotid dapat dilakukan dengan
menggunakan alat cup Carlson-Crittenden/cupLashley. Alat cupLashley terdiri dari
dua chamber, dimana bagian dalam chamber diletakkan diatas orifisi duktus stensen
(mukosa bukal disekitar gigi molar satu permanen), sementara bagian luar chamber
dihubungkan ke suction. Dalam keadaan tanpa stimulasi, aliran saliva individu
kelenjar parotid sangat rendah/hampir tidak ada, sehingga pengumpulan saliva
individu kelenjar parotid biasanya dilakukan dalam keadaan terstimulasi
menggunakan larutan asam sitrat 2-4%. Larutan ini diaplikasikan pada lateral border
Gambar 1. Pengumpulan saliva individu kelenjar parotid. A= Alat cup Lashley, B= Posisi peletakan alat diatas orifisi kelenjar parotid (duktus Stensen)27
d. Saliva individu kelenjar submandibula dan sublingual
Pengumpulan saliva individu kelenjar submandibula dan sublingual juga dapat
dilakukan dalam keadaan tanpa stimulasi maupun dalam keadaan terstimulasi
(dengan asam sitrat 2-4%). Pengumpulan saliva biasanya dilakukan dengan
menggunakan metode suction. Pada teknik ini, duktus Stensen dihambat
menggunakan cup Lashley atau cotton rolls dan saliva yang terakumulasi pada dasar
mulut dapat diaspirasi menggunakan syringe atau menggunakan alat suction yang
diperkenalkan Wolff.27
Gambar 2. Pengumpulan saliva individu kelenjar submandibula dan sublingual. A=Metode suction menggunakan syringe, B= alat suction menurut
Wolff27
A B
B
4. Metode lain
Selain metode pemeriksaan seperti penjelasan sebelumnya, untuk
mengevaluasi fungsi saliva dapat juga dilakukan dengan melihat kemampuan
seseorang untuk mengunyah dan menelan biskuit kering dalam keadaan tanpa air.3
Sialografi, Ultrasonografi, MRI dan CT scan digunakan untuk mendeteksi adanya
keadaan patologis seperti sialolith, obstruksi/kerusakan duktus, tumor dan kista yang
menyebabkan disfungsi kelenjar saliva.39
2.4 Hubungan Penggunaan Obat Bronkodilator pada Pasien PPOK terhadap Terjadinya Xerostomia
Dalam keadaan istirahat, kelenjar saliva minor diperkirakan memproduksi
setengah bagian dari saliva di rongga mulut.33 Sementara dalam keadaan stimulasi,
sekitar 90% saliva dihasilkan oleh kelenjar mayor. Kelenjar mayor terdiri dari
kelenjar parotid, kelenjar submandibula dan kelenjar sublingual. Struktur anatomi
kelenjar saliva terdiri dari sel asinar dan sel duktus. Sel asinar membentuk hasil akhir
sekretori, sedangkan sel duktus membentuk sistem cabang yang mendistribusi saliva
dari sel asinar kedalam rongga mulut. Sel asini kelenjar parotid menghasilkan saliva
serous, kelenjar sublingual dan kelenjar minor menghasilkan saliva mukus dan
kelenjar submandibula menghasilkan saliva seromukus yang didominasi sifat
mukus.1,33 Saliva serous adalah saliva yang encer, sementara saliva mukus lebih
kental karena adanya kandungan musin, glikoprotein.1
Saliva terdiri dari dua komponen, yaitu komponen cairan yang mencakup
ion-ion dan komponen protein. Kedua komponen tersebut disekresi secara terpisah
dengan mekanisme berbeda yang berada di bawah rangsangan sistem saraf autonom.
Sekresi komponen cairan diatur oleh rangsangan parasimpatis melalui reseptor
muskarinik-kolinergik dan pelepasan komponen protein oleh rangsangan simpatis
melalui reseptor beta adrenergik. Rangsangan saraf parasimpatis akan menghasilkan
saliva dengan kandungan komponen cairan yang tinggi, tetapi dengan konsentrasi
protein yang tinggi, tetapi sedikit saliva. Oleh karena itu, rangsangan simpatis
menyebabkan sensasi mulut kering.33,41
Penggunaan agonis beta 2 menyebabkan perubahan komposisi saliva dan
berkurangnya sekresi saliva.16 Obat bronkodilator agonis beta 2, merupakan obat
simpatomimetik, yaitu obat yang bekerja pada saraf simpatis dan menyerupai kerja
neurotransmitter adrenergik.26 Dengan adanya rangsangan simpatis, maka akan
terangsang kelenjar submandibula dan kelenjar sublingual yang menghasilkan saliva
mukus yang tebal dan kental, sedangkan kelenjar parotid yang tidak dipersarafi saraf
simpatis tidak menghasilkan saliva.26 Dengan demikian, volume saliva yang
dihasilkan akan lebih sedikit. Padahal dalam keadaan terstimulasi, kelenjar parotid
berkontribusi besar menghasilkan saliva (50-70%).1 Selain itu, obat golongan
simpatomimetik juga menyebabkan vasokonstriksi sehingga terjadi penurunan aliran
saliva dan akhirnya mengakibatkan xerostomia.26
Obat bronkodilator antikolinergik memiliki mekanisme kerja yang berbeda
dalam menyebabkan xerostomia. Obat golongan antikolinergik merupakan obat
parasimpatolitik yang bekerja antagonis pada saraf parasimpatis.26 Seperti uraian
sebelumnya, rangsangan parasimpatis berfungsi untuk mengatur sekresi komponen
cairan saliva. Dengan adanya kerja obat antikolinergik yang menghambat perlekatan
asetilkolin pada reseptor muskarinik-kolinergik saraf parasimpatis, maka akan terjadi
2.6 Kerangka Konsep
Xerostomia Obat bronkodilator pada pasien
PPOK
Jenis obat
Lama pemberian obat
Jenis Kelamin Usia pasien