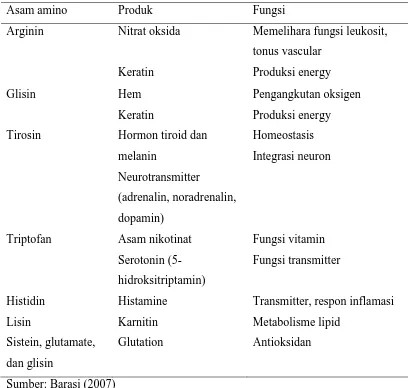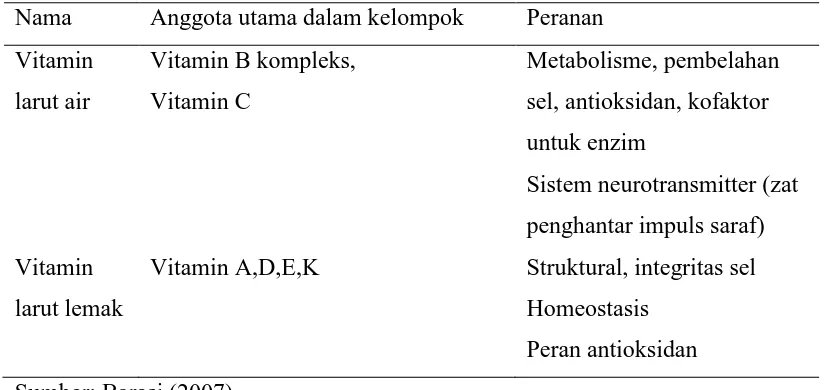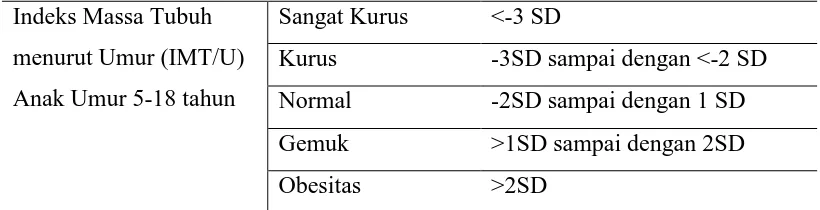BAB 2
T INJAUAN PUSTAKA 2.1 Asupan Makanan
2.1.1 Defenisi
Menurut Maretha (2009) dalam Anjani (2013), asupan makanan adalah
informasi tentang jumlah dan jenis makanan yang dimakan atau dikonsumsi oleh
seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu. Dari asupan makanan
diperoleh zat gizi esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memelihara pertumbuhan
dan kesehatan yang baik (Budianto, 2009).
Makanan terdiri dari bermacam-macam zat kimia. Beberapa zat dikenal
sebagai nutrien dan terdapat banyak zat lain, terutama dalam bahan makanan
nabati. Zat ini memacu pertumbuhan tanaman, melindunginya dari pemangsa dan
memperbaiki penampilan atau menambah aromanya. Zat-zat ini (fitokimia) tidak
dianggap sebagai nutrien tetapi mungkin aktif secara biologis dan memenuhi efek
menguntungkan pada manusia (Barasi, 2007).
Nutrien dibedakan menjadi makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien
diperlukan dalam jumlah yang besar oleh tubuh sedangkan mikronutrien hanya
diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya adalah air yang menjadi
komponen esensial dalam diet karena asupan cairan yang cukup merupakan hal
yang vital bagi kelangsungan hidup. Makronutrien dalam diet mencakup
karbohidrat, lemak dan protein. Sedangkan mikronutrien mencakup vitamin dan
mineral (Barasi, 2007).
2.1.2 Karbohidrat
Karbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi manusia yang harganya
relatif murah. Karbohidrat tersusun dari berbagai kompleksitas untuk membentuk
gula sederhana serta unit yang lebih besar seperti oligosakarida dan polisakarida
(Barasi, 2007). Fungsi utamanya adalah sebagai sumber energi dalam bentuk
glukosa. Satu gram karbohidat menghasilkan 4 kalori. Karbohidrat didalam tubuh
Sebagian lagi disimpan sebagai bentuk glikogen dalam hati dan jaringan otot, dan
sebagian lagi disimpan di jaringan lemak (Almatsier, 2010).
Fungsi lain karbohidrat adalah sebagai penghemat protein artinya ketika
karobihdrat tidak mencukupi, maka protein akan digunakan untuk memenuhi
kebutuhan energi. Dan sebaliknya, bila karbohidrat cukup, protein terutama akan
digunakan sebagai zat pembangun (Yuniastuti, 2008).
Jenis karbohidrat dalam makanan dikelompokkan menjadi monosakarida,
disakarida, dan polisakarida. Monosakarida dibagi lagi menjadi glukosa, fruktosa,
dan galaktosa. Galaktosa merupakan gula khusus yang terdapat pada bahan
hewani, yaitu air susu. Disakarida dalam bahan makanan yang penting adalah
sukrosa, maltosa, dan laktosa. Laktosa hanya dijumpai pada susu hewan menyusui
dan air susu ibu. Dalam bahan makanan nabati terdapat dua jenis polisakarida
yang dapat dicerna (yaitu amilum dan dekstrin) dan tidak dapat dicerna (seperti
selulosa, pentosan, dan galaktan). Sedangkan dalam bahan makanan hewani
terdapat polisakarida yang dapat dicerna yang disebut glikogen (Anonimus, 2007).
Tabel 2.1 Kelompok karbohidrat
Kelompok Contoh
CHO sederhana
Monosakarida Glukosa, fruktosa
Disakarida Sukrosa, laktosa, maltose
Oligosakarida Rafinosa, inulin
CHO kompleks
Zat pati Zat pati yang dapat dicerna
Polisakarida nonpati Selulosa, polisakarida nonselulosa
Sumber: Barasi(2007)
2.1.3 Lemak
Lemak meliputi berbagai macam zat yang larut dalam lipid, sebagian besar
merupakan trigliserida atau triasigliserol (TAG). Produk turunannya seperti
kelompok ini. TAG dipecah untuk menghasilkan energi dan menyusun cadangan
energi utama bagi tubuh dalam jaringan adiposa (Barasi, 2007).
Lemak dan minyak merupkan zat makanan yan penting untuk menjaga
kesehatan tubuh manusia. Dan merupkana sumber energi yang lebih efektif
dibanding dengan karobidrat dan protein. Besar energi yang dihasilkan per gram
lemak adalah 9 kalori. Fungsi lain lemak dalam tubuh adalah sebagai
pembangun/pembentuk susunan tubuh, pelindung kehilangan panas tubuh, pelarut
vitamin A, D, E, dan K (Budianto, 2009).
Sumber utama lemak adalah minyak tumbuhan, mentega, margarin, dan
lemak hewan. Sumber lain berasal dari kacang-kacangan, susu, kedelai, kuning
telur dan sebagainya (Almatsier, 2010). Lemak hewan ada yang berbentuk padat
antara lain lemak susu, lemak sapi, dan berbentuk cair seperti minyak ikan paus,
minyak ikan cod, minyak ikan herring (Budianto, 2009).
2.1.4 Protein
Protein merupakan suatu zat makanan yang sangat penting bagi tubuh
karena mengandung unsur C,H,O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak atau
karbohidrat. Molekul protein mengandung pula fosfor, belerang, dan logam. Tiap
gram protein mengandung energi sebanyak 4 kalori (Budianto, 2009).
Protein terdiri atas berbagai rantai dari asam amino tunggal yang tergabung
membentuk beraneka ragam protein. Saat dicerna masing-masing asam amino
digunakan untuk sintesis asam amino serta protein lainnya yang diperlukan oleh
tubuh. Jika asam amino tidak dibutuhkan lebih lanjut, barulah asam amino
tersebut dipecah dan digunakan sebagai sumber energi (Barasi, 2007).
Protein ada di semua jaringan tubuh dan merupakan material dasar di kulit,
otot, tendon, saraf dan darah. Selain itu, protein juga membentuk antibodi dan
Tabel 2.2 Penggunaan asam amino untuk sintesis produk turunannya.
Asam amino Produk Fungsi
Arginin Nitrat oksida
Keratin
Tirosin Hormon tiroid dan
melanin
Triptofan Asam nikotinat
Serotonin
(5-hidroksitriptamin)
Fungsi vitamin
Fungsi transmitter
Histidin Histamine Transmitter, respon inflamasi
Lisin Karnitin Metabolisme lipid
Sistein, glutamate,
dan glisin
Glutation Antioksidan
Sumber: Barasi (2007)
2.1.5 Vitamin
Vitamin merupakan suatu molekul organik yang dibutuhkan untuk proses
metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Vitamin tidak dapat dibuat oleh
tubuh dalam jumlah yang sangat cukup. Oleh karena itu, harus diperoleh dari
asupan makanan (Budianto, 2009).
Vitamin dibagi dalam dua kelompok yaitu vitamin larut dalam lemak
(A,D,E, dan K) dan vitamin larut dalam air (vitamin B dan C). Tiap vitamin
memiliki tugas spesifik dalam tubuh (Almatsier, 2010). Vitamin yang berperan
dalam pembentukan darah ( asam folat dan vitamin B12), sebagai antioksidan
metabolisme energi (thiamin, riboflavin dan pirodoksin) dan pembentukan tulang
oleh vitamin D (Eastwood, 2003). Dan pada dasarnya vitamin berperan dalam
beberapa tahap reaksi metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh.
Pada umumnya sebagai koenzim atau sebagai bagian dari enzim (Almatsier,
2010).
Tabel 2.3. Klasifikasi vitamin dan peranannya
Nama Anggota utama dalam kelompok Peranan
Vitamin
Vitamin A,D,E,K Struktural, integritas sel
Homeostasis
Peran antioksidan
Sumber: Barasi (2007)
2.1.6 Mineral
Mineral merupakan unsur esensial dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik
pada tingkat sel, jaringan, organ maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Mineral
digolongkan atas dua yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro
(natrium, klorida, kalium, kalsium fosfor, magnesium dan sulfur) dibutuhkan
tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg sehari sedangkan mineral mikro (besi,
seng, iodium, selenium dll) dibutuhkan kurang dari 100 mg sehari (Almatsier,
2004).
2.1.7 Air
Air menciptakan media dasar tempat berlangsungnya semua reaksi dalam
tubuh. Asupan cairan yang tidak cukup akan cepat menggangu fungsi
dari keseluruhan berat badan. Sepertiga adalah cairan ekstraseluler dan dua per
tiga berada di intraseluler. Kompartemen ini dipisahkan oleh membran sel dan
dapat dilalui oleh air (Eastwood, 2003). Air memiliki berbagai fungsi dalam
proses vital tubuh yaitu sebagai pelarut dan alat angkut, katalisator, pelumas,
pengatur suhu, dan fasilitator pertumbuhan (Almatsier, 2004).
Kebutuhan air sehari dinyatakan sebagai proporsi terhadap jumlah energi
yang dikeluarkan tubuh dalam keadaan lingkungan rata-rata. Untuk orang dewasa
dibutuhkan sebanyak 1,0-1,5 ml/kkal, sedangkan untuk bayi 1,5 ml/kkal
(Yuniastuti, 2008). Sumber air dapat diperoleh dari minuman, jus, susu, buah,
sayuran, dan makanan lain (Drummond dan Brefere, 2007).
2.2 Kecukupan gizi
Standar kecukupan gizi di Indonesia masih menggunakan ukuran makro
yaitu kecukupan kalori (energi) dan kecukupan protein (Agus, 2004).
Recommended dietary allowances (RDA) adalah istilah yang digunakan di
Amerika yang merupakan standar berisi kebutuhan rata-rata gizi per hari yang
dianjurkan sehingga suatu masyarakat dapat hidup sehat. Sementara di Indonesia
dikenal dengan istilah AKG (Angka Kecukupan Gizi). AKG dipengaruhi oleh
umur, jenis kelamin, aktivitas, berat badan, tinggi badan, genetika dan keadaan
fisiologis (Anonimus, 2007).
2.2.1 Kecukupan energi
Energi dibutuhkan untuk semua fungsi yang dijalankan oleh tubuh yang
meliputi :
1. Aktivitas metabolik pada tingkat seluler, jaringaan, dan organ yang sebagian
besar berlangsung di luar kesadaran.
2. Aktivitas sadar yang dilakukan sebagai bagian dari aktivitas fisik dan
memerlukan energi dalam jumlah yang berbeda-beda.
3. Pertumbuhan, dalam tahun-tahun awal kehidupan, pada masa remaja, dan
Semua energi yang diperlukan tubuh disuplai melalui asupan makanan.
Makronutrien dalam makanan dan minuman menghasilkan energi ketika dipecah.
Mineral dan vitamin dalam makanan tidak menghasilkan energi, meskipun
beberapa di antaranya bersifat esensial dalam proses biokimia yang menghasilkan
energi (Barasi, 2007).
Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dapat dihitung dengan cara
membandingkan rata-rata konsumsi sehari dengan AKG yang dikoreksi dengan
berat badan. Sesudah diketahui tingkat konsumsi gizi, untuk keperluan deskriptif
maka dapat diklasifikasikan seperti yang termuat dalam tabel 2.4 (WNPG, 2004).
Tabel 2.4 Klasifikasi TKE
Tingkat Konsumsi Energi Persentase terhadap AKG
Baik 80-110% AKG
Kurang < 80% AKG
Lebih >110% AKG
Sumber : WNPG (2004)
2.2.2 Kecukupan protein
Banyaknya protein dalam tubuh digunakan untuk memenuhi kebutuhan
basal dan sejumlah tambahan untuk mengimbangi adanya kerusakan, infeksi,
stress dan sebagainya. Kehilangan protein dapat melalui air seni, kotoran dan kulit
(Anonimus, 2007).
Tingkat Konsumsi Protein (TKP) dapat dihitung dengan cara
membandingkan rata-rata konsumsi sehari dengan AKG yang dikoreksi dengan
berat badan. Sesudah diketahui tingkat konsumsi protein, untuk keperluan
deskriptif maka dapat diklasifikasikan seperti yang termuat dalam tabel 2.5
Tabel 2.5 Klasifikasi TKP
Tingkat Konsumsi Protein
Baik 80-110% AKG
Kurang < 80% AKG
Lebih >110% AKG
Sumber : WNPG (2004)
2.3 Penilaian Asupan Makanan
Penilaian asupan makanan atau survei diet adalah salah satu metode yang
digunakan dalam penentuan status gizi perorangan atau kelompok. Tujuannya
adalah untuk mengetahui kebiasaan makan dan gambaran tingkat kecukupan
bahan makanan dan zat gizi pada tingkat kelompok, rumah tangga dan perorangan
serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi makanan tersebut.
Sedangkan secara khusus, tujuan dari survei diet adalah menentukan status
kesehatan dan gizi keluarga dan individu, sebagai dasar perencanaan dan program
pengembangan gizi (Supariasa, Bakri, dan Fajar, 2002).
Metode-metode pengukuran konsumsi makanan antara lain :
1. Metode frekuensi makanan (food frequency).
Metode frekuensi makanan adalah untuk memperoleh data tentang frekuensi
konsumsi sejumlah bahan makanan atau makanan jadi selama periode
tertentu seperti hari, minggu, bulan, dan tahun. Cara ini paling sering
digunakan dalam penelitian epidemiologi gizi.
2. Metode ingatan pangan24 jam (24-hours food recall).
Prinsip dari metode ini adalah mencatat jenis dan jumlah bahan makanan
yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Dalam metode ini,
responden diminta untuk menceritakan semua yang dimakan dan diminum
selama 24 jam yang lalu. Data konsumsi yang dicatat mulai bangun pagi
dari recall 24 jam bersifat kualitatif. Sehingga perlu ditanyakan secara teliti
dengan menggunakan alat ukuran rumah tangga.
3. Metode pendaftaran makanan (food list).
Dilakukan dengan menanyakan dan mencatat seluruh bahan makanan dan
memperhitungkan bahan makanan yang terbuang atau rusak. Pengumpulan
data dilakukan dengan wawancara.
4. Metode Penimbangan (food weighing).
Petugas menimbang dan mencatat seluruh makanan yang dikonsumsi
selama satu hari. Jumlah makanan yang dikonsumsi sehari kemudian
dianalisis dengan menggunakan DKBM atau DKGJ ( Daftar Konsumsi Gizi
Jajanan). Setelah itu, hasilnya dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi
(AKG) yang dianjurkan. Kelebihan dari metode ini adalah bahwa data yang
diperoleh lebih akurat.
2.4. Status gizi
2.4.1. Defenisi Status Gizi
Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk
variabel tertentu atau perwujudan dari nutriture dalam bentuk variabel tertentu.
Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi secara garis besar dibagi dua yaitu
konsumsi makanan dan kesehatan. Konsumsi makanan sangat dipengaruhi oleh
tersedianya bahan makanan, makanan dan pendapatan untuk mencukupi keperluan
makan. Selanjutnya adalah keadaan kesehatan yang dipengaruhi oleh
pemeliharaan kesehatan dan lingkungan fisik dan sosial (Supariasa, Bakri,dan
Fajar, 2002).
2.4.2. Penilaian Status Gizi
Penilaian status gizi pada dasranya merupakan proses pemeriksaan keadaan
gizi seseorang dengan cara mengumpulkan data penting, baik yang bersifat
objektif maupun subjektif. Kemudian dibandingkan dengan baku yang telah
Beberapa cara dalam melakukan penilaian status gizi yaitu antara lain :
1. Biokimia
Dengan pemeriksaan protein visceral, albumin, transferin serum,
Thyroxine-binding prealbumin (TBPA), fungsi kekebalan. Selain itu dapat juga dengan
memeriksa sensivitas kulit, protein somatik, hematologik dan keadaan
hidrasi (Arisman, 2002).
2. Pemeriksaan klinis
Meliputi pemeriksaan fisik secara menyeluruh, termasuk riwayat kesehatan,
bagian tubuh yang harus lebih diperhatikan ialah kulit, gigi, gusi, bibir,
lidah, mata dan alat kelamin (Arisman, 2002).
3. Pemeriksaan antropometri
Pertumbuhan dipengaruhi oleh determinan biologis yang meliputi jenis
kelamin, lingkungan di dalam rahim, jumlah kelahiran, berat lahir pada
kehamilan tunggal atau majemuk, gen serta faktor lingkungan (iklim,
musim, sosial-ekonomi). Tujuan dalam pemeriksaan antropometris ialah
besaran komposisi tubuh yang dapat dijadikan isyarat dini perubahan status
gizi (Arisman, 2002).
Adapun beberapa indikator dalam pemeriksaan antropometri ialah :
a. Tinggi badan
Tinggi atau panjang badan merupakan indikator umum ukuran tubuh
dan panjang tulang. Namun, harus digabung dengan indikator lain
(Arisman, 2002). Tinggi badan menggambarkan keadaan pertumbuhan
skeletal dan tumbuh sering dengan pertambahan umur (Supariasa,
Bakri,dan Fajar, 2002).
b. Berat badan
Berat badan merupakan ukuran antropometris yang paling banyak
digunakan. Agar berat dapat dijadikan satu ukuran yang valid,
parameter lain seperti tinggi, ukuran rangka, proporsi lemak, otot,
tulang, serta komponen berat patologis harus dipertimbangkan. Dengan
kata lain, ukuran berat harus dikombinasikan dengan parameter
c. Umur
Umur sangat memegang peranan penting dalam penentuan status gizi,
kesalahan penentuan akan menyebabkan interpretasi gizi yang salah.
Oleh sebab itu, penentuan umur anak perlu dihitung dengan cermat.
Ketentuannya yaitu 1 tahun adalah 12 bulan, 1 bulan adalah 30 hari.
Jadi perhitungan umur adalah dalam bulan penuh, artinya sisa umur
dalam hari tidak diperhitungkan (Depkes, 2004 ).
Pada anak penentuan status gizi dapat menggunakan indeks massa tubuh
berdasarkan usia. Dengan terlebih dahulu menghitung Indeks Massa Tubuh (IMT)
anak yaitu membandingkan berat badan dalam kilogram dengan kuadarat tinggi
badan dalam meter.
Lalu disesuaikan dengan tabel standar antropometri penilaian status gizi
anak di Indonesia untuk mengetahui klasifikasi status gizinya (Keputusan Menteri
Kesehatan RI, 2010)
Tabel 2.1 Kategori dan Ambang Status Gizi Anak Berdasarkan IMT
Indeks Massa Tubuh
menurut Umur (IMT/U)
Anak Umur 5-18 tahun
Sangat Kurus <-3 SD
Kurus -3SD sampai dengan <-2 SD
Normal -2SD sampai dengan 1 SD
Gemuk >1SD sampai dengan 2SD
Obesitas >2SD