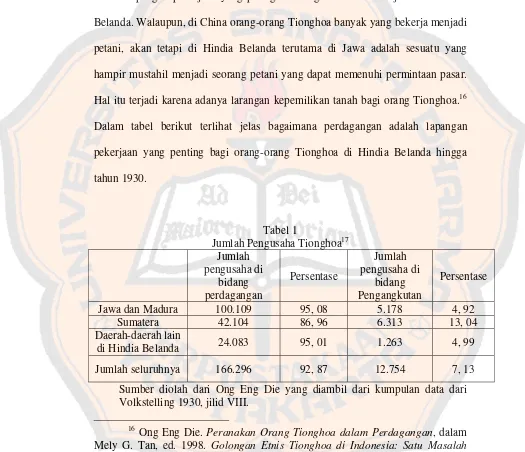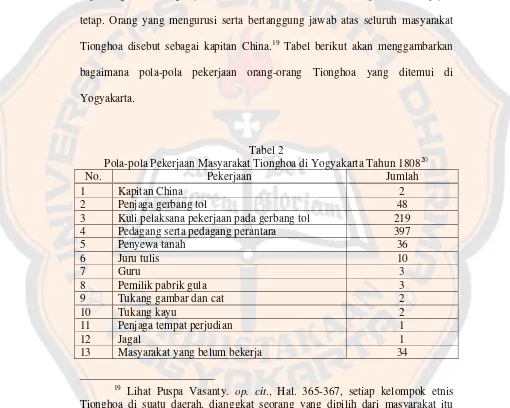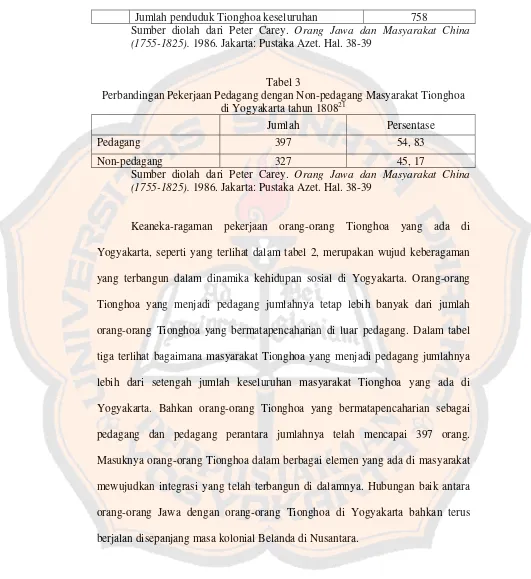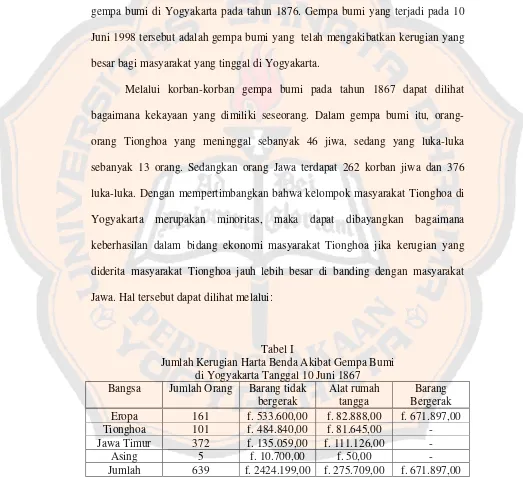MASYARAKAT TIONGHOA DI YOGYAKARTA
1877-1920
Sripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sastra
Program Studi Ilmu Sejarah
Nama : Audy Bramara
Nim : 07 4314 007
JURUSAN ILMU SEJARAH FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
MASYARAKAT TIONGHOA DI YOGYAKARTA
1877-1920
Sripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sastra
Program Studi Ilmu Sejarah
Nama : Audy Bramara
Nim : 07 4314 007
JURUSAN ILMU SEJARAH FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA
Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan
karya saya sendiri dan tidak diambil dari karya orang lain, kecuali
disebutkan dalam kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka.
Yogyakarta, 9 Agustus 2011
Penulis
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata
Dharma:
Nama : Audy Bramara
Nomor Mahasiswa : 07 4314 007
Demi pengembangan ilmu pengetahuan memberikan kepada Perpustakaan
Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul ‘MASYARAKAT
TIONGHOA DI YOGYAKARTA 1877-1920.’ Dengan demikian saya
memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk
menyimpan, dan mengalihkan dalam bentuk media lain untuk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada
saya selama tetap mencantum nama saya sebagai penulis.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal 14 September 2011
Yang menyatakan,
MOTTO
Kesadaran adalah matahari.
Kesabaran adalah Bumi.
Keberanian menjadi cakrawala.
dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata.
PERSEMBAHAN
Karya ini saya persembahkan
untuk masyarakat Tionghoa di Yogyakarta,
ABSTRAK
Masyarakat Tionghoa di Yogyakarta 1877-1920
Tulisan ini membahas mengenai sejarah yang berhubungan dengan dinamika kelompok masyarakat Tionghoa di Yogyakarta dalam kurun waktu antara tahun 1877-1920. Keberadaan masyarakat Tionghoa sudah diketahui jauh sebelum Kasultanan Yogyakarta berdiri yaitu tahun 1755. Bahkan keberadaan masyarakat Tionghoa sudah diketahui sebelum kedatangan bangsa Belanda di Nusantara. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa proses interaksi sosial antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Jawa di Yogyakarta sudah terjadi sejak lama.
Demi kepentingan politik dan ekonomi yang menguntungkan Belanda, melalui pemerintahan kolonialnya, Belanda mengeluarkan peraturan-peraturan yang secara langsung telah mempengaruhi interaksi sosial kelompok masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Pengaruh yang ditimbulkan oleh kebijakan politik pemerintah kolonial Belanda cenderung membawa pada perpecahan sosial. Konstruksi sosial yang dibangun oleh Belanda terhadap kelompok masyarakat Tionghoa melahirkan jarak dan kesenjangan diantara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Jawa. Walaupun di satu sisi Belanda membutuhkan keberadaan orang-orang Tionghoa untuk menjadi mitra dagangnya, namun di sisi lain, populasi masyarakat Tionghoa yang semakin besar dan hubungan yang baik dengan masyarakat pribumi dikhawatirkan akan mengancam dominasi Belanda di segala bidang.
Peraturan-peraturan pemerintah kolonial telah membangun konstruksi sosial yang cenderung mengkotak-kotakkan kelompok masyarakat. Hal tersebut tentu mengancam integrasi sosial yang terjadi antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Jawa. Sebagai akibatnya, kerusuhan rasial antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Jawa sering terjadi. Akan tetapi di wilayah Yogyakarta hampir tidak dirasakan adanya konflik rasial. Integrasi dapat terjadi diantara kelompok masyarakat Tionghoa dengan kelompok masyarakat Jawa di Yogyakarta. Kerusuhan rasial yang terjadi akibat konflik antar kelompok masyarakat tidak terjadi. Integrasi yang terjadi di Yogyakarta tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor yang mendukung.
Sultan sebagai raja yang berkuasa di Yogyakarta mengambil peranan yang menentukan dalam dinamika kehidupan seluruh masyarakat Yogyakarta. Kondisi kultural yang sangat kuat membawa masyarakat Yogyakarta untuk menjadikan sosok Sultan sebagai sosok panutan. Sultan sebagai penguasa lokal di wilayah Yogyakarta telah menjadi pengawal dari kehidupan kolektif di Yogyakarta, dalam hal ini terutama adalah kehidupan yang plural.
ABSTRACT
The Subject of this writing is the history which related to the dynamics of the Chinese community in Yogyakarta in the period of 1877 – 1920. The Chinese has already been in existence long before the Kingdom of Yogyakarta was established in the year of 1755. The existence of Chinese even had been recognized long before the arrival of the Dutch in the Archipelago. Thus, it is be sure that the interaction process within the Chinese and the Javanese in Yogyakarta had been done since very long time ago
For the political and economical benefit of the Dutch, the colonial government of the Netherlands-Indies issued a rules that generally influenced the relationship between the Chinese and the Javanese. The influence of a policy of divide and rule that brought social conflicts. Social construction built by the Dutch for the Chinese has made a gap among the Chinese community and the Javanese. Even though in one side the Dutch needed the Chinese as a trading partner, but in the other side, the population which got bigger and the good relationship with the indigenous threatened the domination of the Dutch.
The rules that created by the colonial government was shaped a social construction that made separation among people. Thus, it would threat social integration between Chinese and Javanese. Racial riot between the Chinese and the Javanes had happened very often. But seemingly, in the region of Yogyakarta, that kind of conflict has never been heard. In Yogyakarta integration could be built between the Chinese community and the Javanese. Racial riot has not been happened in Yogyakarta.
Sultan as a king who controlled the region of Yogyakarta took an important role to the dynamics of life for the people of Yogyakarta. Cultural conditions has made the Sultan became a central figure. Sultan as the King of the local region of Yogyakarta has become a communal guard, moreover in the plurality of the people in Yogyakarta.
KATA PENGANTAR
Setelah melewati proses yang cukup panjang, pada akhirnya skripsi ini
dapat diselesaikan. Sehingga puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa, atas berkatNya yang melimpah. Tulisan ini sudah barang tentu
tidak bisa terwujud tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya layak dan
pantas jika dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih
kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan mendukung penulis.
Ucapan terima kasih dialamatkan kepada:
1. Dosen Pembimbing, Drs. Heribertus Hery Santosa, M.Hum yang juga
sekaligus merupakan pembimbing akademik. Dalam kesempatan ini saya
mengucapkan terima kasih yang besar atas kesabaran dalam membimbing
saya selama proses pengerjaan skripsi ataupun selama proses perkuliahan.
2. Pak Silverio R. L. A. S., yang menjabat sebagai kepala Indonesiana.
Terimakasih atas saran dan kritikan yang telah manjadikan saya menjadi lebih
baik.
3. Pak Sandiwan yang telah banyak memberikan saya masukan dalam penulisan
skripsi, serta terimakasih pula untuk semua ilmu yang diberikan selama
proses perkuliahan. Pak Anton Haryono, terimakasih untuk kuliah-kuliah
yang banyak membantu saya terutama ketika memulai penulisan skripsi ini,
serta lokalitas yang bapak tawarkan dalam pemikiran-pemikiran bapak,
Suwarno, terimakasih atas semangat bapak dalam mengajar, sehingga banyak
menginspirasi saya untuk tetap semangat dalam menghadapi segala sesuatu.
4. Pak Manu terima kasih atas buku-buku yang dipinjamkan kepada saya.
Terima kasih juga atas semua dorongan dan motivasi untuk menulis tentang
sesuatu yang ada di daerah dalam hal ini Yogyakarata. Terima kasih juga
karena telah memperkenalkan saya dengan kebudayaan Jawa, sehingga saya
terpicu untuk lebih giat belajar lagi.
5. Rm. G. Budi Subanar, SJ yang telah memberikan masukan refrensi kepada
saya, serta mengajari saya untuk berpikir secara kritis. Terima kasih juga
untuk Rm. FX. Baskara T. Wardaya, SJ yang telah membantu saya untuk
berpikir secara lebih sistematis dan membantu saya untu dapat melihat
sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Karena dengan begitu
subjektifitas dapat direduksi.
6. Mas Tri yang di Sekretariat Fakultas Sastra USD, terima kasih untuk semua
bantuan administratif sewaktu saya kuliah.
7. Terima kasih atas dorongan semangat dari keluarga: Papa, Mama, Elang,
Gunung, dan Puri. Juga saudara-saudara yang terus mengikuti perkembangan
kuliah saya dalam semester akhir: Ibu Emawati, Bapak Suhendro Djayusman.
8. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman di Jurusan Ilmu
Sejarah USD. terutama angkatan 2007: Benedito Savio, Ligia, Krisna,
Wahyu, Adi Siswanto, Irawan, Andriawan, Aryo Baskara, Tian. Trima kasih
juga untuk teman teman sastra atas dukungan dan bantuan: Denty Piawai
9. Teman-teman Salt 2011, terima kasih atas dukungan serta toleransi yang
sudah teman-teman berikan: Mas Anton, Andre, Yosan, Dias.
Semoga apa yang telah diberikan kepada saya diterima oleh Tuhan Yang
Maha Esa. Pada akhirnya harus diakui bahwa hasil karya ini tidak sempurna, oleh
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS v
HALAMAN MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
ABSTRAK viii
F. Kerangka Teoritis 11 G.Metode Penelitian 13
H.Sistematika 13
BAB II MASYARAKAT BELANDA DAN MASYARAKAT TIONGHOA DI YOGYAKARTA SERTA KRATON KASULTANAN PASCA PERJANJIAN GIYANTI TAHUN
A. Masyarakat Belanda 16 B. Sejarah Kedatangan Etnis Tionghoa 20 1. Migrasi ke Nusantara 20 2. Menetap di Yogyakarta 24 C. Pekerjaan orang-orang Tionghoa di Yogyakarta 25 D. Dualisme Pemerintah Hindia Belanda atas Orang-Orang
Tionghoa di Jawa 29
E. Kedekatan dengan Kraton 33
BAB III MENJADI BANGSAWAN DAN ELITE MASYARAKAT 37 A.Menjadi Bagian dari Kraton 42 B.Elite Masyarakat 48
BAB IV MASYARAKAT TIONGHOA DIANTARA
PENERIMAAN DAN PENOLAKAN 56 A.Hubungan Baik yang Terjalin 57 1. Pembangunan Klenteng 57 2. Menjadi Bagian dari Kraton Kasultanan Yogyakarta 59 3. Stabilitas Ekonomi dalam Perdagangan 61
4. Pendidikan 65
5. Pers 68
B.Ancaman Disintegrasi 72
1. Perdagangan 73
2. Industri 75
BAB V PENUTUP 77
Kesimpulan 77
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR TABEL
1. Jumlah pengusaha Tionghoa 26
2. Pola-pola pekerjaan masyarakat Tionghoa di Yogyakarta tahun 1808 28
3. Perbandingan Pekerjaan Pedagang dengan Non-pedagang Masyarakat
Tionghoa di Yogyakarta tahun 1808 29
4. Jumlah Kerugian Harta benda Akibat Gempa Bumi di Yogyakarta
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kedatangan orang-orang Tionghoa di Nusantara berada pada puncaknya
terjadi pada abad ke-19 dan ke-20. Perkembangan teknologi pada kapal motor,
serta telah dicabutnya larangan bepergian ke luar daerah China pada masa dinasti
Ching, memberi pengaruh besar terhadap migrasi orang-orang Tionghoa dari
daratan China ke wilayah Nusantara. Banyak di antara orang-orang Tionghoa itu
datang ke Nusantara dengan tujuan ingin memperbaiki nasib mereka, karena pada
waktu itu situasi di daratan China sangat sulit. Di Nusantara sebagian dari mereka
bekerja sebagai buruh, dan juga petani. Walaupun demikian, banyak di antara
orang-orang Tionghoa di Nusantara itu yang menjadi pedagang. Pada awalnya,
kedatangan orang-orang dari negeri China ke Nusantara terjadi karena adanya
motif perdagangan. Sehingga, dalam masa-masa sesudahnya perdagangan banyak
digeluti orang-orang Tionghoa, terutama orang Tionghoa dari sub suku bangsa
Hokkien. Hubungan perdagangan dengan negeri China sendiri telah terjadi sekitar
abad ke-16.1
Pada masa kolonial Belanda, hubungan sosial antara masyarakat Tionghoa
dengan masyarakat Jawa pada dasarnya berjalan secara harmonis. Hal inilah yang
memungkinkan terjadinya akulturasi antara mereka. Perkawinan antara orang
1
Tionghoa dengan penduduk setempat, merupakan wujud dari proses akulturasi
yang terjadi.
Pada dasarnya, dalam mata pencaharian orang-orang Tionghoa di
Nusantara, tidak melulu menjadi pedagang. Banyak di antara orang-orang
Tionghoa yang ada di Nusantara menjadi petani, tukang atau buruh, atau bahkan
menduduki jabatan pada sistem birokrasi lokal. Dalam perkembangannya,
keberadaan orang-orang Tionghoa itu dianggap membahayakan dominasi
ekonomi pemerintah Hindia Belanda. Selain bidang ekonomi, dalam bidang
politik etnis Tionghoa juga dianggap berbahaya bagi pemerintah kolonial
Belanda. Jumlah populasi mereka yang semakin berkembang, dan hubungan
mereka yang sangat baik dengan orang-orang Jawa kelas atas, adalah ancaman
yang dapat membahayakan dominasi pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena
itu, pemerintah Belanda banyak mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang
cenderung merugikan masyarakat Tionghoa. Salah satunya adalah peraturan
Zoning Stelsel yang dikeluarkan pada tahun 1863.2 Peraturan ini memaksa semua
penduduk Tionghoa di wilayah Nusantara menetap pada area yang secara khusus
diperuntukkan bagi orang Tionghoa. Area khusus bagi orang Tionghoa itu
biasanya berada di dekat pasar. Wilayah inilah yang kemudian dikenal dengan
nama pecinan. Peraturan Pemerintah kolonial Belanda ini jelas mengganggu
proses asimilasi antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat pribumi.
Peraturan tersebut telah membentengi terjadinya asimilasi antara masyarakat
2
Siauw Tiong Djin. Siauw Giok Tjha: Perjuangan seorang Patriot membangun Nasion Indonesia dan -Masyarakat Bhineka Tunggal Ika. 1999.
Tionghoa dengan masyarakat Jawa dan melahirkan citra eksklusivisme pada
masyarakat Tionghoa. Masyarakat Tionghoa diarahkan hanya untuk hal-hal yang
bersifat ekonomi saja. Zoning Stelsel telah membentuk kehidupan masyarakat
Tionghoa bahkan sampai masa sesudahnya. Sampai saat ini, banyak muncul
stereotip dari masyarakat Indonesia yang mengatakan bahwa orang-orang
Tionghoa sangat eksklusif, suka berkelompok-kelompok, menjauhkan diri dari
pergaulan sosial dan tinggal di lingkungan yang tersendiri pula.3 Di sisi lain,
peraturan tersebut mempunyai nilai positif bagi masyarakat Tionghoa sendiri.
Sadar atau tidak, peraturan inilah yang telah melesatarikan kebudayaan
masyarakat Tionghoa. Dengan adanya Zoning Stelsel, kebudayaan Tionghoa
berpeluang untuk tetap eksis.
Wilayah Zoning Stelsel di Yogyakarta dapat ditemui di kampung
Ketandan dan Pajeksan, yang terletak di sebelah utara pasar Beringharjo.
Menariknya, peraturan yang dibuat Belanda untuk etnis Tionghoa itu, tidak
menimbulkan suatu konflik sosial yang mengarah pada kerusuhan rasial dengan
penduduk setempat di daerah Kasultanan Yogyakarta. Bahkan dampak dari
Peristiwa ’65 yang banyak menempatkan orang-orang Tionghoa sebagai korban
dari strategi politik pemerintah Orde Baru hampir tidak dirasakan di Yogyakarta.
Di Yogyakarta, etnis Tionghoa dapat hidup harmonis berdampingan dengan
masyarakat sekitar.
3
Pada tahun 1812, jumlah orang Tionghoa di daerah Kasultanan
Yogyakarta mencapai 758 orang laki-laki.4 Mereka yang datang di Kasultanan
pada awalnya adalah laki-laki saja. Orang-orang Tionghoa yang hidup di daerah
Kasultanan Yogyakarta ini secara sosial berada di tempat yang dapat mendukung
Harmonisasi. Di antara orang-orang Tionghoa itu, ada yang memiliki hubungan
dekat dengan orang-orang Jawa dari kalangan atas di Yogyakarta, baik dalam
hubungan ekonomi maupun sosial.
Dalam perkembangannya hubungan baik yang terjadi antara Kasultanan
Yogyakarta dengan orang-orang Tionghoa yang tinggal di Yogyakarta menjadi
sebuah kesempatan bagi budaya Tionghoa untuk tetap menjaga eksistensinya.
Wujud dari hubungan baik itu terlihat dari berdirinya klenteng-klenteng di tanah
milik Kasultanan Yogyakarta. Bukanlah suatu hal yang mudah untuk mendirikan
sebuah bangunan yang berhubungan erat dengan budaya non-Jawa seperti
kelenteng, tanpa ijin atau campur tangan penguasa tanah, dalam hal ini pihak
Kasultanan Yogyakarta.
Salah satu wujud dari kebudayaan adalah kebudayaan fisik. Kebudayaan
fisik merupakan sebuah hasil dari aktifitas, atau karya manusia dalam
masyarakatnya.5 Klenteng merupakan manifestasi sebuah kebudayaan fisik yang
berhubungan erat dengan proses lahirnya kebudayaan yang memuat ideologi dan
adat-istiadat. Proses akal budi manusia yang akhirnya melahirkan apa yang
4
Peter Carey, op. cit., Hal.35
5
dinamakan kebudayaan fisik. Bagi kelompok masyarakat Tionghoa perantauan
yang jauh dari tanah asalnya, menciptakan sebuah kebudayaan fisik seperti
Klenteng tidaklah mudah. Mereka perlu dukungan dari penguasa ataupun
kelompok masyarakat mayoritas di lingkungannya.
Klenteng adalah sebuah bangunan tempat peribadatan masyarakat
Tionghoa, yang pada abad ke-19 dan ke-20 banyak ditemukan di sekitar wilayah
Pecinan. Sebutan “klenteng” sendiri pada dasarnya merupakan sebuah nama yang
lahir di Nusantara. Di negara lain seperti Malaysia, Philipina, dan Singapura
istilah klenteng tidak ditemukan. Istilah Klenteng kemungkinan berasal dari suara
lonceng yang kerap kali terdengar dari tempat tersebut. Sebelum dikenal dengan
sebutan Klenteng, tempat peribadatan tersebut pada mulanya disebut: Bio, Kiong,
Tong, Ting, Si.6
Di Yogyakarta terdapat dua klenteng yakni klenteng Kwan Tee Kiong atau
Cing Ling Kiong dan klenteng Ho Liong Bo. Klenteng Kwan Tee Kiong atau juga
Cing Liong Kong yang berada di jalan Poncowinatan dan didirikan pada tanggal
1 Desember 1906. Sedangkan klenteng Ho Liong Bio yang berada di jalan
Gondomanan dan didirikan pada tanggal 15 Agustus 1900.7 Kedua klenteng
Tionghoa yang ada di Yogyakarta ini didirikan oleh kaum Tionghoa yang
memiliki hubungan yang dekat dengan orang Jawa dari kalangan atas. Hubungan
6
Moerthiko, ed. Riwayat Klenteng, Vihara, Lithang, Tempet Ibadah Tridharma se-Jawa. 1980. Semarang: Sidoyoso. Hal. 95-87.
7
tersebut juga membuat masyarakat Tionghoa di Yogyakarta luput dari
konflik-konflik rasial dengan kelompok masyarakat lain.
Tulisan ini berkonsentrasi pada sejarah etnis Tionghoa di Yogyakarta
selama periode tahun 1877-1920. Dalam tahun 1877-1920 merupakan periode
masa jabatan Sri Sultan Hamengku Buwana ke-VII dalam memerintah Kasultanan
Yogyakarta. Dalam sejarahnya masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwana
ke-VII merupakan titik yang paling menentukan terutama dalam pembangunan
perekonomian daerah Kasultanan Yogyakarta. Hal ini dikarenakan Sri Sultan
Hamengku Buwana VII selama masa pemerintahannya banyak menyewakan
tanah Kasultanan Yogyakarta, untuk para investor yang kemudian digunakan
sebagai pusat-pusat industri. Sehingga dalam perkembangannya, berdirinya
pabrik-pabrik gula di tanah Kasultanan Yogyakarta dapat mendorong
perekonomian di Yogyakarta. Bagi masyarakat umum keuntungan yang di dapat
adalah terbukanya lapangan pekerjaan di pabrik-pabrik gula tersebut, sedangkan
Kraton mendapatkan keuntungan yang besar dari sewa tanah pabrik-pabrik gula
tersebut. Datangnya para investor yang mendirikan pabrik-pabrik gula di
Yogyakarta mampu mengangkat perekonomian Yogyakarta. Dengan naiknya
keadaan ekonomi di Yogyakarta, pembangunan mulai dilakukan di berbagai
sektor kehidupan. Pembangunan tersebut bahkan juga sampai pada masalah religi
masyarakat. Dalam periode ini berdiri dua Klenteng yang letaknya berada di pusat
kota Yogyakarta. Sehingga melalui periode yang berpengaruh bagi kehidupan
tentang sejarah dinamika masyarakat Tionghoa yang hidup di tengah masyarakat
lain di Yogyakarta.
B. Permasalahan
Ada sebuah pameo yang mengatakan bahwa barang siapa ingin mengenal
“manusia sekarang” maka sebaiknya berusahalah untuk mengenal “manusia
lama”. Oleh sebab itu, dalam rangka melihat kembali proses lahirnya identitas
kolektif di dalam masyarakat di Yogyakarta, maka tulisan ini akan memusatkan
perhatian pada sejarah etnis warga Tionghoa di Yogyakarta. Permasalahan yang
akan menjadi perhatian dapat didalami melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai
berikut:
1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat Tionghoa yang tinggal di daerah
Yogyakarta tidak banyak menghadapi konflik sosial yang mengarah pada
kerusuhan rasial dengan kelompok masyarakat lain di lingkungannya?
2. Bagaimana dinamika sosial kebudayaan masyarakat Tionghoa di daerah
keraton Kasultanan Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh keberadaan masyarakat Tionghoa di Yogyakarta bagi
lingkungan sosial di sekitarnya?
C. Tujuan
1. Akademis
Secara Akademis, tujuan dari penulisan ini adalah mendokumentasikan
Melalui tulisan ini diharapkan mampu menambahkan wacana tentang sejarah etnis
Tionghoa dalam khasanah sejarah Indonesia. Tulisan ini juga diharapkan mampu
mereduksi steriotip masyarakat Indonesia mengenai etnis Tionghoa-Indonesia
yang dianggap etnis yang “berbeda” dengan Indonesia.
2. Praktis
Penulisan ini berusaha melakukan pengkajian sejarah etnis Tionghoa di
Yogyakarta pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwona VII yakni
tahun 1877-1920. Dalam kerangka tersebut, fokus diarahkan pada bagaimana
eksistensi kebudayaan Tionghoa dipertahankan melalui tataran sosial, ekonomi,
ataupun intelektual. Dengan demikian diharapkan identitas masyarakat Tionghoa
mampu dibaca melalui kacamata sejarah etnis Tionghoa di Yogyakarta.
D. Manfaat
1. Manfaat Teoretis
Tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi
perkembangan penulisan sejarah etnis Tionghoa di Nusantara, dimana pada era
pasca Orde Baru tulisan mengenai sejarah etnis Tionghoa mulai di kaji kembali.
Minimnya tulisan mengenai sejarah etnis Tionghoa membuat sejarah tidak
mengakomodasi semangat kebersamaan, persatuan, dan kesatuan dalam berbangsa
dan bernegara. Bhineka Tunggal Ika hendaknya dipahami sebagai landasan
berpikir untuk mereduksi banyaknya steriotip negatif mengenai etnis
2. Manfaat Praktis
Penulisan ini diharapkan dapat memotret serta memberikan interpretasi
yang objektif mengenai situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan etnis
Tionghoa di Yogyakarta pada masa lalu. Orang-orang Tionghoa di Yogyakarta
telah berusaha mengangkat kebudayaan Tionghoa, berdampingan dengan
kebudayaan Jawa pada masa pemerintahan Hamengku Buwana VII, baik melalui
bidang ekonomi, sosial, ataupun intektual. Tulisan ini juga diharapkan
mempunyai daya guna dalam upaya memberikan sudut pandang lain dari sejarah
dinamika kehidupan masyarakat di Yogyakarta.
E. Tinjauan Pustaka
Kepustakaan yang senada dengan tulisan ini adalah buku dengan judul
Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930 karya Abdurrachman
Surjomihardjo. Dalam buku Kota Yogyakarta Tempo Doeloe ini dibahas
mengenai sejarah kota Yogyakarta dari tahun 1880-1930. Ditinjau dari periode
yang dipilih, buku hampir sama dengan periode yang digunakan dalam tulisan
berjudul Masyarakat Tionghoa di Yogyakarta ini, yakni tahun 1877-1920, serta
keduanya sama-sama melakukan pembahasan pada daerah Yogyakarta. Hanya
saja, dalam buku Kota Yogyakarta Tempo Doeloe, merupakan buku sejarah kota,
sehingga dari buku ini tidak dibahas secara rinci mengenai bagaimana dinamika
sosial, yang meletakkan hubungan sosial-kebudayaan yang terjadi antara
kelompok masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Jawa, Belanda, di Yogyakarta
Kepustakaan yang lain adalah buku berjudul Orang Jawa dan Masyarakat
Cina (1755-1825) karya Peter Carey. Buku Orang Jawa dan Masyarakat Cina
(1755-1825) ini membahas mengenai bagaimana hubungan sosial, ekonomi, serta
politik antar orang-orang Jawa dan masyarakat Tionghoa. Hubungan yang terjadi
antar kedua kelompok tersebut telah menempatkan orang-orang Tionghoa dalam
penerimaan masyarakat. Bahkan hubungan baik antara orang-orang Tionghoa
dengan Kraton telah terjadi setelah perjanjian Giyanti yang melahirkan kraton
Yogyakarta. Yang membedakan buku karya Peter Carey ini dengan tulisan
Masyarakat Tionghoa di Yogyakarta ini adalah perbedaan konsentrasi pada
periode. Sebab, periode buku Orang Jawa dan Masyarakat Cina adalah
1755-1825. Sehingga dalam periode itu tidak membahas bagaimana pengaruh politik
Etis Belanda yang dalam masa sesudahnya melahirkan elit-elit yang turut
mewarnai dinamika sosial-budaya Yogyakarta.
Selain kedua pustaka di atas, ada pula buku berjudul Identitas dan
Postkolonialitas di Indonesia. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dimana Budi
Susanto, S.J. menjadi editornya. Di dalam salah satu bagian dari buku tersebut ada
karya dari Abdul Wahid dengan judul Proses Menjadi (Tidak) Indonesia?
Persepsi dan Memori Massa-Rakyat Tionghoa di Yogyakarta. Dalam tulisan
karya Abdul Wahid ini dipaparkan mengenai sejarah masyarakat Tionghoa di
Yogyakarta dengan melalui konflik-konflik yang pernah terjadi di masa silam
untuk membangun kembali identitas di masa kini. Yogyakarta yang cenderung
terbebas dari kerusuhan masa yang mengarah pada konflik rasial tentu bukan
Hal tersebut dikarenakan konflik merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan
dari kehidupan sosial. Akan tetapi yang membedakan tulisan Abdul Wahid ini
adalah pada konsentrasi periodesasi. Dalam Tulisan Abdul Wahid konflik yang
dituliskan dapat dibagi kedalam masa: Kolonialisme, atau tepatnya pada masa Tan
Jing Sing diangkat menjadi Bupati, pada masa pendudukan Jepang, tahun 1965,
dan 1998. Sehingga yang membedakan adalah ada periode kontemporer yang
dicantumkan. Selain itu, tulisan Abdul Wahid tidak memberikan analisa secara
lengkap terhadap periode tahun 1877-1920.
F. Kerangka Teoretis
Tulisan ini akan didasarkan atas pemikiran bahwa lahirnya kebudayaan
baru tidak melulu terjadi karena adanya perencanaan manusia secara sadar.
Realitas masyarakat telah menjaga untuk mengembangkan kebudayaan mereka
sendiri, dan hampir tanpa disadari oleh masyarakatnya. Kebudayaan secara
konstan dan otomatis dalam konteks pertemuan dua budaya atau lebih dalam
satuan wilayah, akan menawarkan sebuah integrasi. Dalam sudut pandang lain,
integrasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi kalangan atau golongan yang
mendapatkan keuntungan melalui integerasi, dalam hal ini adalah golongan
minoritas. Hal ini terjadi karena melalui integrasi golongan minoritas dapat
menjaga eksistensi mereka.
Pada dasarnya integrasi merupakan sebuah proses dalam kehidupan
sosial-budaya manusia yang akan terus berkembang seiring perubahan jaman. Integrasi
mereka dalam kehidupan. Pada saat suatu masyarakat “diserang” oleh masalah
secara konstan dan akhirnya mereka akan mencoba untuk mempertahankan
eksistensi mereka. Sehingga akhirnya integrasi adalah bagian dari perjuangan dan
perlawanan masyarakat untuk suatu eksistensi.8
Integrasi terjadi tidak melulu karena adanya penerimaan dari kedua pihak.
Integrasi juga dapat terjadi karena adanya keinginan dari salah satu pihaknya
dalam rangka mewujudkan kepentingan tertentu. Oleh karenanya proses
terjadinya integrasi dapat terwujud karena adanya kepentingan dari salah satu
kelompok yang berusaha mempertahankan eksistensi mereka.
Fokus kajian untuk melihat bagaimana masyarakat etnis Tionghoa
berusaha menjaga eksistensinya adalah dalam kurun waktu 1877-1920, dimana di
Yogyakarta pada masa itu dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwana VII.
Bagaimana kebudayaan Tionghoa yang ada “terjaga” dalam daerah Zoning Stelsel
membuat mereka berusaha eksis, dan puncaknya adalah berdirinya dua Klenteng
di Yogyakarta. Pembuatan Klenteng di tengah kota adalah bagian dari simbol
yang mengarah pada terjadinya integrasi. Hal ini merupakan bukti telah terjadi
integrasi antara masyarakat Tionghoa di Yogyakarta dengan masyarakat Jawa
pada umumnya, serta Kraton Kasultanan Yogyakarta. Walaupun demikian
integrasi yang terjadi tersebut juga merupakan sebuah usaha suatu kelompok
minoritas dalam rangka mempertahankan eksistensi mereka di dalam kehidupan
bersama kelompok masyarakat yang lebih besar. Hal tersebut juga berlaku
8
terhadap kelompok masyarakat Tionghoa di Yogyakarta, yang berusaha masuk
dalam simbol-simbol yang ada dalam sistem sosial ataupun kebudayaan Jawa
untuk tujuan integrasi.
G. Metode Penelitian
Metode sejarah digunakan oleh para sejarawan dalam rangka melakukan
penelitian serta penulisan sejarah. Tulisan ini menggunakan metode penelitian
sejarah yang terdiri dari: Pemilihan Subyek Kajian, Heuristik, Kritik, Sintesa, dan
Historiografi.9 Heuristik merupakan usaha pengumpulan sumber yang berkaitan
dengan permasalahan yang diteliti. Dalam tahap pengumpulan data akan
dilakukan dengan cara studi pustaka pada bidang terkait. Selain dengan
melakukan studi pustaka sebagai pengumpulan data utama, penelitian ini juga
akan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan kelompok etnis Tionghoa
di Yogyakarta. Wawancara yang dilakukan diharapkan mampu membantu
menggambarkan pola-pola integrasi yang ada di masyarakat sekarang dan
merupakan warisan masa lalu. Sehingga menjadi sebuah proyeksi ke belakang
untuk melihat masa lalu.
Tahapan selanjutnya adalah Kritik. Kritik merupakan proses pengujian
sumber-sumber yang telah terkumpul untuk mengetahui kredibilitas fakta dan
keaslian sumber. Sehingga melalui tahapan kritik sumber ini, didapatkan sumber
yang mampu menjawab permasalahan yang ada. Tahapan selanjutnya adalah
9
usaha penggabungan fakta-fakta berdasar kronologis dan sebab akibatnya. Tahap
ini disebut dengan sintesa. Sedangkan tahap terakhir adalah historiografi. Pada
tahap historiografi ini akan dilakukan perangkaian fakta-fakta yang didapat dan
telah disintesakan sebelumnya. Tahap ini merupakan tahap terakhir yang
dilakukan dalam rangka menuliskan peristiwa sejarah.
H. Sistematika
Dalam Bab I berisi mengenai pendahuluan penulisan. Bab ini, memuat
Kerangka konseptual yang membangun dan memagari penulisan ini. Adapun
dalam Bab I, berisikan Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan dan Manfaat,
Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoritis, Metode penelitian, dan Sistematika
penulisan.
Bab II berjudul Masyarakat Belanda dan Masyarakat Tionghoa di
Yogyakarta serta Kraton Kasultanan Pasca Perjanjian Giyanti Tahun 1755. Bab
ini merupakan pemetaan dari setiap elemen yang ada dalam konteks sejarah etnis
Tionghoa di Yogyakarta tahun 1877-1920. Dalam Bab ini mengunakan periode
pasca perjanjian gityanti yakni tahun 1755. Hal tersebut dikarenakan perjanjian
giyanti adalah titik penting yang kemudian melahirkan Kraton Kasultanan
Yogyakarta. Dengan lahirnya Kraton maka banyak orang yang datang untuk
berdagang dan kemudian menetap di Yogyakarta. Oleh karena itu, Bab II
merupakan sejarah kedatangan etnis Tioonghoa di Yogyakarta yang juga menjadi
Bab III berjudul Mejadi Bangsawan dan Elite Masyarakat. Bab III secara
khusus membahas tentang dinamika integrasi yang terjadi antara kelompok
masyarakat Tionghoa di Yogyakarta dengan masyarakat Yogyakarta sendiri.
Proses integrasi yang terjadi itu kemudian direpresentasikan oleh masuknya
orang-orang Tionghoa ke dalam lingkungan Kraton Kasultanan Yogyakarta, atau
dengan pengangkatan gelar kebangsawanana, serta melalui sektor-sektor sosial
kebudayaan.
Bab IV berjudul Masyarakat Tionghoa di antara Penerimaan dan
Penolakan. Bab ini menuliskan mengenai penerimaan dan penolakan masyarakat
Tionghoa yang merupakan dampak dari pengaruh keberadaan masyarakat
Tionghoa yang kian lama kian mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang
kian besar. Penerimaan dan penolakan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat
Tionghoa oleh karena konstrusi sosial yang telah dibangun di dalam masyarakat.
Bab V, adalah Penutup. Dalam Bab V ini dituliskan mengenai kesimpulan
BAB II
MASYARAKAT BELANDA DAN MASYARAKAT TIONGHOA
DI YOGYAKARTA SERTA KRATON KASULTANAN PASCA
PERJANJIAN GIYANTI TAHUN 1755
Setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, Kerajaan Mataram terpecah
menjadi dua yakni Kasunanan Surakarta dengan Kasultanan Yogyakarta. VOC,
sebuah perusahaan dagang dari negeri Belanda, memegang peran utama atas
terjadinya perjanjian Giyanti tersebut. Muatan politik bagi kepentingan kekuasaan
Belanda sangat kental mewarnai perjanjian tersebut. Dengan adanya perjanjian
Giyanti, Belanda Bahkan Belanda dapat melakukan intervensi politik, bahkan
sampai menyentuh ke dalam sistem pemerintahan Kerajaan Mataram yang
terpecah itu. Salah satu isi dari perjanjian Giyanti menyebutkan bahwa dalam
pergantian Raja, seorang calon Raja memerlukan persetujuan dari Belanda.1 Hal
ini menyebabkan Belanda menjadi pemegang supremasi kekuasaan yang paling
mendominasi di pulau Jawa.
A. Masyarakat Belanda
Masyarakat Belanda ataupun juga orang-orang Eropa lainnya merupakan
kelompok masyarakat yang berada pada level paling atas dari struktur masyarakat
kolonial. Masyarakat kolonial dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok
berdasarkan etnis atau suku. Orang-orang Belanda yang berada di Yogyakarta,
1 G. Moedjanto.
pada umumnya bermatapencaharian sebagai pegawai-pegawai pemerintah,
pengusaha perkebunan, pengusaha dibidang industri, dan juga pedagang.
Abad ke-19, merupakan masa yang cukup berat bagi negeri Belanda yang
disebabkan oleh situasi politik di dalam negeri yang tidak kondusif.2 Disamping
itu, di jawa juga terjadi pergolakan hebat dengan terjadinya perang besar yang
dinamakan Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 - 1830. Perang tersebut
telah banyak merugikan Belanda. Kemudian terjadi suksesi dimana Raja William
II digantikan oleh anaknya William III yang memerintah dari tahun 1849-1890.
Untuk meningkatkan laju perekonomian negeri Belanda, pada masa itu dibuatlah
kebijakan-kebijakan atau strategi politik kolonial dengan maksud agar dapat
diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kejayaan Negeri Belanda.
Kebijakan-kebijakan kolonial tersebut kemudian berdampak secara langsung pada
proses integrasi antar etnis di Hindia Belanda.
Kolonial Belanda menganut sistem politik apartheid.3 Dalam sistem
politik tersebut, masyarakat kolonial dibagi kedalam tiga golongan yang
membentuk hierarki vertikal. Dalam strata menurun masyarakat Hindia Belanda
dibagi dalam golongan-golongan yang berbeda yaitu: golongan Eropa atau
orang-orang Belanda; golongan Timur Asing yang termasuk didalamnya masyarakat
2
Lihat, FL. Hasto Rosariyanto, SJ. Van Lith Pembuka Pendidikan Guru di Jawa. 2009. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma. Hal. 20-21
3
Tionghoa, Arab, India, dan yang terakhir adalah golongan masyarakat pribumi.
Menurut Onghokham, bahkan golongan pribumi di bedakan lagi berdasarkan
suku-suku. Karena pengkotak-kotakan itu, menyebabkan pada masa itu banyak
masyarakat yang mengelompokkan diri atau terkelompokkan berdasarkan
sukunya. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya daerah atau wilayah yang diberi
nama sesuai dengan nama suku, misalnya kampung Melayu, Kampung Ambon,
pecinan, dan lain sebagainya.
Yogyakarta adalah sebuah tempat yang mempertemukan dua kekuasaan,
yakni kekuasaan kolonial dan juga kekuasaan tradisional. Kasultanan Yogyakarta
menjadi kekuasaan tradisional setelah ditandatanganinya perjanjian giyanti pada
tahun 1755. Kemudian dalam proses perjalanannya, pelaksanaan perjanjian
tersebut tetap diawasi oleh Pemerintah kolonial Belanda. Sejak saat ini
Pemerintah kolonial Belanda mulai melakukan usaha-usahanya yang dilakukan
dalam rangka mewujudkan kepentingan kolonialismenya. Dalam
perkembangannya kekuasaan Pemerintah kolonial Belanda terus menunjukkan
dominasinya.
Bagi pihak Belanda, Sultan Yogyakarta dianggap cukup membahayakan
posisi Belanda. Menurut Vincent J. H. Houben, pada periode sekitar tahun 1755
Sultan diharuskan untuk berjanji tidak akan melakukan klaim apapun atas tanah
milik Pemerintah Hindia Belanda atau Susuhunan dari Keraton Surakarta, tidak
berusaha mencari gara-gara pada kedua pihak tersebut dan juga dengan
pangeran-pangeran independen, dan diharuskan menyerahkan orang-orang yang telah
Belanda.4 Pemerintah Hindia Belanda melakukan strategi politik ini ialah untuk
mereduksi setiap kemungkinan dari kekuasan Kasultanan Yogyakarta yang makin
besar. Bagi Pemerintah Kolonial Belanda, Kasultanan Yogyakarta dianggap
memiliki potensi dalam mewujudkan persatuan di Pulau Jawa dibawah kekuasaan
Kasultanan Yogyakarta. Apabila itu terjadi sudah barang tentu akan
menyingkirkan Belanda dari tanah Jawa.
Sedangkan dengan orang-orang Tionghoa, Belanda ingin memelihara
hubungan baik karena adanya kepentingan dalam perdagangan. Menurut
Onghokham, Belanda yang datang ke Nusantara dalam rangka melakukan
perdagangan sangat membutuhkan mitra untuk berdagang terutama mengingat
jumlah orang-orang Belanda yang datang ke Nusantara tergolong sedikit.5 Jumlah
orang-orang Belanda yang sedikit itu kemudian mendorong Belanda mencari
mitra dagang yang dapat mendistribusikan dagangannya hingga pelosok pedesaan
di Jawa. Orang-orang Tionghoa yang sudah ada di Nusantara adalah orang-orang
yang pandai berdagang dan dapat berinteraksi dengan masyarakat lokal. Dengan
bekerjasama dengan orang-orang Tionghoa tersebut, Belanda akan mendapatkan
banyak keuntungan. Bagi pemerintah Hindia Belanda orang-orang Tionghoa
memiliki peran penting dalam membangun basis perekonomian yang dapat
memberikan keuntungan dari koloni di Hindia Belanda, khususnya Jawa.
4
Vincent J. H. Houben. Keraton dan Kompeni; Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870. 2002. Yogyakarta: Bentang. Hal. 274
5
B. Sejarah kedatangan Tionghoa
1. Migrasi ke Nusantara
Kedatangan kelompok masyarakat Tionghoa dari negeri China jauh lebih
lama dari pada kedatangan orang-orang Belanda di Nusantara.6 Secara geografis
letak wilayah Nusantara yang berada pada jalur perlayaran dan perdagangan
internasional menjadikan Nusantara sebagai tempat yang banyak dikunjungi
orang-orang Tionghoa dan kelompok masyarakat lain di dunia. Tidak semua
masyarakat Tionghoa yang datang ke Nusantara memutuskan untuk tinggal atau
menetap di Nusantara. Migrasi orang-orang Tionghoa di China menuju Nusantara
pada umumnya dilakukan secara bersama-sama atau sering dinamakan bedol desa.
Namun ada pula yang melakukan migrasi dalam kelompok kecil atau bahkan
perorangan. Meskipun migrasi orang-orang Tionghoa sudah lama terjadi, tetapi
akibat konstruksi politik yang dibangun kolonial Belanda membuat semua hal
yang berkaitan dengan masalah orang-orang Tionghoa terutama dewasa ini di
Indonesia, menjadi seolah dimulai bersamaan dengan kolonialisme Belanda yang
ada di Nusantara.
Motivasi yang melatarbelakangi migrasi yang dilakukan orang-orang
Tionghoa dari negeri China ke Nusantara adalah harapan akan kehidupan yang
lebih baik. Sebelum abad ke-19, alat transportasi laut belum begitu berkembang.
Untuk melakukan perjalanan antar pulau dengan kapal, orang harus berjuang
6 Catatan sejarah mengatakan bahwa perjalanan pertama kali bahkan sudah
menempuh bahaya selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Tanpa harapan
akan kehidupan yang lebih membahagiakan, mustahil seseorang mau melakukan
perjalanan yang panjang dan penuh resiko itu.
Menurut Onghokham, Belanda dan juga China berasal dari sebuah
peradaban yang hampir sama. Kesamaan itu ditunjukkan dari latar belakang kota
yang dikelilingi oleh “dinding”. Sehingga pada dasarnya keduanya merupakan
penduduk urban atau penduduk kota. Datangnya orang-orang Tionghoa dan juga
Belanda pada pada umumnya dilakukan dalam rangka berdagang. Dalam
perkembangannya karena mereka berkecimpung dalam bidang yang sama, banyak
orang-orang Tionghoa yang kemudian menjadi mitra dagang Belanda.7 Hal ini
kemudian yang juga turut berperan, terutama dalam bidang-bidang perdagangan
yang terjadi di Nusantara
Perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa di Nusantara
sebenarnya sudah terjadi sejak abad ke-7. Akan tetapi, baru mengalami
perkembangan yang besar pada abad ke-19. Hal ini dikarenakan di pertengahan
abad ke-19 terjadi peningkatan migrasi yang sangat besar. Menurut Siauw Tiong
Djin, kebanyakan masyarakat Tionghoa yang bermigrasi berasal dari China
bagian selatan. Mereka memilih untuk meninggalkan tanah kelahirannya untuk
mengadu nasib di tanah seberang karena keadaan ekonomi China yang sangat
parah terutama karena dampak pemberontakan Tai Ping.8 Di antara
kelompok- 7
Onghokham. loc. cit
8
kelompok masyarakat Tionghoa yang pergi meninggalkan tanah kelahirannya,
banyak yang memilih Hindia Belanda sebagai tujuannya. Hindia Belanda
dianggap tempat yang dapat memberikan harapan masa depan yang menjanjikan,
karena pada waktu itu investasi Belanda mengalami perkembangan pesat terutama
setelah dibukanya perkebunan dan pertambangan di wilayah Sumatra dan
Kalimantan.
Migrasi besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa dari
China ke seluruh pelosok wilayah Nusantara atau Hindia Belanda, dimulai pada
abad ke -16 hingga akhir abad ke-19. Menurut Puspa Vasanty, orang-orang
Tionghoa yang bermigrasi itu kebanyakan berasal dari suku-suku di dua propinsi
negeri China yakni propinsi Fukie dan Kwangtung.9 Masyarakat Tionghoa
bukanlah sebuah entitas satu suku, tetapi di dalamnya penuh dengan
keberagaman. Sehingga untuk dapat memahami sejarah masyarakat Tionghoa,
perlu untuk mengenal latarbelakang mereka secara lebih dalam.
Imigran dari China yang berasal dari bermacam-macam kolompok etnis
tersebut, datang ke Nusantara dengan membawa kebudayaan setiap sukunya
masing-masing. Kebudayaan yang mereka bawa dari tanah asal mereka itu dalam
perkembangannya turut menjadi sebuah strategi kebudayaan dalam
mempertahankan eksistensi mereka, terutama dalam mempertahankan hubungan
sosial antara masyarakat pribumi kelas atas dan masyarakat kolonial Belanda. Hal
itu terutama terjadi dalam kaitannya dengan dunia perekonomian. Di seluruh
9
gugusan kepulauan Nusantara, yang kemudian setelah proklamasi kemerdekaan
17 Agustus 1945 menjadi Negara Republik Indonesia, terdapat empat bahasa dari
suku-suku di China yang dapat ditemukan. Empat bahasa tersebut adalah:
Hokkien, Teo-Chiu, Hakka, dan Kanton. Bahasa-bahasa tersebut berbeda satu
dengan lainnya walaupun keempatnya sama-sama berasal dari negeri China.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di seluruh Nusantara terdapat empat
suku besar yang berasal dari negeri China. Oleh karenanya, banyak di atara
orang-orang Tionghoa yang memakai bahasa dari tanah leluhur mereka tidak bisa atau
tidak mengerti pembicaraan antar satu suku dengan suku yang lainnya.
Pada umumnya, orang-orang Tionghoa yang tinggal di daerah Jawa Timur,
Jawa Tengah, dan pantai barat Sumatra adalah orang Tionghoa dari suku
Hokkien. Sesuai dengan kebudayaan asalnya, orang-orang dari suku Hokkien ini
sangat maju dalam bidang perdagangan. Konstruksi kebudayaan itu juga yang
membuat orang-orang Tionghoa yang berasal dari suku Hokkien menjadi
pedagang yang paling berhasil jika dibandingkan dengan masyarakat suku-suku
China lain yang tinggal di Nusantara. Sementara orang-orang Tionghoa dari suku
Teo-Chiu dan Hakka atau Khek, dahulu pada awalnya banyak bekerja sebagai kuli
perkebunan dan pertambangan di Sumatra Timur, Bangka. Sedangkan suku
Hakka adalah suku yang memiliki kebudayaan maritim yang kuat. Orang-orang
Tionghoa dari suku Hakka banyak bekerja di bidang kemaritiman. Seperti
diketahui, migrasi yang mereka lakukan umumnya berdasarkan kebutuhan akan
mata pencarian untuk kehidupan mereka. Orang-orang Hakka berasal dari
orang-orang Hakka yang terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1850 sampai tahun
1930, menempatkan orang-orang Hakka sebagai imigran termiskin imigran lain.
Sebaliknya orang-orang dari suku Kanton atau Kwong Fu mereka datang dengan
membawa modal besar dan dengan kemampuan teknis yang tinggi. Orang-orang
dari suku Kanton dalam abad ke-19 banyak datang ke wilayah pulau Bangka
karena pertambangan timahnya.10 Di daerah Asia Tenggara terkenal sebagai kuli
pertambangan.
2. Menetap di Yogyakarta
Setelah Kasultanan Yogyakarta berdiri tahun 1756, banyak orang-orang
dari berbagai penjuru Nusantara datang di Yogyakarta. Kedatangan mereka pada
umumnya adalah dalam rangka berdagang. Kemudian, dalam perkembangan
selanjutnya para pedagang tersebut banyak yang kemudian memilih untuk
menetap di Yogyakarta. Di antara para pendatang tersebut adalah orang-orang
Tionghoa.11 Dalam masa-masa awal ini, sebagian besar dari orang-orang
Tionghoa yang menetap di Yogyakarta merupakan kaum laki-laki yang berusia
empat belas tahun ke atas.12
10
Ibid., Hal. 353-354
11
Darmasugito. 200 tahun kota Yogyakarta ( 7-10-1756 – 7-10-1956).
1956. Yogyakarta: Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 tahun kota Yogyakarta Sub Panitia Penerbitan. Hal.7
12 Peter Carey.
Pada awalnya oleh penguasa Belanda, orang-orang Tionghoa yang
menetap di Yogyakarta dipusatkan di sekitar sebelah utara pasar Gede. Kemudian
dalam perkembangan yang lebih lanjut, pada tahun 1867 pemukiman komunitas
Tionghoa atau yang dikenal dengan nama pecinan telah menyebar di
daerah-daerah seperti: Ketandan, Gandekan, Ngabean, Ngadiwinatan, Suronatan, Gading,
Ngasem, wilayah patuk utara hingga wilayah antara rel kereta api dan tugu
Yogyakarta.13
Dalam tulisannya, Darmosugito berpendapat bahwa pada mulanya,
orang-orang Tionghoa tinggal di daerah kampung Kranggan.14 Seiring dengan
pertumbuhan penduduk orang-orang Tionghoa yang makin bertambah dengan ijin
Kasultanan mereka kemudian diperbolehkan menempati daerah selatan kampung
Kranggan hingga batas pasar Gede.15 Keberadaan orang-orang Tionghoa di
Yogyakarta yang menempati daerah-daerah di dekat pusat perekonomian
Yogyakarta, secara langsung maupun tidak langsung telah turut membangun
perekonomian Yogyakarta.
13
Rezza Maulana. Dari ‘Muslim Tionghoa’ ke ‘Tionghoa Muslim’: Perjumpaan Tionghoa dengan Islam di Nusantara Abad XVI-XXI. Hal. 43-44
14
Darmasugito, op. cit., Hal. 23
15
C. Pekerjaan orang-orang Tionghoa di Yogyakarta
Perdagangan adalah lapangan pekerjaan yang paling penting bagi
orang-orang Tionghoa. Hal ini terutama terjadi karena bagi orang-orang Tionghoa perdagangan
adalah lapangan pekerjaan yang paling memungkinkan untuk dijalani di Hindia
Belanda. Walaupun, di China orang-orang Tionghoa banyak yang bekerja menjadi
petani, akan tetapi di Hindia Belanda terutama di Jawa adalah sesuatu yang
hampir mustahil menjadi seorang petani yang dapat memenuhi permintaan pasar.
Hal itu terjadi karena adanya larangan kepemilikan tanah bagi orang Tionghoa.16
Dalam tabel berikut terlihat jelas bagaimana perdagangan adalah lapangan
pekerjaan yang penting bagi orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda hingga
tahun 1930.
Sumber diolah dari Ong Eng Die yang diambil dari kumpulan data dari Volkstelling 1930, jilid VIII.
16
Ong Eng Die. Peranakan Orang Tionghoa dalam Perdagangan, dalam Mely G. Tan, ed. 1998. Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Satu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa. Jakarta: Gramedia. Hal. 30
17
Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas, orang-orang Tionghoa yang
tinggal di Hindia Belanda, mayoritas berada di pulau Jawa dan Madura. Bahkan
pada tahun 1930 populasi orang Tionghoa yang berada di Pulau Jawa dan Madura
telah mencapai 100.109 jiwa. Sedangkan di wilayah Sumatra cenderung lebih
sedikit jumlah pedagangnya, karena banyak orang Tionghoa di wilayah tersebut
bekerja sebagai buruh di perkebunan atau pertambangan milik Belanda.
Peraturan-peraturan pemerintah kolonial cenderung mempersempit ruang
gerak orang-orang Tionghoa. Orang-orang Tionghoa tidak dapat memiliki tanah,
bahkan ruang gerak mereka dipersempit dengan adanya peraturan surat jalan serta
mereka dikelompokkan dalam pemukiman yang telah ditentukan oleh pihak
Belanda. Dengan keadaan yang mengekang kebebasan mereka tersebut, membuat
mereka banyak yang mencari nafkah dalam bidang di luar pertanian. Bidang
perdagangan menjadi bidang yang banyak digeluti orang-orang Tionghoa. Hal
tersebut terutama dalam bidang pedagang perantara.18 Posisi demikian membuat
orang-orang Tionghoa memiliki peranan penting dalam perdagangan di Hindia
Belanda. Peran tersebut dapat dilihat melalui orang-orang Tionghoa yang banyak
menjadi mitra dagang Belanda untuk menjadi pedagang perantara ke pelosok
pedesaan. Dengan adanya pedagang yang menjadi perantara, barang-barang
perdagangan dapat disalurkan pada para konsumen. Selain itu, keadaan demikian
membuat orang Tionghoa memiliki hubungan yang dekat dengan
orang-orang Jawa kalangan atas. Hal tersebut terjadi karena orang-orang-orang-orang Jawa kalangan
18
atas banyak yang memiliki kepentingan dalam bidang perdagangan. Dengan
demikian, orang-orang Tionghoa memiliki peran yang besar dalam membangun
perekonomian di Hindia Belanda.
Mata pencaharian orang-orang Tionghoa di Yogyakarta pada tahun 1808
dapat tergambar dengan jelas melalui catatan dalam aktivitas pembayaran pajak
tetap. Orang yang mengurusi serta bertanggung jawab atas seluruh masyarakat
Tionghoa disebut sebagai kapitan China.19 Tabel berikut akan menggambarkan
bagaimana pola-pola pekerjaan orang-orang Tionghoa yang ditemui di
Yogyakarta.
Tabel 2
Pola-pola Pekerjaan Masyarakat Tionghoa di Yogyakarta Tahun 180820
No. Pekerjaan Jumlah
1 Kapitan China 2
2 Penjaga gerbang tol 48 3 Kuli pelaksana pekerjaan pada gerbang tol 219 4 Pedagang serta pedagang perantara 397
5 Penyewa tanah 36
13 Masyarakat yang belum bekerja 34
19
Lihat Puspa Vasanty. op. cit., Hal. 365-367, setiap kelompok etnis Tionghoa di suatu daerah, dianggkat seorang yang dipilih dari masyarakat itu sebagai pimpinan oleh pemerintah Belanda. Peminpin-pemimkpin itu memakai pangkatg majjor, kapiten, luitenant dan wijkmeester. Orang-orang itu bertugas menghubungkan antara orang Tionghoa dengan pemerintah Belanda.
20
Jumlah penduduk Tionghoa keseluruhan 758
Sumber diolah dari Peter Carey. Orang Jawa dan Masyarakat China (1755-1825). 1986. Jakarta: Pustaka Azet. Hal. 38-39
Tabel 3
Perbandingan Pekerjaan Pedagang dengan Non-pedagang Masyarakat Tionghoa di Yogyakarta tahun 180821
Jumlah Persentase
Pedagang 397 54, 83
Non-pedagang 327 45, 17
Sumber diolah dari Peter Carey. Orang Jawa dan Masyarakat China (1755-1825). 1986. Jakarta: Pustaka Azet. Hal. 38-39
Keaneka-ragaman pekerjaan orang-orang Tionghoa yang ada di
Yogyakarta, seperti yang terlihat dalam tabel 2, merupakan wujud keberagaman
yang terbangun dalam dinamika kehidupan sosial di Yogyakarta. Orang-orang
Tionghoa yang menjadi pedagang jumlahnya tetap lebih banyak dari jumlah
orang-orang Tionghoa yang bermatapencaharian di luar pedagang. Dalam tabel
tiga terlihat bagaimana masyarakat Tionghoa yang menjadi pedagang jumlahnya
lebih dari setengah jumlah keseluruhan masyarakat Tionghoa yang ada di
Yogyakarta. Bahkan orang-orang Tionghoa yang bermatapencaharian sebagai
pedagang dan pedagang perantara jumlahnya telah mencapai 397 orang.
Masuknya orang-orang Tionghoa dalam berbagai elemen yang ada di masyarakat
mewujudkan integrasi yang telah terbangun di dalamnya. Hubungan baik antara
orang-orang Jawa dengan orang-orang Tionghoa di Yogyakarta bahkan terus
berjalan disepanjang masa kolonial Belanda di Nusantara.
D. Dualisme Pemerintah Hindia Belanda atas Orang-Orang Tionghoa di
Jawa
Dalam tahun 1830-1870, pemerintah Hindia Belanda melahirkan sebuah
sistem yang dikenal dengan nama Sistem Tanam Paksa. Sistem ini merupakan
sistem dalam pemilikan perkebunan di Jawa yang dalam prakteknya mampu
meningkatkan pundi-pundi perekonomian kolonial. Akan tetapi konsekuensinya
adalah sebagian besar petani yang tinggal di daerah perkebunan diharuskan
menjadi buruh. Oleh karenanya Belanda menganggap petani di Jawa adalah
potensi buruh yang perlu dilindungi terutama dalam kepentingan sistem tanam
paksa itu sendiri. Sedangkan orang-orang Tionghoa dalam masa ini mulai
dipertanyakan oleh pemerintah Hindia Belanda mengenai seberapa
membahayakannya orang-orang Tionghoa dalam kaitannya dengan persaingan
ekonomi di Hindia Belanda. Menurut Onghokham, sering orang-orang Tionghoa
dianggap sebagai kelompok yang merusak harga pasar.22 Walaupun demikian,
orang-orang Tionghoa banyak berjasa dalam membangun perekonomian Belanda
melalui perdagangan. Keadaan ini melahirkan sikap dualisme Belanda terhadap
orang-orang Tionghoa. Hal ini juga menjadi alasan Pemerintah Hindia Belanda
untuk melahirkan peraturan-peraturan yang membatasi ruang gerak orang-orang
Tionghoa di Hindia Belanda khususnya di Jawa.
Peraturan-peraturan bagi orang-orang Tionghoa yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Hindia Belanda mulai diberlakukan sejak tahun 1863. Sejak tahun
22 Onghokham.
tersebut orang-orang Tionghoa secara resmi dipaksa untuk tinggal dalam tempat
yang telah ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi
kepentingan-kepentingan pemerintah kolonial jugalah yang pada akhirnya membuat peraturan
ini tidak dijalankan secara tegas. Pejabat setempat biasanya hanya melakukan
teguran bagi orang Tionghoa yang melanggarnya. Hukuman yang dianggap ringan
juga menjadi alasan orang-orang Tionghoa yang tinggal di daerah yang telah
ditentukan pemerintah Hindia Belanda untuk tidak terlalu menghiraukan peraturan
tersebut.
Di sisi lain, kondisi dimana orang-orang Tionghoa harus tinggal di satu
wilayah tertentu dengan komunitas yang homogen, justru membuat masyarakat
Tionghoa dapat terus mempertahankan eksistensi budaya Tionghoa. Hal ini
terbukti dari adanya simbol-simbol kebudayaan yang ada pada setiap rumah di
Pecinan, atau banyak ditemukannya makam-makam khas orang-orang Tionghoa.
Peraturan tersebut berhasil menjaga kebudayaan Tionghoa dalam eksistensinya di
tengah kehidupan masyarakat di wilayah Kasultanan Yogyakarta.
Selain peraturan tentang tempat tinggal, pemerintah Hindia Belanda juga
membuat peraturan tentang surat jalan. Pertaturan ini, pada dasarnya sangat
membatasi gerak orang-orang Tionghoa di wilayah pedalaman Jawa. Peraturan
ini, mengharuskan setiap orang Tionghoa yang hendak pergi dari luar daerah
pecinan harus memiliki surat jalan untuk bepergian. Surat-surat itu di dapat atas
permohonan yang diajukan pada pemerintah Belanda. Praktis peraturan tersebut
merupakan sebuah hambatan bagi orang-orang Tionghoa terutama yang bermata
hingga daerah pelosok di desa-desa Jawa. Tiap kali orang ingin berpergian,
mereka harus mengajukan permohonan dengan para pegawai pemerintah Hindia
Belanda. Sehingga cukup jelas kiranya bagaimana surat jalan menjadi masalah
bagi orang-orang Tionghoa di Jawa, terutama di kota-kota besar. Akan tetapi,
banyak juga yang mengabaikan peraturan semacam ini. Hal ini terlebih dilakukan
bagi orang-orang yang hendak melakukan perjalanan yang cenderung pendek atau
hanya menempuh jarak di daerah yang dekat pecinan. Petugas-petugas yang
berwenang yang mengetahui pelanggaran tersebut, dalam prakteknya juga banyak
melakukan pembiaran tindakan tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa
berjalan atau tidaknya sistem surat jalan yang dikeluarkan pihak Belanda sangat
bergantung pada pegawai-pegawai yang bekerja di wilayah setempat. Jika dilihat
dari pemerintah Belanda di Hindia Belanda, tentu mereka menginginkan adanya
peraturan yang ketat. Akan tetapi, mereka hanya bisa mengingatkan kepada para
pegawai setempat untuk mengawasi peraturan ini secara ketat.
Sikap dualisme yang dimiliki pemerintah Belanda ataupun perusahaan
dagang swasta Belanda terhadap orang-orang Tionghoa, menjadikan peraturan
yang dibuat untuk membatasi ruang gerak orang-orang Tionghoa menjadi tidak
efektif. Artinya, keinginan Belanda untuk membatasi ruang gerak etnis Tionghoa
dapat dikatakan hampir tidak terjadi. Menurut Onghokham, semua itu
dikarenakan adanya kepentingan bisnis yang menguntungkan bagi orang-orang
Belanda. Sebagaimana dapat terlihat, disaat yang sama Pemerintah Belanda
perahu tambang, serta pajak pasar kepada orang-orang Tionghoa.23 Oleh karena
orang-orang Tionghoa mempunyai potensi dapat membawa keuntungan untuk
orang Belanda, maka orang Belanda juga berpendapat bahwa
orang-orang Tionghoa harus di berikan ruang gerak seluas-luasnya.
E. Kedekatan Orang-orang Tionghoa dengan Kraton
Setelah kedatangan orang-orang Tionghoa ke Yogyakarta untuk pertama
kalinya, terutama setelah Kasultanan Yogyakarta berdiri pada tahun 1756, jumlah
orang-orang Tionghoa yang tinggal menetap di Yogyakarta setiap tahunnya terus
saja meningkat. Dalam data yang menunjukkan jumlah penduduk Tionghoa di
Yogyakarta pada tahun-tahun akhir jabatan Sri Sultan Hamengku Buwana VII
yaitu tahun 1906-1910 memperlihatkan jumlah penduduk di wilayah Yogyakarta
sebanyak 79. 567 jiwa. Di atara keseluruhan jumlah tersebut, penduduk Tionghoa
ada sebanyak 5. 266 jiwa, atau 6,61% dari keseluruhan jumlah penduduk.24
Jumlah ini cukup untuk mengindikasikan adanya keberagaman penduduk di
dalam wilayah Kasultanan Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan keadaan di
Kasunanan Surakarta, yang nota bene adalah kerajaan yang lebih tua dari
Kasultanan Yogyakarta serta memiliki sejarah yang berhubungan dengan etnis
Tionghoa lebih awal, dapat dikatakan bahwa kehidupan sosial antar etnis di
23
Ibid., Hal. 39
24 Melly. G. Tan, ed.
wilayah Yogyakarta lebih beragam.25 Dalam tahun yang sama di Surakarta
terdapat persentase jumlah penduduk total yang lebih kecil dari pada yang ada di
wilayah Yogyakarta yakni 5, 51%.26
Bahkan menurut Peter Carey, pada permulaan abad ke-19 hubungan baik
menjadi ciri yang menyelimuti segala urusan yang melibatkan orang-orang Jawa
dan orang-orang Tionghoa.27 Akan tetapi, sebelumnya yaitu pada masa-masa awal
Kasultanan, kerjasama atau hubungan baik yang dilakukan orang-orang Jawa
dengan orang-orang Tionghoa jarang terjadi. Justru rasa saling curigalah yang
muncul mereka. Dalam periode dimana banyak terjadi perang, memunculkan
kondisi yang meletakkan kelompok orang Tionghoa dan juga orang Jawa dalam
suasana yang membuat saling tidak mempercayai. Hal ini bahkan dituliskan oleh
Diponegoro dalam Serat Babad Dipanagaran, 2 : 26: XXXIII (Maskumambang)
yang berbunyi:
71. ………
China ing Lasem sedaya
72. mapan sampun sumeja manjing Agami
Den Sasradilaga
Dadya supe weling Aji Anjamahi Nyonyah China
73. pan punika ingkang dadi mar ganeki
Hubungan kurang harmonis antara orang Jawa dan Tionghoa yang terjadi
pada masa kolonialisme itu dapat terlihat dari potongan babad tersebut. Hal
tersebut terjadi terutama karena banyak dari para elite Jawa mulai terpengaruh
dominasi pemerintah Belanda memunculkan anggapan tentang kurang
bermanfaatnya menjalin hubungan dengan orang-orang Tionghoa.
Ketidakharmonisan hubungan Jawa-Tionghoa ini memang tidak terjadi serentak
di seluruh wilayah Jawa, akan tetapi yang pasti gelombang perpecahan terjadi di
kalangan elit Jawa dengan Tionghoa. Hal tersebut juga karena banyak di atara
para priyayi Jawa adalah kalangan yang memilih suatu kondisi yang
menempatkan mereka dalam status quo dimana mereka tetap dapat merasakan
kenyamanan jabatan mereka. Menurut Kuntowijoyo, priyayi bukanlah
semata-mata sebuah pekerjaan, akan tetapi juga berarti sebuah kehorsemata-matan, dan mereka
akan menjaga itu bahkan dengan cara mempertegas stratifikasi yang ada melalui
berbagai macam cara.29
Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai:
71.………..
China yang di lasem semuanya 72.karena sudah sanggup dan bersedia Untuk memeluk satu agama
Dan sebagai panglima perang
Ternyata telah dilupakan dan melanggar pantangan yaitu menggauli Nyonya China 73.Hal itulah yang menjadi penyebab Kekalahan perang
………..
29
Di Yogyakarta, hubungan yang terjadi antara Kasultanan dengan orang
Tionghoa lebih dari sekedar hubungan yang berlatar belakang urusan perdagangan
belaka. Sultan Yogyakarta banyak mempercayakan urusan-urusan tertentu di luar
urusan perdagangan kepada orang-orang Tionghoa. Sultan Hamengku Buwana II
misalnya, mempercayakan kesehataannya dengan mengangkat seorang Tionghoa
sebagai dokter pribadinya yang tidak lain adalah ahli obat tradisional atau
jamu-jamuan.30 Menurut Abdurrachman Surjomiharjo, salah satu ciri dari corak
dinamika sejarah di Yogyakarta adalah terjadinya interaksi antara sistem
stratifikasi tradisional dengan sistem stratifikasi yang tercipta karena kehadiran
kolonial.31 Sehingga kolonial menjadi pihak yang telah membawa banyak
pembaharuan dalam dinamika sejarah di Yogyakarta. Setelah berakhirnya perang
Diponegoro dimana pemerintah Belanda mulai melakukan pengawasan lebih ketat
di wilayah Jawa, proses plruralisasi sosial di berbagai bidang justu tampak di
Yogyakarta. Hal tersebut dapat diketahui dari mulai munculnya orang-orang
Tionghoa yang menduduki jabatan atau bekerja pada bidang yang penting di
Yogyakarta.
30
Peter Carey, op. cit., Hal. 41
31 Abddurachman Surjomihardjo. Kota Yogyakarta 1880-1930, Sejarah
BAB III
MENJADI BANGSAWAN DAN ELITE MASYARAKAT
Orang Tionghoa mulai ada di Yogyakarta setelah Keraton Yogyakarta
berdiri, yaitu pasca perjanjian Giyanti. Dwi Naga Rasa Tunggal adalah sengkala
memet yang ada di bagian Selatan keraton Yogyakarta, merupakan lambang yang
menunjukkan berdirinya keraton, yaitu pada bulan September 1755.1 Denys
Lombard mengatakan bahwa sengkala memet yang terdapat di kraton Kasultanan
mempunyai pemikiran yang mendalam bahwa pendirian Yogyakarta merupakan
sebuah tindakan ganda yang bersifat politis namun juga spiritual sekaligus.2
Bagi sebuah kerajaan yang baru saja berdiri, pembangunan pada bidang
ekonomi menjadi bagian yang penting untuk menggerakkan roda pemerintahan.
Berdirinya pasar dekat kraton selain mempunyai fungsi secara simbolis terhadap
sistem pemerintahan kraton juga berfungsi untuk memicu para pedagang dari luar
daerah untuk datang ke Yogyakarta. Masyarakat Tionghoa adalah salah satu dari
kelompok etnis yang datang untuk berdagang dan pada akhirnya menetap di
Yogyakarta.
Berdirinya Kasultanan Yogyakarta merupakan awal keberadaan
Masyarakat Tionghoa di Yogyakarta. Sejak itu, jumlah masyarakat Tionghoa di
1
G. Moedjanto. Suksesi dalam Sejarah Jawa. 2002. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma. Hal. 121-122
2
Yogyakarta terus berkembang seiring perubahan waktu. Setiap generasi baru
masyarakat Tionghoa tumbuh dalam konstruksi identitas sosial dari lingkungan
sekitar. Melalui konstruksi budaya Jawa serta konstruksi identitas sosial
masyarakat Yogyakata, tiap generasi yang lahir dileburkan dalam satu ruang,
yakni masyarakat Yogyakarta itu sendiri. Hal inilah yang membawa etnis
Tionghoa di Yogyakarta bergabung dalam sebuah komunitas terbayang bersama
dengan kejawaan di Yogyakarta.3
Dalam konteks menjadi bagian dari sebuah komunitas yang terbayang,
setiap orang yang menjadi bagian dari komunitas tersebut atas dasar
kesetiakawanan akhirnya rela mengorbankan orang lain atau bahkan dirinya
sendiri.4 Proses inilah yang membentuk dinamika sosial masyarakat dalam
pencarian identitas kolektif rela bahkan menempuh jalur konflik atau kekerasan.
Dalam kaitannya dengan orang-orang Tionghoa di Yogyakarta, proses pencarian
identitas seperti itu akhirnya membawa mereka pada sebuah perputaran roda
kehidupan antara harmonisasi dan disharmonisasi sosial.
Posisi kelompok masyarakat Tionghoa di Yogyakarta sendiri, tidak dapat
dipisahkan dari latar belakang sosial dan budaya Jawa di Yogyakarta, serta posisi
Sultan sebagai figur yang berada pada puncak struktur kosmologis dan sistem
3
Konsep ini dibuat oleh Benedict Anderson dalam: Benedict Anderson.
Imagined Communities: Komunitas-komunitas Terbayang. 2002. Yogyakarta: Insist. Hal. 11
4
sosial di Yogyakarta.5 Sultan sebagai raja mengambil peran dalam menaungi masa
rakyatnya. Oleh karenanya, Sultan mengambil posisi yang cukup penting di dalam
seluruh dinamika masyarakat di Yogyakarta. Dalam kaitannya dengan etnis
Tionghoa di Yogyakarta, Sultan turut berperan atas keadaan masyarakat Tionghoa
di Yogyakarta. Hal tersebut terutama mengenai sikap orang-orang Yogyakarta
untuk dapat saling memahami serta menghormati.
Y. B. Mangunwijaya mengatakan bahwa dalam citra manusia tradisional
Jawa, pada hakikatnya adalah citra wayang belaka dalam kelir jagad cilik atau
yang dinamakan mikrokosmos. Di mana dalam kehidupan dipahami sebagai
sesuatu yang tidak sejati, bayangan, yang di gerakkan oleh Ki Dalang, dalam alam
penentu sejati.6 Pemahaman ini melahirkan sebuah upaya penyadaran posisi serta
kewajiban manusia muda dalam tatanan kehidupan yang dimuat di sebuah
piramida hirarkis. Sehingga, penyadaran posisi manusia melahirkan etika yang
mencoba memainkankan peran dalam kehidupan bersama. Sedangkan konflik
muncul sebagai benturan dari kepentingan-kepentingan manusia. Konflik selalu
muncul dalam kehidupan sebagai bagian dari dinamika sosial kehidupan manusia.
Dari sudut inilah muncul dualisme antara penerimaan dan penolakan masyarakat
Tionghoa oleh masyarakat sekitar. Penerimaan dan penolakan ini akan dilihat dari
beberapa bidang kehidupan yang terus berputar dan membentuk arus hubungan
yang harmonis dan disharmonis.
5 Budi Susanto, S. J., ed.
Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia. 2003. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 71
6