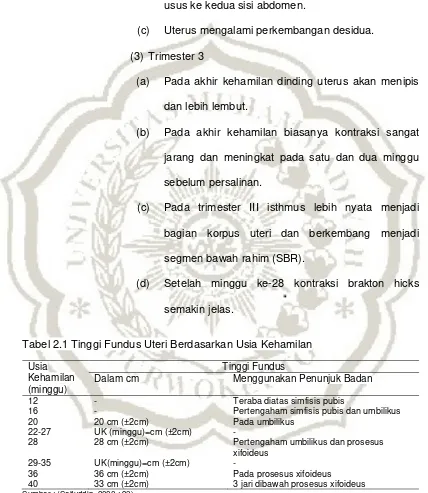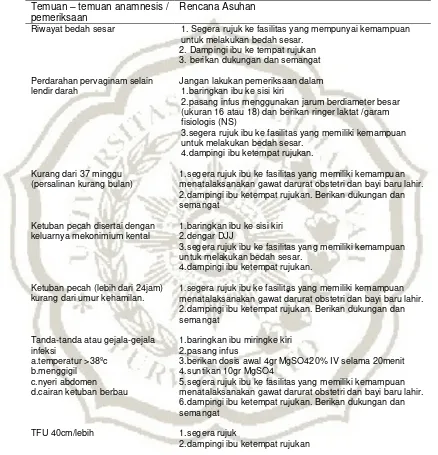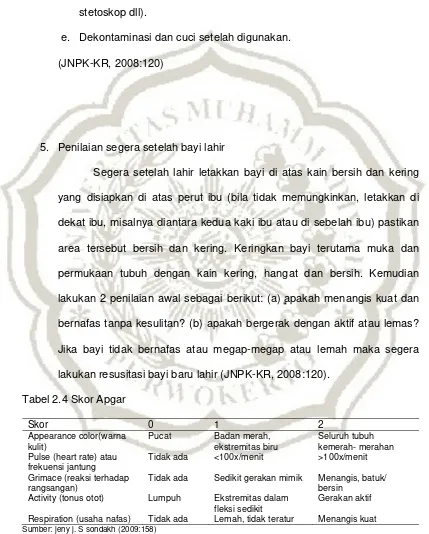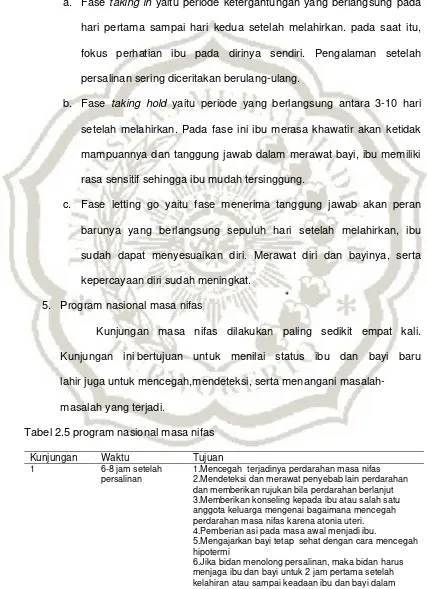BAB II TINJAUAN TEORI
A. KONSEP DASAR KEHAMILAN
1. Definisi Kehamilan
Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, Kehamilan
didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan
ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari
saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung
dalam 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender
internasional. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester, dimana trimester ke
satu berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu ( minggu
ke-13 hingga ke-27 ), dan trimester ketiga 13 minggu ( minggu ke-28
hingga ke-40 ) (Prawirohardjo, 2008 : 213).
Sedangkan menurut Saifudin (2008 : 89) kehamilan adalah suatu
masa yang dimulai dari konsepi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil
normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari haid
pertama haid terakhir.
2. Proses Terjadinya Kehamilan
Proses kehamilan merupakan mata rantai yang
berkesinambungan dan terdiri dari ovulasi, migrasi spermatozoa dan
ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi (implementasi) pada
uterus, pembentukan plasenta dan tumbuh kembang hasil konsepsi
Sedangkan menurut Wiknjosastro (2008 : 139) menjabarkan
proses kehamilan yakni bahwa wanita pada umumnya mempunyai 2
indung telur ( ovarium ) yaitu di sebelah kanan dan kiri, dan diperkirakan
dalam ovarium wanita terdapat kira-kira 100,000 folikel primer. Pada
setiap bulannya indung telur akan melepaskan 1 atau 2 sel telur ( ovum )
yang kemudian di tangkap oleh fimbria dan disalurkan ovum tersebut ke
dalam tuba. Untuk setiap kehamilan yang dibutuhkan adalah
spermatozoa, ovum, pembuahan ovum, dan nidasi hasil konsepsi.
Pada waktu koitus, jutaan spermatozoa pria dikeluarkan di forniks
vagina dan di sekitar portio wanita, hanya beberapa ratus ribu
spermatozoon saja yang dapat bertahan hingga kavum uteri dan tuba,
dan beberapa ratus yang dapat sampai ke bagian ampula tuba dimana
spermatozoon dapat memasuki ovum yang telah siap untuk dibuahi.
Disekitar sel telur terdapat zona pellucida yang melindungi ovum, ratusan
spermatozoon tersebut berkumpul untuk mengeluarkan ferment (ragi)
agar dapat mengikis zona pellucida dan hanya satu spermatozoon yang
mempunyai kemampuan untuk membuahi sel telur, peristiwa ini disebut
pembuahan ( konsepsi ).
Dalam beberapa jam setelah pembuahan terjadi, dimulailah
proses pembelahan zigot sambil bergerak menuju kavum uteri oleh arus
serta getaran sillia pada permukaan sel-sel tuba dan kontraksi tuba. Pada
umumnya jika hasil konsepsi telah sampai kavum uteri maka akan terjadi
perlekatan pada dinding depan atau belakang uterus dekat fundus uteri,
perlekatan itu disebut nidasi dan jika terjadi nidasi barulah dapat
sesuatu untuk membuat janin tumbuh dengan baik yaitu plasenta,
umumnya plasenta terbentuk dengan lengkap pada usia kehamilan
kurang lebih 16 minggu. Plasenta ini sebagian besar berasal dari janin
dan sebagian kecil dari ibu (Wiknjosastro, 2008 : 139).
3. Tanda kehamilan
Tanda kehamilan menurut Manuaba (2010: 107) dibagi menjadi 3
bagian, yaitu:
a. Tanda tidak pasti kehamilan
1) Amenorea (tidak dapat haid)
Gejala ini sangat penting karena umumnya wanita hamil tidak
dapat haid lagi. Dengan diketahuinya tanggal hari pertama haid
terakhir supaya dapat ditaksir umur kehamilan dan taksiran
tanggal persalinan akan terjadi, dengan memakai rumus Neagie: HT – 3 (bulan + 7).
2) Mual dan muntah
Biasa terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan hingga akhir
triwulan pertama. Sering terjadi pada pagi hari disebut “morning sickness”.
3) Mengidam (ingin makanan khusus)
Sering terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan, akan tetapi
menghilang dengan makin tuanya kehamilan.
4) Pingsan
Bila berada pada tempat-tempat ramai yang sesak dan padat.
5) Anoreksia (tidak ada selera makan)
Hanya berlangsung pada triwulan pertama kehamilan, tetapi
setelah itu nafsu makan timbul lagi.
6) Mamae menjadi tegang dan membesar.
Keadaan ini disebabkan pengaruh hormon estrogen dan
progesteron yang merangsang duktus dan alveoli payudara.
7) Miksi sering
Sering buang air kecil disebabkan karena kandung kemih
tertekan oleh uterus yang mulai membesar. Gejala ini akan
hilang pada triwulan kedua kehamilan. Pada akhir kehamilan,
gejala ini kembali karena kandung kemih ditekan oleh kepala
janin.
8) Konstipasi atau obstipasi
Ini terjadi karena tonus otot usus menurun yang disebabkan oleh
pengaruh hormon steroid yang dapat menyebabkan kesulitan
untuk buang air besar.
9) Pigmentasi (perubahan warna kulit)
Pada areola mamae, genital, cloasma, linea alba yang berwarna
lebih tegas, melebar dan bertambah gelap terdapat pada perut
bagian bawah.
10) Epulis
11) Varises (pemekaran vena-vena)
Karena pengaruh dari hormon estrogen dan progesteron terjadi
penampakan pembuluh darah vena. Penampakan pembuluh
darah itu terjadi disekitar genetalia eksterna, kaki dan betis, dan
payudara.
b. Tanda kemungkinan kehamilan
1) Perut membesar
Setelah kehamilan 14 minggu, rahim dapat diraba dari luar dan
mulai pembesaran perut.
2) Uterus membesar
Terjadi perubahan dalam bentuk, besar, dan konsistensi dari
rahim. Pada pemeriksaan dalam dapat diraba bahwa uterus
membesar dan bentuknya makin lama makin bundar.
3) Tanda Hegar
Konsistensi rahim dalam kehamilan berubah menjadi lunak,
terutama daerah ismus. Pada minggu-minggu pertama ismus
uteri mengalami hipertrofi seperti korpus uteri. Hipertrofi ismus
pada triwulan pertama mengakibatkan ismus menjadi panjang
dan lebih lunak.
4) Tanda Chadwick
Perubahan warna menjadi kebiruan atau keunguan pada vulva,
vagina, dan serviks. Perubahan warna ini disebabkan oleh
5) Tanda Piscaseck
Uterus mengalami pembesaran, kadang–kadang pembesaran
tidak rata tetapi di daerah telur bernidasi lebih cepat tumbuhnya.
Hal ini menyebabkan uterus membesar ke salah satu jurusan
hingga menonjol jelas ke jurusan pembesaran.
6) Tanda Braxton-Hicks
Bila uterus dirangsang mudah berkontraksi. Tanda khas untuk
uterus dalam masa hamil. Pada keadaan uterus yang membesar
tetapi tidak ada kehamilan misalnya pada mioma uteri, tanda
Braxton-Hicks tidak ditemukan. 7) Teraba ballotemen
Merupakan fenomena bandul atau pantulan balik. Ini adalah
tanda adanya janin di dalam uterus.
8) Reaksi kehamilan positif
Cara khas yang dipakai dengan menentukan adanya human chorionic gonadotropin pada kehamilan muda adalah air kencing pertama pada pagi hari. Dengan tes ini dapat membantu
menentukan diagnosa kehamilan sedini mungkin.
c. Tanda pasti kehamilan
1) Gerakan janin yang dapat dilihat, dirasa atau diraba, juga
bagian-bagian janin.
2) Denyut jantung janin
a) Didengar dengan stetoskop-monoral Laennec
b) Dicatat dan didengar dengan alat doppler
3) Dilihat pada ultrasonograf terlihat tulang-tulang janin dalam
foto-rontgen
4. Proses Adaptasi Fisiologis dan Psikologi Dalam Masa Kehamilan
Menurut Asrinah dan kawan kawan (2010:55), periode antepartum
adalah periode kehamilan yang dihitung sejak hari pertama haid terakhir
(HPHT) sampai dimulainya persalinan. Periode antepartum dibagi
menjadi tiga trimester, pembagian waktu ini diambil dari ketentuan yang
mempertimbangan bahwa lama kehamilan diperkirakan kurang dari 40
minggu. Pembuahan berlangsung ketika terjadi ovulasi, kurang lebih 14
hari setelah haid terakhir (dengan perkiraan siklus 28 hari). Pada
praktiknya, trimester I secara umum dipertimbangkan berlangsung pada
minggu pertama hingga ke-12 (12 minggu), trimester II minggu ke-13
sampai dengan minggu ke-27 (15 minggu), dan trimester III minggu ke-27
hingga minggu ke-40 (13 minggu).
Lamanya kehamilan yaitu antara 280 hari atau 40 pekan (minggu)
atau 10 bulan (lunar months) dihitung dari HPHT. Kehamilan dibagi atas 3
triwulan (trimester) kehamilan trimester I antar 0-14 minggu, kehamilan
trimester II antara 15-27 minggu, kehamilan trimester III antara 28-36
minggu dan diatas 36 minggu (Varney,dkk. 2007 : 7).
a. Perubahan Fisiologis pada kehamilan trimester 1, 2 dan 3
1) Sistem reproduksi
a) Uterus
Uterus merupakan organ berbentuk seperti buah alvokad
(bagain usus sebelum dubur) di belakang dan kandung
kemih di depan. Perubahan yang terjadi pada uterus, yaitu
peningkatan berat dari 30 gram sampai 1000 gram pada
akhir kehamilan. Berikut ini adalah perubahan uterus pada
setiap trimester kehamilan yaitu, sebagai berikut :
(1) Trimester 1
(a) Uterus akan membesar pada bulan-bulan pertama
kehamilan di bawah pengaruh estrogen dan
progesterone.
(b) Selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk
menerima konsepsi sampai persalinan.
(c) Pada minggu-minggu pertama kehamilan uterus
berbentuk seperti buah alvokad.
(d) Pada kehamilan 8 minggu uterus membesar
sebesar telur bebek.
(e) Pada kehamilan 12 minggu kira-kira sebesar telur
angsa, pada saat ini fundus uteri telah dapat diraba
dari luar di atas sympisis.
(f) Terjadi perubahan pada isthmus uteri yang
menyebabkan isthemus uteri menjadi lebih lunak
dan panjang.
(2) Trimester 2
(a) Pada trimester II ini uterus mulai memasuki rongga
(b) Uterus akan bertambah besar dalam rongga pelvis
dan menyentuh dinding abdomen dan mendesak
usus ke kedua sisi abdomen.
(c) Uterus mengalami perkembangan desidua.
(3) Trimester 3
(a) Pada akhir kehamilan dinding uterus akan menipis
dan lebih lembut.
(b) Pada akhir kehamilan biasanya kontraksi sangat
jarang dan meningkat pada satu dan dua minggu
sebelum persalinan.
(c) Pada trimester III isthmus lebih nyata menjadi
bagian korpus uteri dan berkembang menjadi
segmen bawah rahim (SBR).
(d) Setelah minggu ke-28 kontraksi brakton hicks
semakin jelas.
Tabel 2.1 Tinggi Fundus Uteri Berdasarkan Usia Kehamilan
Usia Kehamilan (minggu)
Tinggi Fundus
Dalam cm Menggunakan Penunjuk Badan
12 - Teraba diatas simfisis pubis
16 - Pertengaham simfisis pubis dan umbilikus 20 20 cm (±2cm) Pada umbilikus
22-27 UK (minggu)=cm (±2cm) -
28 28 cm (±2cm) Pertengaham umbilikus dan prosesus xifoideus
29-35 UK(minggu)=cm (±2cm) -
36 36 cm (±2cm) Pada prosesus xifoideus
40 33 cm (±2cm) 3 jari dibawah prosesus xifoideus
b) Vagina
Vagina merupakan saluran yang elastis, panjangnya sekitar
8 – 10 cm, dan berakhir pada rahim.Vagina dilalui oleh darah
pada saat menstruasi dan merupakan jalan lahir. Karena
terbentuk dari otot, vagina bisa melebar dan menyempit,
berikut ini adalah perubahan vagina tiap trimester kehamilan,
yaitu sebagai berikut :
(1) Trimester 1
(a) Terjadi peningkatan vaskularisasi karena pengaruh
hormon estrogen, peningkatan vaskularisasi
menimbulkan tanda chadwick (warna merah tua
atau kebiruan) pada vagina sampai minggu ke-8
kehamilan.
(b) Selama masa hamil Ph sekresi vagina menjadi lebih
asam. Keasaman berubah dari 4 - 6,5.
(2) Trimester 2
(a) Karena hormone estrogen dan progesterone terus
meningkat dan terjadi hipervaskularisasi
mengakibatkan pembuluh-pembuluh darah alat
genitalia membesar.
(b) Sekresi vagina meningkat, Hal ini normal jika tidak
disertai gatal, iritasi atau berbau busuk.
(3) Trimester 3
(a) Dinding vagina mengalami peregangan (bertambah
(b) Lapisan otot membesar, vagina lebih elastic.
c) Ovarium
Ovarium berjumlah sepasang dan terletak antara rahim dan
dinding panggul. Ovulasi berhenti selama kehamilan dan
pematangan folikel ditunda. Hanya satu korpus luteum yang
berfungsi (max 6-7 minggu) di dalam ovarium wanita hamil
kemudian fungsinya diganti oleh plasenta pada umur
kehamilan 16 minggu. Berikut ini adalah perubahan yang
terjadi setiap trimester kehamilan, yaitu sebagai berikut :
(1) Trimester 1
Pada permulaan kehamilan masih terdapat korpus luteum
graviditatum, korpus luteum graviditatium berdiameter
kira-kira 3 cm dan akan mengecil setelah plasenta
terbentuk.
(2) Trimester 2 dan 3
Pada usia kehamilan 16 minggu, plasenta mulai terbentuk
dan menggantikan fungsi korpus luteum graviditatum.
d) Serviks
(1) Trimester 1
(a) Satu bulan setelah konsepsi serviks akan menjadi
lunak yg disebut dengan tanda Goodlell.
(b) Selama kehamilan serviks tetap tertutup rapat.
(2) Trimester 2
(a) Pada awal trimester ini berkas kolagen kurang kuat
(b) Konsistensi serviks menjadi lunak dan
kelenjar-kelenjar di serviks berfungsi lebih dan mengeluarkan
sekresi lebih banyak.
(3) Trimester 3
Akibat aktivitas uterus selama kehamilan serviks
mengalami pematangan secara bertahap dan kanal
mengalami dilatasi.
2) Kenaikan berat badan
Berat badan (Ai Yeyeh, 2009 : 34) sesuai dengan teori
yang menyebutkan bahwa berat badan ibu hamil akan
bertambah antara 6,5 kg-16,5 kg. Berdasarkan IMT (Indeks
Massa Tubuh) berat badan ibu masih dalam batas normal
dengan kalkulasi sebagai berikut :
Tabel 2.2 Status Gizi
Nilai Status Gizi Kesimpulan
<17,0 Gizi kurang Sangat kurus
17,0-18,5 Kurang Kurus
18,5-25,0 Baik Normal
25,0-27,0 Lebih Gemuk
>27,0 Lebih Sangat gemuk
Sumber : Ai Yeyeh (2009 : 34)
b. Perubahan psikologis pada ibu hamil
1) Perubahan Psikologis pada Trimester I (Periode Penyesuaian)
a) Ibu merasa tidak sehat dan kadang-kadang merasa benci
dengan kehamilannya.
b) Kadang muncul penolakan, kecemasan dan kesedihan.
c) Ibu akan selalu mencari tanda-tanda apakah ia benar-benar
hamil. Hal ini dilakukan sekedar untuk meyakinkan dirinya.
d) Setiap perubahan yang terjadi dalam dirinya akan selalu
mendapat perhatian dengan seksama.
e) Oleh karena perutnya masih kecil, kehamilan merupakan
rahasia seseorang yang mungkin akan diberitahukannya
kepada orang lain atau bahkan merahasiakannya.
(Sulistyawati, 2009 : 76)
2) Perubahan psikologis pada trimester II
a) Ibu merasa sehat, tubuh ibu sudah terbiasa dengan kadar
hormone yang tinggi.
b) Ibu sudah bisa menerima kehamilannya.
c) Merasakan gerakan anak.
d) Merasa terlepas dari ketidaknyamanan dan kekhawatiran.
e) Libido meningkat.
f) Menuntut perhatian dan cinta.
g) Merasa bahwa bayi sebagai individu yang merupakan bagian
dari dirinya.
h) Hubungan sosial meningkat dengan wanita hamil lainnya
atau pada orang lain yang baru menjadi ibu.
i) Ketertarikan dan aktivitasnya terfokus pada kehamilan,
kelahiran, dan persiapan untuk peran baru.
3) Perubahan Psikologis pada Trimester III
a) Rasa tidak nyaman timbul kembali, merasa dirinya jelek, aneh
dan tidak menarik.
b) Merasa tidak menyenangkan ketika bayi tidak lahir tepat waktu.
c) Takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang timbul pada saat
melahirkan, khawatir akan keselamatannya.
d) Khawatir bayi akan dilahirkan dalam keadaan tidak normal,
bermimpi yang mencerminkan perhatian dan kekhawatirannya.
e) Merasa sedih karena akan terpisah dari bayinya.
f) Merasa kehilangan perhatian.
(Sulistyawati, 2009 : 77)
5. Antenatal Care
a. Definisi Antenatal Care
Antenatal care adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan
pada ibu hamil sejak ibu mulai merasakan kehamilannya sampai saat
bersalin (Saefuddin, 2008 : 89).
b. Tujuan asuhan atenatal
1) Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu
dan tumbuh kembang bayi.
2) Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental dan
social ibu dan bayi.
3) Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi
4) Mempersiapkan kehamilan cukup bulan, melahirkan dengan
selamat, ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin.
5) Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan
pemberian asi ekslusif.
c. Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran
bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal. (Sarwono,2008:89)
d. Menurut Sulistiawati (2009:69), pelayanan / asuhan standar minimal
termasuk ‘14T‘ yakni :
1) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan
2) Ukur tekanan darah
3) Nilai Status Gizi
4) Ukur tinggi fundus uteri
5) Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)
6) Imunisasi Tetanus Toksoid (TT)
7) Pemberian Tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan
8) Test laboratorium (rutin dan khusus)
9) Tatalaksana kasus
10) Temu wicara (konseling), termasuk Perencanaaan Persalinan dan
Pencegahan Komplikasi (P4K) serta KB pasca persalinan.
11) Pemeriksaan protein urine atas indikasi
12) Pemeriksaan reduksi urine atas indikasi
13) Pemberian terapi kapsul yodium untuk daerah endemis gondok
e. Kebijakan teknis
Setiap kehamilan dapat berkembang menjadi masalah atau
komplikasi setiap saat. Itu sebabnya mengapa ibu hamil memerlukan
pemantauan selama kehamilannya. Penatalaksanaan ibu hamil secara
keseluruhan meliputi komponen-komponen sebagai berikut :
1) Mengupayakan kehamilan yang sehat.
2) Melakukan deteksi dini komplikasi, melakukan penatalaksanaan
awal serta rujukan bila di perlukan.
3) Persiapan persalinan yang bersih dan aman.
4) Perencanaan antisipasif dan persiapan dini untuk melakukan
rujukan jika terjadi komplikasi.
(Saifuddin, 2008 : 90)
f. Informasi pada kunjungan ANC, menurut Saifuddin (2008 : N2)
1) Trimester 1 ( sebelum minggu ke 14 )
a) Membangun hubungan saling percaya antara petugas
kesehatan dan ibu hamil.
b) Mendeteksi masalah dan menanganinya.
c) Melakukan tindakan pencegahan seperti tetanus neonatorum,
anemia kekurangan zat besi, penggunaan praktek tradisional
yang merugikan.
d) Memulai persiapan kelahiran bayinya dan kesiapan untuk
menghadapi komplikasi.
e) Mendorong prilaku sehat ( gizi, kebersihan, istirahat dan
2) Trimester II (sebelum minggu ke-14-28)
Sama seperti di atas, ditambah kewaspadaan khusus mengenai
preeklampsi (tanya ibu tentang gejala - gejala preeklampsia,
pantau tekanan darah, evaluasi oedema periksa untuk mengetahui
protein urine).
3) Trimester III (antara minggu ke 28-36 dan sesudah minggu ke-36)
Sama dengan yang di atas , kewaspadaan terhadap eklampsia,
pemeriksaan palpasi abdominal untuk mengetahui apakah
terdapat hamil ganda. Setelah 36 minggu pada trimester III : Sama
halnya dengan di atas, pada hamil lebih dari 36 minggu di lakukan
pemeriksaan pendeteksian letak bayi yang tidak normal atau
kondisi lainnya yang mengharuskannya untuk melahirkan di rumah
sakit.
g. Standar Asuhan
1) Identifikasi ibu hamil
Bidan mengadakan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan
masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan
motivasi ibu, suami dan keluarga agar mau memeriksakan
kehamilannya.
a) Pemeriksaan dan pemantauan ANC
Menurut Saifuddin (2008 : 90) kunjungan antenatal sebaiknya
dilakukan sedikitnya 4 kali selama masa kehamilan :
(1) K1 Pertama kali berkunjung pada trimester1 (sebelum 14
(2) K2 Satu kali kunjungan selama trimester kedua (antara
minggu 14 – 28).
(3) K3 & K4 Dua kali kunjungan selama trimester ketiga
(antara minggu 28 – 36 dan sesudah minggu ke 36).
h. Palpasi Abdomen
Palpasi adalah menyentuh atau menekan permukaan luar
tubuh dengan jari. Dilakukan untuk menentukan besarnya rahim
dengan menentukan usia kehamilan serta menentukan letak anak
dalam rahim. Pemeriksaan secara palpasi dilakukan dengan
menggunakan metode leopold, yakni :
1) Leopold I digunakan untuk menentukan usia kehamilan dan
bagian apa yang ada di fundus, dengan cara pemeriksa berdiri
sebelah kanan dan menghadap kemuka ibu, kemudian kaki ibu
dibengkokkan pada lutut dan lipat paha, lengkukan jari-jari kedua
tangan untuk mengelilingi bagian atas fundus, lalu tentukan apa
yang ada didalam fundus. Bila kepala sifatnya keras, bundar dan
melenting.
2) Leopold II digunakan untuk menentukan letak punggung anak dan
letak bagian kecil pada anak. Caranya Letakkan kedua tangan
pada sisi uterus, dan tentukan dimanakan bagian terkecil bayi.
3) Leopold III digunakan untuk menentukan bagian apa yang
terdapat di bagian bawah dan apakah bagian bawah anak sudah
lembut dan masuk ke dalam abdomen pasien di atas simpisis
pubis. Kemudian peganglah bagian presentasi bayi, lalu bagian
apakah yang menjadi presentasi tersebut.
4) Leopold IV digunakan untuk menentukan apa yang menjadi bagian
bawah dan seberapa masuknya bagian bawah tersebut ke dalam
rongga panggul. Caranya letakkan kedua tangan di sisi bawah
uterus lalu tekan ke dalam dan gerakkan jari-jari kearah rongga
panggul, dimanakah tonjolan sefalik dan apakah bagian presentasi
telah masuk. Pemeriksaan ini dilakukan bila kepala masih tinggi,
pemeriksaan leopold lengkap dapat dilakukan bila janin cukup
besar, kira-kira bulan ke VI ke atas.
(Aziz, 2008 : 142)
i. Pengolahan Anemia pada Kehamilan
Bidan melakukan tindakan pencegahan, penemuan,
penanganan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Tiap tablet mengandung FeSO4 320 mg (zat
besi 60 mg) dan asam folat 500 mg, minimal masing–masing 90 tablet.
Tablet besi sebaiknya diminum bersamaan dengan vitamin C atau air
jeruk agar cepat dalam penyerapan dan tidak diminum bersama teh
atau kopi karena akan mengganggu penyerapan. (Safrudin, 2009 : 85)
j. Pengolahan Dini Hypertensi Pada Kehamilan
Bidan menemukan secara dini kenaikan tekanan darah pada
kehamilan dan mengenali tanda gejala pre-eklampsi, serta mengambil
k. Persiapan Persalinan
Bidan memberikan saran yang tepat pada ibu hamil, suami
serta keluarga pada trimester II untuk memastikan bahwa persiapan
persalinan yang bersih dan aman serta suasana yang menyenangkan
direncanakan dengan baik, transportasi, biaya dan merujuk bila ada
kegawatan. (Safrudin, 2009 : 86)
6. Identifikasi, Komplikasi Dini Kehamilan
Ada enam tanda bahaya dalam masa periode antenatal :
a. Perdarahan pervaginam pada hamil muda maupun hamil tua.
b. Bengkak pada kaki, tangan atau wajah disertai sakit kepala yang
hebat, menetap dan tidak menghilang, serta kejang.
c. Demam atau panas tinggi.
d. Air ketuban keluar sebelum waktunya.
e. Bayi dalam kandungan gerakannya berkurang, tidak seperti biasanya
atau tidak bergerak sama sekali.
f. Muntah terus dan tidak mau makan.
Komplikasi dan penyulit kehamilan yang umumnya ditemukan pada:
a. Trimester I
1) Hiperemesis gravidarum
Mual dan muntah sering terjadi pada pagi hari tapi kadang
juga terjadi sepanjang hari. Penyebab dari hiperemesis belum
diketahui secara pasti tapi ada yang menyatakan bahwa mual
dan muntah tersebut disebabkan oleh peningkatan kadar
2) Abortus
Perdarahan yang terjadi pada kehamilan kurang dari 22
minggu dengan gejala – gejala perdarahan, kaku perut,
keluarnya sebagian atau seluruh hasil konsepsi, servix
berdeletasi atau uterus mengecil dari seharusnya.
3) Kehamilan ektopik terganggu
Terjadi perdarahan pada wanita yang selama hamilnya
mengalami anemi, dan mengalami nyeri perut yang tidak
biasa.
4) Molahidatidosa
Merupakan suatu kehamilan yang tidak berkembang secara
tidak wajar dimana tidak ditemukan nya janin, secara
makroskopi. Molahidatidosa berisi cairan jernih dengan
ukuran bervariasi. Adanya molahidatidosa harus dicurigai bila
seseorang wanita yang mengalami amenore, perdarahan
pervaginam, uterus lebih besar dari usia kehamilan
seharusnya, dan tidak ditemukannya tanda tanda kehamilan.
5) Anemia
Anemia dalam kehamilan kurang baik bagi ibu baik dalam
kehamilan, persalinan, dan nifas dan masa selanjutnya,
karena berbagi penyulit dapat timbul karenanya.
b. Trimester II dan III
1) Letak janin
Letak janin yang tidak pas pada posisi yang tidak normal akan
2) Hipertensi
Hipertensi dalam kehamilan adalah hal yang serius yang
terjadi pada trimester II dan III, apalagi diiring dengan gejala
edem, kejang, di usia kehamilan di atas 22 minggu, dengan
ketentuan kenaikan tekanan sistolik 30 mmHg, kenaikan
darah absolute 149/90 atau 160/110 yang diambil selang 6
jam dalam keadaan istirahat.
3) Ketuban pecah dini
Pecahnya ketuban sebelum terdapat tanda – tanda persalinan
dan di tunggu satu jam belum terjadi inpartu, sebagian besar
KPD ini terjadi pada kehamilan di atas 37 minggu sedangkan
di bawah 36 minggu jarang terjadi.
4) Gerak anak kurang
Ibu mersakan gerak bayinya antara 20 minggu sampai 24
minggu dimana ibu merasakan gerak janinnya 3 X dalam
periode 3 jam. Gerkan ini akan lebih terasa bila ibu dalam
posisi berbaring atau istirahat.
5) Kehamilan lewat waktu
Kehamilan yang terjadi melewati 294 hari atau 42 minggu
6) Kehamilan ganda
Pada kehamilan ganda dapat menyebabkan komplikasi yang
dapat terjadi pada trimester II atau III yaitu :
a) Persalinan premature
b) Hidramnion
d) Kelainan letak plasenta previa / sulusio plasenta
e) Gangguan pertumbuhan janin
7) Badan panas
Ibu mengalami peningkatan suhu badan di atas 38ºC, dimana
menunjukan bahwa ibu mengalami gejala infeksi dan adanya
sesuatu yang dapat membahayakan kehamilannya.
6) Adanya tanda – tanda inpartu sebelum waktunya
Adanya tanda – tanda persalinan sebelu, kehamilan di atas 37
minggu karena dapat terjadi persalinan premature.
7) Sakit kepala hebat
Sakit kepala yang terjadi dapat menyebabkan rasa ketidak
nyamanan, dimana sakit kepala yang menetap dan tidak
hilang dengan istirahat, dan dapat di curigai adanya gejala
dari eklamsi. (Setyaningrum 2009:11)
B. KONSEP DASAR PERSALINAN
1. Definisi Persalinan
Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya servik, dan
janin turun dalam jalan lahir. kelahiran adalah proses dimana janin dan
ketuban di dorong keluar melalui jalan lahir. (Sarwono, 2008:100)
Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin
yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan
dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam
2. Tujuan persalinan normal
Tujuan asuhan persalinan normal adalah menjaga kelangsungan
hidup dan memberikan drajat kesehatan yang tinggibagi ibu dan bayinya,
melalui berbagai upaya yang terintegrasi dan lengkap tetapi dengan
intervensi yang seminimal mungkin agar prinsip keamanan dan kualitas
pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang diinginka (optimal). (JNPK-KR:
2008:3)
3. Tanda dan Gejala
Sebelum terjadi persalinan sebenarnya beberapa minggu
sebelumnya wanita memasuki ”Bulannya”, minggunya dan ”Harinya” yang
disebut kala pendahuluan (preparatomi satge of labor) memberikan tanda-tanda sebagai berikut :
a. Ligehtening/settling/dropping yaitu kepala turun memasuki pintu atas panggul (PAP) terutama pada primigravida.
b. Perut kelihatan lebih melebar, fundus uteri turun.
c. Perasaan sering atau susah kencing, karena kandung kemih tertekan
oleh bagian terendah janin.
d. Rasa sakit perut dan pinggang oleh adanya kontraksi-kontraksi lemah
dari uterus kadang-kadang disebut ”false labor pains” Serviks menjadi lembek mulai mendatar dan sekresinya bertambah dan bisa
bercampur darah (bloody show).
e. Tanda dan gejala inpartu seperti adanya penipisan dan pembukaan
serviks, kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan servik
(frekuensi minimal 2 kali dalam 10 menit), dan cairan lendir
4. Lima benang merah
Ada lima aspek dasar atau lima benang merah, yang penting dan
saling terkait asuhan persalinan yang bersih dan aman. Berbagai aspek
tersebut melekat pada setiap persalinan, baik normal maupun patologis.
Lima benang merah tersebut (JNPK-KR, 2008 : 7) adalah :
a. Keputusan klinik
Langkah dalam membuat keputusan klinik antara lain:
1) Pengumpulan data utama dan relevan untuk membuat
keputusan
2) Menginterprestasikan data dan mengidentifikasi masalah.
3) Membuat diagnosis atau menentukan masalah yang
terjadi/dihadapi
4) Menilai adanya kebutuhan dan kesiapan intervensi untuk
mengatasi masalah.
5) Menyusun rencana pemberian asuhan atau intervensi untuk
solusi masalah.
6) Melaksanakan asuhan/intervensi terpilih.
7) memant au dan mengevaluasi efektifitas asuhan atau intervensi.
b. Asuhan sayang ibu dan bayi
Beberapa prinsip dasar asuhan sayang ibu adalah dengan
mengkutsertakan suami dan keluarga selama proses persalinan dan
kelahiran bayi. Banyak hasil menunjukkan bahwa jika para ibu
diperhatikan dan diberi dukungan selama persalinan dan kelahiran
asuhan yang akan mereka terima, mereka akan mendapatkan hasil
rasa aman dan hasil yang lebih baik.
Disebutkan pula bahwa hal tersebut pula dapat mengurangi
terjadinya persalinan dengan vakum, cunam, dan seksio sesar, dan
persalinan berlangsung lebih cepat.
c. Pencegahan infeksi
Pencegahan infeksi adalah bagian esensial dari asuhan
lengkap yang di berikan kepada ibu dan bayi baru lahir serta harus di
laksanakan secara rutin pada saat menolong persalinan dan
kelahiran. Saat memberikan asuhan dasar selama kunjungan
antenatal atau post partum, dan saat menatalaksana penyulit.
1) Tujuan pencegahan infeksi dalam pelayanan asuhan kesehatan
a) Meminimalkan infeksi yang disebabkan oleh
mikroorganisme.
b) Menurunkan resiko penularan penyakit yang mengancam
jiwa seperti hepatitis, HIV/AIDS.
2) Tindakan – tindakan pencegahan infeksi dalam pelayanan
asuhan kesehatan, yaitu :
a) Cuci tangan ;
b) Memakai sarung tangan ;
c) Memakai perlengkapan pelindung (celemek/ baju penutup,
kacamata, sepatu tertutup) ;
d) Menggunakan asepsis atau teknik aseptic ;
e) Memproses alat bekas pakai ;
g) Menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan serta
pembuangan sampah secara benar.
d. Pendokumentasian
Pendokumentasian adalah bagian penting dari proses
membuat keputusan klinik karena memungkinkan penolong
persalinan untuk terus menerus memperhatikan asuhan yang
diberikan selama proses persalinan dan kelahiran bayi. Catat semua
asuhan yang telah diberikan kepada ibu dan bayi, jika asuhan yang
telah diberikan tidak dicatat maka maka dapat dianggap bahwa tidak
pernah dilakukan asuhan yang dimaksud.
e. Rujukan
Rujukan adalah kondisi optimal dan tepat waktu ke fasilitas
kesehatan rujukan atau yang memiliki sarana lebih lengkap
diharapkan mampu menyelamatkan jiwa ibu dan bayinya.
Singkatan BAKSOKUDA dapat digunakan dalam
mempersiapkan rujukan :
1) B : ( Bidan ) Pastikan bahwa ibu dan bayi di dampingi oleh
penolong persalinan saat di bawa ke fasilitas kesehatan rujukan.
2) A : ( Alat ) Bawa perlengkapan dan bahan-bahan untuk asuhan
persalinan ke tempat rujukan, perlengkapan dan bahan-bahan
tersebut mungkin di perlukan dalam perjalanan.
3) K : ( Keluarga ) Beritahu ibu dan keluarga mengenai ibu dan
janin, suami atau keluarga yang lain harus menemani ibu dan
4) S : ( Surat ) Berikan surat ke tempat rujukan, surat ini harus
memberikan identifikasi mengenai ibu dan bayi.
5) O : ( Obat ) Bawa obat-obatan esensial pada mungkin diperlukan
selama perjalanan.
6) K : ( Kendaraan ) Siapkan kendaraan yang paling mungkin untuk
merujuk dalam kondisi yang cukup nyaman.
7) U : ( Uang ) Ingatkan pada keluarga agar membawa uang dalam
jumlah yang cukup.
8) Da : ( Darah untuk transfusi )
(JNPK-KR, 2008 : 36)
5. Faktor Penting Dalam Persalinan
a. Passange (jalan lahir)
Adalah jalan lahir yang harus dilewati oleh janin terdiri dari
rongga panggul, dasar panggul, serviks dan vagina. Agar janin dan
plasenta dapat melalui jalan lahir tanpa ada rintangan, maka jalan
lahir tersebut harus normal. Rongga-rongga panggul yang normal
adalah pintu atas panggil hampir berbentuk bundar, sacrum lebar dan
melengkung, promontorium tidak menonjol ke depan, kedua spina
ischiadica tidak menonjol kedalam, sudut arcus pubis cukup luas
(90-100), ukuran conjugata vera (ukuran muka belakang pintu atas
panggul yaitu dari bawah simpisis ke promontorium) ialah 10-11 cm,
ukuran diameter transversa (ukuran melintang pintu atas panggul)
14 cm, diameter oblique (ukuran sserong pintu atas panggul)
Jalan lahir dianggap tidak normal dan kemungkinan dapat
menyebabkan hambatan persalinan apabila panggul sempit
seluruhnya, panggul sempit sebagian, panggul miring, panggul
seperti corong, ada tumor dalam panggul. Dasar panggul terdiri dari
otot-otot dan macam-macam jaringan, untuk dapat dilalui bayi
dengan mudah jaringan dan otot-otot harus lemas dan mudah
meregang, apabila terdapat kekakuan pada jaringan, maka otot-otot
ini akan mudah ruptur.
Kelainan pada jalan lahir lunak diantaranya disebabkan oleh
serviks yang kaku (pada primi tua primer atau sekunder dan serviks
yang cacat atau skiatrik), serviks gantung (OUE terbuka lebar, namun
OUI tidak terbuka), serviks konglumer (OUI terbuka, namun OUE
tidak terbuka), edema serviks (terutama karena kesempitan panggul,
sehingga serviks terjepit diantara kepala dan jalan lahir dan timbul
edema), terdapat vaginal septum, dan tumor pada vagina.
b. Power (kekuatan)
Power adalah kekuatan atau tenaga untuk melahirkan yang
terdiri dari his atau kontraksi uterus dan tenaga meneran dari ibu.
Power merupakan tenaga primer atau kekuatan utama yang
dihasilkan oleh adanya kontraksi dan retraksi otot-otot rahim.His
adalah kontraksi otot-otot rahim pada persalinan.Kontraksi adalah
gerakan memendek dan menebalnya otot-otot rahim yang terjadi
diluar kesadaran (involuter) dan dibawah pengendalian syaraf
Retraksi adalah pemendekan otot-otot rahim yang bersifat
menetap setelah adanya kontraksi.His yang normal adalah timbulnya
mula-mula perlahan tetapi teratur, makin lama bertambah kuat
sampai kepada puncaknya yang paling kuat kemudian
berangsur-angsur menurun menjadi lemah. His tersebut makin lama makin
cepat dan teratur jaraknya sesuai dengan proses persalinan sampai
anak dilahirkan. His yang normal mempunyai sifat : kontarksi otot
rahim mulai dari salah satu tanduk rahim, kontraksi bersifat simetris,
fundal dominan yaitu menjalar ke seluruh otot rahim, kekuatannya
seperti memeras isi rahim, otot rahim yang berkontraksi tidak kembali
ke panjang semula sehingga terjadi retraksi dan pembentukan
segmen bawah rahim, bersifat involunter yaitu tidak dapat diatur oleh
parturient. Tenaga meneran merupakan kekuatan lain atau tenaga
sekunder yang berperan dalam persalinan, tenaga ini digunakan
pada saat kala 2 dan untuk membantu mendorong bayi keluar,
tenaga ini berasal dari otot perut dan diafragma.
Meneran memberikan kekuatan yang sangat membantu
dalam mengatasi resistensi otot-otot dasar panggul. Persalinan akan
berjalan normal, jika his dan tenaga meneran ibu baik. Kelainan his
dan tenaga meneran dapat disebabkan karena hypotonic / atonia
uteri dan hypertonic / tetania uteri.
c. Passanger
Passenger terdiri dari janin dan plasenta. Janin merupakan
passanger utama, dan bagian janin yang paling penting adalah
90% bayi dilahirkan dengan letak kepala. Kelainan-kelainan yang
sering menghambat dari pihak passanger adalah kelainan ukuran
dan bentuk kepala anak seperti hydrocephalus ataupun
anencephalus, kelainan letak seperti letak muka ataupun letak dahi,
kelainan kedudukan anak seperti kedudukan lintang ataupun letak
sungsang.
d. Psyche (psikologis)
Faktor psikologis ketakutan dan kecemasan sering menjadi
penyebab lamanya persalinan, his menjadi kurang baik, pembukaan
menjadi kurang lancer. Menurut Pritchard, perasaan takut dan cemas
merupakan faktor utama yang menyebabkan rasa sakit dalam
persalinan dan berpengaruh terhadap kontraksi rahim dan dilatasi
serviks sehingga persalinan menjadi lama.
e. Penolong (tenaga kesehatan)
Meliputi pengalamannya dalam memimpin persalinan,
kesabaran dan pengertiannya dalam menghadapi pasien terutama
terhadap primípara. (Safrudin,2009:101)
6. Mekanisme Persalinan Normal
Mekanisme persalinan merupakan gerakan janin dalam
menyesuaikan dengan ukuran dirinya dengan ukuran panggul saat kepala
melewati panggul, yaitu :
a. Engangement
Engangement pada primigravida terjadi pada bulan terakhir
kehamilan, dan pada multigravida terjadi pada awal persalinan.
pintu atas panggul dengan sutura sagitalis melintang/oblik didalam
jalan lahir dan sedikit fleksi. (Sumarah,2009:88)
b. Penurunan kepala
Menurut Cuningham (1995) dan Varney (2002) seperti dikutip
pada sumarah (2009:92), kekuatan yang mendukung yaitu tekanan
cairan amnion, tekanan langsung fundus pada bokong, kontraksi
otot-otot abdomen, ekstensi dan pelurusan badan janin atau tulang
belakang janin menyebabkan penurunan kepala.
c. Fleksi
Gerakan fleksi disebabkan karena janin terus didorong maju
tetapi kepala janin terhambat oleh serviks, dinding panggul atau
dasar panggul.Pada kepala janin, dengan adanya fleksi maka
diameter oksipitofrontalis 12cm berubah menjadi
suboksipitobregmatika 9 cm. Posisi dagu bergeser kearah dada janin.
(Sumarah, 2009:92)
d. Rotasi dalam
Rotasi dalam atau putar paksi dalam adalah pemutaran
bagian terendah janin dari posisi sebelumnya kearah depan sampai
dibawah simpisis. Gerakan ini adalah upaya kepala janin untuk
menyesuaikan dengan bentuk jalan lahir yaitu bentuk bidang tengah
dan pintu bawah panggul.Rotasi ini terjadi setelah kepala melewati
hodge III (setinggi spina) atau setelah didasar panggul. Pada
pemeriksaan dalam ubun- ubun kecil mengarah ke jam 12.
e. Ekstensi
Penyebab dikarenakan sumbu jalan lahir pada pintu bawah
panggul mengarah ke depan dan ke atas, sehingga kepala
menyesuaikan dengan cara ekstensi agar dapat melaluinya. Pada
saat itu ada dua gaya yang mempengaruhi, yaitu :
1) Gaya dorong dari fundus uteri kearah belakang.
2) Tahanan dasar panggul dan simpisis kearah depan.
Hasil kerja dari dua gaya tersebut mendorong ke vulva dan
terjadilah ekstensi. Maka berangsur–angsur lahirlah ubun-ubun
kecil, ubun-ubun besar, dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu. Pada
saat kepala sudah lahir seluruhnya, dagu bayi berada di atas anus
ibu.
(Sumarah,2009:95)
f. Rotasi luar
Terjadinya gerakan rotasi luar atau putar paksi luar
dipengaruhi oleh faktor-faktor panggul,sama seperti pada rotasi
dalam. (Sumarah,2009:97)
g. Ekspulsi
Setelah terjadinya rotasi luar, bahu depan berfungsi sebagai
hypomochlion untuk kelahiran bahu belakang. Kemudian setelah
kedua bahu lahir disusul lahirlah trochanter depan dan belakang
sampai lahir janin seluruhnya. Gerakan kelahiran bahu depan, bahu
7. Langkah Pertolongan Persalinan dan Manajemen Kebidanan Pada Ibu
Bersalin
Berlangsungnya proses persalinan normal dibagi menjadi 4 kala, yaitu:
a. Kala I (Kala Pembukaan)
Berlangsung antara pembukaan nol sampai pembukaan
lengkap (10 cm). Pada fase aktif Lamanya kala 1 untuk primigravida
berlangsung 13 jam, sedangkan multigravida sekitar 7 jam dengan
perhitungan pembukaan primigravida 1 cm/jam dan pembukaan
multigravida 2 cm/jam. (Saifuddin, 2008:N8)
1) Kala I ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu:
a) Fase laten
Dimana pembukaan servik berlangsung lambat, sampai
pembukaan 3 cm berlangsung dalam 7–8 jam.
b) Fase aktif
Berlangsung selama 6 jam dan dibagi atas 3 subfase, yaitu
fase akselerasi berlangsung selama 2 jam (pembukaan
terjadi 4 cm), fase dilatasi maksimal selama 2 jam
pembukaan berlangsung cepat menjadi 9 cm, fase
deselerasi berlangsung lambat dalam waktu 2 jam
(pembukaan menjadi 10 cm atau lengkap).
Fase-fase tersebut diatas dijumpai pada primigravida pada
multigravida pun demikian, tetapi fase laten, fase aktif dan
2) Asuhan Kala I Persalinan
a) Menghadirkan orang yang dianggap penting oleh ibu seperti
suami, dan keluarga untuk memberikan dukungan kepada
ibu.
b) Mengatur aktifitas dan posisi yang nyaman bagi ibu.
c) Membimbing ibu untuk rileks sewaktu ada his dengan cara
ibu diminta untuk menarik nafas panjang, kemudian
dilepaskan dengan meniup sewaktu ada his.
d) Menjaga privasi ibu antara lain dengan menggunakan
penutup atau tirai dan tidak menghadirkan orang lain tanpa
pengetahuan ibu dan seizin ibu.
e) Menjelaskan kemajuan persalinan, perubahan yang terjadi
dalam tubuh ibu, prosedur yang akan dilaksanakan dan hasil
pemeriksaan.
f) Menjaga kebersihan diri dengan membolehkan ibu untuk
mandi dan menganjurkan ibu untuk membasuh
kemaluannya seusai buang air besar atau kecil.
g) Mengatasi rasa panas ibu bersalin biasanya merasa panas
dan banyak keringat. Bidan dapat mengatasinya dengan
meggunakan kipas angin/AC.
h) Masase dengan melakukan pijatan pada punggung dan
mengusap perut dengan lembut.
i) Pemberian cukup minum untuk memenuhi kebutuhan energi
j) Mempertahankan kandung kemih tetap kosong dengan
menyarankan ibu untuk berkemih sesering mungkin.
k) Memberikan support pada ibu dan keluarga.
(Saifuddin,2008:N8)
b. Kala II (Kala Pengeluaran Janin)
Dimulai dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai bayi lahir.
pada kala ini his terkoordinir, kuat, cepat, dan lebih lama, kira-kira 2–
3 menit sekali, kepala janin telah turun masuk ruang panggul
sehingga terjadilah tekanan pada otot-otot dasar panggul yang
secara reflektoris menimbulkan rasa mengedan karena tekanan pada
rektum, ibu merasa seperti ingin BAB, dengan tanda anus terbuka,
kepala janin mulai kelihatan, vulva membuka dan perineum
meregang. Dengan his mengedan yang terpimpin dan lahirlah kepala,
diikuti oleh seluruh badan janin, kala II pada primi: 2 jam pada multi: 1
jam. (sumarah, 2009:106)
1) Tanda dan gejala kala II
a) Ibu merasa ingin meneran (dorongan meneran/doran)
b) Perineum menonjol (perjol)
c) Vulva vagina membuka (vulka)
d) Adanya tekanan pada spincter anus (teknus)
e) Jumlah pengeluaran air ketuban meningkat
f) Meningkatnya pengeluaran darah dan lendir
g) Kepala telah turun didasar panggul
h) Ibu kemungkinan ingin buang air besar
2) Asuhan Kala II
a) Memberikan dukungan pada ibu dalam menghadapi
persalinan.
b) Memberikan ibu makanan dan minuman jika tidak ada his.
c) Mendampingi ibu dengan keluarga atau suami saat
melahirkan.
d) Memantau DJJ setelah setiap kontraksi untuk memastikan
janin tidak mengalami bradikardi (nadi 12x/menit). Selama
mengedan yang lama akan terjadi pengurangan aliran darah
dan oksigen ke janin.
e) Memimpin persalinan jika sudah ada tanda-tanda Kala II.
f) Memakai sarung tangan saat kepala bayi terlihat
g) Menjaga kebersihan ibu jika ada kotoran keluar dari rektum,
bersihkan dengan kain bersih.
h) Bantu kepala bayi lahir perlahan, sebaiknya diantara his.
i) Begitu kepala bayi lahir, usap mulut dan hidung bayi dengan
kasa bersih dan biarkan kepala bayi memutar.
j) Begitu bahu sudah pada posisi anterior-posterior yang benar,
bantulah persalinan dengan cara tepat.
k) Segera setelah lahir, periksa keadaaan bayi, letakkan di perut
ibu, dan segara keringkan bayi dengan handuk bersih yang
hangat. Setelah bayi kering, selimuti bayi dengan handuk baru
yang bersih dan hangat.
l) Minta ibu memegang bayinya. Tali pusat di klem di dua
m) Letakkan bayi dalam pelukan ibu dan mulai menyusui.
(JNPK,2008:79)
c. Kala III (Kala Pengeluaran Uri)
Dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya
plasenta, yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit.Setelah bayi
lahir uterus teraba keras dengan fundus uteri agak diatas pusat.
Beberapa menit kemudian uterus berkontraksi lagi untuk melepaskan
plasenta dari dindingnya. (sumarah, 2009:7)
Tanda-tanda pelepasan plasenta adalah uterus yang
membundar dan keras, uterus terdorong keatas, tali pusat bertambah
panjang, ada semburan darah.Setelah plasenta lahir harus diperiksa
untuk melihat apakah ada bagian plasenta yang tertinggal di dalam
uterus, dan biasanya eksplorasi kavum secara manual.
(Prawirohardjo, 2008;117)
1) Manajemen aktif Kala III
Penatalaksanaan aktif Kala III (Pengeluaran Aktif
Plasenta) membantu menghindarkan terjadinya perdarahan
pasca persalinan. Adapun penatalaksanaan kala III meliputi:
a) Pemberian oksitosin dengan segera (2 menit setelah bayi
lahir).
b) Pengendalian tarikan pada tali pusat.
c) Pemijatan uterus segera setelah pada tali pusat.
2) Asuhan Kala III
a) Memberikan oksitosin untuk merangsang uterus berkontraksi
kelahiran bayi guna menghasilkan oksitosin alamiah atau
memberikan ergometrin 0,2 mg IM.
b) Melakukan penegangan tali pusat terkendali (PTT), PTT
dilakukan hanya kalau uterus berkontraksi.
c) Segera setelah plasenta dan selaputnya dikeluarkan, masase
fundus agar menimbulkan kontraksi. Hal ini dilakukan untuk
mengurangi pengeluaran darah dan mencegah perdarahan
pasca persalinan.
d) Jika menggunakan manajemen aktif Kala III dan plasenta
belum lahir dalam 15 menit, berikan oksitosin 10 unit IM dosis
kedua.
e) Periksa kandung kemih dan lakukan katerisasi jika kandung
kemih penuh.
f) Periksa adanya tanda-tanda pelepasan plasenta.
d. Kala IV (Kala Pengawasan atau Observasi)
Kala IV dimaksudkan untuk melakukan observasi karena
perdarahan postpartum paling sedikit terjadi pada 2 jam pertama.
Hal-hal yang diobservasi adalah tingkat kesadaran pasien.
Pemeriksaan tanda-tanda vital : tekanan darah, nadi, suhu dan
pernapasan, kontraksi uterus dan perdarahan yang terjadi.
Darah yang keluar harus ditukar sebaik-baiknya. Kehilangan
darah pada persalinan biasanya disebabkan oleh luka pada
pelepasan uri dan robekan pada serviks dan perineum.Perdarahan
perdarahan lebih maka harus dicari penyebabnya. (Manuaba,
2010:174)
Sebelum meninggalkan wanita pospartum petugas harus
memantau ibu setiap 15 menit pada jam pertama setelah kelahiran
plasenta dan 30 menit pada jam kedua setelah persalinan.
(Saifuddin, 2008:5)
WHO/UNICEF/IVACG Task Force, 2006 merekomendasikan
pemberian 2 dosis vitamin A 200.000 IU dalam selang waktu 24 jam
pada ibu pasca bersalin untuk memperbaiki kadar vitamin A pada ASI
dan mencegah terjadinya lecet puting susu. Selain itu suplementasi
vitamin A akan meningkatkan daya tahan tubuh ibu terhadap infeksi
perlukaan atau laserasi akibat proses persalinan. (JNPK-KR
2008:110)
1) Asuhan Kala IV
a) Evaluasi fungsi fundus dengan meletakkan jari tangan anda
secara melintang antara pusat dan fundus uteri.
b) Perkirakan kehilangan darah secara keseluruhan.
c) Periksa perenium perdarahan aktif (misalnya, apakah dari
laserasi atau episiotomi). Laserasi diklasifikasikan
berdasarkan luasnya robekan, yaitu:
(1) Laserasi derajat 1: Robekan terjadi pada mukosa
vagina, komisura posterior, dan kulit perineum. Tidak
perlu dijahit jika tidak ada perdarahan dan aposisi luka
(2) Laserasi derajat 2: Robekan terjadi pada mukosa
vagina, komisura posterior, kulit perineum, dan otot
perineum. Diperlukan penjahitan.
(3) Laserasi derajat 3: Robekan terjadi pada mukosa
vagina, komisura posterior, kulit perineum, otot
perineum, dan otot sfingter ani.
(4) Laserasi derajat 4: Robekan terjadi pada mukosa
vagina, komisura posterior, kulit perineum, otot
perineum, otot sfingter ani, dan dinding depan rektum.
Penolong APN tidak dibekali keterampilan untuk
reparasi laserasi perineum derajat 3 atau 4. Segera
rujuk ke fasilitas rujukan.
d) Evaluasi kondisi secara umum.
e) Dokumentasikan semua asuhan dan temuan selama kala IV
persalinan.
(JNPK-KR,2008:111)
8. Pertolongan persalinan menggunakan metode Asuhan Persalinan Normal
58 angkah Asuhan Persalinan Normal :
1) Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala dua
2) Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk
mematahkan ampul oksitosin dan memasukkan alat suntik sekali
pakai 2 ½ ml ke dalam wadah partus set.
3) Memakai celemek plastik.
4) Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan
5) Menggunakasn sarung tangan DTT pada tangan kanan yang akan
digunakan untuk pemeriksaan dalam.
6) Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi
dengan oksitosin dan letakkan kembali ke dalam wadah partus set.
7) Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah dan
gerakan vulva ke perineum.
8) Melakukan pemeriksaan dalam, pastikan pembukaan sudah
lengkap dan selaput ketuban sudah pecah.
9) Mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam
larutan clorin 0,5 %, membuka sarung tangan dalam keadaan
terbalik dan merendamnya dalam larutan clorin 0,5 %.
10) Memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai,
pastikan DJJ dalam batas normal (120-160 x/menit).
11) Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin
baik, meminta ibu untuk meneran saat ada His apabila ibu sudah
merasa ingin meneran.
12) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk
meneran (pada saat ada His, bantu ibu dalam posisi setengah
duduk dan pastikan ia meneran nyaman).
13) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang
kuat untuk meneran.
14) Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi
nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam
15) Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu,
jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm.
16) Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian bawah bokong ibu.
17) Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali
kelengkapan alat dan bahan.
18) Memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan.
19) Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5-6 cm,
memasang handuk bersih untuk mengeringkan janin pada perut.
20) Memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin.
21) Menunggu hingga kapala janin selesai melakukan putaran paksi
luar secara spontan.
22) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara
biparental.Menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi.
Dengan lembut gerakan kepala kearah bawah dan distal hingga
bahu depan muncul dibawah arkus pubis dan kemudian gerakan
arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.
23) Setelah bahu lahir, geser tangan bawah kearah perineum ibu untuk
menyanggah kepala, lengan, dan siku sebelah atas.
24) Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung
kearah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai
bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri diantara kedua lutut janin)
25) Menilai penilaian selintas:
a) Apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan.
26) Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian
tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks.
Ganti handuk basah dengan handuk/kain yang kering. Membiarkan
bayi atas perut ibu.
27) Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi
dalam uterus.
28) Memberitahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus
berkontraksi baik.
29) Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit IM
(intramuskuler) di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan
aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin).
30) Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem
kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah distal dan
jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.
31) Dengan satu tangan. Pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi
perut bayi), dan lakukan pengguntingan tali pusat diantara 2 klem.
32) Mengikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi
kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya
dengan simpul kunci pada sisi lainnya.
33) Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di
kepala bayi.
34) Memindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva.
35) Meletakkan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas
36) Setelah uterus berkontraksi, menegangkan tali pusat dengan
tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan
hati-hati kearah dorsokranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40
detik, hentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga timbul
kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.
37) Melakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta
terlepas, minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat
dengan arah seejajar, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan
tekanan dorso-kranial).
38) Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta
dengan hati-hati. Bila perlu (terasa ada tahanan), pegang plasenta
dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu
pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.
39) Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri
dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan
bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus
terabakeras).
40) Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan
kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput
ketuban sudah lahir lengkap, dan masukan kedalam kantong plastik
yang tersedia.
41) Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum.
Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.
42) Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi
43) Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu
paling sedikit 1 jam.
44) Setelah satu jam, lakukan penimbangan/pengukuran bayi, beri tetes
mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 1mg intramaskuler di
paha kiri anterolateral.
45) Setelah 1 jam pemberian vitamin K1 berikan suntikan imunisasi
Hepatitis B di paha kanan anterolateral.
46) Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan
pervaginam.
47) Mengajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan
menilai kontraksi.
48) Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah.
49) Memeriksakan nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15
menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit
selama jam kedua pasca persalinan.
50) Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas
dengan baik.
51) Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin
0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan
setelah di dekontaminasi.
52) Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang
sesuai.
53) Membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Membersihkan
sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian
54) Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk
membantu apabila ibu ingin minum.
55) Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5 %.
56) Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5%
melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan
merendamnya dalam larutan klorin 0,5%.
57) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
58) Melengkapi partograf.
9. Partograf
Partograf adalah catatan grafik kemajuan persalinan untuk
memantau keadaan ibu dan janin tanpa menghiraukan apakah persalinan
tersebut normal atau dengan komplikasi (Prawirohardjo, 2008:315).
Partograf adalah alat bantu yang di gunakan selama fase aktif persalinan
(JNPK-KR, 2008: 54). Partograf di pakai untuk memantau kemajuan
persalinan dan membantu petugas kesehatan dalam mengambil
keputusan dalam penatalaksanaan (Saifuddin,2008:N8).
Tujuan dari partograf menurut Prawrohardjo (2008:315) adalah :
a. meningkatkan mutu dan keteraturan pemantauan janin dan ibu
selama persalinan.
b. untuk mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan
menilai pembukaan serviks melalui pemeriksaan dalam.
c. untuk mengetahui lebih awal adanya persalinan abnormal dan
mencegah terjadinya persalinan lama yang dapat menurunkan resiko
perdarahan post partum dan sepsis, mencegah persalinan macet,
d. membantu mengambil keputusan lebih awal, kapan seorang ibu
harus di rujuk, di percepat dan di akhiri persalinannya.
Partograf di mulai pada pembukaan 4 cm ( fase aktif ). Partograf
sebaiknya di buat untuk setiap ibu bersalin, tanpa menghiraukan apakah
persalinan tersebut normal atau dengan komplikasi.Menurut JNPK-KR,
(2008:55) partograf harus di gunakan :
1) Untuk semua ibu dalam fase aktif kala I persalian sebagai elemen
penting asuhan persalian.
2) Selama persalianan dan kelahiran di semua tempat.
3) Secara rutin oleh semua penolong persalinan yang memberikan
asuhan kepada ibu selama persalinan dan kelahiran.
Petugas harus mencatat kondisi ibu dan bayi sebagai berikut :
1) Denyut jantung janin, di periksa setiap ½ jam
2) Air ketuban, catat air ketuban setiap pemeriksaan vagina :
a) U : Selaput utuh
b) J : Selaput pecah
c) M : Air ketuban bercampur mekonium
d) K : Tidak ada cairan ketuban atau kering
3) Perubahan kepala janin ( Molding atau Molase )
a) O : Sutura terpisah
b) 1 : Sutura ( pertemuan dan tulang tengkorak ) Bersesuaian
c) 2 : Sutura tumpang tindih tetapi dapat di perbaiki
d) 3 : Sutura tumpang tindih dan tidak dapat di perbaiki
4) Pembukaan mulut rahim (serviks) di nilai setiap 4 jam dan di berikan
5) Penurunan : mengacu pada bagian kepala (di bagi 5 bagian) yang
teraba pada pemeriksaan abdomen / luar di atas simfisis pubic. Catat
dengan lingkaran (O) pada setiap pemeriksaan dalam. Pada posisi
O/5 sinsiput (S) atau paruh atas kepala berada di simfisis pubis
6) Waktu : menyatakan berapa jam waktu yang telah di jalani sesudah
pasien di terima
7) Jam ; catat jam sesungguhnya
8) Kontraksi : catat setiap setengah jam; lakukan palpasi untuk
menghitung banyaknya kontraksi dalam 10 menit dan lamanya tiap
kontraksi dalam hitungan detik
a) kurang dari 20 detik ; kontraksi lemah
b) antara 20 – 40 detik : kontraksi sedang
c) lebih dari 40 detik : kontraksi kuat
9) Oksitosin ; jika memakai oksitosin catatlah banyaknya oksitosin per
volume cairan infuse dan dalam tetesan per menit
10) Catat semua obat yang di berikan
11) Nadi catatlah setiap 30 – 60 menit dan tandai dengan sebuah titik
besar
12) Tekanan darah cacatlah setiap 4 jam dan tandai dengan anak panah
13) Suhu badan catatlah setiap 2 jam
14) Protein aseton dan volume urine catatlah setiap 2 jam.
Jika temuan – temuan melintas kearah kanan dari garis waspada,
petugas kesehatan harus melakukan penilaian terhadap kondisi ibu dan
10. Identifikasi komplikasi dan deteksi dini pada persalinan
Tabel 2.3 Deteksi pada tanda persalinan
Temuan – temuan anamnesis / pemeriksaan
Rencana Asuhan
Riwayat bedah sesar 1. Segera rujuk ke fasilitas yang mempunyai kemampuan untuk melakukan bedah sesar.
2. Dampingi ibu ke tempat rujukan 3. berikan dukungan dan semangat Perdarahan pervaginam selain
lendir darah
Jangan lakukan pemeriksaan dalam 1.baringkan ibu ke sisi kiri
2.pasang infus menggunakan jarum berdiameter besar (ukuran 16 atau 18) dan berikan ringer laktat /garam fisiologis (NS)
3.segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan bedah sesar.
4.dampingi ibu ketempat rujukan. Kurang dari 37 minggu
(persalinan kurang bulan)
1.segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan menatalaksanakan gawat darurat obstetri dan bayi baru lahir. 2.dampingi ibu ketempat rujukan. Berikan dukungan dan semangat
Ketuban pecah disertai dengan keluarnya mekonimium kental
1.baringkan ibu ke sisi kiri 2.dengar DJJ
3.segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan bedah sesar.
4.dampingi ibu ketempat rujukan. Ketuban pecah (lebih dari 24jam)
kurang dari umur kehamilan.
1.segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan menatalaksanakan gawat darurat obstetri dan bayi baru lahir. 2.dampingi ibu ketempat rujukan. Berikan dukungan dan semangat
1.baringkan ibu miringke kiri 2.pasang infus
3.berikan dosis awal 4gr MgSO420% IV selama 20menit 4.suntikan 10gr MgSO4
5.segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan menatalaksanakan gawat darurat obstetri dan bayi baru lahir. 6.dampingi ibu ketempat rujukan. Berikan dukungan dan semangat
TFU 40cm/lebih 1.segera rujuk
2.dampingi ibu ketempat rujukan DJJ kurang dari 100 / lebih dari
180x/menit pada dua kali penilaian dengan jarak 5 menit
1.baringkan ibu miring ke sisi kiri dan anjurkan untuk bernafas secara teratur
2.pasang infus
3.segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan menatalaksanakan gawat darurat obstetri dan bayi baru lahir. 4.dampingi ibu ketempat rujukan. Berikan dukungan dan semangat
Primipara dalam fase aktif kala 1 persalinan dengan penurunan kepala jamin 5/5
1.baringkan ibu miring ke kiri
Temuan – temuan anamnesis / pemeriksaan
Rencana Asuhan Presentasi bukan belakang kepala
(sungsang, letak lintang dll)
1.baringkan ibu miring ke sisi kiri
2.segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan menatalaksanakan gawat darurat obstetri dan bayi baru lahir. 3.dampingi ibu ketempat rujukan. Berikan dukungan dan semangat
Tali pusat menumbung (jika tali pusat masih berdenyut)
1.gunakan sarung tangan disenfeksi tingkat tinggi, letakan satu tangan di vagina dan jauhkan kepala janin dari taki pusat yang menumbung, tangan lain mendorong bayi melalui dinding abdomen agar bagian terbawah janin tidak menekan tali pusatnya.
2.segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan menatalaksanakan gawat darurat obstetri dan bayi baru lahir. 3.dampingi ibu ketempat rujukan. Berikan dukungan dan semangat
Tanda dan gejala syok a.nadi cepat >110x/menit
b.TD menurun (sistolik<90mmHg) c.pucat
d.berkeringat, kulit lembab, dingin e.nafas cepat >30x/menit
f.cemas
g.produksi urine sedikit
1.baringkan ibu ke sisi kiri
2.jika mungkin naikan kedua kaki ibu untuk meningkatkan aliran darah ke jantung
3.pasang infus
4.segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan menatalaksanakan gawat darurat obstetri dan bayi baru lahir. 5.dampingi ibu ketempat rujukan. Berikan dukungan dan semangat
Tanda dan gejala fase laten berkepanjangan
a.pembukaan servik kurang dari 4cm setelah 8jam
b.kontraksi teratur (lebih dari 2 dalam 10menit)
1.segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan menatalaksanakan gawat darurat obstetri dan bayi baru lahir. 2.dampingi ibu ketempat rujukan. Berikan dukungan dan semangat
Tanda dan gejala belum inpartu a.frekuensi kontraksi kurang dari dua kali dalam 10 menit dan lamanya kurang dari 20detik b.tidak ada perubahan pada servik dalam waktu 1jam hingga 2jam
1.anjurkan ibu untuk minum dan makan 2.anjurkan ibu untuk bergerak bebas
3.jika kontraksi berhenti atau tidak ada perubahan servik, evaluasi DJJ, jika tidak ada tanda-tanda kegawat daruratan pada ibu dan janin, persilahkan ibu untuk pulang dengan nasehat untuk:
-menjaga pola makan dan minum
-datang untuk mendapatkan asuhan jika terjadi peningkatan frekuensi dan lama kontraksi.
Tanda dan gejala partus lama a.pembukaan servik mengarah kesebelah kanan garis waspada partograf
b.pembukaan servik kurang dari 1cm perjam
c.frekuensi kontraksi kurang dari 2kali dalam 10menit dan lamanya kurang dari 40detik
1.segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan menatalaksanakan gawat darurat obstetri dan bayi baru lahir. 2.dampingi ibu ketempat rujukan. Berikan dukungan dan semangat.
C. KONSEP DASAR BAYI BARU LAHIR
1. Definisi bayi baru lahir
Bayi baru lahir disebut juga dengan neonatus merupakan individu
yang sedang bertumbuh dan baru saja mengalami trauma kelahiran serta
harus dapat melakukan penyesuaian diri dari kehidupan intra uterin ke
kehidupan ekstrauterin. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir
pada uisa kehamilan 37 – 42 minggu dan berat badanya 2500 – 4000
gram. (dewi 2010:1)
2. Perubahan fisiologis bayi baru lahir (prawirohardjo, 2008:161)
a. Perubahan metabolisme karbohidrat.
Dalam waktu 2 jam setelah lahir akan terjadi penurunan kadar
gula darah, untuk menambah energi pada jam 3 pertama setelah lahir
diambil dari hasil metabolisme asam lemak, bila karena sesuatu hal
misalnya bayi mengalami, metabolisme asam lemak tidak memenuhi
kebutuhan pada neonatus maka kemungkinan besar bayi akan
menderita hipoglikemia.
b. Perubahan suhu tubuh
Ketika bayi baru lahir, bayi berada pada suhu lingkungan yang
lebih rendah dibanding suhu dalam rahim Ibu, apalagi bayi dibiarkan
dalam suhu kamar 25o C maka bayi akan kehilangan panas melalui
konveksi, radiasi dan evaporasi sebanyak 200kal/ kg, BB/ menit.
Sedangkan produksi panas yang dihasilkan tubuh bayi hanya 1/10
nya.