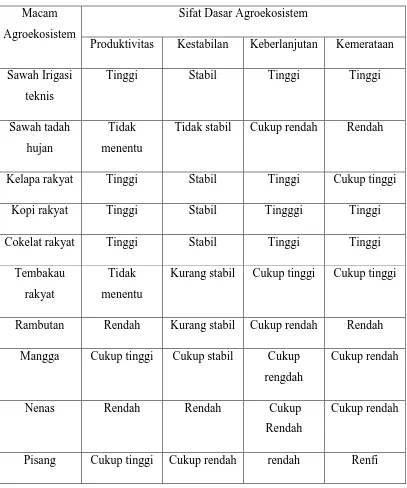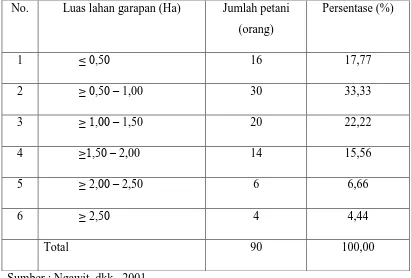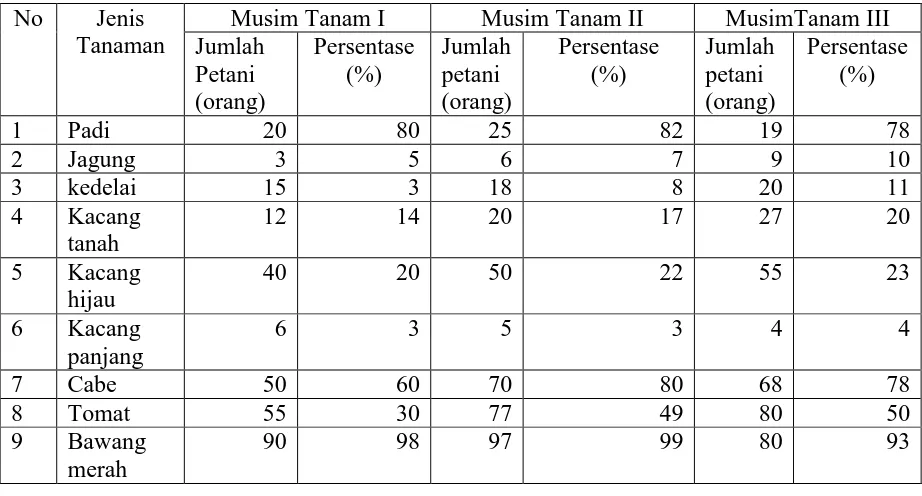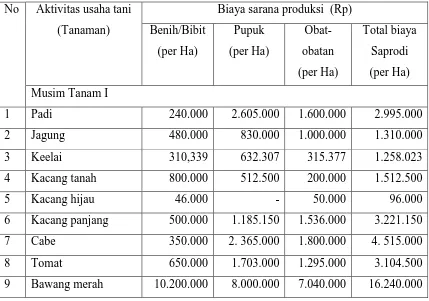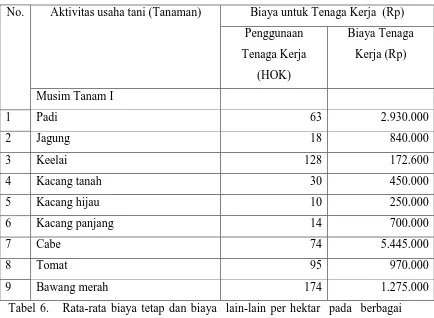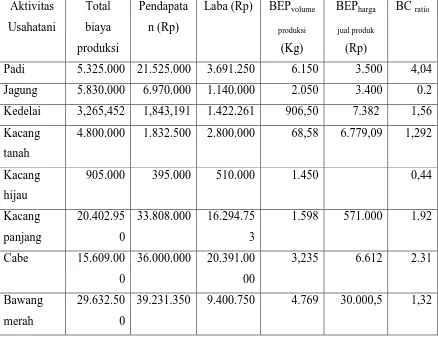LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM PERTANIAN
DISUSUN OLEH :
KELOMPOK IV
Anggota :
HASAN BASRI C1M 013 069
HENDRI WIJAYA C1M 013 070
HIKMATUL AMNI C1M 013 076
HUSNUL HAKIM C1M 013 079
I GEDE ASENA PRADANA C1M 013 080 I KOMANG TRI JUNIARTA W. C1M 013 081
IBNU FAHMI SAIF C1M 013 083
IDAYANTI C1M 013 084
IDRIS HAMDAN WARIDHO C1M 013 085 IKA MAULANI MEYARTI C1M 013 086
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MATARAM
HALAMAN PENGESAHAN
Laporan ini diterima sebagai salah satu syarat yang diperlukan guna
menyelesaikan peraktikum Mata Kuliah Sistem Pertanian,.
Mataran, 20 juni 2016
Mengetahui :
Koordinator Praktikum
Sistem Pertanian
KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan YME atas
limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Laporan Sistem Pertanian ini dapat
terselesaikan dengan baik. Laporan Sistem Sertanian dimaksud agar dapat
menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan Mata Kuliah Sistem Pertanian.
Kami menyadari bahwa isi penulisan maupun sistematika Laporan Sistem
Pertanian ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu secara lapang kami
membuka kritik maupun saran dari pembaca untuk perbaikan dan kesempurnaan
Laporan Sistem Pertanian ini.
Ucapan terima kasih kami sampaikan dengan tulus kepada semua pihak
yang telah membantu dalam penyusunan Laporan sistem Pertanian ini sehingga
dapat berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik.
Mataram, 20 Juni 2016
DAFTAR ISI
II.Acara I. Pengamatan Terhadap Sisfat-Sifat Dasar AgroekosistemA. Landasan Teori... III.Acara II. Deskripsi Dan Identifikasi Produktivitas Lahan Dalam
DAFTAR TABEL
halaman
TABEL 1. Karakteristik dari sifat dasar beberapa agroekeosistem... 9
TABEL 2. Sebaran petani responden berdasarkan jenis tanaman yang diusahakan setiap musim tanam lokasi survey...
21
TABEL 3.Rata-rata produksi per hektar beberapa jenis komuditi yang diusahakan oleh petani responden pada setiap musim tanam...
21
TABEL 4. Rata-rata biaya sarana produksi yang dikeluarkan petani per - hektar untuk setiap aktivitas pengusahaan tanaman ...
22
TABEL 5. Rata-rata biaya tenaga kerja per hektar pada berbagai aktivitas usahatani yang dikeluarkan petani responden untuk setiap jenis komuditi...
22
TABEL 6. . Rata-rata biaya tetap dan biaya lain-lain per hektar pada berbagai aktivitas usahatani yang dikeluarkan petani responden untuk setiap jenis komuditi...
23
TABEL 7. Rata-rata total biaya produksi, pendapatan, laba, BEP dan BC-ratio per hektar pada berbagai aktivitas usahatani petani responden untuk setiap jenis komuditi...
I. PENDAHULUAN
Sistem pertanian merupakan pengelolaan komoditas tanaman untuk
memperoleh hasil yang diinginkan yaitu berupa bahan pangan, keuntungan
financial, kepuasan batin atau gabungan dari ketiganya. Sistem pertanian di
daerah tropika, termasuk Indonesia berbeda dengan daerah subtropis dan daerah
beriklim sedang. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kondisi iklim, jenis
tanaman dan keadaan sosial ekonomi petaninya.
Meningkatkan produksi pertanian suatu negara adalah suatu tugas yang
kompleks, kerena banyaknya kondisi yang berbeda yang harus dibina atau diubah
oleh orang ataupun kelompok yang berbeda pula. Seperti halnya permasalahan
pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengimbangi permintaan atas
kebutuhan pangan meningkat pesat, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan
produksi hasil pertanian yang mampu untuk memenuhi permintaan kebutuhan
akan bahan pangan.
Namun hal itu juga mendorong para petani untuk mencoba menanam
jenis-jenis tanaman baru, dan dengan bantuan para insinyur dan para peneliti
untuk mengembangkan varietas tanaman tersebut dengan menemukan teknik
penggunaan pupuk, mengatur kelembapan tanah yang lebih maju serta
menggunakan teknologi pertanian yang lebih maju untuk mengembangkan
pembangunan pertanian ke arah yang lebih baik sehingga mampu untuk
memenuhi kebutuhan pangan dari jumlah masyarakat yang terus meningkat.
Pada dasarnya pembangunan pertanian di Indonesia sudah berjalan sejak
masyarakat Indonesia mengenal cara bercocok tanam, namun perkembangan
tersebut berjalan secara lambat. Pertanian awalnya hanya bersifat primitif dengan
cara kerja yang lebih sederhana. Seiring berjalannya waktu, lama kelamaan
pertanian berkembang menjadi lebih modern untuk mempermudah para petani
mengolah hasil pertanian dan mendapatkan hasil terbaik dan banyak.
Dengan demikian pembangunan pertanian mulai berkembang dari masa ke
masa. Dalam proses pembangunan pertanian tersebut, bantuan para ahli di bidang
fasilitas maupun pegetahuan kepada para petani untuk memberi metode baru
kepada para petani dan mengubah cara berpikir mereka menjadi lebih kompleks
sehingga mampu untuk meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.
Mengenai perkembangan luas lahan dan luas produksi padi yang
dihasilkan, terlihat bahwa sejak masa Orde Baru memegang pemerintahan (1966)
sampai dengan tahun 1987 luas lahan irigasi melonjak hampir 2 kali lipat dengan
laju sebesar 2,4% per tahun. Luas kenaikan maksimum dicapai pada tahun 1987.
tendensi ini diikuti dengan melonjaknya jumlah produktifitas padi. Pada tahun
1987 produksi padi meningkat hingga 44 juta ton, naik 3 kali lipat sejak tahun
1966. Tingkat produksi yang dicapai ini diperoleh dengan naiknya intensitas
tanam hingga mencapai rata-rata 1,8. Mengenai kenaikan produksi persatuan luas,
tercatat naik dari 2,4 ton/ha menjadi 4,5 ton/ha. Nilai ini bila diplotkan ke dalam
sejarah evolusi padi di negara-negara berkembang dengan Jepang sebagai
perbandingan, telah berada di fase keempat bersama-sama dengan Taiwan.
Walaupun demikian masih lebih rendah Korea dan Jepang yang telah mencapai
6-7 ton/ha, tetapi jauh lebih tinggi dari Philipina, Laos, Myanmar maupun Vietnam.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa lahan irigasi memberikan peranan
yang besar dalam mencapai swasembada pangan. Kira-kira 60-70% padi
diproduksi dari lahan beririgasi. Walaupun demikian, bila melihat perkembangn
penduduk, untuk terus mempertahankan swasembada pangan masih perlu banyak
inovasi baru. Perhitungan secara sederhana mengenai luas lahan beririgasi terus
meningkat seirama dengan pertambahan penduduk. Padahal kalau melihat
besarnya derajad irigasi seperti telah diuraikan di atas, peluang mengembangkan
lahan irigasi secara horizontal, terutama di pulau-pulau yang termasuk dalam grup
pertama, nampaknya semakin sempit.
Yang menjadi persoalannya adalah bagaimana menyeimbangkan antar
penyediaan sumberdaya air dari alam dengan kebutuhan air khususnya untuk
memproduksi bahan pangan yang semakin meningkat itu tetapi tanpa merusak
kondisi hidrologinya sendiri.
Sistem pertanian dari masa ke masa yang dibangun oleh berbagai generasi
tentunya juga memiliki kekurangan yang timbul akibat kebijakan-kenijakan
tersebut.
Sistem bertanam adalah pola-pola tanam yang digunakan petani dan
interaksinya dengan sumber-sumber alam dan teknologi yang tersedia. Sedangkan
pola tanam adalah penyusunan cara dan saat tanam dari jenis-jenis tanaman yang
akan ditanam berikut waktu-waktu kosong (tidak ada tanaman) pada sebidang
lahan tertentu. Pola tanam ini mencakup beberapa bentuk/macam sebagai berikut:
1. Multiple Cropping (System Tanam Ganda)
Penanaman lebih dari satu jenis tanaman pada sebidang tanah yang sama dalam
satu tahun.Yang termasuk dalam Sistem Tanam ganda ini adalah : Intercropping,
Mixed Cropping, dan Relay Cropping.
a. Intercropping (Sistem Tumpangsari)
Penanaman serentak dua atau lebih jenis tanaman dalam barisan
berselang-seling pada sebidang tanah yang sama. Sebagai contoh yang umum
dilakukan oleh petani di India adalah tumpangsari antara tanaman sorghum dan
tanaman kacang tunggak dan di Indonesia antara tanaman ubikayu dan jagung
atau kacang tanah.
b. Mixed Cropping (Sistem Tanam Campuran)
Penanaman dua atau lebih jenis tanaman secara serentak dan bercampur
pada sebidang lahan yang sama. Dewasa ini termasuk di Indonesia., sistem ini
jarang digunakan petani karena adanya berbagai masalah terutama yang
menyangkut pemeliharaan. Sistem tanam campuran lebih banyak diterapkan
dalam usaha pengendalian hama dan penyakit.
c. Relay Cropping (Sistem Tanam Sisipan)
Penanaman sisipan adalah penanaman suatu jenis tanaman ke dalam
pertanaman yang ada sebelum tanaman yang ada tersebut dipanen. Atau dengan
istilah lain : suatu bentuk tumpang sari dimana tidak semua jenis tanaman ditanam
jagung ditanam bersama-sama kemudian ubikayu ditanam sebagai tanaman sela
satu bulan atau lebih sesudahnya.
2. Seguantial Cropping ( Pergiliran Tanaman)
Penanaman lebih dari satu jenis tanaman pada sebidang lahan dalam satu
tahun, dimana tanaman kedua ditanam setelah tanaman pertama dipanen.
Demikian pula bila ada tanaman ketiga, tanaman ini ditanam setelah tanaman
kedua dipanen.
3. Maximum Cropping (Sistem Tanam Maksimum)
Adalah pengusahaan lahan untuk mendapatkan hasil panen yang
setinggi-tingginya tanpa memperhatikan aspek ekonomisnya (biaya, pendapatan dan
keuntungan) dan apalagi aspek kelestarian produksinya dalam jangka panjang.
4. Sole Cropping/Monoculture (Sistem Tanam Tunggal)
Adalah penanaman satu jenis tanaman pada lahan dan periode waktu yang
sama. Pertanian lahan kering di Indonesia (selain lahan hutan) mencapai 57 juta
ha dan 18 juta ha diantaranya sudah mengalami degradasi yang berarti adanya
penurunan produktivitas dan ancaman perusakan lingkungan. Apabila dibiarkan.
Lahan yang mengalami proses degradasi tersebut akan bertambah rusak dan
akhirnya menjadi lahan kritis. Lahan kering yang kritis/marginal inilah yang
merupakan factor penyebab rendahnya kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu
dilakukan upaya peningkatan produktivitasnya. Salah satu system bertanam yang
berpeluang besar adalah system bertanam konservasi dengan budidaya tanaman
lorong (“aley cropping”). Sistem bertanam ini merupakan cara konservasi
vegetatif yang efektif dan murah, serta menyumbangkan bahan hijauan yang dapat
II. ACARA I : PENGAMATAN TERHADAP SISFAT-SIFAT
DASAR AGROEKOSISTEM
A. Landasan Teori
Tembakau merupakan salah satu komoditi pertanian andalan yang dapat
memberikan kesempatan kerja yang luas dan memberikan penghasilan bagi
masyarakat pada setiap rantai agribisnisnya. Selain itu tembakau menunjang
pembagunan nasional berupa pajak dan devisa negara. Dalam perdagangan
tembakau internasional, tembakau Indonesia sangat dikenal, seperti tembakau deli
dari Sumatera Utara (Cahyono, 2005).
Tembakau merupakan tanaman yang memiliki benefeciary tertinggi
dibandingkan dengan tanaman semusim lainnya. Lebih dari itu, usahatani
tembakau sebagai pendorong bergeraknya roda perekonomian di daerah. Oleh
karenanya, sektor pertembakauan harus berjalan dengan saling integrated, agar ini
yang memperkuat sektor tembakau tetap eksis di negeri kretek ini (Santos, 2008).
Nanas merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomis
cukup tinggi dan sangat potensial baik untuk pasar negeri (domestik) maupun
sasaran pasar luar negeri (ekspor). Permintaan pasar dalam negeri terhadap buah
nanas cenderung terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk,
semakin baik pendapatan masyarakat maka makin tinggi kesadaran penduduk
akan nilai gizi dari buah-buahan dan makin bertambahnya permintaan bahan baku
industri pengolahan buah-buahan. Selain memenuhi permintaan domestik,
Indonesia juga sudah mulai mengekspor nanas dalam bentuk buah segar
(Rukmana, 2003).
Hortikultura merupakan salah satu sektor pertanian yang dapat
dikembangkan di Indonesia karena dapat meningkatkan sumber pendapatan
petani. Seiring dengan berkembangnya permintaan pasar baik di Indonesia
maupun untuk ekspor, nanas dapat dimanfaatkan dalam industry pengolahan
penghasilan mereka melalui usahatani nanas yang dapat menguntungkan petani
(Soedarya, 2009).
Praktek budidaya Kopi multistrata (mixed/ shaded coffee atau agroforestri
kopi) yang dipercaya dapat memenuhi kepentingan ekonomi dan ekologi pada
saat yang sama, baru menjadi wacana sejak dua dasa warsa belakangan ini.
Padahal budidaya kopi multi-strata sudah lama dipraktekkan oleh para petani kopi
tradisional di berbagai belahan dunia, termasuk di antaranya di Sumberjaya – kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) Tulang Bawang, propinsi Lampung,
Pulau Sumatra. Kajian tentang manfaat ekologi dari budidaya kopi multistrata
mengarah pada kesimpulan bahwa budidaya kopi multistrata memiliki fungsi
konservasi terhadap keragaman hayati (Faminow dan Rodriguez, 2001;
Soto-Pinto et al., 2000; Perfecto dan Armbrect, 2003), dan mampu menekan erosi
sampai pada tingkat yang dapat diterima (Arsyad, 1977; Ginting, 1982; Afandi et
al., 1999 dan Hartobudoyo, 1979). Perkembangan pasar kopi internasional
menunjukkan bahwa komoditas kopi yang dihasilkan oleh budidaya kopi yang
ramah lingkungan tersebut, yang oleh Giovanucci (2003) disebut sebagai salah
satu jenis „Sustainable Coffee‟, berpeluang untuk mendapatkan harga premium. Komoditas Kelapa di Indonesia memiliki peranan yang sangat strategis
baik dari segi social budaya, penerimaan devisa negara, sumber pendapatan petani
dan lapangan kerja yang sangat potensial dan tidak kalah pentingnya sebagai
sumber utama minyak makan dalam negeri. Penerimaan devisa negara dari
komoditas ini, dilaporkan pada tahun 1994 sebesar US $ 280.241 juta sedang pada
tahun 2000 devisa yang dihasilkan mencapai US$ 394 juta (Haz, 2001).
Peranannya sebagai sumber devisa cenderung meningkat namun fluktuatif
sehingga secara proporsional kontribusinya masih relatif kecil yaitu 0,75%
terhadap nilai total ekspor secara nasional (Tondok, 1998). Penerimaan devisa
tersebut pada dasarnya masih dapat ditingkatkan karena produk-produk kelapa
yang di ekspor masih sebagian besar adalah produk tradisional atau produk
primair yang menghadapi persaingan ketat di pasar internasional dengan produk
yang sama dari negara-negara penghasil kelapa lainnya (Filipina, India, Srilanka,
2002b). Sebagai sumber pendapatan perkebunan kelapa berperan sangat besar
karena tanaman kelapa mempunyai kemampuan berproduksi sepanjang tahun
terus menerus dan dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga petani.
Kasryno (1993) melaporkan jumlah penduduk yang hidupnya tergantung secara
langsung maupun tidak langsung dari tanaman kelapa diperkirakan tidak kurang
dari 12,8 juta jiwa/tahun atau 14,5% dari angkatan kerja sub sektor perkebunan.
Kakao (Theobroma cacao) berasal dari Benua Amerika khususnya
Negarabagian yang mempunyai iklim tropis. Sangat sulit untuk mengetahui
Negara bagianmana tepatnya tanaman ini berasal, karena tanaman ini telah
tersebar secara luassemenjak penduduk daerah itu masih hidup mengembara.
Tanaman ini mulai masukke Indonesia sekitar tahun 1560 yang dibawa oleh orang
Spanyol melalui Sulawesidan kakao mulai dibudidayakan secara luas sejak tahun
1970 (Darwis, 2007).
Kakao merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan yang
peranannyac ukup penting bagi perkonomian nasional, khususnya sebagai
penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa Negara. Di samping itu
kakao juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan
pengembangan agroindustri. Padatahun 2002, perkebunan kakao telah
menyediakan lapangan kerja dan Sumber pendapatan bagi sekitar 900 ribu kepala
keluarga petani yang sebagian besar beradadi Kawasan Timur Indonesia (KTI)
serta memberikan sumbangan devisa terbesar ketiga sub sector perkebunan setelah
karet dan minyak sawit dengan nilai US $701juta (Tino, 2006).
Daerah tadah hujan hanya mengandalkan ketersediaan air dari curah
hujan dalam proses produksi pertanian. Pengaturan sistem pertanaman diatur
dalam bentuk tumpang sari menggunakan tanaman dengan umur panen yang
berbeda. Pertumbuhan tanaman di daerah tadah hujan tidak banyak memerlukan
air dan merupakan salah satu alternatif untuk memecahkan masalah keterbatasan
air. Di lahan kering, tanaman yang digunakan disesuaikan antara ketersediaan
air dengan tanaman yang biasa ditanam petani dan tentunya memiliki pangsa
Daerah tadah hujan atau lahan sawah semi intensif merupakan
sumberdaya fisik yang potensial untuk pengembangan komoditas jagung.
Sebagian dari lahan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan pada
umumnya hanya ditanami sekali dalam setahun yaitu dengan tanaman padi,
bahkan pada beberapa lokasi di Sumatera Barat lahan sawah tadah hujan sudah
berubah menjadi lahan tidur atau tidak ditanami akibat kendala irigasi yang tidak
lancar (Misran 2013).
B. Tujuan Praktikum
Untuk mengetahui a). Produktivitas; b). Kestabilan; c.) Keberlanjutan ;
dan d.) Kemerataan dari beberapa sistem agroekosistem
C. Bahan dan Alat
Transportasi Buku data
Lembar Quisener Alat tulus menulis
Tustel Masker
Topi Sarung tangan
D. Pelaksanaan Praktikum
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode deskriptif
dengan teknik survei. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan
petani sampel (responden) yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah
disiapkan. Masing-masing kelompok praktikan yang beranggotakan 10-12 orang,
melakukan survey di beberapa wilayah tipe agroekosistem lahan perkebunan yang
ada di wilayah Pulau Lombok. Pada masing-masing wilayah ditetapkan 3-5 petani
responden yang mewakili agroekosistem lahan secara purposive sampling, atas
dasar keprofesionalannya dibidang pengelolaan usahatani dan luas kepemilikan
lahan (minimal 1 ha).
Paramater yang diamati adalah : a). Produktivitas; b). Kestabilan; c.)
E. Tabulasi dan Analisis Data
Tabel 1. Karakteristik dari sifat dasar beberapa agroekeosistem
Macam
Agroekosistem
Sifat Dasar Agroekosistem
Produktivitas Kestabilan Keberlanjutan Kemerataan
Sawah Irigasi
teknis
Tinggi Stabil Tinggi Tinggi
Sawah tadah
hujan
Tidak
menentu
Tidak stabil Cukup rendah Rendah
Kelapa rakyat Tinggi Stabil Tinggi Cukup tinggi
Kopi rakyat Tinggi Stabil Tingggi Tinggi
Cokelat rakyat Tinggi Stabil Tinggi Tinggi
Tembakau
rakyat
Tidak
menentu
Kurang stabil Cukup tinggi Cukup tinggi
Rambutan Rendah Kurang stabil Cukup rendah Rendah
Mangga Cukup tinggi Cukup stabil Cukup
rengdah
Cukup rendah
Nenas Rendah Rendah Cukup
Rendah
Cukup rendah
F. Pembahasan Usaha Tani Tembakau
Tembakau merupakan salah satu komoditi pertanian andalan yang dapat
memberikan kesempatan kerja yang luas dan memberikan penghasilan bagi
masyarakat pada setiap rantai agribisnisnya. Selain itu tembakau menunjang
pembagunan nasional berupa pajak dan devisa negara. Dalam perdagangan
tembakau internasional, tembakau Indonesia sangat dikenal, seperti tembakau deli
dari Sumatera Utara (Cahyono, 2005).
Tembakau merupakan tanaman yang memiliki benefeciary tertinggi
dibandingkan dengan tanaman semusim lainnya. Lebih dari itu, usahatani
tembakau sebagai pendorong bergeraknya roda perekonomian di daerah. Oleh
karenanya, sektor pertembakauan harus berjalan dengan saling integrated, agar ini
yang memperkuat sektor tembakau tetap eksis di negeri kretek ini (Santos, 2008).
Secara umum perkembangan luas areal tembakau di Indonesia selama
tahun 1971-2009 tampak berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar
3,23%. Total luas areal tembakau menunjukkan peningkatan pasa periode tahun
1971-1997 dengan laju pertumbuhan rata-rata mencapai 4,76% per tahun.
Menginjak tahun 1998-2009 terjadi kecenderungan penurunan laju pertumbuhan
luas areal tembakau menjadi 0,07% per tahun. Terjadinya penurunan laju
pertumbuhan luas areal tembakau pada periode tahun 1990-2009, dikarenakan
tembakau di Indonesia hanya diusahakan Perkebunan Rakyat (PR) dan
Perkebunan Besae Negara (PBN), sementara Perkebunan Besar Swasta (PBS)
tidak melakukan penanaman sama sekali (Anonimus, 1995).
Usahatani Nanas.
Nanas merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomis
cukup tinggi dan sangat potensial baik untuk pasar negeri (domestik) maupun
sasaran pasar luar negeri (ekspor). Permintaan pasar dalam negeri terhadap buah
nanas cenderung terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk,
semakin baik pendapatan masyarakat maka makin tinggi kesadaran penduduk
akan nilai gizi dari buah-buahan dan makin bertambahnya permintaan bahan baku
Indonesia juga sudah mulai mengekspor nanas dalam bentuk buah segar
(Rukmana, 2003).
Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi nanas yang
diperoleh dengan harga jual oleh petani nanas. Jadi, penerimaan ditentukan oleh
besar kecilnya produksi nanas yang dihasilkan dan harga dari produksi nanas
tersebut.
Usaha Tani Kop Rakyat
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agraris yang memiliki
kekayaan alam yang berlimpah, salah satu kekayaan alam tersebut adalah tanaman
kopi, tanaman kopi hampir tumbuh di seluruh tanah Nusantara. Hal ini sebenarnya
tidak terlalu mengherankan mengingat Indonesia memiliki wilayah yang kaya
akan bahan baku hayati dan hewani. Desa timba nuh, kecamatan pringga sela,
Lotim merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi komoditi pertanian
untuk dikembangkan, khususnya perkebunan kopi yang tumbuh subur.
Potensi dan kekayaan alam tersebut bila dimanfaatkan dengan benar dan
sungguh akan menciptakan keuntungan ekonomi yang akan berdampak pada
pendapatan daerah, petani, perusahaan dan masyarakat dalam rangka
menciptakanlapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi
pengangguran. Dari perkembangan teknologi pertanian dengan pertimbangan
aspek kesehatan dan minat pasar, para petani sudah mulai beralih, dari budidaya
kopi secara konvensional menjadi sistem organik (organic coffee).
Pemanfaatan potensi merupakan suatu strategi pembangunan yang tepat,
untuk menjawab tantangan dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan
pertanian organik di sektor pertanian dan perkebunan, khususnya budidaya kopi
secara organik, dalam rangka menciptakan produk yang ramah lingkungan dan
juga bernilai ekonomis tinggi, karena mengingat sekarang ini masyarakat
indonesia sudah mulai sadar akan pentingnya kesehatan dengan mengkonsumsi
makanan dan minuman sehat, ini semua didapatkan dari hasil pertanian organik.
Dalam rangka menciptakan produk yang bernilai ekonomis maka keseimbangan
maupun lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemasaran produk dalam rangka
mensukseskan otonomi daerah sangat dibutuhkan. Pemerintah Daerah harus bisa
mengembangkan potensi alam yang ada di daerahnya. khususnya bidang pertanian
dan perkebunan. Tanaman kopi bias menjadi andalan mengingat tanaman ini bisa
tumbuh dengan subur di tanah NTB, dan selama ini kopi terus dikonsumsi dan
sudah tidak dapat dipisahkan dari masyarakat NTB.
Usaha Tani Kelapa
Komoditas kelapa di Indonesia memiliki peranan yang sangat strategis
baik dari segi social budaya, penerimaan devisa negara, sumber pendapatan petani
dan lapangan kerja yang sangat potensial dan tidak kalah pentingnya sebagai
sumber utama minyak makan dalam negeri. Penerimaan devisa negara dari
komoditas ini, dilaporkan pada tahun 1994 sebesar US $ 280.241 juta sedang pada
tahun 2000 devisa yang dihasilkan mencapai US$ 394 juta (Haz, 2001).
Peranannya sebagai sumber devisa cenderung meningkat namun fluktuatif
sehingga secara proporsional kontribusinya masih relatif kecil yaitu 0,75%
terhadap nilai total ekspor secara nasional (Tondok, 1998). Penerimaan devisa
tersebut pada dasarnya masih dapat ditingkatkan karena produk-produk kelapa
yang di ekspor masih sebagian besar adalah produk tradisional atau produk
primair yang menghadapi persaingan ketat di pasar internasional dengan produk
yang sama dari negara-negara penghasil kelapa lainnya (Filipina, India, Srilanka,
Vietnam) maupun dengan produk-produk substitusi yang tersedia (Tarigans,
2002b). Sebagai sumber pendapatan perkebunan kelapa berperan sangat besar
karena tanaman kelapa mempunyai kemampuan berproduksi sepanjang tahun
terus menerus dan dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga petani.
Kasryno (1993) melaporkan jumlah penduduk yang hidupnya tergantung secara
langsung maupun tidak langsung dari tanaman kelapa diperkirakan tidak kurang
dari 12,8 juta jiwa/tahun atau 14,5% dari angkatan kerja sub sektor perkebunan.
Sedangkan pada tahun 1998 diperkirakan melibatkan sebanyak 20 juta jiwa
(Kasryno, et. al. 1998; Sulistyo, 1998) Dari sisi pendapatan usahatani belum
dilaksanakan di sentra-sentra produksi kelapa di Indonesia menunjukkan bahwa
kehidupan keluarga petani kelapa secara umum sampai saat ini masih berada
dibawah garis kemiskinan (Tarigans, 2002a). Bavappa et al. (1995) melaporkan
bahwa proporsi pendapatan petani kelapa di Indonesia sangat kecil hanya 20%
dari total pendapatannya. Disamping itu, usaha-usaha yang telah dilaksanakan
pemerintah dalam periode tiga dekade terakhir belum sepenuhnya memberikan
perbaikan taraf hidup petani kelapa. Kenyataan demikian, menunjukkan peranan
ekonomi komoditas kelapa belum optimal bila dilihat dari segi pendapatan petani,
pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan sumber devisa negara secara
nasional. Melihat permasalahan demikian dipandang perlu melakukan perubahan
paradigma pembangunan kelapa nasional, kearah metoda yang dinilai mampu
memecahkan masalah tersebut.
Usaha Tani Kakao
Sampai saat ini, komoditas kakao Indonesia masih sangat bergantung pada
pasar ekspor dalam bentuk biji yaitu sekitar 83%. Disisi lain, kakao Indonesia
khususnya yang dihasilkan oleh perkebunan rakyat di pasaran internasional
dihargai paling rendah, karena didominasi oleh biji-biji tanpa fermentasi, kadar
kotoran yang tinggi dan banyak terkontaminasi serangga, jamur dan mikotoksin,
serta cita rasa yang lemah. Diskon terhadap kakao Indonesia yang dikenakan oleh
pemerintah Amerika Serikat terus meningkat dari tahun ke tahun, yang pada tahun
2005 telah mencapai US$ 250 per ton (Askindo, 2005). Kabupaten Jembrana
merupakan kabupaten yang memiliki luas areal panen kakao terluas di Provinsi
Bali. Sebagian besar produksi kakao diusahakan oleh perkebunan rakyat.
Pendapatan yang diperoleh petani dari usahatani kakao ini sangat berkaitan erat
dengan produksi dan alokasi faktor produksi. Demikian juga dengan penggunaan
biaya untuk pengeluaran input produksi. Produktivitas tenaga kerja pada usaha
tani kakao terkait dengan kemampuan memperoleh manfaat yang
sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan output
yang optimal. Petani selalu mempertimbangkan biaya produksi secara
pengusahaan input, teknologi, dan curahan kerja yang berorientasi pada
pencapaian produksi yang maksimum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan :
(1) mengetahui penerapan pola tanam tumpang sari dan alasan pemilihan pola
tanam tumpang sari, (2) menganalisis ada tidaknya perbedaan efisiensi
penggunaan biaya produksi pada keempat pola tanam tumpang sari, (3)
menganalisis ada tidaknya perbedaan dan keuntungan pada keempat pola tanam
tumpang sari, danserta (4) menganalisis ada tidaknya perbedaan produktivitas
tenaga kerja dari pada keempat pola tanam tumpang sari.
Lahan Tadah Hujan
Sifat curah hujan yang sangat bervariasi mempunyai pengaruh yang besar
pada produksi pertanian. Variasi curah hujan tahunan terutama menyebabkan
kegagalan tanam atau panen akibat kekeringan atau banjir. Meskipun secara
umum awal musim hujan telah ketahui, namun sifat hujan selama musim tanam
masih sulit diprediksi karena sangat bervariasi dari tahun ke tahun. Pemahaman
mengenai penyebab variasi sifat hujan ini di pulau Lombok akan dapat memberi
implikasi pada perbaikan strategi tanam dan pengelolaan air untuk pertanian.
Kemarau panjang dan periode tanpa hujan yang terjadi beberapa minggu
di tengah-tengah musim hujan sering menyebabkan kacaunya sistem managemen
pertanian lahan sawah tadah hujan. Seringkai petani gogo rancah, misalnya,
menugal pada saat kondisi lengas tanah sangat rendah dengan keyakinan besok
atau lusa akan turun hujan yang cukup untuk memulai pertumbuhan padi di
sawahnya. Akan tetapi apabila prakiraan mereka meleset maka benih yang ditugal
tidak tumbuh atau bibit yang baru saja tumbuh segera mati karena kekeringan
(Pramudia et al, 1991). Hal ini menyebabkan mereka harus menugal ulang dan
membeli benih lagi sehingga membuat sistem pertanian gogo rancah di lahan
tadah hujan sering tidak efisien. Sayuti et al. (2001) menyatakan bahwa apabila
terjadi periode kering beberapa minggu pada periode awal pertumbuhan tanaman
yang paling parah mengalami cekaman air adalah tanaman padi yang ditanam di
lahan tadah hujan. Dampak kekurangan air dari tanaman lahan tadah hujan ini
tanaman di lahan irigasi. Berdasarkan catatan dalam NTB dalam angka yang
diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Propinsi NTB (1997) menunjukkan
bahwa hasil rata-rata tanaman padi sawah tadah hujan berkisar antara 2 – 3.5 ton/ ha, sementara padi di lahan beririgasi dapat memberi hasil antara 4.5 sampai 5.5
ton/ha. Kedelai yang ditanam sebar di lahan tadah hujan hasilnya akan mendekati
hasil tanaman kedelai di daerah irigasi (kira-kira 1000 kg/ha) bila sepanjang
musim tanam terdapat hujan lebih kurang 100 mm; Namun hal itu jarang terjadi
dan umumnya mereka memetik hasil kurang dari 500 kg/ha. Prakiraan sifat hujan
sepanjang musim merupakan hal yang sangat penting pada sistem lahan tadah
hujan karena dapat menggambarkan perkiraan jumlah air tersedia pada suatu
periode tertentu. Hal ini bila dibarengi dengan seleksi jenis tanaman yang
kebutuhan airnya sesuai dengan ketersediaan air maka kejadian cekaman air pada
tanaman dapat ditekan sekecil mungkin. Selain itu, penggunaan prakiraan jatuh
awal musim hujan dan sifat hujan sepanjang musim tanam juda dapat untuk
menentukan saat tanam atau saat tugal yang tepat sehingga tanaman yang baru
tumbuh tidak mati karena kekeringan atau justru membusuk karena terlalu banyak
hujan. Informasi sifat hujan selama musim tanam akan menjadi dasar pemilihan
tanaman yang sesuai dengan kondisi musim yang diprakirakan. Tindakan ini akan
dapat menyelamatkan produksi pertanian dari gagal panen karena
kekeringan.Tulisan ini bertujuan membahas hubungan fluktuasi curah hujan dan
kebutuhan air bagi pertanian tadah hujan di Lombok.
Sawah Irigasi Teknis
Implementasi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan efisiensi
pemanfatan air irigasi pada lahan sawah tadah hujan di antaranya dengan
pembuatan embung. Dengan embung, pengairan tanaman pada musim kemarau
dapat memanfaatkan air limpasan hujan yang ditampung di kolam penampung air.
Pada musim hujan, kolam dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan ikan. Data
penelitian di Pati, Jawa Tengah menunjukkan keuntungan yang diperoleh dari
penerapan teknologi embung mencapai sekitar 50% lebih tinggi daripada tanpa
sumur bor di areal pertanaman. Sumur dilengkapi dengan pompa air untuk
menaikkan air ke permukaan. Untuk menggerakkan pompa digunakan mesin
traktor pengolah tanah. Selain dapat menyelamatkan tanaman dari ancaman
kekeringan pada musim kemarau, cara itu juga dapat meningkatkan intensitas
tanam dari satu kali (padi) menjadi dua kali (padi-padi), atau bahkan tiga kali
setahun (padi-padi-palawija).
Efisiensi pengelolaan air juga dapat dilakukan dengan strategi
penghematan air sawah irigasi, di antaranya dengan pemilihan varietas dan
metode pengelolaan air (metode macak-macak, gilir giring dan metode basah
kering). Dengan cara ini areal sawah yang dapat diairi pada musim kemarau
menjadi 2 kali lebih luas. Pemilihan varietas umur genjah dan atau toleran
kekeringan juga bisa menjadi alternatif. Umur varietas padi sawah berpengaruh
terhadap tingkat konsumsi air. Makin pendek atau genjah (90-100 hari) umur
tanaman padi, makin sedikit total konsumsi air bila dibanding dengan varietas
padi sawah berumur lebih panjang (> 125 hari). Beberapa ciri varietas padi sawah
yang relatif toleran terhadap kekurangan air adalah: laju transpirasi rendah dan air
daun potensial tetap tinggi pada kondisi tanah kekurangan air, dan bersifat ampibi
yaitu bisa ditanam pada lahan sawah dan kering. (Ali Bosar
Harahap/cybex.pertanian).
G. Simpulan dan Saran 1. kesimpulan
Berdasarkan hasil praktikum dan pembahasan maka dapat disimpulkan
sebagai berikut :
Budidya tanaman hortikultura dan perkebunan dalam berbagai
agroekosistem memiliki potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan namun
produktifitasnya masih rendah, masih belum stabil, keberlanjutan dan kemerataan
2. Saran
Dalam pengembangan dan peningkatan produktifitas, kestabilan,
keberlanjutan dan kemerataan tanaman hortikultura dan perkebunan, hendaknya
ditunjang dengan peningkatan sarana dan pra sarana serta perlu mendapatkan
III. ACARA II : DESKRIPSI DAN IDENTIFIKASI
PRODUKTIVITAS LAHAN DALAM
PENGUSAHAAN TANAMAN SEMUSIM DI
BEBERAPAWILAYAH PULAU LOMBOK
A. Landasan Teori
Penggunaan lahan di beberapa wilayah pulau Lombok, didominansi oleh
usaha tani ladang, tegalan, sawah tadah huan dan sawah irigasi dengan
memanfaatkan irigasi air permukaan dan air tanah dengan sumur bor.
Pemanfaatan untuk sawah irigasi teknis dan tadah hujan, cukup luas dan beragam,
yang diutamakan untuk pengusahaan tanaman pangan pokok seperti padi, jagung,
kacang tanah, kedelai, kacang hijau, ubi jalar, dan tanaman pangan penunjang
lainya seperti sayur-sayuran dan buah-buahan semusim. Penggunaan untuk usaha
perkebunan seperti kelapa, coklat, kopi, cengkeh dan vanili serta buah-buahan
tahunan tersebar di lereng bawah gunung sampai di daearah-daearah perbukitan
timur laut wilayah ini. Penggunaan lahan di wilayah lahan kering tipe III
(Contohnya di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur) didominansi
oleh sawah di bagaian selatan dan tengah, sawah tadah hujan dan tegalan di
bagian utara, sedangkan kebun campuran dekat dengan pemukiman penduduk.
Penggunaan lahan lainnya berupa rumput/padang pengembalaan, belukar dan
hutan terdapat di lereng bawah dan tengah gunung yang terletak di bagian utara
daerah tersebut.
Luas lahan garapan yang diusahakan oleh petani di tiga wilayah pulau
Lombok cukup bervariasi, yaitu berkisar antara 0,50 hektar hingga 2,50 hektar.
Pada Tabel 13 berikut disajikan luas lahan garapan petani responden di tiga
wilayah penelitian pulau Lombok. Tampak bahwa sebagaian besar petani di
wilayah Lombok memiliki lahan garapan antara 0,5 – 1,5 Ha, yaitu sebesar 55,55 %, sedangkan petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 Ha juga cukup banyak
yaitu mencapai 17,77 %. Sementara petani yang memiliki lahan garapan yang
wilayah Lombok, tampak bahwa lahan garapan yang diusahakan petani relatif
kurang luas, yaitu dengan rata-rata 0,78 Ha.
Tabel 13. Rata-rata luas lahan garapan petani di tiga wilayah penelitian
No. Luas lahan garapan (Ha) Jumlah petani
(orang)
Persentase (%)
1 ≤ 0,50 16 17,77
2 ≥ 0,50 – 1,00 30 33,33
3 ≥ 1,00 – 1,50 20 22,22
4 ≥1,50 – 2,00 14 15,56
5 ≥ 2,00 – 2,50 6 6,66
6 ≥ 2,50 4 4,44
Total 90 100,00
Sumber : Ngawit, dkk., 2001.
Sempitnya luas lahan garapan petani di wilayah Lombok akibat sering
terjadinya pembagian lahan terutama kepada anak-anak petani yang telah berumah
tangga, baik melalaui proses jual beli maupun berupa pembagian atau pemberian
orang tua kepada anak-anak mereka sebagai bekal untuk hidup mandiri. Selain itu
ditemukan pula beberapa petani responden di tiga wilayah penelitian, yaitu 4,22
– 6,44 % dari seluruh petani responden yang tidak mampu mengusahakan semua lahan yang dimilikinya. Hal ini terutama karena keterbatasan modal petani
terutama untuk sarana produksi, pengolahan tanah dan biaya air irigasi. Ini berarti
terjadi ketidak imbangan antara potensi lahan dengan produktivitas akibat
terbatasnya sarana produksi. Sehubungan dengan hal itu perlu dikaji secara
khusus potensi lahan yang ada dan produktivitasnya terutama untuk pengusahaan
kacang panjang, cabe rawit, tomat, terong, bayam, sawi, kangkung, bawang putih,
bawang merah, semangka, melon dan blewah.
B. Tujuan Praktikum
Untuk mengetahui tingkat produktivitas lahan dalam pengusahaannya
untuk tanaman semusim di beberapa wilayah Lombok melalui analisis pendapatan
petani yang mencangkup analisis: Produk dan nilai produk; Biaya produksi;
Pendapatan; Laba-Rugi; BIP; dan BC-ratio. Analisis ini dilakukan pada setiap
panenan komuditi pada setiap sistem pola tanam yang di usahakan oleh petani
responden.
C. Bahan dan Alat
Transportasi Buku data
Lembar Quisener Alat tulus menulis
Tustel Masker
Topi Sarung tangan
D. Pelaksanaan Praktikum
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode deskriptif
dengan teknik survei. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan
petani sampel (responden) yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah
disiapkan. Masing-masing kelompok praktikan yang beranggotakan 5 orang,
melakukan survey di beberapa wilayah tipe agroekosistem lahan baik lahan basah
(sawah dengan irigasi teknis) maupun lahan kering yang ada di wilayah Pulau
Lombok. Pada masing-masing wilayah ditetapkan 10 petani responden yang
mewakili agroekosistem lahan secara purposive sampling, atas dasar
keprofesionalannya dibidang pengelolaan usahatani dan luas kepemilikan lahan
Paramater yang diamati adalah : Modal (termasuk saprodi dan tenaga
kerja), Indeks pendapatan, BEP dan B/C-ratio (yang diukur berdasarkan total
biaya produksi, dan nilai hasil usaha selama siklus produksi).
E. Tabulasi dan Analisis Data
Tabel 2. Sebaran petani responden berdasarkan jenis tanaman yang diusahakan
setiap musim tanam lokasi survei
No Jenis Tanaman
Musim Tanam I Musim Tanam II MusimTanam III Jumlah
Tabel 3. Rata-rata produksi per hektar beberapa jenis komuditi yang diusahakan
oleh petani responden pada setiap musim tanam
5 Kacang hijau 15 3000 3.000.000
6 Kacang panjang 38 4.000 12.380.000
7 Cabe 90 4.000 15. 609.000
8 Tomat 500 2000 10.000.000
9 Bawang merah 48 10.000 48.000.000
Tabel 4. Rata-rata biaya sarana produksi yang dikeluarkan petani per - hektar
untuk setiap aktivitas pengusahaan tanaman
No Aktivitas usaha tani
(Tanaman)
Biaya sarana produksi (Rp)
Benih/Bibit
(per Ha)
Pupuk
(per Ha)
Obat-obatan
(per Ha)
Total biaya
Saprodi
(per Ha)
Musim Tanam I
1 Padi 240.000 2.605.000 1.600.000 2.995.000
2 Jagung 480.000 830.000 1.000.000 1.310.000
3 Keelai 310,339 632.307 315.377 1.258.023
4 Kacang tanah 800.000 512.500 200.000 1.512.500
5 Kacang hijau 46.000 - 50.000 96.000
6 Kacang panjang 500.000 1.185.150 1.536.000 3.221.150
7 Cabe 350.000 2. 365.000 1.800.000 4. 515.000
8 Tomat 650.000 1.703.000 1.295.000 3.104.500
Tabel 5. Rata-rata biaya tenaga kerja per hektar pada berbagai aktivitas
usahatani yang dikeluarkan petani responden untuk setiap jenis komuditi
No. Aktivitas usaha tani (Tanaman) Biaya untuk Tenaga Kerja (Rp)
Penggunaan
Tenaga Kerja
(HOK)
Biaya Tenaga
Kerja (Rp)
Musim Tanam I
1 Padi 63 2.930.000
2 Jagung 18 840.000
3 Keelai 128 172.600
4 Kacang tanah 30 450.000
5 Kacang hijau 10 250.000
6 Kacang panjang 14 700.000
7 Cabe 74 5.445.000
8 Tomat 95 970.000
9 Bawang merah 174 1.275.000
Tabel 6. Rata-rata biaya tetap dan biaya lain-lain per hektar pada berbagai
aktivitas usahatani yang dikeluarkan petani responden untuk setiap jenis komuditi
No. Aktivitas usaha tani (Tanaman) Biaya tetap dan Biaya lain-lain
(Rp)
Musim Tanam I
1 Padi 5.325.000
2 Jagung 5.830.000
3 Kedelai 3,648,566
4 Kacang tanah 4.000.000
5 Kacang hijau 646.000
6 Kacang panjang 1.854.000
7 Cabe 3.250.000
Tabel 7. Rata-rata total biaya produksi, pendapatan, laba, BEP dan BC-ratio
Terdapat beberapa tujuan Pemanfaatan lahan yang dimiliki oleh petani
salah satunya yakni sebagai usaha untuk mendapatkan hasil dan menambah
keuntungan financial. Usahatani merupakan upaya petani untuk menggunakan
atau memanfaatkan seluruh sumberdaya (tanah, pupuk, air, obat-obatan, uang,
tenaga dan lain-lain) dalam suatu usaha pertanian secara efisien sehingga dapat
diperoleh hasil berupa produksi maupun keuntungan finansial secara optimal. Satu
kata yang mengandung arti „bisnisnya petani‟ dengan lahan garapan yang dikelola
dalam bahasa Inggris yang bisa sebagai kata benda maupun kata kerja yang diberi
arti sebidang lahan dengan bisnis tanaman dan hewannya. Jadi pada hakikatnya,
usaha tani adalah proses industri. Karena itu, memberdayakan usahatani tidak
ubahnya dengan memberdayakan industri.
Dalam pelaksanan usaha tani terdapat beberapa aspek/komponen yang
terdapat pada kegiatan tersebut. Salah satunya adalah modal. Modal merupakan
syarat mutlak berlangsungnya suatu usaha, Demikian Pula dengan usahatani,
menurut Vink, Benda benda termasuk tanah yang Mendatangkan pendapatan
dianggap sebagai Modal. Namun, Tidak demikian halnya dengan Koens yang
menganggap bahwa hanya uang yang tunai saja dianggap sebagai modal
Usahatani, Penggolongan modal Ini akan Semakin rancu jika dibicarakan kan
adalah usahatani Keluarga cenderung Memisahkan Faktor tanah dari alat produksi
yang lain. Hal ini dikarenakan Belum ada Pemisahan yang jelas antara modal
usaha dan modal Pribadi. Modal Dikatakan Land Saving Capital jika dengan
modal tersebut dapat Menghemat Penggunaan Lahan.Tetapi produksi dapat dilipat
gandakan tanpa harus memperluas Areal, Contohnya Pemakaian Pupuk, Bibit
unggul, Pestisida, dan intensifikasi, Modal Dikatakan labour saving capital jika
dengan modal Tersebut dapat menghemat Penggunaan tenaga kerja contoh
Pemakaian traktor untuk membajak, Mesin Pengiling padi (Rice Milling
Unit/RMU) untuk memproses padi menjadi Beras Pemakaian Tresher Untuk
penggabahan dan Sebagainya.
Dalam Arti ekonomi perusahaan Modal Adalah barang ekonomi dapat
dipergunakan untuk memproduksi kembali atau Modal Adalah Barang ekonomi
yang dapat dipergunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan pendapatan.
Pendapatan petani berasal dari usahatani dan luar usaha tani. Usaha tani
merupakan sumber utama pendapatan petani namun demikian dalam
kenyataannya petani dalam upayanya mengoptimalkan pengelolaan usaha taninya
berhadapan dengan berbagai masalah yaitu kekurangan modal, jumlah tenaga
kerja keluarga, tidak dikuasainya teknik budidaya maupun adanya gangguan hama
sedikit untuk mengelola usaha taninya. Rendahnya modal tersebut akan
menyebabkan produktivitas usaha taninya menjadi rendah (Saragih, 1993). Dalam
menaksir pendapatan kotor semua komponen produk harus dinilai berdasarkan
harga pasar. Tanaman dihitung dengan cara mengalikan produksi dengan harga
pasar. Perhitungan pendapatan harus juga mencakup semua perubahan nilai
tanaman dilapangan antara permulaan dan akhir tahun pembukuan. Perubahan
semacam itu sangat penting. Meskipun demikian pada umumnya perubahan ini
diabaikan karena penilaiannya sangat sukar. Pendapatan kotor usahatani adalah
ukuran hasil perolehan total sumber daya yang digunakan dalam usaha tani.
Nisbah seperti pendapatan kotor per hektar atau per unit kerja dapat dihitung
untuk menunjukkan intensitas operasi usaha tani (Soekartawi, 1996).
Berdasarkan hasil survey dapat di simpulkan pendapatan kotor usahatani padi
sebesar Rp. 21.525.000, jagung Rp. 5.830.000, kacang panjang Rp. 12.380.000,
kedelai Rp. 5.108.642, tomat Rp. 100.000.000. pada nilai pendapatan kotor
tersebut belum termasuk biaya pemeliharaan, tenaga kerja dan aspek aspek lain
yang dilakukan ketika budidaya.
Selain modal dan pendapatan, aspek penting dalam usaha ialah biaya.
Untuk meningkatkan pendapatan atau keuntungan maka perlunya manajemen
biaya sehingga penggunaan biaya dapat diforsir seefisien mungkin. Beberapa
macam biaya yang perlu di perhatikan dalam kegiatan usaha tani : Biaya tetap
adalah biaya yang besarnya relatif konstan dari waktu ke waktu (misalnya dari
musim ke musim atau dari tahun ke tahun). Besarnya biaya tetap tidak
dipengaruhi oleh komoditi apa yang akan diusahakan dan berapa banyak produksi
akan dihasilkan. Beberapa unsur biaya tetap, antara lain: sewa lahan, penyusutan
alat mesin, bunga modal (terutama atas sarana tahan lama), pajak, upah tenaga
kerja tetap, dll. Biaya tidak tetap ialah jenis biaya yang besarnya naik atau turun
bersama-sama dengan naik atau turunnya produksi. Jika skala produksi
ditingkatkan, maka biaya tidak tetap meningkat pula, dan sebaliknya.
Analisa usahatani dilakukan untuk melihat apakah suatu usahatani itu
menguntungkan atau tidak. Alat yang dipakai untuk menghitung keuntungan ini
dapat dilakukan dengan mengidentifikasi komponen-komponen yang akan
dianalisa yaitu komponen input dan output. Komponen input dan output dapat
diperoleh dari hasil pencatatan kegiatan usaha yang dilakukan secara tertib dan
lengkap. Tidak adanya catatan-catatan kegiatan usahatani akan membuat hasil
analisa akan tidak akurat dan bias, sehingga petani harus dimotivasi agar dapat
melakukan pencatatan dengan tertib.
Efisiensi usahatani memberikan batas layak dan tidaknya suatu usahatani
dilaksanakan. Perhitungan efisiensinya menggunakan biaya dalam usahatani
dianalisis melalui imbangan antara penerimaan total dengan biaya total yang
disebut Return and Cost Ratio (R/C ratio). Pada metode ini mengandung arti
bahwa tingkat efisiensi usahatani diukur atas dasar keuntungan (Hernanto, 1988).
Efisiensi perlu diperhitungkan karena pendapatan usahatani yang tinggi tidak
selalu mencerminkan efisiensi yang tinggi pula, selanjutnya untuk mengetahui
manfaat dari suatu teknologi atau keragaman usahatani yang satu terhadap yang
lain dapat dilakukan dengan analisis B/C ratio (Soeharjo, et al, 1977). Selain BEP
dan ROI yang digunakan dalam analisis usahatani adalah analisis yang bersifat
menyeluruh dan ada juga analisis untuk kelayakan usahatani. Analisis lebih
menekankan pada kriteria investasi yang pengukurannya diarahkan pada
usaha-usaha untuk membandingkan, mengukur serta menghitung tingkat hubungan suatu
usahatani. Dan beberapa modal yang dapat digunakan sebagai indikator dalam
pengukuran analisis kelayakan. Model ini paling dianjurkan karena
perhitungannya masih dalam keadaan kotor. Rumusnya adalah sebagai berikut:
B/C = Hasil penjualan
Modal produksi
(Rahardi, et al, 1999).
Berdasarkan hasil table di dapatkan BC-ratio pada tanaman padi 4,05,
jagung 0,2 dan kacang panjang 1,92 artinya tanaman padi memiliki efisiensi
produksi lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman dengan komuditi lainnya.
biaya untuk komuditi ini tidak akan meningkatkan produksi karena nilai BC-
ratio kurang dari satu Seperti pernyataan Teteto (2012) B/C ratio yang nilainya >
1 ini menunjukkan bahwa penambahan biaya untuk kedua varietas ini masih
memberikan manfaat atau dengan kata lain penambahan produksi untuk kedua
varietas ini masih lebih besar daripada penambahan biayanya.
G. Simpulan dan Saran 1. kesimpulan
a. Terdapat beberapa tujuan Pemanfaatan lahan yang dimiliki oleh petani salah satunya yakni sebagai usaha untuk mendapatkan hasil dan menambah keuntungan financial
b. Modal merupakan syarat mutlak berlangsungnya suatu usaha termasuk semua komponen yang mendukng system usaha tersebut.
c. Dalam Arti ekonomi perusahaan Modal Adalah barang ekonomi dapat dipergunakan untuk memproduksi kembali atau Modal Adalah Barang ekonomi yang dapat dipergunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan pendapatan
d. Dalam menaksir pendapatan kotor semua komponen produk harus dinilai berdasarkan harga pasar. Tanaman dihitung dengan cara mengalikan produksi dengan harga pasar
e. Pendapatan kotor usahatani adalah ukuran hasil perolehan total sumber daya yang digunakan dalam usaha tani. Nisbah seperti pendapatan kotor per hektar atau per unit kerja dapat dihitung untuk menunjukkan intensitas operasi usaha tani
f. hasil survey dapat di simpulkan pendapatan kotor usahatani padi sebesar Rp. 21.525.000, jagung Rp. 5.830.000, kacang panjang Rp. 12.380.000, kedelai Rp. 5.108.642, tomat Rp. 100.000.000
g. Analisa usahatani dilakukan untuk melihat apakah suatu usahatani itu menguntungkan atau tidak
h. Efisiensi usahatani memberikan batas layak dan tidaknya suatu usahatani dilaksanakan. Perhitungan efisiensinya menggunakan biaya dalam usahatani dianalisis melalui imbangan antara penerimaan total dengan biaya total yang disebut Return and Cost Ratio (R/C ratio)
i. keragaman usahatani yang satu terhadap yang lain dapat dilakukan dengan analisis B/C ratio
DAFTAR PUSTAKA
Bavappa, K.V.A S.N. Darwis and D.D. Tarigans. 1995. Coconut Production and
Productivity in Indonesia. Asian and Pacific Coconut Community 80pp.
Cahyono, 2005. Teknik Budi Daya Tembakau Dan Analisis Usaha Tani. Kanasius, Yogyakarta.
Cimerak. Journal Penelitian Tanaman Industri 8(4) : 109-116.
Darwis.V., Nur Khoiriyah. A. 2007. Perspektif Agribisnis Kakao diSulawesi
Tenggara (Studi Kasus Kabupaten Kloaka).
Haz, H. 2001. Sambutan Tertulis Wakil Presiden Republik Indonesia Pada Pekan
Perkelapaan
Kasryno, F. 1993. Penelitian dan Pengembangan Perkelapaan di Indonesia.
Prosiding KNK III, Yogyakarta 20-23 Juli 1993.
Rakyat 2001, Riau, 4 Nopember 2001 6 pp.
Rukmana, 2003. Strategi Pengembangan Pemasaran. Universitas indonesia Press
(Ul-Press). Jakarta.
Tino Mutiarawati. 2006. Kendala Peluang dalam Produksi Pertanian Organik di
Indonesia. Jakarta.
Tondok, A.R. 1998. Pemanfaatan Peluang Pengembangan Kelapa Dalam
Menghadapi Era Globalisasi. Modernisasi Usaha Pertanian Berbasis Kelapa