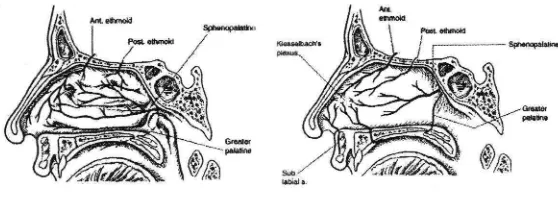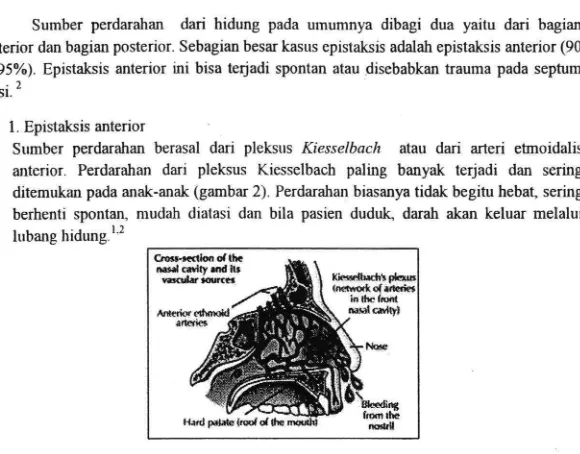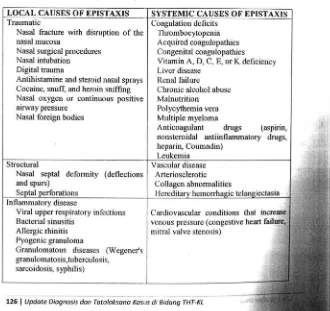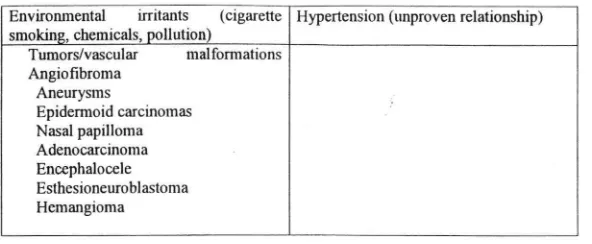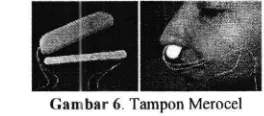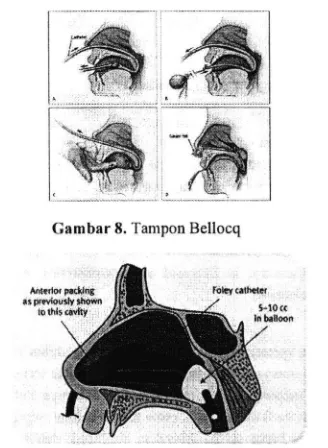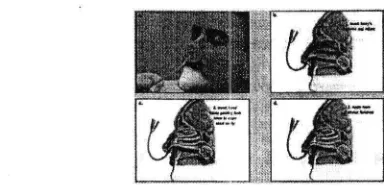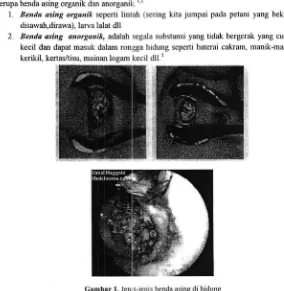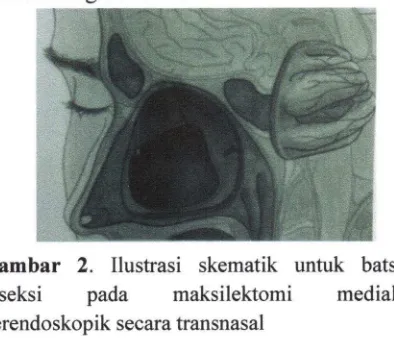Demo
:
Penatalaksanaan
Epistaksis
Dr, Bestari Jaka Budiman, Sp. THT-KL(K)Dr. Dolly lrfandy, SP.THT-KL
Bagian llmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Andalas/RSUP Dr.M.Djamil Padang
ANATOMI HIDUNG
Rongga hidung atau kavum nasi berbentuk terowongan dari depan ke belakang, dipisahkan oleh septum nasi pada bagian tengahnya menjadi kavum nasi kanan dan kiri. Pintu masuk kavum nasi bagian depan disebut nares anterior dan lubang belakang disebut
nares posterior (koana) yang menghubungkan kavum nasi dengan nasofaring. Tiap kavum nasi mempunyai 4 buah dinding yaitu dindrng medial, lateral, inferior dan superior r.
Dinding medial hidung adalah septum nasi. Septum dibentuk oleh tulang dan tulang
rawan. Bagian tulang terdiri dari larnina perpendikularis os ehnoid, vomer, krista nasalis
os. rnaksila, kista nasalis os. palatina. Bagian tulang rawan septum adalah kartilago
septum (lamina kuadrangularis) dan kolumela
Septum dilapisi oleh perikondrium pada bagian tulang rawan dan periosteum pada
bagian tulang. sedangkan diluamya dilapisi mukosa. Pada dinding lateral terdapat 4 buah konka yaitu konka inferior, media, superior dan konka suprema. Konka inferior,
merupakan konka terbesar dan merupakan fulang tersendiri yang melekat pada os maksila
dan labirin etmoid sedangkan konlia media, superior dan suprema merupakan bagian dari
labirin etmoid.
Pada rongga hidung terdapat rongga sempit antara konka dan dinding lateral hidung yang disebut meatus. Terdapat 3 meatus, yatu meatus inferior, terletak antara konka inferior dan dasar hidung dan disini terdapat muara duktus nasolakrimalis. Meatus media
terletak antara konka media dan dinding lateral rongga hidung, disni terdapat muara sinus
frontal, sinus maksila dan sinus etmoid anterior. Meatus superior merupakan ruang antala konka superior dan konka media dan disini terdapat muara sinus etmoid posterior dan sinus
sfenoid.
*"-i-i-Dinding inferior merupakan dasar rongga hidung dan dibentuk oleh osi Maksila dan
os. Palatum. Dinding superior atau atap hidung sangat sempit dan dibentuk oleh lanina
kibriformis yang memisahkan rongga tengkorak dari rongga hidung. Lamina kibrosa
PERDARAHAN HIDUNG
Mukosa nasal mempunyai cabang-cabang pembuluh darah yang sangat banyak.2
'
Perdarahan hidung berasal dari cabang terminal a. Karotis ekstema dan a. Karotis intema 3 Bagian atas rongga hidung mendapat perrlarahan dari a. Etmoid anterior dan posterior yang merupakan cabang dari a. Oftalmika dari a. Karotis interna.l Walaupun hanya dinamaidengan anterior dan posterior, arteri etmoid mungkin terdiri lebih dari dua pembuluh darah.z Bagian bawah rongga hidung rnendapat perdarahan dari cabang a. Maksilaris interna dintaranya a. Palatina mayor tlan a. Sfenopalatina yang keluar dari foramen
sfenopalatina dan memasuki rongga hirlung di belakang ujung posterior konka media.
Bagian depan hidung mendapat perdarahan dari cabang-cabang a. Fasialis. Pada bagian
depan septum nasi terdapat little's area alau plexus kiesselbach yang merupakan gabungan
dari pembuluh darah kecil yang berasal dari arteri etmoid anterior, arteri palatina mayor dan arteri labialis superior yang merupakan cabang a. fasialis. Bagian superior dari mukosa
hidung diperdarahi oleh arteri etmoid.r
[image:2.381.59.338.223.325.2]@e @a
Gambar Perdarahan hidungl
Vena-vena hidung mernpuyai narna yang sama dan berjalan berdampingan dengan arterinya. Vena di vestibulum dan stru]<tur luar hidung bermuara ke v. Oftalmika yang berhubungan dengan sinus kavernosus. Vena-vena di hidung tidak mernpunyai katup, sehingga merupakan faktor predisposisr untuk mudahnya penyebaran inleksi sampai ke
EPISTAKSIS
Sumber perdarahan dari hidung pada umumnya dibagi dua yaitu dari bagian anterior dan bagian posterior. Sebagian besar kasus epistaksis adalah epistaksis anterior (90
-
95%). Epistaksis anterior ini bisa te{adi spontan atau disebabkan tauma pada septumnasl.
l. Epistaksis anterior
Sumber perdarahan berasal dari pleksus Kiesselbach atau dari arteri efinoidalis anterior. Perdarahan dari pleksus Kiesselbach paling banyak terjadi dan sering ditemukan pada anak-anak (gambar 2). Perdarahan biasanya tidak begitu hebat, sering
berhenti spontan, mudah diatasi dan bila pasien duduk, darah akan keluar melalui
Iubang hidung.r'2
C6'ffho oari. d{@ltyndlrr
solvre Xi!..{bdrl
[image:3.381.49.339.64.291.2]Hrd Frrr. (@f or 0P
Gambar 2. Pleksus Kiesselbach (little area, anastomosis a. etmoid anterior dan posterior, a. sfenopalatina cabang septal,a.palatina mayor, a. labialis superior) 2. Epistaksis posterior
Sumber perdarahan berasal dari arteri sfenopalatina dan arteri etmoidalis posterior.
(gambar 2). Epistaksis posterior bersifat rnasif dan dapat mengancam nyawa. Penyebab epistaksis masif ini umumnya tidak diketahui, sehingga perlu anamnesis
yang hati-hati dan cermat untuk mencari faktor resiko, yang tersering adalah menggunakan obat-obatan anti pembekuan darah dan pada pasien usia lanjut yang menderita hipertensi, arteriosklerosis, penyakit kardiovaskular atau penyakit sistemik
larnnya. Perdarahan biasanya hebat danjarang berhenti spontan sehingga memerlukan
Gambar 3.Pleksus l{oodruff(anastomosis a. sfenopalatina, a. palatina descenden dan kontribusi kecil dari a. etmoid posterior)
Penyebab dari epistaksis dapat
di
bagi menjadi akibat lokal dan sistemik, bagaimanapun yang terbanyak (80-90 %) adalah idiopatik (tabel I ). rTabel l. Faktor resiko dan penyebab episraksis l
LOCAL CAUSES OF' EPISTAXIS SYSTEMIC CAUSES OF EPISTAXIS Traumatic
Nasal fracture with disruption of the
nasal mucosa
Nasal surgical procedures Nasal intubation Digital trauma
Antihistamine and steroid nasal sprays Cocaine, snuff, and heroin sniffing Nasal oxygen or continuous positive airway pressure
Nasal foreign bodies
Coagulation deficits Thrornbocytopenia Acquired coagulopathies
Congenital coagulopathies
Vitamin A, D, C, E, or K deficiency Liver disease
Renal failure Chronic alcohol abuse Malnutrition Polycythemia vera
Multiple myeloma
Anticoagulant
drugs
(aspirin,nonsteroidal antiinflammatory drugs,
heparin, Coumadin) Leukemia
Structural
Nasal septal deformity (deflections
and spurs) Septal perforations
Vascular disease Arteriosclerotic Collagen abnormalities
Hereditarv hemorrhagic telangiectasia
Inflammatory disease
Viral upper respiratory infections
Bacterial sinusitis
Allergic rhinitis
Pyogenic granuloma
Granulomatous diseases (Wegener's granulomatosis.tuberculosis,
sarcoidosis, syphilis)
Cardiovascular conditions that venous pressure (congestive heart
[image:4.381.41.371.239.550.2]Environmental
irritants
(cigarettesmoking, chemicals, pollution)
Hypertension (unproven relationship)
TumorVvascular malformations Angiofibroma
Aneurysms
Epidermoid carcinomas Nasal papilloma
Adenocarcinoma Encephalocele Esthesioneuroblastoma Hemangioma
Pembuluh darah pada mukosa hidung berjalan sangat superfisial dan hampir tidak ada proteksi dan merupakan faktor penting dalam pecahnya pembuluh darah pada
epistaksis. rl
Pengobatan disesuaikan dengan keadaan penderita, apakah dalam keadaan aliut
atau tidak. Perbaiki keadaan umum penderita, penderita diperiksa dalam posisi duduk kecuali bila penderita sangat lemah atau keadaaan syok. Beberapa cara megatasi perdarahan antara lain : l3
l.
Menekan cuping hidungLangkah awal mengontrol perdarahan. Cara : pasien duduk dengan kepala ditegakkan,
[image:5.382.37.333.51.173.2]kemudian cuping hidung ditekan ke arah septutn dapat dilakukan penekanan pada bagian kartilago hidung selama l5 menit, dengan cara.
-!
2.
KauterisasiPada epistaksis anterior, jika sumber perdarahan dapat dilihat dengan jelas, dapat dilakrrkan kaustik dengan kauter l.imiawi (larutan nitras argenti AgNO320%-30%, asam trikloroasetat l0%,elektrokauter) dengan tekanan ringan pada lokasi perdarahan selama 5-10 detihatau dengan laser atau eleklrokauter di barvah anestesi lokal dengan
memberikan energi termal pada pembuluh darah hidung.
3. Tampon anterior
Bila dengan kauterisasi perdaraharr anterior masih terus berlangsung, atau sumber perdarahan tidak terlihat, diperlukan pemasangan tampon anterior, berupa :
a) Kapas atau pita kain kasa yang diberi vaselin dan dicampur betadin atau zat
antibiotika
[image:6.382.146.278.342.400.2],#
Gambar 5. Tarnpon anterior pita kmsa
b) Merosel : dibuat dari alkohol polivinyl, foam yang dikompresi dimasukan kedalam hidung dan akan membesar bila basah yang akan mengisi kavum nasi rnengakibatkan tekanan dialas sunrber perdarahan, keadan ini juga menjadikan
faktor lokal untuk terbentuk-nya clotting yang memfasilitasi pembekuan. Merosel mudah untuk dimasukan ke dalam hidung. Tingkat efektifitasnya 85 %, tidak ada
perbedaan dibandingkan dengan tampon kasa tradisionil.
Grnrbar 6. Tampon Merocel
c)
Rapid zno : mengandung karboksi metil selulosa. Rapid rino ini merupakanmateri hodrokoloid yang diperkaya agregator platelet dan menjad licin bila kontak dengan air. Rapid rino ini punya cuffyang digembungkan dengan udara.
:'w
Gambar 7. Tarnpon Rapid rino
ea
,m
Tarnpon anterior harus dilapisi dengan antibiotika topikal, dan pasien juga diberi antibiotika sistemik selain untuk mencegah infeksi juga untuk mencegah toxic shock
syndrome.3
4.
Tampon posteriorPerdarahan posterior diatasi dengan pemasangan tampon posterior atau tampon
[image:7.381.117.281.170.394.2]Bellocq (gambar 8 ). Sebagai pengganti tampon Bellocq dapat dipakai kateter Foley dengan balon (gambar 9). Pada perdarahan anterior dan posterior dapat digunakan tampon pita kassadan balon kateter (gambar l0)
Gambar 8. Tampon Bellocq
[oht €lh.t.r
Gambar 9. Tampon posterior balon kateter
ffi
Gambar 10. Tampon anterior pita kassa dan tampon posterior balon kateter pada
epistaksis anterior dan posterior
5. Intervensi bedah
Beberapa intervensi yang dapat dilalukan
d) Diatermi
e) Operasi septum
Dilakukan untuk mengoreks;i septum yang deviasi atau mengangkat spina
septum yang menyebabkan epistaksis atau apabila perdarahan terjadi dari septum sendti.
$
Ligasi arteri, dilakukan pada epistaksis berat dan berulang yang lidak dapatdiatasi dengan pemasangan tampon posterior. Ligasi arteri dapat dilakukan pada a. Sfenopalatina, a. Ethmoid anterior/posterior, a. Maksilaris ekstema dan a.
Karotis eksterna.
Komplikasi epistaksis dapat te!;rdi langsung akibat epistaksis sendiri atau akibat
usaha penanggulangannya.Akibat perdar:ftan hebat dapat terjadi syok dan anemia" iskemia otak insufisiensi koroner, infark miok;rrd dan akhirnya kematian. Akibat pemasangan
tampon dapat menimbulkan sinusitis, otitis media bahkan septikemi4 sehingga pada setiap pemasangan tampon harus selalu diberil<an antibiotik dan setelah 2-3 hari harus dicabut
rneski akan dipasang tampon baru bila lnasih berdarah. Akibat rnengalimya darah secara retrograd melalui tuba Eustachius, darat terjadi hemotimpanum dan air mata yang berdarah. Pada waktu pem.Lsangan tampcn Bellocq dapat terjadi laserasi palatum mole dan
Daftar Pustaka
l. Mangunkusumo E, Wardani RS. Epistaksis. Dalam: Soepardi EA, Iskandar N, Bashiruddin.T,
Restuti RD, editors. Buku ajar telinga hidung tenggorok kepala & leher. Edisi keenam. Jakarta: FKUI;2007. h. 155-9
2. Synderman CH, Carrau RL. Epistaxis. ln: Myers EN, ed. Operative Otolaryngology Head and
Neck Surgery. 2d ed. Philadelphia: Saunders, Elsevier in corp ' 2006. p7-16
3. Cumnnng CW, Flint PW, Haughey .BH, Robbins KT, Thomas JR. Harker LA, et al.
Otolaryngology head & neck surgery. 4rd edition. Philadelphia.Elsevier Mosby;2005. p. 943-9
4. Wormald PJ. Epistaxis. In: Bailey BJ, Johnson JT, Newlands SD, editors.Head & Neck
Strrgery-Otolaryngology.4'r edition. Philadelphia: Lipincolt Williams & Wilkins; 2006. p.50s-14.
5. Nguyen QA. Epistaxis. Available fiom: http://www.emedicine.medscape.com.Accesed octobe120h, 20 1 1.
6. Kucik CJ, Clenney T. Managementof epistaxis. Am Fam Phy 2005;71(2):305-l l.
,.Demo
:
Penatalaksanaan Benda
Asing
Hidung
Dr. Effy Huriyati, Sp. THT-KL
Dr. Dolly lrfandy, Sp.THT-KL
Bagian Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher Fakultas Kedolleran Universitas AndalaVRS UP Dr.M.Djamil Padang
Benda asing di hidung pada anal merupakan kasus yang sering dijumpai. Angka kejadian benda asing hidung cukup banlrak ,terutarna pada anak balita, sering pada anak
yang hiperaktif atau sebaliknya pada ani& dengan retardasi mental, namun kasus ini juga sering dijumpai pada orang dewasa dengan retardasi mental. Benda asing hidung dapat
berupa benda asing organik dan anorganik. r'2
1. Benda asing organik seperti lintah (sering kita jumpai pada petani yang bekerja disawah,dirawa), larva lalat dll
2. Benda asing anorgani&, adalah segala substansi yang tidak bergerak yang cukup
[image:10.381.54.338.201.492.2]kecil dan dapat masuk dalam rongga hidung seperti baterai cakram, manik-manik, kerikil, kertas/tisu, mainan logam kecil dll.r
Gambar l. Jenr s-jenis benda asing di hidung
.l lt,
,./lliFESS
.L.
.,.. .r.n\wr H\\,, H.,,,U,r,E,,.tut,r,J\t,,tnr, r\tr,kir!,,t r\,1,,\,\,\-t), (,r,,,,tt,\,Lr\rv!,,|t(,tr, . r\trx,1r\,1,,\,{r
Endonasal
prelacrimal
approach
to remove
impacted
tooth in
Maxillary
Sinus
Dolly
Irfandy,
Bestari Budiman,Arsia
Dilla
Faculty of Medicine Andalas University/ Dr. M. Djamil Hospital
Padang
ABSTRACT
Background:
Dentigerous cysts ar€ odontogenic cyst derivedfrom
the crownof
the
impacted teeth, ectopic teethor
fromunerupted
teeth.
Thesecysts
are
generally
more
in
men. Approximately30%
of
these cysts arisefrom the
ma,rilla.Purpose: There are several approaches
to
treat this cyst, thiscase reported
with pre
lacrimal
approachwith
endoscopic. Case: Reported a caseof
a male 24 years oldwith
swelling in right cheek that enlarged slowly during 1.5 years with a historyof
dental pain, resultsof
a
CT
scanof
paranasal sinuses issuspected
as
a
dentigerouscyst.
Management:
Extirpation using endoscopicwith
prelacrimal approach. Operarive ftndingfound a molar teeth and cyst in right maxillary sinus- Patfiologic Anatomy finding was similar to dentigerous cysts. Conclusion:
Dentygerous
cyst
in
maxillary
sinus wasa
cyst that
usually comeform
impactedor
ectopic teeth. The involvementof
themaxillary sinus can lead to the severity of symptoms in patients
with
these cysts. There are various approachto
this case, butwe choose preJacrimal approach with endoscopy because it has
a minimum risk and high success rate.
Keywords: Dentygerous cyst, maxillary sinus, impacted tooth, prelacrimal approach with endoscopy
Endonasal
Prelacrimal Approach
to
RemoveImpacted Tooth
in
Maxillary
Sinus
Dolly
Irfandy,
Bestari
Budiman,
arsia
Dilla
Abstrak
Pendahuluan:
Kista
dentigerus
adalah
kista
odontogenik
yang
berasal
darimahkota gigi
yang
impaksi,
gigi
ektopik
ataugigi
yangtidak tumbuh.
Kista
ini
umunnya
lebih
banyak padalaki-laki
dibandingkan perempuan. Sekitar 70% darikista
ini
muncul
pada
daerah
mandibula
dan
30Yo
pada
maksila.
Terdapat beberapa pendekatanuntuk
penatalaksaankista
ini.
Padakasus
ini
dilaporkan
pendekatan secara
maksilektomi
mediai
perendoskopik.
Laporan
Kasus:
Dilaporkan
satu kasus seoranglaki laki
24 tahun dengan bengkak padapipi
kananyang
membesar secara perlahan selama 1,5tahun
denganriwayat
sakit
gigi,
danhasil
CT
scan sinus paranasaldicurigai
sebagaikista
dentigerus. Penatalaksanaandengan dilakukan ekstirpasi mengggunakar
teknik
maksilektomi
medialperendoskopik. Ditemukan
adanyagigi
molar
dan
kista
di
dalam sinus maksila
kanan. Hasil
patologi anatomi
sesuaiuntuk kista
dentigerus.Kesimpulan:
Kista
dentigerus pada sinus
maksila
adalahkista yang muncul
perlahan yang biasanyaberasal
dari
gigi
yangimpaksi
ataugigi
ektopik. Keterlibatan
sinus maksila dapatmengakibatkan beratnya gejala pada pasien
ini.
Terdapat berbagai
pendekatanuntuk
kasusini,
yang
dipilih
adalahmaksilektomi medial perendoskopik
karenamemiliki risiko
yang
paling minimal dan memiliki
angka
keberhasilan lebih
tinggi.
Kata
Kunci:
Kista
dentigerus,
sinus
maksilla,
maksilektomi
medialperendoskopik
Abstract
Introduction:
Dentigerous cysts is odontogenic cystderivedfrom
thecrown
of theimpacted teeth,
ectopic
teeth orfrom
uneruptedteeth.
These cystsare generally
more
in
men
than
in
women.Approximately
70ohof
these cysts afisefrom
themandibular region and
30okof
themaxilla.
Thereare
several approachesto treat
this
cyst, this casereported approach
with
endoscopicmedial maxillectomy.
Casereport:
Reporteda
caseofa
male 21years
old
with
swelling
in
right
cheekthat
enlarged
slowly
during
I .5 yearswith
ahistory of
dentalpain
, and
the resultsof
a
CT
scanof paranasal
sinusesis
suspected asa
dentigerous cyst. Managementextirpation using
endoscopic
medial
maxillectomy. Operatite
./inding Found
amolar
teeth and cystin
theright
maxillary
sinus,Anqtomic
Pathologt
results suitelo
dentigerous
cysts.Conclusion:
Dentygerouscyst
in
maxillary
sinus
is
4
cystthat
usually
cameform
impacted
or
ectopic teeth. The
involvement
of
themaxillary
sinus can lead
to
theseverily of
symptoms inpatients
with
these cysts. Thereare various
approach lo
this
case,but
we choose endoscopicmaxillectomi
medial becoause
it
has aminimum
risk and high success rate.PENDAHULUAN
Kista
dentigerus
adalah
kista
odontogenik
yang
berasal
dari
mahkotagigi
yang
impaksi, gigi
ektopik
ataugigi
yang
tidak
tumbuh. Kista
ini
merupakanlesi
kistik
yang
paling umum dari
rahangsetelah
kista radikular. Kista
dentigerus secaraklasik
diartikan
sebagailesi
kistik
yang
disebabkan
oleh
pemisahan
dari
folikel
disekitar mahkota
dari
gigi
yangtidak tumbuh. Kista
dentigerus mulanya
diberi
nama kistafolikular
karena
kistaini
berasal
dari folikel
gigi
yang
merupakan bagiandari
struktur mesodermal. l-7GIGI PERMANEN 1-4 untul ajtt p€.,i.n€nt
I - rahantat.skanan
2 = rahant atas kiri
3. r.hangbawah kti
4 = rehant b.wah lanan
1817 16 15 14 13 12 11 2122 23 24 23 26 27 2a aa at rcas
uti tztl!r
32 33 34 35 36 37 38l)s
U
LCUrL.l
J
J.1,l
u ltirt
,,'rr
fr'
f/lPf
I
flTt(
1l'r{t't.'t
Gambar 1.
Nomenklatur gigi permanenPatofisiologi
Kista
dentigerus
berasal
dari
enamel
gigi
setelah
terjadi
amelogenesisyang
komplit. Kista
dentigerus
muncul
akibat
akumulasi
dari
cairan
antara
gigi
yang tidak
erupsi
dengan daerah
sekitargigi
yang enamel epitelnya berkurang.l'3Cairan yang muncul
ini
bersifathiperosmolar
karena
adanya
albumin,
immunoglobulin
dan
debris
epitelskuamosa.
Cairan
hiperosmolar
ini
menyebabkan
masuknya
cairanekstraselular
ke
dalam
kista
sehinggamengakibatkan membesamya
kista. Lapisanepitel dari kista
ini
mensekresikan kolagen danfaktor aktivasi
osteoklas yang menyebabkan reasorbsitulang
lokal
yangmenyebabkan
semakin
membesamya ukuran kista.16Gambaran
Klinis
Penderita
kista
dentigerus biasanyadatang dengan bengkak
pada
sisi
yang terkenayang
tidak
disertai nyeri.
Kista
ini
dapat bersifat
asimptomatis
jika
beradadalam
ukuran
kecil.
Jika
pada
palpasipembengkakan
ini
teraba keras,
hal
ini
mengindikasikan
adanya
ekspansi
ketulang.a
Jika
terjadi
perluasan
denganstruktur disekitamya
seperti sinus maksila,atau
terjadi
infeksi
sekunder,
pasien dapatEpidemiologi
Kista
ini
umunnya
lebih
banyakpada
laki-laki
dibandingkan
perempuan.Kista
ini
muncul
pada dekade dua sampaitiga kehidupan. r'2'3'6
Sekitar
70%
dari
kista
ini
muncul
pada
daerah mandibula
dan 30%
padamaksila.
Kista
dentigerus
dapat
berasaldari
gigi
impaksi,
gigi
supernumary(adanya
satu
atau
lebih
elemen
gigi
melebihi
jumlah gigi.
yang
normal), gigi
ektopik
atau akar
gigi
yang ditemukan
di
dalam
sinus maksila.l'sAdapun
gigi
yangpaling
sering
terlibat
adalah
gigi
molar
ketiga
mandibula
dan
gigi
kaninusmaksila,
kemudian
dikuti
oleh
gigi
premolar mandibula
dan
gigi
molar
tiga
maksilla.l'2'3'5'7
Kista
dentigerus sangat
jarang
berasal
dari
gigi
ektopik
yang
tumbuh
di
sinus
maksilla.l
Kista
dentigerus
yangberhubungan
dengan
gigi
supernumarysekitar hanya sekitar 5-6%
dari
semuakista
dentigerus,
dan
90
%
berasal dari
meisodens
maksila
(gigi
supemumerarydi
mengeluhkan
adanya
nyeri
pada
wajah,sumbatan
hidung,
gejala
sinusitis
danadanya deformitas
wajah
dengan
gejala seperti abses, perubahan saraf sensorik danpembentukan fistuia.a's
Jika
pasien datangdengan
rasa
nyeri dan
pembengkakanberlangsung
cepat,
hal
ini
akibat
telah terjadinyaproses
infl amasi.3Gambaran Radiologi
Kista
dentigerus
umumnyaditemukan secara
tidak
sengaja
padapemeriksaan
radiologi
rutin
atau
padapemeriksaan
radiologi
yang
bertujuanuntuk
mengetahui kenapa
ada
gigi
yangtidak
tumbuh.
Kista
dentigerus
pada pemeriksaan panoramik ditemukan sebagaigambaran
radiolusen
unilokular,
berbatassklerotik
yang
tegas, berhubungan denganmahkota
gigi
yangtidak
erups i.1'2'3 '6'7 '13Pemeriksaan
CT
scan pada
kista
dentigerus
dapat memberikan
gambarantulang yang lebih
jelas
sehingga membantumemberikan
informasi
mengenaiketerlibatan
tulang
dan perluasandari kista
dentigerus
ini.
Gambaran
CT
scan
padakista
dentigerus
yang
berada
di
sinusmaksila
dapat
memperlihatkan
adanya"tooth
like
density" pada
lesi
kistik
di
dalam sinus
yang
terlibat.
Padapemeriksaan
MRI,
gambaran
gigi
dapattidak
terlihat atau
tampak
gambaranhipointens dan cairan kista lz
ipointens
padaT1 dan
hiperintens
padaT2.l'sHistopatologi
Kista
dentigerus
dibatasi
oleh
lapisan
dari epitel
skuamosa berlapistidak
berkeratin,
yang
terdiri
dari
2-4 lapis
seldan
elemen
keratin
jarang
ditemukan di
dinding
dalam kista.
Kista
ini
dikelilingi
oleh
jaringan
ikat
yang mengandung epitelrespirasi.
Juga
ditemukan
sel silia,
selkuboid, sel
kolumnar,
hyaline body
dan
jugaditemukkan
invasidari
sel radang.l'7'13Stroma
jaringan
ikat
padakista
ini,
akan
menunjukkan gambaran
dari
tipe
primitif
dari
ektomesenkim.
Temuanhistologi
untuk kista dentigerus
didasarioleh
terinfeksi atau
tidak
terinfeksinya
kista dentigerus tersebut. 7'13
Pada
kista
dentigerus
yang
tidak
meradang, ketebalan
lapisan
epitel
dapatmuncul
dengan lapisan
jaringan
ikat
fibrous yang
tersusun
longgar.
Lapisanpembatas
kista yaag
berasal
dari
epitel enamelberjumlah
sekitar2-4 lapis
denganbentuk yang
berasal
dari
ektomesenkimyang
primitif.
Bentuk
selnya
adalahkuboid,
atau
kolumnar
pendek.
Formasiretepegs
tidak
ditemukan,
kecuali
padakasus dengan
infeksi
sekunder.
Karenadinding
jaringan ikat
berasal
dari
folikel
gigi
dari
enamel
organ
yang
sedangberkembang,
maka
stroma
jaringan
ikat
longgamya
kaya
dengan
asammukopolisakarida.?
Pada
kista
dentigerus
yangmeradang, gambaran
sel
epitel
akanmennnjukkan
adanyahiperplasia
dai
reteridges
dandinding kista
yangfibrosa
akanmenunjukkan
infiltrat
sel radang. Fibroblas muda akanmuncul
pada stroma. Pembatassel
dapatmenunjukkan
adanya perubahanmetaplasia
dari
bentuk
sel
yangmemproduksi
mukus
atau
sel
skretorik
seperti sel goblet.T
Diagnosis
Banding
Diagnosis
banding
untuk
kasuskista
dentigerus
adalah
uniksitik
ameloblastoma, adenomatoid odontogenik
tumor
(AOT),
stadium awal
dari
kista
Gorlin,
ameloblstik fibroma,
ameloblastik
fibro-odontoma,
odontogenik keratosit.Unikistik
ameloblastoma
biasa30 tahun, sebarannya sama rata,
baik
padalaki-laki
ataupun
perempuan, memiliki
tendensi
untuk
kambuh pada
mandibulabagian posterior dan
berhubungan denganmahkota
dari
gigi
molar
tiga
yang
tidak
erupsi.
AOT
umunnya muncul
padadekade
kedua,
mengenai perempuan
duakali
lebih
banyak dibanding
laki-laki,
tempat
predileksinya
terbatas padamaksila
anterior
dan
74%
berhubungan
denganmahkota
dari
gigi
taring yang
tidak
tumbuh.
Kista Gorlin
umumnya tumbuh
pada
daerah
incisivus
dan
caninus.Ameloblastik
fibroma
merupakan
jenis
tumor
yangtidak
umum,
biasanyamuncul
pada dekade kedua,
lebih
sering padalaki
laki,
umumnyaditemukan
pada mandibulaposterior,
dan
75Yoberhubungan
dengangigi
yang tidak
erupsi.
Odontogenikkeratosit
dapat
dijumpai
mulai dari
anaksampai
dewasa,umumnya
dijumpai
padabagian
posterior
dari
ramus
mandibula,dan
25%-40%
kasus
ini
berhubungandengan
gigi
yangtidak
erupsi. IKista
dentigerus
dan
beberapatumor
jinak
dengan tertanamnya
gigi
di
dalamnya,
menunjukkan
kesamaan bentukdalam radiografi. Tumor-tumor
jinak
itu
diantaranya
adalah
ameloblastoma
dantumor
odontogenik
adenomatoid,ameloblastik
fibroma,
ameloblastik
fibro-odontoma dan odontogenik
keratosit.
r'8Terapi
dan Prognosis
Terapi
definitif untuk
kasus kista
dentigerus adalah dengan membuang
kista
dan
gigi
impaksi
yang
ikut
terlibat.r
Prognosis
untuk
kasus
kista
dentigerusadalah
baik,
kekambuhan sangat jarang
ditemukan.6'7 Pada semua
kista
dentigerus,semua gambaran
mikoskopiknya
harusdiperhatikan,
untuk
menyingkirkan
terjadinya
transformasi
menjadiameloblastoma
atau
karsinoma
sel skuamosa.T'loTatalaksana Kista Dentigerus
Secara
umum,
kista
maksila
dapatditerapi
denganmarsupialisasi,
enukleasi,penggunaan
teknik
Caldwell
Luc
dangraft
tulang
dengan
pendekatan
intraoral.
Karena
indikasi untuk
operasi bedah sinustelah
meluas,
telah
dilaporkan
beberapakasus
kista
odontogenik dan
tumor
yangditerapi secara
endoskopik,
namundemikian,
tidak
selalu mungkin
untuk
mengenukleasi
lesi
ini
pada
semuakista
hanya
dengan
teknik
endoskopisaja.9' 11'lz't+'t s
Maksilektomi
Medial Perendoskopik
Maksilektomi
medial
adalahprosedur
yang aman dan
efektif
untuk
tatalaksana
beberapa
kasus
kista
odontogenik. Terdapat beberapa
carauntuk
melakukan maksilektomi
medialperendoskopik
seperti
yang
akandijabarkan
berikut
ini.
Dilakukan
insisi
pada meatus
inferior
pada perbatasandari
dinding lateral
denganlantai
karum
nasi.Dilakukan
inferior
meatotomi
padaujung
anterior
dari
meatus. Gunakanpahat
lurusuntuk
memahat
dinding
sinus maksila.e,l 1,12,14,r5,17Batas anterior
dari
reseksi ini
adalah perlekatan anterior
dari
konka
media
ke
dinding lateral
karum
nasihingga
prosesus
unsinatus
dapat
juga
sampai
ke
krista
maksila
dan
duktussnasolakrimal. Osteotomi
ini
berada di
anterior
dari
kanal
nasolakrimal.
Dinding
lateral
dibuka
sehingga terdapatjala
masukke
sinusmaksila
sehinggajika
ada massaatau
kista
yang
berada
di
sinus
maksila
dapat terpapar dengan
baik.
Diperlukan
penggunaan
hopbin
telescope30'
dan70'
agar dapat
melihat
secara keseluruhandari
dinding
superior,
lateral,
inferior
danmaksila
dapat dibersihkan dengan
baik. [image:16.599.83.280.118.287.2] [image:16.599.366.480.174.321.2]Jika perlu,
dapat
dilakukan
pengeboran daridinding
sinus maksila.17Gambar
2.
Ilustrasi
skematik
untuk
batsreseksi
pada
maksilektomi
medial perendoskopik secara transnasalLAPORAN
KASUS
Seorang pasien
laki-laki
berusia 24tahun
datang
ke
poliklinik THT-KL
subbagian Rinologi RSUP
Dr.
M.
Djamil
Padang pada
tanggal2llldarct
2015 dengankeluhan utama bengkak
di
pipi
kanan yangmembesar
secara perlahan.
Keluhanbengkak
di
pipi
kanan sudah
dirasakansejak
1,5
tahun yang
lalu.
Mulanya
bengkak berukuran
kecil,
makin
lamamakin
membesar. Sebelumnya
pasienmengeluhkan
nyeri
di
sekitar
gusi
bagian atas. Pasien selamaini
berobat
ke
dokter
gigi
untuk
meredakan
rasa
nyeri
di
gusinya,
sampaiakhimya
bengkakdi
pipi
kanan pasien
semakin membesar,
pasienpun
disarankan
untuk
berobat
ke
dokter
THT
oleh dokter gigi.
Kemudian
pasienberobat
ke
dokter
THT
di
salah satu
RSswasta
di
Padang
dan
diajurkan
untuk
dilakukan
CT
Scan. Setelahhasil CT
scankeluar, pasien
dilakukan pungsi
danirigasi
sinus maksila, 2
minggu
sesudahitu
pasienkembali
ke
RS
swasta tersebut
dengankeluhan
keluar
darah
dari
hidungnya
dan pasien disarankanuntuk
ke RSM.Djamil.
Tidak
ada riwayat
penurunanpenciuman,
tidak
ada
riwayat
keluhanhidung
tersumbat sebelumnya,
tidak
adarasa ingus
mengalir di
tenggorok,tidak
adaingus kental,
tidak
ada riwayat
keluar
darah
dan
nanah
dari
hidung dan
mulut.
Tidak
ada keluhanbersin-bersin
lebih
dari
lima kali
jika
pasien terpapar
debu
ataudingin.
Gambar 3. Foto pasien saat pertama kali datang. Tampak pembengkakan di pipi sebelah kanan.
Pada pemeriksaan
fisik
didapatkanstatus generalis dalam batas
normal. Tidak
ditemukan
kelainan pada
pemeriksaantelinga dan
tenggorok.
Pada pemeriksaan nasoendoskopi,kawm
nasi kanan
sempit,konka
inferior
edem, terdapat
sinekiaantara
konka
inferior
denganlantai kavum
nasi, konka media atrofi,
meatus
mediaterbuka, terdapat
sekret
serous,
tidak
terapat
septum
deviasi.
Kavum nasi kiri
sempit,
konka inferior
edema,
konka
media
edema, meatus
media
terbuka,terdapat
sekret
serous, terdapat
septumdeviasi (krista).
Pada
pemeiksaan oral
cavity,
tidak
ditemukan
gigi
molar 3
padaregio maksila
kanan dankiri,
danmolar
3pada
regio
mandibula kanan dankiri,
tidak
ditemukan
adanya
fistula.
Padapemeriksaan regio maksila dekstra terdapat
edema
di
regio tersebut (gambar 3).Hasil
CT
scan
yang dilakukan di
RS
swasta tersebut (gambar
4)menunjukkan
adanya
lesi
isodense
padasinus maksilaris kanan
dengan
struktur
gigi
di
dalamnya. Pasien
didiagnosis{
L
dengan suspek massa
terinfeksi
+
septumdeviasi, dengan diagnosis banding sinusitis
maksila
dengan destruksi
dinding
sinusmaksila
dan
pasien
disarankan
untuk
dilakukan
rontgen panoramik
dandisarankan
untuk meminta
secondopinion
pada
radiolog
RSUP
Dr.
M.
Djamil
Padang, selanjutnya
pasien
diberikan
terapi
siprofloksasin
2
x
500
mg,
dan [image:17.598.75.269.397.488.2]mehonidazole
3x
500mg,
dandianjurkan
kontrol
satuminggu
.Gambar 4. CT Scan sinus paranasal menunjukkan
adanya perselubungan di sinus maksila dekstra dan
tampak struktur gigi di dalamnya.
Grmbrr 5. Foto panoramik pasien yang menunjukkan
adanya kista dentigerus
di
sinus maksila kanan dan tarnpak struktur gigi di dalamnyaPada
tanggal
10 maret 2015 pasien datang membawahasil
rontgenpanoramik
(gambar
5)
dan
didapatkan
hasil
tampak gambarangigi
molar
kemungkinan
besarmolar 3
geraham kanan atasdi
intra
sinusmaksilaris
kanan dengan
dinding
inferior
sinus
yang
sudah
tidak
terlihat
jelas
kemungkinan
destruksi tulang.
Tampakimpacted
M3
kanan dan
kiri
bawah, M3
kiri
atas.Kesimpulan
suspek dentygerouscysl
mencapai sinus maksilaris
kanan,impacted 3 geraham kanan dan
kiri
bawah,Ml kiri
atas.
Kemudian
pasiendipersiapkan
untuk
dilakukan
ekstirpasikista
dentigerus padasub
bagianrinologi.
Dilakukan
pemeriksaan
laboratorium
darah dan didapatkan
hasil
Hb
16,8 g/dl,
Leukosit
72.2001mm3,
Trombosit
240.000imm3,
PT
9,9detik,
APTT
34,5detik
yang
disimpulkan
masih dalam batasnormal. Pasien dikonsulkan
ke
bagiananestesi
dan
disetujui
untuk
dilakukan
tindakan dalam anestesi umum.
Pada tanggal
26
Maret
2015
dilakukan tindakan maksilektomi
medialperendoskopi
dalam
anestesi
umum.Operasi
dilakukan
dengan
posisi
pasienberbaring telentang
diatas meja
operasidalam
anestesiumum
dan
dipasangoral
pac,t.
Dilakukan tindakan aseptik
danantiseptik
pada
lapangan
operasi
dandipasang
duk
steril.
Operasi
dilakukan
pada lobang hidung kanan.
Dilakukan
pemasangan tampon
adrenalin
I
:
200.000pada kedua lobang hidung selama
10menit,
lalu
tampon dibuka.
Insisi
dilakukan pada
konka inferior
dekstrauntuk dijadikan
flap kira-kira 3 mm
dari
anterior
konka
inferior.
Kemudian
mukosakonka
inferior
dilepaskan
dari
dinding
lateral hidung
dengan
raspatolium.
Kemudian
tulang dinding lateral
hidung
yang
merupakansisi medial
sinusmaksila
dipahat,
dan
dilebarkan
denganrongeur,
terlihat
massa
kistik
di
dalam
sinusmaksila. Kemudian
dicoba mengidentifi kasikan massa tersebut, massakistik
coba
dikeluarkan secara
intoto,
namun saat
proses
pengeluaran,
massatersebut pecah, dan
keluar cairan
kuning
kecoklatan, dan
ditemukan
gigi
pada dasarkista, dan
gigi
dikeluarkan. Massa
kistik
dikeluarkan
dengan
cara dikuret
sampaibersih. Ditemukan adanya
ostium
assesorissinus
maksila" kemudian
dilakukan
unsinektomi
untuk
melebarkan
danmenggabungkan ostium
assesoriss denganostium natural. Ditemukan pula
jaringan
l.t
aaE
7!--=;
seperti
polip
diantara prosesus
unsinatusdengan
konka media, jaringan
tersebutdiangkat.
Perdarahandirawat.
Dilakukan
evaluasi
kawm nasi
sinistra,
tampak adanyakrista, namun
setelahdinilai
krista
ini
tidak
mengganggu
aliran
KOM,
sehingga diputuskan
untuk tidak dilakukan
septoplasti pada pasien
ini
Dilakukan
evaluasi
akhir
pada sinus maksila
dekstradan
tidak
ditemukanlagi
sisajaringan kista
dipasang
tampon anterior.
Tampon [image:18.598.84.260.273.463.2] [image:18.598.75.283.507.715.2]difiksasi
dibagian luar. Operasi selesai.Gambar 6, Temuan operasi di dalam sinus maksila
kanan, ditemukan selaput kista dan gigi molar
Pasca operasi
diberikan terapi drip
tramadol
dalam
1
kolf
IVFD
RL
8jam/kolf,
Injeksi
seftriaksone
2
x
1
gr
intravena.
Injeksi
deksametason3
x
5
mgintravena.
Direncanakan
untuk
pengangkatan tampon keesokan harinya.
Gambar
7.
Foto pasien saatkontrol
ketiga. Bengkak di pipi kanan sudah berkurang.Pada
tanggal 27
Marel2015
(hari
pertama pascaoperasi) pasien
tidak
mengeluhkannyeri
kepala,tidak
ada
air
matamengalir
terus
menerus,
pasien
mengeluhkan
ada rasanyeri
di
daerahpipi
kanan dan adaair
ludah
bercampur
darah.
Dilakukan
pengangkatan tampon anterior pada
kalum
nasi
kanan dan dilakukan
evaluasi tidak
terdapat
tanda
perdarahan.
Pasiendiperbolehkan
pulang
dan
disarankanuntuk kontrol ke
poli THT 3 hari
setelahpulang
dari
rumah
sakit. Terapi
pulangyang
diberikan kepada pasien
adalahsiprofloksasin tablet 2
x
500mg
dan asammefenamat3x500mg.
Pada saat
kontrol
pertama 30Maret
2015
(5
hari
setelah operasi),
pasienmengatakan
bengkak
di
pipi
kanan
sudahberkurang,
nyeri
di
pipi
kanan
sudahberkurang,
hidung
kanan
tersumbat,
dantidak
ada keluhan mata berair. Padakavum
nasi
kanan
tampak
flap
yang
merupakankonka
inferior dalam posisi baik,
tidak
terbuka, tampak
krusta
kecokatan,
dandarah yang
membeku,
evaluasi
ostiumsinus
asesorisyang
dihubungkan
denganostium natural
menggunakan
scope
30'
tampak dalam
kondisi baik,
hanya terdapatsedikit
krusta
disekelilingnya.
Krusta
dibersihkan dan
dicuci hidung
NaCl
0,9 %3
kali
sehari
sebanyak
20
cc,
terapiantibiotik
dan analgetik diteruskan.Saat
kontrol
kedua
6
April
2015pasien mengatakan bengkak
di pipi
kanansudah
berkurang, namun
terkadang masihnyeri
jika
ditekan.
Pasien
tidak
terlalu
mengeluhkan adanya
hidung
tersumbat.Pasien
juga
mengatakankeluar
gumpalan darahdari
hidung
danmulut
setelahcuci
hidung. Pada
kavum
nasi
kanan,ditemukan
flap
dalam
kondisi
baik,
tampak
kusta
kecoklatan
bercampurseket
mukoid
yang kemudian dibersihkan,ostium
assesorisdievaluasi dengan
scopeI
\
L
a-l
il
30'
tampak dalam kondisi baik,
krustayang
berada disekitar
ostium
sudahberkurang. Terapi
sebelumnyadilanjutkan
dan ditambah pemberian ambroksol 3
x
30mg peroral.
Pada
kontrol ketiga
13
April
2015sebagian besar keluhan pasien
sudahberkurang, hanya
tinggal
bengkak
di
pipi
kanan
yang belum hilang
seutuhnya,tidak
ada
lagi
nyeri
di
pipi
kanan
saat ditekan,tidak ada
lagi
keluhan
keluar
darahmenggumpal
dari
hidung
atau tenggorok
saat
cuci
hidung.
Pasien
juga
tidak
mengeluhkan
lagi
adanya
hidung
tersumbat.
Pada pemeriksaankalum
nasikanan,
flap
dalam
posisi
baik,
krustaminimal, tampak
sedikit
sekretseromukous
pada
kavum nasi
kanan,
danostium assesoris dalam
kondisi
baik.Pasien
datang
membawa
hasilPatologi
Anatomi
dengan
hasil
tampak stromajaringan ikat
yang
sebagian udem,mengandung
kelenjar
seromukous
yang sebagianmelebar dan
berisi
massaamorf
eosinofilik.
Tampakjuga
pembuluh
darahyang
melebar, stroma
bersebukanringan
limfosit dan sel
lasma,
diagnosis
nasalpolip.
Ditemukan
juga
potongan jaringan
yang
sebagian
dilapisi epitel
berlapisgepeng,
sebagianoleh epitel
respiratoriusdan
sebagian
dilapis
2-3
lapis
epitel.Dibawahnya
tampakjaringan
ikat
dengansebukan
sedanglimfosit dan
sel
plasma,ada potongan
tulang rawan,
serta kristal
kolestrol. tampak
juga
bagian
yanghiperemik hemoragik,
diagnosisdentygerous
cyst
(gambar
8).
Terapiantibiotik
dan
analgetik
pada
pasiendihentikan,
pasien hanyadiberi
terapi cuci
hidung
NaCl
0,9%
3 x
20
cc
danambroksol
3
x
30 mg
dan
disarankankontrol
2
minggu lagi
dan
direncanakanuntuk konsul
ke
bagian
gigi
dan
mulut
mengenai
gigi
impaksinya.Gamtrar
8.
Tampak lapisan
kista
denganepitel respiratorius
DISKUSI
Telah dilaporkan
satu kasus kista
dentigerus
di
sinus maksila kanan
pada seoranglaki-laki
24 tahun yang ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaanfisik
dan
pemeriksaan
penunjang
sepertinasoendoskopi
serta
CT
scan
sinusparanasal
dan
dipertegas
dengan
hasil
patologi
anatomi.Pasien
adalah seorang
laki-laki
berusia
24
tahun,
hal
ini
sesuai
dengankepustakaan
yang
mengatakan
bahwakasus
kista
dentigeruslebih
banyakterjadi
pada
lakiJaki
dibandingkan
perempuan.Dengan kejadian banyak
muncul
pada dekade2-
3 kehidupan.r'2'3'6Pasien
datang
dengan
keluhanutama bengkak pada
pipi
kanan
yang membesar secaraperlahan.
Hal
ini
sesuaidengan banyak kasus
yang
ditemukan dikepustakaanbahwa pasien akan
datangdengan keluhan bengkak pada
pipi
yangterkena
yang
membesar
secaraperlahan.l'a'6'? Pada beberapa kasus seperti yang dikemukakan
oleh
Mili
etalro
bahwamereka
juga
pemah
mendapatkan
kasuskista
dentigerus
yang
berukuran
sangat besar. dan ganggu penglihatan pasien.Dengan adanya
keterlibatan
sinusmaksila pada pasien
ini,
semakin memperberatkondisi
pasien, karena dapatterjadi
destruksitulang
akibat
pembesarandari
massa
kista
ini
secara
perlahan.ZfrI
f,s
E'rq
=rt-{
L-1
?
L(r
.a
Seperti
yang
dikutip
dari
Singh6
dan MhaskeTbahwa
kista
dentigerusmemiliki
potensi
untuk
menjadi
sangat besar
danmenyebabkan
ekspansi
bahkan
erositulang. Motamedi
et
al3
mengemukakan bahwakista
dentigerus dapat menghalangigigi
yang
akan tumbuh,
menjadi
sangatbesar
hingga
menghancurkan
tulang
danmencapai
struktur
vital
seperti
sinusmaksila.
Sedangkan Soon5
menyatakanbahwa
jika
kista
dentigerus
berukuranbesar, maka
kista
ini
dapat mengobstruksisinus maksila.
Pada
pemeriksaan
fisik,
dannasoendoskopi
tidak
ditemukan
kelainanyang khas untuk
kasus
ini.
Pada
kasustertentu,
dapat
ditemukan
adanyapendorongan
dinding
lateral sinus maksila. Setelahdilakukan
foto
panoramik,barulah
muncul
kecurigaan
bahwapembengkakan
pada
pipi
pasienkemwrgkinan adalah kista dentigerus. Pada
hampir
semualiteratur
menyatakan bahwakista
dentigerus
umunnya
terdiagnosissecara
tidak
sengaja saat pasien melakukanfoto
panoramik
rutin.l'7
Pada
gambaranfoto
panoramik
pasien
ini di
dapatkankesimpulan
suspek
dentigerous
cyst mencapai sinus maksilaris kanan, impactedM3
gerahamkanan dan
kiri
bawah, M3
geraham
kiri
atas.Secara
radiologik
perlu
dibedakanantara
kista
dentigerus dengan tumorjinak
lainnya
yang
juga
terdapat
struktur
gigi
didalamnya.
Seperti yang
dikemukakanoleh
Ikeshima
et
al8
bahwa
kista
dentigerous
dapat
didiagnosis
bandingdengan
tumor
yangjuga
memiliki
struktur
gigi
di
dalamnya,yaitu
ameloblasoma danadenomatoid
tumor
tanpa
kalsifikasi.
Hal
ini
dapat
ditegaskan
dengan
memeriksajarak
antara cemento
enamel
junction
ketempat
gigi
yang tertanam.8Pada
pemeriksaan
CT
Scanditemukan adanya
struktur
gigi
di
dalamsinus
maksila
yang
menguatkankecurigaan
bahwa
ini
adalah suatu kista
dentigerus. Seperti yang dikemukakan oleh Soon
et
al5, gambaranCT
scan padakista
dentigerus
yang
berada
di
sinus
maksila
dapat memperlihatkan adanya
"tooth
like
densiyr'pada lesi
kistik
yang
berada
di
dalam sinus yang
terlibat.
PemeriksaanCT
scan pada kasus
ini
juga
sangat
pentinguntuk
mengetahui apakahterjadi
perluasanke
tulang yang
mengakibatkan
destruksi danperlu untuk menyingkirkan
keganasanjika terjadi
keterlibatan
yangmengakibatkan destruksi
pterygoid plate
atau orbita.5
Teknik
operasi
yang
digunakanpada kasus
ini
adalahmaksilektomi
medialperendoskopik.
Teknik
ini
dipilih
karenaaman
dan
efektif untuk
mengobatibeberapa
kasus
kista
odontogenik termasukkista
dentigerus.e'l l'12 Dahulunyateknik yang
digunakan
untuk
menatalaksana
kasus
kista
dentigerusadalah dengan
menggunakan
prosedurCaldwell-Luc. Namun
temyata
teknik ini
merusak
mukosa sinus maksila
sehinggamengakibatkan
hilangnya
fungsi
mukosiliar yang
ada
di
dalamnya
karenamucociliary
clearance
dari
sinus maksila
selalu
mengarah
ke
ostium
natural,
danalirannya
dimulai
dari
lantai sinus
danberlanjut
sampai
dinding ostium
natural melawan gravitasi.l6Seno et
al
12
mengutarakan bahwapembedahan
sinus
perendoskopik
selain dapat digunakan sebagai tatalaksanauntuk
menterapi
rinosinusitis
konis,
tumor
jinak
kavum nasi,
fistula
serebrovaskular, dapatjuga
digunakan
untuk
mengobati
pasiendengan
kista
odontogenik sinus
maksila.Teknik
maksilektomi medial
perendoskopiinvasif,
angka keberhasilan
lebih
tinggi
dan
komplikasi lebih minimal.
Nakayama
et
ale
menggunakanteknik maksilektomi
medial perendoskopikuntuk
mengevakuasikista
dentigerus yangberada
di
dalam sinus maksila.
Prinsip
dasar
dari
maksilektomi
medialperendoskopik
untuk
kasus
kista
dentigerus
yang telah
mencapai
sinusmaksila
adalah
untuk
menjaga
keutuhankonka
inferior
dan duktus
nasolakrimalis.Keuntungan
untuk
penggunaan teknik
maksilektomi medial perendoskopi
adalahteknik
ini
memungkinkan
dilakukannya
reseksi
komplit pada
satu
operasi.Thulasidas
et
all6
menambahkan
bahwatujuan
dari
penggunaan
teknik
maksilektomi
medial
perendoskopikadalah
untuk
menciptakan drainase
sinusmaksila
yang
gravity-dependent Berikut
dirangkum
perbedaan
pilihan
teknik
operasi
secara Caldwell-Luc
denganmaksilektomi
medial perendoskopik.Tabel
1,
Perbedaan maksitelrtomi medial perendoskopik dengan teknik Cadwell-LucPada
temuan operatif
ditemukaaadanya
gigi
molar,
yang
kemungkinan
besar adalah
gigi molar 3
pasien
ini,
hal
dikonfirmasikan dengan hilangnya
gigi
molar
3,
sehingga
gigi
yang
ditemukan pada sinusmaksila
kanan pasienini
adalahgigi
molar
3
kanan pasienyang
impacteddan akibat terbentuknya kista
disekitar
gigi
maka
gigi
itu
masuk ke sinus maksila.Hasil
Patologi
Anatomi
padatemuan operasi
pada
pasien
ini
adalahditemukan potongan
jaringan yang
berisi
epitel
berlapis gepeng
yang
sebagianmerupakan
epitel
respiratorius
dan sebagiandilapisi
oleh dua sampaitiga
lapisepitel.
Di
bawalrnya tampakjaringan ikat
dengan sebukan sel radang
limfosit
dan selplasma, tampak potongan
tulang
rawan, sertakristal
kolestrol,
tampakjuga
bagianyang
hiperemik
hemoragik
dengandiagnosis
kista
dentigerus.
Temuan diatas serupa dengan gambaran kista dentigerusMenurut
Kasat
et
all,
Soon
et
alsKista
dentigerusdibatasi oleh
lapisandari
epitel
skuamosaberlapis
tidak
berkeratin,yang
terdiri
dari
2-4 lapis
sel dan
elemen keratinjarang ditemukan
di
dinding
dalam kista,kista
ini dikelilingi
olehjaringan
ikat
yang
mengandung
epitel
respirasi.
Dapatjuga
ditemukan
sel silia, sel kuboid,
selkolumnar,
hyaline body dan
dapat
juga
ditemukkan invasi dari
sel-sel radang.l'5Prognosis
pada
kasus
kista
dentigerus
adalah
baik.
Seperti
yangdiungkapkan
oleh
Seno
et
alr2
dari
tiga
pasien
dengan
kista
dentigerus
yangdilakukan
tindakan
modifikasi
maksilektomi
medial
perendoskopik
dandilakukan
follow up
pada
pasien-pasientersebut,
tidak
ditemukan
adanya kekambuhan setelah 11-72bulan.
Mhsakeet
al7
mengutarakan
bahwa
prognosisuntuk hampir
semua kasus kista dentigerusyang
didiagnosis secara
histopatologi
Caldwell-Luc
Maksilektomi
medial
perendoskopik
Dilakukan
endoskopi tersediabila
tidak
Dapat mengakibatkan gangguan persarafanTidak
mengganggupersarafan
Lapangan
operasilebih
luasLapangan
operasi terbatasDapat
digunakanuntuk
mengangkatkista yang
besarsecara
keseluruhandi
sinusmaksila
Pengangkatan kista
yang
berukuranbesar
tidak
dapatdilakukan
secarautuh
Angka
kekambuhantinggi
Angka
kekambuhanjarang
Dilakukan
jika
adalah
sangat
baik,
kekambuhan
sangatjarang
ditemukan.
Singh
et
al6
menilai
radiografi
postoperatifpada
pasien dengankista
dentigerus
akan
memperlihatkan gambaran pembentukan dan penyembuhantulang
setelah 6 bulan post operasi.KESIMPULAN
Keluhan bengkak
di
pipi
yang membesar secaraperlahan dan
ditemukanstruktur
gigi
pada
sinus
maksila,merupakan
diagnosis
untuk
kista
dentigerus.
Namun demikian,
diagnosiskista
dentigerustidak
dapatberdiri
sendirtanpa
adanya anamnesis
yang
baik
danpemeriksaan
penunjang
yang
lengkapseperti Rontgen
panoramik dan
CT
Scan sinus paranasal, dankonfirmasi
dari PA.Ada
banyak
teknik
pembedahanyang
dapat dipergunakan pada kasus
ini,
rurmun sebaiknya
dipilih teknik
yangminimal
invasife dan
dapat
memaparkanisi
sinus
dengan
baik
dan
meminimalisir
risiko
pasca operasi seperti
teknik
maksilektomi medial
perendoskopi. Jika
kista
ini
reseksi dengan
sempurna, makaangka
kekambuhannya sangatjarang,
danprognosisnya
baik.
DAFTAR PUSTAKA
l.
Kasat
VO,
Freny
R,
Laddha
RS.Dentigerous
cyst
assosiatedwith
anectopic
third
molarin
maxillary
sinus: a casereport and review
of
literature. Contemp Clin Dent. 2013;3 (3):373-6.2.
Chung
LW,
Cox DP,
Ochs
MW.Odontogenic Cyst, Tumors, and Related
Jaw Lesion.
In
Bailey
BJ,
Johnson JT,Newlands
SD,
editors. HeadAnd
Neck Surgery-Otolaryngology 4'h ed. LippincottWilliams
&
Wilkins:
Texas;
2006; p.1590-l3.
Motamedi
MHK,
Talesh
KT. Managementof
extensive
dentigerouscyst.
Brit
Dent J. 2005; 198(4):203-6.4.
Badran
W
Karam,
Yau
&ffiy,
TracyLauren,
HassoA;
Massive dentigerous cyst presentingwith
facial deformity and maxillary sinusitis;A
studyof
two cases.Jar' 2013 Indian
J
Otolaryngol. 2013; 58(l)
15.
SoonHJ,
Heung
LM, Kim
HD, et
al. Dentigerous cyst involving the maxillarysinus. J.Rhinol. 2001; 8 (1,2): 54-57
6.
SinghS,
SinghM,
ChhabAN,
YamunaN.
Dentigerouscyst:
Aa
case report. JIndian Soc Pedo Prev Dent.
2001;9:
123-5.
7.
MhasakeS,
Ragavendra&
Doshki
JJ,Nadaf
I.
Dentigerous cyst associated withimpacted
permanentmaxillary
canine. People's Sci ResI.
2009;2(2):17 -19.8.
Ikeshima
A,
Tamura
Y.
Differentialdiagnosis between dentigerous
cyst
and benigntumor
with
an
embedded tooth. Oral Sci 1.20A2; 44 (l):1317 .9.
NakayamaT,
Otori
N,
AsakaD, et
al.Endoscopic
modified
medialmaxillectomy
for
odontogenicyst
andtumours. J Rhinol. 2014; 52: 37 6-380. 10.
Mili
MK,
PathakGK.
A
giant
caseof
dentigerous
cyst
:
a
casereport.
Int
JDent Med Res. 2015; 1 (5) : 84-86. 11.
Eloy Ph,
Mardyla
N,
Bertrand
B,Rombaux
Ph.
Endoscopic
endonasalmedial maxillectomy: case series. Indian J
Otolaryngol
.2010;62
(3):252-7 .12. Seno S, Ogawa
T,
ShibayamaM,
et
al.Endoscopic
sinus
surgery
for
theodontogenic
maxillary
cyst.
J
Rhinol. 2009; 47:305-309.13. Shergil
AK,
Singh P, CharotteM,
et
al.Dentigerous
cyst
associatedwith
anerupted tooth an unusual presentation.
Int
J
Sci Stud.2014;2 (2): 100-10214.
Amin
ZA,
Amran
M,
Khairudin
A.Removal
of
extensive
maxillarydentigerous
cyst
via
a
caldwell-lucprocedure. Orofac Sci J.2008; 3
(2):48-5l
15.
Dagista
S,
Cakur
B,
GoregenM.
A
dentigerous
cyst
containingan
ectopiccanine
tooth below
the floor
of
themaxillary sinus: a case report. Oral Sci J.
2007; 49 (3):249-252.
16. Thulasidas P, Vaidya
V.
Role of modifiedendoscopic
medial
maxillectomy
inpersistent chronic
maxillary
sinusitis. IntArch
Otorhinolayngol.2014;
18
:
159-164.
17. Sadeghi
N,
Al-Dhahri
S,
Manoukian J.Transnasal endoscopic
medialPolip
NasiAngiomatosa (Angiomatous
NasalPolyps)
dr. Bestari Jaka Budiman Sp.T.H.T.K.L (K), dr Dolly lrfandy Sp.T.H.T.K.L, dr. Eko wahyudi*
Departemen llmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Andalas RSUP Dr. M. Djamil Padang
Abstrak
Pendahuluan: Polip
nasi
angiomatosa
sangat jarang
terjadi
dankejadiannya hanya 4-5o/o
dari
kasuspolip
nasi. Polip nasi angiomatosa ditandaidengan adanya proliferasi vaskular
yang
luas.
Tujuan:
Mengetahui
diagnosis dan penatalaksanaan polip nasi angiomatosa.Laporan
Kasus:
Dilaporkan satukasus
laki
laki berumur
34
tahun yang didiagnosis awal dengan tumor
kavumnasi bilateral. Pada kasus
ini
dilakukan biopsi eksisi tumor
perendoskopi. Darihasil
pemeriksaan histopatologi, didapatkan
kesan polip nasi
angiomatosa.Kesimpulan:
Polip nasi angiomatosabisa
menyerupai gambaran keganasan dikavum nasi. Pemeriksaan histopatologis menjadi baku emas dalam menegakkan
diagnosis dalam kasus ini
Kata
kunci
: polip angiomatosa, tumor kavum nasi, polip nasiAbstract
lntroduction:
Angiomatous
nasal polyp/Angiectatic nasal
polyps (ANP)is rare
and
its incidenceis 4-5% of
all
nasal polyps. ANPSa/e characteized by
extensive vascular
proliferation
and
ectasia.
Objectives:
To
understand aboutdiagnos,s
and
management
of
angiomatous
nasa, polyps. Case
Report:
Repofting
an
case in a 34year
male that previously diagnosedas
bilateral nasalcavity
tumor.
Resuftfrom
histopathology examination revealed
angiomatousanasal polyps
Conclusion:
ANPSmay presenf
as
malignancy
in
nasal
cavity.Histopathology examination
as
gold standard can established diagnosisof
nasalpolyp
Keryords:
Angiomatouspolyp,
nasal cavity tumor, nasalpdyps
PENDAHULUAN
Berdasarkan
elemen utama
yang
membentuk
polip
nasi,
secarahistopatologis polip
nasi
inflamasi dibagiatas
5tipe:
(1)tipe
edema,terdiri
dari eosinofildan sel
mast dalamjumlah yang
banyak,(2) lipe
fibrous, mengandungbanyak limfosit,
(3),
tipe
glandular, mengandung kelenjar seromusin,
(4)
tipekistik
dan (5) tipe
angiomatosa,
terdapat
proliferasi
vaskular
yang
luas
dan deposit dari pseudoamiloid.1 '?Hidung tersumbat
merupakan
gejala yang
sering dikeluhkan
pasien dengan polip nasi angiomatosa. Selain itu, epistaksis, bengkak pada wajah dansnoflhg
juga
bisa
terjadi.Pada
pemeriksaanfisik
rinoskopi anterior,
diGmukanadanya massa polipoid
yang
berwarna kebiruan
atau
merah, permukaan
licindan
mengkilat yang mengisi kavum nasi. Pada pemeriksaanCf
Scan, polip nasiangiomatosa memberikan gambaran lesi dengan densitas
yang
heterogen yangmengisi
kavum nasi atau sinus
dan
massa
menunjukkan penyangatan
yangminimal pada batas lesi.26
Pada
pemeriksaan histopatologi,
polip nasi
angiomatosa
memberikan gambaran kelompokan pembuluh darah yang dikelilingi fibrin matrik ekstraselularyang
menyerupai eosinofil,jaringan
nekrosis,sel
inflamasi,trombosis
pembuluhdarah
dan
ekstravasasi komponen
darah
ke
dalam stroma.
Perubahanhistopatologi
yang terjadi
bisa
bervariasi,
dari
hanya
berupa
fibrosis
stromalsampai terbentuknya perubahan
vaskularisasi,
termasuk
adanya
proliferasivaskular2'3'7
Penatalaksanaan
pada kasus polip
nasi
angiomatosa
berupapembedahan.
Eksisi
perendoskopi merupakanprosedur
penatalaksanaan yang aman dan efektif pada polip nasi angiomatosa.5'8LAPORAN KASUS
Seorang pasien
laki
laki berumur 34 tahun datang
ke
Poliklinik THT-KL RSUP Dr. M.Jamil Padang padatanggal
8 Januari 2016 dengan keluhan utamahidung tersumbat sejak
4
bulan
yang lalu.
Pasien
mulai
merasakan
keluhanhidung tersumbat sejak
6
tahun yang lalu, yang makin lama makin berat sejak 4bulan
terakhir. Keluar ingus
kentaldari hidung
sejak4
bulanyang lalu.
Pasienjuga
mengeluhkan keluardarah dari hidung,
sebanyakt
I
sendok makan
danbisa
berhentisendiri.
Penciuman tergangguada.
Pasien merasakanrasa
lendirmengalir
di
tenggorok. Nyeri kepala ada, hilang timbul. Suara pasien
berubahmenjadi sengau
sejak
1
tahun yang lalu.
Keluhan telinga
terasa
penuh
ada.Pasien sebelumnya telah menjalani operasi polip pada tahun 2009
di
RS swastadengan
keluhan
yang sama. Satu tahun setelah
operasi,
pasien
kembali merasakan keluhan hidung tersumbat. Pasien jugatelah
menjalani biopsi hidungdi
bagian THT-KL
pada
bulan Agustus 2015, dengan
hasil polip nasi
dandianjurkan kontrol,
tapi
pasien
tidak kontrol
ke
bagian
THT
setelah
operasi.Mempunyai kebiasaan merokok 1 bungkus sehari sejak 10 tahun yang lalu.
Pada pemeriksaan fisik, didapatkan keadaan umum
dalam
batas normal.Pada pemeriksaan status lokalis THT, pemeriksaan telinga dan tenggorok dalam
batas normal. Pada
pemeriksaan nasoendoskopi ditemukankedua kavum
nasisempit, massa memenuhi kedua kavum nasi dengan permukaan yang tidak rata,
mudah berdarah dan ditutupi dengan jaringan nekrotik. Ditemukan adanya sekret
yang
mukopurulen. Peme