PEMAHAMAN ANAK KELAS III DAN VI SEKOLAH DASAR (SD) TENTANG BUMI DAN PERISTIWA SIANG-MALAM : STUDI KASUS
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Fisika
Disusun Oleh :
Yusinta Devi Kurniati
NIM : 031424032
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
2009
iv
Hid up han y a t ent an g seb uah pil ihan…
A pakah kit a akan t et ap b er d iam,
A t au kit a b el aj ar men j ad i sesuat u y an g l eb ih d an
l eb ih…
Skripsi ini kupersembahkan kepada A llah SW T; awal dari semua cerita.
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:
Nama : Yusinta Devi Kurniati
Nomor Mahasiswa : 031424032
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:
Pemahaman Anak Kelas III dan VI Sekolah Dasar (SD) Tentang Bumi dan Peristiwa Siang–Malam: Studi Kasus
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal: 25 Februari 2009
Yang menyatakan,
(Yusinta Devi Kurniati)
ABSTRAK
PEMAHAMAN ANAK KELAS III DAN VI SEKOLAH DASAR (SD) TENTANG BUMI DAN PERISTIWA SIANG-MALAM : STUDI KASUS
Yusinta Devi Kurniati, ”Pemahaman Anak Kelas III Dan VI Sekolah Dasar (SD) Tentang Bumi Dan Peristiwa Siang Malam : Studi Kasus”. Program Studi Pendidikan Fisika Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 2008
Penelitian ini bertujuan untuk : Untuk mengungkap pemahaman siswa dan bagaimana gagasan yang dimiliki oleh anak dapat diungkap, baik dengan lisan maupun tulisan.
Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Timbul Rejo, Sleman dan SD Nusawungu III, Cilacap pada bulan Oktober. Subyek penelitian adalah 6 orang dengan rincian 4 anak SD Negeri Timbul Rejo (2 orang kelas III dan 2 orang kelas VI) dan 2 anak kelas VI SD Negeri Nusawungu III. Peneliti melakukan pengamatan langsung kepada subyek tanpa pemberian treatment terlebih dahulu. Data pemahaman anak tentang materi bumi dan peristiwa siang malam diperoleh dari pengisian lembar kerja dan wawancara subyek; anak terlebih dahulu mengisi lembar kerja sebelum diwawancara. Data pemahaman anak tentang materi bumi dan peristiwa terjadinya siang – malam dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan : (1) pemahaman anak tentang bumi dan peristiwa siang malam masih terbatas pada informasi yang disampaikan guru dalam kelas. (2) anak masih memahami pengetahuan yang disampaikan guru di sekolah sebagai teori yang harus dihafal dan bukan penerapannya dalam kehidupan sehari – hari (3) pemahaman anak SD masih terbatas pada sesuatu yang konkrit.
ABSTRACT
UNDERSTANDING OF CHILD CLASS III AND VI ELEMENTARY SCHOOL (SD) ABOUT EARTH AND EVENT DAY-NIGHT: CASE
STUDY
Yusinta Devi Kurniati
Understanding Of Child Class of III And of VI Elementary School ( SD) About Earth And Event Day – Night : Case Study.
Physics Education Study Program, the Department of Mathematics and Science, Faculty of Teacher Training and Education, Sanata Dharma University, Yogyakarta (2008).
This research was aimed at reveal to know the student’s understanding and how idea had by child can be expressed.
This research was held in SD Negeri Timbul Rejo, Sleman and SD Negeri Nusawungu III, Cilacap on October 2008. The subject of this research is 6 student’s with detail 4 child of SD N Timbul Rejo ( 2 child class III and 2 child class VI) and 2 child class VI SD Negeri Nusawungu III. Researcher do direct observation without giving treatment beforehand. The data was obtained by the subject was filling a spread sheet and then researcher was interviewing subyek. Data of child understanding about earth and event of day and night analysed by deskriptif qualitative.
The result of this research shows that : (1) children’s understanding about earth and day - night event still limited to submitted by teacher information in class (2) child still comprehend knowledge in school as theory which must be memorized and not its applying in life (3) understanding of elementary school student’s still limited to something that konkrit.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya,
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemahaman
Anak Kelas III Dan VI Sekolah Dasar (SD) Tentang Bumi Dan Peristiwa Siang
Malam : Studi Kasus”.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan Fisika di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Dalam penyusunan tulisan ini peneliti didukung oleh banyak pihak, oleh
karena itu penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:
1. Drs. T. Sarkim, M.Ed.,Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang telah
memberikan bimbingan dengan baik dan sabar, yang telah banyak meluangkan
waktu, masukan selama penulisan skripsi ini.
2. Bp. R. Rohandi, M.Ed., selaku dosen pembimbing akademik, Bp. T. Sarkim,
Ph.D., Bp. Drs. Domi S, M.Si, Bp. Drs. Fr. Y. Kartika Budi, M.Pd, Bp. A.
Atmadi, M.Si., Ibu Maslichah Asy’ari, M.Pd. dan Bp. Drs. F. Sinaradi, M.Pd.
selaku dosen program studi Pendidikan Fisika USD yang telah membimbing
penulis selama melaksanakan pendidikan di Universitas Sanata Dharma ini.
3. Bapak Drs. Domi Saverius, M.Si selaku kaprodi, terimakasih juga untuk
bimbingan dan masukannya.
4. Keluarga besar SD Negeri Timbul Rejo, Sleman dan SD Negeri Nusawungu
III, Cilacap atas bantuan, waktu dan ijin untuk pelaksanaan penelitian ini.
5. Bapak Danang T. R (kediamanmu adalah semangat bagiku) dan Ibu Kartini
(senyummu adalah kekuatanku), harapan, kepercayaanmu, nasehatmu adalah
sumber inspirasiku, kasih sayang dan doamu adalah hidupku. Hanya ini yang
dapat kupersembahkan, semoga akan mejadi sesuatu yang membanggakan dari
anakmu.
6. Adikku Melynda, bergabung dalam keluarga JP MIPA bukan sesuatu yang
buruk bukan? Semangat!!!
7. Yang selalu ada dihatiku Deni Hariyanto, mengenalmu adalah sesuatu yang
tidak pernah kubayangkan. Terimakasih untuk segala pengertian, kasih sayang
dan dukungan.
8. Keluarga besarku di Jogja, terimakasih semangat, pengertian dan
tumpangannya waktu sinta kesepian dikos.
9. Para personil ex-KSB (Kelompok Skripsi Bareng) : dede (terimakasih untuk
semua cerita yang pernah ada, terimakasih untuk persahabatan yang boleh
kurasakan darimu. ayo dums semangat), ciwi (kamu orang pertama yang aku
kenal saat menginjakkan kaki di Sanata Dharma, terimakasih untuk semua,
untuk persahabatan kita), kakak botak (terimakasih telah menjadi kakak
selama aku hidup di Jogja, semoga sinta gak cengeng lagi), dimas (makasih
udah banyak dibantu mengawali analisis skripsi ini, patner PPL, KKN dan lain
– lain. Ayo tem kita ujian bersama, kapan kita ke perpus lagi?), eko (teruslah
membuat banyak orang tertawa, terimakasih atas saran dan masukan serta
selalu membuatku tersenyum), dias (kriting, terimakasih untuk
semangatnya...), lilis (lis terimakasih untuk pengalaman yang aku peroleh
darimu, semoga aku juga cepat mengikuti jejakmu menjadi ibu guru), tomas
(ternyata kamu gak se-‘olok’ yang anak – anak bilang, nyatanya kamu lulus
pertama), kalian semua sahabat terbaikku di Sanata Dharma tanpa kalian aku
bukan apa – apa.
10.Teman-teman P.Fis 2003 (Tica, Nana, Ica, Boni, Rosa, Sisca, Mba Endar,
Ervan, Agata, Ely, Dewi Klaten, Yeni, Gilang, Romo Dion, Luci, Juni, Ipus,
Andre, Cornel, Loren, Eka, Mei, Alfon, Simrosa, Gita, Titis, St.Ruth, Wahyu
terimakasih ya suatu keberuntungan bagiku bisa bertemu dan menimba ilmu
bersama kalian, takan pernah kulupakan kebersamaan kita.
11.Kos lebah, Shinta, Mbak asih, Mbak Yuni, Amel, Melon, kalian merupakan
bagian terindah selama perjalanku kuliah di Jogja.
12.Keluarga besar Bapak Joko, eyang kakung & eyang uti, terimakasih sudah
diterima ditengah – tengah keluarga ini.
13.Semua pihak yang tidak bisa disebutkan, terima kasih atas segala bantuan doa
dan dukungannya.
Demikianlah tulisan ini dapat diselesaikan. Peneliti memohon maaf apabila
terdapat kesalahan dalam penyusunan tulisan ini. Tulisan ini jauh dari sempurna,
oleh karena itu peneliti juga mengharapkan kritik dan saran demi pengembangan
tulisan ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING... ii
HALAMAN PENGESAHAN... iii
HALAMAN PERSEMBAHAN... iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA... v
PERNYATAAN PUBLIKASI... vi
ABSTRAK... vii
ABSTRACT... viii
KATA PENGANTAR... ix
DAFTAR ISI... xii
DAFTAR LAMPIRAN... xvi
DAFTAR TABEL... xvi
DAFTAR GAMBAR... xvi
BAB I. PENDAHULUAN... 1
A. Latar Belakang ... 1
B. Landasan Teori... 4
1. Berpikir Ilmiah pada Anak... 4
a. Ide Bersifat Lebih Personal... 6
b. Ide – Ide yang Dikemukakan Anak Nampak Tidak Koheren 6 c. Ide Masih Bersifat Stabil... 7
d. Pemikiran Anak Didominasi oleh Persepsi... 7
e. Pusat Perhatian Anak Terbatas... 7
f. Pusat Perhatian Lebih pada Perubahan Bukan Keadaan.... 8
2. Hakekat Sains... 8
3. Metode “POP”... 9
4. Berpikir Sebagai Bagian dari Proses belajar... 10
a. Pembentukan Pengertian... 10
b. Pembentukan Pendapat ... 11
c. Penarikan Kesimpulan ... 11
5. Belajar ... 12
a. Pengertian Belajar ... 12
b. Jenis - Jenis Belajar... 12
1) Menurut A. De Block... 12
2) Menurut C. Van Pareren ... 13
6. Perkembangan Pengetahuan ... 13
a. Peran Pengetahuan Awal dalam Perkembangan Pengetahuan 13 b. Perkembangan Pengetahuan pada Anak ... 14
7. Kecerdasan/Intelegensi ... 18
C. Rumusan Masalah ... 23
D. Tujuan Penelitian ... 23
E. Manfaat ... 24
BAB II. METODOLOGI PENELITIAN... 25
A. Jenis Penelitian... 25
B. Partisipan Penelitian... 25
C. Desain Penelitian... 26
D. Waktu dan Tempat ... 28
E. Validitas ... 28
F. Metode Pengumpulan Data ... 29
G. Instrumen Penelitian ... 30
H. Metode Analisis Data... 30
BAB III. DATA DAN ANALISIS DATA... 36
A. Deskripsi Penelitian ... 36
B. Data ... 38
C. Hasil... 48
1. Kelas III... 48
a. Seperti Apa Bentuk Bumi? ... 48
b. Mengapa Benda Jatuh ke Bumi?... 49
c. Bagaimana Siang dan Malam Terjadi? ... 50
2. Kelas VI ... 51
a. Seperti Apa Bentuk Bumi? ... 51
b. Mengapa Benda Jatuh ke Bumi?... 51
c. Bagaimana Siang dan Malam Terjadi? ... 52
D. Pembahasan... 53
1. Bagaimana Pendapat yang Dikemukakan Anak tentang Materi Bumi dan Peristiwa Siang - Malam? ... 53
2. Bagaimana Pemahaman Anak tentang Peristiwa
yang Berhubungan dengan Masalah Sains yang
Biasa Mereka Temui dalam Kehidupan Sehari-Hari? ... 58
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN... 65
A. Kesimpulan ... 65
B. Saran... 66
C. Keterbatasan Penelitian... 67
DAFTAR PUSTAKA... 68
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Lembar Kerja ... 70
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara... 71
Lampiran 3 Lembar Kerja Jawaban Responden... 72
Lampiran 4 Transkrip Wawancara Responden... 78
Lampiran 5 Lampiran Gambar Responden ... 104
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Anak mengisi LKS ... 37
Gambar 2. Wawancara ... 37
DAFTAR TABEL Tabel ringkasan jawaban responden ... 38
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.
Pada dasarnya anak-anak lebih banyak memperoleh pengetahuan dari
lingkungan sekitar, dari apa yang mereka lihat, dengar dan alami secara
langsung. Dapat dikatakan bagaimana anak memperoleh pengetahuan dasar,
tergantung fasilitas yang tersedia dalam lingkungan tempat tinggalnya.
Semakin banyak yang mereka alami, semakin banyak hal-hal yang dipelajari
anak tersebut. Bagaimanapun juga lingkungan yang kondusif memungkinkan
seorang anak menjadi lebih kritis dalam perkembangannya. Saat ini sudah
sangat lazim jika seorang anak yang masih tergolong balita mulai memperoleh
pengetahuan secara terarah, meskipun masih terbatas pada hal-hal tertentu dan
sederhana yang pasti berbeda jika dibandingkan dengan pendidikan formal.
Tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan tiap anak berbeda-beda.
Selama berabad-abad berkembang pendapat jika seorang anak yang banyak
bertanya dan memiliki rasa selalu ingin tahu mengenai segala hal diidentikan
dengan tingkat kecerdasan. Tetapi apakah pendapat ini benar dan dapat
diterima begitu saja? Dalam sebuah sumber (www.balitacerdas.com)
disebutkan keaktifan anak untuk bertanya banyak hal tidak selalu berarti
bahwa anak ini cerdas, tergantung bagaimana anak menanggapi jawaban dari
pernah memperhatikan jawaban yang merupakan kelanjutan dari pertanyaan
yang diajukan anak tersebut.
Permasalahan seperti ini sebenarnya sangat sederhana, namun dari
masalah-masalah tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan anak dengan
berbagai latar belakang akan membawa anak-anak pada pengetahuan awal
yang berbeda dan tidak dapat disamakan. Kebanyakan guru belum
mempertimbangkan bahwa setiap anak memerlukan pendampingan yang tidak
sama pada tiap individu karena pengetahuan bawaan dan ketertarikan belajar
tiap anak ini juga berbeda.
Latar belakang tersebut terkadang menimbulkan masalah dalam dunia
pendidikan. Mulai dari masalah cara atau pola belajar siswa sampai dengan
masalah yang paling kompleks dan umum terjadi yaitu miskonsepsi terhadap
sebuah materi pengajaran. Permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan
bukan saja terletak pada pergantian kurikulum atau sistem pendidikan, namun
lebih pada masalah mendasar yaitu pola atau cara pandang masyarakat sendiri
terhadap pentingnya proses belajar anak dalam lingkungan sekolah atau
lingkungan tempat tinggalnya.
Setiap anak memiliki daya imajinasi, baik yang disadari atau tidak.
Daya imajinasi ini yang mendukung kreativitas mereka untuk “menganalisis”
penyebab dari fenomena yang mereka lihat. Ketika mulai memasuki jenjang
pendidikan yang paling dasar, mereka membawa pengetahuan awal ke
lingkungan pendidikan. Persepsi yang dibawa oleh siswa tersebut jelas
berbeda, kemungkinan akan menghasilkan pola berpikir yang tidak sama pada
masing-masing anak.
Oleh karena itu ketertarikan anak untuk mempelajari sesuatu pasti akan
berbeda dan tidak dapat disamakan begitu saja. Sebagai contoh hal yang
paling sederhana yang ditemui anak pada awal pembelajaran seperti ketika
mereka belajar mengeja alfabet, belum tentu semua anak dikelas mengerti
dengan metode mengajar guru.
Yang akan dilihat peneliti sebatas bagaimana anak mampu
menganalisa sebuah permasalahan tentang fenomena fisika sederhana dan
kemudian membahasakannya. Sesuai dengan tingkat perkembangannya, anak
tidak dituntut untuk berpikir sesuai dengan metode ilmiah yang biasa
digunakan dalam penelitian terbimbing. Namun lebih pada apakah jawaban
anak cukup masuk akal dan sesuai dengan teori yang sudah ada selama ini.
Dari hal seperti itulah timbul sebuah pertanyaan apakah anak-anak
mempunyai bakat dan kemampuan untuk berpikir ilmiah? Mereka hanya
diberi masalah yang sangat sederhana kemudian mereka menyatakan pendapat
mengenai fenomena yang mereka lihat dari sudut pandang anak tanpa
pengaruh dari peneliti. Dari cara-cara yang ditempuh anak inilah pola berpikir
mereka dilihat, apakah penyelesaian masalah dalam versi mereka sudah cukup
menggambarkan bahwa seorang anak dalam rentang usia tertentu sudah
mampu mengemukakan gagasan yang notabene bersifat ilmiah sesuai dengan
Untuk alasan itulah maka peneliti mengambil judul: “Pemahaman
Anak Usia Sekolah Dasar Kelas III Dan VI Tentang Bumi Dan Peristiwa
Siang Malam”(Studi Kasus).
B. Landasan Teori.
1. Berpikir Ilmiah pada Anak.
Berpikir ilmiah pada anak tidak dapat diartikan seperti kegiatan
orang dewasa dalam menganalisis sesuatu secara sistematis dan sesuai
dengan metode yang ada, dimana seorang ilmuwan akan memulai dari
sebuah hipotesis yang kemudian diikuti dengan percobaan (eksperimen)
dan terakhir menarik kesimpulan (Sumadi : 1984). Proses ilmiah yang
runtut dimulai dari hipotesis sampai dengan penarikan kesimpulan tersebut
tidak dapat dipaksakan untuk seorang anak, karena bagaimanapun juga
mereka masih mengalami perkembangan pengetahuan yang terus-menerus
dalam lingkungan pendidikan formal.
Istilah dalam sains sangat berbeda dengan istilah-istilah yang
sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kata-kata tersebut
biasa kita dengar namun maknanya akan sangat berbeda. Perbedaan makna
kata-kata tersebut terkadang mengakibatkan kerancuan bagi seorang anak
yang belum mengenyam pendidikan formal dan hanya belajar dari
pengalaman. Hal ini akan membangun persepsi tersendiri pada anak.
Contohnya seperti saat anak melihat benda jatuh atau ketika mereka
Selama bertahun-tahun penelitian dengan subjek anak hanya
berusaha menggambarkan apa yang sekiranya dianggap mampu dilakukan
oleh anak-anak. Namun pada kenyataannya seorang anak mempunyai
pengetahuan dan kemampuan menjelaskan segala sesuatu yang mereka
lihat dan alami lebih dari apa yang pernah diduga oleh para ilmuwan akan
ditemukan pada anak-anak. Anak belajar mengenai dunia dengan bertanya
kepada orang di sekeliling mereka, menonton televisi atau dengan sekedar
bermain-main diluar.
Kapasitas untuk mengungkapkan gagasan ilmiah pada anak kecil
(pada tingkatan anak TK) jauh lebih besar jika dibandingkan dengan
perkiraan selama ini (Purwanto : 2006). Anak dengan berbagai latar
belakang ekonomi dan sosial menunjukan fakta jika mereka memiliki
pengalaman mengemukakan gagasan ilmiah. Meskipun pengalaman dan
pengetahuan anak masih kurang namun semua yang sudah mereka ketahui
dapat digunakan sebagai dasar untuk mempelajari sesuatu sebagai proses
kompleks. Dengan memberikan perhatian pada pola pikir anak,
mendengarkan mereka dan menanggapi ide yang mereka kemukakan
secara lebih serius untuk mengerti arah pikiran anak, guru dapat
membangun pengetahuan berdasar apa yang sudah anak ketahui dan
lakukan.
Kenyataan seperti ini menggambarkan bahwa anak-anak mampu
dalam bidang sains, dapat dilihat dari bagaimana ketika mereka mendapat
dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Karena itulah
anak perlu mendapatkan bimbingan agar apa yang mereka bangun terarah
dan terstruktur sejak level pendidikan paling dasar yaitu TK.
Adapun ciri-ciri pemahaman anak mengenai konsepsi gejala alam
dan segala objek yang ada di dalamnya (Sarkim : 2006):
a. Ide bersifat lebih personal.
Setiap anak memiliki konsepsi sendiri-sendiri mengenai apa yang
mereka lihat dan alami, pengalaman diluar lingkungan sekolah
mempengaruhi pembentukan pengetahuan dan kemampuan anak yang
akan mereka bawa ke dalam kelas. Sebagai contoh ketika anak-anak
dalam satu kelas diminta menuliskan pengertian mereka tentang bumi
dan segala yang ada didalamnya, dapat dipastikan akan muncul jawaban
yang sangat beragam. Variasi jawaban yang dibuat anak merupakan
gambaran sifat alami tentang cara mereka berpikir dan
mengkomunikasikannya. Pendapat anak ketika menanggapi peristiwa
alam dengan interpretasinya juga sangat dipengaruhi oleh harapan dan
ide-ide mereka sendiri terhadap apa yang mereka amati. Tiap individu
memiliki ide-ide personal yang mereka bangun dari pengalaman.
Namun meskipun ide yang dimiliki anak bersifat personal, tidak
menutup kemungkinan terdapat kesamaan ide dengan yang lain.
b. Ide-ide yang dikemukakan anak nampak tidak koheren.
Anak-anak seringkali memiliki konsepsi yang berbeda tentang sebuah
mengakibatkan prediksi yang bertentangan dengan sudut pandang sains.
Koherensi pada kerangka beripikir anak memang diperlukan namun
harus terarah dengan kriteria tertentu.
c. Ide masih bersifat stabil.
Pengetahuan awal anak bersifat stabil, konsep awal yang sudah
terbentuk pada diri anak sangat sulit dihilangkan. Banyak anak yang
tidak menyadari bahwa pemahaman yang mereka yakini selama ini
bertentangan dengan teori, bahkan dalam level pendidikan setingkat
SMP para guru masih kesulitan memberikan penjelasan untuk
mengubah ide anak mengenai berbagai fenomena. Misalnya pada bab
tentang mekanika, siswa akan cenderung berpendapat lintasan gerak
benda hanya akan lengkung jika terjadi perpaduan anatara GLB dan
GLBB pada arah yang lain seperti pada gerak peluru.
d. Pemikiran anak didominasi oleh persepsi.
Penalaran anak berdasar hal-hal yang terlihat saat mereka melakukan
observasi. Contoh : seorang anak memandang bahwa bentuk bumi
adalah datar dengan langit diatasnya.
e. Pusat perhatian anak terbatas.
Dalam banyak kasus sangat terlihat bahwa anak hanya memperhatikan
aspek-aspek tertentu dari sebuah peristiwa. Pusat perhatian anak selalu
tertuju pada hal-hal yang kelihatan mencolok. Sebagai contoh, dalam
mereka tidak memperhitungkan bahwa dalam proses pembakaran ada
faktor lain seperti oksigen.
f. Pusat perhatian lebih pada perubahan bukan pada keadaan.
Kecenderungan bahwa anak lebih memperhatikan perubahan dari pada
keadaan dapat menjadi bagian dari ciri perhatian anak yang terbatas.
Anak-anak kurang memperhatikan segala sesuatu yang terlihat diam,
seperti tekanan pada air yang tenang. Anak beranggapan bahwa tekanan
pada zat cair hanya ada jika zat cair tersebut bergerak atau mengalir.
2. Hakekat sains.
Dalam arti sempit sains dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang
dibagi menjadi dua bagian yaitu physical sciences dan life sciences.
Sedangkan sains sendiri merupakan upaya membangkitkan minat manusia
untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang alam semesta
dan seisinya. Dalam artian yang luas sains sendiri diartikan sebagai ilmu
yang mempelajari gejala alam.
Sains merupakan sebuah proses untuk untuk mempelajari alam
dengan segala yang ada (John : 1983).
a. Sains sebagai proses untuk mengantarkan anak pada sebuah penemuan.
Sains sebagai sebuah proses panjang yang menuntun anak pada sebuah
kesimpulan yang ditemukannya sendiri. Anak dibimbing untuk
menemukan sendiri penjelasan atas peristiwa ilmiah yang ada
b. Sains sebagai pengetahuan.
Sains disini dimaksudkan sebagai hasil dari pengetahuan yang berasal
dari konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya.
c. Sains menghasilkan sesuatu yang bernilai.
Banyak hal yang yang berbau teknologi dan berguna untuk kehidupan
berasal dari riset dan penelitian.
3. Metode “POP”.
Strategi “POP” merupakan suatu strategi dalam pembelajaran yang
melibatkan siswa untuk ikut aktif selama proses belajar berlangsung. POP
dibagi mejadi tiga tahap kegiatan untuk memecahkan masalah, yaitu tahap
prediksi, observasi dan penjelasan (Sumaji : 1998).
a. Prediksi.
Prediksi yang dimaksudkan disini mengenai masalah sains yang
diajukan dan prediksi bukan kegiatan yang bersifat untung-untungan,
melainkan kegiatan yang didasarkan pada alasan, pertimbangan atau
perhitungan yang bersifat ilmiah.
b. Observasi.
Pada tahap ini anak dihadapkan pada masalah konkret, anak hanya
mengamati gejala-gejala selama kegiatan berlangsung.
c. Penjelasan.
Tahap terakhir dalam metode POP adalah penjelasan. Siswa
membandingkannya dengan prediksi yang sudah dibuat. Antara prediksi
dan penjelasan sendiri dapat berupa penguatan, bila keduanya sesuai
atau justru sebaliknya.
4. Berpikir sebagai Bagian dari Proses Belajar.
Berpikir merupakan sifat dasar manusia yang menjadi ciri khas dan
membedakan dengan makhluk lain. Secara garis besar berpikir dapat
diasumsikan sebagai satu keaktifan manusia yang mengakibatkan
penemuan yang terarah pada suatu tujuan. Menurut M. Ngalim Purwanto
(2006 : 43) ciri utama berpikir adalah adanya abstraksi. Abstraksi dalam
hal ini yaitu bagaimana penggambaran seseorang dalam usaha mencari
suatu jawaban atau pembenaran dari pertanyaan yang muncul. Dalam hal
lain berpikir juga diartikan sebagai usaha mengkaitkan atau
menghubungkan hal-hal yang sekiranya relevan.
Menurut Suryabrata (1984) berpikir memiliki proses atau
tahapan-tahapan yaitu ;
a. Pembentukan pengertian.
Pengertian yang ingin dibentuk selama proses berpikir
berlangsung adalah pengertian logis. Pengertian seseorang dapat
terbentuk ketika mereka mulai melihat bahwa suatu obyek yang sejenis
memiliki ciri khas masing-masing dan tidak dapat disamakan.
Selanjutnya ciri-ciri tersebut diklasifikasikan sesuai dengan kesamaan
b. Pembentukan pendapat.
Suryabrata (1984:58) membentuk pendapat adalah meletakan
hubungan antara dua buah pengertian atau lebih. Dari dua buah
pendapat yang berkaitan atau bahkan tidak berhubungan sama sekali
dicari kesamaan dan perbedaanya untuk kemudian dilihat kaitan
diantara keduanya.
c. Penarikan kesimpulan.
Kesimpulan yang diinginkan disini merupakan generalisasi dari
pendapat-pendapat yang sudah ada sebelumnya dan dikemas dalam
sebuah pemahaman baru yang diyakini kebenarannya tentang suatu hal.
Terlepas dari semua hal yang merupakan proses berpikir, pada
anak-anak perkembangan kognitif memiliki proses mental yang berbeda.
Anak memiliki keterbatasan dalam hal perhatian dan ingatan yang
merupakan dua hal penting dalam memproses informasi.
Ingatan merupakan suatu proses sentral dalam perkembangan
kognitif anak, ingatan meliputi rangkaian penyimpanan memori yang
kontinyu. Ingatan sadar anak dimulai saat berumur 7 bulan, meskipun pada
usia ini sampai rentang usia pra sekolah ingatan yang terbentuk hanya
5. Belajar.
a. Pengertian Belajar.
Secara umum belajar adalah proses perubahan dari belum
mampu menjadi sudah mampu dan terjadi dalam jangka waktu tertentu.
Berlangsungnya proses belajar tersebut ditandai dengan adanya
perubahan pada diri individu tersebut. Semakin banyak kemampuan
yang diperoleh maka akan semakin banyak juga perubahan yang terjadi
pada diri seseorang.
Menurut A. De Block dalam Winkel (1987:40) belajar meliputi
tiga bidang, yaitu belajar di bidang kognitif, sensorik-psikomotorik, dan
dinamik afektif. Melalui belajar bidang kognitif, anak memperoleh
pengetahuan dan pemahaman. Melalui bidang belajar
sensorik-psikomotorik, anak memperoleh kemampuan motorik. Dan yang
terakhir belajar dinamik-afektif, anak memperoleh berbagai sikap dan
tingkah lakunya.
b. Jenis-jenis belajar.
1) Menurut A. De Block dalam Winkel (1987:40).
Dalam bergaul dengan lingkungan hidupnya, orang juga belajar
banyak hal yang berguna untuk mengatur kehidupan. Orang yang
cenderung belajar dari pengalaman hidupnya disebut belajar
insidental. Belajar insidental berlangsung, jika orang mempelajari
sesuatu dengan tujuan tertentu, tetapi disamping itu juga belajar hal
ini sendiri biasanya hanya terbatas pada pengetahuan tentang data
dan fakta.
2) Menurut C. Van Parreren dalam Winkel (1987:50)
C. Van Parreren menyebutkan bahwa belajar membentuk
otomatisme. Bentuk belajar ini terutama meliputi belajar
ketrampilan motorik, namun tidak menutup kemungkinan juga
akan meliputi belajar kognitif. Ciri khas dari hasil
belajar/kemampuan yang diperoleh ini, terletak dalam otomatisasi
sejumlah rangkaian gerak-gerik yang terkoordinir satu sama lain.
Suatu program berlangsung seolah-olah terjadi dengan sendirinya.
Disamping jenis-jenis belajar yang sudah disampaikan diatas, ada
juga pengertian belajar menurut teori kognitif. Menurut teori ini yang
ditekankan adalah proses belajar dan bukan bagaimana hasilnya. Model
belajar ini menyatakan tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh persepsi
serta pemahamannya tentang sesuatu. Selain itu teori kognitif juga
menyebutkan bahwa belajar merupakan sebuah proses berpikir yang
kompleks dan melibatkan banyak aspek seperti ingatan, retensi,
pengolahan informasi, emosi dan aspek kejiwaan lainnya.
6. Perkembangan Pengetahuan.
a. Peran Pengetahuan awal dalam perkembangan pengetahuan.
Pada dasarnya setiap siswa masuk ke dalam lingkungan sekolah
pengaruh bagi mereka selama proses belajar berlangsung. Meskipun
pengetahuan awal ini dapat dirubah namun membutuhkan proses yang
panjang dan tidak mudah. Apa yang diperoleh anak dari proses belajar
melalui pengalaman akan memberikan pemahaman tersendiri yang
diyakini kebenarannya. Pengetahuan awal ini nantinya akan
berkembang seiring dengan perubahan dan kemajuan yang terjadi pada
diri anak itu sendiri (Winkel : 1987).
b. Perkembangan pengetahuan pada anak.
Setiap orang pasti akan mengalami perubahan seiring dengan
waktu, perkembangan yang dialami pasti akan berbeda pada tiap pribadi
yang berbeda pula (Winkel : 1987). Istilah perkembangan identik
dengan pertumbuhan meskipun dalam masyarakat kata pertumbuhan
lebih familiar dibanding perkembangan. Dua kata ini sebenarnya
memiliki arti yang sangat berbeda, perkembangan merupakan
perubahan kualitiatif dan kuantitatif sedangkan pertumbuhan lebih
berkaitan dengan perubahan kuntitatif yaitu peningkatan ukuran dan
struktur.
Perkembangan dapat diartikan sebagai proses berlangsungnya
perubahan-perubahan dalam diri seseorang yang membawa
penyempurnaan dalam kepribadiannya. Proses perkembangan sudah
dimulai saat anak belum memperoleh pendidikan formal, jadi
Dalam tahap perkembangan pengetahuan seorang anak, yang
pertama kali dipelajari adalah hal-hal dalam lingkungan sekitarnya.
Anak belajar dari apa yang mereka lihat, dengar dan alami. Setiap hal
yang mereka temui ditangkap sebagai sebuah pengalaman belajar
meskipun terkadang belum ada penjelasan logis untuk hal tersebut.
Pada dasarnya setiap anak mempunyai daya imajinasi untuk
menjelaskan dengan cara mereka sendiri meskipun tidak masuk akal.
Imajinasi dibagi menjadi dua yaitu yang disadari dan tidak disadari,
tentunya imajinasi dari masing-masing anak tidak akan sama. Dengan
melihat gambaran imajinasi anak ini, dapat diraba bagaimana
sebenarnya pola pikir anak-anak dan sejauh mana cara pandang mereka
dapat dikaitkan dengan kemampuan menganalisis sesuatu secara
sistematis/ilmiah.
Kemampuan anak akan meningkat selaras dengan bertambahnya
umur. Seseorang memperoleh kecakapan intelektual tergantung dari apa
yang mereka rasakan dan ketahui dengan yang mereka lihat mengenai
sebuah fenomena sebagai pengalaman baru. Agar seseorang dapat terus
mengembangkan pengetahuan dan mental maka perlu adanya
keseimbangan. Proses keseimbangan yang dimaksud adalah bagaimana
orang tersebut mampu menyeimbangkan faktor lingkungan luar dan
kemampuan kognitifnya. Jika tidak terjadi proses keseimbangan akan
Hal ini biasanya nampak pada cara berbicara yang tidak runtut,
berbelit-belit, terputus-putus, tidak logis, dan sebagainya.
Menurut J. Piaget seperti dijelaskan dalam Purwanto (1987)
perkembangan intelektual anak dapat dibagi dalam 4 taraf yaitu :
1) Fase sensomotorik (umur 0-2 tahun).
Selama fase ini kemampuan anak hanya sebatas pada
kegiatan motorik dan persepsinya yang masih sederhana. Ciri dari
tahap ini dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan langkah demi
langkah. Misalnya suka meperhatikan sesuatu lebih lama atau
mendifinisikan sesuatu dengan manipulasinya.
2) Fase pra-operasional, (umur 2-7/8 tahun).
Anak belum dapat mengadakan perbedaan yang tegas
antara perasaan dan motif pribadinya dengan realitas dunia luar.
Fase ini dibedakan menjadi 2 bagian yaitu preoperasional dan
intuitif. Pada umur 2-4 tahun anak telah mampu menggunakan
bahasa namun kemungkinan untuk menyampaikan konsep-konsep
tertentu kepada anak sangat terbatas. Anak sudah mampu
mengembangkan konsepnya meskipun masih sangat sederhana,
sehingga sering terjadi kesalahan dalam memahami objek.
Umur 4-7 atau 8 tahun anak memperoleh pengetahuan
abstrak, namun anak dengan kisaran usia ini belum dapat
mengungkapkan kesimpulan yang mereka ambil melalui kata-kata.
simbol-simbol. Di tahap ini seorang anak sudah mulai mengetahui
hubungan yang logis terhadap hal-hal yang lebih kompleks.
3) Fase operasi konkrit (umur 7/8-11/12 tahun).
Ciri utama perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah
memiliki kecakapan logis meskipun masih terbatas pada benda
yang bersifat konkret. Dalam menghadapi sebuah permasalahan
anak tidak perlu memecahkannya dengan percobaan dan perbuatan
yang nyata, ia telah mampu melakukan dalam pikirannya. Namun
anak hanya akan menyelesaikan masalah yang dialami secara nyata
karena anak masih mengalami masalah untuk berpikir abstrak.
4) Fase operasi formal (umur 11/12-18 tahun).
Anak telah mampu beroperasi berdasarkan kemungkinan
hipotesis dan tidak lagi dibatasi oleh apa yang berlangsung atau apa
yang telah dialami sebelumnya. Anak telah mampu menentukan
variabel-variabel yang memungkinkan serta hubungan yang
mungkin. Pada fase ini anak memiliki pemikiran logis dan dapat
memberikan pernyataan formal tentang ide-ide yang konkrit.
Seorang anak dalam rentang usia ini mampu berpikir abstrak dan
logis dengan menggunakan pola berpikir “kemungkinan”
7. Kecerdasan/intelegensi.
Sebagian besar orang tua mempunyai anggapan anak-anak yang
cerdas lebih aktif dibandingkan dengan anak-anak yang kurang cerdas.
Anak-anak yang cerdas lebih menyenangi permainan-permainan yang
bersifat intelektual atau permainan yang banyak merangsang daya berpikir
mereka, misalnya permainan drama, menonton film, atau membaca
bacaan-bacaan yang bersifat intelektual. Hal ini seolah membenarkan
bahwa ukuran seberapa pandai individu dapat diukur dengan sebuah
takaran.
Tidak banyak orang yang mengerti bahwa kecerdasan seseorang
tidaklah tunggal melainkan jamak dan terbagi-bagi menjadi beberapa
bagian. Menurut Robert J. Stenberg seperti dijelaskan dalam Suparno
(1986), kecerdasan terwujud dalam tiga bentuk, antara lain intelegensi
analitis, intelegensi kreatif dan intelegensi praktis. Hal tersebut dapat
diartikan bahwa kemampuan seseorang dalam bidang matematis baru
mewakili satu bentuk kecerdasan yaitu intelegensi analitis dan praktis.
Sementara intelegensi kreatif adalah kemempuan untuk menciptakan,
mendesain, menemukan hal-hal baru.
Di sisi lain beberapa teori menyebutkan bahwa intelegensi atau IQ
seseorang dipengaruhi oleh faktor biologis atau dengan kata lain
kecerdasan/intelegensi merupakan sifat bawaan, dan tidak dapat dirubah
berkaitan dengan hal tersebut. Meskipun begitu sebenarnya masih belum
ada definisi pasti yang menyebutkan mengenai pengertian intelegensi.
Adapun faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi
kecerdasan seseorang antara lain (www.iqeq.web.id):
a. Faktor bawaan atau keturunan seperti yang sudah disebutkan diatas,
yaitu merupakan masalah genetik yang diyakini tidak bisa dirubah
dengan training atau pelatihan-pelatihan karena sudah merupakan sifat
bawaan pada diri orang itu sendiri.
b. Faktor lingkungan, walaupun pada dasarnya ada ciri-ciri sejak lahir
namun lingkungan ternyata juga mampu memberikan perubahan pada
tingkat intelektualitas seseorang. Anak yang tumbuh dalam lingkungan
yang kondusif pastilah perkembangannya akan lebih baik. Misalnya
saja dengan pemenuhan gizi yang cukup atau dengan pemberian
rangsangan kognitif emosional dari lingkungan.
Salah satu pendapat menyatakan bahwa intelegensi merupakan
kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan dalam situasi yang
nyata. Dari pengertian tersebut sudah dapat dilihat bahwa sebenarnya
intelegensi bukan sekedar kemampuan untuk menjawab pertanyaan
dalam tes IQ, namun lebih pada kemampuan untuk memecahkan masalah
yang benar-benar dihadapi dalam situasi yang bermacam-macam.
Beberapa contoh dapat ditemukan misalnya seseorang yang berhasil dalam
pada dasarnya tidak lepas dari pengukuran IQ yang hanya ditekankan pada
kemampuan matematis-logis dan linguistik seseorang.
Setiap anak cerdas, tidak ada yang berkembang sebagai anak
bodoh. Menurut Suparno (2004:13) setiap orang menpunyai kemampuan
yang bermacam-macam, intelegensi bukanlah tunggal. Gardner dalam
Suparno (2004:19) menyebutkan saat ini ada sembilan intelegensi yang
diterima yaitu :
a. Intelegensi linguistik (linguistic intelligence).
Intelegensi linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata
baik secara verbal maupun tertulis. Kemampuan seperti ini biasanya
dimiliki oleh para penulis/jurnalis dan pemain teater.
b. Intelegensi matematis-logis (logical-mathematical intelligence).
Kecerdasan matematis-logis lebih berkaitan pada kemampuan
matematis dalam penggunaan bilangan dan logika. Orang-orang dengan
intelegensi matematis logis yang menonjol akan lebih mudah
mengabstraksikan suatu persoalan dan cara pikirnya memiliki alur
sehingga mudah mengembangkan pola sebab akibat atau sering disebut
sebagai pola pikir ilmiah. Oarang seperti ini sangat cocok
berkecimpung dibidang sains.
c. Intelegensi ruang (spatial intelligence).
Intelegensi ruang merupakan kemampuan seseorang dalam menangkap
d. Intelegensi kinestik-badani (bodily-kinesthetic intelligence).
Intelegensi kinestetik-badani biasanya ditemui pada seorang aktor atau
penari. Kecerdasan kinestetik badani adalah keahlian menggunakan
tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan, jadi semua hal
yang ingin mereka sampaikan diekspresikan melalui bahasa tubuh.
e. Intelegensi musikal (musical intelligence).
Intelegensi usikal adalah kemampuan untuk mengembangkan gagasan
dalam bentuk musik seperti yang dimiliki oleh para musisi.
f. Intelegensi interpersonal (interpersonal intelligence).
Kemampuan untuk menangkap dan membuat pembedaan dalam
perasaan, intensi, motivasi dan perasaan orang lain
g. Intelegensi intrapersonal (intrapersonal intelligence).
Pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara
adaptif berdasar pengenalan diri itu. Keseimbangan diri seseorang
termasuk dalam intelegensi intrapersonal.
h. Intelegensi lingkungan/naturalis (naturalist intelligence).
Intelegensi naturalis lebih berkaitan dengan pengenalan pada alam,
flora dan fauna yang bersifat biologis. Kemampuan seperti ini dimiliki
oleh seorang pecinta alam.
i. Intelegensi eksistensial (existential intelligence).
Intelegensi eksistensial lebih berupa kemampuan untuk berfikir
Ke-sembilan intelegensi menurut Gardner tersebut dimiliki oleh
setiap orang. Namun pada umumnya seseorang hanya menguasai beberapa
keahlian saja. Misalnya seorang anak yang terlihat lebih menonjol pada
bidang sains mungkin lemah dalam bidang musik. Sebagai penggambaran
yang lebih nyata lagi yaitu tentang pernyataan tentang jenius seperti
Einstein, ilmuwan sehebat Einstein belum tentu mampu menghasilkan
deretan notasi musik yang indah untuk didengar. Atau mungkin sebaliknya
pernyataan yang diajukan kepada Mozart sang maestro musik, apakah
mampu menjawab fenomena alam dengan gagasan pasti maupun
pembuktian rumus yang tidak terbantahkan?
Kecerdasan matematis-logis seseorang tidak menjamim bahwa
orang tersebut dapat melakukan segala hal. Dari contoh tersebut diatas
dapat terlihat dengan sangat jelas bahwa orang yang sangat cerdas
sekalipun memiliki kelemahan dalam bidang-bidang tertentu.
Idealnya prestasi anak atau siapapun yang sedang mengalami
proses belajar dapat “tereksploitasi” dengan baik jika disesuaikan dengan
minat dan ketertarikannya dalam suatu bidang. Dari uraian tersebut dapat
disimpulkan bahwa sebenarnya apa yang ingin disampaikan guru dapat
diserap dengan baik oleh siswa jika diajarkan dengan metode yang sesuai
dengan kecerdasan yang menonjol pada diri anak itu. Hanya yang menjadi
masalah berikutnya adalah bukan suatu hal mudah untuk mengetahui
tersebut untuk siswa yang pada dasarnya memiliki kemampuan
berbeda-beda.
C. Rumusan Masalah.
Setiap anak berkembang dengan pemikiran mereka yang bersifat
personal dengan latar belakang pengetahuan yang jelas berbeda. Pengetahuan
awal anak terbentuk karena pengalaman belajar dari lingkungan yang
berbeda-beda juga pada masing-masing individu. Teori Piaget menyebutkan bahwa
pemikiran anak akan berkembang sesuai dengan fase yang mereka lalui, mulai
dari sensomotorik, pemikiran konkrit baru pemikiran abstrak. Maka dalam
mempelajari IPA, anak juga perlu memulai dari kejadian atau peristiwa yang
konkrit sebelum dihadapkan pada sesuatu yang abstrak.
Masalah yang akan dikaji adalah: “Bagaimana pemahaman anak tentang peristiwa yang biasa mereka temui dalam kehidupan sehari-hari?”. Di dalam penelitian ini, peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang dipilih adalah bentuk bumi dan peristiwa siang dan malam.
D. Tujuan Penelitian.
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pemahaman siswa tentang bumi
E. Manfaat.
Manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai bahan wacana
dalam menghadapi pembelajaran pada anak-anak, sehingga dapat
“menginspirasi” peneliti lain.
Sebagai wacana hendaknya penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi
guru pada level pendidikan dasar dan menengah agar dapat menempatkan diri
di tengah-tengah siswa. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencari metode
BAB II
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis penelitian.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dan
kualitatif. Dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan hanya
untuk menggambarkan suatu keadaan tertentu. Metode ini dipilih karena
peneliti hanya ingin mengungkapkan sejauh mana anak mampu melihat
sebuah fenomena yang berhubungan dengan fisika dan menganalisis keadaan
tersebut. Secara umum penelitian ini hanya bertujuan untuk melihat
pemahaman siswa dan keadaan pengetahuan awal siswa dalam sebuah
populasi tertentu.
“Pada proses penelitian untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mampu menelaah dan memilah pengalaman mereka menjadi pengetahuan yang berharga, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain sebagainya (Poerwandari, 2005:56).”
B. Partisipan Penelitian
Subyek penelitian ini adalah enam orang siswa Sekolah Dasar di SD
Timbulrejo; Sleman dan SD N Nusawungu V; Cilacap. Beberapa siswa
diambil secara acak pada siswa Sekolah Dasar kelas III dan kelas VI. Hasil
yang diperoleh dalam penelitian bersifat studi kasus karena subjek diambil
secara random dan hanya mewakili populasi tertentu sehinggga tidak dapat
dijadikan acuan secara mutlak untuk penelitian selanjutnya.
C. Desain Penelitian.
Penelitian terbatas pada ruang lingkup yang kecil, hal ini dikarenakan
subjek hanya beberapa orang saja sehingga pengambilan data dilakukan pada
kelompok kecil. Anak harus dibuat agar merasa senyaman mungkin selama
penelitian.
Setiap anak boleh menjawab pertanyaan sesuai dengan pengetahuan
yang mereka miliki, sekalipun jawaban yang dikemukakan anak salah. Dari
pendapat yang terlontar ini kemudian dilakukan wawancara lebih lanjut untuk
mengetahui alasan mereka mengemukakan pendapat tesebut. Setiap kali anak
berpendapat tidak diharuskan untuk mengemukakannya secara lisan, mereka
boleh saja menulis dalam bentuk karangan atau menggambar sesuai dengan
apa yang mereka pikirkan.
Bagan proses penelitian adalah sebagai berikut:
• Observasi
pengetahuan anak SD
• Analisis awal
Pengambilan data dengan lembar kerja
Tahap penelitian sebagai berikut:
1. Sebelum pengambilan data dimulai, proses pertama yang dilakukan
peneliti adalah melakukan observasi pengetahuan anak. Observasi ini
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peta pengetahuan anak
sehingga peneliti dapat menentukan pertanyaan apa saja yang dapat
digunakan untuk menggali pemahaman anak tentang materi bumi dan
peristiwa siang-malam. Materi yang dipilih disesuaikan dengan silabus
pelajaran IPA kelas VI Sekolah Dasar.
Subyek observasi berbeda dengan responden penelitian, subyek observasi
diberikan 9 pertanyaan tertulis kemudian dilanjutkan wawancara tidak
tersruktur dengan ruang lingkup bahasan materi bumi dan peristiwa
siang-malam. Berdasarkan hasil obsetrvasi ini lalu disusun 3 pertanyaan dalam
lembar kerja dan daftar pertanyaan wawancara.
(Lembar kerja dan daftar pertanyaan wawancara lihat lampiran)
2. Pada tahap pengambilan data yang pertama siswa diberi lembar kerja
(LKS) berisi pertanyaan tentang materi bumi. Siswa diminta untuk
mengisi LKS dengan jawaban berupa tulisan maupun gambar. Jawaban
responden juga tidak harus benar, responden mengisi LKS sesuai dengan
pengetahuan yang dimiliki.
Daftar pertanyaan (lihat lampiran)
3. Tahap pengambilan data yang ke dua adalah wawancara responden,
setelah responden selesai mengisi LKS kemudian responden diwawancara
terstruktur karena wawancara hanya mengikuti alur jawaban responden
meskipun peneliti sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan
wawancara yang disusun peneliti hanya sebagai patokan mengenai hal-hal
apa saja yang harus digali lebih jauh dari anak.
Daftar pertanyaan wawancara (lihat lampiran)
4. Dari data yang sudah diperoleh baik itu dari lembar kerja, transkrip
wawancara maupun pengamatan kemudian dianalisis.
D. Waktu dan Tempat.
1. Waktu penelitian.
Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2008.
2. Tempat penelitian.
Sekolah Dasar Negeri Timbulrejo; Sleman; Yogyakarta dan Sekolah
Dasar Negeri Nusawungu V; Cilacap; Jawa Tengah.
E. Validitas.
Untuk instrumen berupa lembar kerja, validitas data dilihat dari
kesesuaian jawaban yang dikemukakan anak dalam lembar kerja dengan teori
yang ada. Namun meskipun demikian tidak ada jawaban salah untuk anak,
apapun yang dikemukakan anak itulah yang akan dianalisis karena setiap anak
mempunyai pandangan dan pendapat masing-masing berdasarkan
melalui proses sampai ahirnya menarik sebuah kesimpulan dan
mengemukakannya dengan cara mereka.
Sedangkan untuk metode wawancara instrumen penelitian berupa alat
rekam (recorder). Untuk menguji instrumen yang digunakan pada
pengambilan data, peneliti hanya memandang dari segi validitas isi (content
validity). Sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas isi apabila sesuai
dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu instrumen dibuat sungguh-sungguh
dan sesuai tujuan penelitian.
F. Metode Pengumpulan Data.
1. Pengisian Lembar kerja.
Lembar kerja berisi pertanyaan untuk lebih mengarahkan anak dalam
mengemukakan ide mereka mengenai sebuah topik dalam hal ini adalah
topik mengenai bumi. Meskipun lembar kerja berupa urutan pertanyaan
namun anak tidak diharuskan mengemukakan ide mereka dalam bentuk
tulisan atau karangan, mereka diperbolehkan mengutarakan gagasan
mereka dengan gambar-gambar.
2. Wawancara
Dalam hal ini wawancara yang dilakukan tidak terstruktur, disesuaikan
dengan kebutuhan dan kelengkapan data. Wawancara hanya berpedoman
pada alur pemikiran anak tanpa dilakukan treatment terlebih dulu. Dengan
diberi kesempatan mengemukakan jawaban mereka tanpa pengaruh dari
peneliti.
3. Pengamatan
Untuk melengkapi data yang diperlukan, peneliti melihat dari perilaku
anak selama penelitian berlangsung dan transkrip wawancara dengan
responden. Selanjutnya transkrip wawancara dianalisis dan dilihat
kesesuaiannya.
G. Instrumen Penelitian
1. Lembar Kerja
Lembar kerja berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai fenomena alam
yang biasa dilihat oleh anak dalam kehidupan sehari-hari.
2. Recorder
Recorder digunakan untuk merekam wawancara. Wawancara ini sendiri
bersifat fleksibel, untuk mengetahui pengetahuan awal anak.
3. Lembar Pengamatan
Pengamatan dilakukan oleh peneliti selama proses pengambilan data
berlangsung.
H. Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan untuk mengolah data adalah berupa
analisis deskriptif melalui wawancara, gambar, cerita lisan atau bahkan
Ketika dihadapkan pada sebuah soal setiap anak pasti akan cenderung
berpendapat menurut apa yang mereka yakini, bagaimana pendapat ini
diungkapkan mungkin berbeda antara anak yang satu dengan lainya. Disini
anak akan diberi kebebasan lebih untuk mengemukakan ide dengan cara
mereka sendiri misalnya dengan gambar atau tertulis.
Penelitian ini cenderung menggunakan analisis data secara kualitatif.
Setiap pertanyaan dalam lembar kerja yang diberikan pada siswa mewakili
tahap prediksi, observasi dan penjelasan mengenai apa yang mereka lihat dari
percobaan. Kemampuan anak dalam mengemukakan gagasan ilmiah dapat
dilihat dari lembar kerja yang diisi saat percobaan berlangsung. Kemampuan
anak mengemukakan gagasan sendiri dilihat dari penjelasan mereka mengenai
fenomena yang disajikan peneliti.
Selain dari data hasil pekerjaan pada lembar kerja, data juga diperoleh
dari wawancara. Data yang sudah diperoleh dari wawancara kemudian diubah
menjadi bentuk narasi tertulis yang menggambarkan proses wawancara
tersebut. Transkrip wawancara dan observasi dikaji oleh peneliti dengan cara
mengikuti pola jawaban anak. Selain dari hasil transkrip wawancara, perilaku
anak selama proses pengambilan data berlangsung juga tidak luput dari
perhatian peneliti. Sikap anak ini yang dapat dijadikan indikasi sejauh mana
mereka mampu menyelesaikan masalah.
Sesuai dengan teori Piaget, anak dengan rentang usia antara 7-12 tahun
anak sudah mempunyai kecakapan logis walaupun kemampuan mereka masih
terbatas pada benda-benda yang bersifat konkret.
Setiap jawaban yang dikemukakan anak akan dianalisis untuk melihat
sejauh mana tahapan dalam metode ilmiah terpenuhi. Apakah anak sudah
mampu melalui tahap prediksi, observasi dan penjelasan.
Tahap analisis data :
1. Analisis data tertulis responden.
Analisis data dimulai dari proses pengelompokan kasar jawaban anak
berdasarkan jawaban dalam lembar kerja, pengelompokan hanya berdasar
jawaban anak. Hal ini dikarenakan jawaban anak dalam lembar kerja
berupa jawaban singkat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti
dalam lembar kerja.
2. Mengubah data wawancara menjadi narasi tertulis.
Pengolahan data wawancara dan pengamatan dimulai dengan mengubah
hasil rekaman wawancara menjadi narasi tertulis atau transkripsi. Dalam
transkrip wawancara ini akan telihat pendapat anak secara lebih jelas
bagaimana pemahaman anak tentang bumi dan peristiwa siang-malam
disertai alasan yang melatar belakangi jawaban mereka. Dari hasil
wawancara juga akan terlihat dari mana anak memperoleh informasi
pengetahuan yang mereka ungkapkan.
3. Pengelompokan data.
Tahap terakhir yaitu pengelompokan jawaban atau pengkategorian data
data berdasarkan pada jawaban tertulis anak yang kemudian diperjelas
dengan pengungkapan gagasan pada proses wawancara. Kriteria
pengkategorian bukan hanya dilihat dari benar atau salah jawaban anak
namun ditentukan juga oleh beberapa faktor antara lain sumber jawaban
anak, alasan anak mengemukakan pendapat atau jawaban.
Pengkategorian data ini dibagi dalam 4 proses yaitu:
a) Setelah data wawancara diperoleh kemudian dilihat pendapat yang
dikemukakan anak, kemudian disesuaikan dengan data tertulis hasil
pengisian lembar kerja.
b) Ditarik sebuah garis besar atau inti jawaban anak baik tertulis maupun
wawancara sebagai data responden. Untuk memperjelas keterangan
jawaban anak pada kolom data, penulis menyertakan kalimat yang
menyatakan pendapat anak (dikutip dari transkrip wawancara).
c) Peneliti mengelompokan beberapa pendapat anak yang terlihat
mengarah pada sebuah kesimpulan yang sama.
d) Setelah data dikelompokan kemudian dilihat alasan atau latar belakang
jawaban anak, apa alasan anak mengungkapkan jawabannya tersebut.
Setelah alasan anak mengemukakan jawaban diperoleh kemudian
dilihat juga dari mana anak memperoleh informasi mengenai pendapat
yang dikemukakan. Selain itu dilihat juga faktor apa sajakah yang
mempengaruhi jawaban anak, misalnya faktor agama atau anak hanya
e) Yang terakhir adalah data dikategorikan berdasarkan bagaimana
pendapat anak diperoleh, apakah melalui pemahaman konsep yang
sudah diterima dari sekolah, apakah anak belajar otodidak dari
lingkungan seperti misalnya membaca buku tanpa memahami apa yang
mereka pelajari, atau anak tidak memiliki dasar sama sekali dan hanya
mengkaitkan dengan ilmu agama yang sudah diperoleh lebih dahulu.
Menurut Boyatzis dalam (Poerwandari, 2005:152) analisis penelitian
kualitatif memerlukan kemampuan dan kompetensi tertentu:
1. Kemampuan mengenali pola (pattern recognition) yaitu kemampuan
melihat pola-pola dalam informasi yang terkesan acak dan tidak beraturan.
Untuk memungkinkan hal ini, peneliti harus memiliki keterbukaan dan
keluwesan konseptual.
2. Kemampuan melakukan perencanaan dan penyusunan sistem terhadap
data (planning and systems thinking) yakni hal yang memungkinkan
peneliti mengorganisasi pengamatannya dan mengidentifikasi pola-pola
menjadi sistem yang dapat digunakan untuk pengamatan (usable system
for observation). Suatu hal yang juga dapat digunakan oleh peneliti lain,
atau dapat digunakan oleh peneliti yang sama dalam kesempatan berbeda.
3. Pengetahuan mengenai hal-hal relevan dengan topik yang diteliti
merupakan hal yang krusial. Melakukan penelitian kualitatif mencakup
juga emosi, nilai-nilai (value-laden), prakonsepsi teoritis, pilihan-pilihan
4. Hal yang paling mutlak dalam menggunakan analisis tematik adalah
dimilikinya kompleksitas kognitif dalam beenak peneliti. Kompleksitas
kognitif meliputi kemampuan mempersepsi sebab-sebab ganda (miltiple
causality), menemukan variabel-variabel yang berbrda sejalan dengan
waktu dan variasi lain, juga kemampuan untuk mengkonseptualisasi
sistem hubungan.
5. Hal-hal lain yang diperlukan antara lain adalah empati dan objektivitas
BAB III
DATA DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Penelitian.
Penelitian ini dilaksanakan di dua Sekolah Dasar (SD) yaitu SD Negeri
Timbulrejo, Sleman dan SD Negeri Nusawungu V Cilacap pada bulan
Oktober 2008. Responden penelitian ini adalah siswa kelas III dan VI yang
berjumlah 6 orang. Reponden diambil secara acak dari 2 sekolah berbeda,
masing-masing 2 orang siswa kelas III dan 2 orang kelas VI SD Negeri
Timbulrejo, Sleman; serta 2 orang responden kelas VI SD Nusawungu V
Cilacap. Penelitian ini dilakukan di dua tempat yang berbeda yaitu Sleman;
Yogyakarta dan Cilacap; Jawa Tengah bukan dengan maksud sebagai
perbandingan apakah dengan latar belakang budaya yang berbeda juga akan
mempengaruhi cara pandang anak terhadap sesuatu yang sering mereka
temui/alami dan notabene merupakan bagian dari pengetahuan sains.
Penelitian ini bersifat langsung, peneliti secara langsung memberikan
perlakuan-perlakuan kepada responden untuk mengetahui sejauh mana
pemahaman anak Sekolah Dasar (SD) kelas III dan VI tentang materi bumi.
Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Oktober 2008.
Pengambilan data ini dibagi menjadi dua tahap; yaitu pengisian lembar kerja
yang meliputi pertanyaan tentang bumi dan peristiwa siang-malam serta tahap
ke dua adalah wawancara untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak
tentang materi ini. Pengambilan data ini dilakukan secara langsung dalam
waktu sehari, setelah anak mengerjakan lembar kerja kemudian dilanjutkan
dengan wawancara
Gambar 1. Anak mengisi LKS Gambar 2. Wawancara
Dalam pengambilan data, peneliti tidak memberikan materi prasyarat
terlebih dahulu, karena yang ingin dilihat adalah pemahaman anak tentang
materi bumi dan pengetahuan awalnya baik itu dari sekolah maupun pengaruh
lingkungan.
Penelitian dan pengambilan data berlangsung dengan proses sebagai
berikut. Tahap pertama pengambilan data; anak hanya diminta untuk mengisi
lembar kerja yang sudah disiapkan peneliti, lembar kerja ini berisi tiga
pertanyaan yang semuanya berhubungan dengan materi bumi (lihat lampiran).
Responden boleh menuliskan apa saja dalam lembar kerja ini, bahkan jika
responden lebih nyaman dengan gambar-gambar, jawaban dilembar kerja
boleh juga dalam bentuk gambar.
Jawaban anak dalam lembar kerja masih belum cukup untuk
mengetahui pemahaman tentang materi bumi. Oleh karena itu pengambilan
data kemudian dilanjutkan dengan tahap ke dua yaitu wawancara responden.
Wawancara yang dilakukan bersifat personal dan tidak terstruktur, artinya
dengan kebutuhan/kelengkapan data. Selain itu selama pengambilan data,
responden boleh mengajukan pertanyaan kepada peneliti.
B. Data.
Pemahaman anak terhadap materi bumi diketahui melalui pengisian
lembar kerja yang dilakukan oleh anak, wawancara dan pengamatan oleh
peneliti. Berikut ini adalah rangkuman data pemahaman anak tentang materi
bumi yang diambil dari lembar kerja, hasil tanskrip wawancara dan
pengamatan.
1. Seperti apa bentuk bumi?
Responden Data responden Keterangan Kategori
S1 Bumi bulat seperti bulan
S1 belum pernah mendapat
materi tentang bumi di
Sekolah.
S1 membandingkan bentuk
bumi yang bulat dengan bulan,
karena dalam pengertian S1
bulan itu benar-benar bulat.
S3 Bumi berbentuk bulat
S3 belum pernah diajari materi
bumi Di Sekolah.
S3 berpendapat bahwa bumi
berbentuk bulat karena sudah
menjadi ciptaaan Tuhan Yang
Maha Esa dan tidak mungkin
berbentuk lain. S3
mencontohkan bentuk bumi
yang kotak akan aneh dan
tidak akan dapat berputar
Pengetahuan
awal yang
diperoleh dari
lingkungan di
(rotasi).
S2 Bumi bulat seperti bola
S2 menyimpulkan bahwa bumi
itu berbentuk bulat dari
pelajaran di Sekolah, dengan
melihat globe yang pernah
dibawa guru ketika
mengajarkan materi tentang
bumi.
S4 Bumi berbentuk bulat seperti bola
S4 hanya dapat menjawab
bumi bulat seperti bola karena
pernah diajarkan di sekolah.
S5 Bentuk bumi bulat seperti bola
Pemahaman S5 tentang bentuk
bumi diperoleh dari membaca
buku pelajaran.
S6 Bumi berbentuk bulat seperti bola
Bumi berbentuk bulat pada
dimisalkan seperti bola ping
pong oleh S6.
Pengetahuan
awal yang
diperoleh dari
sekolah
2. Alasan/bukti bahwa bumi bulat?
Responden Data responden Keterangan Kategori
S1 Karena sudah pasti
Tidak dapat menjawab
karena belum diajarkan di
S6 Globe. tahu dari pelajaran di Sekolah
S5 Dari buku
S5 mendapat
pengetahuan bahwa bumi
bulat dari buku yang
pernah dibaca, meskipun
S5 sendiri tidak tahu
alasannya.
Kalau bumi kotak tidak
bisa berputar.
3. Gambar posisi orang yang berdiri diatas permukaan bumi?
Responden Data responden Keterangan Kategori
S1
Langsung dapat
menggambar posisi orang
yang berdiri dipermukaan
bumi dengan benar saat
peneliti mengajukan
pertanyaan.
Pemahaman
S3
Gambar yang dibuat S5
benar tanpa dibantu
disisi – sisi lain pada
gambar bumi.
lain (sisi lain bumi dalam
gambar) S2
menggambarkan dengan
benar.
S4
S4 memilih salah satu
alternatif gambar yang
dicontohkan peneliti,
jawaban benar tetapi
terlihat tidak yakin dan
asal menunjuk.
S6
Harus diberikan contoh
terlebih dahulu sebelum
dapat menggambarkan
posisi orang yang berdiri
dipermukaan bumi.
Namun setelah diberi
contoh, S6 dapat dengan
cepat menangkap yang
dimaksudkan peneliti
4. Apakah semua benda jatuh ke bumi?
Responden Data responden Keterangan Kategori
S1 Semua benda jatuh ke
bumi Karena keajaiban.
Pengaruh
lingkungan dan
budaya.
S3 Tidak semua benda jatuh ke bumi
Awan dianggap sebagai
benda dan awan tidak
jatuh ke bumi.
Pengalaman
belajar.
S2 Semua benda jatuh ke
bumi Gaya gravitasi.
S4 Semua benda jatuh ke
bumi Gaya gravitasi.
S5 Semua benda jatuh ke
bumi Gaya gravitasi.
S6 Semua benda jatuh ke
bumi Gaya gravitasi.
5. Yang menyebabkan benda jatuh ke bumi?
Responden Data responden Keterangan Kategori
S1 Keajaiban dari langit
Semua benda jatuh karena
sesuatu yang sudah pasti dan
tidak dapat dijelaskan dengan
teori ilmiah.
Pengaruh
lingkungan.
S3 Tidak dipegangi
Benda dapat jatuh ke bumi kalau
tidak dipegangi.
Misalnya buah yang ada
dipohon, tidak jatuh karena ada
batang yang menahan agar buah
tidak jatuh.
Pengalaman
belajar dari
lingkungan.
S2 Gaya gravitasi
Gaya magnet yang ada di bumi
yang dapat menarik semua
benda agar tidak melayang
diatas permukaan bumi.
S4 Gaya gravitasi
Gaya yang membuat benda akan
jatuh lagi ke bumi jika dilempar
ke atas
S5 Gaya gravitasi Gaya yang menarik
S6 Gaya gravitasi Gaya gravitasi adalah tarikan menuju bumi
6. Peristiwa terjadinya siang dan malam?
Responden Data responden Keterangan Kategori
S1 Bumi yang bergerak
Tidak dapat menentukan
bumi berputar dari mana
kearah mana (arah mata
angin) maupun arah
S4 Matahari mengelilingi bumi.
Bumi berputar dari timur
ke barat karena bumi yang
bergerak, bukan matahari.
searah dari barat ke timur,
S2 tidak bisa menjawab
bagaimana arah putaran
bumi (searah putaran
jarum jam atau
berlawanan) sekalipun
sudah diberi contoh
konkret dengan jeruk yang
diumpamakan sebagai
bumi.
S3 Bumi berputar
Setelah melihat gambar
S3 menjawab arah putaran
bumi dari barat ke timur
searah putaran jarum jam.
S6 Bumi berputar pada porosnya
Bumi berputar dari timur
ke barat, namun belum
bisa menunjukkan
bagaimana arah putaran
bumi.
7. Waktu yang diperlukan bumi berotasi?
Responden Data responden Keterangan Kategori
S1 24 jam
Hanya menjawab 1 hari,
8. Saat bumi berotasi dan berevolusi apakah matahari juga ikut bergerak (rotasi/revolusi)?
Responden Data responden Keterangan Kategori
S1 Tidak. Yang bisa berputar hanya bumi.
S2 Matahari tetap diam.
Anak menganggap bahwa
S3 Matahari ikut berputar. Matahari berputar seperti
putaran bumi (rotasi) Konsep.
9. Jika ditempat tinggal sekarang malam, adakah ditempat lain yang sedang siang?
Responden Data responden Keterangan Kategori
S1 Ada.
Jika tempat tinggal S1
sekarang sedang siang,
tempat tinggal S3 dan
Arab.
Pegalaman
belajar dari
S2 Ada.
siang berarti yang sedang
malam adalah bagian
bumi sebaliknya
S6 Ada.
Mencontohkan dengan
benda yang berbentuk
bulat, bagian bumi yang
C. Hasil.
1. Kelas III
a. Seperti apakah bentuk bumi?
Meskipun kepada responden belum pernah diajarkan materi
bumi disekolah, responden dapat menjawab bentuk bumi adalah bulat.
Pada dasarnya jawaban dua anak sesuai dengan konsep yang ada pada
pelajaran sains hanya saja alasan yang dikemukakan oleh responden
tidak berdasarkan pada konsep-konsep sains. Meskipun jawaban
responden sama namun latar belakang jawaban mereka juga ternyata
sangatlah berbeda. Responden menggambarkan bentuk bumi yang
bulat dengan membandingkan bentuk bumi dan sesuatu yang pernah
mereka lihat dimana benda tersebut notabene berbentuk bulat.
S1 membandingkan bumi berbentuk bulat seperti bulan, karena
kemungkinan S1 sudah sering melihat gambaran yang lebih konkrit
tentang bentuk bulan melalui film-film anak yang ada ditelevisi
ataupun dari buku-buku cerita anak yang terkadang disisipi gambar
ilustratif. Sedangkan S3 menganggap bentuk bumi yang bulat
merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan sudah pasti.
Jawaban S3 tersebut lebih mengacu pada pelajaran agama yang sudah
pernah diperoleh anak. Bahkan anak mengungkapkan jika bentuk
bumi adalah kotak maka tidak akan dapat berputar.
Selain itu anak juga ternyata dapat menggambarkan posisi
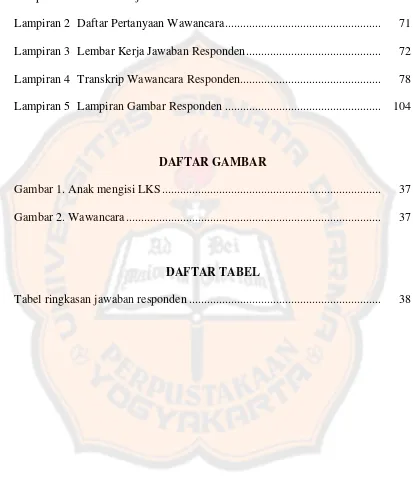
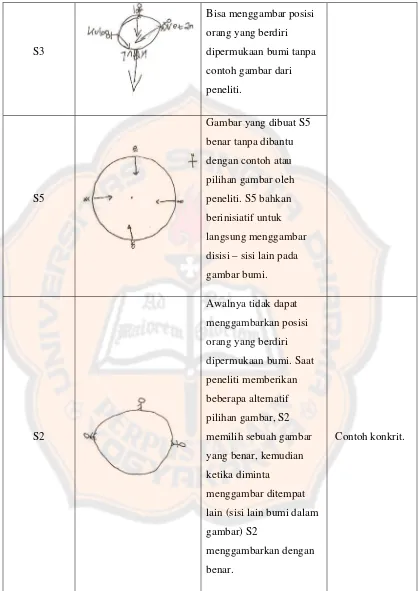
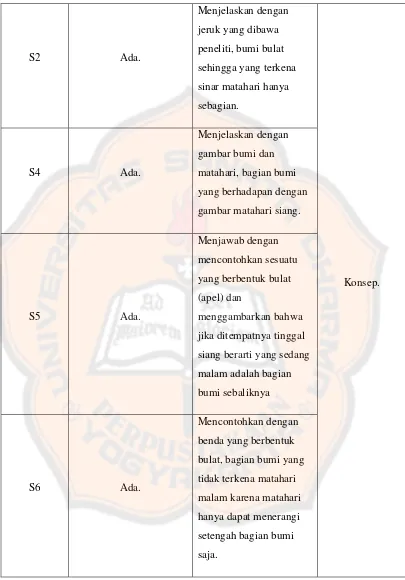
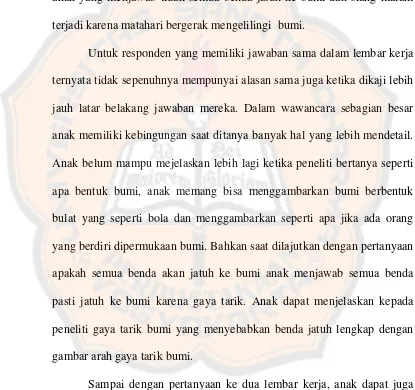
![gambar (gambar 1.1)]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/1660744.2072725/95.595.101.496.148.731/gambar-gambar.webp)
![gambar], kalau susah digambar diputar kertasnya.”](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/1660744.2072725/96.595.97.506.71.757/gambar-kalau-susah-digambar-diputar-kertasnya.webp)
![gambar bumi (gambar 2.2)]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/1660744.2072725/101.595.96.514.105.724/gambar-bumi-gambar.webp)
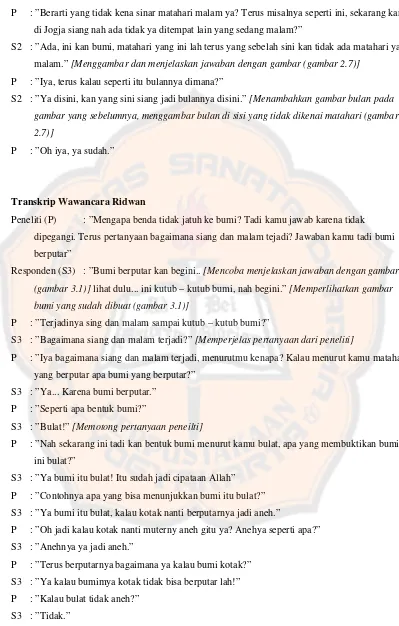
![gambar orang yang dimaksudkan tegak lurus dengan permukaan bumi (gambar 3.2)]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/1660744.2072725/105.595.100.505.97.752/gambar-orang-dimaksudkan-tegak-lurus-permukaan-bumi-gambar.webp)
![gambar (gambar 4.2)]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/1660744.2072725/110.595.100.506.101.748/gambar-gambar.webp)