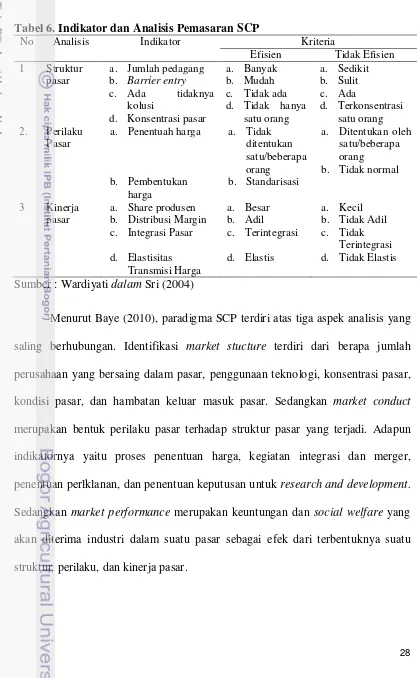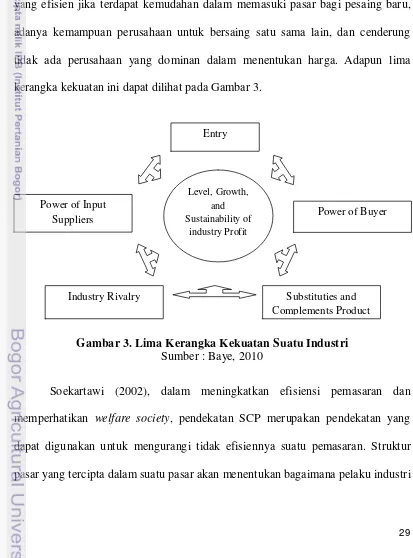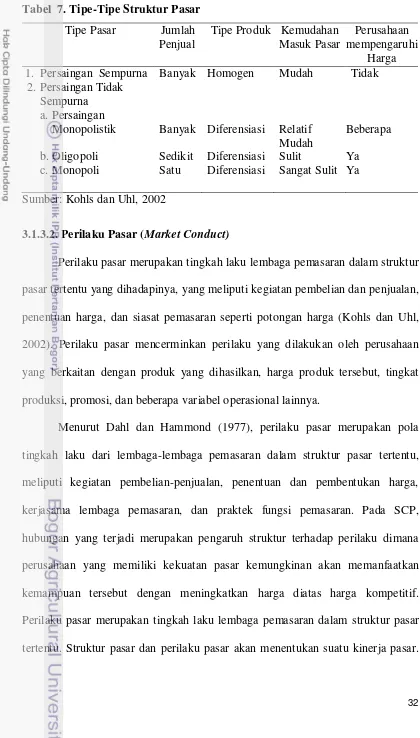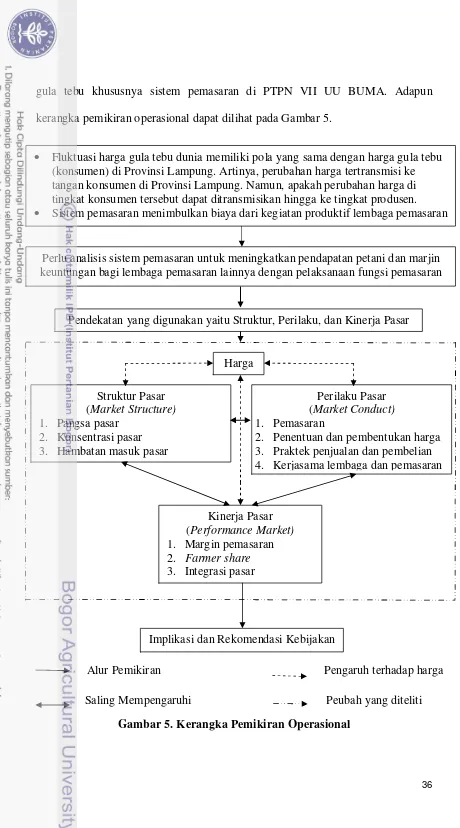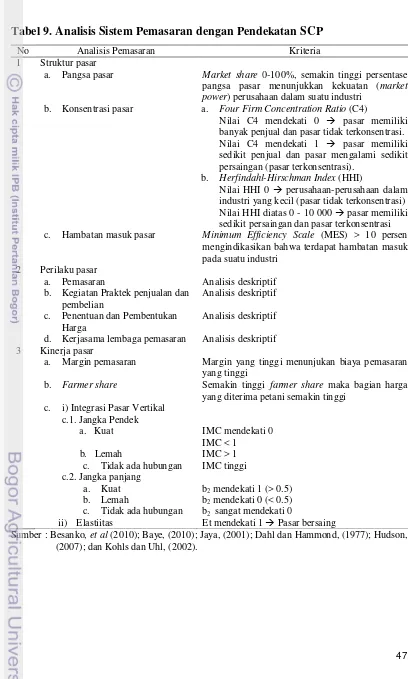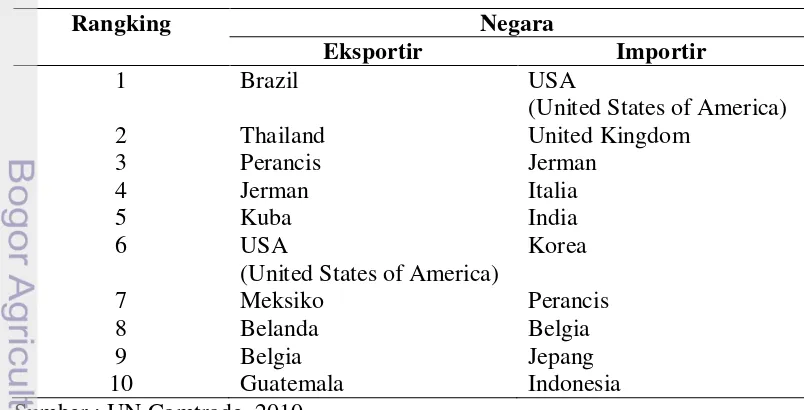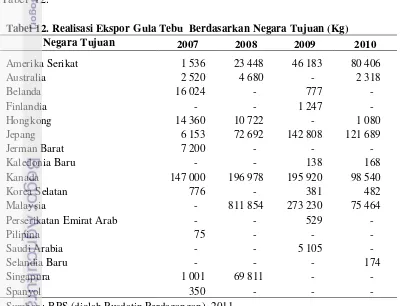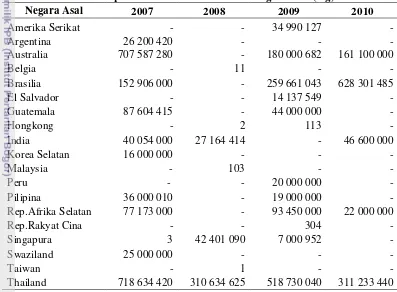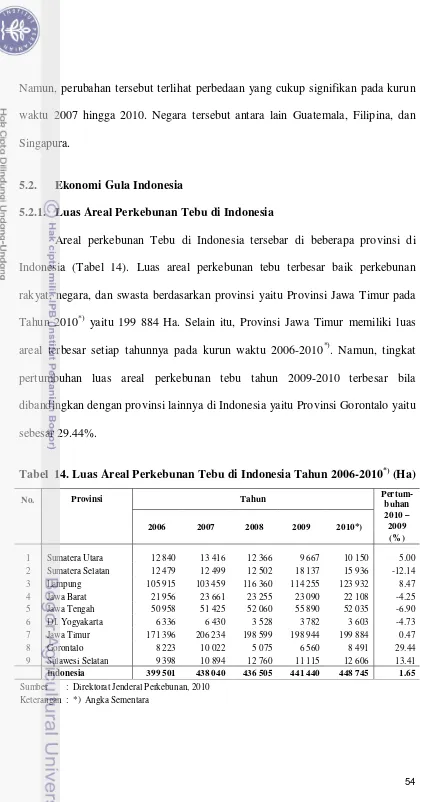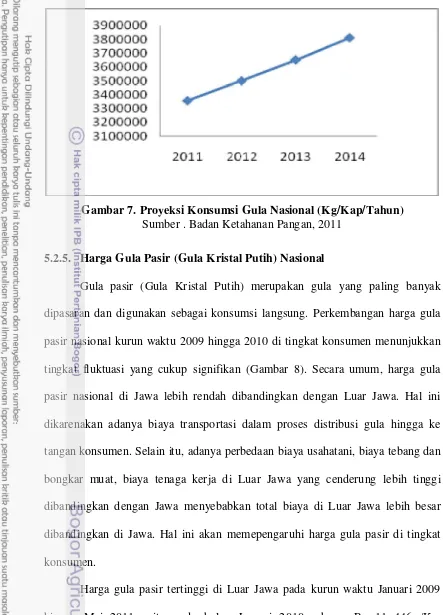SISTEM PEMASARAN GULA TEBU (CANE SUGAR)
DENGAN PENDEKATAN STRUCTURE, CONDUCT, PERFORMANCE (SCP) [Kasus : Perusahaan Perseroan (Persero)
PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bungamayang]
NIA ROSIANA
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERNYATAAN MENGENAI TESIS
DAN SUMBER INFORMASI
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Sistem Pemasaran Gula Tebu (Cane Sugar) dengan Pendekatan Structure, Conduct, Performance (SCP) [Kasus : Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bungamayang] adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis ini.
Bogor, Februari 2012
ABSTRACT
NIA ROSIANA. The Marketing System of Cane Sugar with Structure, Conduct, Performance Approach (SCP) [Case : Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bungamayang]. Under direction of RITA NURMALINA and HARMINI
Fluctuations international prices of cane sugar have an impact on the price of cane sugar in the country. One of the areas that became centers of production of cane sugar that sense changes in the international price of cane sugar Provinsi Lampung. The uncertainty of the price risk to the marketing agency involved. The general objective of this research is to analyze the marketing system of cane sugar approach to structure, conduct, performance (SCP) to the case in PTPN VII Unit Usaha Bungamayang. Research results indicate that the market structure facing the market is concentrated with a small level of competition and have barriers to entry for competitors. Market structure in Provinsi Lampung is oligopoly. Analysis of market behavior in the determination and formation of prices is still dominated by one of the marketing agencies. Market behaviour in PTPN VII UU BUMA have a marketing colution when the fixed prices by large salers. Market performance analysis shows that changes in the price of sugar cane at the consumer level is not transmitted to farmers. The results indicate that analysis of cane sugar marketing system in PTPN VII UU BUMA likely more advantages large salers than farmers. The farmers are price taker in the short run and long run.
RINGKASAN
NIA ROSIANA. Sistem Pemasaran Gula Tebu (Cane Sugar) dengan Pendekatan Structure, Conduct, Performance (SCP) [Kasus : Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bungamayang]. Dibimbing oleh RITA NURMALINA dan HARMINI.
Kebutuhan gula meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia. Namun, peningkatan konsumsi dunia tidak diimbangi dengan produksi sehingga menyebabkan defisit sebesar 9.12 juta ton di tahun 2008/2009. Produksi gula pasir nasional lebih kecil dibanding dengan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia tahun 2006-2010 yang menyebabkan kebutuhan gula nasional mengalami defisit (BKP, 2010). Menurut Dinas Perkebunan Provinsi Lampung (2010), perusahaan yang menjadi salah satu sentra penanaman tebu dengan tingkat jumlah petani yang mengusahakan tebu rakyat terbesar di Provinsi Lampung yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bungamayang (PTPN VII UU BUMA).
Adanya fluktuasi harga gula tebu internasional berdampak pada harga gula tebu di dalam negeri. Salah satu daerah yang menjadi sentra produksi gula tebu yang merasakan perubahan harga gula tebu internasional yaitu Provinsi Lampung. Fluktuasi harga gula tebu dunia memiliki pola yang sama dengan harga gula tebu di Provinsi Lampung. Fluktuasi harga gula tebu dunia yang segera direspon dengan cepat oleh Provinsi Lampung cenderung membentuk pasar yang terintegrasi dan memiliki sistem pemasaran yang efisien. Namun, perubahan harga gula tebu tersebut apakah dapat tertransmisi hingga ke tangan produsen.
Struktur pasar (market structure) yang terbentuk akan menentukan kemampuan suatu perusahaan dalam industri gula tebu di Provinsi Lampung. Hal ini akan mendorong pada kemampuan perusahaan dalam mengontrol harga gula tebu. Adanya struktur pasar yang terbentuk akan berpengaruh pada perilaku pasar (market conduct) berupa penentuan dan pembentukan harga. Fluktuasi harga akan berpengaruh pada keputusan dan kemampuan lembaga pemasaran yang terlibat dalam merespon perubahan tersebut melalui penentuan dan pembentukan harga. Namun, seberapa cepat perubahan harga tersebut dapat direspon oleh setiap lembaga pemasaran akan diketahui melalui analisis kinerja pasar (market performance). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan analisis sistem pemasaran melalui pendekatan SCP yaitu structure, conduct, performance.
BUMA memiliki market power yang rendah dalam industri gula tebu di Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan produksi gula tebu PTPN VII UU BUMA masih dibawah perusahaan lainnya.
Struktur pasar yang terbentuk akan berpengaruh pada perilaku pasar (market conduct) gula tebu PTPN VII UU BUMA. Lembaga dan praktek fungsi pemasaran yang terlibat yaitu petani-kelompok tani-koordinator, pabrik gula, pedagang besar, distributor, retail. Fungsi pemasaran yang dilakukan yaitu fungsi pertukaran, fisik, dan fasilitas. Saluran pemasaran gula tebu yang digunakan yaitu dua saluran. Saluran pertama, petani-kelompok tani-koordinator, pabrik gula, pedagang besar, distributor, retail. Saluran kedua, pekelompok tani-koordinator, pabrik gula, pedagang besar, retail. Seluruh lembaga pemasaran melakukan kegiatan penjualan gula tebu. Namun, gula milik petani dijual ke pedagang besar yang terdaftar di pabrik gula (PG) sedangkan gula milik PG dijual dengan menggunakan sistem lelang.
Harga jual gula milik petani ditentukan oleh kesepakatan petani dan pedagang besar. Namun, dalam prakteknya kegiatan pembelian gula milik petani yang dilakukan cenderung menimbulkan kolusi oleh pedagang besar yang menyebabkan penentuan harga gula petani didominasi pihak tersebut. Kemitraan yang dilakukan antara petani dan PG melalui sistem bagi hasil. Namun, kemitraan tersebut kurang menguntungkan petani karena pencairan dana hasil penjualan gula milik petani yang dikelola oleh PG memerlukan waktu relatif lama (3-5 bulan dari waktu penjualan). Kurangnya peran kelompok tani dalam kegiatan pemasaran khususnya penjualan gula petani menyebabkan bargaining power petani yang semakin lemah.
Hasil analisis kinerja pasar (market performance) gula tebu menunjukkan bahwa semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat maka semakin besar pula nilai total marjin pada suatu saluran pemasaran. Marjin pemasaran saluran pertama (petani-kelompok tani-koordinator, pabrik gula, pedagang besar, distributor, retail) lebih besar dari saluran kedua (pekelompok tani-koordinator, pabrik gula, pedagang besar, retail). Semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat maka marjin pemasaran semakin tinggi. Hal ini menyebabkan farmer share yang semakin rendah.
Analisis integrasi pasar dalam jangka pendek dan jangka panjang menunjukkan bahwa perubahan harga gula di tingkat retail (konsumen) dan distributor tidak mempengaruhi harga gula di tingkat petani. Sedangkan perubahan harga di pedagang besar mempengaruhi harga di petani meskipun memiliki integrasi yang lemah. Sedangkan pada jangka panjang, perubahan harga gula di tingkat petani sangat dipengaruhi oleh harga gula di tingkat pedagang besar. Analisis elastisitas menunjukkan bahwa lembaga yang paling cepat merespon perubahan harga konsumen adalah distributor dan pedagang besar. Hasil menunjukkan bahwa analisis sistem pemasaran gula tebu di PTPN VII UU BUMA cenderung menguntungkan pedagang besar dibandingkan petani. Petani cenderung sebagai penerima harga (price taker) baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan analisis SCP, sistem pemasaran gula tebu di PTPN VII UU BUMA cenderung tidak efisien.
© Hak Cipta milik IPB, tahun 2008 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB
SISTEM PEMASARAN GULA TEBU (SUGAR CANE)
DENGAN PENDEKATAN STRUCTURE, CONDUCT, PERFORMANCE (SCP)
[Kasus : Perusahaan Perseroan (Persero)
PT.Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bungamayang]
NIA ROSIANA
Tesis
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada
Program Studi Agribisnis
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Judul Tesis : Sistem Pemasaran Gula Tebu (Cane Sugar)
dengan Pendekatan Structure, Conduct, Performance (SCP) [Kasus: Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bungamayang]
Nama : Nia Rosiana
NIM : H451100021
Disetujui,
Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Ir. Rita Nurmalina, MS Ir. Harmini, M.Si Ketua Anggota
Diketahui,
Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Magister Sains Agribisnis
Prof. Dr. Ir. Rita Nurmalina, MS Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr
Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis: Dr. Ir. Ratna Winandi, MS
(Dosen Magister Sains Agribisnis, Institut Pertanian Bogor)
Penguji Wakil Program Studi Agribisnis: Dr. Ir. Suharno, MADev
(Sekretaris Program Studi Magister Sains Agribisnis, Sekolah Pascasarjana
PRAKATA
Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
penelitian tesis yang berjudul “Sistem Pemasaran Gula Tebu (Cane Sugar) dengan
Pendekatan Structure, Conduct, Performance (SCP) [Kasus: Perusahaan
Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bungamayang]”.
Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister
Sains pada Program Studi Agribisnis.
Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sistem pemasaran gula
dengan pendekatan structure, conduct, dan performance. Penelitian ini diharapkan
dapat memberikan alternatif kebijakan bagi lembaga terkait untuk membantu
petani dalam upaya peningkatan pendapatan dan memberikan keuntungan bagi
setiap lembaga pemasaran sesuai dengan pelaksanaan fungsi pemasaran.
Pentingnya jaminan kepastian harga gula tebu dapat menjadi stimulus bagi petani
untuk tetap melakukan kegiatan budidaya dan pengolahan tebu guna membantu
pemenuhan kebutuhan konsumsi gula nasional.
Penulis mengucapkan terima kasih pada Tim Peneliti Gula pada Penelitian
Unggulan Departemen (PUD) Agribisnis 2011 yang berjudul “Analisis Transmisi
Harga dalam Supply Chain Gula Tebu”. Tesis ini merupakan bagian dari
penelitian tersebut. Selain itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak
terhingga kepada:
1. Prof. Dr. Ir. Rita Nurmalina, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Ketua
Program Studi yang telah memberikan bimbingan, saran, dan kritik pada
kasih atas diberikannya kesempatan baik bantuan moril dan spriritual untuk
melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi guna kemajuan penulis.
2. Ir. Harmini, M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah
memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi bagi penulis pada proses
penelitian hingga penulisan tesis. Selain itu, terima kasih atas ilmu yang
diberikan selama penulis menyelesaikan studi di Magister Sains Agribisnis.
3. Dr. Ir. Ratna Winandi, MS selaku Penguji Luar Komisi yang telah
memberikan bimbingan dan arahan bagi perbaikan tesis ini.
4. Dr. Ir. Suharno, MADev selaku Penguji Wakil Program Studi Magister
Agribisnis yang telah memberikan masukan bagi perbaikan tesis.
5. Bpk. Syukur Kepala Bagian Tanaman, Perusahaan Perseroan (Persero)
PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bunga Mayang yang telah
memberikan izin dalam melakukan penelitian di perusahaan tersebut.
6. Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS dan Ir. Dwi Rachmina, M.Si selaku Ketua dan
Sekretaris Departemen Agribisnis yang telah memberikan bimbingan dalam
proses pembelajaran selama penulis kuliah di Magister Sains Agribisnis.
7. Tim Penelitian Unggulan Departemen 2011 (Tim Gula): Prof. Dr. Ir. Rita
Nurmalina, MS; Dr. Ir. Ratna Winandi, MS; Amzul Rifin, PhD; Ir. Harmini,
MSi; Suprehatin, SP.M.Agribuss; Feryanto, SP. M.Si; Khoirul Aziz, SE;
Maryono, SP. M.Sc; Triana Gita D, SE; Fitria Dieni Afifah; dan Mahardi
Safarudin atas kerjasama dalam penelitian gula di Provinsi Lampung.
8. Tintin Sarianti, SP, M.Si yang telah memberikan motivasi dan dukungan
9. Seluruh Dosen Magister Sains Agribisnis yang telah memberikan ilmu selama
penulis menyelesaikan studi. Selain itu, terima kasih kepada Staf Magister
Sains Agribisnis dan Departemen Agribisnis yang telah memberikan
kelancaran administrasi selama menyelesaikan studi.
10.Teman-teman Magister Sains Agribisnis (MSA) Angkatan I (2010) yang telah
memberikan masukan bagi perbaikan penelitian penulis
11.Penghargaan yang tinggi penulis sampaikan kepada orang tua tercinta
Bpk.Tato Sumarto dan Ibu Tati Sunarti yang telah memberikan doa tulus tiada
henti untuk keberhasilan putra putrinya dalam menuntut ilmu. Ucapan terima
kasih atas doa dan dukungannya kepada Ibu Mertua (Ibu Sabariah Saragih dan
Ibu Mimah). Terima kasih doa dan dukungannya untuk saudara kandungku
Dian Kusumasari, A.Md dan Arief Prasetyo serta kakak ipar Kurniawan
Febrianto, SH.
12.Ucapan terima kasih yang khusus disampaikan kepada suami tercinta
sekaligus calon ayah Feryanto, SP. M.Si, yang telah menjadi motivator untuk
menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas bantuan, doa, kasih sayang,
kesabaran, dan pengertiannya selama penulis menyelesaikan penelitian.
13.Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses
penyelesaian penelitian ini.
Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi
stakeholders yang memerlukan.
Bogor, Februari 2012
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Garut pada tanggal 3 September 1986 dari ayah Tato
Sumarto dan ibu Tati Sunarti. Penulis merupakan putri kedua dari tiga bersaudara.
Tahun 2004 penulis lulus dari SMU Negeri 1 Garut dan pada tahun yang
sama lulus seleksi masuk IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB
(USMI). Penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Manajemen
Agribisnis, Fakultas Pertanian. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang master
pada Program Magister Sains Agribisnis (MSA), Sekolah Pascasarjana, Institut
Pertanian Bogor pada Tahun 2010.
Penulis bekerja sebagai Asisten Dosen di Departemen Agribisnis, Fakultas
Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor sejak Tahun 2007 hingga
sekarang. Selain itu, penulis menjadi dosen tidak tetap di Direktorat Program
Diploma, Institut Pertanian Bogor sejak Tahun 2009 hingga sekarang. Penulis
juga sering melakukan penelitian yang berkaitan dengan ilmu Agribisnis bersama
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ... i
DAFTAR TABEL ... v
DAFTAR GAMBAR... vii
DAFTAR LAMPIRAN ... viii
I. PENDAHULUAN ... 1
1.1. Latar Belakang ... 1
1.2. Perumusan Masalah... 7
1.3. Tujuan Penelitian ... 10
1.4. Manfaat Penelitian ... 10
1.5. Ruang Lingkup Penelitian ... 11
II. TINJAUAN PUSTAKA ... 13
2.1. Sistem Pemasaran Gula ... 13
2.3. Penerapan SCP (Market Structure, Market Conduct, Market Performance) dalam Analisis Pemasaran ... 15
III. KERANGKA PEMIKIRAN ... 21
3.1. Kerangka Pemikiran Konseptual ... 21
3.1.1. Konsep Pemasaran ... 21
3.1.2. Konsep Efisiensi Pemasaran ... 24
3.1.3. Konsep SCP (Market Structure, Market Conduct, Market Performance) ... 27
3.1.3.1. Struktur Pasar (Market Structure) ... 30
3.1.3.2. Perilaku Pasar (Market Conduct) ... 32
ii
3.2. Kerangka Pemikiran Operasional... 34
IV. METODE PENELITIAN ... 37
4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 37
4.2. Sumber dan Jenis Data ... 37
4.3. Metode Pengambilan Sampel ... 37
4.4. Teknik Pengolahan dan Metode Analisis Data ... 38
4.4.1. Analisis Struktur Pasar ... 38
4.4.1.1. Pangsa Pasar... 38
4.4.1.2. Konsentrasi Pasar ... 40
4.4.1.3. Hambatan Masuk Pasar ... 42
4.4.2. Analisis Perilaku Pasar ... 42
4.4.3. Analisis Kinerja Pasar ... 43
4.4.3.1. Margin Pemasaran ... 43
4.4.3.2. Farmer Share ... 44
4.4.3.3. Analisis Integrasi Pasar Vertikal ... 44
V. EKONOMI GULA ... 49
5.1. Ekonomi Gula Dunia ... 49
5.1.1. Produksi dan Konsumsi Gula Dunia ... 49
5.1.2. Harga Gula Pasir Dunia ... 49
5.1.3. Eksportir dan Importir Gula ... 50
5.1.4. Realisasi Ekspor Gula Tebu Berdasarkan Negara Tujuan... 52
5.1.5. Realisasi Impor Gula Tebu Berdasarkan Negara Asal ... 53
5.2. Ekonomi Gula Indonesia ... 54
iii
5.2.2. Produksi Tebu di Indonesia ... 55
5.2.3. Produktivitas Tebu di Indonesia ... 56
5.2.4. Perkembangan Produksi dan Konsumsi Gula di Indonesia ... 56
5.2.5. Harga Gula Pasir (Gula Kristal Putih) Nasional ... 58
5.3. Ekonomi Gula Provinsi Lampung... 59
VI. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 63
6.1. Analisis Struktur Pasar (Market Structure) ... 63
6.1.1. Pangsa Pasar ... 63
6.1.1.1. Pangsa pasar PTPN VII UU BUMA terhadap Nasional ... 63
6.1.1.2. Pangsa Pasar Perusahaan Gula di Provinsi Lampung terhadap Provinsi Lampung ... 65
6.1.2. Konsentrasi Pasar ... 67
6.1.3. Hambatan Masuk Pasar ... 70
6.2. Analisis Perilaku Pasar (Market Conduct) ... 72
6.2.1. Pemasaran Gula Tebu... 72
6.2.1.1. Lembaga dan Praktek Fungsi Pemasaran ... 72
6.2.1.2. Analisis Saluran Pemasaran Gula Tebu ... 86
6.2.2. Kegiatan Praktek Penjualan dan Pembelian ... 88
6.2.3. Penentuan dan Pembentukan Harga ... 93
6.2.4. Kerjasama Lembaga Pemasaran ... 96
6.3. Analisis Kinerja Pasar (Market Performance)... 100
6.3.1. Marjin Pemasaran ... 100
6.3.2. Farmer Share ... 104
iv
6.3.3.1. Integrasi Jangka Pendek ... 107
6.3.3.2. Integrasi Jangka Panjang ... 108
6.3.3.3. Elastisitas ... 109
6.4. Implikasi Hasil Analisis Sistem Pemasaran Gula Tebu ... 112
VII. KESIMPULAN DAN SARAN ... 119
7.1. Kesimpulan ... 119
7.2. Saran ... 121
DAFTAR PUSTAKA ... 123
v
DAFTAR TABEL
Nomor Halaman
1. Neraca Gula Dunia Tahun 2006-2010* (Juta Ton) ... 2
2. Produksi dan Konsumsi Gula Pasir Nasional Tahun 2006-2010 (Ton)... 3
3. Proyeksi Permintaan dan Penawaran Gula Indonesia ... 3
4. Lokasi Perkebunan Tebu di Provinsi Lampung Tahun 2009 ... 4
5. Luas Areal Tebu, Produksi Tebu, dan Produksi Gula Tebu PTPN VII UU BUMA Tahun 2007-2010... 5
6. Indikator dan Analisis Pemasaran SCP ... 28
7. Tipe-Tipe Struktur Pasar ... 32
8. Syarat Suatu Pasar Terintegrasi/TIdak ... 46
9. Analisis Pemasaran dengan Pendekatan SCP... 47
10.Produksi dan Konsumsi Gula Dunia (Thousand tones, raw value) ... 49
11.Rangking Negara Pengekspor dan Pengimpor Gula Dunia ... 51
12.Realisasi Ekspor Gula Tebu Berdasarkan Negara Tujuan (Kg) ... 52
13.Realisasi Impor Gula Tebu Berdasarkan Negara Asal (Kg) ... 53
14.Luas Areal Perkebunan Tebu di Indonesia Tahun 2006-2010*) (Ha) ... 54
15.Produksi Tebu di Indonesia Tahun 2006-2010*) (Ton) ... 55
16.Produktivitas Tebu di Indonesia Tahun 2006-2010*) (Kg/Ha) ... 56
17.Perkembangan Produksi dan Konsumsi Gula Indonesia Tahun 2005-2010 (Ton) ... 57
vi
19.Realisasi Kegiatan Akselerasi Peningkatan Produksi Gula di
Provinsi Lampung TA 2008-2011 melalui Perluasan Areal Tebu... 61
20.Perkembangan Pergulaan PTPN VII UU BUngamayang ... 61
21.Perkembangan Tebu Rakyat di PTPN VII UU Bungamayang ... 62
22.Perdagangan Gula di Provinsi Lampung dan Antar Pulau Tahun 2010 (Ton) ... 66
23.Pangsa Pasar Gula Tebu Perusahaan Gula di terhadap Provinsi Lampung tahun 2010 (%) ... 67
24.Produksi Gula Propinsi Lampung Tahun 2008-2009 (Ton) ... 68
25.Konsentrasi Rasio Empat Perusahaan Terbesar di Provinsi Lampung Tahun 2010 (%) ... 69
26.Herfindahl-Hirschman Index (HHI) Industri Gula di lampung Tahun 2010 ... 70
27.Skala Efisiensi Maksimum (MES) Industri Gula di Provinsi Lampung Tahun 2006-2010 (%) ... 71
28.Fungsi-Fungsi Pemasaran pada Setiap Lembaga Pemasaran Gula Tebu ... 85
29.Kegiatan Penjualan dan Pembelian Gula Setiap Lembaga Pemasaran ... 93
30.Hak Kewajiban... 97
31.Marjin pemasaran ... 103
32.Indeks Integrasi Pasar Gula pada Jangka Pendek ... 108
33.Indeks Integrasi Pasar Gula pada Jangka Panjang ... 109
34.Elastisitas Transmisi Harga Gula ... 110
35.Hasil Analisis Integrasi Pasar Vertikal ... 111
vii
DAFTAR GAMBAR
Nomor Halaman
1. Harga Gula Tebu (Cane Sugar) Dunia dan Provinsi Lampung
Tahun 2009-2010 ... 6
2. Rantai Pemasaran Gula Nasional ... 8
3. Lima Kerangka Kekuatan Suatu Industri ... 29
4. Hubungan Market Structure, Market Conduct, and Market Performance ... 30
5. Kerangka Pemikiran Operasional ... 36
6. Harga Gula Pasir Dunia (Rp/Kg) ... 50
7. Proyeksi Konsumsi Gula Nasional (Kg/Kap/Tahun) ... 58
8. Perkembangan Harga Gula Pasir Nasional Januari 2009- Mei 2011 ... 59
9. Pangsa Pasar PTPN VII UU BUMA Terhadap Produksi Gula Nasional Tahun 2006-2010 ... 65
10.Alur Produksi Gula PTPN VII UU BUMA... 76
11.Gula PTPN VII UU BUMA ... 82
12.Saluran Pemasaran Gula Tebu PTPN VII UU BUMA ... 87
13.Efek Perbedaan Saluran Pemasaran Gula di PTPN VII UU BUMA ... 106
viii
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Halaman
1
I.
PENDAHULUAN
1.1.
Latar BelakangBerdasarkan UU No 7 Tahun 1996 tentang pangan, ketahanan pangan
merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan yang tercermin dari
tersedianya pangan secara cukup baik dari jumlah maupun mutunya, aman,
merata, dan terjangkau. Perwujudan ketahanan pangan yang mantap dan
berkesinambungan dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu
(1) ketersediaan pangan yang cukup dan merata, (2) distribusi pangan yang efektif
dan efisien, serta (3) konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang
(BKP, 2010).
Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) yang
dicanangkan Presiden RI 11 Juni 2005 menyatakan bahwa Indonesia perlu
membangun ketahanan pangan yang mantap dengan memfokuskan pada
peningkatan kapasitas produksi nasional untuk lima komoditas pangan strategis
yaitu padi, jagung, tebu, kedelai, dan daging sapi.
Salah satu komoditas pangan strategis nasional yang termasuk dalam
program RPPK yaitu tebu. Tebu merupakan salah satu komoditas perkebunan
yang ditanam untuk bahan baku utama gula. Gula terdiri dari beberapa jenis yang
dilihat dari tingkat keputihannya melalui standar ICUMSA (International
Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis) yaitu raw sugar, refined
sugar, dan plantation white sugar (KPPU, 2010).
Tebu yang diolah menjadi gula merupakan salah satu kebutuhan
2
2010). Kebutuhan gula akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah
penduduk dunia. Konsumsi gula dunia tahun 2006 hingga 2010 mengalami
peningkatan setiap tahunnya (Tabel 1). Namun, peningkatan konsumsi dunia tidak
diimbangi dengan produksi sehingga menyebabkan defisit sebesar 9.12 juta ton di
tahun 2008/2009. Defisit produksi gula tahun 2009 diperkirakan terjadi pula tahun
2010. Kontribusi defisit terbesar akibat turunnya produksi gula India dari tahun
2008 sebesar 26.81 ton pada tahun 2009 menjadi hanya sebesar 15.86 ton serta
merubah posisi India dari pengekspor menjadi pengimpor (Dewan Gula
Indonesia, 2009).
Tabel 1 . Neraca Gula Dunia Tahun 2006-2010* (Juta Ton)
No Uraian 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010*
1 Produksi 160.21 162.30 147.92 153.07
2 Konsumsi 147.92 154.18 157.04 158.00
3 Surplus/Defisit 12.29 8.12 -9.12 -5.23
4 Stok Akhir 35.36 43.48 34.36 29.13
5 Rasio Stok
(Konsumsi dalam %)
0.24 0.28 0.22 0.18
Sumber : World Sugar Report dalam Dewan Gula Indonesia (2009) Keterangan : (*), Angka Ramalan
Produksi Gula Kristal Putih (GKP)/gula pasir dalam negeri mengalami
peningkatan selama kurun waktu 2006 hingga 2008 (Tabel 2). Namun, tahun 2009
mengalami penurunan akibat adanya penurunan produksi tebu nasional
(Ditjenbun, 2010). Secara umum, produksi gula pasir nasional lebih kecil
dibanding dengan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang menyebabkan
kebutuhan gula nasional mengalami defisit. Hal ini cenderung membukanya
3 Tabel 2. Produksi dan Konsumsi Gula Pasir Nasional
Tahun 2006-2010 (Ton)
Tahun Produksi Konsumsi Surplus/Defisit
2006 2 307 027 2 664 610 -357 583
2007 2 448 143 2 698 859 -250 716
2008 2 580 088 2 733 349 -153 261
2009 2 299 504 2 767 592 -468 088
2010 2 290 117 2 801 729 -511 612
Sumber : Badan Ketahanan Pangan, 2010
Meskipun tahun 2010 masih mengalami defisit GKP, namun pemerintah
menargetkan swasembada gula dapat tercapai tahun 2014 (Ditjenbun, 2011).
Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan gula nasional
melalui peningkatan industri gula berbasis tebu yaitu adanya revitalisasi kebun
dan pabrik gula yang tersebar dibeberapa wilayah Indonesia. Hal ini diikuti
dengan adanya peningkatan luas areal, produksi, dan produktivitas tebu di
Indonesia pada tahun 2010 (Ditjenbun, 2010).
Pencapaian target swasembada gula dimaksudkan agar produksi gula
nasional dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Tahun 2011 dan 2012
diproyeksikan produksi gula dalam negeri akan mampu memenuhi permintaan
dalam negeri. Diproyeksikan pula tahun 2011 mengalami surplus gula yang
menjadi pendorong tercapainya target swasembada gula tahun 2014. Proyeksi
permintaan dan penawaran gula dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Proyeksi Permintaan dan Penawaran Gula Indonesia
Tahun Penawaran(Ton) Permintaan (Ton) Surplus
2011 3 021 158 2 219 425 801 733
2012 3 102 584 2 256 651 845 933
4
Provinsi Lampung merupakan salah satu sentra penghasil tebu yang
berkontribusi dalam produksi tebu nasional tahun 2010 sebesar 37.8% (Ditjenbun,
2010). Provinsi Lampung memiliki tingkat produktivitas tebu terbesar di
Indonesia pada Tahun 2010 yaitu 8 211 ton/ha meskipun luas areal dan tingkat
produksi lebih kecil dari Provinsi Jawa Timur (Ditjenbun, 2010). Hal ini
dikarenakan tingkat produktivitas tebu di suatu tempat ditentukan oleh beberapa
faktor seperti penyediaan benih unggul, varietas yang tahan penyakit hangus daun,
sarana irigasi yang memadai, dan agroklimat yang mendukung.
Pengembangan tebu di Provinsi Lampung salah satunya dimaksudkan
untuk meningkatkan peran Provinsi Lampung sebagai pemasok gula terbesar
nasional melalui pelaksanaan kemitraan petani tebu sekitar wilayah pabrik gula
baik perusahaan negara maupun swasta (Disbun Provinsi Lampung, 2011).
Perusahaan perkebunan tebu negara maupun swasta di Provinsi Lampung tersebar
di empat lokasi yaitu Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan
Way Kanan (Tabel 4).
Tabel 4. Lokasi Perkebunan Tebu di Provinsi Lampung Tahun 2009
No Lokasi Perusahaan Luas Areal
(Ton)
Produksi (Ton) 1 Lampung Utara PTPN VII UU Bunga Mayang 14 243 73 908 2 Lampung Tengah Gunung Madu Plantations 26 958 201 216 Gula Putih Mataram 22 235 152 357 3 Tulang Bawang Sweet Indo Lampung 21 861 129 052 Indo Lampung Perkasa 18 177 129 052 4 Way Kanan Pemuka Sakti Manis Indah 7 000 40 000 Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, 2011
Menurut Dinas Perkebunan Provinsi Lampung (2010), perusahaan yang
menjadi salah satu sentra penanaman tebu dengan tingkat jumlah petani yang
5
Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bungamayang
(PTPN VII UU BUMA). Namun, tahun 2007 hingga 2010 luas areal penanaman
tebu dan produksi tebu PTPN VII UU BUMA menurun dan berakibat pada
penurunan hasil gula tebu (Tabel 5). Hal ini dikarenakan banyaknya petani yang
beralih menanam singkong karena biaya produksi yang relatif lebih murah dan
harga yang cenderung tidak berfluktuatif. Hal ini akan berpengaruh pada
keuntungan yang diperoleh. Namun, tingkat rendemen di PTPN VII UU BUMA
tahun 2010 menunjukkan nilai tertinggi selama kurun waktu 2007 hingga 2010.
Hal ini dikarenakan PTPN VII UU BUMA menggunakan bibit varietas unggul
dan sarana irigasi yang terus diperbaiki setiap tahun.
Tabel 5. Luas Areal Tebu, Produksi Tebu, dan Produksi Gula Tebu PTPN VII UU BUMA Tahun 2007-2010
Keterangan Tahun
2007 2008 2009 2010
Real 2006 Real 2007 Real 2008 Real 2009
Luas (Ha) 20 394 20 320 18 956 14 243
Tebu (Ton) 1 362 393 1 356 226 1 330 688 950 378
Rendemen (%) 7.72 7.25 7.35 7.78
Hasil olah gula (Ton) 105 433 98 590 98 000 74 103 Sumber : PTPN VII UU BUMA, 2011
Fluktuasi harga gula tebu yang cenderung berfluktuasi disebabkan adanya
perubahan penawaran-permintaan dalam negeri dan harga gula tebu dunia. Harga
gula tebu dunia cenderung berfluktuatif pada bulan Januari 2009 hingga Juli 2010
(Gambar 1). Harga tertinggi berada pada Bulan Januari 2010. Harga gula
internasional yang tinggi disebabkan penurunan produksi gula di beberapa negara
produsen akibat adanya perubahan iklim (P3GI, 2010). Implikasi peningkatan
harga gula tebu internasional berpengaruh pada harga gula tebu dalam negeri
6
gula tebu di Provinsi Lampung memiliki pola yang sama dengan harga gula tebu
dunia. Artinya, perubahan harga gula dunia tertransmisi hingga ke Provinsi
Lampung. Maka, pasar gula dunia dan Provinsi Lampung merupakan pasar yang
terintegrasi. Hal ini dikarenakan harga domestik mengikuti perkembangan harga
dunia. Harga tertinggi di Provinsi Lampung pun sama dengan harga dunia yaitu
pada Bulan Januari 2010.
Gambar 1. Harga Gula Tebu (Cane Sugar) Dunia dan Provinsi Lampung Tahun 2009-2010
Sumber. Ditjenbun, 2010 dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Unit Kerja Ketahanan Pangan Provinsi, 2011
Fluktuasi harga gula tebu dunia berdampak pada perubahan harga gula
tebu tingkat konsumen di Provinsi Lampung. Namun, perubahan harga tersebut
apakah tertrasmisi hingga ke tingkat produsen. Struktur dan perilaku akan
mempengaruhi penentuan dan pembentukan harga dan pada akhirnya akan
menentukan kinerja pasar dari perubahan harga tersebut. Struktur pasar yang
dianalisis yaitu pangsa pasar, konsentrasi pasar, dan hambatan masuk pasar. Jika
perusahaan memiliki pangsa pasar yang tinggi dalam suatu industri maka
perusahaan memiliki kemampuan untuk menentukan harga di pasar. Struktur
7
pasar yang terbentuk akan berpengaruh pada perilaku dan kinerja suatu
perusahaan dalam suatu industri. Analisis perilaku pasar (tingkah laku lembaga
pemasaran) seperti pemasaran, kegiatan praktek penjualan-pembelian, penentuan
dan pembentukan harga, dan kerjasama lembaga pemasaran. Akibat dari struktur
dan perilaku pasar yang ada, maka akan menentukan kinerja suatu pasar seperti
perubahan harga di tingkat konsumen apakah akan ditransmisikan ke tingkat
produsen. Selain itu, adanya lembaga-lembaga pemasaran gula tebu akan
menimbulkan margin pemasaran yang menunjukkan keuntungan yang diterima
setiap lembaga pemasaran termasuk menentukan bagian harga yang diterima
petani (farmer share).
1.2. Perumusan Masalah
Gula merupakan salah satu kebutuhan pokok yang menjadi nilai strategis
bagi ketahanan pangan. Hal ini menyebabkan ditetapkannya gula sebagai Barang
Dalam Pengawasan (Departemen Perdagangan, 2009). Terdapat berbagai macam
gula namun yang banyak dikonsumsi oleh masayarakat yaitu gula berbahan dasar
tebu atau yang biasa disebut gula pasir/gula tebu. Gambar 2 merupakan rantai
pemasaran gula nasional. Adanya pemasaran gula tersebut memungkinkan gula
dari produsen dibeli oleh distributor/pedagang besar di tempat yang berbeda
melalui perantara Bulog (badan Urusan Logistik) provinsi setempat dengan syarat
minimal pembelian sebesar 100 ton. Pemasaran tersebut mengakibatkan harga
gula ditentukan oleh harga pasar tanpa intervensi dari pemerintah dengan
penetapan harga awal ditentukan oleh pihak produsen dengan mempertimbangkan
harga gula internasional dan domestik. Harga jual yang ditetapkan pabrik belum
8
pedagang besar meliputi biaya pembelian dan biaya transportasi. Selanjutnya
pedagang besar akan menjual ke retailer hingga gula sampai ke tangan konsumen.
Alur Informasi
Alur Barang
Gambar 2. Rantai Pemasaran Gula Nasional
Sumber : Bank Indonesia, 2009
PTPN VII UU BUMA merupakan perusahaan perkebunan rakyat yang
menjadi bagian dari rantai pemasaran gula nasional. Sistem pemasaran gula tebu
dari tangan produsen ke tangan konsumen melibatkan lembaga-lembaga
pemasaran. Sistem pemasaran menimbulkan biaya akibat dari kegiatan yang
produktif tersebut (Downey et al, 1981). Saluran pemasaran akan menentukan
besarnya biaya pemasaran yang harus dilalui oleh lembaga pemasaran sebelum
sampai ke tangan konsumen. Selain itu, saluran pemasaran akan menentukan
bagian harga yang diterima produsen dalam hal ini petani tebu.
Adanya fluktuasi harga gula tebu internasional berdampak pada harga gula
tebu di dalam negeri. Salah satu daerah yang menjadi sentra produksi gula tebu
yang merasakan perubahan harga gula tebu internasional yaitu Provinsi Lampung.
Berdasarkan Gambar 1 bahwa fluktuasi harga gula tebu dunia memiliki pola yang
9
sama dengan harga gula tebu di Provinsi Lampung. Fluktuasi harga gula tebu
dunia yang segera direspon dengan cepat oleh Provinsi Lampung cenderung
membentuk pasar yang terintegrasi dan memiliki sistem pemasaran yang efisien.
Namun, perubahan harga gula tebu tersebut apakah dapat tertransmisi hingga ke
tangan produsen.
Analisis sistem pemasaran dilakukan untuk mengetahui efisiensi suatu
pasar. Struktur pasar (market structure) yang terbentuk akan menentukan
kemampuan suatu perusahaan dalam industri gula tebu di Provinsi Lampung. Hal
ini akan mendorong pada kemampuan perusahaan dalam mengontrol harga gula
tebu. Adanya struktur pasar yang terbentuk akan berpengaruh pada perilaku pasar
(market conduct) berupa penentuan dan pembentukan harga. Fluktuasi harga akan
berpengaruh pada keputusan dan kemampuan lembaga pemasaran yang terlibat
dalam merespon perubahan tersebut melalui penentuan dan pembentukan harga.
Namun, seberapa cepat perubahan harga tersebut dapat direspon oleh setiap
lembaga pemasaran akan diketahui melalui analisis kinerja pasar (market
performance).
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan analisis sistem
pemasaran yang menyeluruh melalui pendekatan market structure (struktur
pasar), market conduct (perilaku pasar), dan market performance (kinerja pasar).
Adapun permasalahan yang dikaji pada penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana struktur pasar industri gula tebu di Provinsi Lampung dan
kaitannya dengan PTPN VII UU BUMA?
2. Bagaimana perilaku pasar gula tebu PTPN VII UU BUMA?
10 1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan
umum dan khusus. Adapun tujuan tersebut yaitu :
- Tujuan umum :
Menganalisis sistem pemasaran gula tebu (Cane Sugar) dengan pendekatan
structure, conduct, performance (SCP) dengan kasus di PTPN VII UU BUMA.
- Tujuan Khusus :
1. Menganalisis struktur pasar industri gula tebu di Provinsi Lampung dan
kaitannya dengan PTPN VII UU BUMA.
2. Menganalisis perilaku pasar gula tebu PTPN VII UU BUMA.
3. Menganalisis kinerja pasar gula tebu PTPN VII UU BUMA.
1.4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu :
1. Bagi petani dan lembaga pemasaran lainnya, adanya jaminan kepastian harga
yang akan meningkatkan pendapatan petani dan memberikan margin
keuntungan dengan pelaksanaan fungsi pemasaran bagi setiap lembaga
pemasaran yang terlibat melalui pembagian harga yang sesuai.
2. Bagi PTPN VII UU BUMA, dapat memberikan jaminan kepastian harga
khususnya bagi para petani dalam upaya merespon perubahan harga gula tebu.
Selain itu, menentukan posisi perusahaan dalam industri gula tebu sehingga
menentukan kemampuan perusahaan melalui pangsa pasar. Hal ini dapat
membantu petani melalui penentuan dan informasi harga jual yang tepat
3. Bagi pemerintah daerah, dapat menentukan kebijakan yang berkaitan dengan
11
4. Bagi saya, dapat mengembangkan daya analisis sistem pemasaran gula tebu
dengan pendekatan SCP dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu
agribisnis.
1.5. Ruang Lingkup Penelitian
Adapun ruang lingkup pada penelitian ini, yaitu :
1. Penelitian ini mengkaji seluruh lembaga pemasaran gula tebu PTPN VII UU
BUMA. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan kesimpulan
yang akurat mengenai tingkat pemasaran gula tebu di PTPN VII UU BUMA.
2. Komoditas yang diteliti adalah gula tebu (cane sugar)/Gula Kristal Putih
(GKP)/gula pasir dan tidak termasuk gula rafinasi.
3. Penelitian ini mencakup analisis struktur pasar (pangsa pasar, konsentrasi
pasar, dan hambatan masuk pasar), perilaku pasar (pemasaran,
penentuan-pembentukan harga, praktek penjualan dan pembelian, dan kerjasama lembaga
pemasaran, dan kinerja pasar (margin pemasaran, farmer share, dan analisis
13
II.
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Sistem Pemasaran Gula
Sistem pemasaran merupakan suatu kegiatan yang produktif, sangat
kompleks, sesuai dengan ketetapan, dan menimbulkan biaya (Downey et al,
1981). Pemasaran gula dalam negeri dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat Indonesia. Pemerintah menjamin ketersediaan gula secara kontinu jika
sistem pemasaran gula berjalan secara efisien (Amang, 1993). Ketidakefisienan
dalam pemasaran gula ditentukan oleh panjangnya rantai distribusi dan besarnya
biaya pemasaran yang harus dilalui oleh lembaga pemasaran sebelum sampai ke
konsumen (Ariani, 2000). Namun, kegiatan pemasaran yang baik tidak tergantung
dari panjang pendeknya rantai pemasaran melainkan dari fungsi lembaga
pemasaran tersebut melakukan kegiatan pemasaran.
Besar kecilnya biaya pemasaran tergantung jarak yang harus ditempuh
hingga sampai ke tangan konsumen. Sehingga biaya pemasaran dapat dijadikan
sebagai indikator efisiensi sistem tataniaga tersebut. Masalah yang dihadapi dalam
pemasaran gula yaitu masalah pengadaan dan pendistribusian. Kebijakan yang
dilakukan pemerintah antara lain kebijakan peningkatan kapasitas produksi,
pengembangan distribusi, dan akses tataniaga (Manik, 2007).
Deptan dan LPPM IPB (2002), melakukan penelitian keragaan agribisnis
gula di Jawa Barat. Sistem pengusahaan tebu di Jawa Barat dilakukan dengan
sistem hak guna usaha (PG Subang dan PG Jatitujuh) dan sistem Tebu Rakyat
(TR) yaitu di PG Sindang Laut, PG Tersana Baru, PG Karangsuswung. Dalam
sistem HGU pelaksanaan penanaman tebu sampai tebang angkut kemudian
14
yang terjadi di kebun menjadi tanggung jawab petani sementara kegiatan tebang
angkut walaupun biayanya ditangung petani pengawasan berada di PG. Terdapat
tiga saluran pemasaran gula di Jawa Barat yaitu :
a. Saluran 1: petanipedagang pengumpulgrosirpengecerkonsumen
b. Saluran 2: petanimediator (ketua kelompok tani, koperasi, petani tebu,
karyawan PG)grosirpengecerkonsumen
c. Saluran 3: petanigrosirpengecerkonsumen
Hasilnya menunjukkan bahwa keuntungan paling besar diperoleh pengecer. Hal
ini menunjukan marjin yang diterima pengecer lebih besar dibandingkan lembaga
lainnya.
Nahdodin dan Joko Roemanto (2008) melakukan penelitian mengenai
penerapan kebijakan gula SK 643 yang dapat mengetahui seberapa efisien tingkat
pemasaran gula. Hasilnya bahwa indikator inefisiensi pemasaran adalah margin
pemasaran sangat besar sehingga meskipun harga gula dunia rendah. Dengan
monopolisasi impor, harga eceran akan dapat membumbung tinggi. Margin
pemasaran rendah SK 643 cenderung tidak menimbulkan perilaku monopolisasi.
sehingga margin pemasaran tidak membesar dan tidak merugikan konsumen.
sehingga SK 643 menunjukkan pemasaran yang efisien. Selain itu SK 643 cukup
melindungi produsen gula berdasarkan indikator gula yang berlaku
Manik (2007) melakukan penelitian gula di Sumatera Utara dan
menyatakan bahwa saluran pemasaran gula terdiri dari dua saluran pemasaran.
Pertama, P3G1Pabrik Gula Petani TRI KUDPabrik Gula. Kedua,
P3GIPetani Petani TRB Pedagang Pengumpul Pabrik Gula. Hasilnya
15
Amang (1993) menyatakan bahwa kebijaksanaan pemasaran yang
ditempuh saat ini tidak terlepas dari struktur pasar gula yang cenderung oligopoli,
dimana tebu dihasilkan oleh jutaan petani sedangkan jumlah pabrik gula hanya
puluhan. Hal ini menunjukkan pelaku pasar yang kuat lebih mudah mengontrol
supply gula.
Kondisi pemasaran gula di Indonesia mempunyai karakteristik yang
kurang mendukung stabilitas harga, yaitu; (1) produksi gula dalam negeri belum
seimbang dengan kebutuhan konsumen; (2) produksi yang bersifat musiman;
(3) distribusi yang memerlukan biaya yang relatif tinggi. Amang (2003) Jika
kondisi gula seperti ini maka kebijaksanaan pemasaran gula memiliki peranan
yang penting dalam usaha untuk mencapai tujuan dalam distribusi gula. Oleh
karena itu, dalam melakukan pemasaran gula terdapat lembaga pemasaran yang
menyalurkan gula sampai ketangan konsumen yang melibatkan beberapa pelaku
pasar seperti produsen, distributor, dan pengecer.
2.2. Penerapan SCP (Market Structure, Market Conduct, Market Performance) dalam Analisis Sistem Pemasaran
Yuprin (2009) melakukan penelitian analisis pemasaran karet di
Kabupaten Kapuas. Penelitian ini menggunakan konsep SCP. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa (1) saluran pemasaran karet terdiri dari enam macam dan
dapat diidentifikasi satu macam saluran terbaik, yaitu petani–pedagang
kecamatan–eksportir. Saluran ini digunakan oleh sedikit petani di daerah
penelitian, berarti hanya sedikit petani yang memiliki aksesibilitas baik terhadap
eksportir. Petani sebagian besar memasarkan karet melalui saluran pemasaran
16
eksportir. Saluran ini terpaksa digunakan, karena petani sudah terikat dengan
pedagang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya; (2) struktur pasar di
tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten bersifat oligopsoni konsentrasi sedang
yang menunjukkan bahwa pedagang memiliki tingkat kekuasaan yang sedang
dalam mempengaruhi pasar. Struktur pasar di tingkat eksportir adalah monopsoni
yang menunjukkan adanya kekuasaan tunggal ekportir dalam mempengaruhi
pasar; (3) perilaku pasar ditunjukkan dengan tidak sempurnanya keterpaduan
harga karet pada pasar yang satu dengan harga karet pada pasar yang lain, baik
secara horisontal maupun vertikal; dan (4) penampilan pasar ditunjukkan dengan
marjin pemasaran yang relatif besar dan didominasi oleh share keuntungan yang
besar dan tidak merata. Hal ini menunjukkan bahwa pemasaran hasil karet tidak
efisien, sehingga merugikan pedagang tingkat bawah dan petani yang berposisi
paling bawah. Apabila ditinjau dari segi produksi karet di tingkat petani, perilaku
dan penampilan pasar karet yang merugikan pedagang di tingkat bawah dan
petani yang berposisi paling bawah disebabkan kualitas laboratorium yang di
bawah standar. Struktur, perilaku, dan penampilan pasar yang terjadi sebagaimana
yang telah diuraikan sebelumnya, menyebabkan pedagang lebih banyak
menikmati keuntungan dan share harga yang diterima petani relatif lebih kecil.
Fadla (2008) menganalisis integrasi pasar dalam mengukur efisiensi
pemasaran komoditas beras, kacang tanah kupas, dan kedelai kuning di Propinsi
NAD (Nangroe Aceh Darussalam). Dengan menggunakan model ekonometrika
dalam analisis integrasi pasar secara horizontal, vertikal, jangka pendek dan
jangka panjang, serta dari hasil analisis SCP, Hasil analisis dengan pendekatan
17
pangan (beras, kacang tanah, dan kedelai kuning) hal ini disebabkan juga faktor
sosial politik yang tidak kondusif di Propinsi yang sangat mempengaruhi keadaan
pasar dan perekonomian masyarakat. Hasil analisis elastisitas transmisi harga
menunjukan rata-rata koefisien elastisitas harga tergolong dalam kategori yang
elastis. Artinya di daerah penelitian, perubahan harga di tingkat pasar konsumen
selalu diikuti dengan perubahan harga di tingkat pasar produsen yang lebih besar,
dimana pasar produsen lebih berperan dari pada pasar konsumen dalam
mengendalikan harga. Hal ini menunjukkan proporsi keuntungan yang lebih besar
diperoleh pedagang di pasar tingkat produsen. Analisis integrasi pasar dan
efisiensi pemasaran dengan pendekatan SCP belum memberikan hasil yang
memuaskan, dikarenakan penelitian hanya menggunakan data sekunder.
Sri Haryanto (2004) menganalisis sistem pemasaran apel manalagi (Malus
sylvestris Mill) di Kota Batu Propinsi Jawa Timur. Struktur pasar yang terjadi
cenderung oligopsoni. Informasi harga (59 %) dipengaruhi oleh pedagang yang
berpegaruh dan proses pemasaran apel manalagi pada tingkat lembaga dilakukan
melalui jalur khusus (50-72.2 %). Selain itu terdapat kesulitan masuk pasar bagi
pedagang baru. Perilaku pasar khususnya dalam penentuan harga antara penjual
dan pembeli dilakukan secara terbuka. Namun proses penentuan harga lebih
dominan dipengaruhi oleh informasi harga yang berasal dari sesama pedagang dan
pedagang yang berpengaruh. Dalam hal ini pemasaran cenderung kurang efisien.
Distribusi margin yang paling tinggi berada pada pedagang pengecer. Namun,
pengecer menanggung resiko kerusakan dan biaya lain yang cukup tinggi. Hasil
analisis menunjukkan perbandingan keuntungan dan biaya produksi yang
18
Analisis elastisitas transmisi harga menunjukkan elastisitas lebih kecil dari satu.
Artinya perubahan nisbi harga pada pasar pelaku yang dipengaruhi tidak akan
melebihi perubahan nisbi harga di tingkat pelaku pasar acuan yang
mempengaruhi. Hasil analisis integrasi pasar vertikal menunjukkan bahwa secara
umum pada setiap tingkatan proses pemasaran terjadi integrasi jangka pendek dan
tidak terjadi integrasi jangka panjang. Oleh karena itu, dikatakan bahwa
perubahan harga di pasar lokal tidak diikuti oleh perbedaan harga di tingkat pasar
acuan.
Hukama (2003) menganalisis pemasaran jambu mete dengan
menggunakan SCP. Pemasaran jambu mete belum efisien karena saluran
pemasaran masih panjang dan melibatkan banyak pelaku pemasaran. Struktur
pasar yaitu oligopsoni. Keuntungan sebagian besar diambil oleh pedagang.
Analisis keterpaduan pasar dominasi pedagang besar dalam penetapkan harga di
petani sebagai penerima harga.
Kurniawan (2003), yang meneliti kelembagaan pemasaran gaharu di
Kalimantan Timur menggunakan pendekatan SCP untuk menganalisis perilaku
usaha pengumpul dan pedagang gaharu. Sedangkan untuk mengetahui
karakteristik kelembagaan pemasaran gaharu dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kelembagaan yang diterapkan dalam
kelembagaan pemasaran gaharu adalah sistem patron-klien, struktur pasar gaharu
baik di tingkat kelembagaan pengumpul (desa), maupun pedagang gaharu (kota)
adalah oligopsoni. Hasil lain yang dikemukakan adalah tidak seluruh patron
(pedagang) dapat mengambil keuntungan dalam pemasaran gaharu. Perilaku
19
dirugikan akan merespon dengan mengurangi loyalitasnya kepada patron dimana
perilaku ini menimbulkan moral hazard dalam kelembagaan gaharu.
Berbeda halnya dengan Slameto (2003) yang menganalisis kinerja
kelembagaan pemasaran kakao rakyat di Lampung dengan menggunakan SCP.
Struktur pasar cenderung oligopoli. Harga ditentukan pedagang dan belum
dipatuhinya grading dan standarisasi produk. Keragaan pasar kakao belum baik
karena hubungan pasar lokal dan pasar acuan kurang padu sehingga harga tidak
tertransmisi dengan baik.
Yusrachman (2001), menganalisis sistem pemasaran ikan segar di PPI
Muara Angke Jakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur pasar yang
berlaku yaitu pasar tidak bersaing sempurna (oligopsoni). Penyebaran margin
belum efisien karena marjin pada setiap lembaga pemasaran tidak merata.
Pedagang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga yang terjadi pasar. Hal
ini menunjukkan pemasaran yang tidak efisien.
Andrias et al (2003) melakukan penelitian analisis tataniaga dan pilihan
kelembagaan pemasaran tembakau di Kabupaten Temanggung. Hasilnya
menunjukkan bahwa perilaku pasar tembakau ditentukan oleh konsumen yaitu
perusahaan rokok dan pedagang besar. Struktur pasar yang terbentuk oligopsoni.
Distribusi keuntungan tidak merata. Maka, pemasaran tembakau di kabupaten
Tembakau belum efisien.
Triyono (2000) melakukan penelitian perkembangan posisi tawar petani
dalam pemasaran damar mata kucing di Lampung. Hasilnya menunjukkan perilaku
20 sempurna. Hal ini dikarenakan adanya hambatan masuk. Secara umum, pemasaran
yang dilakukan belum efisien.
Referensi yang telah diperoleh dapat membantu penulis dalam melakukan
analisis dalam penelitian ini. Penelitian sistem pemasaran gula yang dilakukan
oleh beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa sistem pemasaran gula dapat
berjalan efisien jika seluruh lembaga pemasaran yang terlibat melakukan fungsi
pemasaran yang sesuai dan melakukan kegiatan pemasaran secara fair. Penerapan
SCP dalam analisis sistem pemasaran yang telah dilakukan beberapa sumber
menghasilkan kesimpulan umum bahwa sistem pemasaran akan efisien jika
21
III.
KERANGKA PEMIKIRAN
3.1. Kerangka Pemikiran Konseptual 3.1.1. Konsep Pemasaran
Definisi tentang pemasaran telah banyak dikemukakan oleh para ahli
ekonomi, pada hakekatnya bahwa pemasaran merupakan aktivitas yang ditujukan
terhadap barang dan jasa sehingga dapat berpindah dari tangan produsen ke
tangan konsumen. Pemasaran menurut Kohls dan Uhl (2002) merupakan sebuah
sistem meliputi seluruh aliran produk dan jasa-jasa yang ada, mulai dari titik awal
produksi pertanian sampai semua produk dan jasa tersebut ditangan konsumen
Hal ini sejalan dengan Dahl dan Hammond (1977) yang mendefinisikan
pemasaran sebagai rangkaian urutan fungsi-fungsi yang dilakukan ketika produk
bergerak dari titik produksi sampai ke konsumen akhir. Menurut Downey et al
(1981) pemasaran merupakan proses aliran produk dari produsen ke konsumen
akhir. Kompleksitas saluran pemasaran tergantung pada masing-masing komoditi.
Pemasaran melibatkan banyak perbedaan aktivitas yang dapat memberikan nilai
tambah terhadap suatu produk sebagai perubahan melalui suatu sistem. Sistem
pemasaran merupakan suatu kegiatan yang produktif, sangat kompleks, sesuai
dengan ketetapan, dan menimbulkan biaya.
Berbeda halnya dengan Lamb et al (2001), pemasaran dari segi ekonomi
merupakan tindakan atau kegiatan produktif yang menghasilkan pembentukan
kegunaan yaitu kegunaan waktu, bentuk, tempat, dan kepemilikan. Kotler (1993)
mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses sosial dimana individu dan
kelompok mendapatkan apa yang dibutuhkan melalui penciptaan, penawaran, dan
22
Sitorus (1987) mengungkapkan konsep pemasaran sebagai suatu sistem
keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan
harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat
memuaskan kebutuhan pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Saefuddin
(1982) mengemukakan bahwa rantai pemasaran atau saluran pemasaran
merupakan aliran yang dilalui oleh barang dan jasa dari produsen melalui lembaga
pemasaran sampai barang dan jasa tersebut sampai di tangan konsumen.
Pemasaran merupakan pembelian bahan pangan dan semua yang dibutuhkan oleh
rumah tangga. Mulai dari kegiatan menyimpan hingga menyampaikan produk ke
tangan konsumen (Cramer et al. 2001).
Pemasaran ditinjau dari dua perspektif yaitu perspektif makro dan mikro
(Schaffner, et.al dalam Asmarantaka, 2009). Perspektif makro menganalisis
sistem pemasaran setelah dari petani yaitu fungsi-fungsi pemasaran untuk
menyampaikan produk/jasa yang berhubungan dengan nilai guna, waktu, bentuk,
dan tempat, dan kepemilikan kepada konsumen serta kelembagaan yang terlibat
dalam sistem pemasaran. Perspektif mikro menekankan pada aspek manajemen
dimana perusahaan secara individu, pada setiap tahapan pemasaran dalam mencari
keuntungan.
Menurut Solomon, et al. (2006), basis gagasan pemasaran adalah
berangkat dari upaya untuk mengirimkan values (nilai-nilai) kepada setiap orang
yang mampu dipengaruhi dalam sebuah transaksi. Sedangkan Levens (2010),
pemasaran adalah sebuah fungsi organisasi dan kumpulan sebuah proses yang
dirancang dalam rangka untuk merencanakan, menciptakan, mengkomunikasikan,
23
hubungan yang efektif dengan pelanggan dengan adanya benefit yang dirasakan
oleh organisasi dan para stakeholdernya. Levens menegaskan bahwa salah satu
konsep terpenting dari ilmu ekonomi yang digunakan dalam pemasaran adalah ide
tentang utilitas. Utilitas didefinisikan sebagai kepuasan yang diterima oleh
konsumen dari produk atau jasa yang dimiliki atau dikonsumsinya. marketing
adalah lebih luas dari pada aktivitas menjual (selling) atau aktivitas penawaran
iklan (advertising). Pemasaran mempengaruhi konsumen berdasarkan pilihan saat
ini dan di masa depan, serta berdasarkan kondisi ekonomi. Perusahaan
menciptakan nilai-nilai (values) berdasarkan pada apa yang mereka tawarkan,
mengkomunikasikan nilai-nilai tersebut kepada konsumen, dan kemudian
menghantarkan nilai-nilai tersebut dalam pertukarannya dengan uang yang dapat
diberikan oleh konsumen.
Tujuan dari pemasaran yaitu agar barang dan jasa yang dihasilkan oleh
petani maupun perusahaan sebagai produsen sampai ke konsumen.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar barang dan jasa dapat berpindah dari sektor
produksi ke sektor konsumsi disebut sebagai fungsi pemasaran. Downey (1981),
fungsi pemasaran yang dimaksud tersebut meliputi; a) fungsi pertukaran yang
meliputi pembelian dan penjualan; b) fungsi fisik meliputi pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan, pengangkutan; c) fungsi fasilitas yang meliputi
standarisasi dan grading, penanggungan resiko, pembiayaan, dan informasi harga.
Levens (2010), fungsi marketing didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas
yang ditampilkan oleh perusahaan atau organisasi ketika menciptakan nilai
(value) secara spesifik untuk produk atau jasa yang ditawarkannya. Fungsi-fungsi
24
dan jasa dari sektor produksi ke sektor konsumsi. fungsi marketing dapat
dikelompokkan dalam tiga kategori umum, di mana setiap kategori
menggambarkan proses (aktivitas) marketing yang terjadi. Tiga kategori fungsi
tersebut antara lain:
1. Fungsi pertukaran (exchange function)
2. Fungsi fisik (physical function)
3. Fungsi fasilitasi (facilitating function)
Fungsi pertukaran adalah aktivitas-aktivitas untuk mempromosikan dan
mentransfer kepemilikan. Contohnya antara lain penjualan, pembelian, harga,
iklan, promosi penjualan dan public relation. Fungsi fisik merupakan aktivitas
untuk mengalirkan barang dari perusahaan (manufaktur) kepada konsumen.
Contohnya antara lain: perakitan (assembling), transportasi dan penanganan
(transporting and handling), pergudangan (warehousing), pengolahan dan
pengemasan (processing and packaging), standarisasi (standardizing), dan
grading. Adapun fungsi fasilitasi di dalamnya merupakan aktivitas-aktivitas
pendampingan dalam proses eksekusi fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Contoh
aktivitas fasilitasi ini antara lain: pembiayaan dan pengambilan risiko (financing
and risk taking), informasi pemasaran dan penelitian, dan janji layanan (promise
of servicing).
3.1.2. Konsep Efisiensi Pemasaran
Soekartawi (2002), efisiensi pemasaran merupakan nisbah antara total
biaya dengan total nilai produk yang dipasarkan. Faktor yang menjadi ukuran
efisiensi pemasaran yaitu keuntungan pemasaran, harga yang diterima petani,
25
Asmarantaka (2009), efisiensi pemasaran dapat dilakukan dengan
beberapa pengukuran, yaitu: 1) efisiensi operasional dan 2) efisiensi harga.
Efisiensi operasional berhubungan dengan penanganan aktivitas-aktivitas yang
dapat meningktakan rasio dari output-input pemasaran. Input pemasaran adalah
sumberdaya (tenaga kerja, pengepakan, mesin, dan lainnya) yang diperlukan
untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran. Output pemasaran yang
berhubungan dengan kepuasan konsumen. Oleh sebab itu, sumberdaya adalah
biaya sedangkan kegunaan adalah benefits dari rasio efisiensi pemasaran. Rasio
efisiensi pemasaran dapat dilihat dalam dua cara yaitu perubahan sistem
pemasaran dengan mengurangi biaya pada fungsi-fungsi pemasaran tanpa
mengubah manfaat konsumen dan meningkatkan keguanaan output dari proses
pemasaran tanpa meningkatkan biaya pemasaran. Efisiensi harga menekankan
kepada kemampuan dari sistem pemasaran yang sesuai dengan keinginan
konsumen. Sasaran dari efisiensi harga yaitu efisiensi alokasi sumberdaya dan
maksimum output. Efisiensi harga dapat tercapai apabila pihak-pihak yang terlibat
dalam pemasaran responsif terhadap harga yang berlaku. Menurut Soekartawi
(2002) bila keuntungan yang diperoleh sebagai akibat pengaruh harga maka dapat
dikatakan bahwa pengalokasian faktor produksi memenuhi efisiensi harga.
Efisiensi pemasaran tercipta ketika pihak-pihak yang terlibat baik
produsen, lembaga-lembaga pemasaran maupun konsumen memperoleh kepuasan
(Limbong dan Sitorus, 1987). Apabila terjadi suatu perubahan yang menyebabkan
biaya input untuk menghasilkan suatu barang dan atau jasa meningkat dengan
tidak mengurangi kepuasan konsumen dikatakan sebagai peningkatan efisiensi.
26
input tetapi tidak mempertahankan atau tidak diikuti dengan peningkatan
kepuasan konsumen maka dikatakan terjadi penurunan efisiensi. Penggunaan
konsep efisiensi seperti ini sangat sulit karena adanya kesulitan dalam mengukur
tingkat kepuasan. Sejalan dengan hal tersebut, produk yang sampai ke tangan
konsumen dengan harga murah dan adanya pembagian yang adil bagi produsen
dan lembaga-lembaga pemasaran dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen
merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan secara efisien (Mubyarto, 1985).
Hobbs (1997) pilihan saluran pemasaran ditentukan oleh biaya transaksi. Biaya
pemasaran yang tinggi akan membuat sistem pemasaran menjadi tidak efisien
(Kohls dan Uhl, 2002). Pasar yang tidak efisien disebabkan oleh tingginya biaya
pemasaran dibandingkan dengan nilai produk yang dijual (Soekartawi, 2002).
Sudiyono (2002) mengemukakan bahwa indikator yang biasa digunakan
untuk menentukan efisiensi pemasaran adalah margin pemasaran. Margin
pemasaran yaitu perbedaan harga yang dibayar oleh konsumen akhir dengan harga
yang diterima pada tingkat petani. Marjin pemasaran dapat bersifat statis dan
dinamis tergantung pada nilai tambah suatu komoditas atau produk. Margin
pemasaran dapat mengetahui penyebaran marjin, efisiensi operasional, dan
efisiensi harga. Ukuran efisiensi operasional yaitu adanya biaya pemasaran dan
margin pemasaran. Semakin besar biaya pemasaran maka margin pemasaran
semakin besar yang menyebabkan sistem pemasaran menjadi tidak efisien.
Sedangkan efisiensi harga diukur oleh korelasi harga akibat adanya pergerakan
27 3.1.3. Konsep SCP (Market Structure, Market Conduct, Market Performance)
Konsep SCP awalnya hanya digunakan untuk menganalisis organisasi
pasar dalam sektor industri di negara-negara industri maju seperti Amerika
Serikat, namun sekarang telah banyak digunakan untuk menganalisis kegiatan
pertanian. Dasar paradigma SCP dicetuskan oleh Mason tahun 1939 yang
mengemukakan bahwa struktur suatu industri akan menentukan bagaimana pelaku
industri berperilaku, yang pada akhirnya menentukan keragaan atau kinerja
industri tersebut.
Philips dalam Asmarantaka (2009) mengajukan konsep yang bersifat
dinamis, keterkaitan hubungan dua arah yang bersifat timbal balik dan sifat
hubungan endogenous diantara variabel-variabel SCP serta memperhitungkan
waktu. Pendekatannya menunjukkan bahwa structure (S), conduct (C), dan
performance (P) dalam suatu waktu berada pada sistem dimana S dan C adalah
faktor penentu dari P, dilain waktu S dan C ditentukan oleh P. Hal ini
menunjukkan suatu sistem dinamis yang mengembangkan respon penyesuaian
dari perusahaan terhadap kondisi pasar dan keadaan yang memungkinkan.
Sudiyono (2002), upaya memaksimumkan efisiensi pemasaran di negara
berkembang dapat dilakukan dengan pendekatan SPC (Structure, Performance,
Conduct). Wardiyati dalam Sri (2004) mengemukakan bahwa terdapat beberapa
indikator dalam menentukan efisiensi pemasaran dengan pendekatan SCP.
Indikator dalam struktur pasar seperti jumlah pedagang, hambatan masuk, ada
tidaknya kolusi pasar, dan konsentrasi pasar. Sedangkan indikator dari analisis
28
yang menjadi indikator yaitu share produsen, distribusi margin, integrasi pasar,
dan elastisitas transmisi harga. Adapun indikator ini dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Indikator dan Analisis Pemasaran SCP
No Analisis Indikator Kriteria
Efisien Tidak Efisien
Sumber : Wardiyati dalam Sri (2004)
Menurut Baye (2010), paradigma SCP terdiri atas tiga aspek analisis yang
saling berhubungan. Identifikasi market stucture terdiri dari berapa jumlah
perusahaan yang bersaing dalam pasar, penggunaan teknologi, konsentrasi pasar,
kondisi pasar, dan hambatan keluar masuk pasar. Sedangkan market conduct
merupakan bentuk perilaku pasar terhadap struktur pasar yang terjadi. Adapun
indikatornya yaitu proses penentuan harga, kegiatan integrasi dan merger,
penentuan perlklanan, dan penentuan keputusan untuk research and development.
Sedangkan market performance merupakan keuntungan dan social welfare yang
akan diterima industri dalam suatu pasar sebagai efek dari terbentuknya suatu