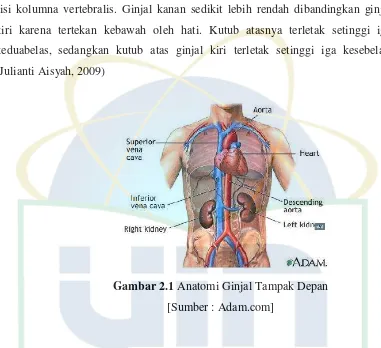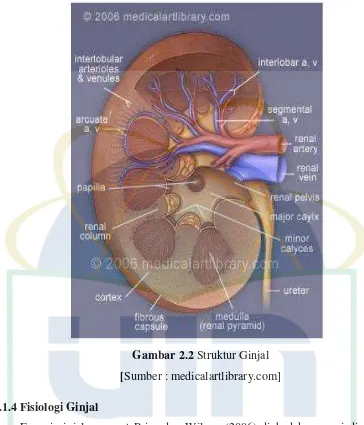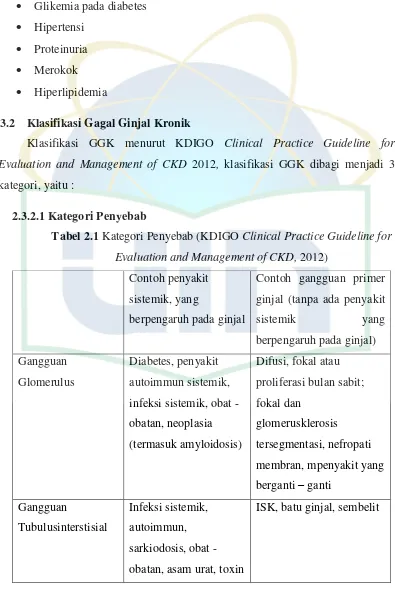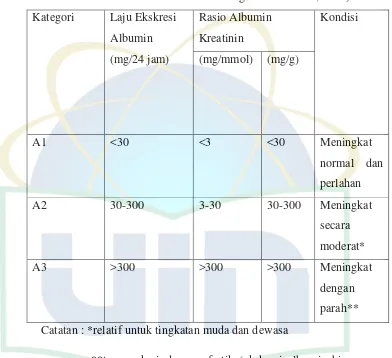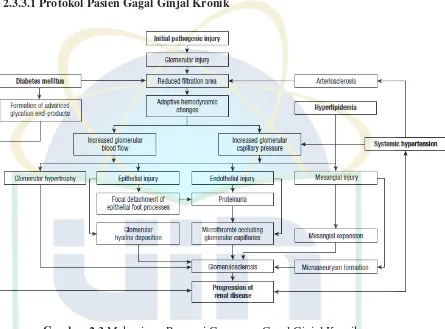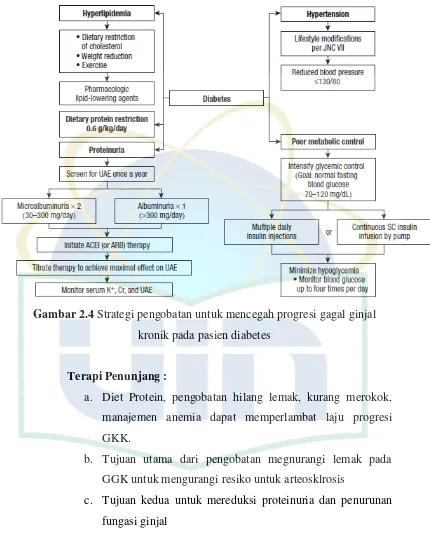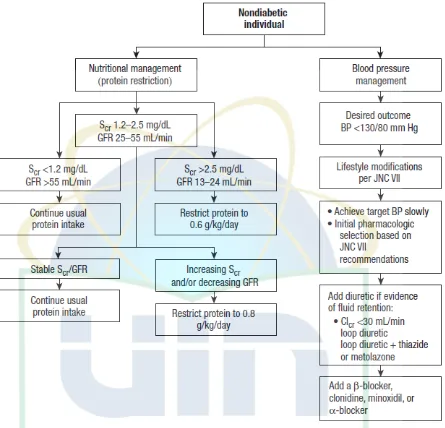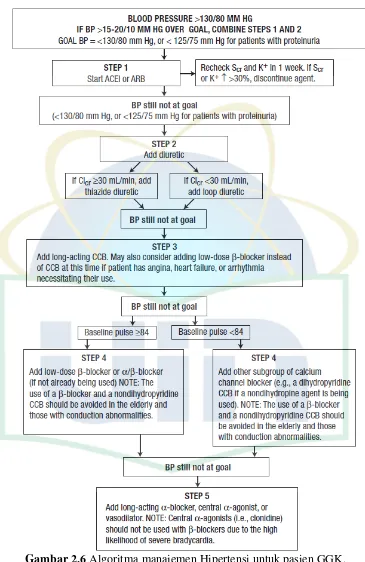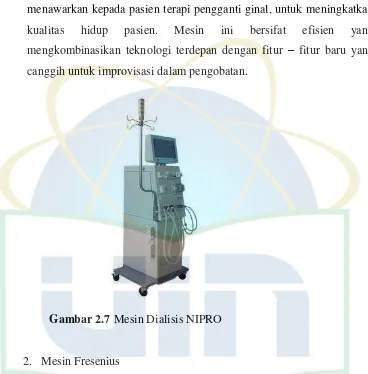EVALUASI
DRUG RELATED PROBLEM
PADA PASIEN
GAGAL GINJAL KRONIK DI RUMAH SAKIT
PELABUHAN JAKARTA UTARA
SKRIPSI
AGUNG PRAKOSO TRISNA
NIM: 1111102000078
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI FARMASI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
EVALUASI DRUG RELATED PROBLEM PADA PASIEN
GAGAL GINJAL KRONIK DI RUMAH SAKIT
PELABUHAN JAKARTA UTARA
SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi
AGUNG PRAKOSO TRISNA
NIM: 1111102000078
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI FARMASI
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ii
Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan
semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar
Nama : Agung Prakoso Trisa
NIM : 111110200078
Tanda Tangan :
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta v
Nama : Agung Prakoso Trisa
NIM : 1111102000078
Program Studi : Strata-1 Farmasi
Judul Skripsi : Evaluasi Drug Related Problems Kategori Penyesuaian Dosis Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik di Rumah Sakit
Pelabuhan Jakarta Utara
DRP (Drug Related Problems) didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang
tidak diinginkan atau risiko yang dialami oleh pasien, yang melibatkan atau
diduga melibatkan terapi obat. Terjadinya DRP dapat mencegah atau menunda
pasien dari pencapaian terapi yang diinginkan. Pasien GGK (Gagal Ginjal Kronik)
menerima berbagai agen obat terapi, terlebih untuk pasien yang sudah
berkomplikasi penyakitnya. Hal ini menyebabkan tingginya resiko terjadinya
DRP. Salah satu masalah DRP yang paling penting pada pasien penyakit ginjal
kronis (GGK) adalah kesalahan dosis obat. Banyak obat dan metabolitnya yang
dieliminasi melalui ginjal. Dengan demikian, fungsi ginjal yang memadai penting
untuk menghindari toksisitas. Pasien dengan gangguan ginjal sering memiliki
perubahan dalam parameter farmakokinetik dan farmakodinamik. Oleh karena itu,
pertimbangan khusus harus diambil ketika obat ini diresepkan untuk pasien
dengan gangguan fungsi ginjal. Penelitian DRP kategori penyesuaian dosis masih
jarang dilakukan, karena itu penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa besar
angka kejadian DRP kategori dosis yang terjadi. Penelitian menggunakan desain
cross sectional dengan pendekatan retrospektif terhadap 26 pasien rawat inap RS
Pelabuhan Jakarta Utara yang mengalami GGK pada tahun 2014. Dari hasil
didapatkan terdapat 9 pasien (34,62 %) yang mengalami DRP dosis dibawah
terapi, presentase tertinggi didapat pada obat Aminefront sebanyak 5 kejadian
(45,46 %). Lalu terdapat 22 pasien (84,62 %) yang mengalami DRP dosis diatas
terapi, presentase tertinggi didapat pada obat Vometa (Domperidone) sebanyak 9
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta vi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta vii
Name : Agung Prakoso Trisa
NIM : 1111102000078
Study Program : Strate-1 Pharmacy
Title : Evaluation of Drug Related Problems Category Adjusment Dose with Chronic Kidney Disease Patients
at Pelabuhan Hospital of North Jakarta
DRPs (Drug Related Problems) are defined as an undesirable occurrence
or risk that underwent by patient, involving or allegedly involving therapeutic
drugs. DRPs could prevent or delay patients outcome. Patients with CKD
(Chronic Kidney Disease) receives multi therapeutic drugs, especially for patients
who have complicated disease. One of the most important DRPs in patients with
CKD is medication errors. Many medications and their metabolites are eliminated
through the kidney. Thus, adequate renal function is important to avoid toxicity.
Patients with renal impairment often have alterations in their pharmacokinetic and
pharmacodynamic parameters. Therefore, special consideration should be taken
when these drugs are prescribed to patients with impaired renal function. Study of
DRPs category adjusment dose is still rare, accordingly this study aims to evaluate
precentage of DRP category adjusment dose that occurs. This study used cross
sectional design with retrospective towards 26 hospitalized patients at Pelabuhan
Hospital of North Jakarta with CKD in 2014. The results figured that 9 patients
(34,62 %) with DRP under dosage, the highest precentage of the drugs goes to
Aminefront with 5 cases (45,46 %). And then figured that 22 patients (84,62 %)
with DRP over dosage, the highest precentage goes to Vometa (Domperidone)
with 9 cases (21,43 %). The results showed that DRP over dosage occur more
than 50 %, this case can be used for attention and evaluation for the future of
Hospital.
Keywords : DRPs, Chronic Kidney Disease, Adjusment Dose, Pelabuhan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta viii
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan segala
rahmat-nya kepada kita semua. Khususnya penulis dapat menyelesaikan skripsi
yang berjudul “Evaluasi Drug Related Problem Kategori Penyesuaian Dosis pada
Pasien Gagal Ginjal Kronik Di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Utara” ini.
Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita nabi
Muhammada SAW, yang merupakan suri tauladan bagi kita semua.
Skripsi ini disusun dari hasil penelitian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit
Pelabuhan Jakarta Utara. Dalam proses penyususnan skripsi dan dalam
menyelesaikan masa perkuliahan tentu banyak berbagai halangan serta kesulitan yang menyertai, sehingga penuli tidak terlepas dari do’a, dorongan, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk
menghaturkan ucapkan terimakasih yang mendalam kepada :
1. Bapak Yardi, PhD., Apt sebagai Pembimbing I dan selaku Ketua Program Studi
Farmasi UIN, Bu Isti Qomarsih, S.Si, MARS.,Apt. sebagai Pembimbing II, Bu
Vidia Anwar, S.Si.,Apt. sebagai pembimbing lapangan yang telah memberikan
ilmu, waktu, tenaga, nasihat, serta arahan selama penelitian dan penulisan skripsi
ini.
2. Bapak Dr. H. Arif Sumantri, SKM., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran
dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Haddad Triyono dan Ibunda Monalisa Sjarif
yang selalu iklas tanpa pamrih membeikan kasih sayang, dukungan moral,
material, nasihat-nasihat, serta lantunan doa disetiap waktu.
4. Kakakku tersayang Rhealina Trisa yang selalu memberi dukungan do’a dan
moral.
5. Ibu Nelly Suryani, PhD., M.Si., Apt selaku Sekretaris Program Studi Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
6. Ibu Dr. Delina Hasan, M.Kes, Apt selaku Penasehat Akademik yang Selalu
Membimbing Penulisan.
7. Rekan terbaikku Ayu Diah Gunardi yang selalu membantu, mengingatkan dan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ix
9. Teman sepenelitianku Inten Novita terimakasih atas motivasinya sejak awal
hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
10. Teman – teman bermain (Cokers Farmasi) yang tidak pernah menolak jika
diminta bantuan.
11. Bapak dan ibu staf pengajar, serta karyawan yang telah memberikan bimbingan
dan bantuan selama menempuh pendidikan di Program Studi Farmasi Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
12. Ibu dan bapak seluruh pegawai RS Pelabuhan Jakarta Utara yang telah
memberikan bantuan kepada penulis selama penelitian.
13. Teman-teman program studi Farmasi khususnya 2011.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian dan
penulisan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Semoga semua bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah
SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, oleh
karena itu keritik dan saran sangat diharpkan demi perbaikan skripsi ini. Dan semoga
skripsi ini bisa bermanfaat nagi pengembangan ilmu pengetahuan.
Jakarta, Oktober 2015
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta x
Sebagai sivitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Agung Prakoso Trisa
NIM : 1111102000078
Program Studi : Strata-1 Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)
Jenis Karya : Skripsi
Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui skripsi/karya
ilmiah saya dengan judul :
Evaluasi Drug Related Problems Kategori Penyesuaian Dosis Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Utara.
untuk dipublikasi atau ditampilkan di internet atau media lain yaitu Digital Library Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta untuk kepentingan akademik sebatas sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta. Demikian persetujuan publikasi karya ilmiah ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Ciputat
Pada Tanggal : Oktober 2015
Yang menyatakan,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta xi
HALAMAN PERNYATAAN ORSINILITAS ... ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... iii
HALAMAN PENGESAHAN ... iv
ABSTRAK ...v
ABSTRACT ... vii
KATA PENGANTAR ... viii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ...x
DAFTAR ISI ... xi
DAFTAR GAMBAR ... xiv
DAFTAR TABEL ...xv
DAFTAR LAMPIRAN ... xvi
DAFTAR SINGKATAN ... xvii
BAB 1 PENDAHULUAN ...1
1.1 Latar Belakang ...1
1.2 Rumusan Masalah ...3
1.3 Pertanyaan Penelitian ...4
1.4 Tujuan Penelituan ...4
1.4.1 Tujuan Umum ...4
1.4.2 Tujuan Khusus...4
1.5 Manfaat Penelitian ...4
1.5.1 Teoritis ...4
1.5.2 Metodologi ...4
1.5.3 Aplikatif ...4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ...5
2.1 Drug Related Problems (DRPs) ...5
2.2 Ginjal ...6
2.2.1 Anatomi dan Fisiologi Ginjal ...7
2.2.1.1 Anatomi Ginjal ...7
2.2.1.2 Struktur Makroskopik Ginjal ...8
2.2.1.3 Struktur Mikroskopik Ginjal ...8
2.2.1.4 Fisiologi Ginkal ...10
2.2.2 Penilaian Fungsi Ginjal ...12
2.2.2.1 Persamaan Cockcroft-Gault ...12
2.2.2.2 Persamaan MDRD ...13
2.3 Definisi Gagal Ginjal Kronik ...14
2.3.1 Etilogi Gagal Ginjal Kronik ...15
2.3.2 Klasifikasi Gagal Ginjal Kronik ...16
2.3.2.1 Kategori Penyebab ...16
2.3.2.2 Kategori GFR ...17
2.3.2.3 Kategori Albuminuria ...18
2.3.3 Patofisiologi Gagal Ginjal ...19
2.3.3.1 Protokol Pasien Gagal Ginjal Kronik ...20
2.3.3.2 Pengobatan Progresi dengan Modifikasi Terapi ...21
2.3.4 Terapi Pengganti Ginjal ...28
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta xii
2.4 Rumah Sakit ...31
2.4.1 Pelayanan Farmasi Klinik Di Rumah Sakit...33
2.5 Rekam Medik ...34
BAB 3 METODE PENELITIAN ...36
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian ...36
3.1.1 Tempat Penelitian ...36
3.1.2 Waktu Penelitian ...36
3.2 Desain Penelitian ...36
3.3 Kerangka Konsep ...37
3.4 Definisi Operasional ...38
3.5 Populasi dan Sampel Penelitian ...42
3.5.1 Populasi ...42
3.5.2 Sampel ...42
3.6 Kriteria Inklusi dan Eksklusi Penelitian ...42
3.6.1 Kriteria Inklusi Sample ...42
3.6.2 Kriteria Ekslusi Sampel ...43
3.7 Prosedur Penelitaian...43
3.7.1 Bagan Alur Penelitian ...43
3.7.2 Persiapan Penelitan ...43
3.7.3 Pelaksanaan Pengumpulan Data...44
3.7.3.1 Penelusuran Dokumen ...44
3.7.4 Manajemen Data ...44
3.7.5 Pengolahan Data ...44
3.8 Analisa Data ...45
3.8.1 Analisa Univariat...44
BAB 4 HASIL DSN PEMBAHASAN ...46
4.1 Hasil Penelitian ...46
4.1.1 Karakteristik Pasien...46
4.1.2 Profil Penggunaan Obat ...48
4.1.2.1 Profil Penggunaan Obat Injeksi ...48
4.1.2.2 Profil Penggunaan Obat Oral ...49
4.1.3 DRPs Kategori Dosis Dibawah Dosis Terapi ...50
4.1.3 DRPs Kategori Dosis Diatas Dosis Terapi ...51
4.2 Pembahasan ...53
4.2.1 Karakteristik Pasien...53
4.2.2 Profil Penggunaan Obat ...55
4.2.3 DRPs Kategori Dosis Dibawah Dosis Terapi ...60
4.2.4 DRPs Kategori Dosis Diatas Dosis Terapi ...61
4.3 Keterbatasan Penelitian ...63
4.3.1 Kendala ...63
4.3.2 Kelemahan ...63
4.3.3 Kekutan ...64
BAB 5 KESIMPULAN ...65
5.1 Kesimpulan ...65
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta xiv
Gambar Halaman
Gambar 2.1 Anatomi Ginjal Tampak Depan ...7
Gambar 2.2 Struktur Ginjal ...10
Gambar 2.3 Mekanisme Progresi Gangguan Gagal Ginjal Kronik ...20
Gambar 2.4 Strategi Pengobatan Untuk Mencegah Gagal Ginjal Kronik Pada Pasien Diabetes...25
Gambar 2.5 Strategi Pengobatan Untuk Mencegah Gagal Ginjal Kronik Pada Pasien Non Diabetes ...26
Gambar 2.6 Algoritma Manajemen Hipertensi Untuk Pasien GGK ...27
Gambar 2.7 Mesin Dialisis Nipro ...29
Gambar 2.8 Mesin Dialisis Fresenieus ...30
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta xv
Tabel Halaman
Tabel 2.1 Klasifikasi GGK Kategori Penyebab ...16
Tabel 2.2 Klasifikasi GGK Kategori Albuminuria...18
Tabel 3.1 Definisi Operasional ...38
Tabel 4.1 Distribusi Pasien Berdasarkan Karakteristik ...46
Tabel 4.2 Distribusi Penyakit Penyerta Pada Pasin GGK ...46
Tabel 4.3 Presentase Distribusi Jumlah Pasien Berdasarkan Profil Penggunaan Obat Injeksi ...48
Tabel 4.4 Presentase Distribusi Jumlah Pasien Berdasarkan Profil Penggunaan Obat Oral ...49
Tabel 4.5 Presentase Prevalensi Dosis Dibawah Dosis Terapi Berdasarkan Jumlah Pasien yang Mengalaminya ...50
Tabel 4.6 Presentase Distribusi Jumlah Dosis Dibawah Dosis Terapi ....50
Tabel 4.7 Presentase Prevalensi Dosis Diatas Dosis Terapi Berdasarkan Jumlah Pasien yang Mengalaminya ...50
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta xvi
Lampiran Halaman
Lampiran 1 ...70
Lampiran 2 ...72
Lampiran 3 ...75
Lampiran 4 ...108
Lampiran 5 ...124
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta xvii
CAD : Coronary Artery Disease
CHF : Congestive Heart Failure
CKD : Chronic Kidney Disease
Clcr : Clearance Creatinine
DM : Diabetes Melitus
DRP : Drug Related Problem
ESRD : End Stage of Renal Disease
GERD : Gastroesophagel Reflux Disease
GFR : Glomerulus Filtration Rate
GGK : Gagal Ginjal Kronik
HHD : Hypertention Heart Disease
HT : Hypertension
LFG : Laju Filtrasi Glomerulus
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
BAB I
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
Gagal ginjal kronik merupakan gangguan fungsi ginjal yang bersifat
progresif dan irreversibel. Gangguan fungsi ginjal ini terjadi ketika tubuh gagal
untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit
sehingga menyebabkan retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah.
Kerusakan ginjal ini mengakibatkan masalah pada kemampuan dan kekuatan
tubuh yang menyebabkan aktivitas kerja terganggu, tubuh jadi mudah lelah dan
lemas sehingga kualitas hidup pasien menurun (Brunner & Suddarth, 2001).
Didefinisikan sebagai gagal ginjal kronik jika pernah didiagnosis menderita
penyakit gagal ginjal kronik (minimal sakit selama 3 bulan berturut-turut) oleh
dokter. (Riskesdas, 2013).
Berdasarkan riset kesehatan Kementerian Kesehatan 2013, prevalensi gagal
ginjal kronik berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia sebesar 0,2 persen.
Prevalensi tertinggi di Sulawesi Tengah sebesar 0,5 persen, diikuti Aceh,
Gorontalo, dan Sulawesi Utara masing-masing 0,4 persen. Sementara Nusa
Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, dan Jawa Timur masing – masing 0,3 persen. (Riskesdas, 2013)
Gagal ginjal kronik ini berdasarkan wawancara yang didiagnosis dokter
meningkat seiring dengan bertambahnya umur, meningkat tajam pada kelompok
umur 35-44 tahun (0,3%), diikuti umur 45-54 tahun (0,4%), dan umur 55-74 tahun
(0,5%), tertinggi pada kelompok umur ≥75 tahun (0,6%). Prevalensi pada laki-laki (0,3%) lebih tinggi dari perempuan (0,2%), prevalensi lebih tinggi pada
masyarakat perdesaan (0,3%), tidak bersekolah (0,4%), pekerjaan wiraswasta,
petani/nelayan/buruh (0,3%), dan kuintil indeks kepemilikan terbawah dan
menengah bawah masing-masing 0,3 persen. (Riskesdas, 2013). Dari data yang
dikumpulkan oleh Indonesian Renal Registry (IRR) pada tahun 2007-2008
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diabetes melitus (23%), hipertensi (20%) dan ginjal polikistik (10%) (Roesli,
2008).
Gagal Ginjal dapat disebabkan beberapa faktor, beberapa diantara yaitu
usia, menurunnya masa ginjal, diabetes, hipertensi, dan beberapa penyakit lainnya
(Dipiro 6th). Ditambah lagi untuk pasien yang sudah berkomplikasi penyakitnya,
pasti membutuhkan obat terapi yang cukup banyak untuk mengatasi gejala
penyakitnya. Semakin banyak obat terapi yang digunakan pastinya akan
menimbulkan potensi adanya Drug Related Problems pada proses pengobatannya.
DRP (Drug Related Problems) didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang
tidak diinginkan atau risiko yang dialami oleh pasien, yang melibatkan atau
diduga melibatkan terapi obat (Strand et al., 1990). Terjadinya DRP dapat
mencegah atau menunda pasien dari pencapaian terapi yang diinginkan. Sebuah
DRP sebenarnya adalah peristiwa yang telah terjadi pada pasien, sedangkan DRP
potensial adalah suatu peristiwa yang mungkin sekali terjadi jika apoteker tidak
melakukan intervensi yang tepat (Nurhalimah, 2012).
Menurut Yahaya Hassan dkk. (2009), salah satu masalah DRP yang paling
penting pada pasien penyakit ginjal kronis (GGK) adalah kesalahan dosis obat.
Banyak obat dan metabolitnya yang dieliminasi melalui ginjal. Dengan demikian,
fungsi ginjal yang memadai penting untuk menghindari toksisitas. Pasien dengan
gangguan ginjal sering memiliki perubahan dalam parameter farmakokinetik dan
farmakodinamik. Oleh karena itu, pertimbangan khusus harus diambil ketika obat
ini diresepkan untuk pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Meskipun pentingnya
penyesuaian dosis pada pasien dengan CKD, penyesuaian tersebut kadang-kadang
diabaikan.
Stephanie et.al (2010), menemukan intervensi farmasi yang bersangkutan
dengan DRP indikasi tidak diobati (30%), dosis terlalu rendah (25,9%) dan dosis
terlalu tinggi (18,3%), pada pasien GGK di RS Universitas Grenoble. Hasil
penelitian Nurhalimah (2012) di RSUD dr MM Dunda Limboto, menunjukkan
bahwa ketidaksesuaian dosis pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani tahap
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (28,75%) diantaranya mengalami DRPs. Jumlah obat yang secara rutin diresepkan
untuk 7 pasien (sebagai subyek penelitian) terdapat 3 jenis obat, 2 obat mengalami
DRPs kategori tidak tepat dosis yaitu Allupurinol (85,71%) dan Nephrovit Fe
(14,28%).
Apoteker memegang peranan penting dalam peningkatan mutu pelayanan
kesehatan yang berorientasi. Sebagai seorang apoteker, peningkatan mutu
pelayanan ini dapat dilakukan melalui suatu proses pelayanan kefarmasian
(pharmaceutical care), yaitu merupakan suatu kegiatan yang terpadu dengan
tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan
masalah yang berhubungan dengan kesehatan (Anonim, 2004). Oleh karena itu,
peran seorang apoteker sangat penting dalam keberhasilan penatalaksanaan dan
pemberian terapi yang tepat, sehingga tidak menimbulkan Drug Related Problems
(DRPs). Dengan demikian diperlukan penelitian tentang keberhasilan
penatalaksanaan terapi obat melalui evaluasi DRPs untuk pasien gagal ginjal.
Berdasarkan paparan diatas, menunjukan bahwa pentingnya pemilihan obat
terutama pada pasien gagal ginjal kronik untuk menghindari atau menurunkan
angka terjadinya DRPs khususnya pada kategori penyesuaian dosis, sehingga
diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas layanan di Rumah Sakit
Pelabuhan Jakarta Utara agar tercapai suatu keberhasilan terapi.
1.2Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah yang
akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini :
1. Salah satu penyebab terjadinya Gagal Ginjal Kronik adalah penyakit
penyerta yang menunjang terjadinya penyakit Ginjal.
2. Banyaknya penyakit penyerta menyebabkan terjadinya pengobatan yang
kompleks
3. Pengobatan yang kompleks dapat menyebabkan terjadinya DRPs.
4. Salah satu DRPs yang paling penting pada pasien GGK adalah
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1.3Pertanyaan Penelitian
Bagaimana DRPs kategori penyesuaian dosis pada pasien Gagal Ginjal
Kronik di Instalasi Rawat Inap RS Pelabuhan Jakarta Utara pada tahun 2014, yang
ditinjau dari :
1. Dosis terlalu rendah (under dosage) ?
2. Dosis terlalu tinggi (over dosage) ?
1.4Tujuan Penelitian
1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengideintifikasi DRPs kategori
penyesuaian dosis pada pasien Gagal Ginjal Kronik yang di Rawat Inap di Rumah
Sakit Pelabuhan Jakarta Utara periode tahun 2014.
1.4.2 Tujuan Khusus
Mengetahui DRPs pada pengobatan pasien Gagal Ginjal Kronik yang
mendapat terapi obat di Instalasi Rawat Inap RS Pelabuhan Jakarta Utara periode
Januari-Juni 2014 yang ditinjau dari :
a. Dosis terlalu rendah (under dosage)
b. Dosis terlalu tinggi (over dosage)
1.5Manfaat Penelitian
1.5.1 Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu
pengetahuan, bagaimana cara mengevaluasi DRPs kategori penyesuaian dosis
pada pasien Gagal Ginjal Kronik di RS Pelabuhan
1.5.2 Metodologi
Metode dalam penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi DRPs
kategori penyesuaian dosis pada pasien Gagal Ginjal Kronik.
1.5.3 Aplikatif
Secara aplikatif hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu bahan
pertimbangan ataupun informasi bagi dokter, apoteker dan tenaga kesehatan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Drug Related Problems (DRPs)
Drug Related Probems (DRPs) merupakan peristiwa yang tidak diinginkan
yang dialami pasien yang memerlukan atau diduga memerlukan terapi obat dan
berkaitan dengan tercapainya tujuan terapi yang diinginkan. Identifikasi DRPs
menjadi fokus penilaian dan pengambilan keputusan terakhir dalam tahap proses
patient care (Cippole, Strand, Morley, 2004). Drug Related Problems (DRPs)
sering disebut juga Drug Therapy Problems atau masalah-masalah yang
berhubungan dengan obat. Kejadian DRPs ini menjadi masalah aktual maupun
potensial yang kental dibicarakan dalam hubungan antara farmasi dengan dokter.
Yang dimaksud dengan masalah aktual DRPs adalah masalah yang sudah terjadi
pada pasien dan farmasis harus berusaha menyelesaikannya. Masalah DRPs yang
potensial adalah suatu masalah yang mungkin menjadi risiko yang dapat
berkembang pada pasien jika farmasi tidak melakukan tindakan untuk mencegah
(Rovers, 2003). Jika DRPs aktual terjadi, farmasi sebaiknya mengambil suatu
tindakan untuk memecahkan masalah yang terjadi. Bila DRPs potensial terjadi
maka farmasis sebaiknya mengambil tindakan seperlunya saja untuk mencegah
masalah-masalah yang akan muncul (Roverse, 2003).Mengetahui hal tersebut
maka seorang farmasis memegang peran penting dalam mencegah maupun
mengendalikan masalah tersebut.
Ada beberapa hal yang termasuk dalam kategori penyebab timbulnya
permasalahan yang berhubungan dengan DRPs kategori ketidaktepatan
penyesuaian dosis (Cippole dkk, 2004).
1. Dosis terlalu rendah ( too low dosage)
Penyebab terjadinya ialah dosis terlalu rendah untuk menghasilkan respon
yang diinginkan, interaksi obat mengurangi jumlah ketersediaan obat yang
aktif, durasi obat terlalu singkat untuk menghasilkan respon yang
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tepat. Penyebab dosis rendah, seperti frekuensi pemberian dosis yang tidak
sesuai, jarak dan waktu pemberian terapi obat terlalu singkat,
penyimpanan obat yang tidak sesuai (misalnya, menyimpan obat di tempat
yang terlalu panas atau lembab, menyebabkan degradasi bentuk sediaan
dan dosis subterapi), pemberian obat yang tidak sesuai, dan interaksi obat
(Mahmoud, 2008).
2. Dosis terlalu tinggi (too high dosage)
Hal ini terjadi ketika dosis yang diberikan terlalu tinggi untuk memberikan
efek, dosis obat dinaikkan cepat, frekuensi pemberian, durasi terapi, cara
pemberian obat pada pasien yang tidak tepat, dan konsentrasi obat diatas
kisaran terapi (Strand, et al, 1998). Seorang pasien yang menerima dosis
obat yang terlalu tinggi dan mengalami efek toksik yang tergantung dosis
atau konsentrasi menunjukkan pasien mengalami DRPs (Cippole et.al
1998). Pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal, kemampuan ginjal
untuk menghilangkan obat-obatan dan metabolitnya menurun, yang
akhirnya menyebabkan akumulasi obat dan produk-produk beracun di
ginjal. Misalnya, jika dosis prokainamid tidak disesuaikan untuk pasien
dengan compromised-fungsi ginjal, N-acetylprocainamide dapat
terakumulasi dalam ginjal (Mahmoud, 2008).
3. Interaksi obat
Interaksi obat merupakan hasil interaksi dari obat dengan obat, obat
dengan makanan dan obat dengan laboratorium. Hal ini dapat terjadi pada
pasien yang menerima obat dari kelas farmakologis yang berbeda serta
dalam kelas farmakologis yang sama (Mahmoud, 2008).
2.2 Ginjal
Ginjal adalah suatu organ yang secara struktural kompleks dan telah
berkembang untuk melaksanakan sejumlah fungsi penting, seperti : ekskresi
produk sisa metabolisme, pengendalian air dan garam, pemeliharaan
keseimbangan asam yang sesuai, dan sekresi berbagai hormon dan autokoid.
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2.2.1 Anatomi & Fisiologi Ginjal
2.2.1.1Anatomi Ginjal
Ginjal merupakan organ berbentuk seperti kacang yang terletak di kedua
sisi kolumna vertebralis. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dibandingkan ginjal
kiri karena tertekan kebawah oleh hati. Kutub atasnya terletak setinggi iga
keduabelas, sedangkan kutub atas ginjal kiri terletak setinggi iga kesebelas.
(Julianti Aisyah, 2009)
Gambar 2.1 Anatomi Ginjal Tampak Depan
[Sumber : Adam.com]
Ginjal terletak di bagian belakang abdomen atas, di belakang peritoneum,
di depan dua iga terakhir, dan tiga otot besar-transversus abdominis, kuadratus
lumborum, dan psoas mayor. Ginjal dipertahankan dalam posisi tersebut oleh
bantalan lemak yang tebal. Ginjal terlindung dengan baik dari trauma langsung,
disebelah posterior (atas) dilindungi oleh iga dan otot-otot yang meliputi iga,
sedangkan di anterior (bawah) dilindungi oleh bantalan usus yang tebal Ginjal
kanan dikelilingi oleh hepar, kolon, dan duodenum, sedangkan ginjal kiri
dikelilingi oleh lien, lambung, pankreas, jejunum dan kolon. Struktur Ginjal
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2.2.1.2Struktur Makroskopik Ginjal
Pada orang dewasa , panjang ginjal adalah sekitar 12 sampai 13 cm (4,7
hingga 5,1 inci), lebarnya 6 cm (2,4 inci), tebalnya 2,5 cm (1 inci), dan beratnya
sekitar 150 gram. Secara anatomik ginjal terbagi dalam dua bagian, yaitu korteks
dan medula ginjal. Ginjal terdiri darai bagian dalam (medula) dan luar (korteks).
1. Bagian dalam (internal) medula. Substansia medularis terdiri dari piramid
renalis yang jumlahnya antara 18-16 buah yang mempunyai basis
sepanjang ginjal, sedangkan apeksnya mengahadap ke sinus renalis.
Mengandung bagian tubulus yang lurus, ansa henle, vasa rekta dan diktus
koligens terminal.
2. Bagian luar (eksternal) korteks. Substansia kortekalis berwarna coklat
merah, konsistensi lunak dan bergranula. Substansia ini tepat dibawah
tunika fibrosa, melengkung sapanjang basis piramid yang berdekatan
dengan garis sinus renalis, dan bagian dalam diantara piramid dinamakan
kolumna renalis. Mengandung glomerulus, tubulus proksimal dan distal
yang berkelok-kelok dan duktus koligens.
2.2.1.3Struktur Mikroskopik Ginjal
1. Nefron
Tiap tubulus ginjal dan glomerolusnya membentuk satu kesatuan (nefron).
Ukuran ginjal terutama ditentukan oleh jumlah nefron yang
membentuknya. Tiap ginjal manusia memiliki kira-kira 1.3 juta nefron.
Setiap nefron bisa membentuk urin sendiri. Karena itu fungsi satu nefron
dapat menerangkan fungsi ginjal.
2. Glomerulus
Setiap nefron pada ginjal berawal dari berkas kapiler yang disebut
glomerulus, yang terletak didalam korteks, bagian terluar dari ginjal.
Tekanan darah mendorong sekitar 120 ml plasma darah melalui dinding
kapiler glomerular setiap menit. Plasma yang tersaring masuk ke dalam
tubulus. Sel-sel darah dan protein yang besar dalam plasma terlalu besar
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 3. Tubulus kontortus proksimal
Berbentuk seperti koil longgar berfungsi menerima cairan yang telah
disaring oleh glomerulus melalui kapsula bowman. Sebagian besar dari
filtrat glomerulus diserap kembali ke dalam aliran darah melalui
kapiler-kapiler sekitar tubulus kotortus proksimal. Panjang 15 mm dan diameter
55 μm.
4. Ansa henle
Berbentuk seperti penjepit rambut yang merupakan bagian dari nefron
ginjal dimana, tubulus menurun kedalam medula, bagian dalam ginjal, dan
kemudian naik kembali kebagian korteks dan membentuk ansa. Total
panjang ansa henle 2-14 mm.
5. Tubulus kontortus distalis
Merupakan tangkai yang naik dari ansa henle mengarah pada koil longgar
kedua. Penyesuaian yang sangat baik terhadap komposisi urin dibuat pada
tubulus kontortus. Hanya sekitar 15% dari filtrat glomerulus (sekitar 20
ml/menit) mencapai tubulus distal, sisanya telah diserap kembali dalam
tubulus proksimal.
6. Duktus koligen medula
Merupakan saluran yang secara metabolik tidak aktif. Pengaturan secara
halus dari ekskresi natrium urin terjadi disini. Duktus ini memiliki
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gambar 2.2 Struktur Ginjal
[Sumber : medicalartlibrary.com]
2.2.1.4Fisiologi Ginjal
Fungsi ginjal menurut Price dan Wilson (2006) di bedakan menjadi dua
yaitu fungsi eksresi dan non ekskresi, antara lain:
a. Fungsi ekskresi
1. Mempertahankan osmolalitas plasma sekitar 285 osmol dengan
mengubah-ubah ekskresi air.
2. Mempertahankan volume ECF dan tekanan darah dengan
mengubah-ubah ekskresi Na+.
3. Mempertahankan konsentrasi plasma masing-masing elektrolit
individu dalam rentang normal.
4. Mempertahankan pH plasma sekitar 7,4 dengan mengeluarkan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 5. Mengekskresikan produk akhir nitrogen dari metabolisme protein
(terutama urea, asam urat dan kreatinin).
6. Bekerja sebagai jalur ekskretori untuk sebagian besar obat.
b. Fungsi non ekskresi
1. Menghasilkan renin: penting dalam pengaturan tekanan darah.
2. Menghasilkan eritropoetin: meransang produksi sel darah merah
oleh sumsum tulang.
3. Menghasilkan 1,25-dihidroksivitamin D3: hidroksilasi akhir
vitamin D3menjadi bentuk yang paling kuat.
4. Mengaktifkan prostaglandin: sebagian besar adalah vasodilator,
bekerja secara lokal, dan melindungi dari kerusakan iskemik ginjal.
5. Mengaktifkan degradasi hormon polipeptida.
6. Mengaktifkan insulin, glukagon, parathormon, prolaktin, hormon
pertumbuhan, ADH, dan hormon gastrointestinal (gastrin,
polipeptida intestinal vasoaktif (VIP).
Proses pembentukan urine menurut Syaifuddin (2006), glomerulus
berfungsi sebagai ultrafiltrasi pada simpai bowman, berfungsi untuk menampung
hasil filtrasi dari glomerulus. Pada tubulus ginjal akan terjadi penyerapan kembali
zat-zat yang sudah disaring pada glomerulus, sisa cairan akan diteruskan ke piala
ginjal berlanjut ke ureter.
Urin berasal dari darah yang dibawa arteri renalis masuk ke dalam ginjal,
darah ini terdiri dari bagian yang padat yaitu sel darah dan bagian plasma darah.
Ada tiga tahap pembentukan urin:
a. Proses filtrasi
Terjadi di glomerulus, proses ini terjadi karena permukaan aferen Lebih
besar dari permukaan eferen maka terjadi penyerapan darah. Sedangkan
sebagian yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan
yang tersaring ditampung oleh simpai Bowman yang terdiri dari glukosa,
air, natrium, klorida, sulfat, bikarbonat dll, yang diteruskan ke tubulus
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta b. Proses reabsorbsi
Pada proses ini terjadi penyerapan kembali sebagian besar glukosa,
natrium, klorida, fosfat, dan ion bikarbonat. Prosesnya terjadi secara pasif
yang dikenal dengan obligator reabsorbsi terjadi pada tubulus atas.
Sedangkan pada tubulus ginjal bagian bawah terjadi kembali penyerapan
natrium dan ion bikarbonat. Bila diperlukan akan diserap kembali ke
dalam tubulus bagian bawah. Penyerapanya terjadi secara aktif dikenal
dengan reabsorbsi fakultatif dan sisanya dialirkan pada papila renalis.
c. Proses sekresi
Sisanya penyerapan urine kembali yang pada tubulus dan diteruskan ke
piala ginjal selanjutnya diteruskan ke ureter masuk ke vesika urinaria.
2.2.2 Penilaian Fungsi Ginjal
Estimasi laju filtrasi glomerulus (LFG) sangat penting dalam manajemen
klinis pasien dengan penyakit ginjal kronik. LFG digunakan untuk menilai
keberadaan dan tingkat fungsi ginjal dan membantu dalam melakukan
penyesuaian dosis obat diekskresi melalui ginjal. Pedoman NKF-K/DOQI
merekomendasikan modifikasi diet pada penyakit ginjal (Modification of Diet in
Renal Disease/MDRD) dan persamaan Cockcroft-Gault sebagai pengukuran yang
berguna untuk memperkirakan LFG (Levey et al., 2002). Oleh karena itu,
kreatinin serum (SCr) tidak dapat digunakan sendiri untuk menilai tingkat fungsi
ginjal karena korelasi nonlinear antara SCr dan fungsi ginjal (Mahmoud, 2008).
2.2.2.1Persamaan Cockcroft-Gault
Persamaan Cockcroft-Gault berasal dari 249 pasien rawat inap (96%
laki-laki, rentang usia 18-92 tahun) dengan disfungsi ginjal ringan di Rumah Sakit
Queens Mary Veterans di Kanada berdasarkan pengukuran tunggal dari ClCr
(klirens kreatinin) 24 jam. Persamaan Cockcroft-Gault memberikan estimasi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1) Persamaan Cockcroft-Gault:
Laki-laki: ClCr (ml/min) =
Wanita: ClCr (ml/min) =
x 0,85
2) Persamaan Cockcroft-Gault disesuaikan dengan Luas Permukaan Tubuh
(Body Surface Area/BSA):
Laki-laki: ClCr (ml/min) =
Wanita: ClCr (ml/min) =
Keterbatasan Persamaan Cockcroft-Gault
Persamaan Cockcroft-Gault tergantung pada SCr, yang berhubungan dengan
sekresi tubular kreatinin. Hal ini dapat mengakibatkan estimasi LFG yang terlalu
tinggi sekitar 10 – 40% pada masing-masing orang dengan fungsi ginjal yang
normal (Levey et al., 2002). Selain itu, SCr dapat dipengaruhi oleh banyak faktor
non-ginjal seperti diet (misalnya, diet vegetarian dan suplemen kreatinin), massa
tubuh (misalnya, amputasi, kekurangan gizi, kekurusan) dan terapi obat
(misalnya, simetidin dan trimetoprim). Meskipun keterbatasan ini, persamaan
Cockcroft-Gault telah banyak digunakan untuk menentukan dosis obat pada
masing-masing orang berdasarkan fungsi ginjal pada pengaturan klinis
(Mahmoud, 2008).
2.2.2.2Persamaan MDRD
Persamaan MDRD diperkenalkan oleh Levey et al. pada tahun 1999 untuk
mengatasi keterbatasan estimasi LFG berdasarkan ClCr. Pada tahun 1999,
persamaan MDRD 6-variabel berasal dari populasi MDRD sebanyak 1.628 pasien
dengan gagal ginjal kronik tanpa diabetes (rata-rata LFG 40 ml/menit/1,73m2)
yang bersamaan memiliki pengukuran LFG menggunakan iothalamate
(Mahmoud, 2008). Persamaan ini dikembangkan menggunakan variabel pasien
termasuk usia, SCr, nitrogen urea darah (blood urea nitrogen/BUN), albumin, ras
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari persamaan MDRD berdasarkan hanya usia, jenis kelamin, ras dan tingkat SCr
yang diperkenalkan dan telah menjadi persamaan yang paling diterima dan
digunakan dalam pengaturan klinis rawat jalan, menggantikan persamaan MDRD
6-variabel dan persamaan Cockcroft-Gault (Mahmoud, 2008).
1) Estimasi LFG (MDRD 6-variabel)
eLFG = 170 x (SCr)–0,999 x (usia)–0,176 x (0,762 jika wanita) x (1,180 jika
orang Afrika Amerika) x (BUN)–0,170 x (Alb)+0,318
2) Estimasi LFG (MDRD 4-variabel)
eLFG = 186 x (SCr)–1,154 x (usia)–0,203 x (0,742 jika wanita) x (1,210 jika
orang Afrika Amerika)
Keterbatasan Persamaan MDRD
Estimasi LFG menggunakan persamaan MDRD mengakibatkan tidak
mempertimbangkan LFG sebenarnya pada orang sehat, donor ginjal, dan
pasien dengan DM tipe 1. Selain itu, 125I-iothalamate (LFGi) dilaporkan
lebih sesuai untuk mengukur kadar terbaru dari LFG dibandingkan dengan
persamaan MDRD pada pasien rawat inap dengan penyakit ginjal lanjut.
Persamaan MDRD belum divalidasi pada anak-anak, wanita hamil, orang
lanjut usia (> 70 tahun) atau ras selain Kaukasia dan Afrika Amerika
(Mahmoud, 2008).
2.3 Definisi Gagal Ginjal Kronik
Gagal Ginjal Kronik adalah hilangnya fungsi ginjal secara progresif
selama beberapa bulan sampai bertahun – tahun, ditandai dengan penggantian
bertahap struktur ginjal normal dengan fibrosis intertisial (DiPiro
pharmacotherapy 7th, 858). Keabnormalan struktur dan fungsi ginjal, yang
terjadi lebih dari 3 bulan dengan implikasi kesehatan. (KDIGO 2012 Clinical
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2.3.1 Etiologi Gagal Ginjal Kronik
Menurut DiPiro edisi 6, ada beberapa faktor yang menyebabkam
terjadinya GGK yaitu:
1. Faktor Kerentanan (individu)
Faktor ini dapat meningkatkan penyakit ginjal tetapi tidak secara langsung,
faktor – faktor ini termasuk :
Usia lanjut
Penurunan masa ginjal, dan BB kelahiran yang rendah Ras dan minoritas suku
Riwayat keluarga
Penghasilan rendah atau pendidikan Inflamasi sistemik
Dislipidemia
2. Faktor Inisiasi
Adalah faktor yang menginisiasi kerusakan ginjal, dapat diatasi dengan terapi
obat. Yang termasuk faktor inisiasi adalah :
Diabetes Melitus Hipertensi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 3. Faktor Progresi
Dapat mempercepat penurunan fungsi ginjal setelah inisiasi kerusakan ginjal.
Yang termasuk faktor progresi adalah :
Glikemia pada diabetes Hipertensi
Proteinuria Merokok Hiperlipidemia
2.3.2 Klasifikasi Gagal Ginjal Kronik
Klasifikasi GGK menurut KDIGO Clinical Practice Guideline for
Evaluation and Management of CKD 2012, klasifikasi GGK dibagi menjadi 3
kategori, yaitu :
2.3.2.1Kategori Penyebab
Tabel 2.1 Kategori Penyebab (KDIGO Clinical Practice Guideline for
Evaluation and Management of CKD, 2012)
Contoh penyakit
sistemik, yang
berpengaruh pada ginjal
Contoh gangguan primer
ginjal (tanpa ada penyakit
sistemik yang
berpengaruh pada ginjal)
Gangguan
Glomerulus
Diabetes, penyakit
autoimmun sistemik,
infeksi sistemik, obat -
obatan, neoplasia
(termasuk amyloidosis)
Difusi, fokal atau
proliferasi bulan sabit;
fokal dan
glomerusklerosis
tersegmentasi, nefropati
membran, mpenyakit yang
berganti – ganti
Gangguan
Tubulusinterstisial
Infeksi sistemik,
autoimmun,
sarkiodosis, obat -
obatan, asam urat, toxin
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta lingkungan (asam
aristolisik, sklerosis
sistemik
Gangguan Vaskular Arterosklerosis, HT,
iskemi, emboli
kolesterol, vaskulitik
sistemik, pembekuan
mikroangiopati,
sklerosis sistemik
Displasia fibromuskular,
ANCA-berhubungan
dengan vaskulitik terbaas
pada ginjal
Kista dan Penyakit
Bawaan
Polikista ginjal, sidrom
alport, penyakaait fabry
Displasia ginjal, kista
sumsum tulang belakang,
podositopati
Catatan : bahwa ada banyak cara yang berbeda di mana untuk
mengklasifikasikan CKD. Metode ini satu – satunya yang memisahkan
penyakit sistemik dan penyakit ginjal primer, yang diusulkan oleh
Kelompok Kerja, untuk membantu dalam pendekatan konseptual.
2.3.2.2Kategori GFR (Glomerulus Filtration Rate) / LFG (Laju Filtrasi
Glomerulus)
1. Stadium 1: kerusakan ginjal dengan LFG normal atau menurun, LFG
90 ml/min/1,73 m2
2. Stadium 2: kerusakan ginjal dengan penurunan LFG ringan, LFG 60 –
89 ml/min/1,73 m2
3. Stadium 3: penurunan LFG sedang (moderat), LFG 30 – 59
ml/min/1,73 m2
4. Stadium 4: penurunan LFG berat, LFG 15 – 29 ml/min/1,73 m2
5. Stadium 5: gagal ginjal, LFG < 15 ml/min/1,73 m2 atau dialisis
Catatan : Jika tidak menunjukan kerusakan ginjal, untuk stadium 1
dan 2 tidak memenuhi kriteria GGK (KDIGO Clinical Practice Guideline
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2.3.2.3Kategori Albuminuria
Tabel 2.2 Menurut Albuminuria (KDIGO Clinical Practice
Guideline for Evaluation and Management of CKD, 2012)
Kategori Laju Ekskresi
Albumin
(mg/24 jam)
Rasio Albumin
Kreatinin
Kondisi
(mg/mmol) (mg/g)
A1 <30 <3 <30 Meningkat
normal dan
perlahan
A2 30-300 3-30 30-300 Meningkat
secara
moderat*
A3 >300 >300 >300 Meningkat
dengan
parah**
Catatan : *relatif untuk tingkatan muda dan dewasa
**termasuk sindrom nefrotik (ekskresi albumin biasanya
>2200 mg/24 jam[Rasio albumin-kreatinin > 2220
mg/g;220 mg/mmol]).
Kategori albuminuria merupakan prediktor penting dari hasil.
Hubungan tingginya kadar proteinuria dengan tanda-tanda dan gejala
sindrom nefrotik sangat dikenali. Deteksi dan evaluasi kecil dari jumlah
proteinuria telah mendapatkan hasil yang signifikan. Beberapa penelitian
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2.3.3 Patofisiologi Gagal Ginjal
Patofisiologi penyakit ginjal kronik pada awalnya tergantung pada penyakit
yang mendasarinya. Pengurangan masa ginjal mengakibatkan hipertrofi struktural
dan fungsional nefron yang masih tersisa (surviving nephrons) sebagai upaya
kompensasi, yang diperantarai oleh molekul vasoaktif seperti sitokin dan growth
factors. Hal ini mengakibatkan terjadinya hiperfitrasi, yang diikuti oleh
peningkatan tekanan kapiler dan aliran darah glomerulus. Proses adaptasi
berlangsung singkat, akhirnya diikuti oleh proses maladaptasi berupa sklerosis
nefron yang masih tersisa. Proses ini akhirnya diikuti dengan penurunan fungsi
nefron yang progresif, walaupun penyakit dasarnya sudah tidak aktif lagi (Suwitra
dalam Sudoyo, 2006).
Fungsi renal menurun menyebabkan produk akhir metabolisme protein
(yang normalnya diekskresikan ke dalam urin) tertimbun dalam darah. Akibatnya
terjadi uremia dan mempengaruhi setiap sistem tubuh. Semakin banyak timbunan
produk sampah, maka gejala akan semakin berat (Smeltzer dan Bare, 2002).
Retensi cairan dan natrium akibat dari penurunan fungsi ginjal dapat
mengakibatkan edema, gagal jantung kongestif/ CHF, dan hipertensi. Hipertensi
juga dapat terjadi karena aktivitas aksis renin angiotensin dan kerjasama keduanya
meningkatkan sekresi aldosteron. CKD juga menyebabkan asidosis metabolik
yang terjadi akibat ginjal tidak mampu mensekresi asam (H-) yang berlebihan.
Asidosis 19 metabolik juga terjadi akibat tubulus ginjal tidak mampu mensekresi
ammonia (NH3-) dan mengabsorpsi natrium bikarbonat (HCO3).
Pada stadium paling dini penyakit GGK, terjadi kehilangan daya cadangan
ginjal (ranal reserve), pada keadaan mana basal Laju Filtrasi Glomerulus (LFG)
masih normal. Kemudian secara perlahan tapi pasti, akan terjadi penurunan fungsi
nefron, yang ditandai dengan peningkatan kadar urea dan kretinin serum. Sampai
pada LFG sebesar 60%, pasien belum menunjukkan keluhan (asimtomatik), tetapi
sudah terjadi peningkatan kadar urea dan kreatinin serum. Sampai pada LFG 30%,
mulai terjadi keluhan pasien seperti nokturia, badan lemah, nafsu makan
berkurang, penurunan berat badan. Sampai pada LFG di bawah 30%, pasien
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta peningkatan tekanan darah, gangguan metabolisme fosfor dan kalsium, mual
muntah dan lain sebagainya. Pada LFG dibawah 15% akan terjadi gejala dan
komplikasi yang lebih serius, dan pasien sudah memerlukan terapi pengganti
ginjal antara lain dialisis atau transplantasi ginjal (Suwitra, 2006).
2.3.3.1Protokol Pasien Gagal Ginjal Kronik
Gambar 2.3 Mekanisme Progresi Gangguan Gagal Ginjal Kronik
Perkembangan dan progresi GGK tersembunyi. Pasien dengan
stadium 1 dan 2 biasanya tidak mempunyai gejala atau ketidak seimbangan
cairan metabolik yang terlihat pada stadium 3 sampai 5, seperti anemia,
hiperparatiroid sekunder, penyakit kardiovaskular, malnutrisi dan
keabnormalan cairan elektrolit yang umum pada fungsi ginjal. Gejala
uremia umumnya tidak menyertai oada stadium 1 dan 2, minimal selama
stadium 3 dan 4, dan umumnya pada stadium 5 yang juga terbiasa gatal –
gatal, alergi dingin, peningkatan berat badan, dan neforpati periferal.
Pengobatan bertujuan untuk menunda progresi GGK, dan meminimalisisr
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2.3.3.2Pengobatan Progresi dengan Modifikasi Terapi
1. Terapi non farmakologi :
Diet rendah protein (0,6 sampai 0,7 g/kg/hari) dapat
menunda progresi dari GGKpada pasien dengan atau tanpa
diabetes, walaupun efeknya relati kecil. (DiPiro, 7th ed)
2. Terapi Farmakologi :
Hiperglikemia :
a. Terapi intensif pada pasien tipe 1 dan 2 diabetes
mengurangi komplikasi mikrovaskular, termasuk
nefropaty. Dapat berupa insulin oral dan tes gula darah
setidaknya 3 kali sehari
b. Insulin (Inten Novita, 2015)
1. Farmakologi
Insulin merupakan hormon anabolik dan
antikatabolik, yang berperan utama pada protein,
karbohidrat, dan metabolisme. Insulin endogen
diproduksi dari proinsulin peptida pada sel β.
2. Karakteristik
Insulin biasanya dikategorikan berdasarkan
sumbernya, kekuatan, onset dan durasi kerja. Selain
itu insulin memiliki asam amino dalam molekul
insulin termodifikasi. Sediaan insulin biasanya
U-100 dan U-500, U-100 unit/mL dan 500 unit/mL.
3. Farmakokinetik
Kinetik injeksi subkutan tergantung pada onset,
puncak, dan durasi kerja. Penambahan protamin
NPH, NPL, dan suspense protamin aspart) atau
kelebihan seng maka dapat menunda onset, puncak,
dan durasi efek insulin.
Waktu paruh injeksi insulin reguler (IV) yaitu 9
menit. Sehingga wkatu efektif untuk injeksi insulin
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta insulin lainnya. Insulin terdegradasi di hati, otot,
dan ginjal. Insulin dimetabolisme dihati sekitar 20%
- 50%, sedangkan dimetabolisme di ginjal sekitar
25% - 20%. Sehingga tidak dianjurkan untuk pasien
menggunakan insulin jika terdapat penyakit ginjal
stadium akhir.
4. Komplikasi mikrovaskular
Insulin telah terbukti sebagai agen oral untuk
mengobati DM. Penelitian di Amerika telah
membuktikan bahwa efikasi antara insulin dan
sulfonilurea menunjukkan efikasi yang sama dalam
penurunan mikrovaskular.
5. Komplikasi makrovaskular
Hubungan antara masalah tingginya kadar insulin
(hiperinsulinemia), resistensi insulin, dan
kardiovaskular sehingga dapat dipercayai bahwa
terapi insulin dapat menyebabkan komplikasi
makrovaskular. Namun UKPDS dan DCCT tidak
menemukan hubungan antara komplikasi
makrovaskular dengan terapi insulin.
6. Efek samping
Secara umum efek samping insulin yaitu
hipoglikemia dan kenaikan berat badan.
Hipoglikemia lebih sering terjadi pada pasien yang
instensif melakukan terapi, dan lebih sering terjadi
pada pasien DM tipe 1 daripada tipe2. Sehingga
pemantauan kadar glukosa darah sangat penting
dilakukaan pada pasien yang menggunakan terapi
insulin. Jika pasien telah mengalami hipoglikemia
yang berat maka akan terjadi takikardia dan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 7. Dosis dan cara pemberian
Pada pasien DM tipe 1, dosis seharinya 0,5-0,6
unit/kg. Selama penyakit akut atau ketosis resistensi
insulin maka dapat diberikan dosis yang lebih
tinggi. Dosis diberikan tergantung dengan keadaan
patologi pasien.
c. Progresi GGK dapat dibatasi dengan kontrol optimal
hiperglikemia dan hipertensi.
Hipertensi :
a. Kontrol tekanan dara secara adekuat dapat mengurangi
laju penurunan GFR dan albuminuria dengan pasien
atau tanpa diabetes
b. Obat antihipertensi harus dimulai pada pasien diateik
ataupun nondiabetik dengan ACEI atau angiotensin II.
Nondyhydropyridine dan CCB untuk pilihan kedua
c. Klirens ACEI direduksi pada pasien GGK
d. GFR yang biasanya menurun 25 % sampai 30 % pada 3
sampai 7 hari setelah ACEI karena tipe ini
e. Pilihan Utama Obat Antihipertensi pada Pasien GGK :
(Intan Mustika, 2009)
1. ACE Inhibitor
ACE inhibitor menghambat perubahan angiotensin I
menjadi angiotensin II sehingga terjadi vasodilatasi
dan penurunan sekresi aldosteron. Selain itu,
degradasi bradikinin juga dihambat sehingga kadar
bradikinin dalam darah meningkat dan berperan
dalam efek vasodilatasi ACE-Inhibitor. Vasodilatasi
secara langsung akan menurunkan tekanan darah,
sedangkan berkurangnya aldosteron akan
menyebabkan ekskresi air dan natrium dan retensi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diindikasikan untuk hipertensi dengan penyakit
ginjal kronik.
2. Angiotensin Reseptor Blocker
Dengan mencegah efek angiotensin II, senyawa -
senyawa ini merelaksasi otot polos sehingga
mendorong vasodilatasi, meningkatkan ekskresi
garam dan air di ginjal, menurunkan volume plasma,
dan mengurangi hipertrofi sel. Antagonis reseptor
angiotensin II secara teoritis juga mengatasi
beberapa kelemahan ACE inhibitor.
f. Pilihan Kedua Obat Antihipertensi pada Pasien GGK :
1. CCB (Calcium Channel Blocker)
Calcium Channel Blocker bukanlah agen lini
pertama tetapi merupakan obat antihipertensi yang
efektif, terutama pada ras kulit hitam. Calcium
Channel Blocker mempunyai indikasi khusus untuk
yang beresiko tinggi penyakit koroner dan diabetes,
tetapi sebagai obat tambahan atau pengganti.
Penelitian NORDIL menemukan diltiazem
ekuivalen dengan diuretik dan penyekat beta dalam
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gambar 2.4 Strategi pengobatan untuk mencegah progresi gagal ginjal
kronik pada pasien diabetes
Terapi Penunjang :
a. Diet Protein, pengobatan hilang lemak, kurang merokok,
manajemen anemia dapat memperlambat laju progresi
GKK.
b. Tujuan utama dari pengobatan megnurangi lemak pada
GGK untuk mengurangi resiko untuk arteosklrosis
c. Tujuan kedua untuk mereduksi proteinuria dan penurunan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gambar 2.5 Strategi pengobatan untuk mencegah progresi gagal ginjal
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gambar 2.6 Algoritma manajemen Hipertensi untuk pasien GGK.
Penyesuaian dosis haru dibuat setiap 2 sampai 4 minggu sesuai kebutuhan.
Dosis salah satu obat harus dimaksimalkan sebelum yang lainnya
ditambahkan. (ACEI, angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB,
angiotensin receptor blocker; BP, blood pressure; CCB, calcium channel
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2.3.4 Terapi Pengganti Ginjal
Terapi pengganti ginjal dilakukan pada penyakit ginjal kronik stadium 5,
yaitu pada LFG kurang dari 15 ml/menit. Terapi tersebut dapat berupa
hemodialisis, dialisis peritoneal, dan transplantasi ginjal. (Suwitra, 2006).
2.3.4.1Hemodialisis
Tindakan terapi dialisis tidak boleh terlambat untuk mencegah gejala toksik
azotemia, dan malnutrisi. Tetapi terapi dialisis tidak boleh terlalu cepat pada
pasien GGK yang belum tahap akhir akan memperburuk faal ginjal (LFG).
Tindakan terapi dialisis tidak boleh terlambat untuk mencegah gejala toksik
azotemia, dan malnutrisi. Tetapi terapi dialisis tidak boleh terlalu cepat pada
pasien GGK yang belum tahap akhir akan memperburuk faal ginjal (LFG).
Indikasi tindakan terapi dialisis, yaitu indikasi absolut dan indikasi elektif.
Beberapa yang termasuk dalam indikasi absolut, yaitu perikarditis,
ensefalopati/neuropati azotemik, bendungan paru dan kelebihan cairan yang tidak
responsif dengan diuretik, hipertensi refrakter, muntah persisten, dan Blood
Uremic Nitrogen (BUN) > 120 mg% dan kreatinin > 10 mg%. Indikasi elektif,
yaitu LFG antara 5 dan 8 mL/menit/1,73m², mual, anoreksia, muntah, dan astenia
berat (Sukandar, 2006).
Hemodialisis di Indonesia dimulai pada tahun 1970 dan sampai sekarang
telah dilaksanakan di banyak rumah sakit rujukan. Umumnya dipergunakan ginjal
buatan yang kompartemen darahnya adalah kapiler-kapiler selaput semipermiabel
(hollow fibre kidney). Kualitas hidup yang diperoleh cukup baik dan panjang
umur yang tertinggi sampai sekarang 14 tahun. Kendala yang ada adalah biaya
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2.3.4.2Jenis – Jenis Hemodyalizer(Rahmanto Bagyo, 2011)
1. Mesin NIPRO Tipe Suridial ™-55PLUS
Surdial 55 plus mudah untuk digunakan sebagai mesin dialisis
menawarkan kepada pasien terapi pengganti ginal, untuk meningkatkan
kualitas hidup pasien. Mesin ini bersifat efisien yang
mengkombinasikan teknologi terdepan dengan fitur – fitur baru yang
canggih untuk improvisasi dalam pengobatan.
Gambar 2.7 Mesin Dialisis NIPRO
2. Mesin Fresenius
Mesin dialsis modern dari 2008, 4008, dan 5008 seri dari Fresenius
Medical Care membantuk nefrologis untuk menawarkan pengobatan
terbaik yang memungkinkan untuk pasiennya. Lebih dari setiap mesin
dialisa terjual di dunia tiap tahunnya dari 2 perusahaan situs Schweinfurt,
Jerman dan Walnut Geek, California. Mesin dialisa terbaru 5008 sistem
terapi, memenangkan German Business Inovation Award in 2006. 5008
sendiri mengatur bagiannya dengan interfase khusus mudah dipakai dan
rendah perawatan sebaik mungkin rendah air dan energi yang digunakan.
Bahkan, sistem terapi 5008 menawarkan hemodiafiltrasi online sebagain
pilihan standarnya. Ini menjadi pengobatan terbaik yang memungkinkan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gambar 2.8 Mesin Dialisis Fresenius
3. Mesin Nikisso
Terbaru ini Nikisso mengenmbangkan Sistem hemodialisa DBB-07
dengan memenuh kualitas terapi. Biaya terapi yang mirip dengan sistem
dialisa yang standard, mesin ini dapat menawarkan setiap dari pasien
terapi yang terbaik tanpa tambahan biaya. Layar pengguna yang ramah
identik yang dapat menawarakan seri mesin DBB, ditambah lagi untuk
capt dan mudah dipelajarinya sistem mesin ini.
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2.3.4.3Dialisis Peritoneal
Akhir-akhir ini sudah populer Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis
(CAPD) di pusat ginjal di luar negeri dan di Indonesia. Indikasi medik CAPD,
yaitu pasien anak-anak dan orang tua (umur lebih dari 65 tahun), pasien-pasien
yang telah menderita penyakit sistem kardiovaskular, pasien-pasien yang
cenderung akan mengalami perdarahan bila dilakukan hemodialisis, kesulitan
pembuatan AV shunting, pasien dengan stroke, pasien GGT (gagal ginjal
terminal) dengan residual urin masih cukup, dan pasien nefropati diabetik disertai
co-morbidity dan co-mortality. Indikasi non-medik, yaitu keinginan pasien
sendiri, tingkat intelektual tinggi untuk melakukan sendiri (mandiri), dan di
daerah yang jauh dari pusat ginjal (Sukandar, 2006).
2.3.4.4Transplantasi Ginjal
Transplantasi ginjal merupakan terapi pengganti ginjal (anatomi dan faal).
Pertimbangan program transplantasi ginjal, yaitu:
1. Cangkok ginjal (kidney transplant) dapat mengambil alih seluruh (100%) faal
ginjal, sedangkan hemodialisis hanya mengambil alih 70-80% faal ginjal
alamiah
2. Kualitas hidup normal kembali
3. Masa hidup (survival rate) lebih lama
4. Komplikasi (biasanya dapat diantisipasi) terutama berhubungan dengan obat
imunosupresif untuk mencegah reaksi penolakan
5. Biaya lebih murah dan dapat dibatasi
2.4 Rumah Sakit
Rumah sakit adalah suatu organisasi yang kompleks, menggunakan
gabungan alat ilmiah hususnya dan rumit, dan difungsikan oleh berbagai kesatuan
personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medis
modern yang semuanya terikat bersama-sama dalam maksud yang sama, untuk
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Rumah Sakit Umum pemerintah pusat dan daerah diklasifikasikan menjadi
rumah sakit A,B,C, dan D. klasifikasi tersebut didasarkan pada unsur pelayanan
ketenagaan fisik dan peralatan. Klasifikasi Rumah Sakit Umum pemerintah :
1. Rumah sakit umum kelas A adalah rumah sakit umum yang mempunyai
fasilitas dan kemampuan yang pelayanan medis spesialitik luas dan
subspesialitik luas.
2. Rumah sakit umum kelas B adalah rumah sakit umum yang mampunyai
fasilitas dan kemampuan fasilitas pelayanan medis sekurang-kurangnya
11 spesialis dan subspesialis terbatas.
3. Rumah sakit umum kelas C adalah rumah sait yang mempunyai fasilitas
dan kemampuan pelayanan medik dasar spesialitik dasar.
4. Rumah sakit umum kelas D adalah rumah sakit umum yang mempunyai
fasilitas dan kemampuan medik dasar (Siregar dan Lia, 2003).
Jenis perawatan yang diadakan di Rumah Sakit:
1. Perawatan penderita rawat tinggal
Dalam perawatan pendeirta rawat tinggal di rumah sakit ada lima unsur
tahap pelayanan yaitu:
a. Perawatan intensif adalah perawatan bagi penderita kesakitan hebat
yang memerlukan pelayanan khusus selama waktu krisis kesakitannya
atau lukanya, suattu ondisi apabila ia tida mampu melakukan
kebutuhan sendiri. Ia dirawat dalam ruangan perawatan intensif oleh
staf medik dan perawatan khusus.
b. Perawatan intermediet adalah perawatan bagi penderita setelah kondisi
kritis membaik, yang dipindahkan dari ruang perawatan intensif ke
ruang perawatan biasa. Perawatan intermediet merupakan bagian
terbesar dari jenis perawatan dikebanyakan rumah sakit.
c. Perawatan swarawat adalah perawatan yang dilakukan penderita yang
dapat merawat diri sendiri, yang datang ke rumah sakit untuk
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari kesakitan intensif atau intermediet, dapat tinggal dalam suatu unit
perawatan sendiri (self-care unit).
d. Perawatan kronis adalah perawatan penderita dengan kesakitan atau
ketidakmampuan jasmani jangka panjang. Mereka dapat tinggal dalam
bagian terpisah rumah sakit atau dalam fasilitas perawatan tambahan
atau rumah perawatan yang juga dapat dioperasikan oleh rumah sakit.
e. Perawatan rumah adalah perawatan penderita dirumah yang dapat
menerima layanan seperti biasa tersedia dirumah sakit, dibawah suatu
program yang disponsori oleh rumah sakit. Perawatan rumah ini adalah
penting tetapi sangat sedikit yang diterapkan. Perawatan rumah ini
lebih mudah, dan merupakan jenis perawatan yang efektif secara
psikologis.
5. Perawatan penderita Rawat Jalan
Perawatan ini diberikan pada penderita melalui klinik, yang menggunakan
fasilitas rumah sakit tanpa terikat secara fisik dirumah sakit. Mereka
datang kerumah sakit untuk pengobatan atau untuk diagnosis atau datang
sebagai kasus darurat (Siregar dan Lia, 2003).
2.4.1 Pelayanan Farmasi Klinik di Rumah Sakit
Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan
Apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan
meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena Obat, untuk tujuan
keselamatan pasien (patient safety) sehingga kualitas hidup pasien (quality of life)
terjamin. (PermenKes no. 58 tahun 2014).
Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi :
a) pengkajian dan pelayanan Resep;
b) penelusuran riwayat penggunaan Obat;
c) rekonsiliasi Obat;
d) Pelayanan Informasi Obat (PIO);
e) konseling;
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta g) Pemantauan Terapi Obat (PTO);
h) Monitoring Efek Samping Obat (MESO);
i) Evaluasi Penggunaan Obat (EPO);
j) dispensing sediaan steril; dan
k) Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD)
2.5 Rekam Medik
Setiap rumah sakit dipersyaratkan mengadakan dan memelihara rekam medik
dan memadai dari setiap penderita, baik untuk penderita rawat tinggal maupun
penderita rawat jalan. Rekam medik ini harus secara akurat didokumentasikan,
segera tersedia, dapat dipergunakan, mudah ditelusuri kembali (retrieving) dan
lengkap informasi. Rekam medik adalah sejarah ringkas, jelas, dan akurat dari
kehidupan dan kesakitan penderita, ditulis dari sudut pandang medik.
Definsi rekam medik menurut surat keputusan Direktur jenderal pelayanan
medik adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas,
anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan tindakan dan pelayanan lain yang
diberikan kepada seorang penderita selama dirawat dirumah sakit, baik rawat jalan
maupun rawat tinggal (Siregar dan Lia, 2003).
Kegunaan dari rekam medik :
a) Digunakan sebagai dasar perencanaan berkelanjutan perawatan
penderita.
b) Merupakan suatu sarana komunikasi antar dokter dan setiap
professional yang berkontribusi pada perawatan penderita.
c) Melengkapi bukti dokumen terjadinya atau penyebab kesakitan atau
penderita dan penanganan atau pengobatan selama tiap tinggal di
rumah sakit.
d) Digunakan sebagai dasar untuk kajian ulang studi dan evaluasi
perawatan yang diberikan kepada pasien.
e) Membantu perlindungan kepentingan hukum penderita, rumah sakit
dan praktisi yang bertanggung jawab.
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta g) Sebagai dasar perhitungan biaya, dengan menggunakan data rekam
medik, bagian keuangan dapat menetapkan besarnya biaya pengobatan