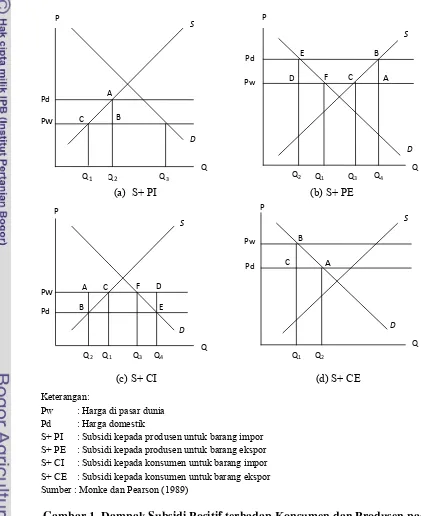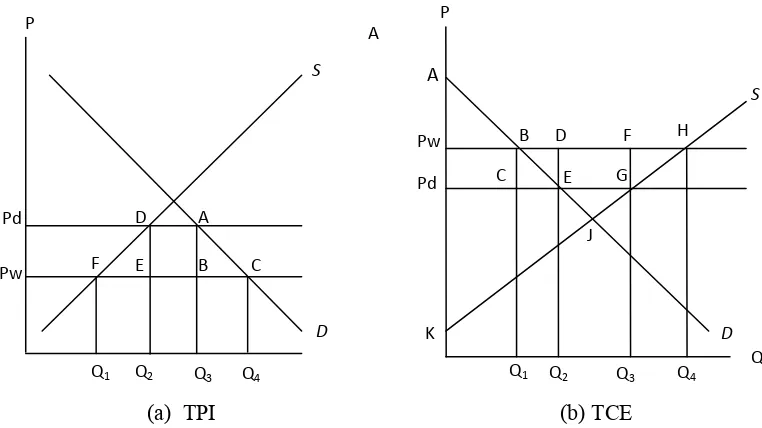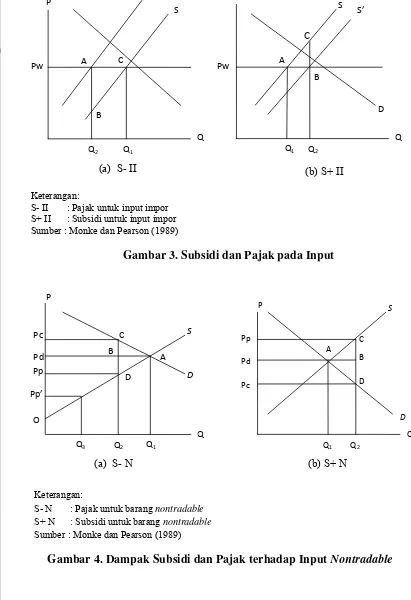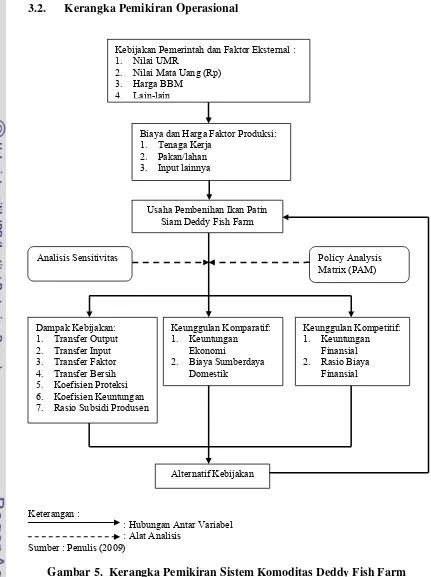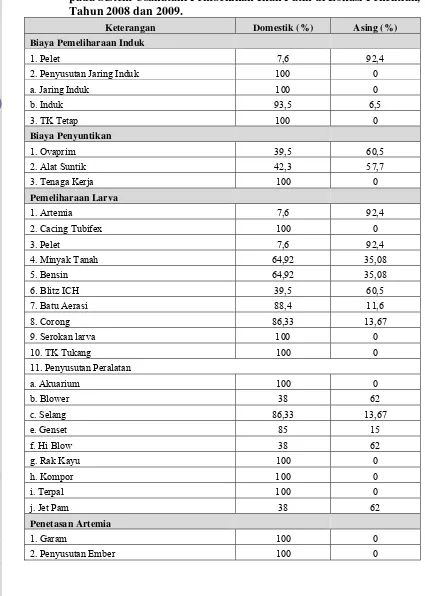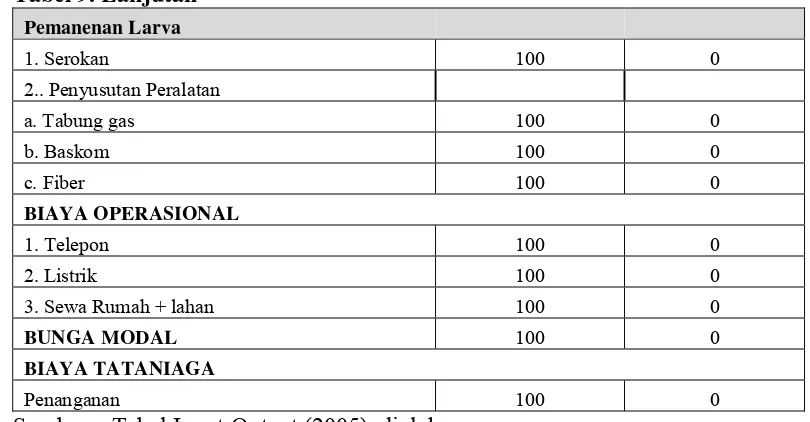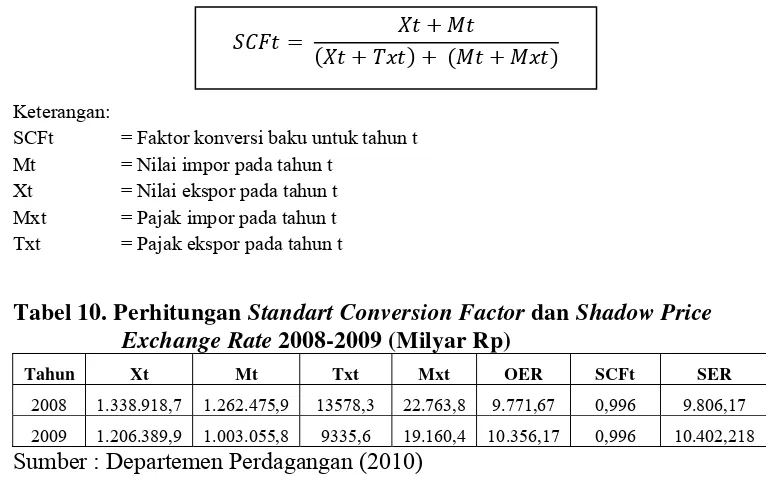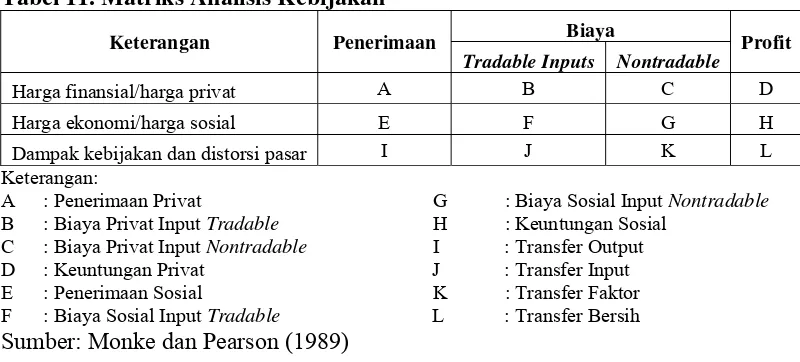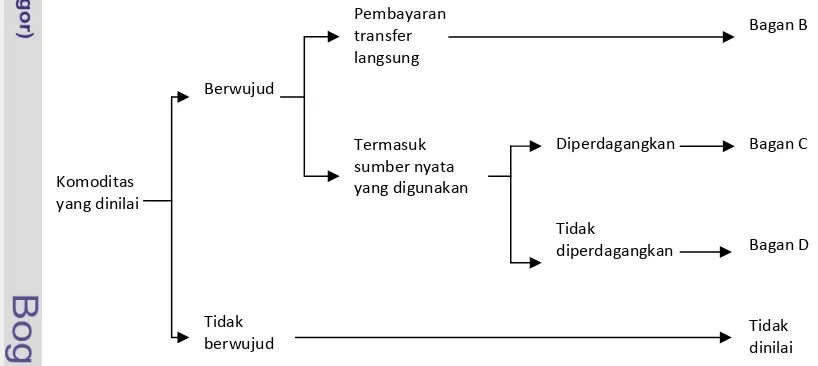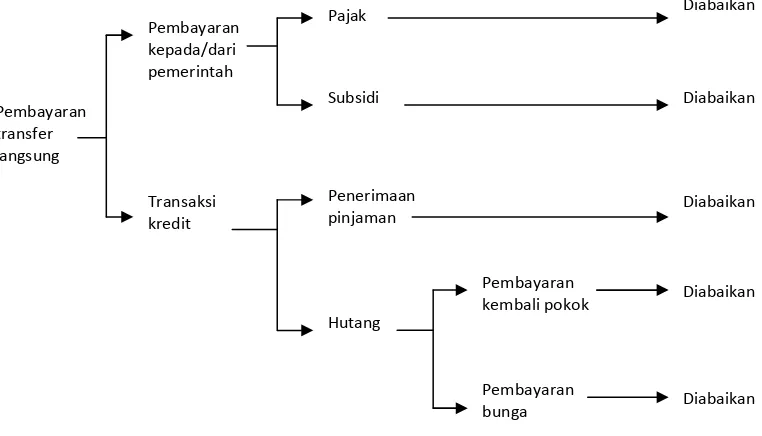PERNYATAAN
RINGKASAN
INTAN DYAH MASTUTI. Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Usaha Pembenihan Ikan Patin Siam (Studi Kasus : Perusahaan Deddy Fish Farm). Dibimbing oleh NOVINDRA.
Tahun 2005, pemerintah merencanakan program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dengan tujuan untuk mengoptimalkan hasil produksi sebagai salah satu langkah mengatasi krisis perikanan tahun 2002. Salah satu komoditas yang menjadi unggulan yaitu ikan patin. Akan tetapi pada kenyataannya, program revitalisasi tersebut belum mampu meningkatkan ekspor patin. Indonesia masih kalah saing dengan Vietnam dalam hal kuantitas output maupun efisiensi biaya produksi. Melihat dari kenyataan tersebut, maka pemerintah memiliki target untuk mewujudkan Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar tahun 2015. Salah satu cara untuk mencapai target tersebut yaitu dengan meningkatkan pengadaan benih patin sebagai upaya untuk meningkatkan ekspor patin.
Deddy Fish Farm merupakan salah satu pihak yang berperan dalam pengadaan benih ikan patin. Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas, muncul tantangan-tantangan yang dihadapi DFF. Tantangan itu antara lain munculnya pesaing baru dan inflasi. Melihat kenyataan tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah DFF memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga layak untuk diusahakan serta menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah dan faktor eksternal lainnya terhadap usaha pembenihan patin DFF. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis keunggulan komparatif dan kompetitif usaha pembenihan patin DFF serta menganalisis kebijakan pemerintah dan faktor eksternal lainnya terhadap keunggulan komparatif dan kompetitif DFF.
Hasil analisis matriks kebijakan menunjukkan bahwa usaha pembenihan ikan patin Deddy Fish Farm memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif baik pada tahun 2008 maupun 2009. Hal ini dilihat dari nilai PP dan SP yang positif, serta PCR dan DRC yang kurang dari satu. Akan tetapi, dalam kurun waktu tersebut ditunjukkan bahwa baik keunggulan komparatif maupun kompetitif mengalami penurunan. Selanjutnya dapat disimpulkan juga bahwa pada tahun 2008 usaha pembenihan ikan patin memiliki keunggulan kompetitif lebih tinggi dibandingkan keunggulan komparatif, sedangkan tahun 2009 menunjukkan hal sebaliknya. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2008 nilai PCR lebih kecil dibandingkan DRC karena biaya sosial produksi lebih besar dibandingkan biaya finansialnya. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemeritah berjalan efektif sehingga keunggulan kompetitif lebih tinggi daripada keunggulan komparatif. Nilai PCR yang lebih besar dari nilai DRC pada tahun 2009 menunjukkan hal sebaliknya, bahwa kebijakan yang ada tidak berjalan efektif sehingga pengorbanan untuk mendapatkan satu satuan output pada analisis privat lebih besar dibandingkan analisis sosial.
ANALISIS KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KOMPETITIF
USAHA PEMBENIHAN IKAN PATIN SIAM
(Studi Kasus : Perusahaan Deddy Fish Farm)
INTAN DYAH MASTUTI
DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
serta analisis gabungan. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa naiknya UMR 7%, naiknya harga input 4%, menurunnya harga output 20%, dan pengurangan subsidi BBM akan menurunkan keunggulan kompetitif. Penurunan keunggulan kompetitif terbesar ditunjukkan pada analisis sensitivitas jika harga privat benih patin menurun sebesar 20%. Adapun hasil analisis sensitivitas dengan melemahnya nilai tukar 6% membuat keunggulan komparatif mengalami penurunan.
Hasil analisis gabungan menunjukkan bahwa penurunan keunggulan kompetitif yang disebabkan oleh naiknya UMR 7%, naiknya harga input 4%, dan menurunnya harga output 20% dapat ditanggulangi dengan kebijakan pemerintah berupa penghapusan PPN pakan sebesar 10% dan adanya kelembagaan yang berfungsi sebagai penampung benih. Hal itu dapat dilihat dari penurunan nilai PCR. Sedangkan penurunan keunggulan komparatif yang disebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dapat ditanggulangi dengan kebijakan pemerintah yang berupa kelembagaan seperti koperasi.
ANALISIS KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KOMPETITIF
USAHA PEMBENIHAN IKAN PATIN SIAM
(Studi Kasus : Perusahaan Deddy Fish Farm)
INTAN DYAH MASTUTI H44052122
Skripsi
Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
Judul Skripsi : Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Usaha Pembenihan Ikan Patin Siam (Studi Kasus : Perusahaan Deddy Fish Farm
Nama : Intan Dyah Mastuti NRP : H44052122
Menyetujui, Dosen Pembimbing
Novindra, SP.
NIP. 19811102 200701 1 001
Mengetahui, Ketua Departemen,
Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT. NIP. 19660717 199203 1 003
RIWAYAT HIDUP
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi Rabbil ‘alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang merupakan salah satu persyaratan kelulusan pada Program Sarjana Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Tugas akhir ini mengambil judul Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Usaha Pembenihan Ikan Patin Siam (Studi Kasus : Perusahaan Deddy Fish Farm).
Penelitian ini berisi analisis mengenai apakah suatu usaha memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif. Penelitian ini juga memaparkan bagaimana analisis dilakukan dengan metode-metode yang sudah ada. Penulis berharap, isi penelitian ini bisa menjadi masukan bagi pembaca, pengambil kebijakan, dan para pengusaha.
Sebagaimana manusia yang tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk penulis pribadi. Selain itu, penulis juga mengharapkan masukan-masukan agar karya ilmiah ini dapat menjadi lebih baik.
Jazakumullah khairan katsiira.
Bogor,
Januari, 2011
UCAPAN TERIMAKASIH
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini, antara lain kepada:
1. Allah SWT, karena dengan rahmat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orangtua tercinta, Ayahanda Masum B.A almarhum dan Ibunda Marwiyah atas segala doa, kasih sayang, dan dukungan baik moral maupun spiritual yang telah diberikan selama ini, serta kepada kelima kakak tercinta yang selalu memberi semangat kepada penulis.
3. Bapak Novindra, SP. yang senantiasa dengan penuh ketekunan dan kesabaran membimbing penulis hingga selesainya penulisan karya ilmiah ini serta atas kesediaan beliau menjadi moderator dan dosen penguji dalam sidang skripsi. 4. Bapak Ir. Ujang Sehabudin dan Bapak Rizal Bahtiar S.Pi, M.Si. atas kesediaan
beliau menjadi dosen penguji dalam sidang skripsi.
5. Bapak Deddy sebagai pemilik perusahaan Deddy Fish Farm dan kepada seluruh pegawai Deddy Fish Farm atas izin dan bantuan kepada penulis selama penelitian.
6. Adhieputra, Riyant, Ais, Novi, Pipit, Ira, Rista, dan teman-teman seperjuangan lain yang yang selalu memberi dukungan kepada penulis selama penelitian ini. 7. Mi-Chan, Oreo, Maze, Onji, Titin, Mong-Mong, Lala, Tete, Tenina, Bon-Bon,
8. Tak lupa rasa terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar ESL yang selama ini menjadi tempat afiliasi penulis serta kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi besar selama pengerjaan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
Bogor, Januari 2011
DAFTAR ISI
2.1.1. Klasifikasi dan Jenis-Jenis Ikan Patin ... 12
2.1.2. Ciri Fisik ... 13
2.1.10.Kebijakan Pemerintah terhadap Komoditas Ikan Patin .... 19
2.2. Kajian Penelititan terdahulu ... 20
III.KERANGKA PEMIKIRAN ... 22
3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis 22
3.1.1. Kebijakan Pemerintah ... 22
3.1.1.1. Kebijakan Pemerintah terhadap Output ... 24
3.1.1.2. Kebijakan Pemerintah terhadap Input ... 28
3.1.2. Tinjauan Konseptual Keunggulan Komparatif dan Kompetitif ... 31
3.1.2.1. Keunggulan Komparatif ... 31
3.1.2.2. Keunggulan Kompetitif ... 33
3.1.2.3. Hubungan Keunggulan Komparatif dan Kompetitif dengan Analisis Kelayakan Finansial dan Ekonomi ... 33
3.1.3. Policy Analysis Matrix (Matriks Analisis Kebijakan) ... 34
3.1.4. Analisis Sensitivitas ... 35
3.2. Kerangka Pemikiran Operasional ... 37
IV.METODE PENELITIAN ... 39
4.3. Metode Pengolahan dan Analisis Data ... 40
4.3.1. Metode Pengolahan Data ... 40
4.3.2. Metode Analisis Data . ... 40
4.4.Penentuan Input dan Output ... 41
4.4.1. Alokasi Biaya ke dalam Komponen Domestik dan Asing . 42 4.4.2. Penentuan Harga Bayangan Input Output ... 45
4.5. Policy Analysis Matrix (PAM) ... 52
4.5.1. Perhitungan Analisis PAM ... 53
4.5.2. Pengambilan Keputusan untuk Menentukan Nilai Ekonomi ... 59
4.6. Analisis Sensitivitas ... 62
V. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ... 64
5.1. Sejarah Lokasi ... 64
5.2. Struktur Organisasi ... 65
5.3. Deskripsi Produk, Konsumen, dan Rantai Pemasaran ... 67
5.4. Fasilitas Pembenihan ... 68
5.5.2.6. Pengamatan Perkembangan Telur dan Larva ... 75
5.5.3. Pemeliharaan Larva ... 76
VI.ANALISIS KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KOMPETITIF USAHA PEMBENIHAN IKAN PATIN SIAM DEDDY FISH FARM ... 83
6.1. Analisis Keuntungan ... 84
6.1.1. Analisis Keuntungan Privat ... 84
6.1.2. Analisis Keuntungan Sosial ... 85
6.2. Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif ... 86
6.2.1. Rasio Biaya Privat (PCR) ... 86
6.3. Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah ... 87
6.3.1. Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Output ... 87
6.3.1.1. Transfer Output (OT) ... 87
6.3.1.2. Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO) ... 88
6.3.1.3. Tingkat Proteksi Output Nominal (NPRO) ... 88
6.3.2. Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Input ... 88
6.3.2.1. Transfer Input (IT) ... 88
6.3.2.2. Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI) ... 89
6.3.2.3. Nilai Tingkat Proteksi Input Nominal (NPRI) ... 89
6.3.2.4. Transfer Faktor (FT) ... 89
6.3.3. Dampak Kebijakan Pemerintah pada Input dan Output ... 90
6.3.3.1. Koefisien Proteksi Efektif (EPC) ... 90
6.3.3.2. Tingkat Proteksi Efektif (EPR) ... 90
6.3.3.3. Koefisien Proteksi (PC) ... 90
6.3.3.4. Transfer Bersih (NT) ... 91
6.3.3.5. Rasio Subsidi Produsen (SRP) ... 91
VII. ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PADA KOMODITAS BENIH IKAN PATIN ... 92
7.1. Kerangka Skenario Perubahan Harga Input dan Output ... 92
7.2. Analisis Sensitivitas pada Keunggulan Komparatif dan Kompetitif ... 92
7.2.1. Analisis Sensitivitas bila terjadi Kenaikan Upah Tenaga Kerja ... 92
7.2.2. Analisis Sensitivitas bila terjadi Kenaikan Harga Input 93
7.2.3. Analisis Sensitivitas bila Nilai Tukar terhadap Dollar Amerika Melemah ... 94
7.2.4. Analisis Sensitivitas bila Terjadi Penurunan Harga Privat Komoditas Benih Ikan Patin ... 95
7.2.5. Analisis Sensitivitas bila Terjadi Kenaikan Harga BBM ... 96
7.2.6. Analisis Sensitivitas bila PPN Pakan Ikan sebesar 10% Dihapuskan ... 97
DAFTAR TABEL
Nomor Halaman
1. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Menurut
Komoditas, 2002-2005 (Ton) ... 2
2. Rencana Pengembangan Patin 2006-2009 . ... 3
3. Hasil Produksi Ikan Patin 2005-2009 (Ton) . ... 4
4. Produksi Ikan Patin Menurut Wilayah Tahun 2005-2007 (Ton) . .. 4
5. Hasil Produksi Ikan Patin Budidaya di Pulau Jawa Tahun 2005-2007 (Ton) ... 4
6. Volume dan Nilai Impor Tepung Ikan Indonesia ... 5
7. Hasil Produksi Benih Patin Kabupaten Bogor ... 7
8. Klasifikasi Kebijakan Harga Komoditas ... 22
9. Alokasi Biaya Produksi ke dalam Komponen Domestik dan Asing pada Sistem Usahatani Pembenihan Ikan Patin di Lokasi Penelitian, Tahun 2008 dan 2009 ... 43
10. Perhitungan Standart Conversion Factor dan Shadow Price Exchange Rate 2008-2009 (Milyar Rp) ... 52
11. Matriks Analisis Kebijakan ... 53
12. Matriks Analisis Kebijakan Pembenihan Ikan Patin DFF tahun 2008 (Rp/Tahun) ... 83
13. Matriks Analisis Kebijakan Pembenihan Ikan Patin DFF tahun 2009 (Rp/Tahun) ... 83
14. Indikator-indikator dari Policy Analysis Matrix ... 84
15. Analisis Sensitivitas Usaha Pembenihan Ikan Patin dengan Kenaikan UMR Sebesar 7% (Rp/Tahun) ... 93
16. Analisis Sensitivitas Usaha Pembenihan Ikan Patin dengan Kenaikan Harga Input Sebesar 4% (Rp/Tahun) ... 94
17. Analisis Sensitivitas Usaha Pembenihan Ikan Patin jika Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika Melemah Sebesar 6% (Rp/Tahun) ... 95
18. Analisis Sensitivitas Usaha Pembenihan Ikan Patin dengan Penurunan Harga Privat Benih Patin Sebesar 20% (Rp/Tahun) ... 96
19. Analisis Sensitivitas Usaha Pembenihan Ikan Patin dengan Kenaikan Harga Premium 40% dan Minyak Tanah 200% (Rp/Tahun) ... 97
21. Analisis Sensitivitas Usaha Pembenihan Ikan Patin dengan Peran Kelembagaan – Pengaruhnya pada Harga Privat Benih (Rp/Tahun) ... 98 22. Analisis Sensitivitas Usaha Pembenihan Ikan Patin dengan Peran
Kelembagaan - Pengaruhnya pada Harga Sosial Input Sebesar
10% (Rp/Tahun) ... 99 23. Analisis Sensitivitas Gabungan – Pengaruh pada Harga Privat
(Rp/Tahun) ... 100 24. Analisis Sensitivitas Gabungan – Pengaruh pada Harga Sosial
DAFTAR GAMBAR
Nomor Halaman
1. Dampak Subsidi Positif terhadap Konsumen dan Produsen pada
Barang Ekspor dan Impor ... 26
2. Restriksi Perdagangan pada Barang Impor ... 27
3. Subsidi dan Pajak pada Input ... 30
4. Dampak Subsidi dan Pajak terhadap Input Nontradable ... 30
5. Kerangka Pemikiran Sistem Komoditas Deddy Fish Farm ... 37
6. Bagan A. Diagram Pengambilan Keputusan untuk Menentukan Nilai Ekonomi : Langkah-langkah Utama ... 60
Bagan B. Diagram Pengambilan Keputusan untuk Menentukan Nilai Ekonomi : Pembayaran Transfer Langsung ... 61
Bagan C. Diagram Pengambilan Keputusan untuk Menentukan Nilai Ekonomi : Komoditas yang Diperdagangkan. ... 61
Bagan D. Diagram Pengambilan Keputusan untuk Menentukan Nilai Ekonomi : Komoditas yang Tidak Diperdagangkan. ... 62
7. Struktur Organisasi Deddy Fish Farm ... 66
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Halaman
1. Matriks Analisis Kebijakan Pembenihan Ikan Patin DFF Tahun
2009 (Analisis Sensitivitas UMR Naik 7%) ... 109
2. Matriks Analisis Kebijakan Pembenihan Ikan Patin DFF Tahun 2009 (Analisis Sensitivitas Harga Input Naik 4%) ... 109
3. Matriks Analisis Kebijakan Pembenihan Ikan Patin DFF Tahun 2009 (Analisis Sensitivitas Nilai Tukar Melemah 6%) ... 109
4. Matriks Analisis Kebijakan Pembenihan Ikan Patin DFF Tahun 2009 (Analisis Sensitivitas Harga Output Turun 20%) ... 109
5. Matriks Analisis Kebijakan Pembenihan Ikan Patin DFF Tahun 2009 (Analisis Sensitivitas Harga Premium Naik 40% dan Minyak Tanah naik 200%) ... 109
6. Matriks Analisis Kebijakan Pembenihan Ikan Patin DFF Tahun 2009 (Analisis Sensitivitas PPN Pakan Dihapuskan 10%) ... 110
7. Matriks Analisis Kebijakan Pembenihan Ikan Patin DFF Tahun 2009 (Analisis Sensitivitas Kelembagaan – Pengaruhnya pada Harga Privat Benih) ... 110
8. Matriks Analisis Kebijakan Pembenihan Ikan Patin DFF Tahun 2009 (Analisis Kelembagaan – Pengaruhnya pada Harga Sosial Input) ... 110
9. Matriks Analisis Kebijakan Pembenihan Ikan Patin DFF Tahun 2009 (Analisis Sensitivitas Gabungan – Pengaruhnya pada Harga Privat) ... 110
10. Matriks Analisis Kebijakan Pembenihan Ikan Patin DFF Tahun 2009 (Analisis Sensitivitas Gabungan - Pengaruhnya pada Harga Sosial) ... 110
11. Indikator-indikator dari Policy Analysis Matrix ... 111
12. Struktur Biaya Produksi DFF Tahun 2008 (Rp) ... 113
13. Struktur Biaya Produksi DFF Tahun 2009 (Rp) ... 115
14. Struktur Biaya Finansial dan Ekonomi Deddy Fish Farm (Rp) ... 117
15. Perhitungan Harga Sosial (Paritas Impor) Induk Patin ... 119
16. Perhitungan Harga Sosial (Paritas Impor) Artemia Tahun 2008 ... 119
17. Perhitungan Harga Sosial (Paritas Impor) Artemia Tahun 2009 ... 119
18. Perhitungan Harga Sosial (Paritas Impor) Garam Tahun 2008 ... 120
19. Perhitungan Harga Sosial (Paritas Impor) Garam Tahun 2009 ... 120
I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Selama ini pasokan ikan dunia termasuk Indonesia sebagian besar berasal
dari penangkapan ikan di laut. Akan tetapi, pemanfaatan sumberdaya tersebut di
sejumlah negara dan perairan internasional saat ini dilaporkan telah berlebih. Data
FAO 2002 (DKP, 2005) menunjukkan bahwa pasokan ikan dari kegiatan
penangkapan di laut oleh sebagian negara, diperkirakan tidak dapat ditingkatkan
lagi. Demikian pula kecenderungan ini terjadi pada usaha penangkapan ikan di
perairan Indonesia. Oleh karena itu, alternatif pemasok hasil perikanan diharapkan
berasal dari perikanan budidaya (akuakultur).
Akuakultur bermula dari penerapan teknologi yang sangat sederhana dan
hanya sebagai subsisten (sampingan). Akhir abad 20, akselerasi perkembangan
perikanan budidaya menunjukkan kecenderungan industrialisasi dengan
penerapan teknologi maju. Perikanan budidaya bukan lagi budidaya konvensional,
tetapi kegiatan ekonomi dengan manajemen modern yang berimplikasi besar pada
berbagai sektor. Produk akualkultur telah membawa perubahan besar bagi industri
pangan yaitu menawarkan pasokan yang konsisten, tingkat harga yang relatif
rendah, dan jenis produk yang lebih sesuai dengan selera konsumen baik dari segi
jumlah maupun mutu (DKP, 2005).
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman
hayati laut tertinggi di dunia yang mendukung akuakultur (Soegiarto dan Polunin,
1981 dalam DKP, 2005). Kelompok ikan yang ada di perairan Indonesia lebih dari
2000 spesies. Potensi lahan perikanan budidaya secara nasional diperkirakan
pemanfaatannya belum dilakukan secara maksimal. Masing-masing baru
mencapai 10,1% untuk budidaya air tawar, 40% untuk budidaya air payau, dan
0,01% untuk budidaya laut (DKP, 2005).
Melihat dari kenyataan tersebut, maka pada tahun 2005, pemerintah
merencanakan program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
Program tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan hasil produksi
salah satunya pada bidang perikanan. Upaya revitalisasi di bidang perikanan
khususnya berupa pengembangan akuakultur.
Salah satu komoditas yang menjadi sasaran revitalisasi tersebut yaitu ikan
patin. Komoditas tersebut menjadi salah satu unggulan dalam revitalisasi
perikanan budidaya karena merupakan jenis ikan yang teknologi budidayanya
sudah dikuasai dan sudah berkembang di masyarakat. Selain itu, komoditas patin
memiliki peluang pasar ekspor yang tinggi dan tingkat serapan pasar dalam negeri
yang cukup besar, tingkat permodalan yang relatif rendah, dan penyerapan tenaga
kerja yang cukup tinggi (DKP, 2005). Data produksi ikan patin dan ikan lainnya
di Indonesia dari tahun 2002 dapat dilihat pada Tabel 1.
Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa produksi perikanan didominasi
oleh rumput laut, bandeng, dan udang. Hasil produksi ikan patin masih jauh lebih
rendah dari rumput laut, bandeng, udang maupun dari beberapa ikan lainnya. Oleh
karena itu, pemerintah bermaksud meningkatkan hasil produksi patin mulai dari
tahun 2006 hingga 2009. Rencana pemerintah dalam peningkatan produksi patin
ditunjukkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Rencana Pengembangan Patin 2006-2009
Parameter 2005 Tahun
2006 2007 2008 2009
Produksi (ton) 16.500 20.000 25.300 30.300
· Lokal 14.850 18.000 20.240 24.240
· Ekspor 1.650 2.000 5.060 6.060
Kebutuhan Benih (x1000 ekor) 55.000 66.670 84.300 101.000
Kebutuhan Induk (ekor) 5.500 6.670 8.430 10.100
Sumber: DKP (2005)
Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa pemerintah menginginkan agar
produksi ikan patin terus meningkat dari tahun ke tahun baik untuk konsumsi
masyarakat (lokal) maupun ekspor. Caranya tentu saja melalui peran akuakultur
dalam meningkatkan jumlah produksi ikan. Peran akuakultur di sini termasuk
usaha budidaya pembenihan. Hal itu dapat dilihat dari target kebutuhan benih dari
tahun 2006 sampai 2009 yang semakin meningkat sejalan dengan target
peningkatan produksi ikan patin.
Berdasarkan target pemerintah yang digambarkan dalam Tabel 2, pada
kenyataannya menunjukkan kenaikan produksi patin sesuai dengan yang
diharapkan. Kenaikan produksi bahkan jauh lebih tinggi dari perkiraan. Hal ini
Tabel 3. Hasil Produksi Ikan Patin 2005-2009 (Ton)
Jenis Ikan Tahun Kenaikan Rata-rata
(%) 2005 2006 2007 2008 2009*)
Patin - Catfish 32.575 31.489 36.755 102.021 132.600 55,23 * Data Sementara
Sumber : DKP (2009)
Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil produksi ikan patin secara nasional
rata-rata menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil produksi
memperlihatkan bahwa program revitalisasi pemerintah untuk meningkatkan
produksi ikan patin tercapai. Tabel 4 menunjukkan kuantitas produksi tiap
wilayah di Indonesia.
Tabel 4. Produksi Ikan Patin Menurut Wilayah Tahun 2005-2007 (Ton)
Wilayah 2005 2006 2007
Sumatera 20.224 16.992 15.990
Jawa 5.503 7.808 11.532
Bali-Nusa Tenggara 2 - 3
Kalimantan 6.840 6.687 9.231
Sulawesi 6 3 -
Total 32.575 31.489 36.755
Sumber : DKP (2007)
Tabel 5. Hasil Produksi Ikan Patin Budidaya di Pulau Jawa Tahun 2005-2007 (Ton)
Wilayah Hasil Produksi
2005 2006 2007
Tabel 4 menunjukkan produksi terbesar dihasilkan di pulau Sumatera
diikuti oleh Kalimantan dan Jawa. Hasil produksi patin tiap wilayah rata-rata
diperlihatkan pada Tabel 5. Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil produksi ikan patin
terbesar dihasilkan di Jawa Barat.
1.2. Perumusan Masalah
Program revitalisasi pemerintah dalam bidang perikanan yang
menunjukkan peningkatan ternyata tidak menjamin ekspor patin meningkat.
Indonesia memang mengembangkan ekspor ke negara-negara lain seperti Timur
Tengah, tapi untuk ekspor ke Amerika dan Eropa lebih rendah dibandingkan
Vietnam. Kebutuhan di dalam negeri juga belum dapat dipenuhi oleh sistem
budidaya yang ada1.
Penyebab Indonesia kalah saing dengan Vietnam yaitu karena harga ikan
patin di dalam negeri cukup tinggi misalnya tahun 2008 sekitar Rp 11.000/kg
sedangkan dari Vietnam hanya Rp 9.000/kg. Mahalnya harga patin di Indonesia
karena tingginya biaya produksi yang salah satunya disebabkan karena harga
pakan yang tinggi. Hal itu karena tepung ikan sebagai bahan baku pembuat pakan
ikan (pelet) masih diimpor dari negara lain2. Volume impor tepung ikan di
Indonesia ditunjukkan oleh Tabel 6.
Tabel 6. Volume dan Nilai Impor Tepung Ikan Indonesia
Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 Total
Volume (Ton) 82.788 88.852 55.685 67.596 42.521 337.442
Nilai (US$) 54.953 76.527 49.923 42.401 24.732 248.536
Sumber : DKP (2009)
Tabel 6 menunjukkan bahwa volume impor terbesar terjadi pada tahun
2005 dan 2006. Mulai tahun 2007, Indonesia sudah mulai menurunkan impor
tepung ikan. Hal ini karena sepanjang 2007, sebanyak 70% dari kebutuhan tepung
ikan sudah bisa dipenuhi oleh tepung ikan lokal. Para pengolah tepung ikan lokal
1
telah mampu meningkatkan produksi dan kualitas tepung ikan yang
dihasilkannya.
Indonesia juga kalah saing dengan Vietnam dalam hal kuantitas produksi
patin. Tahun 2008 Vietnam mampu menghasilkan 1,2 juta ton ikan patin dan
mengekspor 633.000 ton ke 107 negara di dunia3. Angka ini jauh lebih besar
dibandingkan hasil produksi patin Indonesia yang pada tahun 2008 hanya
mencapai 102.021 ton.
Melihat dari kenyataan tersebut, pemerintah memiliki target untuk
mewujudkan Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar
tahun 2015. Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan perikanan
budidaya sebagai ujung tombak penghasil produk perikanan untuk mewujudkan
target tersebut4. Salah satu produk ikan yang diandalkan yaitu ikan patin.
Direktur Pemasaran Luar Negeri, Ditjen P2HP DKP Saut Parulian Hutagalung
mengatakan, ikan patin merupakan komoditas yang sangat prospektif untuk
dikembangkan, selain permintaannya tinggi di dalam negeri, patin juga
merupakan salah satu komoditas budidaya air tawar yang mempunyai pasar yang
sangat bagus di Uni Eropa, Amerika Serikat, Eropa Timur, dan Timur Tengah5.
Salah satu cara untuk mencapai target tersebut yaitu dengan menekan
ongkos produksi akibat mahalnya harga pakan. Pemerintah berencana
membangun pabrik baru untuk memproduksi pakan ikan. Pakan itu berbahan baku
maggot kelapa sawit, bukan tepung ikan yang saat ini digunakan. Pemerintah
mengharapkan dengan melakukan substitusi bahan baku itu, harga pakan ikan
dapat ditekan hingga 10-20% dari harga saat ini. Selain itu pemerintah akan
3
http:// www.globefish.org/ diakses tanggal 3 Mei 2010 4
meningkatkan inovasi teknologi sektor perikanan, khususnya teknologi pengadaan
bibit atau benih unggul dan teknik budidaya, guna mengejar target pertumbuhan
produksi perikanan6.
Berkaitan dengan pengadaan benih, salah satu sentra produksi benih ikan
patin yang potensial di Jawa Barat yaitu Kabupaten Bogor. Hal ini dibuktikan
dengan banyaknya pengusaha pembesaran ikan patin atau pengusaha ikan patin
konsumsi yang berasal dari luar daerah yang membeli benih ikan patin dari
Kabupaten Bogor karena kualitas benih yang relatif baik dibandingkan daerah lain
seperti Sumatera7. Tingkat mortalitas benih patin dari Bogor juga relatif rendah,
kurang dari 0,02%8. Hasil produksi benih patin Kabupaten Bogor ditunjukkan
pada Tabel 7. Tabel 7 menunjukkan bahwa hasil produksi benih di Kabupaten
Bogor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Tabel 7. Hasil Produksi Benih Patin Kabupaten Bogor
Tahun Hasil produksi (ekor)
2006 37.394.810 2007 58.126.000
2008 79.893.000 Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor (2010)
Salah satu daerah pembenihan ikan patin di Kabupaten Bogor yaitu
Ciampea. Petani pembenihan di Ciampea salah satunya aitu Deddy Fish Farm
(DFF). Selain pembenihan patin, DFF juga menekuni pembenihan ikan lainnya
seperti ikan hias sebagai usaha sampingan. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun
1999. Selama ini produk DFF sudah dipasarkan ke berbagai daerah baik Jawa
maupun luar Jawa seperti Solo, Palembang, dan Banjarmasin. Berdasarkan
rata-rata jumlah benih yang dihasilkan yang mencapai hampir 2 juta dan larva
6
http://www.indonesia.go.id/ diakses tanggal 17 Juli 2010 7
mencapai 600.000 per tahun, DFF mengambil peran yang cukup besar dalam
peningkatan produksi patin di Indonesia.
Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas serta berkembangnya
isu-isu internasional akhir-akhir ini, muncul tantangan-tantangan yang dihadapi
dalam pengembangan usaha akuakultur, termasuk DFF sendiri. Tantangan itu
antara lain: (1) perdagangan global yang sangat kompetitif, (2) ketatnya syarat
mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh negara pengimpor, dan (3) iklim
usaha yang kurang kondusif terutama mengenai jaminan kepastian dan keamanan
usaha. Beberapa permasalahan lain juga dihadapi oleh DFF seperti munculnya
pesaing baru dan inflasi.
Awalnya daerah Bogor Barat merupakan sentra penampungan benih ikan
patin, kemudian muncul calon sentra baru yaitu Parung yang mengakibatkan
bertambahnya saingan bagi DFF. Produsen patin di Parung menggunakan tenaga
kerja berpengalaman (dulunya petani ikan lele), sedangkan DFF menggunakan
tenaga kerja belum berpengalaman. Dengan menggunakan tenaga kerja
berpengalaman, produksi benih patin di Parung lebih efisien daripada DFF.
Sebagai akibatnya, jika benih ikan dijual dengan harga yang sama, pengusaha ikan
patin di Parung mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan DFF.
Salah satu strategi DFF untuk menghadapi persaingan ini yaitu dengan
meningkatkan kualitas benih ikan yang dihasilkan. Hal itu dilakukan DFF dengan
cara memproduksi ikan dengan warna yang lebih jernih sehingga tingkat
mortalitas ikan lebih rendah dibandingkan dengan warna ikan yang kurang jernih.
Daya tumbuh benih ikan yang diproduksi DFF mencapai 90%, sedangkan yang di
tinggi. Selain itu, DFF mampu menghasilkan benih dengan ukuran yang seragam
sedangkan petani di Parung masih menghasilkan benih dengan ukuran tidak
seragam.
DFF mampu menghadapi persaingan dengan petani ikan di parung dengan
keunggulan yang dimiliki. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, petani
pembenihan patin di Parung semakin mampu menghasilkan benih patin dengan
kualitas seperti benih patin hasil produksi DFF. Petani pembenihan di Parung
mampu menghasilkan benih dengan ukuran yang lebih seragam dan lebih besar
dibandingkan dengan ukuran benih yang dihasilkan DFF. Akibatnya, DFF
menghadapi persaingan yang semakin sulit.
Inflasi juga berpengaruh terhadap usaha DFF. Inflasi di Indonesia yang
berfluktuasi mengakibatkan harga-harga input cenderung meningkat tiap tahunnya
sedangkan harga jual benih ikan dari tahun ke tahun cenderung stabil bahkan
saat-saat tertentu harga benih turun. Hal ini berdampak pada keuntungan riil yang
diperoleh tidak sebesar keuntungan riil saat inflasi sedang rendah.
Kebijakan pemerintah di bidang pertanian khususnya perikanan yang
diterapkan selama ini diharapkan bisa menciptakan iklim yang kondusif bagi
usaha agribisnis perikanan terutama usaha pembenihan ikan patin. Akan tetapi,
kebijakan pemerintah tersebut seringkali mengakibatkan perbedaan harga input
maupun output yang diterima produsen dan konsumen yang berdampak pada
besar keuntungan yang diperoleh. Pemberlakuan PPN pada barang input misalnya,
akan membuat harga barang menjadi semakin mahal. PP Nomor 7 tahun 2007,
ternyata tidak diberlakukan sebagaimana mestinya. Pakan ikan masih dikenai PPN
sehingga harganya tetap mahal.
Keuntungan yang diperoleh suatu usaha agribisnis akan menentukan
apakah usaha tersebut memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang
berdampak pada kelangsungan usaha. Banyak bidang usaha yang memiliki
keunggulan kompetitif jika perhitungan biaya dan keuntungan didasarkan pada
harga pasar. Akan tetapi jika perhitungan didasarkan pada harga sosial, maka
belum tentu setiap perusahaan memiliki keunggulan komparatif. Misalnya, saat
inflasi sedang cukup tinggi, apakah DFF masih memiliki keunggulan kompetitif
maupun komparatif dibandingkan saat inflasi sedang rendah.
Berdasarkan uraian di atas, perumusan masalah yang dikaji dalam
penelitian ini yaitu:
1) Bagaimanakah keunggulan komparatif dan kompetitif dari pengusahaan benih
patin.
2) Bagaimanakah dampak perubahan kebijakan pemerintah dan faktor lainnya
terhadap keunggulan komparatif dan kompetitif pengusahaan benih ikan patin.
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari
penelitian ini yaitu:
1) Menganalisis keunggulan komparatif dan kompetitif pengusahaan benih ikan
patin Deddy Fish Farm.
2) Menganalisis dampak perubahan kebijakan pemerintah dan faktor lainnya
1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1) Bagi para peneliti, diharapkan penelitian ini dapat digunakan dalam
pengembangan ilmu pertanian khususnya perikanan.
2) Bagi perusahaan yang bersangkutan (DFF), penelitian ini dapat memberikan
informasi yang berguna dalam melakukan evaluasi dan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan.
3) Rujukan bagi peneliti yang ingin melakukan studi lainnya yang berhubungan
dengan perikanan, terutama perikanan budidaya.
1.5. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Deddy Fish Farm, sebuah perusahaan
agribisnis yang bergerak di bidang pembenihan ikan patin yang berlokasi di
Ciampea. Ciampea merupakan salah satu daerah yang banyak terdapat petani
pembenihan ikan patin dan DFF merupakan salah satu perusahaan yang cukup
baik dalam menghasilkan benih patin sehingga dapat mewakili
perusahaan-perusahaan pembenihan patin lainnya di daerah Bogor. Komoditas yang diteliti
yaitu benih ikan patin yang merupakan hasil produksi DFF. Kualitas benih patin
yang dihasilkan oleh DFF termasuk baik, dilihat dari rendahnya tingkat mortalitas
II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Gambaran Umum Ikan Patin
Gambaran umum berisi mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan
ikan patin. Diantaranya klasifikasi ikan patin, jenis, ciri fisik, kandungan gizi, dan
pemanfaatan. Selain itu juga terdapat penjelasan mengenai sentra perikanan,
syarat lokasi dan pedoman budidaya, pakan, hama dan penyakit, serta pemasaran.
2.1.1. Klasifikasi dan Jenis-jenis Ikan Patin
Klasifikasi ikan patin yaitu sebagai berikut9:
Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Actinopterygii
Ordo : Siluriformes
Famili : Pangasiidae
Genus : Pangasius Spesies : Pangasius sp.
Jenis ikan patin di Indonesia cukup banyak, diantaranya (Prahasta dan
Masturi, 2008) :
1) Patin lokal dengan nama ilmiah Pangasius sp. Terdapat beberapa jenis ikan patin yang populer di Indonesia. Salah satu jenis populer yang berpeluang
menjadi komoditas ekspor adalah patin djambal (Pangasius djambal).
2) Patin siam (Pangasius hypopthalmus atau Pangasius sutchi) yaitu patin bangkok karena asalnya dari Bangkok (Thailand). Patin jenis ini banyak
dibudidayakan oleh petani di Indonesia karena ukurannya yang relatif lebih
besar, relatif mudah untuk dibudidayakan, dan memiliki laju perumbuhan
yang lebih cepat jika dibandingkan patin lokal.
3) Pangasius polyuranodo (ikan juaro), Pangasius macronema (ikan rios, riu, lancang), Pangasius micronemus (wakal, rius caring), Pangasius nasutus (pedado) dan Pangasius nieuwenbuissii (ikan lawang) yang penyebarannya hanya di Kalimantan Timur.
4) Patin bocourti yang terdapat di perairan umum di Vietnam dan merupakan
komoditas ekspor ke Amerika Serikat, Eropa, dan beberapa negara Asia.
2.1.2. Ciri Fisik
Ciri morfologi ikan patin yaitu memiliki kepala yang melebar ke arah
punggung. Mata berukuran sedang pada sisi kepala, lubang hidung relatif besar.
Mulut relatif kecil dan melebar ke samping serta memiliki gigi yang tajam. Ikan
patin berwarna putih perak dengan punggung berwarna kebiru-biruan. Panjang
tubuh bisa mencapai lebih dari satu meter. Kepala ikan patin relatif kecil, dengan
mulut terletak di ujung kepala agak di sebelah bawah (merupakan ciri khas
golongan catfish) dan memiliki dua pasang kumis atau antena pendek yang berfungsi sebagai peraba (Prahasta dan Masturi, 2008).
2.1.3. Kandungan Gizi dan Pemanfaatan
Daging ikan patin memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi (protein
65%, lemak 2%, dan kalori 48%). Rasa dagingnya khas, enak, lezat dan gurih.
Ikan patin dinilai lebih aman untuk kesehatan karena kadar kolesterolnya lebih
rendah dibandingkan dengan daging ternak10. Produk olahan patin diantaranya
nugget, empek-empek, dan kerupuk kulit ikan patin.
2.1.4. Sentra Perikanan
Daerah yang merupakan sentra perikanan ikan patin di Indonesia meliputi
Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Daerah Kalimantan yang menjadi sentra
produksi patin yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Daerah Sumatera
yang menjadi sentra produksi patin yaitu Riau, Jambi, Lampung, dan Sumatera
Selatan, sedangkan di Jawa yaitu Jawa Barat11.
2.1.5. Persyaratan Lokasi
Budidaya pembesaran ikan patin dapat dilakukan dengan sistem kolam,
sistem karamba/karamba jaring apung, dan sistem Fence. Jenis kolam yang biasa digunakan yaitu kolam irigasi, kolam tadah hujan, dan kolam rawa. Lokasi
pemasangan karamba bisa di kolam, danau, waduk atau di pinggir sungai dengan
kedalaman tertentu. Pembesaran dengan sistem Fence dilakukan di pinggir sungai atau rawa dengan membuat pagar-pagar keliling yang ditanam di dasar sungai
atau rawa dengan kedalaman tertentu. Perbedaan cara budidaya ini terkait dengan
skala usaha (Prahasta dan Masturi, 2008).
Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jika petani ingin melakukan
pemeliharaan di kolam yaitu12:
1) Tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan yaitu jenis tanah liat/lempung dan
tidak berporos. Jenis tanah tersebut dapat menahan massa air yang besar dan
tidak bocor sehingga dapat dibuat pematang/dinding kolam.
2) Kemiringan tanah yang baik untuk pembuatan kolam berkisar antara 3-5%
untuk memudahkan pengairan kolam secara gravitasi.
11
3) Untuk pemeliharaan larva, kualitas air untuk pemeliharaan ikan patin harus
bersih, tidak terlalu keruh, dan tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun
maupun minyak/limbah pabrik. Suhu air yang baik pada saat penetasan telur
menjadi larva di akuarium yaitu antara 260-280C. Pada daerah-daerah yang
suhu airnya relatif rendah diperlukan heater (pemanas) untuk mencapai suhu optimal yang relatif stabil.
4) Keasaman air berkisar antara 6,5-7.
2.1.6. Pedoman Teknis Budidaya
Budidaya ikan patin meliputi beberapa kegiatan, secara garis besar dibagi
menjadi dua kegiatan yaitu pembenihan dan pembesaran13. Kegiatan pembenihan
merupakan upaya untuk menghasilkan benih pada ukuran tertentu. Produk akhir
dari kegiatan pembenihan berupa benih berukuran tertentu, yang umumnya
merupakan benih selepas masa pendederan. Secara garis besar usaha pembenihan
ikan patin meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) pemilihan calon induk
siap pijah (2) persiapan hormon perangsang (3) kawin suntik (induced breeding) (4) pengurutan (striping) (5) penetasan telur (6) perawatan larva (7) pendederan dan (8) pemanenan. Sementara kegiatan pembesaran merupakan upaya
membesarkan benih sampai dewasa untuk kemudian dijual.
2.1.7. Pakan Patin
Pakan merupakan kebutuhan primer untuk mempercepat pertumbuhan
ikan. Ikan patin termasuk salah satu jenis ikan air tawar yang lahap mengonsumsi
pakan. Pakan ikan patin terdiri dari dua macam yaitu pakan alami dan pakan
buatan (Prahasta dan Masturi, 2008).
1) Pakan Alami
Pakan alami mengandung komposisi gizi yang baik diantaranya protein,
lemak, karbohidrat, dan mineral. Pakan alami seperti infori, dapnia, dan artemia,
dan cacing sutra (Tubifex) dibutuhkan dalam proses pembenihan karena pakan dapat bergerak aktif dan merangsang larva ikan untuk memakannya. Selain itu,
ukurannya yang sangat kecil sesuai dengan ukuran mulut larva.
2) Pakan Buatan
Pakan buatan berbentuk pelet, bisa berupa pelet buatan pabrik maupun
buatan sendiri yang dibuat dari campuran ikan asin, dedak, ampas tahu, dan
lain-lain. Ada dua cara pembuatan pakan ramuan sendiri yaitu dengan direbus lebih
dahulu dan tanpa direbus.
2.1.8. Hama dan Penyakit
Salah satu kendala yang sering dihadapi dalam dunia agribisnis perikanan
adalah hama dan penyakit yang menyerang ikan. Hama dan penyakit tersebut bisa
diatasi tapi tidak jarang pula yang menyebabkan kematian ikan secara massal.
Berikut adalah beberapa hama dan penyakit yang sering terdapat pada ikan patin
(Prahasta dan Masturi,2008):
1) Hama
Hama yang mengganggu diantaranya yaitu predator dan kompetitor. Pada
pembesaran ikan patin di jaring apung, sistem sekat, dan karamba, hama yang
mungkin menyerang antara lain lingsang, kura-kura, biawak, ular air, dan burung.
Karamba yang ditanam di dasar perairan relatif aman dari serangan hama. Pada
pembesaran ikan patin di jala apung (sistem sangkar) ada hama berupa ikan buntal
masuk kedalam wadah budidaya akan menjadi pesaing ikan patin dalam hal
mencari makan dan memperoleh oksigen.
2) Penyakit
a) Penyakit Parasit
Penyakit white spot (bintik putih) disebabkan oleh parasit dari bangsa protozoa dari jenis Ichthyoptirus Multifilis Foquet. Penyakit ini menyerang benih berumur 1-6 minggu. Ciri-ciri : adanya bintik-bintik putih di lapisan lendir kulit,
sirip, dan lapisan insang. Penyakit ini menyebabkan kematian benih secara masal.
b) Penyakit Jamur
Penyakit jamur biasanya terjadi akibat adanya luka pada badan ikan.
Penyebab penyakit jamur adalah Saprolegnia sp. dan Achlya sp. Pada kondisi air yang jelek, kemungkinan patin terserang jamur lebih besar. Ciri-ciri ikan patin
yang terserang jamur adalah luka di bagian tubuh, terutama pada tutup insang,
sirip, dan bagian punggung. Bagian-bagian tersebut ditumbuhi benang-benang
halus seperti kapas berwarna putih hingga kecoklatan.
c) Penyakit Bakteri
Bakteri yang sering menyerang patin yaitu Aeromonas sp. dan Pseudomonas sp. Ikan yang terserang akan mengalami pendarahan pada bagian tubuh terutama di bagian dada, perut, danpangkal sirip. Gejalanya lendir di tubuh
ikan berkurang dan terasa kasar saat diraba. Penyakit akibat bakteri mudah
menular, sehingga ikan yang terserang dan keadaannya cukup parah harus segera
dimusnahkan. Sementara yang terinfeksi tetapi belum parah dapat dicoba dengan
d) Penyakit Noninfeksi (Keracunan dan Kurang Gizi)
Keracunan disebabkan oleh banyak faktor seperti pada pemberian pakan
yang berjamur dan berkuman atau karena pencemaran lingkungan perairan. Gejala
keracunan yaitu ikan akan lemah, berenang tersengal-sengal di permukaan air.
Pada kasus keracunan yang berbahaya, ikan berenang terbalik dan mati.
Penyakit noninfeksi lainnya disebabkan karena kurang gizi. Gejala yang
sering timbul adalah kurangnya nafsu makan terutama pada musim kemarau. Ikan
tampak kurus dan kepala terlihat lebih besar tidak seimbang dengan ukuran tubuh,
kurang lincah, dan berkembang tidak normal.
2.1.9. Pemasaran
Ikan patin dikenal sebagai komoditas yang berprospek cerah karena
memiliki harga jual yang tinggi. Hal inilah yang menyebabkan ikan patin
mendapat perhatian dan diminati oleh para pengusaha untuk membudidayakannya
(Prahasta dan Masturi, 2008). Walaupun permintaan di tingkal pasaran lokal akan
ikan patin dan ikan air tawar lainnya selalu mengalami pasang surut, namun
dilihat dari jumlah hasil penjualan secara rata-rata selalu mengalami kenaikan dari
tahun ke tahun. Apabila pasaran lokal ikan patin mengalami kelesuan, maka akan
sangat berpengaruh terhadap harga jual baik di tingkat petani maupun di tingkat
grosir di pasar ikan. Di luar hal tersebut, penjualan benih ikan patin dapat
dikatakan hampir tak ada masalah, prospeknya cukup baik. Selain adanya potensi
pendukung dan faktor permintaan komoditas perikanan untuk pasaran lokal, maka
sektor perikanan merupakan salah satu peluang usaha bisnis yang cerah14.
2.1.10.Kebijakan Pemerintah terhadap Komoditas Ikan Patin
Industri akuakultur saat ini menjadi salah satu andalan masyarakat dunia,
karena selain bergizi tinggi, juga sebagai sumber ekonomi yang bernilai tinggi.
Kebutuhan pasar akan produk akuakultur pun meningkat sejalan dengan turunnya
produksi ikan hasil tangkapan dan meningkatnya jumlah populasi dunia yang
mulai sadar pentingnya makan ikan untuk menjaga kesehatan. Direktur Pemasaran
Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
(P2HP) Departemen Perikanan dan Kelautan (DKP) Saadullah Muhdi mengatakan
bahwa salah satu tantangan yang dihadapi yaitu banyaknya produk impor. Di
samping itu, kontinuitas pasokan ikan juga menjadi kendala tersendiri15.
Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketersediaan
pasokan baik untuk domestik maupun ekspor yaitu (1) pengadaan benih unggul
yang disertai ketersediaan pasar (2) menciptakan sinergitas yang erat antara
swasta, masyarakat, dan pemerintah, termasuk melalui kelembagaan lokal yang
berkewajiban memonitoring produksi kelompok pembudidaya, mengumpulkan
hasil produksi, dan mengatur transportasi produk, dan (3) ketersediaan pakan yang
murah. Ketersediaan pasar dan kelembagaan lokal terkait dengan pendapatan
petani ikan. Harga ikan berfluktuasi tergantung permintaan. Adanya pasar dan
kelembagaan lokal berperan dalam penciptaan harga yang stabil karena petani
ikan harus mendapatkan pendapatan yang pasti, salah satunya dengan kestabilan
harga16.
Kaitannya dengan pakan, harga pakan pabrik menjadi kendala yang lain.
Industri pakan ikan dan udang akan menurun akibat pemberlakuan pajak
15
pertambahan nilai (PPN) atas bahan baku pakan maupun pakan itu sendiri. Bahan
baku pakan berupa bungkil dan kedelai serta tepung ikan masih impor. Kebutuhan
impor yang tinggi menyebabkan harga pakan tidak kompetitif. Karena itulah
diperlukan langkah untuk menurunkan harga pakan ikan sehingga bisa
menurunkan biaya produksi17.
2.2. Kajian Penelitian terdahulu
Policy Analysis Matrix (PAM) merupakan metode yang diperkenalkan oleh Eric A. Monke dan Scott E. Pearson pada tahun 1989 yang merupakan
penyempurnaan dari metode-metode sebelumnya dalam menganalisis keunggulan
komparatif, kompetitif, dan dampak kebijakan pemerintah. Metode ini telah
banyak digunakan dalam penelitian-penelitian untuk menganalisis kebijakan
pemerintah terhadap suatu komoditas. Penelitian-penelitian terdahulu yang
menghitung keunggulan komparatif, kompetitif, dan dampak kebijakan
pemerintah terhadap suatu komoditas antara lain telah dilakukan oleh Rina
Oktaviani (1991), Eka Kaysmir (1994), dan Dewi Gustiani (2004).
Rina Oktaviani melakukan penelitian mengenai efisiensi ekonomi dan
dampak kebijakan insentif pertanian pada produksi komoditas pangan di
Indonesia yaitu padi (1984 dan 1989), jagung (1984 dan 1989), dan ubi kayu
(1984). Daerah penelitian meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan dengan pertimbangan
bahwa keenam daerah tersebut merupakan penghasil pangan utama. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara finansial, pada tahun 1984 padi lebih
efisien ditanam di Sulawesi Selatan, sedangkan pada tahun 1989 lebih efisien
ditanam di Lampung. Secara ekonomi, padi lebih efisien ditanam di Lampung
(1984) dan Sulawesi Selatan (1989). Komoditas jagung secara finansial dan
ekonomi memiliki efisiensi tertinggi di Lampung baik pada tahun 1984 maupun
1989. Demikian pula dengan ubi kayu, memiliki efisiensi finansial dan ekonomi
tertinggi di Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Sulawesi Selatan.
Eka Kasymir meneliti mengenai keunggulan komparatif dan dampak
kebijakan pada komoditas kopi dan lada pada tahun 1992 di wilayah Kabupaten
Lampung Barat, Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
komoditas kopi dan lada (biji kering asalan di tingkat petani, kopi biji grade IV, dan lada mutu ASTA di tingkat eksportir) berdasar harga tahun 1991, secara
finansial hanya komoditas kopi yang layak diusahakan. Secara ekonomi, kedua
komoditas tidak memiliki keunggulan komparatif terutama bagi komoditas lada.
Dewi Gustiani meneliti keunggulan kompetitif dan komparatif dari
komoditas kain tenun sutera alam hasil produksi Kabupaten Garut. Penelitiannya
menunjukkan bahwa komoditas kain tenun sutera alam tersebut memiliki
keunggulan kompetitif dan komparatif. Hal ini dilihat dari nilai PCR dan DCR
yang lebih kecil dari satu yaitu masing-masing sebesar 0,95 dan 0,53. Analisis
sensitivitas juga dilakukan dalam penelitian tersebut. Hasilnya menunjukkan
bahwa pengusahaan kain tenun sutera alam memiliki stabilitas yang cukup tinggi
terhadap perubahan harga output, upah tenaga kerja, harga BBM, nilai tukar
III. KERANGKA PEMIKIRAN 3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis
Kerangka pemikiran teoritis terdiri dari dua hal. Pertama, kebijakan
pemerintah terhadap output dan input. Kedua, konsep keunggulan komparatif dan
kompetitif dalam hubungannya dengan perdagangan.
3.1.1. Kebijakan Pemerintah
Intervensi pemerintah terhadap suatu komoditas antara lain berupa
kebijakan harga dan kebijakan perdagangan. Kebijakan tersebut menimbulkan
perbedaan harga pada input dan output pada kondisi finansial dan ekonomi.
Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap komoditas digambarkan pada Tabel 8.
Tabel 8. Klasifikasi Kebijakan Harga Komoditas
Instrumen Dampak terhadap produsen Dampak terhadap konsumen
Kebijakan subsidi: a. Pada barang impor
(S+PI; S-PI) b. Pada barang ekspor
(S+PE; S-PE)
Subsidi kepada konsumen
a. Pada barang impor (S+CI; S-CI) pasar domestik
b. Pada barang ekspor (S+CE; S-CE) pasar domestik ekspor (TCE) mengubah harga domestik
Keterangan:
S : Kebijakan Subsidi
T : Kebijakan Perdagangan
PE : Produsen Barang Orientasi Ekspor PI : Produsen Barang Substitusi Impor CE : Konsumen Barang Orientasi Ekspor CI : Konsumen Barang Substitusi Impor TCE : Hambatan Barang Ekspor
TPI : Hambatan Barang Impor
Sumber : Monke dan Pearson (1989)
Berdasarkan Tabel 8, kebijakan harga dapat dibedakan dalam tiga kriteria
yaitu tipe instrumen, penerimaan atau keuntungan yang diperoleh (produsen dan
konsumen), dan tipe komoditas (impor atau ekspor). Pelaksanaan dari kebijakan
1) Tipe Instrumen
Dibedakan pengertian antara subsidi dan kebijakan perdagangan dalam
tipe instrumen ini. Menurut Salvatore (1997), subsidi adalah pembayaran dari
atau untuk pemerintah. Pajak atau subsidi negatif merupakan pembayaran kepada
pemerintah, sedangkan pembayaran dari pemerintah disebut subsidi positif. Efek
dan tujuan subsidi yaitu menciptakan harga domestik yang berbeda dengan harga
dunia, kadang-kadang kebijakan menciptakan harga domestik yang terpisah antara
konsumen dan produsen.
Kebijakan perdagangan adalah suatu pembatasan terhadap barang impor
atau ekspor (Monke dan Pearson, 1989). Pembatasan dapat berupa pajak
perdagangan atau pun kuota perdagangan. Tujuannya yaitu untuk mengurangi
jumlah perdagangan internasional dan untuk menciptakan perbedaan harga di
pasar internasional dengan harga domestik. Kebijakan ekspor bertujuan untuk
melindungi konsumen dalam negeri karena harga domestik yang lebih rendah
dibandingkan harga dunia. Kebijakan impor dilakukan untuk melindungi
produsen karena harga di pasar dunia lebih murah dibandingkan harga domestik.
Pada subsidi terdapat delapan tipe yaitu S+PI, PI, S+PE, PE, S+CI,
S-CI, S+CE, dan S-CE, sedangkan pada kebijakan perdagangan hanya ada dua tipe
dasar yaitu TPI dan TPE. Subsidi positif yang diterapkan kepada produsen
maupun konsumen akan membuat harga yang diterima produsen menjadi lebih
tinggi dan pada konsumen menjadi lebih rendah. Kondisi ini lebih baik
dibandingkan saat sebelum adanya kebijakan subsidi positif. Subsidi negatif akan
konsumen menjadi lebih tinggi. Kondisi ini lebih buruk dibandingkan saat
sebelum adanya kebijakan subsidi negatif.
2) Kelompok Penerimaan
Klasifikasi kelompok penerimaan adalah kebijakan yang dikenakan pada
produsen dan konsumen. Subsidi atau kebijakan perdagangan mengakibatkan
terjadinya transfer di antara produsen, konsumen, dan pemerintah. Anggaran
pemerintah tidak dibayarkan seluruhnya untuk transfer, hal ini mengakibatkan
produsen mengalami keuntungan dan konsumen mengalami kerugian. Akan
tetapi, dengan adanya transfer yang diikuti efisiensi ekonomi yang hilang akan
menyebabkan keuntungan yang diperoleh lebih kecil dari kerugian yang diterima.
3) Tipe Komoditas
Klasifikasi ini bertujuan untuk membedakan harga barang impor dan
ekspor. Jika tidak ada kebijakan ini, maka harga domestik sama dengan harga
dunia, dimana untuk ekspor digunakan harga fob (free on board) dan untuk impor digunakan harga cif (cost freight and insurance). Adanya kebijakan komoditas menyebabkan harga domestik berbeda dengan harga fob dan cif.
3.1.1.1. Kebijakan Pemerintah terhadap Output
Kebijakan yang ditetapkan pada output dapat berupa kebijakan subsidi
(subsidi positif dan negatif) dan kebijakan hambatan perdagangan. Kebijakan
subsidi produsen barang sustitusi impor (S+PI) akan menguntungkan bagi
produsen lokal barang substitusi impor karena dengan adanya kebijakan subsidi
bagi produsen barang substitusi impor, penerimaan produsen lokal akan
menguntungkan konsumen barang substitusi impor. Kebijakan subsidi positif baik
pada barang ekspor maupun impor ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1 hanya untuk dampak subsidi positif, sedangkan untuk subsidi
negatif adalah kebalikannya. Gambar (a) menunjukkan subsidi positif untuk
produsen pada barang impor di mana harga yang diterima produsen lebih tinggi
dari harga dunia. Hal ini mengakibatkan output produksi dalam negeri meningkat
dari Q1 ke Q2 sedangkan konsumsi tetap di Q3. Subsidi ini mengakibatkan jumlah
impor turun dari Q3 - Q1 menjadi Q3 - Q2. Tingkat subsidi peroutput sebesar (Pd -
Pw) pada output Q2, maka transfer total dari pemerintah ke produsen sebesar Q2
(Pd - Pw) atau PdABPw. Pembiayaan ini akan menghilangkan efisiensi ekonomi
karena pemerintah memilih untuk tidak mengalokasikan sumberdaya pada harga
dunia (Pw). Subsidi mengakibatkan barang yang sebelumnya diimpor menjadi
diproduksi sendiri dengan biaya yang dikorbankan Q1CAQ2, sedangkan
opportunity cost jika barang tersebut dimpor adalah sebesar Q1CBQ2 sehingga
efisiensi yang hilang sebesar CAB.
Gambar (c) menunjukkan subsidi positif pada konsumen untuk output
yang diimpor. Kebijakan subsidi sebesar Pw - Pd mengakibatkan produksi turun
dari Q1 ke Q2 dan konsumsi naik dari Q3 ke Q4 sehingga impor meningkat dari
Q3 - Q1 menjadi Q4 - Q2. Transfer yang terjadi terdiri dari dua bagian yaitu transfer
dari pemerintah ke konsumen sebesar ADEB dan transfer dari produsen kepada
konsumen sebesar PwABPd. Dengan demikian kehilangan efisiensi ekonomi
terjadi baik pada produksi maupun konsumsi. Di sisi produksi turunnya output
dari Q1 ke Q2 mengakibatkan terjadinya kehilangan pendapatan sebesar Pw (Q1 -
Q2BCQ1 sehingga efisiensi ekonomi yang hilang sebesar ACB. Dilihat pada sisi
konsumsi, opportunity cost dari peningkatan konsumsi adalah Pw (Q4 - Q3) atau
Q3FDQ4, sedangkan kemampuan membayar konsumen sebesar Q3FEQ4 sehingga
efisiensi yang hilang sebesar FDE.
P
S+ PI : Subsidi kepada produsen untuk barang impor S+ PE : Subsidi kepada produsen untuk barang ekspor S+ CI : Subsidi kepada konsumen untuk barang impor S+ CE : Subsidi kepada konsumen untuk barang ekspor Sumber : Monke dan Pearson (1989)
Selain kebijakan subsidi pada output, pemerintah juga memberlakukan
kebijakan restriksi (hambatan) perdagangan pada barang-barang impor. Hal
tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. Gambar (a) menunjukkan adanya hambatan
tarif pada barang impor di mana terdapat tarif sebesar Pd - Pw sehingga
menaikkan harga di dalam negeri baik untuk produsen maupun konsumen. Output
domestik meningkat dari Q1 ke Q2 dan konsumsi turun dari Q4 ke Q3. Dengan
demikian impor turun dari Q4 - Q1 menjadi Q3 - Q2. Terdapat transfer penerimaan
dari konsumen sebesar PdABPw yaitu kepada produsen sebesar PdDEPw dan
kepada pemerintah sebesar EDAB. Efisiensi ekonomi yang hilang dari konsumen
adalah perbedaan antara opportunity cost konsumen dalam mengubah konsumsi sebesar Q4BCQ3 dengan kemampuan membayar yang sama Q3ACQ4 sehingga
didapatkan efisiensi ekonomi yang hilang pada konsumen sebesar ABC dan pada K
TPI : Hambatan perdagangan pada produsen untuk barang impor TCE : Hambatan perdagangan pada konsumen untuk barang impor Sumber : Monke dan Pearson (1989)
Gambar (b) menunjukkan pada situasi perdagangan bebas harga yang
diterima oleh produsen output dan konsumen dalam negeri sama dengan harga
dunia yaitu sebesar Pw. Dengan tingkat harga sebesar Pw, output yang dihasilkan
produsen adalah sebesar Q4 dan konsumsi sebesar Q1, sehingga terjadi ekses
suplai di dalam negeri sebesar segitiga BHJ. Terjadinya ekses suplai tersebut
membuat output yang dihasilkan harus diekspor ke luar negeri yaitu sebesar
Q4 - Q1. Besarnya surplus konsumen adalah ABPw, sedangkan surplus produsen
sebesar PwHK.
Adanya subsidi negatif pada produsen output (NPCO negatif),
mengakibatkan perubahan harga dalam negeri yaitu harga yang diterima produsen
dan konsumen (harga finansial) menjadi lebih rendah dari harga pasar dunia
(Pd < Pw). Dengan tingkat harga sebesar ini, mengakibatkan konsumsi dalam
negeri meningkat dari Q1 menjadi Q2, penurunan produksi dari Q4 menjadi Q3,
penurunan ekspor dari Q4 – Q1 menjadi Q3 - Q2, terjadi perubahan surplus
produsen yaitu sebesar PwHGPd, perubahan surplus konsumen sebesar PdEBPw,
dan besarnya transfer output atau transfer pajak kepada pemerintah sebesar
DFGE. Efisiensi ekonomi yang hilang adalah sebesar BDE dan FGH yang
merupakan kesempatan yang hilang dari produsen untuk memperoleh keuntungan
dan juga tidak ditransfer baik kepada konsumen maupun pemerintah.
3.1.1.2. Kebijakan Pemerintah terhadap Input
Kebijakan terhadap input dapat diterapkan pada input tradable dan input nontradable. Pada kedua input tersebut kebijakan dapat berupa subsidi positif maupun negatif, sedangkan kebijakan hambatan perdagangan tidak diterapkan
yang diproduksi dan dikonsumsi di dalam negeri. Kebijakan pemerintah terhadap
input ditunjukkan pada Gambar 3.
Berdasarkan Gambar 3, Gambar (a) menunjukkan efek pajak terhadap
input tradable yang digunakan. Pajak pada input menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga pada tingkat harga output yang sama, output domestik turun
dari Q1 ke Q2 dan kurva suplai (S) bergeser ke atas. Efisiensi ekonomi yang hilang
adalah ABC, yang merupakan perbedaan antara nilai output yang hilang Q1CAQ2
dengan ongkos produksi Q2BCQ1. Gambar (b) menunjukkan dampak subsidi
input mengakibatkan harga input dan biaya produksi lebih rendah sehingga kurva
suplai (S) bergeser ke bawah dan produksi naik dari Q1 ke Q2. Adanya
peningkatan produksi menyebabkan terjadinya peningkatan penggunaan
sumberdaya yaitu sebesar Q1ACQ2 dan meningkatnya penerimaan menjadi
sebesar Q1ABQ2. Efisiensi ekonomi yang hilang dari produksi adalah ABC yang
merupakan pengaruh perbedaan antara biaya produksi setelah output meningkat
dengan nilai dari output yang meningkat.
Intervensi pemerintah berupa hambatan perdagangan pada input yang
nontradable tidak tampak karena input nontradable hanya diproduksi dan dikonsumsi di dalam negeri. Intervensi pemerintah adalah subsidi positif dan
subsidi negatif (pajak) yang dapat dijelaskan pada Gambar 4. Pada Gambar (a)
adanya pajak (Pc - Pp) mengakibatkan produk yang dihasilkan turun menjadi Q2.
Efisiensi ekonomi yang hilang dari produsen sebesar DBA dan dari
konsumen sebesar BCA. Gambar (b) menunjukkan adanya subsidi mengakibatkan
produk meningkat dari Q1 ke Q2, harga yang diterima produsen naik menjadi Pp
dilihat dari perbandingan antara peningkatan nilai output dengan meningkatnya
ongkos produksi dan meningkatnya keinginan konsumen untuk membayar.
P Sumber : Monke dan Pearson (1989)
Gambar 3. Subsidi dan Pajak pada Input
Keterangan:
S- N : Pajak untuk barang nontradable S+ N : Subsidi untuk barang nontradable Sumber : Monke dan Pearson (1989)
3.1.2. Tinjauan Konseptual Keunggulan Komparatif dan Kompetitif
Terkait dengan konsep keunggulan komparatif yaitu kelayakan ekonomi,
dan terkait dengan keunggulan kompetitif yaitu kelayakan finansial. Kelayakan
finansial melihat manfaat proyek atau aktivitas ekonomi dari sudut lembaga atau
individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Kelayakan ekonomi menilai suatu
aktivitas atas manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Kadariah et al., 1978). Secara umum komoditas pertanian memiliki keunggulan komparatif dan
sekaligus keunggulan kompetitif, namun parameter keunggulan komparatif lebih
rendah dibandingkan keunggulan kompetitifnya. Hal ini mengandung makna
bahwa petani membayar harga input produksi lebih tinggi dari yang seharusnya
dan atau menerima harga output lebih rendah dari yang seharusnya. Faktanya
dewasa ini produk pertanian tetap mengalami kesulitan untuk dapat bersaing dan
akses terhadap pasar internasional karena masalah kualitas, kontinuitas pasokan,
tingginya kerusakan dalam pengangkutan, serta kondisi sosial politik dalam negeri
yang belum kondusif (Saptana et al., 2001).
3.1.2.1.Keunggulan Komparatif
Konsep keunggulan komparatif pertama kali dikemukakan oleh David
Ricardo. Konsep tersebut dikenal dengan nama hukum keunggulan komparatif
(the law of comparative advantage) atau Model Ricardian Ricardo. Menurut beliau, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan
komparatif antar negara. Keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara
mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih
murah daripada negara lainnya. Akan tetapi, sekalipun suatu negara mengalami
dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan yang saling
menguntungkan masih dapat berlangsung. Negara yang kurang efisien akan
berspesialisasi dalam produksi dan mengekspor komoditas yang mempunyai
keunggulan komparatif, sebaliknya negara tersebut akan mengimpor komoditas
yang mempunyai kerugian komparatif (Salvatore, 1997).
Teori keunggulan komparatif Ricardian Ricardo kemudian disempurnakan
oleh Harberler (1936) yang mengemukakan konsep keunggulan komparatif
berdasarkan Teori Biaya Imbangan (Opportunity Cost Theory). Harberler menyatakan bahwa biaya dari suatu komoditas adalah jumlah komoditas terbaik
yang harus dikorbankan untuk memperoleh sumberdaya yang cukup untuk
memproduksi satu unit tambahan komoditas pertama. Negara yang memiliki biaya
opportunitas lebih rendah dalam memproduksi sebuah komoditas akan memiliki
keunggulan komparatif dalam komoditas tersebut dan memiliki kerugian
komparatif dalam komoditas kedua (Salvatore, 1997).
Teori keunggulan yang lebih modern yaitu teori Heckschser dan Ohlin (1933). Menurut teori H-O, basis terjadinya perdagangan yaitu perbedaan di
dalam pre traderelativecommodityprices, yang dapat disebabkan oleh perbedaan dari faktor endowment, technology, ataupun tastes dari kedua negara yang bersangkutan. Akibat perbedaan tersebut, akan mendorong perbedaan atas biaya
produksi dan atau harganya. Suatu negara akan mengadakan spesialisasi produksi
yang mempunyai faktor produksi relatif melimpah yang berarti biayanya juga
akan murah dan dalam waktu bersamaan negara tersebut akan mengimpor
komoditas yang produksinya memerlukan sumberdaya yang relatif langka dan
3.1.2.2. Keunggulan Kompetitif
Keunggulan kompetitif pada awalnya dikembangkan oleh Porter pada
tahun 1980 sebagai perluasan dari teori keunggulan komparatif dengan bertitik
tolak dari kenyataan-kenyataan perdagangan internasional. Menurut Porter (1991),
keunggulan perdagangan antar negara di dalam perdagangan internasional secara
spesifik untuk produk-produk tertentu sebenarnya tidak ada. Pada kenyataannya
yang ada yaitu persaingan antar kelompok kecil industri di suatu negara dengan
negara lainnya, bahkan antar kelompok industri yang ada dalam satu negara.
Porter juga mengemukakan tentang tidak adanya korelasi langsung antara dua
faktor produksi (sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia
yang murah) yang dimiliki suatu negara, yang dimanfaatkan menjadi keunggulan
daya saing dalam perdagangan internasional. Keunggulan kompetitif tidak
bergantung pada kondisi alam suatu negara, namun lebih ditekankan pada
produktivitasnya. Porter menyebutkan bahwa peran pemerintah sangat penting
dalan peningkatan daya saing selain faktor produksi.
Selain itu, menurut Porter, salah satu esensi dari keunggulan kompetitif
adalah bagaimana menciptakan produk atau layanan serta seluruh proses yang
menyertainya sedemikian sehingga sulit ditiru oleh pesaing. Untuk meraih
keunggulan kompetitif di dalam lingkungan persaingan yang ketat, suatu
perusahaan perlu mengadopsi strategi yang tepat. Ada dua jenis strategi yaitu
3.1.3. Policy Analysis Matrix (Matriks Analisis Kebijakan)
Policy Analysis Matrix merupakan suatu alat yang digunakan untuk menganalisis pengaruh intervensi pemerintah dan dampaknya pada sistem
komoditas. Sistem komoditas yang dapat dipengaruhi meliputi empat aktivitas
yaitu (Monke dan Pearson, 1989) : (1) tingkat usaha tani (farm production); (2) penyampaian dari usaha tani ke pengolah; (3) pengolahan; dan (4) pemasaran.
Metode PAM membantu pengambil kebijakan baik di pusat maupun daerah untuk
menelaah tiga isu sentral analisis kebijakan pertanian. Isu pertama berkaitan
dengan apakah sebuah sistem usahatani memiliki dayasaing pada tingkat harga
dan teknologi yang ada, yaitu apakah ada keuntungan pada tingkat harga aktual
(dengan menghitung perbedaan antara harga privat antara sebelum ada kebijakan
dengan sesudah ada kebijakan). Isu kedua yaitu dampak investasi publik (dalam
bentuk pembangunan infrastruktur baru) terhadap tingkat efisiensi sistem
usahatani. Efisiensi dihitung berdasarkan tingkat keuntungan sosial. Isu ke tiga
yaitu dampak investasi baru dalam bentuk riset atau teknologi pertanian terhadap
tingkat efisiensi sistem usaha tani (Pearson et al., 2005).
Tujuan utama dari metode PAM ada tiga, yaitu pertama memberikan
informasi dan analisis untuk membantu pengambil kebijakan pertanian dalam
ketiga isu di atas. Kedua, menghitung tingkat keuntungan sosial dari sebuah
usahatani. Ketiga, menghitung efek transfer sebagai dampak dari sebuah
kebijakan (dengan membandingkan biaya dan pendapatan).
Input yang digunakan dalam proses produksi pada analisis PAM dapat