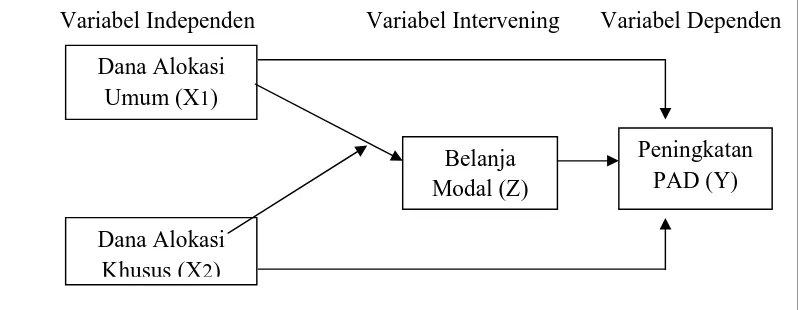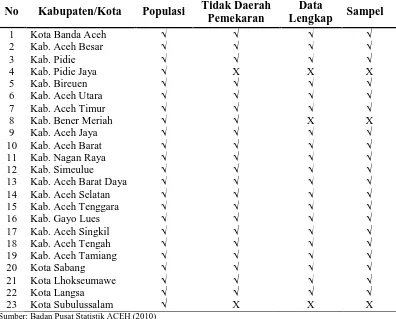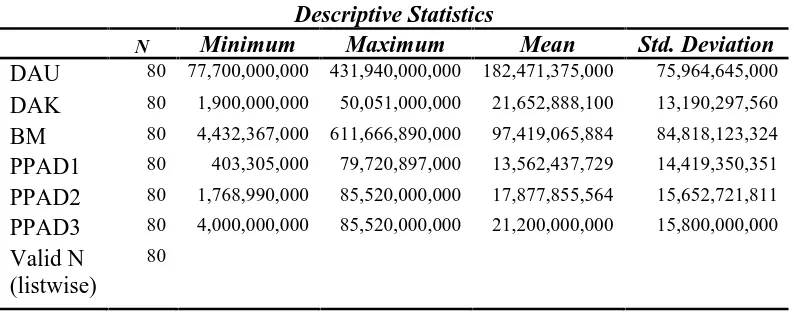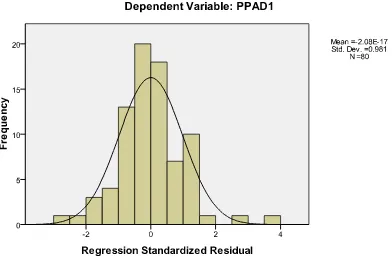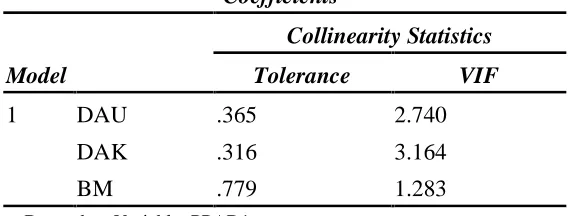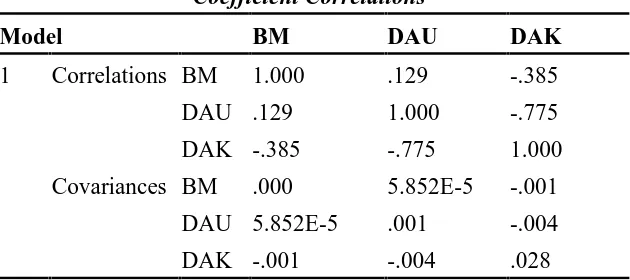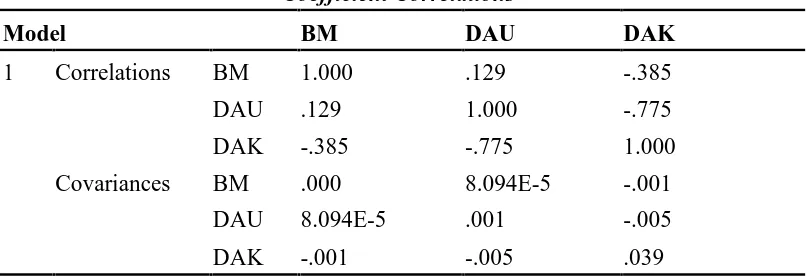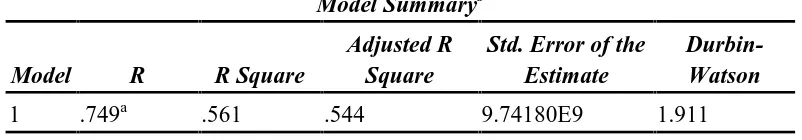PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN/
KOTA PROVINSI ACEH
TESIS
Oleh
HASRINA HUSNI
087017098/Akt
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2011
S E K
O L
A H
P A
S C
A S A R JA N
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN/
KOTA PROVINSI ACEH
TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Akuntansi pada Sekolah Pascasarjana
Universitas Sumatera Utara
Oleh
HASRINA HUSNI
087017098/Akt
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Judul Tesis : PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH
Nama Mahasiswa : Hasrina Husni Nomor Pokok : 087017098 Program Studi : Akuntansi
Menyetujui
Komisi Pembimbing,
(Dr. Murni Daulay, M.Si) (Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si, Ak) Ketua Anggota
Ketua Program Studi, Direktur,
(Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, Ak) (Prof. Dr. Ir. A. Rahim Matondang, MSIE)
Telah diuji pada
Tanggal : 14 Januari 2011
PANITIA PENGUJI TESIS:
Ketua : Dr. Murni Daulay, M.Si
Anggota : 1. Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si, Ak
2. Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, M.Si, Ak
3. Dra. Tapi Anda Sari Lubis, M.Si, Ak
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan tesis yang berjudul:
“PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN
BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING STUDI EMPIRIS
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH”.
Adalah benar hasil kerja saya sendiri dan belum dipublikasikan oleh siapapun
sebelumnya. Sumber-sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan
secara benar dan jelas.
Medan, Januari 2011 Yang membuat pernyataan
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN/
KOTA PROVINSI ACEH
Hasrina Husni; Dr. Murni Daulay, M.Si dan Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si, Ak
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal sebagai variabel intervening pada lag satu, lag dua dan lag tiga tahun.
Populasi penelitian ini sejumlah 23 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, dan yang memenuhi kriteria disertakan sebagai anggota sampel
sejumlah 20 pemerintah daerah kabupaten/kota. Data pengamatan selama 4 tahun (2004 – 2007) sehingga analisis amatan menjadi 80. Sumber data penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik tentang Laporan Tahunan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis jalur model Trimming.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berkontribusi signifikan sedangkan Dana Alokasi Umum tidak terhadap belanja modal. Pada lag satu tahun, Dana Alokasi Umum, belanja modal berkontribusi signifikan sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pada lag dua tahun Dana Alokasi Umum, belanja modal berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak. Pada lag tiga tahun, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan belanja modal berkontribusi signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
THE INFLUENCE OF BLOCK GRANT, SPECIPIC GRANT TO REGIONAL INCOME IMPROVEMENT WITH CAPITAL EXPENDITURES AS AN
INTERVENING VARIABLE EMPIRICAL STUDY IN THE DISTRICT/ CITY OF PROVINCI ACEH
Hasrina Husni; Dr. Murni Daulay, M.Si and Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si, Ak
ABSTRACT
The purpose of this research is conducted to obtain empirical evidence and analyze the influence of Block Grant (DAU), Specific Grant (DAK) of Regional Income Improvement through Capital Expenditure as an intervening variable in lag one, lag two and lag three years.
The research population of 23 local government districts and cities in Provinci Aceh, which fulfill the criteria included as a member of a sample of 20 local government districts. Observation data for 4 years (2004-2007) so that analysis of observations to 80. Sources of research data is derived from Statistics Indonesia on Annual Reports of A Realization of Budgeting the Local Government Receipt and Expenditure (APBD). Hypothesis examination is performed with path analysis model of Trimming.
Research results show that the specific grant contribute significantly while the block grant is not against capital expenditure. At the lag one year, the block grant, capital expenditure contribute significantly but the specific grant does not to improve in regional income. In the two-year lag of block grant, capital expenditure increase to contribute significantly to the regional income while the specific grant is not. In the three-year, the block grant, specific grant, capital expenditure contribute significantly to improve regional income.
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Allah azza wa jalla rabb semesta alam, serta
shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan Rasulullah S.A.W,
keluarga dan para sahabatnya. Berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya penulis dapat
menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum,
Dana Alokasi Khusus terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan
Belanja Modal sebagai Variabel Intervening Studi Empiris di Kabupaten/Kota
Provinsi Aceh”. Penyusunan tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai derajat
Strata Dua (S2) pada Magister Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera
Utara.
Dalam penulisan tesis ini penulis mengalami berbagai macam kesulitan dan
kendala, namun penulis menyadari tugas ini dapat diselesaikan atas bantuan moril
maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis
mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM & H. MSc, (CTM), SpA(K), selaku
Rektor Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. A. Rahim Matondang, MSIE, selaku Direktur Sekolah
Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
3. Ibu Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, Ak, selaku Ketua Program Studi
sebagai Dosen Pembanding yang telah banyak memberikan saran dan kritik untuk
perbaikan sehingga selesainya tesis ini.
4. Ibu Dra. Tapi Anda Sari Lubis, M.Si, Ak, selaku Sekretaris Program Magister
Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara sekaligus sebagai
Dosen Pembanding yang telah banyak memberikan saran dan kritik untuk
perbaikan sehingga selesainya tesis ini.
5. Ibu Dr. Murni Daulay, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak
memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam proses penelitian dan penulisan
untuk menyusun tesis ini.
6. Bapak Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah
banyak memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam proses penelitian dan
penulisan untuk menyusun tesis ini.
7. Bapak Drs. Iskandar Muda, M.Si, Ak selaku Dosen Pembanding yang telah
banyak memberikan saran dan kritik untuk perbaikan sehingga selesainya tesis
ini.
8. Bapak Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, Ibu Kepala
Bidang Akuntansi serta teman-teman staf bidang Akuntansi DPKKA.
9. Pimpinan dan Staf Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, yang telah
menyediakan dan memberikan data maupun informasi yang diperlukan sehingga
penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10.Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh pegawai pada Sekolah Pascasarjana
11.Rekan-rekan pengelola Sekretariat Program Studi Magister Akuntansi, Bang Ari,
Mbak Yusna, Mbak Dori dkk yang telah banyak membantu administrasi
penelitian ini.
12.Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Ayahanda Drs. H. Husni H. Benseh (alm)
dan Ibunda Hj. Nuraini Hamzah, Pakwa Ir. Joesbenz, MT, Ibu Mertua Dra. Hj.
Nurdjani yang telah memberikan dukungan, doa, cinta dan kasih sayang yang
tiada hentinya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di
Sekolah Pascasarjana ini.
13.Suami tersayang Mohd. Rizal Mahdi, S.Ag, SP, M.Si, ananda yang selalu setia
berjuang bersama ummi Siti Hafidzah Almahdi serta adinda Hasnita Husni, SE
dan Muzakkir, S.PdI, M.Ed, Hidayatna Husni, S.ST dan dr. Suprinardi, Diana
Fitri Husni, Rahadatul ’Aisy Husni, Ziyad Rizqullah Husni. Kakanda dr. Surya
Nola & Kel serta Suhartini, yang telah memberikan dukungan dengan penuh
kasih sayang kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Sekolah Pascasarjana
ini.
14.Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan saran-saran yang
berarti bagi penulis serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu
persatu yang telah banyak membantu dan memberikan saran maupun
perhatiannya sehingga penulisan tesis ini terselesaikan.
Jasa mereka semua tidak dapat dinilai, penulis tidak dapat membalasnya, dan
dengan ketulusan serta keikhlasan do’a yang penulis panjatkan semoga Allah
perhatian dan bantuan yang telah diberikan. Akhirnya penulis menyadari dengan
kemampuan dan pengetahuan yang sangat terbatas, penulisan ini masih jauh dari
kesempurnaan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang
konstruktif demi kesempurnaan tesis ini, dan semoga dapat bermanfaat bagi penulis
serta berbagai pihak yang memerlukannya.
Medan, Januari 2011
RIWAYAT HIDUP
1. Nama : HASRINA HUSNI
2. Tempat/Tanggal Lahir : Bireuen, 29 April 1981
3. Alamat : Jl. Teuladan No. 16 Kp. Keuramat Banda Aceh
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Pekerjaan : Pegawai DPKKA
7. Status : Menikah
8. No. Hp : 081360088069
9. E-mail : asri_nad@yahoo.co.id
10.Pendidikan :
a. Lulus SD Negeri No. 67 Banda Aceh tahun 1993.
b. Lulus SMP Negeri 6 Banda Aceh tahun 1996.
c. Lulus SMU Negeri 3 Banda Aceh tahun 1999.
d. Lulus Sarjana (S1) Universitas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2004.
11.Riwayat Pekerjaan :
a. 2005 – sekarang : Staf Bagian Akuntansi Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Aceh
DAFTAR ISI
2.1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ... 10
2.1.2. Laporan Realisasi Anggaran ... 11
2.1.3. Pendapatan Daerah ... 12
2.1.3.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ... 13
2.1.3.1.1. Sumber-sumber pendapatan asli daerah ... 15
2.1.3.1.1.1. Pajak daerah ... 15
2.1.3.1.1.2. Retribusi daerah ... 17
2.1.3.1.1.3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ... 20
2.1.3.1.1.4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah... 21
2.1.3.1.2. Potensi peningkatan PAD ... 22
2.1.3.2. Dana perimbangan ... 25
2.1.3.2.1. Dana Alokasi Umum (DAU) ... 25
2.1.3.2.2. Dana Alokasi Khusus (DAK)... 27
2.1.4. Belanja Daerah ... 28
2.1.4.1. Belanja modal... 29
2.1.4.1.1.1. Klasifikasi aset tetap ... 31
2.1.5. Peranan Pendapatan Asli Daerah Melalui Belanja Modal ... 33
2.1.6. Hubungan DAU dengan Belanja Modal ... 34
2.1.7. Hubungan DAK dengan Belanja Modal ... 35
2.1.8. Hubungan Belanja Modal dengan PAD ... 35
2.1.9. Hubungan DAU dan DAK terhadap Peningkatan PAD . 36 2.2. Review Peneliti Terdahulu (Theoritical Mapping) ... 36
BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS ... 39
3.1. Kerangka Konsep Penelitian ... 39
3.2. Hipotesis ... 41
BAB IV METODE PENELITIAN ... 42
4.1. Jenis Penelitian ... 42
4.2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian ... 42
4.3. Populasi dan Sampel Penelitian ... 42
4.4. Metode Pengumpulan Data ... 44
4.5. Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel ... 45
4.5.1. Peningkatan PAD ... 45
4.6.2.2. Uji multikolinieritas ... 49
4.6.2.3. Uji autokorelasi ... 50
4.6.2.4. Uji heterokedastisitas ... 50
4.7. Pengujian Hipotesis ... 50
4.7.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)... 51
4.7.2. Analisis Jalur Model Trimming ... 52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 53
5.1. Hasil Penelitian ... 53
5.1.1. Deskriptif Sampel Penelitian... 53
5.1.2. Statistik Deskriptif Data Penelitian ... 53
5.4. Pembahasan ... 84
5.4.1. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal ... 85
5.4.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal 85 5.4.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal ... 87
5.4.4. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ... 88
5.4.5. Pengaruh Langsung Dana Alokasi Umum terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ... 89
5.4.6. Pengaruh Langsung Dana Alokasi Khusus terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ... 91
5.4.7. Pengaruh Belanja Modal terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ... 92
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ... 94
6.1. Kesimpulan ... 94
6.2. Keterbatasan Penelitian ... 95
6.3. Saran ... 96
DAFTAR PUSTAKA ... 98
DAFTAR TABEL
No. Judul Halaman
2.1. Review Peneliti Terdahulu……….. 38
4.1. Populasi dan Sampel Penelitian……….. 44
4.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel……….. 47
5.1. Statistik Deskriptif………... 54
5.7. Nilai Koefisien Korelasi Model pada Lag Tiga Tahun... 62
5.8. Uji Statistik Durbin Watson Model pada Lag Satu Tahun... 63
5.9. Uji Statistik Durbin Watson Model pada Lag Dua Tahun... 63
5.10. Uji Statistik Durbin Watson Model pada Lag Tiga Tahun... 64
5.11. Uji Park Model pada Lag Satu Tahun... 65
5.18. Nilai F-Hitung Sub-Struktur 2 pada Lag Satu Tahun... 70
5.19 Nilai Koefisien Model 1 Sub-Struktur 2 pada Lag Satu Tahun... 71
5.20. Nilai Koefisien Model 2 Sub-Struktur 2 pada Lag Satu Tahun ... 72
5.21. Model Summary Model 2 Sub-Struktur 2 pada Lag Satu Tahun.... 73
5.23. Nilai F-hitung Sub-Struktur 2 Lag Dua Tahun... 75
5.24. Nilai Koefisien Model 1 Sub-Struktur 2 pada Lag Dua Tahun... 76
5.25. Nilai Koefisien Model 2 Sub-Struktur 2 pada Lag Dua Tahun... 77
5.26. Model Summary Model 2 Sub-Struktur 2 pada Lag Dua Tahun... 78
5.27. Ringkasan Hasil Koefisien Jalur pada Lag Dua Tahun... 80
5.28. Nilai F-Hitung Sub-Struktur 2 Lag pada lag Tiga Tahun... 80
5.29 Nilai Koefisien Model 1 Sub-Struktur 2 pada Lag Tiga Tahun... 81
5.30. Model Summary Model 2 Sub-Struktur 2 pada Lag Tiga Tahun... 82
DAFTAR GAMBAR
No. Judul Halaman
3.1. Kerangka Konsep……… 39
5.1. Histogram Uji Normalitas Data Model pada Lag Satu Tahun…… 57
5.2. Normal P-P Plot Model Regresi dengan Lag Satu Tahun……….. 57
5.3. Scatterplot... 64
5.4. Kerangka Koefisien Jalur pada Lag Satu Tahun... 74
5.5. Kerangka Koefisien Jalur pada Lag Dua Tahun... 79
5.6. Kerangka Koefisien Jalur pada Lag Tiga Tahun... 83
DAFTAR LAMPIRAN
No. Judul Halaman
1. Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh……. 102
2. Data Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Provinsi Aceh……….. 103
3. Data Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Provinsi Aceh... 104
4. Data Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Aceh... 105
5. Deskriptif Statistik... 106
6. Koefisien………. 107
7. Koefisien Korelasi……….. 108
8. Regresi Sub-Struktur 1 Model 1... 109
9. Chart DAU, DAK terhadap BM... 110
10. Regresi Sub-Struktur 1 Model 2……… 112
11. Regresi Sub-Struktur 2 Model 1 pada Lag Satu Tahun... 113
12. Chart Lag Satu Tahun…………... 114
13. Regresi Sub-Struktur 2 Model 2 pada Lag Satu Tahun... 116
14. Regresi Sub-Struktur 2 Model 1 pada Lag Dua Tahun... 118
15. Chart Lag Dua Tahun…………... 119
16. Regresi Sub-Struktur 2 Model 2 pada Lag Dua Tahun... 121
17. Regresi Sub-Struktur 2 pada Lag Tiga Tahun... 123
18. Chart Lag Tiga Tahun…………... 125
19. Nilai-Nilai untuk Distribusi F... 127
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN/
KOTA PROVINSI ACEH
Hasrina Husni; Dr. Murni Daulay, M.Si dan Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si, Ak
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal sebagai variabel intervening pada lag satu, lag dua dan lag tiga tahun.
Populasi penelitian ini sejumlah 23 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, dan yang memenuhi kriteria disertakan sebagai anggota sampel
sejumlah 20 pemerintah daerah kabupaten/kota. Data pengamatan selama 4 tahun (2004 – 2007) sehingga analisis amatan menjadi 80. Sumber data penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik tentang Laporan Tahunan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis jalur model Trimming.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berkontribusi signifikan sedangkan Dana Alokasi Umum tidak terhadap belanja modal. Pada lag satu tahun, Dana Alokasi Umum, belanja modal berkontribusi signifikan sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pada lag dua tahun Dana Alokasi Umum, belanja modal berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak. Pada lag tiga tahun, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan belanja modal berkontribusi signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
THE INFLUENCE OF BLOCK GRANT, SPECIPIC GRANT TO REGIONAL INCOME IMPROVEMENT WITH CAPITAL EXPENDITURES AS AN
INTERVENING VARIABLE EMPIRICAL STUDY IN THE DISTRICT/ CITY OF PROVINCI ACEH
Hasrina Husni; Dr. Murni Daulay, M.Si and Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si, Ak
ABSTRACT
The purpose of this research is conducted to obtain empirical evidence and analyze the influence of Block Grant (DAU), Specific Grant (DAK) of Regional Income Improvement through Capital Expenditure as an intervening variable in lag one, lag two and lag three years.
The research population of 23 local government districts and cities in Provinci Aceh, which fulfill the criteria included as a member of a sample of 20 local government districts. Observation data for 4 years (2004-2007) so that analysis of observations to 80. Sources of research data is derived from Statistics Indonesia on Annual Reports of A Realization of Budgeting the Local Government Receipt and Expenditure (APBD). Hypothesis examination is performed with path analysis model of Trimming.
Research results show that the specific grant contribute significantly while the block grant is not against capital expenditure. At the lag one year, the block grant, capital expenditure contribute significantly but the specific grant does not to improve in regional income. In the two-year lag of block grant, capital expenditure increase to contribute significantly to the regional income while the specific grant is not. In the three-year, the block grant, specific grant, capital expenditure contribute significantly to improve regional income.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian
diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004, memacu pemerintah daerah untuk menggali potensi
daerahnya masing-masing.
Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan
pendapatan daerahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh
daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Pada Pasal 79 UU Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa,
PAD adalah sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan
uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil
pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan
kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Faktor utama yang dapat meningkatkan jumlah PAD adalah kemampuan dan
keinginan daerah melalui kepala daerah untuk dapat menggali sumber-sumber PAD
wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah
(Haryanto, 2001). Dari data penerimaan Aceh, jumlah PAD Aceh tahun 2005 adalah
141.556.533.242 rupiah, kemudian meningkat di tahun 2006 menjadi
234.854.370.000. Meningkat di tahun 2007 menjadi 317.912.247.000. Tahun 2008
meningkat menjadi 414.164.453.513. Tahun 2009 meningkat sebesar
501.062.000.000 rupiah.
Di dalam TAP MPR No. IV/MPR/2000 ditegaskan bahwasanya kebijakan
desentralisasi daerah diarahkan untuk mencapai peningkatan pelayanan publik dan
pengembangan kreativitas masyarakat serta aparatur pemerintahan di daerah,
kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah itu sendiri
dalam kewenangan dan keuangan untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan,
demokrasi dan kesejahteraan serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian
daerah. Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas maka sumber-sumber
keuangan telah banyak bergeser ke daerah baik melalui perluasan basis pajak (taxing
power) maupun dana perimbangan. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal
yang mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan (1) kewenangan untuk
memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah PAD yang
sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dengan tetap mendasarkan
batas kewajaran, (2) didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan
daerah.
Dana perimbangan diberikan untuk mengatasi adanya kebutuhan pendanaan
Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk
membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi yang
cukup besar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus
(DAK). Proporsi DAU dan DAK yang dialokasikan oleh pemerintah pusat relatif
masih besar bila dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain. Artinya
pemerintah daerah masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Dana transfer dari
pemerintah pusat ke daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Meskipun demikian, menurut Ndandari et.al (2008) yang dikutip dalam Bangun
(2009) bahwa dapat juga terjadi keganjilan di mana terjadi flypaper effect yaitu saat
pemda mendapat transfer dari pemerintah pusat, justru pendapatan masyarakat tidak
meningkat karena transfer tersebut digunakan sepenuhnya untuk kegiatan belanja
pemerintah tanpa diimbangi dengan peningkatan PAD. Menurut Maimunah (2006)
dalam Bangun seharusnya dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan
secara efektif dan efisien oleh pemda untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, selain itu kebijakan penggunaan dana tersebut harus transparan dan
akuntabel.
Untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah
harus mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi belanja modal didasarkan pada
kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan
tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karenanya pemerintah daerah
pelayanan publik yang akan memberikan dampak jangka panjang secara finansial
bagi pemerintah daerah.
Salah satu usaha pemerintah daerah adalah dengan meningkatkan investasi
yang besar pada belanja modal, yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan
pada sektor-sektor produktif. Menurut Mardiasmo (2004), semakin tinggi tingkat
investasi modal, maka semakin tinggi kualitas pelayanan publik. Dengan demikian
tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan juga dapat meningkat yang dapat
mendorong meningkatnya PAD. Semakin masyarakat nyaman dengan fasilitas yang
ada, maka semakin efektif dan efisien usaha yang dijalankan. Keseimbangan
pembangunan daerah lebih dapat tercapai ketika masyarakat memberikan dukungan
yang tinggi.
Agar penyerapan dana menjadi besar untuk belanja modal, maka proses tender
untuk proyek-proyek yang dibiayai dari anggaran belanja modal harus dipercepat.
Dengan demikian, proyek-proyek itu pun cepat bergulir dan roda ekonomi bergerak
(Abdullah, 2008).
Terlepas dari perubahan peraturan perundangan yang mendasari pengelolaan
keuangan daerah yaitu diamandemennya Undang-Undang No. 22/1999 dengan UU
No. 32/2004 dan Kepmendagri No. 29/2002 juga diamandemen dengan Permendagri
N0. 13/2006, pengalokasian sumberdaya ke dalam anggaran belanja modal (capital
expenditure) merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan
politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik
adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses
penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak
efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat (Keefer et.al, 2003 dalam
Abdullah, 2006).
Provinsi Aceh merupakan provinsi yang memiliki sumber daya alam yang
produktif untuk dikembangkan seperti minyak dan gas alam. Sebagai salah satu
daerah yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat melalui
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, proporsi pendapatan untuk sumberdaya minyak dan
gas adalah 70%. Ketetapan itu melebihi otonomi biasa yang mengatur pembagian
pendapatan provinsi hanya 15% dari minyak dan 35% dari gas.
Namun demikian sumber lain harus digali untuk menambah pendapatan
daerah seperti penerimaan yang bersumber dari pajak. Menurut Reksohadiprodjo
(1999), Pajak merupakan bagian terpenting dari penerimaan pemerintah di samping
penerimaan dari minyak bumi dan gas alam serta penerimaan negara bukan pajak.
Apabila suatu daerah ingin mandiri, maka penerimaan dari pajak haruslah
ditingkatkan.
Setelah gempa dan tsunami yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam
tanggal 26 Desember 2004, hampir sebagian sarana prasarana publik seperti gedung,
jalan, jembatan rusak dan bahkan hilang. Hal ini menyebabkan berkurangnya aset
daerah. Untuk memperbaiki kerusakan tersebut, dibentuklah Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Aceh (BRR Aceh). Melalui BRR, segala bantuan dari luar negeri
bantuan tersebut. Seperti dijelaskan dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2002 tentang
Bantuan Luar Negeri dan Pinjaman Provinsi Pasal 1, bahwa bantuan luar negeri
adalah hibah yang diberi oleh pemerintah luar negeri atau lembaga keuangan
internasional atau lembaga lainnya di luar negeri kepada Pemerintah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam.
Dari data BRR-Aceh dalam Waspada (2009), total dana untuk rehabilitasi dan
rekonstruksi Aceh mencapai 25 triliun rupiah dan sejumlah US$7,1 miliar dollar AS
bantuan luar negeri untuk rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh telah direalisasikan
ditambah bantuan-bantuan dari negara lainnya. Bantuan tersebut digunakan untuk
membangun rumah, jalan, jembatan, mesjid, rumah sakit dan rumah yatim piatu.
Dengan adanya bantuan tersebut maka pengeluaran untuk belanja modal yang
seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah menjadi berkurang.
Hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa, dana transfer dalam jangka
panjang berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer akan
mengurangi belanja modal. Pengaruhnya kembali akan menaikkan jumlah PAD
di masa yang akan datang melalui pajak dan retribusi. Prakoso (2004) dalam
Fitriyanti (2009) dalam penelitiannya menemukan bahwa jumlah belanja modal
dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini
menunjukkan bahwa belanja modal sangat dipengaruhi oleh DAU.
Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka peneliti tertarik untuk
Khusus terhadap Peningkatan PAD dengan Belanja Modal sebagai Variabel
Intervening”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja
modal sebagai variabel intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh?
2. Apakah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal berpengaruh
langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada lag satu tahun
di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh?
3. Apakah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal berpengaruh
langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada lag dua tahun
di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh?
4. Apakah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal berpengaruh
langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada lag tiga tahun
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
memperoleh bukti empiris dan menganalisis:
1. Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja modal
sebagai variabel intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
2. Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal terhadap
peningkatan pendapatan asli daerah pada lag satu tahun di Kabupaten/Kota
Provinsi Aceh.
3. Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal terhadap
peningkatan pendapatan asli daerah pada lag dua tahun di Kabupaten/Kota
Provinsi Aceh.
4. Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal terhadap
peningkatan pendapatan asli daerah pada lag tiga tahun di Kabupaten/Kota
Provinsi Aceh.
1.4. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan
manfaat berarti yaitu:
1. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah;
2. Bagi pemerintah kabupaten/kota khususnya di Provinsi Aceh diharapkan
dapat memberikan sumbangan pikiran untuk peningkatan Pendapatan Asli
3. Bagi peneliti berikutnya dapat berguna sebagai bahan masukan, referensi dan
perbandingan dalam penelitian lebih lanjut.
1.5. Originalitas
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Adi (2006) yang meneliti
Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan
Pendapatan Asli Daerah dan Harianto (2007) yang meneliti Hubungan antara Dana
Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:
1. Variabel penelitian terdahulu adalah Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi
Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Sedangkan pada penelitian
ini, variabel independennya adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
Khusus. Variabel dependennya adalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
dengan penambahan variabel intervening Belanja Modal.
2. Sampel penelitian terdahulu adalah Kabupaten dan Kota se-Jawa dan Bali dalam
kurun waktu tahun 1998-2003 dan tahun 2001-2004. Namun dalam penelitian
saat ini pengambilan sampel adalah 20 Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
Dalam bab ini akan dibahas lebih jauh mengenai Dana Alokasi Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mempengaruhi Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah (PPAD) melalui Belanja Modal (BM) sebagai variabel intervening.
Menjabarkan teori-teori yang melandasi penelitian ini dengan referensi atau
keterangan tambahan yang dikumpulkan selama penelitian.
2.1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Dalam Darwanto (2007), anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang
menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dokumen anggaran daerah
di Indonesia disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses
penyusunan anggaran melibatkan dua pihak yaitu eksekutif dan legislatif,
masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Fungsi eksekutif (pemerintah
daerah) adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran
daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan
legislatif (perwakilan rakyat) berperan aktif dalam melaksanakan legislasi,
penganggaran, dan pengawasan. Penyusunan APBD diawali dengan membuat
kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum APBD dan
prioritas dan plafon anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan
sesuai dengan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran yang
kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama
sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda). Dalam perspektif keagenan, hal
ini merupakan bentuk kontrak (incomplete contract), yang menjadi alat bagi legislatif
untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk
pengawasan ini sesuai dengan agency theory yang mana pemerintah daerah sebagai
agen yang menerima pendelegasian otoritas dari prinsipal dan DPRD sebagai
prinsipal yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006
Pasal 21 dijelaskan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember. Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
2.1.2. Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dalam Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer,
surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna
laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya
(a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber
daya ekonomi;
(b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang
berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan
efektivitas penggunaan anggaran.
LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya
ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah
dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. LRA
dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi
perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
(a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
(b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
(c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.1.3. Pendapatan Daerah
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Pasal 20, Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas
umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar
kembali oleh daerah.
Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan daerah adalah hak
pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan perkiraan yang terukur
secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh
pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang
mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh
dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan
tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka
bagi hasil.
Menurut Kadjatmiko dalam Halim (2004: 194), dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan
pada azas desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan
retribusi (tax assignment) serta bantuan keuangan (grant transfer). Pendapatan daerah
terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah.
2.1.3.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan
daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang No. 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah menyebutkan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menurut Mardiasmo (2004: 132), PAD adalah penerimaan yang diperoleh
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah.
PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam
wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Terdapat dua unsur
penting dari konsep PAD yaitu potensi asli daerah dan pengelolaannya sepenuhnya
oleh daerah. Dalam konteks pembiayaan pembangunan daerah, potensi asli daerah
adalah seluruh sumber daya daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan
sehingga memberi nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber
pembiayaan pembangunan daerah. Sedangkan pengelolaan sepenuhnya oleh daerah
adalah penyerahan seluruh hasil pengelolaan sumber daya tersebut kepada daerah
yang bersangkutan (Suhanda, 2007).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 79 disebutkan
bahwa PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan
milik daerah, hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang dipisahkan. Pasal 3 UU Nomor 33 Tahun 2004 PAD
bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai
pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan
desentralisasi. Kemampuan melaksanakan otonomi daerah diukur dari besarnya
kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap total APBD. PAD idealnya menjadi
sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan
2.1.3.1.1. Sumber-sumber pendapatan asli daerah
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 disebutkan bahwa
kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan terdiri atas:
2.1.3.1.1.1. Pajak daerah
Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 1: pajak daerah
adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa
imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut Halim (2004: 67), pajak
daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jadi pajak dapat
diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk
menghasilkan pendapatan disuatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan
prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya
yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut. Pajak merupakan pungutan yang
bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada
timbal balik langsung kepada para pembayar pajak.
Menurut Adriani, pajak objektif dilihat pada objeknya (benda, keadaan,
perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak)
kemudian baru dicari subjeknya baik yang berkediaman di Indonesia maupun tidak.
diantaranya pajak kekayaan, pajak pendapatan, pajak karena menggunakan benda
yang kena pajak; (b) Pajak yang dipungut karena perbuatan diantaranya pajak lalu
lintas kekayaan, pajak lalu lintas hukum, pajak lalu lintas barang, serta pajak atas
pemakaian; (c) Pajak yang dipungut karena peristiwa diantaranya bea pemindahan
di Indonesia contohnya pemindahan harta warisan.
Pajak daerah terdiri dari pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Dalam UU
RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2, jenis
pajak provinsi terdiri dari:
a. Pajak Kendaraan Bermotor.
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
d. Pajak Air Permukaan.
e. Pajak Rokok.
Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:
a. Pajak Hotel.
b. Pajak Restoran.
c. Pajak Hiburan.
d. Pajak Reklame.
e. Pajak Penerangan Jalan.
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
g. Pajak Parkir.
i. Pajak Sarang Burung Walet.
j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 menyebutkan bahwa, daerah
dilarang memungut pajak selain jenis pajak di atas. Jenis pajak tersebut dapat tidak
dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan
daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.1.3.1.1.2. Retribusi daerah
Pengertian retribusi daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan. Menurut Halim (2004: 67), retribusi daerah merupakan
pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Menurut Kaho dalam Syahputra
(2010), secara umum keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah
karena pemungutan retribusi berdasarkan kontraprestasi, di mana tidak ditentukan
secara limitatif seperti halnya sektor pajak. Pembatas utama bagi sektor retribusi
adalah terletak pada ada tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah. Daerah
kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya
dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi
Pasal 108 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan objek retribusi terdiri dari:
a. Jasa Umum
Kriteria retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi
jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. Jasa yang bersangkutan merupakan
kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jasa tersebut memberi
manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi,
di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, jasa tersebut layak
untuk dikenakan retribusi. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional
mengenai penyelenggaraannya, dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan pemungutan
retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas
pelayanan yang lebih baik.
Jenis retribusi jasa umum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 adalah
retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi
penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi
pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan
umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi
pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta,
retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair,
retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan dan retribusi
Jenis Retribusi tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau
atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara
cuma-cuma.
b. Jasa Usaha
Pada Pasal 126 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa objek
retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan
menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/
memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau
pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh
pihak swasta.
Jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah,
retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi
terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/
pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan
kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air
dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
c. Retribusi Perizinan Tertentu
Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan
kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi, perizinan tersebut benar-benar
diperlukan guna melindungi kepentingan umum dan biaya yang menjadi beban
negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi
perizinan.
2.1.3.1.1.3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Menurut Halim (2004: 68), hasil perusahaan milik daerah dan hasil
pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah
yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek
pendapatan mencakup:
a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau
kelompok usaha masyarakat.
Menurut Halim (2004: 68), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan
berikut: 1) bagian laba perusahaan milik daerah, 2) bagian laba lembaga keuangan
bank, 3) bagian laba lembaga keuangan non bank, 4) bagaian laba atas penyertaan
modal/investasi. Dalam Mardiasmo (2004: 154), pemerintah daerah juga dapat
melakukan upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sidik et.al (2004: 85)
mengatakan BUMD sebenarnya juga merupakan salah satu potensi sumber keuangan
kontribusi laba BUMD pada PAD dapat menjadi indikator kuat atau lemahnya
BUMD dalam suatu daerah.
2.1.3.1.1.4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Menurut Halim (2004: 69), pendapatan ini merupakan penerimaan daerah
yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi
objek pendapatan berikut, 1) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan,
2) penerimaan jasa giro, 3) penerimaan bunga deposito, 4) denda keterlambatan
pelaksanaan pekerjaan, 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan
daerah.
Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk
menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah,
retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci
menurut obyek pendapatan yang mencakup:
a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
b. Jasa giro.
c. Pendapatan bunga.
d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing.
h. Pendapatan denda pajak.
i. Pendapatan denda retribusi.
j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
k. Pendapatan dari pengembalian.
l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan
n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
2.1.3.1.2. Potensi peningkatan PAD
Dari sisi perundang-undangan, peluang ke arah peningkatan PAD terbuka
melalui peningkatan tarif maupun perluasan pajak daerah sebagaimana diatur oleh
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pada Pasal 2 undang-undang ini memberi
keleluasaan untuk menambah jenis-jenis pajak baru dengan kriteria:
a. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang
bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya
melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
c. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan
umum.
d. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan/atau obyek pajak
pusat.
e. Potensinya memadai.
g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan
h. Menjaga kelestarian lingkungan.
Menurut Mardiasmo (2004: 148), otonomi daerah tidak berarti eksploitasi
daerah untuk menghasilkan PAD setinggi-tingginya. Jika otonomi diartikan sebagai
eksploitasi PAD, maka justru masyarakat daerahlah yang akan terbebani.
Maksimalisasi PAD akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan
retribusi daerah, karena penyumbang terbesar PAD adalah dua komponen tersebut.
Pemerintah daerah sebaiknya tidak menambah pungutan yang bersifat pajak, jika mau
menambah hendaknya yang bersifat retribusi, sedangkan pajak justru diupayakan
sebagai the last effort saja.
Menurut Widayat (1995) dalam Calangona (2009), upaya untuk
meningkatkan penerimaan PAD agar penerimaannya mendekati atau bahkan sama
dengan potensinya, secara umum ada dua cara, yaitu dengan cara intensifikasi dan
ekstensifikasi.
a. Cara intensifikasi adalah mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan
mengefisienkan cara pemungutannya pada obyek dan subyek yang sudah ada
misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan
dan pelayanan.
b. Cara ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD
dengan cara menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau
Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 7 disebutkan bahwa dalam upaya
meningkatkan PAD, daerah dilarang:
a. menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan
ekonomi biaya tinggi.
b. menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas
penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PPAD) adalah kenaikan pendapatan
yang diperoleh pada tahun berikutnya dari sumber-sumber pendapatan daerah. PPAD
dilihat pada tahun kesatu (lag satu tahun), tahun kedua (lag dua tahun) dan tahun
ketiga (lak tiga tahun). Dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dalam
upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, agar tidak menetapkan
kebijakan pemerintahan daerah yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan
sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, law
enforcement dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi
daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan
asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang dibarengi dengan
peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya
2.1.3.2. Dana perimbangan
Dalam PP Nomor 55 Tahun 2005, Dana Perimbangan adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Bastian (2006:
338), perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah
suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang
mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta
pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan
memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban
dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut,
termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Pada Pasal 23 PP 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dana perimbangan meliputi Dana Bagi
Hasil, DAU dan DAK. Sidik et al. (2004: 152), dalam konteks Indonesia dewasa ini,
transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah adalah dalam wujud DAU dan DAK.
2.1.3.2.1. Dana Alokasi Umum (DAU)
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 1 DAU adalah
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi, kabupaten dan
kota yang besarannya ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam
negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan
kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan
kabupaten/kota. DAU bersifat block Grand yang berarti penggunaannya diserahkan
kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan
pembangunan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
Dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 bahwa DAU
diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai,
kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik
sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan
umum yang dibutuhkan masyarakat.
Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan
berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Hasil
penghitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan
Presiden (Kepres). Dalam Pasal 36 PP 25/2005, Penyaluran DAU dilaksanakan
setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari DAU daerah yang
2.1.3.2.2. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pengertian DAK menurut PP 55/2005, Pasal 1 adalah dana yang bersumber
dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan
sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Sidik et.al. (2004) DAK merupakan
transfer dana yang bersifat spesifik, yaitu untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah
digariskan (specific grant).
Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 38 bahwa besaran DAK ditetapkan
setiap tahun dalam APBN. Pada Pasal 39, DAK dialokasikan kepada daerah tertentu
untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.
Dalam Permendagri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, menerangkan bahwa penggunaan dana
perimbangan untuk DAK agar dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai
kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain
program kegiatan pendidikan dan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk
teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria
khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan
teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis. Dalam Kuncoro
(2004), DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus.
Karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan
wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam DAK
meliputi:
1) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak
mempunyai akses yang memadai ke daerah lain
2) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung
transmigrasi.
3) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/
kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai.
Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping
sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK yang dianggarkan dalam APBD.
Namun daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan
dana pendamping.
2.1.4. Belanja Daerah
Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pasal 20, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah
yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu
tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pada
Pasal 26, belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan
dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan
perundang-undangan.
Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban
daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan
sistem jaminan sosial.
Sesuai dengan Teori Keynes (Keynesian Consumption Model) bahwa
konsumsi saat ini (current consumption) sangat dipengaruhi oleh pendapatan
disposabel saat ini (current disposable income). Jika pendapatan disposabel
meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja peningkatan konsumsi
tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan disposabel (Sudiana, 2010).
Belanja dapat diklasifikasikan menurut jenis belanja yaitu belanja pegawai,
belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja
bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
2.1.4.1. Belanja modal
Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.06/2007 tentang
Bagan Akun Standar (BAS) mendefinisikan belanja modal adalah pengeluaran
anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan
aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi
Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan
kerja, bukan untuk dijual.
Menurut Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan, suatu
belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:
(a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset
lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
(b) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau
aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.
(c) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
Pada Pasal 53 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam
kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/
pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja
modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.
2.1.4.1.1. Aset tetap
Dalam PSAP 07 menyebutkan Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca
di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya.
Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang
Aset Tetap dalam PSAP adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka
pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap
tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah
sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah tetapi
tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah tidak termasuk
dalam pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap di atas,
misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat.
2.1.4.1.1.1. Klasifikasi aset tetap
Dalam PSAP 07, aset tetap di neraca diklasifikasikan menjadi enam akun
sebagaimana dirinci dalam penjelasan berikut ini:
a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau
dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang
digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah
yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut.
b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan
dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam