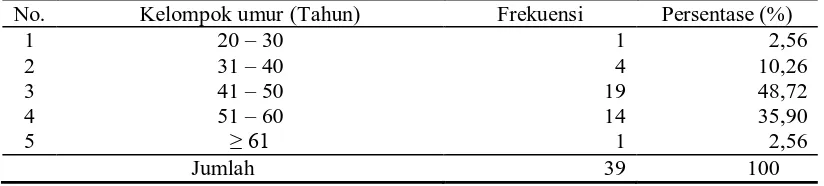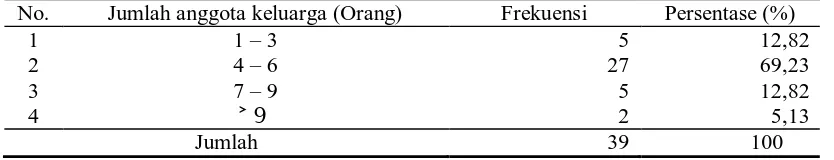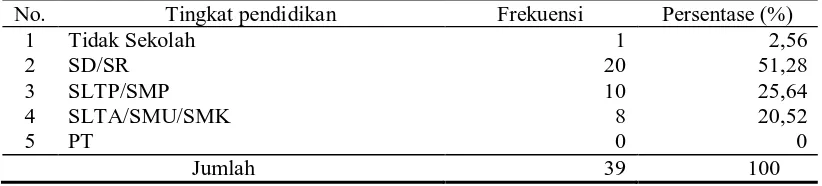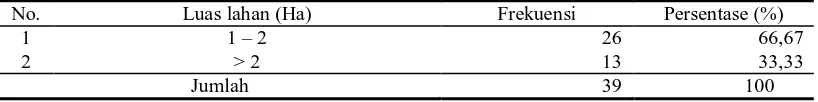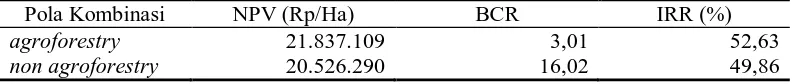ANALISIS FINANSIAL BUDI DAYA KEMENYAN
RAKYAT DALAM SISTEM AGROFORESTRY
(Studi Kasus di Desa Pangurdotan, Kecamatan Pahae
Julu, Kabupaten Tapanuli Utara)
SKRIPSI
JOSUA K. GULTOM
041201030
DEPARTEMEN KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
ABSTRAK
JOSUA K. GULTOM. Analisis Finansial Budi Daya Kemenyan Rakyat dalam Sistem Agroforestry (Studi Kasus di Desa Pangurdotan, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara). Di bawah bimbingan ODING AFFANDI dan EDY BATARA MULYA SIREGAR.
Analisis finansial merupakan suatu cara untuk mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan, manfaat dan keuntungan yang diperoleh, dan waktu untuk memperoleh pengembalian investasi pada tingkat suku bunga tertentu. Adanya perubahan lahan di Desa Pangurdotan dari lahan non agroforestry menjadi
agroforestry, menjadi dasar untuk melakukan analisis finansial di daerah tersebut.
Metode yang digunakan adalah Metode analisis deskriptif dan analisis finansial dengan menghitung besarnya Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR) dan Internal Rate of Return (IRR).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab perubahan lahan non
agroforestry menjadi agroforestry dan membandingkan tingkat kelayakan finansial
kedua sistem tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab masyarakat mengubah lahan mereka dari non agroforestry menjadi agroforestry adalah karena secara finansial sistem agroforestry lebih menguntungkan. Nilai NPV yang diperoleh dengan sistem agroforestry adalah Rp. 21.837.109,- selama 15 tahun/ha, sedangkan dengan sistem non agroforestry adalah Rp. 20.526.290 selama 15 tahun/ha. Nilai BCR dan IRR untuk sistem agroforestry adalah 3,01 dan 52,63% dan untuk non agroforestry adalah 16,02 dan 49,86% dengan tingkat suku bunga yang berlaku, yaitu 6,5%. Kedua sistem tersebut adalah layak secara finansial, dan yang paling optimal adalah sistem agroforestry.
ABSTRACT
JOSUA K. GULTOM. Financial Analysis of Kemenyan Cultivation in
Agroforestry System (Study Case in Pangurdotan, Subdistrict of Pahae Julu, District of Tapanuli Utara). Under Supervision of ODING AFFANDI and
EDY BATARA MULYA SIREGAR.
Financial Analysis is a way to find out the amount of costs, benefits and profits obtained, and time to obtain the investment return at a certain rate. Conversion of land in Pangurdotan of non agroforestry into agroforestry became the basis for financial analysis in the area. The methode used are descriptive analysis and financial analysis by calculating Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR) dan Internal Rate of Return (IRR).
The purpose of this study is to determine the cause of changes non agroforestry into agroforestry and to compare feasibility level of financial of two systems. The result shows that the cause of the people to change their land is because it is financially more profitable. The NPV value of agroforestry system is Rp. 21.837.109,- for 15 years/ha, whereas with non agroforestry system, the NPV value is RP. 20.256.290,- for 15 years/ha. BCR and IRR value of agroforestry system are 3,01 and 52,63% and for non agroforestry system are 16,02 and 49,86% with the level of interest rate is 6,5%. Both of the two systems is financially feasible, and the most optimal is the agroforestry system.
RIWAYAT HIDUP
Josua K. Gultom dilahirkan di Taurutng pada tanggal 14 Juli 1986. Penulis
merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan T. L. Gultom dan H.
Situmorang.
Pada tahun 2001 Penulis mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas
Swasta HKBP 2, Tarutung. Melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
(SPMB) pada tahun 2004, Penulis masuk di Universitas Sumatera Utara, Fakultas
Pertanian, Departemen Kehutanan, Program Studi Manajemen Hutan.
Selama mengikuti perkuliahan, penulis menjadi salah satu anggota
organisasi HIMAS (Himpunan Mahasiswa Sylva). Pada tahun 2006 Penulis
melaksanakan Praktek Pengelolaan dan Pembinaan Hutan (P3H) di Taman
Nasional Batang Gadis (TNBG), Kecamatan Mandailing Natal, Kabupaten
Tapanuli Selatan. Pada akhir studi penulis mengikuti Praktek Kerja Lapangan
(PKL) di HPHTI PT. Arara Abadi, Kabupaten Siak, Pekanbaru, Riau pada tanggal
15 Juni sampai 8 Agustus 2009. Untuk dapat menyelesaikan studi, penulis
melakukan penelitian dengan judul ”Analisis Finansial Budi Daya Kemenyan
Rakyat Dalam Sistem Agroforestry (Studi Kasus di Desa Pangurdotan, Kecamatan
Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara)” dibawah bimbingan Bapak Oding Affandi,
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan berkat dan rahmat-Nya berupa kesehatan dan kesempatan kepada
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Skripsi ini berjudul “Analisis Finansial Budi Daya Kemenyan Rakyat
Dalam Sistem Agroforestry (Studi Kasus di Desa Pangurdotan, Kecamatan
Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara)”. Penelitian ini merupakan salah satu
syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Departemen Kehutanan, Fakultas
Pertanian, Universitas Sumatera Utara.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak
Oding Affandi, S.Hut, M.P dan Bapak Dr. Ir. Edy Batara Mulya Siregar, MS selaku
komisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, karena itu
penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk
penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat.
Medan, Desember 2010
DAFTAR ISI
Manfaat Penelitian... 3
TINJAUAN PUSTAKA Deskripsi Tanaman Kemenyan ... 5
Manfaat/Kegunaan Kemenyan ... 5
Pengertian dan Fungsi Agroforestry ... 8
Klasifikasi Sistem Agroforestry ... 10
Pola Kombinasi Komponen dalam Sistem Agroforestry... 12
Analisis Finansial Agroforestry ... 13
METODE PENELITIAN Tempat dan Waktu Penelitian ... 17
Pengumpulan Data ... 17
Pengolahan Data... 18
HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Responden... 21
Hal-hal yang Menyebabkan Terjadinya Perubahan Pengusahaan Lahan dari non agroforestry menjadi agroforestry ... 25
Analisis Finansial ... 26
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 30
Saran ... 30
DAFTAR TABEL
Hal.
1. Penyebaran responden berdasarkan umur ... 21
2. Penyebaran responden berdasarkan jumlah anggota keluarga ... 22
3. Penyebaran responden berdasarkan pendidikan ... 23
4. Penyebaran responden berdasarkan jumlah tenaga kerja ... 24
5. Penyebaran responden berdasarkan luas lahan agroforestry... 24
DAFTAR LAMPIRAN
Hal.
1. Kuisioner ... 33
2. Karakteristik dan pendapatan responden... 37
3. Tabulasi frekuensi ... 39
4. Analisis biaya dan manfaat sistem agroforestry di Desa Pangurdotan ... 43
5.Analisis biaya dan manfaat sistem non-agroforestry di Desa Pangurdotan ... 44
6.Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), dan Internal Rate Or Return (IRR) usaha kemenyan dalam sistem agroforestry di Desa Pangurdotan 45 7. Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), dan Internal Rate Or Return (IRR) usaha kemenyan dalam sistem non agroforestry di Desa Pangurdotan 46 8. Dokumentasi penelitian ... 47
9. Peta lokasi penelitian Desa Pangurdotan ... 52
10. Surat keterangan Kepala Desa pangurdaotan ... 53
ABSTRAK
JOSUA K. GULTOM. Analisis Finansial Budi Daya Kemenyan Rakyat dalam Sistem Agroforestry (Studi Kasus di Desa Pangurdotan, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara). Di bawah bimbingan ODING AFFANDI dan EDY BATARA MULYA SIREGAR.
Analisis finansial merupakan suatu cara untuk mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan, manfaat dan keuntungan yang diperoleh, dan waktu untuk memperoleh pengembalian investasi pada tingkat suku bunga tertentu. Adanya perubahan lahan di Desa Pangurdotan dari lahan non agroforestry menjadi
agroforestry, menjadi dasar untuk melakukan analisis finansial di daerah tersebut.
Metode yang digunakan adalah Metode analisis deskriptif dan analisis finansial dengan menghitung besarnya Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR) dan Internal Rate of Return (IRR).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab perubahan lahan non
agroforestry menjadi agroforestry dan membandingkan tingkat kelayakan finansial
kedua sistem tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab masyarakat mengubah lahan mereka dari non agroforestry menjadi agroforestry adalah karena secara finansial sistem agroforestry lebih menguntungkan. Nilai NPV yang diperoleh dengan sistem agroforestry adalah Rp. 21.837.109,- selama 15 tahun/ha, sedangkan dengan sistem non agroforestry adalah Rp. 20.526.290 selama 15 tahun/ha. Nilai BCR dan IRR untuk sistem agroforestry adalah 3,01 dan 52,63% dan untuk non agroforestry adalah 16,02 dan 49,86% dengan tingkat suku bunga yang berlaku, yaitu 6,5%. Kedua sistem tersebut adalah layak secara finansial, dan yang paling optimal adalah sistem agroforestry.
ABSTRACT
JOSUA K. GULTOM. Financial Analysis of Kemenyan Cultivation in
Agroforestry System (Study Case in Pangurdotan, Subdistrict of Pahae Julu, District of Tapanuli Utara). Under Supervision of ODING AFFANDI and
EDY BATARA MULYA SIREGAR.
Financial Analysis is a way to find out the amount of costs, benefits and profits obtained, and time to obtain the investment return at a certain rate. Conversion of land in Pangurdotan of non agroforestry into agroforestry became the basis for financial analysis in the area. The methode used are descriptive analysis and financial analysis by calculating Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR) dan Internal Rate of Return (IRR).
The purpose of this study is to determine the cause of changes non agroforestry into agroforestry and to compare feasibility level of financial of two systems. The result shows that the cause of the people to change their land is because it is financially more profitable. The NPV value of agroforestry system is Rp. 21.837.109,- for 15 years/ha, whereas with non agroforestry system, the NPV value is RP. 20.256.290,- for 15 years/ha. BCR and IRR value of agroforestry system are 3,01 and 52,63% and for non agroforestry system are 16,02 and 49,86% with the level of interest rate is 6,5%. Both of the two systems is financially feasible, and the most optimal is the agroforestry system.
I. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Hutan rakyat merupakan salah satu model pengelolaan sumber daya alam
yang berdasarkan inisiatif masyarakat. Hutan rakyat di Indonesia pada umumnya
dikembangkan pada lahan milik masyarakat yang diakui pada tingkat lokal (tanah
adat) maupun di tanah milik yang diakui secara formal oleh pemerintah. Dalam
hutan rakyat diusahakan tanaman pohon-pohon yang hasil utamanya kayu: sengon
(Paraserianthes falcataria), akasia (Accacia auriculiformis); hasil utamanya getah
: kemenyan (Styrax benzoin), damar (Shorea javanica); maupun hasil utamanya
buah: kemiri (Aleurites moluccana) dan bambu (Bambosaa spp) (Suharjito dan
Darusman, 1998).
Pelestarian hutan, yang dewasa ini menjadi isu global, bukan bermaksud
untuk melarang sama sekali manusia memanfaatkan hutan beserta hasilnya. Yang
diinginkan oleh ide pelestarian hutan itu adalah bahwa hutan dimanfaatkan oleh
manusia dengan cara yang arif. Yakni cara pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan
rakyat banyak, dengan senantiasa mengutamakan kesinambungan fungsi-fungsi
ekonomi dan ekologi hutan. Cara-cara pemanfaatan hutan yang arif ini sebenarnya
sudah dipraktikkan oleh rakyat di kebanyakan kampung-kampung hutan. Meski
mereka memanfaatkan hutan untuk kepentingan ekonominya, namun mereka tetap
mengindahkan kepentingan lingkungan dengan cara-cara yang jauh dari sifat tamak
dan serakah. Tetapi karena praktik-praktik pengelolaan hutan tersebut tidak lahir
dari hasil kajian 'ilmiah' maka seringkali "praktik orang kampung" itu direndahkan
ini paling didengarkan seruannya oleh penguasa. Dia bisa menuduh dan membela
diri saat ditemukan kesalahannya (Zuska, 2005).
Salah satu jenis tanaman yang terdapat pada hutan rakyat adalah kemenyan.
Salah satu daerah pengembangan kemenyan ini adalah di Desa Pangurdotan.
Pengembangan hutan rakyat kemenyan di Pangurdotan merupakan upaya untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tersebut, karena keberadaan hutan
rakyat mempunyai arti penting bagi peningkatan keadaan sosial ekonomi
masyarakat. Selain itu hutan rakyat mempunyai arti penting dalam upaya menjaga
tata air, pemanfaatan lahan kering dan terlantar. Tanaman kemenyan merupakan
jenis tanaman yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Pangurdotan dan secara
turun temurun telah dipertahankan oleh masyarakat tersebut, sehingga komoditi ini
menjadi ciri khas masyarakat Pangurdotan.
Sebelum sistem agroforestry diterapkan, masyarakat Desa Pangurdotan
mengelola lahannya dengan sistem non agroforestry dengan kemenyan sebagai
komoditi utama. Setelah Sistem agroforestry diterapkan, petani di Desa
Pangurdotan mengkombinasikan tanaman kehutanan (kemenyan) dengan tanaman
musiman (padi). Kombinasi tanaman kehutanan dengan musiman disebut juga
dengan agroforestry tipe agrisilfikultur.
Pengelolaan lahan dengan sistem agroforestry dianggap sebagai alternatif
yang paling memungkinkan bagi pemilik lahan dalam upaya meningkatkan
pendapatan ekonominya. Namun dalam kenyataan dilapangan, khususnya kondisi
lahan di Desa Pangurdotan yang menjadi lokasi penelitian, penerapan proporsi
kombinasi tanaman tidak seimbang (ada komponen yang dominan). Hal ini yang
mengetahui penyebab masyarakat mengubah sistem pengelolaan lahan di desa
tersebut dan kelayakan finansial budidaya kemenyan dengan penerapan sistem
agroforestry.
Perumusan Masalah
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa petani di Desa
Pangurdotan mengubah lahan non-agroforesty menjadi lahan agroforesty,
Bagaimana tingkat kelayakan pengusahaan lahan secara finansial yang diusahakan
petani dalam sistem non-agroforestry dibandingkan dengan sistem agroforestry?.
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penyebab terjadinya perubahan
pengusahaan lahan di Desa Pangurdotan dan membandingkan kelayakan finansial
pengusahaan lahan dalam sistem agroforestry dengan sistem non-agroforestry.
Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah sebagai informasi bagi masyarakat yang
terdapat di Pangurdotan, agar dapat menerapkan pola kombinasi kemenyan dalam
sistem agroforestry yang memberikan kelayakan secara finansial dan
meningkatkan pengetahuan dan wawasan dari para pembaca tentang kelayakan
II. TINJAUAN PUSTAKA
Hutan rakyat adalah hutan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh
organisasi masyarakat baik pada lahan individu, komunal (bersama), lahan adat,
maupun lahan yang dikuasai oleh negara. Hutan rakyat tersusun dari satuan
ekosistem kehidupan mulai dari tanaman keras, non kayu, satwa, buah-buahan,
satuan budi daya semusim, peternakan, barang dan jasa, serta rekreasi alam
(Awang dkk. 2002).
Salah satu solusi untuk mengurangi tekanan terhadap hutan dan mengatasi
masalah kebutuhan lahan pertanian adalah dengan menerapkan sistem agroforestry.
Agroforestry merupakan sistem pemanfaatan lahan secara optimal berasaskan
kelestarian lingkungan dengan mengusahakan atau mengkombinasikan tanaman
kehutanan dan pertanian (perkebunan, ternak) sehingga dapat meningkatkan
perekonomian petani di pedesaan (Gautama, 2007).
Lembaga Penelitian IPB (1983) dalam Purwanto dkk. (2004) membagi
hutan rakyat dalam tiga kelompok, yaitu:
1. Hutan rakyat murni (monoculture), yaitu hutan rakyat yang hanya terdiri dari
satu jenis tanaman pokok berkayu yang ditanam secara homogen atau
monokultur.
2. Hutan rakyat campuran (polyculture), yaitu hutan rakyat yang terdiri dari
berbagai jenis pohon-pohonan yang ditanam secara campuran.
3. Hutan rakyat wana tani (agroforestry), yaitu yang mempunyai bentuk usaha
pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain yang dikembangkan
secara terpadu.
Pengembangan hutan rakyat dengan komoditi tertentu dapat memperbaiki
mutu lingkungan disamping meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan
iklim mikro yang baik, memperbaiki struktur tanah, dan mengendalikan erosi. Hal
tersebut menjadikan hutan rakyat merupakan salah satu teknik konservasi tanah dan
air secara vegetatif (Purwanto, dkk. 2004). Pembangunan hutan rakyat secara
swadaya merupakan alternatif yang dipilih untuk mengatasi masalah sosial
ekonomi dan lingkungan hidup, selain itu pengaruh positif yang lain adalah
terpeliharanya sumberdaya alam (konservasi tanah dan air) sehingga meningkatkan
daya dukung lahan bagi penduduk dan ikut serta dalam pengelolaan Daerah Aliran
Sungai (DAS), mengurangi terjadinya kerusakan hutan akibat penebangan liar dan
penyerobotan tanah. Kombinasi berbagai jenis tanaman memungkinkan pemetikan
hasil secara terus menerus dan memungkinkan terbentuknya stratifikasi tajuk
sehingga mencegah erosi tanah dan hempasan air hutan (Arief, 2001).
Deskripsi Tanaman Kemenyan
Kemenyan (Styrax spp.) termasuk jenis pohon berukuran besar yaitu dari
famili Styracaceae. Adapun urutan sistematika kemenyan adalah sebagai berikut:
Kingdom : Plantae
Superdivision : Spermatophyta
Division : Angiospermae
Class : Dikotil
Family : Styracaceae
Genus : Styrax
Species : Styrax sumatrana dan Styrax benzoin
Di Indonesia terdapat tujuh jenis atau varietas kemenyan (Styrax spp.) yang
menghasilkan getah akan tetapi hanya dua jenis yang lebih umum dikenal dan
diusahakan di Sumatera Utara, yaitu Styrax sumatrana J.J.SM yang disebut dengan
kemenyan toba dan Styrax benzoin DRYAND yang disebut dengan kemenyan
(haminjon) durame. Dari kedua jenis ini tersebut, jenis yang pertama lebih dominan
karena memiliki kualitas getah yang lebih baik dan bernilai ekonomi lebih tinggi
dibandingkan dengan jenis yang terakhir (Sasmuko, 2000).
Ciri khas kemenyan toba (Styrax sumatrana) adalah kandungan atau kadar
asam sinamatnya cukup tinggi. Jelas bahwa jenis ini dapat menghasilkan getah
kualitas pertama dengan ciri-ciri memiliki aroma yang lebih wangi, berwarna putih
dan tidak lengket. Sedangkan ciri khas jenis kemenyan durame (Styrax benzoin)
bahwa jenis ini dapat menghasilkan getah kemenyan seperti tahir yang memiliki
kualitas getah lebih rendah dengan ciri-ciri berwarna hitam kecoklatan dan agak
lengket.
Manfaat/Kegunaan Kemenyan
Penggunaan kemenyan untuk industri dalam negeri sampai saat ini masih
terbatas, relatif kecil dan belum banyak diketahui serta diteliti kegunaannya,
kecuali dibakar sebagai bahan dupa dalam penyelenggaraan upacara-upacara
Ekstraksi kimia getah kemenyan menghasilkan tincture dan benzoin resin
yang digunakan sebagai fix active agent dalam industri parfum. Ekstraksi
kemenyan juga dapat menghasilkan beberapa senyawa kimia yang diperlukan oleh
industri farmasi antara lain asam balsamat, asam sinamat, benzyl benzoate, sodium
benzoate, benzophenone, ester aromatis dan sebagainya. Di negara-negara industri
maju seperti negara Eropa, kemenyan (Styrax spp.) dipergunakan sebagai bahan
dasar dalam pembuatan asam benzoate atau asam sinamat dan ester-esternya,
industri farmasi (obat-obatan), industri kosmetika dan bahan pembuatan parfum,
pabrik porselin, sabun, plastik sintetis, bahan pengawet pada industri makanan dan
sebagainya.
Penggunaan kemenyan dari segi pemakaiannya sebagai bahan kimia yaitu
antara lain:
1. Pada bidang farmasi (obat-obatan)
Penggunaan kemenyan sebagai obat-obatan telah lama dipergunakan. Hal ini
dibuktikan dari berbagai literatur kimia, yaitu:
- Antiseptik
- Obat mata bagi penyakit kataraks
- Expectorant (melegakan pernafasan)
2. Pada obat-obatan pertanian
Melalui proses esterifikasi, asam sinamat dipergunakan untuk membentuk
ester-ester, seperti metil dan etil ester. Beberapa turunan kimianya dapat
3. Pada parfum
Pada parfum dipergunakan sebagai fix active, yaitu untuk menahan aroma
parfum lebih lama dan mempertemukan dua atau beberapa jenis parfum dari
bahan yang berbeda untuk mendapatkan aroma parfum yang lebih baik.
4. Pada Kosmetik
5. Pabrik rokok dan pabrik porselin
6. Kegiatan religius/upacara agama (dupa)
7. Varnis
Berdasarkan uji coba pembutan varnish dari kemenyan ternyata kemenyan
menghasilkan varnish yang bermutu tinggi (Edison (1983) dalam Yuniandra,
1998).
Pengertian dan Fungsi Agroforestry
Agroforestry adalah suatu nama kolektif untuk sistem-sistem penggunaan
lahan teknologi, dimana tanaman keras berkayu (pohon-pohonan, perdu, jenis-jenis
palm, bambu, dan sebagainya) ditanam bersamaan dengan tanaman pertanian,
dan/atau hewan, dengan suatu tujuan tertentu dalam suatu bentuk pengaturan
spasial atau urutan temporal, dan di dalamnya terdapat interaksi-interaksi ekologi
dan ekonomi diantara berbagai komponen yang bersangkutan (Nair (1989) dalam
Hairiah, 2003).
Fungsi agroforestry terhadap aspek sosial, budaya dan ekonomi antara lain:
(a) Kaitannya dengan aspek tenurial, agroforestry memiliki potensi di masa kini
dan masa yang akan datang sebagai solusi dalam memecahkan konflik
melestarikan identitas kultural masyarakat, pemahaman akan nilai-nilai kultural
dari suatu aktivitas produksi hingga peran berbagai jenis pohon atau tanaman
lainnya di lingkungan masyarakat lokal dalam rangka keberhasilan pemilihan
desain dan kombinasi jenis pada bentuk-bentuk agroforestry modern yang akan
diperkenalkan atau dikembangkan di suatu tempat; (c) Kaitannya dengan
kelembagaan lokal, dengan praktik agroforestry lokal tidak hanya melestarikan
fungsi dari kepala adat, tetapi juga norma, sanksi, nilai, dan kepercayaan
(unsur-unsur dari kelembagaan) tradisional yang berlaku di lingkungan suatu komunitas;
(d) Kaitannya dalam pelestarian pengetahuan tradisional, salah satu ciri dari
agroforestry tradisional adalah diversitas komponen terutama hayati yang tinggi
(polyculture). Sebagian dari tanaman tersebut sengaja ditanam atau dipelihara dari
permudaan alam guna memperoleh manfaat dari beberapa bagian tanaman sebagai
bahan baku pengobatan. Meskipun hampir di seluruh kecamatan di Indonesia sudah
tersedia Puskesmas atau Puskesmas Pembantu (Pusban), tetapi masyarakat masih
banyak yang memanfaatkan lingkungannya sebagai ‘tabib’ bilamana mereka sakit
(Widianto dkk. 2003).
Fungsi agroforestry ditinjau dari aspek biofisik dan lingkungan pada skala
bentang lahan (skala meso) adalah kemampuannya untuk menjaga dan
mempertahankan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, khususnya
terhadap kesesuaian lahan antara lain: (a) Memelihara sifat fisik dan kesuburan
tanah; (b) Mempertahankan fungsi hidrologi kawasan; (c) Mempertahankan
cadangan karbon; (d) Mengurangi emisi gas rumah kaca; dan (e) mempertahankan
Klasifikasi Sistem Agroforestry
Berbagai tipe agroforestry telah banyak diinventarisir dan dikembangkan
dengan bentuk yang beragam tergantung kondisi wilayah, lokasi dan tujuan
agroforestry itu sendiri. Namun demikian, keragaman agroforestry tersebut dapat
dikelompokkan ke dalam empat dasar utama (Sardjono dkk., 2003), yaitu:
(1) Berdasarkan strukturnya (Structural Basis) yang berarti penggolongan dilihat
dari komposisi komponen-komponen penyusunnya (tanaman pertanian, hutan,
pakan, dan/atau ternak). Agroforestry dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Agrisilvikultur (Agrisilvicultural Systems)
Sistem agroforestry yang mengkombinasikan komponen kehutanan (atau
tanaman berkayu/woody plants) dengan komponen pertanian (atau tanaman
non kayu). Tanaman berkayu dimaksudkan yang berdaur panjang (tree crops)
dan tanaman non kayu dari jenis tanaman semusim (annual crops).
b. Silvopastura (Silvopastural Systems)
Sistem agroforestry yang meliputi komponen kehutanan (atau tanaman
berkayu) dengan komponen peternakan (atau binatang ternak/pasture). Kedua
komponen dalam silvopastura seringkali tidak dijumpai pada ruang dan
waktu yang sama (misal: penanaman rumput hijauan ternak di bawah tegakan
pinus, atau yang lebih ekstrim lagi adalah sistem ‘cut and carry’ pada pola
pagar hidup/living fences of fodder hedges and shrubs; atau pohon pakan
serbaguna/multipurpose fodder trees pada lahan pertanian yang disebut
c. Agrosilvopastura (Agrosilvopastural Systems)
Merupakan pengkombinasian komponen berkayu (kehutanan) dengan
pertanian (semusim) dan sekaligus peternakan/binatang pada unit manajemen
lahan yang sama. Contoh: berbagai bentuk kebun pekarangan
(home-gardens), kebun hutan (forest-(home-gardens), ataupun kebun desa
(village-forest-gardens), seperti sistem Parak di Maninjau (Sumatera Barat) atau Lembo dan
Tembawang di Kalimantan.
(2) Berdasarkan sistem produksi, agroforestry dibedakan menjadi :
a. Agroforestry berbasis hutan adalah bentuk agroforestry yang diawali
dengan pembukaan sebagian areal hutan dan/atau belukar untuk aktivitas
pertanian.
b. Agroforestry berbasis pada pertanian yaitu produk utama tanaman
pertanian dan atau peternakan tergantung sistem produksi pertanian dominan
di daerah tersebut. Komponen kehutanan merupakan elemen pendukung bagi
peningkatan produktivitas dan/atau sustainabilitas.
c. Agroforestry berbasis pada keluarga adalah agroforestry yang
dikembangkan di areal pekarangan rumah (homestead agroforestry).
(3) Berdasarkan masa perkembangannya, agroforestry dapat dibedakan menjadi :
a. Agroforestry tradisional/klasik yaitu tiap sistem pertanian, dimana
pohon-pohonan baik yang berasal dari penanaman atau pemeliharaan
tegakan/tanaman yang telah ada menjadi bagian terpadu, sosial ekonomi
dan ekologis dari keseluruhan sistem (agroecosystem).
b. Agroforestry modern umumnya hanya melihat pengkombinasian antara
berbagai model tumpang sari (baik yang dilaksanakan oleh Perhutani di
hutan jati di Jawa atau yang coba diperkenalkan oleh beberapa pengusaha
Hutan Tanaman Industri/HPHTI di luar Jawa).
Pola Kombinasi Komponen dalam Sistem Agroforestry
Secara sederhana agroforestry merupakan pengkombinasian komponen
tanaman berkayu/kehutanan (baik berupa pohon, perdu, palem-paleman, bambu,
dan tanaman berkayu lainnya) dengan tanaman pertanian (tanaman semusim)
dan/atau hewan (peternakan), baik secara tata waktu ataupun secara tata ruang.
Kombinasi yang ideal terjadi bila seluruh komponen agroforestry secara terus
menerus berada pada lahan yang sama. Pengkombinasian dalam sistem
agroforestry dapat menghasilkan berbagai reaksi, yang masing-masing atau bahkan
sekaligus dapat dijumpai pada satu unit manajemen yaitu persaingan, melengkapi,
dan ketergantungan (Sardjono dkk. 2003).
Sardjono dkk. (2003) juga mengatakan bahwa pengkombinasian secara tata
waktu dimaksudkan sebagai durasi interaksi antara komponen kehutanan dengan
pertanian dan atau peternakan. Kombinasi tersebut tidak selalu tampak di lapangan,
sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman bahwa suatu bentuk pemanfaatan
lahan tidak dapat dikategorikan agroforestry. Secara sederhana kombinasi menurut
tata waktu dapat dibagi dua yaitu kombinasi permanen dan sementara. Kombinasi
secara tata ruang dapat secara horizontal dan vertikal. Penyebaran menurut tata
Analisis Finansial Agroforestry
Menurut Widianto dkk (2003) bahwa keberadaan pohon dalam agroforestry
mempunyai dua peranan utama. Pertama, pohon dapat mempertahankan produksi
tanaman pangan dan memberikan pengaruh positif pada lingkungan fisik, terutama
dengan memperlambat kehilangan hara dan energi, dan menahan daya perusak air
dan angin. Kedua, hasil dari pohon berperan penting dalam ekonomi rumah tangga
petani. Pohon dapat menghasilkan: (1) Produk yang digunakan langsung seperti
pangan, bahan bakar, bahan bangunan; (2) Input untuk pertanian seperti pakan
ternak, mulsa; serta (3) Produk atau kegiatan yang mampu menyediakan lapangan
kerja atau penghasilan kepada anggota rumah tangga. Sistem produksi agroforestry
memiliki suatu kekhasan (Suharjito dkk. 2003), di antaranya:
a. Menghasilkan lebih dari satu macam produk
b. Pada lahan yang sama ditanam paling sedikit satu jenis tanaman semusim
dan satu jenis tanaman tahunan/pohon
c. Produk-produk yang dihasilkan dapat bersifat terukur (tangible) dan tak
terukur (intangible)
d. Terdapat kesenjangan waktu (time lag) antara waktu penanaman dan
pemanenan produk tanaman tahunan/pohon yang cukup lama
Sistem agroforestry menghasilkan bermacam-macam produk yang jangka
waktu pemanenannya berbeda, dimana paling sedikit satu jenis produknya
membutuhkan waktu pertumbuhan yang lebih dari satu tahun. Untuk melihat
sejauh mana suatu usaha agroforestry memberikan keuntungan, maka analisis yang
paling sesuai untuk dipakai adalah analisis proyek yang berbasis finansial. Menurut
seberapa besar manfaat yang diperoleh, biaya yang dikeluarkan, berapa
keuntungannya, kapan pengembalian investasi terjadi dan pada tingkat suku bunga
berapa investasi itu memberikan manfaat. Melalui cara berpikir seperti itu maka
harus ada ukuran-ukuran terhadap kinerjanya. Ukuran-ukuran yang digunakan
umumnya adalah :
a. Net Present Value (NPV)
Net Present Value (NPV) yaitu nilai saat ini yang mencerminkan nilai
keuntungan yang diperoleh selama jangka waktu pengusahaan dengan
memperhitungkan nilai waktu dari uang atau time value of money. Karena jangka
waktu kegiatan suatu usaha agroforestry cukup panjang, maka tidak seluruh biaya
bisa dikeluarkan pada saat yang sama, demikian pula hasil yang diperoleh dari
suatu usaha agroforestry dapat berbeda waktunya. Untuk mengetahui nilai uang di
masa yang akan datang dihitung pada saat ini, maka baik biaya maupun pendapatan
agroforestry di masa yang akan datang harus dikalikan dengan faktor diskonto
yang besarnya tergantung kepada tingkat suku bunga bank yang berlaku di pasaran.
Dengan model formulasi sebagai berikut (Suharjito dkk., 2003) :
Dengan kriteria apabila NPV > 0 berarti usaha tersebut menguntungkan, sebaliknya
jika NPV < 0 berarti usaha tersebut tidak layak diusahakan.
b. Benefit Cost Ratio (BCR)
Benefit Cost Ratio (BCR) yaitu perbandingan antara pendapatan dan
pengeluaran selama jangka waktu pengusahaan (dengan memperhitungkan nilai
waktu dari uang atau time value of money). Dengan model formulasi sebagai
berikut (Suharjito dkk. 2003) :
BCR =
BCR = Perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran
Bt = Benefit (aliran kas masuk pada periode-t)
Ct = Cost/ Biaya total
i = Interest (tingkat suku bunga bank yang berlaku)
t = Periode waktu
Dengan kriteria BCR > 1 dinyatakan usaha tersebut layak diusahakan dan
sebaliknya jika BCR < 1 berarti usaha tersebut tidak layak diusahakan.
c. Internal Rate of Returns (IRR)
Internal Rate of Returns (IRR) menunjukkan tingkat suku bunga maksimum
yang dapat dibayar oleh suatu proyek/usaha atau dengan kata lain merupakan
kemampuan memperoleh pendapatan dari uang yang diinvestasikan. Dalam
perhitungan, IRR adalah tingkat suku bunga apabila BCR yang terdiskonto sama
dengan nol. Usaha agroforestry akan dikatakan layak apabila nilai IRR lebih besar Bt – Ct > 0
dari tingkat suku bunga yang berlaku di pasar pada saat tersebut. Dengan rumus
sebagai berikut (Suharjito dkk. 2003) :
IRR = i1 + 2 1 1
2 1
i i NPV NPV
NPV
− × −
Dimana :
IRR = Suku bunga maksimum yang dapat dibayar oleh suatu
proyek
NPV1 = Nilai NPV yang positif pada tingkat suku tertentu
NPV2 = Nilai NPV yang negatif pada tingkat suku bunga tertentu
i1 = Discount Factor (tingkat bunga) pertama dimana diperoleh
NPV Positif
i2 = Discount Factor (tingkat bunga) kedua dimana diperoleh
II. TINJAUAN PUSTAKA
Hutan rakyat adalah hutan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh
organisasi masyarakat baik pada lahan individu, komunal (bersama), lahan adat,
maupun lahan yang dikuasai oleh negara. Hutan rakyat tersusun dari satuan
ekosistem kehidupan mulai dari tanaman keras, non kayu, satwa, buah-buahan,
satuan budi daya semusim, peternakan, barang dan jasa, serta rekreasi alam
(Awang dkk. 2002).
Salah satu solusi untuk mengurangi tekanan terhadap hutan dan mengatasi
masalah kebutuhan lahan pertanian adalah dengan menerapkan sistem agroforestry.
Agroforestry merupakan sistem pemanfaatan lahan secara optimal berasaskan
kelestarian lingkungan dengan mengusahakan atau mengkombinasikan tanaman
kehutanan dan pertanian (perkebunan, ternak) sehingga dapat meningkatkan
perekonomian petani di pedesaan (Gautama, 2007).
Lembaga Penelitian IPB (1983) dalam Purwanto dkk. (2004) membagi
hutan rakyat dalam tiga kelompok, yaitu:
1. Hutan rakyat murni (monoculture), yaitu hutan rakyat yang hanya terdiri dari
satu jenis tanaman pokok berkayu yang ditanam secara homogen atau
monokultur.
2. Hutan rakyat campuran (polyculture), yaitu hutan rakyat yang terdiri dari
berbagai jenis pohon-pohonan yang ditanam secara campuran.
3. Hutan rakyat wana tani (agroforestry), yaitu yang mempunyai bentuk usaha
pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain yang dikembangkan
secara terpadu.
Pengembangan hutan rakyat dengan komoditi tertentu dapat memperbaiki
mutu lingkungan disamping meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan
iklim mikro yang baik, memperbaiki struktur tanah, dan mengendalikan erosi. Hal
tersebut menjadikan hutan rakyat merupakan salah satu teknik konservasi tanah dan
air secara vegetatif (Purwanto, dkk. 2004). Pembangunan hutan rakyat secara
swadaya merupakan alternatif yang dipilih untuk mengatasi masalah sosial
ekonomi dan lingkungan hidup, selain itu pengaruh positif yang lain adalah
terpeliharanya sumberdaya alam (konservasi tanah dan air) sehingga meningkatkan
daya dukung lahan bagi penduduk dan ikut serta dalam pengelolaan Daerah Aliran
Sungai (DAS), mengurangi terjadinya kerusakan hutan akibat penebangan liar dan
penyerobotan tanah. Kombinasi berbagai jenis tanaman memungkinkan pemetikan
hasil secara terus menerus dan memungkinkan terbentuknya stratifikasi tajuk
sehingga mencegah erosi tanah dan hempasan air hutan (Arief, 2001).
Deskripsi Tanaman Kemenyan
Kemenyan (Styrax spp.) termasuk jenis pohon berukuran besar yaitu dari
famili Styracaceae. Adapun urutan sistematika kemenyan adalah sebagai berikut:
Kingdom : Plantae
Superdivision : Spermatophyta
Division : Angiospermae
Class : Dikotil
Family : Styracaceae
Genus : Styrax
Species : Styrax sumatrana dan Styrax benzoin
Di Indonesia terdapat tujuh jenis atau varietas kemenyan (Styrax spp.) yang
menghasilkan getah akan tetapi hanya dua jenis yang lebih umum dikenal dan
diusahakan di Sumatera Utara, yaitu Styrax sumatrana J.J.SM yang disebut dengan
kemenyan toba dan Styrax benzoin DRYAND yang disebut dengan kemenyan
(haminjon) durame. Dari kedua jenis ini tersebut, jenis yang pertama lebih dominan
karena memiliki kualitas getah yang lebih baik dan bernilai ekonomi lebih tinggi
dibandingkan dengan jenis yang terakhir (Sasmuko, 2000).
Ciri khas kemenyan toba (Styrax sumatrana) adalah kandungan atau kadar
asam sinamatnya cukup tinggi. Jelas bahwa jenis ini dapat menghasilkan getah
kualitas pertama dengan ciri-ciri memiliki aroma yang lebih wangi, berwarna putih
dan tidak lengket. Sedangkan ciri khas jenis kemenyan durame (Styrax benzoin)
bahwa jenis ini dapat menghasilkan getah kemenyan seperti tahir yang memiliki
kualitas getah lebih rendah dengan ciri-ciri berwarna hitam kecoklatan dan agak
lengket.
Manfaat/Kegunaan Kemenyan
Penggunaan kemenyan untuk industri dalam negeri sampai saat ini masih
terbatas, relatif kecil dan belum banyak diketahui serta diteliti kegunaannya,
kecuali dibakar sebagai bahan dupa dalam penyelenggaraan upacara-upacara
Ekstraksi kimia getah kemenyan menghasilkan tincture dan benzoin resin
yang digunakan sebagai fix active agent dalam industri parfum. Ekstraksi
kemenyan juga dapat menghasilkan beberapa senyawa kimia yang diperlukan oleh
industri farmasi antara lain asam balsamat, asam sinamat, benzyl benzoate, sodium
benzoate, benzophenone, ester aromatis dan sebagainya. Di negara-negara industri
maju seperti negara Eropa, kemenyan (Styrax spp.) dipergunakan sebagai bahan
dasar dalam pembuatan asam benzoate atau asam sinamat dan ester-esternya,
industri farmasi (obat-obatan), industri kosmetika dan bahan pembuatan parfum,
pabrik porselin, sabun, plastik sintetis, bahan pengawet pada industri makanan dan
sebagainya.
Penggunaan kemenyan dari segi pemakaiannya sebagai bahan kimia yaitu
antara lain:
1. Pada bidang farmasi (obat-obatan)
Penggunaan kemenyan sebagai obat-obatan telah lama dipergunakan. Hal ini
dibuktikan dari berbagai literatur kimia, yaitu:
- Antiseptik
- Obat mata bagi penyakit kataraks
- Expectorant (melegakan pernafasan)
2. Pada obat-obatan pertanian
Melalui proses esterifikasi, asam sinamat dipergunakan untuk membentuk
ester-ester, seperti metil dan etil ester. Beberapa turunan kimianya dapat
3. Pada parfum
Pada parfum dipergunakan sebagai fix active, yaitu untuk menahan aroma
parfum lebih lama dan mempertemukan dua atau beberapa jenis parfum dari
bahan yang berbeda untuk mendapatkan aroma parfum yang lebih baik.
4. Pada Kosmetik
5. Pabrik rokok dan pabrik porselin
6. Kegiatan religius/upacara agama (dupa)
7. Varnis
Berdasarkan uji coba pembutan varnish dari kemenyan ternyata kemenyan
menghasilkan varnish yang bermutu tinggi (Edison (1983) dalam Yuniandra,
1998).
Pengertian dan Fungsi Agroforestry
Agroforestry adalah suatu nama kolektif untuk sistem-sistem penggunaan
lahan teknologi, dimana tanaman keras berkayu (pohon-pohonan, perdu, jenis-jenis
palm, bambu, dan sebagainya) ditanam bersamaan dengan tanaman pertanian,
dan/atau hewan, dengan suatu tujuan tertentu dalam suatu bentuk pengaturan
spasial atau urutan temporal, dan di dalamnya terdapat interaksi-interaksi ekologi
dan ekonomi diantara berbagai komponen yang bersangkutan (Nair (1989) dalam
Hairiah, 2003).
Fungsi agroforestry terhadap aspek sosial, budaya dan ekonomi antara lain:
(a) Kaitannya dengan aspek tenurial, agroforestry memiliki potensi di masa kini
dan masa yang akan datang sebagai solusi dalam memecahkan konflik
melestarikan identitas kultural masyarakat, pemahaman akan nilai-nilai kultural
dari suatu aktivitas produksi hingga peran berbagai jenis pohon atau tanaman
lainnya di lingkungan masyarakat lokal dalam rangka keberhasilan pemilihan
desain dan kombinasi jenis pada bentuk-bentuk agroforestry modern yang akan
diperkenalkan atau dikembangkan di suatu tempat; (c) Kaitannya dengan
kelembagaan lokal, dengan praktik agroforestry lokal tidak hanya melestarikan
fungsi dari kepala adat, tetapi juga norma, sanksi, nilai, dan kepercayaan
(unsur-unsur dari kelembagaan) tradisional yang berlaku di lingkungan suatu komunitas;
(d) Kaitannya dalam pelestarian pengetahuan tradisional, salah satu ciri dari
agroforestry tradisional adalah diversitas komponen terutama hayati yang tinggi
(polyculture). Sebagian dari tanaman tersebut sengaja ditanam atau dipelihara dari
permudaan alam guna memperoleh manfaat dari beberapa bagian tanaman sebagai
bahan baku pengobatan. Meskipun hampir di seluruh kecamatan di Indonesia sudah
tersedia Puskesmas atau Puskesmas Pembantu (Pusban), tetapi masyarakat masih
banyak yang memanfaatkan lingkungannya sebagai ‘tabib’ bilamana mereka sakit
(Widianto dkk. 2003).
Fungsi agroforestry ditinjau dari aspek biofisik dan lingkungan pada skala
bentang lahan (skala meso) adalah kemampuannya untuk menjaga dan
mempertahankan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, khususnya
terhadap kesesuaian lahan antara lain: (a) Memelihara sifat fisik dan kesuburan
tanah; (b) Mempertahankan fungsi hidrologi kawasan; (c) Mempertahankan
cadangan karbon; (d) Mengurangi emisi gas rumah kaca; dan (e) mempertahankan
Klasifikasi Sistem Agroforestry
Berbagai tipe agroforestry telah banyak diinventarisir dan dikembangkan
dengan bentuk yang beragam tergantung kondisi wilayah, lokasi dan tujuan
agroforestry itu sendiri. Namun demikian, keragaman agroforestry tersebut dapat
dikelompokkan ke dalam empat dasar utama (Sardjono dkk., 2003), yaitu:
(1) Berdasarkan strukturnya (Structural Basis) yang berarti penggolongan dilihat
dari komposisi komponen-komponen penyusunnya (tanaman pertanian, hutan,
pakan, dan/atau ternak). Agroforestry dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Agrisilvikultur (Agrisilvicultural Systems)
Sistem agroforestry yang mengkombinasikan komponen kehutanan (atau
tanaman berkayu/woody plants) dengan komponen pertanian (atau tanaman
non kayu). Tanaman berkayu dimaksudkan yang berdaur panjang (tree crops)
dan tanaman non kayu dari jenis tanaman semusim (annual crops).
b. Silvopastura (Silvopastural Systems)
Sistem agroforestry yang meliputi komponen kehutanan (atau tanaman
berkayu) dengan komponen peternakan (atau binatang ternak/pasture). Kedua
komponen dalam silvopastura seringkali tidak dijumpai pada ruang dan
waktu yang sama (misal: penanaman rumput hijauan ternak di bawah tegakan
pinus, atau yang lebih ekstrim lagi adalah sistem ‘cut and carry’ pada pola
pagar hidup/living fences of fodder hedges and shrubs; atau pohon pakan
serbaguna/multipurpose fodder trees pada lahan pertanian yang disebut
c. Agrosilvopastura (Agrosilvopastural Systems)
Merupakan pengkombinasian komponen berkayu (kehutanan) dengan
pertanian (semusim) dan sekaligus peternakan/binatang pada unit manajemen
lahan yang sama. Contoh: berbagai bentuk kebun pekarangan
(home-gardens), kebun hutan (forest-(home-gardens), ataupun kebun desa
(village-forest-gardens), seperti sistem Parak di Maninjau (Sumatera Barat) atau Lembo dan
Tembawang di Kalimantan.
(2) Berdasarkan sistem produksi, agroforestry dibedakan menjadi :
a. Agroforestry berbasis hutan adalah bentuk agroforestry yang diawali
dengan pembukaan sebagian areal hutan dan/atau belukar untuk aktivitas
pertanian.
b. Agroforestry berbasis pada pertanian yaitu produk utama tanaman
pertanian dan atau peternakan tergantung sistem produksi pertanian dominan
di daerah tersebut. Komponen kehutanan merupakan elemen pendukung bagi
peningkatan produktivitas dan/atau sustainabilitas.
c. Agroforestry berbasis pada keluarga adalah agroforestry yang
dikembangkan di areal pekarangan rumah (homestead agroforestry).
(3) Berdasarkan masa perkembangannya, agroforestry dapat dibedakan menjadi :
a. Agroforestry tradisional/klasik yaitu tiap sistem pertanian, dimana
pohon-pohonan baik yang berasal dari penanaman atau pemeliharaan
tegakan/tanaman yang telah ada menjadi bagian terpadu, sosial ekonomi
dan ekologis dari keseluruhan sistem (agroecosystem).
b. Agroforestry modern umumnya hanya melihat pengkombinasian antara
berbagai model tumpang sari (baik yang dilaksanakan oleh Perhutani di
hutan jati di Jawa atau yang coba diperkenalkan oleh beberapa pengusaha
Hutan Tanaman Industri/HPHTI di luar Jawa).
Pola Kombinasi Komponen dalam Sistem Agroforestry
Secara sederhana agroforestry merupakan pengkombinasian komponen
tanaman berkayu/kehutanan (baik berupa pohon, perdu, palem-paleman, bambu,
dan tanaman berkayu lainnya) dengan tanaman pertanian (tanaman semusim)
dan/atau hewan (peternakan), baik secara tata waktu ataupun secara tata ruang.
Kombinasi yang ideal terjadi bila seluruh komponen agroforestry secara terus
menerus berada pada lahan yang sama. Pengkombinasian dalam sistem
agroforestry dapat menghasilkan berbagai reaksi, yang masing-masing atau bahkan
sekaligus dapat dijumpai pada satu unit manajemen yaitu persaingan, melengkapi,
dan ketergantungan (Sardjono dkk. 2003).
Sardjono dkk. (2003) juga mengatakan bahwa pengkombinasian secara tata
waktu dimaksudkan sebagai durasi interaksi antara komponen kehutanan dengan
pertanian dan atau peternakan. Kombinasi tersebut tidak selalu tampak di lapangan,
sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman bahwa suatu bentuk pemanfaatan
lahan tidak dapat dikategorikan agroforestry. Secara sederhana kombinasi menurut
tata waktu dapat dibagi dua yaitu kombinasi permanen dan sementara. Kombinasi
secara tata ruang dapat secara horizontal dan vertikal. Penyebaran menurut tata
Analisis Finansial Agroforestry
Menurut Widianto dkk (2003) bahwa keberadaan pohon dalam agroforestry
mempunyai dua peranan utama. Pertama, pohon dapat mempertahankan produksi
tanaman pangan dan memberikan pengaruh positif pada lingkungan fisik, terutama
dengan memperlambat kehilangan hara dan energi, dan menahan daya perusak air
dan angin. Kedua, hasil dari pohon berperan penting dalam ekonomi rumah tangga
petani. Pohon dapat menghasilkan: (1) Produk yang digunakan langsung seperti
pangan, bahan bakar, bahan bangunan; (2) Input untuk pertanian seperti pakan
ternak, mulsa; serta (3) Produk atau kegiatan yang mampu menyediakan lapangan
kerja atau penghasilan kepada anggota rumah tangga. Sistem produksi agroforestry
memiliki suatu kekhasan (Suharjito dkk. 2003), di antaranya:
a. Menghasilkan lebih dari satu macam produk
b. Pada lahan yang sama ditanam paling sedikit satu jenis tanaman semusim
dan satu jenis tanaman tahunan/pohon
c. Produk-produk yang dihasilkan dapat bersifat terukur (tangible) dan tak
terukur (intangible)
d. Terdapat kesenjangan waktu (time lag) antara waktu penanaman dan
pemanenan produk tanaman tahunan/pohon yang cukup lama
Sistem agroforestry menghasilkan bermacam-macam produk yang jangka
waktu pemanenannya berbeda, dimana paling sedikit satu jenis produknya
membutuhkan waktu pertumbuhan yang lebih dari satu tahun. Untuk melihat
sejauh mana suatu usaha agroforestry memberikan keuntungan, maka analisis yang
paling sesuai untuk dipakai adalah analisis proyek yang berbasis finansial. Menurut
seberapa besar manfaat yang diperoleh, biaya yang dikeluarkan, berapa
keuntungannya, kapan pengembalian investasi terjadi dan pada tingkat suku bunga
berapa investasi itu memberikan manfaat. Melalui cara berpikir seperti itu maka
harus ada ukuran-ukuran terhadap kinerjanya. Ukuran-ukuran yang digunakan
umumnya adalah :
a. Net Present Value (NPV)
Net Present Value (NPV) yaitu nilai saat ini yang mencerminkan nilai
keuntungan yang diperoleh selama jangka waktu pengusahaan dengan
memperhitungkan nilai waktu dari uang atau time value of money. Karena jangka
waktu kegiatan suatu usaha agroforestry cukup panjang, maka tidak seluruh biaya
bisa dikeluarkan pada saat yang sama, demikian pula hasil yang diperoleh dari
suatu usaha agroforestry dapat berbeda waktunya. Untuk mengetahui nilai uang di
masa yang akan datang dihitung pada saat ini, maka baik biaya maupun pendapatan
agroforestry di masa yang akan datang harus dikalikan dengan faktor diskonto
yang besarnya tergantung kepada tingkat suku bunga bank yang berlaku di pasaran.
Dengan model formulasi sebagai berikut (Suharjito dkk., 2003) :
Dengan kriteria apabila NPV > 0 berarti usaha tersebut menguntungkan, sebaliknya
jika NPV < 0 berarti usaha tersebut tidak layak diusahakan.
b. Benefit Cost Ratio (BCR)
Benefit Cost Ratio (BCR) yaitu perbandingan antara pendapatan dan
pengeluaran selama jangka waktu pengusahaan (dengan memperhitungkan nilai
waktu dari uang atau time value of money). Dengan model formulasi sebagai
berikut (Suharjito dkk. 2003) :
BCR =
BCR = Perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran
Bt = Benefit (aliran kas masuk pada periode-t)
Ct = Cost/ Biaya total
i = Interest (tingkat suku bunga bank yang berlaku)
t = Periode waktu
Dengan kriteria BCR > 1 dinyatakan usaha tersebut layak diusahakan dan
sebaliknya jika BCR < 1 berarti usaha tersebut tidak layak diusahakan.
c. Internal Rate of Returns (IRR)
Internal Rate of Returns (IRR) menunjukkan tingkat suku bunga maksimum
yang dapat dibayar oleh suatu proyek/usaha atau dengan kata lain merupakan
kemampuan memperoleh pendapatan dari uang yang diinvestasikan. Dalam
perhitungan, IRR adalah tingkat suku bunga apabila BCR yang terdiskonto sama
dengan nol. Usaha agroforestry akan dikatakan layak apabila nilai IRR lebih besar Bt – Ct > 0
dari tingkat suku bunga yang berlaku di pasar pada saat tersebut. Dengan rumus
sebagai berikut (Suharjito dkk. 2003) :
IRR = i1 + 2 1 1
2 1
i i NPV NPV
NPV
− × −
Dimana :
IRR = Suku bunga maksimum yang dapat dibayar oleh suatu
proyek
NPV1 = Nilai NPV yang positif pada tingkat suku tertentu
NPV2 = Nilai NPV yang negatif pada tingkat suku bunga tertentu
i1 = Discount Factor (tingkat bunga) pertama dimana diperoleh
NPV Positif
i2 = Discount Factor (tingkat bunga) kedua dimana diperoleh
III. METODE PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pangurdotan, Kecamatan Pahae Julu,
Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yaitu pada
bulan Juni - Juli 2010.
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Desa
Pangurdotan sebanyak 178 KK, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 39
orang dengan kriteria memiliki lahan lebih dari 1 Ha dan mengelola lahannya
dengan sistem agroforestry atau non agriforestry.
Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :
1. Data primer
Data primer yang diperlukan adalah :
a. Karakteristik responden : nama, umur, mata pencaharian, jumlah
anggota keluarga, dan pendidikan
b. Jenis-jenis komoditi atau tanaman yang ditanam petani dengan
kemenyan
c. Komponen-komponen biaya (cost) dan manfaat (benefit) dari
2. Data Sekunder
Data sekunder yang diperlukan adalah data umum yang ada pada instansi
pemerintah desa, kecamatan, dinas kehutanan dan perkebunan, Badan Pusat
Statistik dan lembaga-lembaga lain yang terkait.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara :
1. Kuisioner
Kuisioner (Lampiran 2) merupakan suatu set pertanyaan yang ditujukan
kepada seluruh sampel dalam penelitian. Data yang diperlukan adalah data
primer.
2. Wawancara Mendalam (Deep Interview)
Wawancara ditujukan untuk melengkapi data lainnya yang berkaitan
dengan penelitian.
3. Observasi
Survey langsung ke lapangan dengan melihat kehidupan sehari-hari
masyarakat dan kondisi lahan agroforestry.
4. Studi Pustaka
Dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder yang diperlukan dalam
penelitian.
Pengolahan Data
Analisis-analisis yang digunakan adalah :
1. Analisis Deskriptif
Menurut Nazir (1988), metode deskriptif digunakan untuk mengetahui
mendalam, observasi dan studi pustaka. Data yang terkumpul dari hasil
kuisioner dinyatakan dalam bentuk tabel (tabulasi) frekuensi silang yang
berupa data karakteristik responden yang meliputi umur, mata pencaharian,
jumlah anggota keluarga dan pendidikan serta data pengelolaan berupa luas
lahan, jumlah tenaga kerja, sistem kepemilikan lahan, dan sistem
agroforestry, dianalisis secara deskriptif berdasarkan tabulasi.
2. Analisis Finansial
Analisis finansial pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui
seberapa besar manfaat yang diperoleh, biaya yang dikeluarkan, berapa
keuntungannya, kapan pengembalian investasi terjadi dan pada tingkat suku
bunga berapa investasi itu memberikan manfaat.
Data yang diperoleh dari kuisioner dan wawancara mendalam yang meliput i
pola kombinasi, biaya produksi, produksi/volume hasil, harga jual komoditi, dan
pendapatan dari kemenyan dalam sistem agroforestry dinyatakan dalam bentuk
tabulasi. Kemudian dianalisis kelayakan finansialnya berdasarkan masing-masing
pola dengan menghitung besarnya nilai NPV, BCR dan IRR dengan menggunakan
rumus sebagai berikut (Suharjito dkk. 2003) :
Dimana:
NPV = Nilai bersih sekarang
BCR = Perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran
Bt = Benefit (aliran kas masuk pada periode-t)
Ct = Cost/Biaya total
i dan t = Interest (tingkat suku bunga bank yang berlaku) dan peride waktu
IRR = Suku bunga maksimum yang dapat dibayar oleh suatu proyek
NPV1 = Nilai NPV yang positif pada tingkat suku tertentu
NPV2 = Nilai NPV yang negatif pada tingkat suku bunga tertentu
i1 = Discount factor (tingkat bunga) pertama dimana diperoleh NPV positif.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Responden
Analisis Deskriptif
Data yang memberi pengaruh penting dalam mempengaruhi kelayakan
sistem agroforestry adalah karakteristik responden. Karakteristik responden dalam
penelitian ini adalah nama, umur, mata pencarian, jumlah anggota keluarga,
pendidikan, sistem kepemilikan lahan, dan sistem agroforestry yang dianalisis
secara deskriptif. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nazir (1988) bahwa data yang
terkumpul dari hasil kuisioner dianalisis secara deskriptif berdasarkan tabulasi.
Penyebaran responden berdasarkan umur ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Penyebaran responden berdasarkan umur
No. Kelompok umur (Tahun) Frekuensi Persentase (%)
1 20 – 30 1 2,56
2 31 – 40 4 10,26
3 41 – 50 19 48,72
4 51 – 60 14 35,90
5 ≥ 61 1 2,56
Jumlah 39 100
Umur menyatakan tingkat keproduktifan seseorang dalam melaksanakan
suatu kegiatan. Tabel 1 di atas menyatakan bahwa konsentrasi umur responden
adalah pada kelompok umur 41 – 50 tahun dengan persentase 48,72%. Kemudian
disusul dengan kelompok umur 51 – 60 tahun (35,90%), kelompok umur 31 – 40
tahun (10,26%), dan yang terakhir adalah kelompok umur 20 – 30 tahun dan
kelompok umur ≥ 61 tahun dimana keduanya memiliki frekuensi yang sama.
berumur 20-40 tahun mengelola lahannya dengan sistem agroforestry. Hal ini
menunjukkan bahwa faktor usia mempengaruhi tingkat keproduktifan seseorang
dalam mengelola lahan. Masyarakat yang berumur diatas 50 tahun mengelola
lahannya dengan sistem agroforestry. Gologan umur ini dapat mengelola lahannya
dengan sisten agroforestry karena adanya peran serta anggota keluarga yang
produktif.
Responden dalam penelitian ini rata-rata memiliki jumlah anggota keluarga
rata-rata 4 – 6 orang (69,23%). Tabel 2 menyajikan penyebaran responden
berdasarkan jumlah anggota keluarga.
Tabel 2. Penyebaran responden berdasarkan jumlah anggota keluarga
No. Jumlah anggota keluarga (Orang) Frekuensi Persentase (%)
1 1 – 3 5 12,82
2 4 – 6 27 69,23
3 7 – 9 5 12,82
4 ˃ 9 2 5,13
Jumlah 39 100
Pada umumnya, masyarakat dengan jumlah anggota keluarga 1- 6 orang
mengelola lahannya dengan sistem non agroforestry dan masyarakat dengan
jumlah anggota keluarga lebih dari 5 orang menggunakan sistem agroforestry.
Jumlah anggota keluarga memiliki peran dalam pengelolaan tanaman. Karena jika
anggota keluarga ikut dalam pengelolaannya, maka akan mengurangi pembiayaan
tenaga kerja di luar anggota keluarga. Semakin banyak anggota keluarga yang
berperan dalam pengelolaan tanaman, maka semakin sedikit biaya yang diperlukan.
Masyarakat responden di Desa Pangurdotan rata-rata memiliki pendidikan
Sekolah Dasar (SD), yaitu sebanyak 20 orang responden (51,28%). Kemudian
dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 8 orang (20,52%), dan yang
tidak bersekolah hanya 1 orang (2,56%). Sedangkan untuk tamatan perguruan
tinggi, tidak satupun masyarakat responden yang memiliki pendidikan tersebut.
Penyebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Penyebaran responden berdasarkan pendidikan
No. Tingkat pendidikan Frekuensi Persentase (%)
1 Tidak Sekolah 1 2,56
2 SD/SR 20 51,28
3 SLTP/SMP 10 25,64
4 SLTA/SMU/SMK 8 20,52
5 PT 0 0
Jumlah 39 100
Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa
Pangurdotan terbilang rendah. Karena sebagian besar masyarakatnya didominasi
oleh pendidikan SD. Tingkat pendidikan tentu saja berpengaruh pada cara
masyarakat mengembangkan lahan agroforestry maupun non agroforestry.
Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin baik pola
pikirnya untuk memikirkan banyak cara dalam proses pengembangan pengelolaan
tanaman karena akan semakin banyak informasi yang diperoleh. Jika informasi
tersebut diterapkan dengan baik dalam proses pengelolaan tanaman, maka akan
memberikan hasil yang baik pula.
Para petani responden biasanya menggunakan tenaga kerja sebanyak 3 – 4
orang. Sebagian tenaga kerja yang digunakan adalah anggota keluarga, namun
biasanya tetap memerlukan tenaga kerja lain. Penyebaran responden dilihat dari
No. Jumlah tenaga kerja (Orang) Frekuensi Persentase (%)
1 1 – 2 12 30,77
2 3 – 4 24 61,53
3 ˃ 4 3 7,70
Jumlah 39 100
Tabel 4 menunjukkan bahwa masyarakat responden paling banyak
memerlukan jumlah tenaga kerja adalah 3 – 4 orang, yaitu terdapat 24 orang dari
keseluruhan responden (61,53%). Terdapat 12 (30,77%) dari responden tersebut
hanya memerlukan 1 – 2 orang tenaga kerja dan yang paling sedikit adalah
masyarakat responden yang memerlukan tenaga kerja berjumlah lebih dari 4 orang,
yaitu hanya 3 responden (7,70%). Tentu saja hal ini akan berpengaruh pada hasil
akhir pengelolaan. Semakin banyak tenaga yang diperlukan, maka akan semakin
besar biaya yang akan dikeluarkan, termasuk memberi upah kepada para tenaga
kerja.
Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kelayakan budi daya kemenyan
dalam sistem agroforestry adalah luas lahan yang dimiliki masyarakat responden.
Penyebaran responden berdasarkan luas lahan yang dimilikinya disajikan dalam
Tabel 5.
Tabel 5. Penyebaran responden berdasarkan luas lahan agroforestry
No. Luas lahan (Ha) Frekuensi Persentase (%)
1 1 – 2 26 66,67
2 > 2 13 33,33
Jumlah 39 100
Responden yang memiliki luas lahan 1 – 2 ha adalah sebanyak 26 orang
responden (66,67%). Kemudian disusul dengan responden yang memiliki luas
lahan > 2 ha, yaitu sebanyak 13 orang (33,33%), atau sama dengan setengah dari
memiliki luas 1 – 2 ha terdapat 10 orang yang mengelola lahannya secara non
agroforestry dan 16 orang yang mengelola lahannya secara agroforestry.
Sedangkan masyarakat yang memiliki luas lahan > 2 ha mengelola lahannya
dengan sistem agroforestry. Semakin luas lahan yang dikelola seseorang, maka
akan semakin banyak hasil yang diperoleh dari lahan tersebut. Dan tentu saja jika
didukung dengan pengelolaan yang baik.
B. Hal-hal yang Menyebabkan Terjadinya Perubahan Pengusahaan Lahan
dari non agroforestry menjadi agroforestry
Pola kombinasi sistem agroforestry di Desa Pangurdotan adalah Sistem
Agrisilvikultur. Pola tanaman yang diterapkan adalah kemenyan sebagai tanaman
kehutanan dan sebagai tanaman musimannya adalah padi dan cokelat. Berdasarkan
pengamatan yang dilakukan di lapangan, ada beberapa hal yang menyebabkan
terjadinya perubahan pengusahaan lahan dari non agroforestry msnjadi
agroforestry, diantaranya :
- Tanaman kemenyan dengan sistem monokultur tidak menghasilkan produksi
getah secara maksimal sehingga nilai ekonomi yang diperoleh juga tidak
maksimal;
- Maraknya pencurian getah kemenyan sehingga pemilik lahan mengalami
kerugian;
- Kurangnya peranan pemerintah khususnya dalam memberikan perhatian
C. Analisis Finansial
Setiap usaha yang dilakukan oleh setiap orang perlu diketahui seberapa
besar manfaat yang diperoleh, biaya yang dikeluarkan, berapa keuntungannya, dan
kapan investasinya akan kembali. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu
usaha memiliki kelayakan sebagai suatu usaha. Usaha budi daya kemenyan dalam
sistem agroforestry dan non agroforestry di Desa Pangurdotan juga dapat diketahui
tingkat kelayakannya sebagai suatu usaha.
Analisis biaya dan manfaat dapat dilihat dalam beberapa kriteria, yaitu
NPV, BCR, dan IRR pada tingkat suku bunga yang berlaku, yaitu 6,5%. Nilai dari
masing-masing kriteria tersebut ditunjukkan pada Tabel 6.
Tabel 6. Nilai NPV, BCR, dan IRR agroforestry dan non angroforestry Desa Pangurdotan selama 15 tahun.
Pola Kombinasi NPV (Rp/Ha) BCR IRR (%)
agroforestry 21.837.109 3,01 52,63
non agroforestry 20.526.290 16,02 49,86
Tabel 6 menunjukkan besarnya NPV, BCR, dan IRR pada lahan
agroforestry dan non agroforestry di Desa Pangurdotan selama 15 tahun.
Perhitungan nilai NPV, BCR, dan IRR di atas lebih rinci dapat dilihat pada
Lampiran 4, 5, 6, dan 7. Seperti pernyataan Suharjito, dkk. (2003) bahwa nilai saat
ini yang mencerminkan nilai keuntungan yang diperoleh selama jangka waktu
pengusahaan dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang, maka Tabel 6 di atas
juga menunjukkan besarnya nilai keuntungan yang diperoleh dari sistem
agroforestry dan non agroforestry. Dengan pola kombinasi agroforestry,
keuntungan yang diperoleh adalah sebanyak Rp. 21.837.109,- selama 15 tahun/ha
15 tahun/ha. Artinya bahwa pola kombinasi agroforestry lebih menguntungkan
dibandingkan dengan pola non agroforestry.
Benefit Cost Ratio (BCR) adalah perbandingan besarnya pendapatan dengan
pengeluaran selama jangka waktu tertentu, dalam hal ini adalah 15 tahun. Untuk
pola agroforestry, nilai BCR yang diperoleh adalah sebesar 3,01. Artinya adalah
modal yang diinvestasikan akan kembali sebesar 3,01 kali lipat. Sedangkan untuk
pola non agroforestry, nilai BCR yang diperoleh adalah 16,02. Kedua pola
kombinasi di atas merupakan nilai yang layak untuk kategori BCR. Kedua pola
menghasilkan nilai BCR > 1, pola non agroforestry memiliki BCR lebih besar
daripada BCR agroforestry, artinya bahwa pola non agroforestry memiliki nilai
yang lebih optimal untuk diusahakan.
Internal Rate of Returns (IRR) adalah nilai yang menunjukkan berapa
manfaat yang diperoleh dari suatu usaha dimana seseorang menginvestasikan
uangnya. Menurut Suharjito dkk. (2003), IRR adalah tingkat suku bunga apabila
BCR yang terdiskonto sama dengan nol. Usaha agroforestry akan dikatakan layak
apabila nilai IRR lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku di pasar pada
saat tersebut. Besarnya nilai IRR pada pola agroforestry adalah sebesar 52,63%
dan pola non agroforestry adalah sebesar 49,86%. Hal ini menunjukkan bahwa
budi daya secara agroforestry dan non agroforestry layak karena IRR yang
diperoleh lebih besar dari besarnya tingkat suku bunga yang berlaku, yaitu 6,5%.
Nilai NPV pada sistem agroforestry memiliki nilai yang lebih besar
daripada sistem non agroforestry. Namun, nilai BCR dan IRR lebih besar pada
praktek sistem non agroforestry daripada sistem agroforestry. Hal ini terjadi karena
pertama hingga tahun ke-5, tanaman pada pola non agroforestry belum
mendapatkan keuntungan, namun tetap memerlukan biaya pengeluaran untuk biaya
pemeliharaan tanaman. Sedangkan pada sistem agroforestry, tanaman mulai
menghasilkan pada tahun ke-2. Hal ini terjadi karena adanya berbagai jenis
tanaman yang ditanam pada pola agroforestry. Sehingga, sebelum tanaman
kemenyan menghasilkan, terdapat tanaman lain yang telah lebih dahulu
menghasilkan karena kondisi pertumbuhan tanaman yang selalu
berkesinambungan.
Sistem agroforestry (Rp. 21.837.109,-) menghasilkan keuntungan yang
lebih besar jika dibandingkan dengan sistem non agroforestry (Rp. 20.526.290,-)
selama 15 tahun/ha. Hal ini membuat masyarakat berkeinginan untuk mengubah
sistem tanam mereka, yaitu dari sistem non agroforestry menjadi sistem
agroforestry. Tingkat pendidikan masyarakat responden di Desa Pangurdotan ini
terbilang cukup rendah, karena didominasi tamatan SD, namun mereka mencoba
untuk mengubah pengusahaan lahan mereka menjadi sistem non agroforestry. Hal
ini terjadi bukan karena memiliki pendidikan yang tinggi sehingga dapat
mengakses cara dengan memanfaatkan pendidikan ataupun teknologi yang tinggi,
namun semua adalah berdasarkan pada pengalaman para petani responden dalam
mengelola usahanya.
Kondisi tanaman yang pertumbuhannya berkesinambungan juga
memberikan dampak yang positif pada kondisi tanah. Menurut Lahjie (2004),
bahwa fungsi agroforestry jika ditinjau dari aspek biofisik dan lingkungan pada
skala bentang lahan (skala meso) adalah mampu menjaga dan mempertahankan