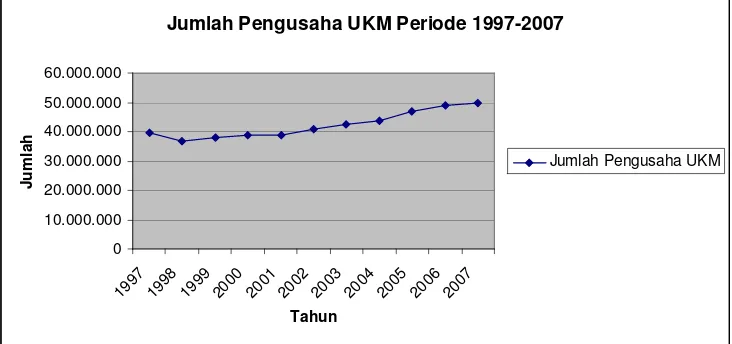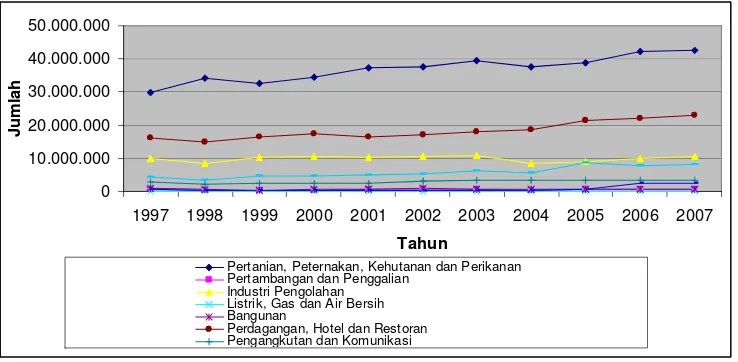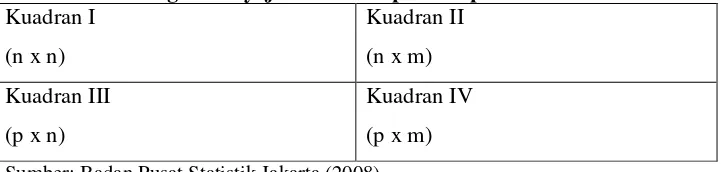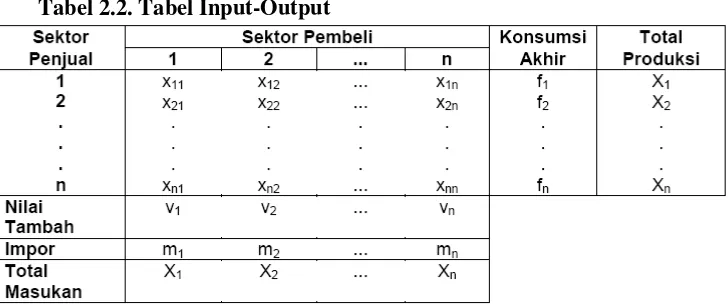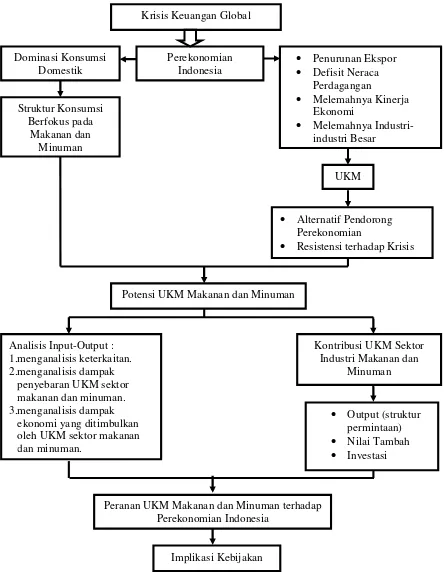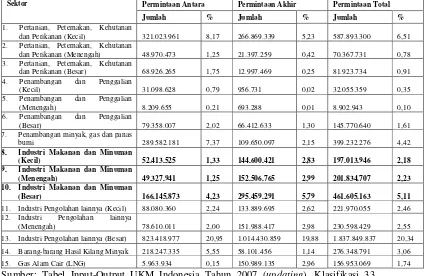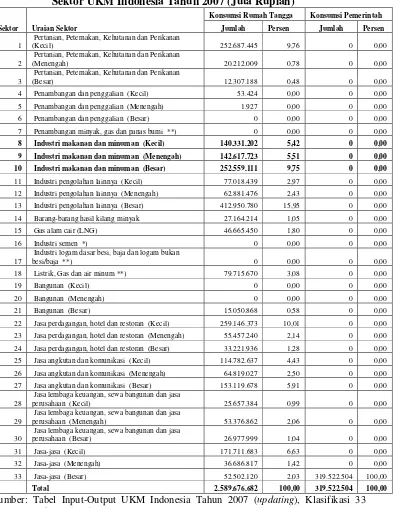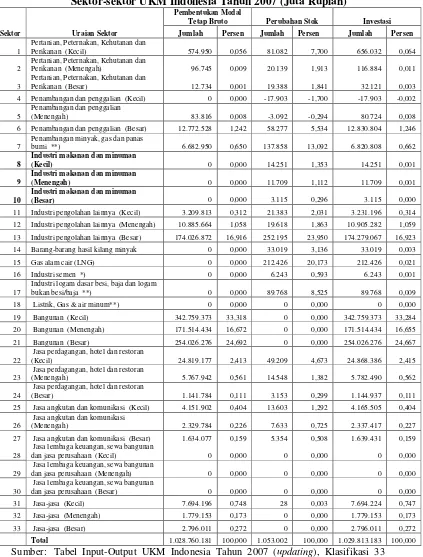ANALISIS PERANAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN
TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
OLEH ANGGI DESTRIA
H14050283
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
RINGKASAN
ANGGI DESTRIA. Analisis Peranan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Industri
Makanan dan Minuman terhadap Perekonomian Indonesia (dibimbing oleh
TONY IRAWAN).
Krisis ekonomi yang terjadi akibat subprime mortgage berdampak pada sektor keuangan Amerika Serikat dan juga berdampak kepada sektor riil serta perekonomian dunia yang terhubung ke dalamnya. Jatuhnya pasar keuangan Amerika Serikat dan kemudian pasar keuangan dunia menimbulkan suatu kontraksi ekonomi yang berdampak luas. Efek kontraksi ekonomi tersebut dapat dirasakan bukan hanya oleh sesama negara maju tetapi yang lebih parah terkena dampak krisis tersebut ialah negara-negara berkembang. Salah satunya adalah Indonesia.
Indonesia memiliki hubungan perdagangan dengan intensitas yang relatif tinggi sehingga saat krisis ekonomi terjadi berdampak pada penurunan permintaan. Hal ini menciptakan tren penurunan surplus (ekspor netto) neraca perdagangan Indonesia. Merosotnya ekspor juga diikuti dengan merosotnya kinerja pasar modal dan perbankan, serta penurunan nilai aset-aset perusahaan besar yang berimbas kepada situasi kontraksi pada industri-industri besar penopang ekonomi Indonesia. Dampak tersebut kemudian berlanjut kepada maraknya kebijakan pemutusan hubungan kerja serta tingkat pengangguran yang semakin meningkat yang akan berujung kepada tingkat kemiskinan yang semakin meningkat. Salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah ini adalah pemanfaatan pasar domestik secara optimal dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat menjadi solusinya.
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) lebih menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan sektor formal. Karena pada sektor formal dibutuhkan suatu keterampilan yang khusus yang tidak dimiliki olh sebagian besar pencari kerja. Dengan kata lain kondisi keterampilan tenaga kerja ini sering tidak sesuai dengan kondisi keterampilan yang dituntut oleh sektor formal pada umumnya. Berdasarkan prospek usaha, UKM merupakan sektor yang potensial dalam menciptakan nilai tambah. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa UKM belum maksimal dikembangkan, terbukti dengan banyaknya kekurangan yang menghambat UKM untuk berkembang. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh yaitu dalam hal permodalan (investasi). Hal tersebut menghambat UKM untuk meningkatkan skala produksi dan perluasan skala usaha. Sehingga meskipun potensial dalam penciptaan lapangan kerja, dengan adanya hambatan tersebut akan menghambat proses penyerapan tenaga kerja dan perluasan usaha.
Untuk melihat peranan UKM sektor industri makanan dan minuman, sehingga tujuan penelitian ini adalah (1) Melihat peranan UKM sektor industri makanan dan minuman dalam struktur permintaan, investasi dan nilai tambah bruto, (2) Menganalisa keterkaitannya dengan sektor-sektor lainnya, (3) Menganalisa dampak penyebaran antara UKM sektor industri makanan dan minuman dengan sektor lainnya, dan (4) Menganalisa dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh UKM sektor industri makanan dan minuman dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja berdasarkan efek pengganda (multiplier) output, pendapatan dan tenaga kerja.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder dari Tabel Input-Output UKM nasional tahun 2007 updating dengan matriks berukuran 233x233 yang kemudian diagregasi menjadi matriks berukuran 33x33 dan juga beberapa data sekunder lainnya. Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan instansi terkait lainnya. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis Input-Output maupun analisis deskriptif. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan software Microsoft Excell 2003.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa UKM sektor industri makanan dan minuman mampu mempengaruhi pembentukan output sektor hulunya terutama sektor industri pengolahan lainnya (besar). Investasi industri makanan dan minuman kecil, menengah maupun besar menunjukkan nilai yang sangat kecil. Hal ini terjadi karena sebagian besar UKM sektor industri makanan dan minuman belum bankable (belum memenuhi syarat berhubungan dengan bank) sehingga sulit untuk mendapatkan kredit untuk penambahan modal. Nilai tambah bruto sektor industri tergolong tinggi, termasuk didalamnya industri makanan dan minuman yang cukup tinggi.
Berdasarkan hasil analisis keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung, industri makanan dan minuman kecil, menengah dan besar memiliki keterkaitan kebelakang yang lebih besar dibandingkan dengan nilai keterkaitan kedepannya. Hal ini disebabkan industri makanan dan minuman kecil, menengah dan besar memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor hulunya yaitu industri pengolahan lainnya (besar). Nilai keterkaitan ke depan yang rendah diakibatkan oleh penggunaan output dari industri makanan dan minuman kecil, menengah dan besar yang lebih banyak dikonsumsi langsung oleh rumah tangga daripada digunakan sebagai input antara oleh sektor produksi lainnya.
Berdasarkan hasil analisis dampak penyebaran menunjukkan bahwa industri makanan dan minuman kecil dan menengah kurang memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan sektor hilirnya tetapi memiliki kemampuan untuk menarik pertumbuhan sektor hulunya. Hal ini sesuai dengan analisis keterkaitan, dimana nilai keterkaitan ke belakang lebih besar daripada keterkaitan ke depannya. Namun dari ke dua analisis tersebut UKM sektor industri makanan dan minuman merupakan industri yang layak untuk dikembangkan.
dibandingkan dengan multiplier pendapatan. Hal ini menjelaskan bahwa jika terjadi peningkatan permintaan akhir pada industri makanan dan minuman (kecil) akan meningkatkan output sektor-sektor lainnya. Industri makanan dan minuman (menengah) memiliki nilai multiplier pendapatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan multiplier output. Hal ini menjelaskan bahwa jika terjadi peningkatan permintaan akhir output dari sektor industri makanan dan minuman (menengah) akan meningkatkan pendapatan rumah tangga yang bekerja pada sektor tersebut.
ANALISIS PERANAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN
TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
Oleh
ANGGI DESTRIA H14050283
Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
Judul Skripsi : Analisis Peranan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Industri Makanan dan Minuman terhadap Perekonomian
Indonesia
Nama : Anggi Destria
NIM : H14050283
Menyetujui, Dosen Pembimbing
Toni Irawan, M. App. Ec
NIP : 19820306 20050 1 1001
Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Dr.Ir. Rina Oktaviani, MS
NIP : 19641023 1989032 002
PERNYATAAN
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.
Bogor, Juli 2009
RIWAYAT HIDUP
Anggi Destria. Dilahirkan di Bogor pada hari Selasa tanggal 16 Desember 1986 dari pasangan Bapak Rochman Effendi dan Ibu Mardiah Rosdiana. Penulis merupakan putri ketiga dari tiga bersaudara. Penulis menjalani kehidupan yang bahagia dari kecil sampai dewasa di kota kelahirannya, kota Bogor, Jawa Barat.
Penulis menjalani pendidikan di bangku sekolah dasar dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1999 di SDN Polisi V Bogor. Selanjutnya meneruskan ke pendidikan lanjutan tingkat pertama dari tahun 1999 sampai tahun 2002 di SLTPN 1 Bogor. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan menengah umum di SMUN 2 Bogor dan lulus pada tahun 2005.
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Segala puji hanya untuk Allah SWT, pencipta dan pemelihara alam semesta beserta isinya. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mendapat kemudahan dan kemampuan dalam setiap langkah penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senatiasa tercurah kepada Qudwah Hasanah kita, Rasulullah Saw, yang telah mengajarkan Al-Islam sebagai jalan hidup sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia sejagad raya.
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Manajemen IPB. Adapun judul skripsi ini adalah Analisis Peranan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Industri Makanan dan Minuman terhadap Perekonomian
Indonesia.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, perhatian, dan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu, ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada:
1. Bapak Tony Irawan, M. App. Ec. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. 2. Ibu Widyastutik, SE, M.Si. dan Ibu Fifi Diana Thamrin, M.Si selaku dosen
penguji utama dan komisi pendidikan, yang telah memberi saran-saran dan ilmu yang bermanfaat.
3. Bapak Ir. Eko Oesman yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan Harry Gustara, Sundoro Ari, Fitrah Mailendra, Riri, Arisa, Ginna, Dian Agustina, Inna, Tanjung, Tyaz, Dewinta, Renny dan seluruh teman-teman angkatan 42 Ilmu Ekonomi.
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan. Dengan kerendahan hati, penulis meminta maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan penulis.
Semoga hasil dari skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun semua pihak yang membutuhkan.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Bogor, Juli 2009
ANALISIS PERANAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN
TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
OLEH ANGGI DESTRIA
H14050283
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
RINGKASAN
ANGGI DESTRIA. Analisis Peranan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Industri
Makanan dan Minuman terhadap Perekonomian Indonesia (dibimbing oleh
TONY IRAWAN).
Krisis ekonomi yang terjadi akibat subprime mortgage berdampak pada sektor keuangan Amerika Serikat dan juga berdampak kepada sektor riil serta perekonomian dunia yang terhubung ke dalamnya. Jatuhnya pasar keuangan Amerika Serikat dan kemudian pasar keuangan dunia menimbulkan suatu kontraksi ekonomi yang berdampak luas. Efek kontraksi ekonomi tersebut dapat dirasakan bukan hanya oleh sesama negara maju tetapi yang lebih parah terkena dampak krisis tersebut ialah negara-negara berkembang. Salah satunya adalah Indonesia.
Indonesia memiliki hubungan perdagangan dengan intensitas yang relatif tinggi sehingga saat krisis ekonomi terjadi berdampak pada penurunan permintaan. Hal ini menciptakan tren penurunan surplus (ekspor netto) neraca perdagangan Indonesia. Merosotnya ekspor juga diikuti dengan merosotnya kinerja pasar modal dan perbankan, serta penurunan nilai aset-aset perusahaan besar yang berimbas kepada situasi kontraksi pada industri-industri besar penopang ekonomi Indonesia. Dampak tersebut kemudian berlanjut kepada maraknya kebijakan pemutusan hubungan kerja serta tingkat pengangguran yang semakin meningkat yang akan berujung kepada tingkat kemiskinan yang semakin meningkat. Salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah ini adalah pemanfaatan pasar domestik secara optimal dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat menjadi solusinya.
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) lebih menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan sektor formal. Karena pada sektor formal dibutuhkan suatu keterampilan yang khusus yang tidak dimiliki olh sebagian besar pencari kerja. Dengan kata lain kondisi keterampilan tenaga kerja ini sering tidak sesuai dengan kondisi keterampilan yang dituntut oleh sektor formal pada umumnya. Berdasarkan prospek usaha, UKM merupakan sektor yang potensial dalam menciptakan nilai tambah. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa UKM belum maksimal dikembangkan, terbukti dengan banyaknya kekurangan yang menghambat UKM untuk berkembang. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh yaitu dalam hal permodalan (investasi). Hal tersebut menghambat UKM untuk meningkatkan skala produksi dan perluasan skala usaha. Sehingga meskipun potensial dalam penciptaan lapangan kerja, dengan adanya hambatan tersebut akan menghambat proses penyerapan tenaga kerja dan perluasan usaha.
Untuk melihat peranan UKM sektor industri makanan dan minuman, sehingga tujuan penelitian ini adalah (1) Melihat peranan UKM sektor industri makanan dan minuman dalam struktur permintaan, investasi dan nilai tambah bruto, (2) Menganalisa keterkaitannya dengan sektor-sektor lainnya, (3) Menganalisa dampak penyebaran antara UKM sektor industri makanan dan minuman dengan sektor lainnya, dan (4) Menganalisa dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh UKM sektor industri makanan dan minuman dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja berdasarkan efek pengganda (multiplier) output, pendapatan dan tenaga kerja.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder dari Tabel Input-Output UKM nasional tahun 2007 updating dengan matriks berukuran 233x233 yang kemudian diagregasi menjadi matriks berukuran 33x33 dan juga beberapa data sekunder lainnya. Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan instansi terkait lainnya. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis Input-Output maupun analisis deskriptif. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan software Microsoft Excell 2003.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa UKM sektor industri makanan dan minuman mampu mempengaruhi pembentukan output sektor hulunya terutama sektor industri pengolahan lainnya (besar). Investasi industri makanan dan minuman kecil, menengah maupun besar menunjukkan nilai yang sangat kecil. Hal ini terjadi karena sebagian besar UKM sektor industri makanan dan minuman belum bankable (belum memenuhi syarat berhubungan dengan bank) sehingga sulit untuk mendapatkan kredit untuk penambahan modal. Nilai tambah bruto sektor industri tergolong tinggi, termasuk didalamnya industri makanan dan minuman yang cukup tinggi.
Berdasarkan hasil analisis keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung, industri makanan dan minuman kecil, menengah dan besar memiliki keterkaitan kebelakang yang lebih besar dibandingkan dengan nilai keterkaitan kedepannya. Hal ini disebabkan industri makanan dan minuman kecil, menengah dan besar memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor hulunya yaitu industri pengolahan lainnya (besar). Nilai keterkaitan ke depan yang rendah diakibatkan oleh penggunaan output dari industri makanan dan minuman kecil, menengah dan besar yang lebih banyak dikonsumsi langsung oleh rumah tangga daripada digunakan sebagai input antara oleh sektor produksi lainnya.
Berdasarkan hasil analisis dampak penyebaran menunjukkan bahwa industri makanan dan minuman kecil dan menengah kurang memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan sektor hilirnya tetapi memiliki kemampuan untuk menarik pertumbuhan sektor hulunya. Hal ini sesuai dengan analisis keterkaitan, dimana nilai keterkaitan ke belakang lebih besar daripada keterkaitan ke depannya. Namun dari ke dua analisis tersebut UKM sektor industri makanan dan minuman merupakan industri yang layak untuk dikembangkan.
dibandingkan dengan multiplier pendapatan. Hal ini menjelaskan bahwa jika terjadi peningkatan permintaan akhir pada industri makanan dan minuman (kecil) akan meningkatkan output sektor-sektor lainnya. Industri makanan dan minuman (menengah) memiliki nilai multiplier pendapatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan multiplier output. Hal ini menjelaskan bahwa jika terjadi peningkatan permintaan akhir output dari sektor industri makanan dan minuman (menengah) akan meningkatkan pendapatan rumah tangga yang bekerja pada sektor tersebut.
ANALISIS PERANAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN
TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
Oleh
ANGGI DESTRIA H14050283
Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
Judul Skripsi : Analisis Peranan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Industri Makanan dan Minuman terhadap Perekonomian
Indonesia
Nama : Anggi Destria
NIM : H14050283
Menyetujui, Dosen Pembimbing
Toni Irawan, M. App. Ec
NIP : 19820306 20050 1 1001
Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Dr.Ir. Rina Oktaviani, MS
NIP : 19641023 1989032 002
PERNYATAAN
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.
Bogor, Juli 2009
RIWAYAT HIDUP
Anggi Destria. Dilahirkan di Bogor pada hari Selasa tanggal 16 Desember 1986 dari pasangan Bapak Rochman Effendi dan Ibu Mardiah Rosdiana. Penulis merupakan putri ketiga dari tiga bersaudara. Penulis menjalani kehidupan yang bahagia dari kecil sampai dewasa di kota kelahirannya, kota Bogor, Jawa Barat.
Penulis menjalani pendidikan di bangku sekolah dasar dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1999 di SDN Polisi V Bogor. Selanjutnya meneruskan ke pendidikan lanjutan tingkat pertama dari tahun 1999 sampai tahun 2002 di SLTPN 1 Bogor. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan menengah umum di SMUN 2 Bogor dan lulus pada tahun 2005.
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Segala puji hanya untuk Allah SWT, pencipta dan pemelihara alam semesta beserta isinya. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mendapat kemudahan dan kemampuan dalam setiap langkah penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senatiasa tercurah kepada Qudwah Hasanah kita, Rasulullah Saw, yang telah mengajarkan Al-Islam sebagai jalan hidup sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia sejagad raya.
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Manajemen IPB. Adapun judul skripsi ini adalah Analisis Peranan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Industri Makanan dan Minuman terhadap Perekonomian
Indonesia.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, perhatian, dan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu, ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada:
1. Bapak Tony Irawan, M. App. Ec. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. 2. Ibu Widyastutik, SE, M.Si. dan Ibu Fifi Diana Thamrin, M.Si selaku dosen
penguji utama dan komisi pendidikan, yang telah memberi saran-saran dan ilmu yang bermanfaat.
3. Bapak Ir. Eko Oesman yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan Harry Gustara, Sundoro Ari, Fitrah Mailendra, Riri, Arisa, Ginna, Dian Agustina, Inna, Tanjung, Tyaz, Dewinta, Renny dan seluruh teman-teman angkatan 42 Ilmu Ekonomi.
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan. Dengan kerendahan hati, penulis meminta maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan penulis.
Semoga hasil dari skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun semua pihak yang membutuhkan.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Bogor, Juli 2009
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR TABEL ... iv
DAFTAR GAMBAR ... v
DAFTAR LAMPIRAN ... vi
I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1
1.2. Perumusan Masalah ... 8
1.3. Tujuan Penelitian ... 10
1.4. Manfaat Penelitian ... 10
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 2.1. Definisi dan Ruang Lingkup Usaha Kecil dan Menengah ... 12
2.2. Peranan UKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi ... 16
2.3. Golongan Industri Makanan dan Minuman Menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 ... 19
2.4. Kondisi Industri Makanan dan Minuman di Indonesia. ... 19
2.5. Tabel Input-Output 2.5.1. Konsep dan Definisi. ... 25
2.5.2. Kerangka Dasar Tabel Input-Output. ... 28
2.6. Analisis Input-Output 2.6.1. Analisis Keterkaitan. ... 31
2.6.2. Analisis Dampak Penyebaran. ... 33
2.6.3. Analisis Pengganda ... 34
2.7. Penelitian Terdahulu ... 36
2.8. Kerangka Penelitian ... 39
III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data ... 43
3.2. Metode Pengolahan dan Analisis Data 3.2.1. Tabel Koefisien Input. ... 44
3.2.3. Koefisien Pendapatan. ... 46 3.2.4. Koefisien Tenaga Kerja ... 47 3.3. Analisis Keterkaiatan
3.3.1. Keterkaitan ke Depan. ... 48 3.3.2. Keterkaitan ke Belakang ... 48 3.4. Analisis Dampak Penyebaran
3.4.1. Kepekaan Penyebaran ... 49 3.4.2. Koefisien Penyebaran. ... 50 3.5. Analisis Pengganda
3.5.1. Pengganda Output. ... 51 3.5.2. Pengganda Pendapatan ... 52 3.5.3. Pengganda Tenaga Kerja. ... 54
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Struktur Input Antara dan Permintaan Antara Usaha Kecil dan Menengah Sektor Industri Makanan dan Minuman
4.1.1. Struktur Input Antara
UKM Sektor Industri Makanan dan Minuman. ... 57 4.1.2. Struktur Permintaan
UKM Sektor Industri Makanan dan Minuman ... 58 4.1.3. Struktur Konsumsi Rumah Tangga
dan Konsumsi Pemerintah. ... 60 4.1.4. Struktur Investasi ... 62 4.1.5. Struktur Nilai Tambah Bruto ... 64 4.2. Analisis Keterkaitan
4.2.1. Keterkaitan ke Depan. ... 68 4.2.2. Keterkaitan ke Belakang. ... 70 4.3. Analisis Dampak Penyebaran... 72 4.4. Analisis Pengganda
V. KESIMPULAN DAN SARAN
DAFTAR TABEL
Nomor Halaman
2.1. Kerangka Penyajian Tabel Input-Output ... 29 2.2. Tabel Input-Output ... 30 3.1. Ringkasan Rumus Multiplier Output, Pendapatan
dan Tenaga Kerja ... 56 4.1. Struktur Komposisi Input Antara UKM 10 Sektor Utama
Indonesia Tahun 2007 ... 58 4.2. Permintaan Antara dan Permintaan Akhir
15 Sektor UKM Indonesia Tahun 2007 ... 59 4.3. Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah
Sektor-Sektor UKM Indonesia Tahun 2007 ... 61 4.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Stok, dan
Investasi Sektor-Sektor UKM Indonesia Tahun 2007 ... 63 4.5. Kontribusi Sektor-Sektor UKM Indonesia terhadap
Nilai Tambah Bruto ... 67 4.6. Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung ke Depan
Sektor-Sektor UKM Indonesia Tahun 2007 ... 69 4.7. Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung ke Belakang
Sektor-Sektor UKM Indonesia Tahun 2007 ... 71 4.8. Nilai Koefisien Penyebaran dan Kepekaan Penyebaran
Sektor-Sektor UKM Indonesia Tahun 2007 ... 74 4.9. Nilai Koefisien Multiplier Output, Multiplier Pendapatan
dan Multiplier Tenaga Kerja Tipe I dan Tipe II
DAFTAR GAMBAR
Nomor Halaman
1.1. Jumlah Pengusaha UKM di Indonesia Periode 1997-2007 ... 5 1.2. Penyerapan Tenaga Kerja oleh UKM di Berbagai Sektor
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Halaman
1. Kode dan Klasifikasi Sektor Tabel yang Digunakan ... 86 2. Tabel Input-Output UKM Indonesia 2007 (Updating)
Klasifikasi 33 Sektor ... 95 3. Matriks Koefisien Input Klasifikasi 33 Sektor ... 102
4. Matriks Kebalikan Leontif Terbuka Klasifikasi 33 Sektor ... 107 5. Matriks Kebalikan Leontif Tertutup Klasifikasi 33 Sektor... 112 6. Permintaan Antara dan Permintaan Akhir Sektor-sektor
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Beberapa tahun terakhir sejak pertengahan tahun 2007 hingga sekarang
menjadi masa-masa terberat bagi perekonomian Amerika Serikat dan juga
berdampak pada perekonomian dunia. Krisis ekonomi yang terjadi akibat
subprime mortgage tersebut bukan hanya berdampak kepada sektor keuangan negara adidaya tersebut tetapi juga berdampak kepada sektor riil serta
perekonomian dunia yang terhubung ke dalamnya. Jatuhnya pasar keuangan
Amerika Serikat dan kemudian pasar keuangan dunia menimbulkan suatu
kontraksi ekonomi yang berdampak luas. Efek kontraksi ekonomi tersebut dapat
dirasakan bukan hanya oleh sesama negara maju tetapi yang lebih parah terkena
dampak krisis tersebut ialah negara-negara berkembang.
Hal ini terjadi karena penurunan harga saham di negara maju seperti
Amerika Serikat dimana bank-bank internasional mengalami kerugian akibat
krisis subprime mortgage yang awalnya menimbulkan penurunan kurs Dollar AS terhadap mata uang Euro dan Yen. Jatuhnya valuasi saham di AS selanjutnya
memicu penurunan harga saham di seluruh dunia karena investor khawatir
pelemahan ekonomi AS akan berdampak pada perlambatan ekonomi dunia.
Dampak berikutnya dari penurunan harga saham di negara berkembang adalah
adanya pelarian modal ke instrumen yang kurang berisiko (misalnya surat utang
negara maju atau emas) sehingga kurs mata uang negara berkembang melemah.
Perlambatan ekonomi hampir terjadi di seluruh negara seperti Amerika
ditambah lagi dengan adanya suatu integrasi pasar keuangan dan perdagangan
dunia sehingga setiap negara merasakan dampak krisis yang hampir serupa.
Negara-negara berkembang memiliki hubungan yang erat dengan Amerika Serikat
yang terkait dengan perdagangan produk-produk. Seperti halnya negara-negara
berkembang lainnya, Indonesia juga memiliki hubungan perdagangan dengan
intensitas yang relatif tinggi. Indonesia memiliki proporsi ekspor produk ke pasar
AS sebesar 20 persen sehingga saat krisis ekonomi terjadi berdampak pada
penurunan permintaan. Lebih lanjut, kondisi krisis global menimbulkan second
round effect berupa melemahnya nilai ekspor netto Indonesia karena penurunan daya beli luar negeri dan semakin mahalnya bahan baku impor akibat pelemahan
Rupiah.
Kondisi ini pun pada gilirannya berkontribusi terhadap tren penurunan
surplus (ekspor netto) neraca perdagangan Indonesia. Idealnya, komponen ekspor
netto memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menopang laju PDB
sekaligus demi menciptakan kondisi aman pada supply cadangan devisa. Akan tetapi, kenyataan berkata lain, kontribusi ekspor netto dalam pembentukan PDB
terus mengalami tren penurunan. Pada tahun 2003, kontribusi ekspor netto
terhadap pembentukan PDB masih sebesar 7,63 persen. Tetapi, pada tahun 2004
kontribusi ekspor netto turun drastis menjadi hanya 4,65 persen. Kemudian, pada
tahun 2005 kontribusi ekspor netto terhadap pembentukan PDB turun lagi menjadi
hanya 4,30 persen. Kontribusi ekspor netto dalam pembentukan PDB mengalami
kenaikan pada tahun 2006 menjadi 5,40 persen. Namun pada tahun 2007
triwulan ketiga 2008 kontribusi ekspor netto sebagai penopang PDB terus
mengalami penurunan. Pada triwulan ketiga 2008, kontribusi ekspor netto, bahkan
tercatat berkontraksi atau tumbuh negatif sebesar 0,10 persen.
Merosotnya ekspor juga diikuti dengan merosotnya kinerja pasar modal
dan perbankan, serta penurunan nilai aset-aset perusahaan besar yang berimbas
kepada situasi kontraksi pada industri-industri besar penopang ekonomi
Indonesia. Dampak tersebut kemudian berlanjut kepada maraknya kebijakan
pemutusan hubungan kerja serta tingkat pengangguran yang semakin meningkat
yang akan berujung kepada tingkat kemiskinan yang semakin meningkat.
Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) telah terjadi pada industri-industri
yang berorientasi ekspor, menyusul kemudian rencana PHK pada industri tekstil
dan produksi tekstil (TPT) dan kertas, dan rencana merumahkan tenaga kerja pada
industri perkayuan dan industri perkebunan. Selain itu, resesi global juga
mengakibatkan PHK atas sebagian dari tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar
negeri, dan pemulangan mereka ke Indonesia, sehingga akan mengurangi
pendapatan devisa dari penghasilan mereka di luar negeri (remittance).
Situasi dan kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu dan dampak
negatif yang dapat ditimbulkannya harus dapat diantisipasi segera oleh seluruh
stakeholders dalam perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia memerlukan suatu alternatif sektor yang dapat menjadi prime sector dan menggantikan sektor industri besar yang sedang terpuruk dalam menyokong
pertumbuhan ekonomi dan kestabilan sosial. Selain itu, diperlukan pemanfaatan
UKM (Usaha Kecil Menengah) diindikasikan dapat menjadi solusi dalam
melewati masa-masa krisis ekonomi seperti sekarang ini.
Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu kegiatan ekonomi
yang telah terbukti tidak rentan terhadap krisis ekonomi. Pengalaman krisis
ekonomi tahun 1997 telah menunjukkan bahwa UKM dapat menjadi penyokong
perekonomian yang paling efektif dalam mengatasi masalah makroekonomi yang
terjadi. UKM memanfaatkan pasar domestik dan memiliki korelasi yang rendah
dengan sistem keuangan, pasar keuangan, dan perekonomian global sehingga
tidak rentan terhadap krisis. Selain itu, UKM bukanlah main partner perbankan sehingga UKM kurang terpengaruh oleh guncangan di sektor perbankan dan
resiko keuangan lainnya. UKM memiliki peranan dalam mengatasi pengangguran
karena sebagian besar bersifat labor intensif dengan memanfaatkan tenaga kerja yang jauh lebih banyak dibandingkan industri besar yang lebih berfokus pada
modal (capital intensive) sehingga terjadi trickle down effect yang lebih besar dan diharapkan dapat membawa perekonomian ke arah yang lebih stabil dalam masa
krisis ini.
Kemampuan UKM untuk tetap bertahan di masa krisis ekonomi
merupakan bukti bahwa sektor UKM merupakan bagian dari sektor usaha yang
cukup tangguh. Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari negara
berkembang belakangan ini memandang penting keberadaan usaha mikro dan
kecil (Berry, et al., 2001). Alasan pertama adalah karena kinerja usaha mikro dan kecil cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif.
peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga adalah karena sering diyakini bahwa usaha mikro dan kecil memiliki keunggulan
dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar.
Jumlah Pengusaha UKM Periode 1997-2007
0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000
1997 1998 19992000 2001 2002 2003 20042005 2006 2007
Tahun
J
u
m
la
h
Jumlah Pengusaha UKM
[image:31.612.135.501.188.360.2]Sumber : Statistik Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2008
Gambar 1.1 Jumlah Pengusaha UKM di Indonesia Periode 1997-2007
Kuncoro (2002) menyebutkan bahwa UKM di Indonesia telah memainkan
peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan
mendukung pendapatan rumah tangga. Pada tahun 1980 jumlah pengusaha yang
bergerak di sektor UKM sekitar 7 ribu dan terus meningkat tiap tahunnya. Pada
saat krisis ekonomi tahun 1997 terjadi penurunan tajam jumlah pengusaha yang
bergerak di sektor UKM ini dari sekitar 39 juta menjadi sekitar 36 juta atau turun
7,4 persen. Setelah krisis ekonomi 1997 jumlah pengusaha di sektor UKM ini
terus mengalami peningkatan. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik tahun
2000, menunjukkan dari 39,04 juta pengusaha, 99,85 persen merupakan
pengusaha kecil dan 0,14 persen merupakan pengusaha menengah, serta hanya
0,05 persen pengusaha besar. Jumlah Pengusaha di sektor UKM ini terus
pengusaha pada tahun 2005. Hingga tahun 2006 jumlah pengusaha di sektor UKM
terus meningkat mencapai 48,78 juta pengusaha.
0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Tahun
J
u
m
la
h
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan
Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi
[image:32.612.135.504.160.341.2]Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah 2008
Gambar 1.2 Penyerapan Tenaga Kerja oleh UKM di Berbagai Sektor di IndonesiaPeriode 1997-2007
Tingkat penyerapan tenaga kerja sektor UKM di Indonesia secara rata-rata
meningkat sebesar 3 persen per tahun. Selama periode 1997-2007, tingkat
penyerapan tenaga kerja meningkat hingga 24 persen sementara pertumbuhan
output sektor UKM meningkat hingga 307,45 persen. Dilihat dari seluruh sektor
ekonomi ternyata secara rata-rata dalam periode 1997-2007, sektor pertanian,
peternakan, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi yang paling besar
terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 98 persen per tahun dengan kontribusi
output rata-rata terhadap output total sektor UKM sebesar 64,7 persen per tahun.
Sektor listrik gas dan air bersih memberikan tingkat penyerapan tenaga kerja yang
paling rendah sebesar 0,4 persen per tahun dengan kontribusi terhadap output total
Menurut Hoselitz (1959), Sektor UKM di negara berkembang merupakan
sektor yang labor intensive sehingga sektor ini diharapkan dapat mengatasi masalah pengangguran di negara berkembang. Selain labor intensive, UKM sering dikenal sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, banyak sisi kebaikan yang dapat
diambil dari usaha mikro dan kecil khususnya dalam mendorong pembangunan di
negara-negara berkembang. UKM mempunyai ciri khusus yakni sifat mereka
yang memiliki keterampilan (skill) dan teknologi khusus, kontribusi dan kewirausahaan akan pembangunan, dan memiliki keterkaitan dengan berbagai
industri (industrial linkages). UKM memberikan prospek yang cerah di masa depan untuk menciptakan tenaga kerja dengan skala yang besar dan kesempatan
mendapatkan pendapatan dengan biaya yang relatif rendah khususnya pada daerah
desa atau pinggiran kota (rural) yang akan mendukung kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dan berkeseimbangan, yang merupakan
syarat untuk memicu dan keluar dari kemiskinan dan masalah-masalah sosial
ekonomi lainnya (Ahmed, 2001).
Subsektor makanan dan minuman merupakan salah satu pusat konsentrasi
dari kegiatan produksi usaha kecil. Hal ini dapat dilihat dari data nilai output dan
nilai tambah dari subsektor makanan dan minuman yaitu sebesar 35,5 persen dan
26 persen dari total nilai output dan total nilai tambah tahun 2005 (BPS, 2005).
Struktur perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa 60 persen pendapatan
nasional didominasi oleh konsumsi rumah tangga, dan faktor inilah yang cukup
mampu menahan dampak krisis global yang sedang berlangsung. Jika dilihat dari
ialah sektor industri makanan dan minuman. Selain itu UKM sektor industri
makanan dan minuman memiliki keterkaitan dengan banyak sektor, mulai dari
proses produksi hingga proses distribusi hasil output. Dengan kata lain,
sektor-sektor ekonomi yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung
terhadap seluruh rangkaian produksi hingga pemasaran produk akhir seperti
pertanian, perdagangan, jasa, transportasi dan sektor-sektor ekonomi lainnya ikut
diuntungkan melalui suatu mekanisme yang dikenal dengan mekanisme
keterkaitan (linkage mechanism).
1.2. Perumusan Masalah
Banyaknya angkatan kerja yang diserap sektor informal merupakan
refleksi ketidakmampuan sektor formal dalam membuka kesempatan kerja lebih
luas terhadap sebagian besar penduduk usia kerja. Sektor formal selama ini
memang diakui sebagai pemberi kontribusi pendapatan terbesar bagi
perekonomian negara namun disatu sisi sektor ini mempunyai ketidakmampuan
dalam menyerap banyak tenaga kerja. Disamping itu, meskipun penyediaan
kesempatan kerja oleh sektor formal terbuka untuk semua orang, namun dalam
kenyataannya kesempatan kerja ini membutuhkan syarat-syarat keterampilan
khusus yang tidak dimiliki oleh sebagian besar pencari kerja. Dengan kata lain
kondisi keterampilan tenaga kerja ini sering tidak sesuai dengan kondisi
keterampilan yang dituntut oleh sektor formal pada umumnya (Cahyono, 1983).
Berdasarkan prospek usaha, UKM merupakan sektor yang potensial dalam
belum maksimal dikembangkan, terbukti dengan banyaknya kekurangan yang
menghambat UKM untuk berkembang. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh
yaitu dalam hal permodalan (investasi). Hal tersebut menghambat UKM untuk
meningkatkan skala produksi dan perluasan skala usaha. Sehingga meskipun
potensial dalam penciptaan lapangan dengan adanya hambatan tersebut akan
menghambat pula proses penyerapan tenaga kerja dan perluasan usaha.
Salah satu sektor UKM yang memiliki potensi dalam menciptakan nilai
tambah adalah UKM sektor industri makanan dan minuman. Hal ini dapat dilihat
dari kontribusi dan peranan UKM sektor industri makanan dan minuman sebagai
salah satu pusat konsentrasi unit usaha kecil dan juga sebagai motor penggerak
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah terbukti handal. UKM sektor industri
makanan dan minuman merupakan salah satu yang memiliki nilai output dan nilai
tambah yang tinggi, juga dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, UKM sektor
industri makanan dan minuman dapat memenuhi kebutuhan masyarakat domestik
atau masyarakat dalam negeri yang didominasi oleh kebutuhan pokok yaitu
makanan dan minuman.
Berdasarkan uraian di atas, beberapa hal yang ingin diidentifikasi dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana peranan UKM sektor industri makanan dan minuman
berdasarkan struktur permintaan, investasi, dan nilai tambah bruto?
2. Bagaimana keterkaitan UKM sektor industri makanan dan minuman dengan
3. Berapa besar dampak penyebaran UKM sektor industri makanan dan
minuman di Indonesia?
4. Berapa besar dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh UKM sektor industri
makanan dan minuman, ditinjau berdasarkan multiplier terhadap output,
pendapatan dan tenaga kerja?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan, tujuan
penelitian adalah :
1. Melihat peranan UKM sektor industri makanan dan minuman dalam struktur
permintaan, investasi dan nilai tambah bruto.
2. Menganalisis keterkaitan UKM sektor industri makanan dan minuman
dengan UKM sektor lainnya.
3. Menganalisis dampak penyebaran UKM sektor industri makanan dan
minuman di Indonesia.
4. Menganalisis dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh UKM sektor industri
makanan dan minuman, ditinjau berdasarkan multiplier terhadap output,
pendapatan dan tenaga kerja.
1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pemegang
kebijakan dan masyarakat pada umumnya. Manfaat atau kegunaan yang
kebijakan mengenai peran UKM dalam pertumbuhan ekonomi khususnya dalam
menciptakan output, nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja serta keterkaitan
dengan perkembangan UKM di sektor lainnya sehingga pemegang kebijakan
dapat mengeluarkan alat kebijakan yang tepat dalam meningkatkan UKM sektor
industri makanan dan minuman.
Penelitian ini juga diharapkan memberikan pengetahuan kepada
masyarakat tentang tabel Input-Output Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Tabel
Input-Output UKM berbeda dengan tabel Input-Output biasa karena pada tabel
Input-Output UKM sektor yang tertulis lebih rinci dilihat dari skala usahanya
yaitu usaha kecil, menengah dan besar. Sehingga kita dapat melihat hubungan
atau keterkaitan antar sektor dan juga hubungan atau keterkaitan antar skala
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.1. Definisi dan Ruang Lingkup Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Pengertian mengenai Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak selalu sama,
tergantung konsep yang digunakan. Dalam konsep tersebut mencakup sedikitnya
dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan
perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap dalam kelompok
perusahaan tersebut. Usaha kecil dioperasikan dan dimiliki secara independent,
tidak dominan dalam daerahnya dan tidak menggunakan praktek-praktek inovatif.
Tapi usaha yang bersifat kewirausahaan adalah usaha yang pada awalnya
bertujuan untuk tumbuh dan menguntungkan serta dapat dikarakteristikkan
dengan praktek-praktek inovasi strategis.
Pengertian usaha kecil dan menengah di Indonesia masih sangat beragam.
Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, Usaha Kecil (UK) memiliki kriteria
yang dilihat dari segi keuangan dan modal sebagai berikut ; Pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak dua ratus juta Rupiah, tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha. Kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak satu milyar rupiah. Ketiga, milik Warga Negara Indonesia (WNI). Keempat, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan
usaha menengah atau usaha besar. Kelima, berbentuk badan usaha orang perseorangan, tidak berbadan hukum termasuk koperasi. Menurut
rakyat yang mempunyai penjualan tahunan di atas satu milyar Rupiah sampai
sepuluh milyar rupiah.
Departemen Perindustrian dan Perdagangan menggunakan kriteria industri
kecil berdasarkan surat keputusan mentri No. 254/MPP/Kep/7/1999 tentang
kriteria industri kecil di lingkungan departemen perindustrian dan perdagangan
yang menyatakan bahwa yang termasuk industri kecil dan usaha dagang kecil
adalah perusahaan yang mempunyai nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai
dengan dua ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
serta pemiliknya adalah WNI. Departemen Perindustrian Republik Indonesia
mulai tahun 2003 membagi industri kecil ke dalam lima cabang industri yaitu
sandang, pangan, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronik serta
kerajinan.
World Bank memiliki definisi yang berbeda mengenai industri kecil dan
menengah. World Bank membaginya kedalam tiga kelompok dengan kriteria :
• Medium Enterprise
o Jumlah karyawan maksimal 300 orang.
o Pendapatan setahun mencapai $ 15 juta.
o Jumlah aset mencapai $ 15 juta.
• Small Enterprise
o Jumlah karyawan kurang dari 10 orang.
o Pendapatan setahun mencapai $ 3 juta.
• Micro Enterprise
o Jumlah karyawan kurang dari 10 orang.
o Pendapatan setahun tidak lebih dari $ 100 ribu.
o Jumlah aset tidak melebihi $ 100 ribu.
Sebenarnya masih ada definisi dan kriteria yang berbeda-beda dari
berbagai lembaga swadaya masyarakat dan para peneliti sesuai dengan tujuan
masing-masing. Namun dalam penelitian ini menggunakan data dengan definisi
UKM dari Badan Pusat Statistik (BPS). Definisi tentang ukuran besar kecilnya
perusahaan di Indonesia berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam
proses produksi menurut BPS dibagi menjadi :
1. Industri rumah tangga, yaitu perusahaan atau industri pengolahan dengan
jumlah tenaga kerja berkisar antara 1-4 orang.
2. Industri kecil, yaitu perusahaan atau industri pengolahan dengan jumlah
tenaga kerja berkisar antara 5-19 orang.
3. Industri sedang, yaitu perusahaan atau industri pengolahan dengan jumlah
tenaga kerja berkisar antara 20-90 orang.
4. Industri besar, yaitu perusahaan atau industri pengolahan dengan jumlah
tenaga kerja lebih besar dari 100 orang.
Klasifikasi baik usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar
menggunakan sembilan penggolongan utama sektor ekonomi yang meliputi :
1. Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan.
2. Pertambangan dan penggalian.
a. Makanan, minuman dan tembakau.
b. Tekstil, barang kulit dan alas kaki.
c. Barang kayu dan hasil hutan lainnya.
d. Kertas dan barang cetakan.
e. Pupuk kimia dan barang dari karet.
f. Semen dan barang galian bukan logam.
g. Logam dasar besi dan baja.
h. Alat angkutan, mesin dan peralatan.
i. Barang lainnya.
4. Listrik, gas dan air bersih.
5. Bangunan.
6. Perdagangan.
7. Pengangkutan dan komunikasi.
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
9. Jasa-jasa.
a. Pemerintah.
b. Swasta.
Dilihat dari beberapa definisi mengenai usaha kecil dan menengah (UKM)
terdapat karakteristik yang hampir seragam. Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil
dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola
Kedua, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal
sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara,
bahkan rentenir. Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum. Keempat, dilihat menurut golongan industri tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada
kelompok usaha industri makanan dan minuman (ISIC31), diikuti oleh kelompok
industri barang galian bukan logam (ISIC36), industri tekstil (ISIC32), dan
industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan
rumahtangga (ISIC33) masing-masing berkisar antara 21 persen hingga 22 persen
dari seluruh industri kecil yang ada. Sedangkan yang bergerak pada kelompok
usaha industri kertas (ISIC34) dan kimia (ISIC35) relatif masih sangat sedikit
sekali yaitu kurang dari 1 persen.
2.2. Peranan UKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, UKM selalu digambarkan
sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting karena sebagian besar
jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil
baik itu di sektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut
menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan yang dikelola
oleh dua departemen, yaitu (1) Departemen Perindustrian dan Perdagangan; (2)
Departemen Koperasi dan UKM. Namun demikian, usaha pengembangan yang
kemajuan UKM sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai
usaha besar.
Dalam analisis makroekonomi pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai
tingkat pertambahan dari pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi ini
digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu perekonomian telah mengalami
perkembangan dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Pertumbuhan
di suatu negara dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDB. Laju pertumbuhan PDB
yang merupakan tingkat output diturunkan dari fungsi produksi suatu barang dan
jasa. Fungsi produksi menurut Mankiw (2003) merupakan hubungan antara
tingkat output (Y) dengan tingkat input (capital and labour). Turunan pertama fungsi produksi dirumuskan sebagai berikut:
Y = f (K,L) (2.1)
Berdasarkan hal tersebut, maka nilai PDB secara langsung dipengaruhi
oleh tingkat investasi yang merupakan K ( capital) dan angkatan kerja yang merupakan Labour (L) dalam fungsi produksi. Investasi UKM setiap tahunnya terus meningkat, hal ini dapat mempertinggi efisiensi ekonomi dalam bentuk
barang-barang modal yang sangat penting artinya dalam pertumbuhan ekonomi.
Peranan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia
paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam
kegiatan ekonomi di berbagai sektor; (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar;
(3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan
pemberdayaan masyarakat; (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi; serta (5)
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian
nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada
masa mendatang (Kuncoro, 2002).
Pemberdayaan UKM secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan
mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat
pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6 persen per tahun. Selain itu juga dapat
mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan,
mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat.
Pemberdayaan UKM diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya
saingnya, serta secara sistematis diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha
baru di sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi yang berbasis
pengetahuan, teknologi dan sumber daya lokal (Gie Kian, K, 2003).
Pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang memadai.
Pada kondisi ekonomi Indonesia saat ini, relatif sulit menarik investasi dalam
jumlah yang besar. Untuk itu, keterbatasan investasi perlu diarahkan pada upaya
mengembangkan wirausaha mikro, kecil dan menengah, karena memiliki ICOR
yang rendah dengan lag waktu yang singkat. Pemberdayaan UKM diharapkan
lebih mampu menstimulan pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dalam
jangka waktu yang relatif pendek dan mampu memberikan lapangan kerja yang
lebih luas dan lebih banyak, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran
terbuka dan tingkat kemiskinan di Indonesia (Kemenkop, 2004).
Pemberdayaan UKM dapat meningkatkan stabilitas ekonomi makro,
akan membantu menstabilkan kurs rupiah dan tingkat inflasi. Pemberdayaan
UKM akan menggerakkan sektor riil, karena UKM umumnya memiliki
keterkaitan industri yang cukup tinggi. Dengan kata lain pemberdayaan UKM
akan memberikan perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan
sehingga dapat mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Kemenkop,
2004).
2.3. Golongan Industri Makanan dan Minuman Menurut Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005
Industri makanan dan minuman pada KBLI tahun 2005 diberi kode 15
(berdasarkan Kode KBLI dua digit). Industri ini dikelompokkan menjadi lima sub
golongan berdasarkan Kode KBLI tiga digit yakni : industri pengolahan dan
pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak dan lemak (kode
KBLI:151); industri susu dan makanan dari susu (kode KBLI:152); industri
penggilingan padi-padian, tepung, dan makanan ternak (kode KBLI:153); industri
makanan lainnya (kode KBLI:154) serta industri minuman (kode KBLI:155).
Sedangkan untuk pengelompokkan industri makanan dan minuman berdasarkan
Kode KBLI lima digit yakni sebanyak 60 kelompok industri.
2.4. Kondisi Industri Makanan dan Minuman di Indonesia
Total industri pangan Indonesia, baik berskala besar, kecil dan menengah,
maupun rumah tangga pada tahun 2004 mencapai jumlah 944.948 industri,
meningkat dibanding tahun 2003 dengan jumlah 883.880 industri. Akan tetapi,
industri. Industri makanan berskala besar dan menengah sejumlah 4.419 industri,
yang berskala kecil 78.449 industri dan rumah tangga sebanyak 862.080 industri.
Namun kalau dilihat nilai output dan penyerapan tenaga kerjanya, maka yang
besar dan menengah mencapai Rp 173,9 triliun dengan penyerapan tenaga kerja
sebanyak 653.930 orang, sedangkan yang skala kecil dan rumah tangga
masing-masing mencapai Rp 13,2 triliun dan Rp 20,1 triliun serta penyerapan tenaga kerja
masing-masing mencapai 635.036 orang dan 1.764.421 orang (Darmawan, 2006).
Omzet industri pangan baik skala besar, menengah, kecil dan rumah
tangga selalu tumbuh dengan besaran 10-12 persen per tahun. Pada tahun 2002
mencapai Rp 163,6 triliun maka pada tahun 2003 telah meningkat menjadi Rp
207,3 triliun. Pada tahun 2004 total omzet industri pangan mencapai kira-kira Rp
800 triliun, dengan perincian 70 persen tidak diolah dan 30 persen diolah. Omzet
industri pangan pada tahun 2005 sebanyak Rp 220 triliun sedangkan pada tahun
2006 menembus jumlah Rp 250 triliun (BPS, 2005). Angka peningkatan ini juga
disumbangkan oleh banyaknya investor asing yang masuk ke Indonesia telah
mencapai kapasitas produksi maksimum sehingga dibutuhkan investasi baru
seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan daya belinya.
Sebagaimana halnya dengan industri pangan skala besar dan sedang,
industri kecil menengah (IKM) atau usaha kecil menengah (UKM) pangan
nasional dari waktu ke waktu juga menunjukkan suatu sumbangsih yang cukup
berarti bagi perekonomian Indonesia. Situasi UKM makanan di Indonesia, pada
umumnya dikerjakan dan dikendalikan oleh SDM yang berpengetahuan minim di
berita mengenai keracunan makanan. Mengacu pada data BPS, banyak usaha kecil
menengah pangan (IKM) yang ada di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2004
berjumlah 1.031.767 (80 persen dari industri yang ada di Indonesia).
UKM pangan yang tumbuh di masyarakat umumnya adalah sebagai
antisipasi masalah krisis ekonomi dan pada umumnya pula skala usaha, sarana
produksi dan manajemennya dirancang pada skala kecil dan tidak memenuhi
standar manajemen pangan yang ada. Strategi usaha demikian memang paling
tepat dan fleksibel untuk menghadapi situasi tak menentu (fluktuatif) sehingga
pola usaha dapat dijalankan dalam pola yang fleksibel tanpa harus menanggung
risiko keuangan yang besar. Selain itu, pada umumnya UKM pangan Indonesia
memanfaatkan bahan baku lokal dalam pelaksanaan produksinya. Oleh karena itu,
tidak diherankan bahwa pada saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia, UKM
pangan mampu bertahan (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh
Indonesia, 2006).
2.5. Tabel Input-Output
Tabel Input-Output (I-O) dan analisisnya pertama kali dikembangkan oleh
Professor Wassily Leontif pada akhir dekade 1930-an. Tabel I-O pada dasarnya
merupakan uraian statistik dalam bentuk matriks yang menyajikan informasi
tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar satuan kegiatan
ekonomi (sektor) dalam suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu. Isian
sepanjang baris dalam matriks menunjukkan bagaimana output suatu sektor
antara dan permintaan akhir, sedangkan isian dalam kolom menunjukkan
pemakaian input antara dan input primer oleh suatu sektor dalam proses
produksinya.
Namun demikian, tabel I-O tidak mampu memberikan informasi tentang
persediaan dan arus barang dan jasa secara rinci menurut komoditi. Semua
infromasi yang dimuat dalam suatu tabel input-output terbatas pada infomasi
untuk sektor ekonomi, yang merupakan gabungan dari berbagai kegiatan ekonomi
atau komoditi. Dengan kata lain, tabel I-O bukan merupakan model atau
perangkat yang mampu memberikan informasi secara rinci tentang berbagai stok
dan arus barang dan jasa yang terjadi pada suatu entitas ekonomi.
Akan tetapi, dengan menggunakan asumsi sederhana memang dapat
disusun dan dikembangkan suatu model ekonomi yang cukup andal. Kenyataan
terakhir inilah yang menjadikan tabel Input-Output diperhitungkan sebagai salah
satu bagian dari sistem neraca nasional yang dapat digunakan sebagai alat untuk
melakukan suatu analisis ekonomi secara komprehensif (BPS, 2008).
Sebagai suatu model kuantitatif, tabel I-O akan memberikan gambaran
menyeluruh mengenai:
1. Struktur perekonomian suatu wilayah yang mencakup struktur output dan
nilai tambah masing-masing sektor.
2. Struktur input antara, yaitu penggunaan berbagai barang dan jasa oleh
3. Struktur penyediaan barang dan jasa baik berupa produksi dalam negeri
maupun barang-barang yang berasal dari impor atau yang berasal dari luar
wilayah tersebut.
4. Struktur permintaan barang dan jasa, baik permintaan antara oleh
sektor-sektor produksi maupun permintaan akhir untuk konsumsi, investasi dan
ekspor.
Mengacu pada konsep dasar yang dikembangkan oleh Leontif menurut
Richardson, Miernyk dan Isard dalam Budiharsono (2001) adalah :
1. Struktur perekonomian tersusun dari berbagai sektor industri yang satu sama
lain berinteraksi melalui jual beli.
2. Output suatu sektor dijual kepada sektor-sektor lainnya dan untuk memenuhi
permintaan akhir.
3. Input suatu sektor dibeli dari sektor-sektor lainnya, dan rumah tangga
(dalam bentuk jasa tenaga kerja), pemerintah (misalnya pembayaran pajak
tidak langsung, penyusutan), surplus usaha serta impor.
4. Hubungan input dengan output bersyarat linier.
5. Dalam suatu kurun waktu analisis (biasanya 1 tahun) total input sama
dengan total output.
6. Suatu sektor terdiri dari satu atau beberapa perusahaan dan output tersebut
diproduksikan oleh satu teknologi.
Dalam suatu model input-output yang bersifat terbuka dan statis,
transaksi-transaksi yang digunakan dalam penyusunan tabel I-O harus memenuhi tiga
1. Asumsi homogenitas yang mensyaratkan bahwa tiap sektor memproduksi
suatu output tunggal dengan struktur input tunggal dan bahwa tidak ada
substitusi otomatis antar berbagai sektor;
2. Asumsi proporsionalitas yang mensyaratkan bahwa dalam proses produksi,
hubungan antara input dengan output merupakan fungsi linear yaitu tiap
jenis input yang diserap oleh sektor tertentu naik atau turun sebanding
dengan kenaikan atau penurunan output sektor tersebut;
3. Asumsi additivitas, yaitu suatu asumsi yang menyebutkan bahwa efek total
dari pelaksanaan produksi di berbagai sektor dihasilkan oleh masing-masing
sektor secara terpisah. Ini berarti bahwa di luar sistem input-output semua
pengaruh dari luar diabaikan.
Keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan model I-O dalam
perencanaan pengembangan wilayah yaitu:
1. Model I-O dapat memberikan deskripsi yang detail mengenai perekonomian
nasional ataupun perekonomian regional dengan mengkuantifikasikan
ketergantungan antar sektor dan asal (sumber) dari ekspor dan impor.
2. Untuk suatu set permintaan akhir dapat ditentukan besarnya output dari
setiap sektor, dan kebutuhannya akan faktor produksi dan sumber daya.
3. Dampak perubahan permintaan terhadap perekonomian baik yang
disebabkan oleh swasta maupun pemerintah dapat ditelusuri dan diramalkan
secara terperinci.
4. Perubahan-perubahan teknologi dan harga relatif dapat diintegrasikan ke
Sedangkan kelemahan model I-O anatara lain : (a) asumsi-asumsi yang
sedikit retriktif, (b) biaya pengumpulan data yang besar dan (c)
hambatan-hambatan dalam mengembangkan model dinamik.
Hambatan terbesar yang dihadapi oleh lembaga-lembaga perencanaan,
terutama di daerah, dalam menggunakan analisis I-O antara lain adalah: (1) biaya
yang relatif besar dalam pengumpulan data; (2) data pokok yang belum memadai,
dan (3) keterbatasan kemampuan teknis. Akan tetapi, bila kendala-kendala
tersebut dapat diatasi maka model I-O ini merupakan model yang canggih untuk
merencanakan pembangunan ekonomi suatu wilayah secara terintegrasi.
Walaupun model Input-Output mengandung berbagai kelemahan-kelemahan
seperti yang telah diuraikan namun model Input-Output masih tetap merupakan
alat analisis yang handal dan bermanfaat, terutama karena kemampuannya untuk
digunakan dalam analisis ekonomi yang lengkap dan komprehensif (Budiharsono,
2001).
2.5.1. Konsep dan Definisi
Untuk lebih mempermudah pemahaman dalam membaca tabel I-O, berikut
ini diuraikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan pengertian-pengertian
pokok yang sering digunakan (BPS, 2008).
a. Output
Output adalah nilai dari seluruh produk yang dihasilkan oleh sektor-sektor
produksi dengan memanfaatkan faktor produksi yang tersedia di suatu wilayah
(negara, propinsi dan sebagainya) dalam suatu periode waktu tertentu (umumnya
b. Input Antara
Input antara adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk barang dan jasa
yang digunakan habis dalam proses produksi. Komponen input antara terdiri dari
barang tidak tahan lama dan jasa yang dapat berupa hasil produksi dalam negeri
atau impor. Barang tidak tahan lama adalah barang yang habis dalam sekali pakai
atau barang yang umur pemakaiannya kurang dari setahun. Contoh dari input
antara adalah bahan baku, bahan penolong, jasa perbankan dan sebagainya.
c. Input Primer
Input primer adalah input atau biaya yang timbul sebagai akibat dari
pemakaian faktor produksi dalam suatu kegiatan ekonomi. Faktor produksi antara
lain terdiri dari tenaga kerja, tanah, modal dan kewiraswastaan. Wujud dari input
primer adalah upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan barang modal dan pajak
tak langsung neto. Input primer disebut juga sebagai balas jasa faktor produksi
atau nilai tambah bruto. Nilai input primer dari suatu sektor akan sama dengan
output dikurangi input antara pada sektor tersebut.
d. Permintaan Antara
Permintaan antara merupakan permintaan barang dan jasa untuk memenuhi
proses produksi. Dengan kata lain, permintaan antara menunjukkan jumlah
penawaran output dari suatu sektor ke sektor lain yang digunakan dalam proses
produksi.
e. Permintaan Akhir dan Impor
Permintaan akhir adalah permintaan atas barang dan jasa yang digunakan
mencakup barang dan jasa yang digunakan untuk kegiatan produksi. Permintaan
akhir terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi
pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor.
(i) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari pembelian barang dan jasa
yang dilakukan oleh rumah tangga dan badan-badan yang tidak mencari untung
dikurangi nilai netto penjualan barang bekas dan barang sisa. Akan tetapi,
pembelian rumah baru oleh rumah tangga dimasukkan sebagai pembentukan
modal tetap sektor usaha persewaan bangunan dan tanah (real estate). (ii) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran pemerintah, baik
pusat maupun daerah, untuk konsumsi kecuali yang sifatnya pembentukan modal,
termasuk pengeluaran untuk kepentingan angkatan bersenjata.
(iii) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
Pembentukan modal tetap bruto mencakup semua pengeluaran untuk
pengadaan barang modal baik dilakukan oleh pemerintah maupun
perusahaan-perusahaan swasta. Barang modal dapat terdiri dari bangunan/konstruksi, mesin
dan peralatan, kendaraan dan angkutan serta barang modal lainnya.
(iv) Perubahan Stok
Perubahan stok sebenarnya juga merupakan pembentukan modal (tidak
tetap) yang diperoleh dari selisih antara stok akhir dan stok awal periode
yang belum sempat dijual dan oleh konsumen sebagai bahan-bahan (inventory) yang belum sempat digunakan.
(v) Ekspor dan Impor
Ekspor dan impor merupakan kegiatan atau transaksi barang dan jasa antara
penduduk di suatu daerah dengan penduduk di luar daerah tersebut, baik
penduduk kota lain maupun luar negeri. Transaksi tersebut terdiri dari ekspor dan
impor untuk barang, jasa pengangkutan, komunikasi, asuransi dan berbagai jasa
lainnya.
2.5.2. Kerangka Dasar Tabel Input-Output
Tabel Input-Output disajikan dalam bentuk matriks, yaitu sistem penyajian
data yang menggunakan dua dimensi : baris dan kolom. Isian sepanjang baris
tabel Input-Output menunjukkan pengalokasian atau pendistribusian dari output
yang dihasilkan oleh suatu sektor dalam memenuhi permintaan antara oleh sektor
lainnya dan permintaan akhir. Sedangkan isian sepanjang kolom menunjukkan
struktur input yang digunakan oleh masing-masing sektor dalam kegiatan
produksinya.
Sesuai dengan sifat dan jenis transaksinya, secara umum matriks yang
disajikan dalam tabel input-output dapat dikelompokkan menjadi 4 sub matriks
Tabel 2.1. Kerangka Penyajian Tabel Input-Output
Kuadran I (n x n)
Kuadran II (n x m) Kuadran III
(p x n)
Kuadran IV (p x m) Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta (2008)
Keterangan : Simbol-simbol di dalam tanda kurung menunjukkan ukuran (ordo) matriks pada kuadran yang bersangkutan. Simbol pertama adalah banyaknya baris dan simbol kedua adalah banyaknya kolom.
Kuadaran pertama menunjukkan arus barang dan jasa yang dihasilkan dan
digunakan oleh sektor-sektor dalam suatu perekonomian. Kuadran ini
menunjukkan distribusi penggunaan barang dan jasa untuk suatu proses produksi.
Penggunaan atau konsumsi barang dan jasa di sini adalah penggunaan untuk
proses kembali, b