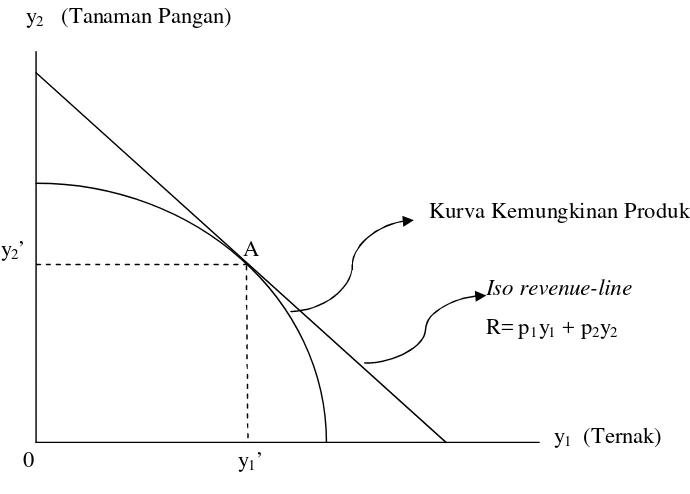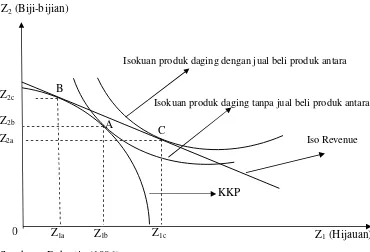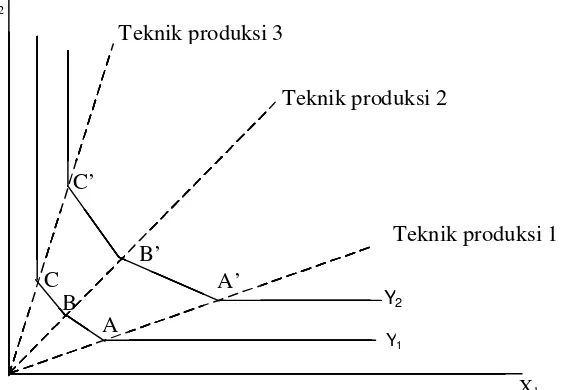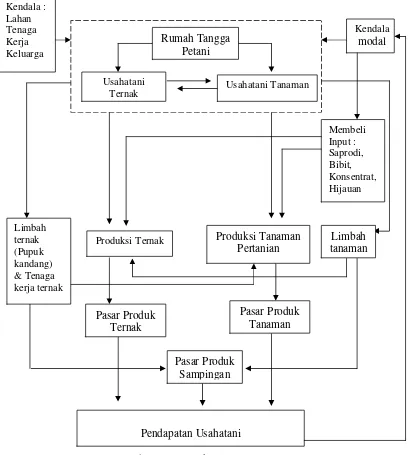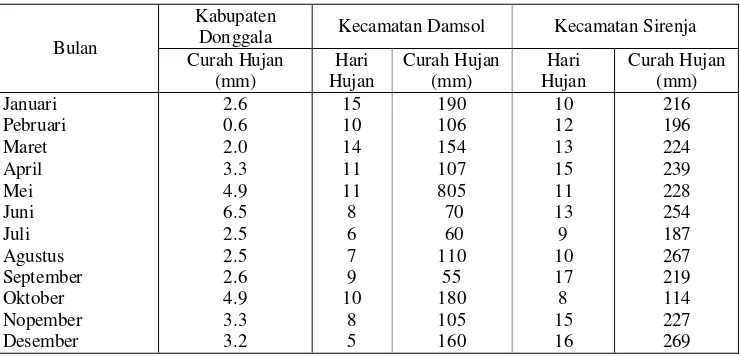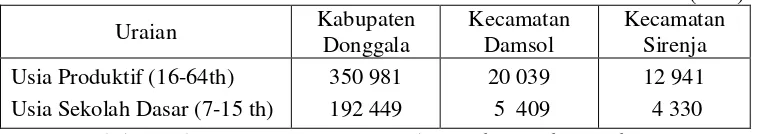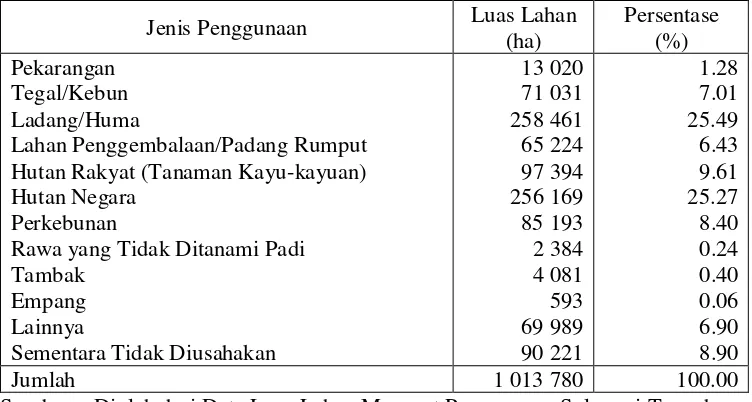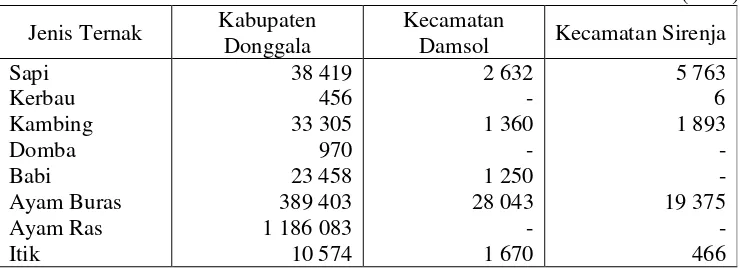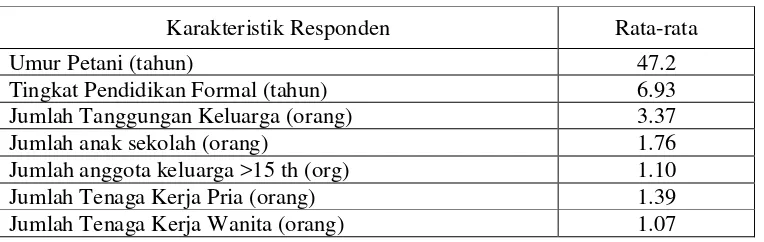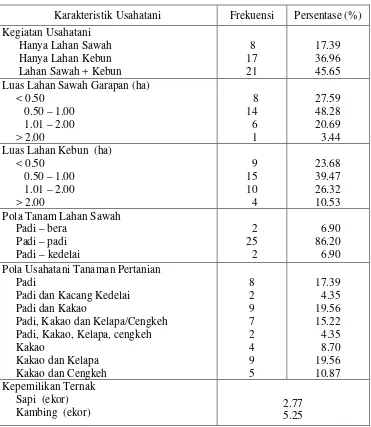MODEL INTEGRASI TANAMAN-TERNAK DI
KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH:
PENDEKATAN OPTIMASI PROGRAM LINIER
SAYEKTI HANDAYANI
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SURAT PERNYATAAN
Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam tesis
saya yang berjudul:
MODEL INTEGRASI TANAMAN-TERNAK
DI KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH:
PENDEKATAN OPTIMASI PROGRAM LINIER
merupakan gagasan atau hasil penelitian tesis saya sendiri dengan bimbingan
komisi pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan rujukannya. Tesis ini
belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di
perguruan tinggi manapun. Semua data dan informasi yang digunakan telah
dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.
Bogor, September 2009
ABSTRACT
SAYEKTI HANDAYANI. Integrated Crop Livestock Models in Kabupaten
Donggala, Central Sulawesi Province: Optimization Analysis Linear
Programming (NUNUNG KUSNADI as a Chairman and SRI HARTOYO as a
Member of the Advisory Committee).
Basic concept of integrated crop livestock system is synergism existence
of farm which the livestock can utilize compost heap. On the other hand, the
farming land can also utilize organic fertilizer produced by the livestock itself.
The government has already implemented the integrated program in the farmer
level. However, the farmers’ desire for not applying the technology of integrated
crop livestock system after the government program ended being the problem.
The objectives of this research are (1) to analyze possibility of integrated crop
livestock system in accordance with economic value and farmers’ resource
availability and (2) to analyze influencing factors towards farmer decision on the
integrated crop livestock system. The method analysis was used a linear
programming method The research result shows that the farmer decision for
deciding the integrated crop livestock system is determined by availability of
intermediate product market. Besides, the farmer decision mainly used to integrate
cacao with livestock, decided by level of cacao productivity. Economically, the
integrated crop livestock system which is possible to develop that is the model
with greenery composition originated from grass during six months rainy season
as well as it derived from fermented straw during six months dry season. The
analyzed results towards farm income, both integrated and non-integrated model
indicates that the obtained income through the integrated crop livestock system is
higher 20.94 % than the same pattern of farming enterprises with non-integrated
model.
RINGKASAN
SAYEKTI HANDAYANI. Model Integrasi Tanaman-Ternak di Kabupaten
Donggala Provinsi Sulawesi Tengah: Pendekatan Optimasi Program Linier
(NUNUNG KUSNADI sebagai Ketua dan SRI HARTOYO sebagai Anggota
Komisi Pembimbing).
Konsep dasar dari sistem integrasi tanaman-ternak adalah adanya
sinergisme dari usahatani yang diintegrasikan. Sistem integrasi mampu mengatasi
permasalahan penurunan kesuburan lahan pertanian sekaligus mengatasi kurangnya
ketersediaan pakan bagi ternak ruminansia,
dimana ternak mampu memanfaatkan
limbah tanaman dan lahan pertanian dapat memanfaatkan pupuk organik yang
dihasilkan ternak. Pemerintah selama ini telah melaksanakan program integrasi ini
di tingkat petani. Namun yang menjadi permasalahan adalah mengapa petani tidak
mau melaksanakan teknologi integrasi ini setelah jangka waktu program
implementasi oleh pemerintah berakhir?
Penelitian ini bertujuan untuk: membangun model integrasi
tanaman-ternak berdasarkan pilihan usaha dan ketersediaan sumberdaya di tingkat petani,
menganalisis kemungkinan penerapan sistem integrasi tanaman-ternak dilihat dari
nilai ekonomi dan ketersediaan sumberdaya petani dan menganalisis faktor-faktor
yang mempengaruhi keputusan petani pada sistem integrasi tanaman-ternak.
Model integrasi yang dibanguan adalah model padi-ternak dengan pilihan
pakan hijauan bersumber dari rumput selama 6 bulan musim hujan dan jerami
fermentasi selama 6 bulan musim kering (model pakan 1) dan sumber hijauan
berasal dari 50 persen rumput + 50 persen jerami fermentasi (model pakan 2).
Sedangkan untuk model kakao-ternak, hijauan berasal dari 70 persen rumput dan
30 persen kulit buah kakao (model 1) dan 50 persen rumput serta 50 persen kulit
buah kakao (model 2). Data dianalisis menggunakan program linier dengan
metode simpleks dan dianalisis secara primal, dual dan sensitivitas.
Keputusan petani untuk memilih integrasi tanaman-ternak ditentukan oleh
tersedianya pasar produk antara, baik produk tanaman maupun kompos. Tanpa
didukung oleh pasar produk antara, maka pendapatan yang dapat diterima dari
model integrasi lebih rendah dari model tanpa integrasi. Selain itu keputusan
petani untuk mengintegrasikan kakao dengan ternak ditentukan pula oleh tingkat
produksi kakao. Produksi yang rendah di bawah 50 persen dari produksi normal
akan memberikan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan model
tanpa integrasi. Secara ekonomi, maka model integrasi yang dapat dikembangkan
adalah model integrasi padi-ternak dengan pilihan komposisi pakan hijauan pada
6 bula musim hujan bersumber dari rumput dan 6 bulan musim kering bersumber
dari jerami fermentasi. Sedangkan untuk model kakao-ternak, maka model
integrasi dengan komposisi hijauan 70 persen rumput dan 30 persen kulit buah
kakao. Hasil analisis terhadap pendapatan usahatani baik secara integrasi maupun
tanpa integrasi menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh melaui integrasi
padi-ternak lebih tinggi 20.94 persen dari pola usahatani tanpa integrasi.
Hak Cipta milik IPB, tahun 2009
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1.
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa
mencantumkan atau menyebutkan sumbernya
a.
Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,
penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
MODEL INTEGRASI TANAMAN-TERNAK DI
KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH:
PENDEKATAN OPTIMASI PROGRAM LINIER
SAYEKTI HANDAYANI
Tesis
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains
pada
Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Penguji Luar Komisi:
Dr.Ir.Anna Fariyanti, MS
Judul Tesis
:
Model Integrasi Tanaman-Ternak di Kabupaten Donggala
Provinsi Sulawesi Tengah: Pendekatan Optimasi Program
Linier
Nama Mahasiswa : Sayekti Handayani
Nomor Pokok
:
H351060051
Program Studi
:
Ilmu Ekonomi Pertanian
Menyetujui,
1. Komisi Pembimbing
Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS Dr. Ir. Sri Hartoyo, MS
Ketua Anggota
Mengetahui,
2. Ketua Program Studi 3. Dekan Sekolah Pascasarjana IPB
Ilmu Ekonomi Pertanian
Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, MA Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan
begitu banyak karunia, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu
menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul ”Model Integrasi Tanaman-Ternak
di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah: Pendekatan Optimasi Program
Linier”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW.
Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Komisi Pembimbing,
Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS dan Dr. Ir. Sri Hartoyo MS yang telah meluangkan
waktunya untuk mengarahkan dan memberikan saran serta pemikiran kepada
penulis sejak penyusunan proposal hingga penulisan tesis ini diselesaikan.
Kepada penguji luar komisi Dr. Ir. Anna Fariyanti, MS dan penguji yang
mewakili Program Studi Dr. Moh. Firdaus, SP MSi, yang telah memberi kritik,
saran dan pemikiran untuk perbaikan tesis ini pada saat ujian berlangsung. Ucapan
terimakasih penulis sampaikan pula kepada:
1. Rektor Universitas Tadulako dan Dekan Fakultas Pertanian Universitas
Tadulako yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk
melanjutkan pendidikan Program Pascasarjana.
2. Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi
Pertanian dan seluruh staf pengajar yang telah memberikan bimbingan dan
proses pembelajaran selama penulis kuliah di Program Studi Ilmu Ekonomi
Pertanian.
Deasi Mayawati, Andi Thamrin, I Gusti Ayu. P Mahendri, Piter Sinaga, dan
I Wayan Sukanata) atas persahabatan, kebersamaan dan kekompakan selama
masa perkuliahan hingga berakhirnya masa studi di EPN. Ibu Aida Taridala,
Dr. Ir. Yundi Hafizrianda, terimakasih atas sumbangan ilmu dan pemikirannya
serta untuk diskusi yang efektif.
4. Seluruh Staf Program Studi EPN (Mba Rubi, Mba Yani, Aam, Bu Kokom dan
Kang Husen) yang telah membantu dalam melayani proses administrasi
selama perkuliahan maupun sampai akhir penulis menyelesaikan studi, serta
pihak-pihak lain yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
5. Saudara-saudaraku terkasih (Kakanda Sri Hani,S.Sos, Ir.Wijayanti.MSi, Betty
Antow, Reyko Pontoh,SH, Ir. Syahrir,MP, dan Ir. Idris Mokoginta) atas doa
dan dukungan yang tiada putusnya diberikan kepada penulis.
Secara khusus dengan segenap rasa cinta dan hormat, penulis
mengucapkan terimakasih yang tulus kepada Ibunda Siti Fatimah dan Ayahanda
Soenarto, BA serta Bapak dan Ibu Mertua Antow Waraba (Alm.) yang dengan
sabar dan tulus memberikan dukungan moril serta doa untuk keberhasilan penulis.
Kepada suami tercinta, Sonny Antow dan anakku tersayang Cantya Puspa Samita,
atas cinta kasih, kesabaran dan pengertian yang tak terhingga, sehingga penulis
dapat menyelesaikan studi ini.
Akhirnya tesis ini dipersembahkan kepada pembaca sebagai pengetahuan
dan sumber informasi yang diharapkan berguna bagi semua pihak yang
membutuhkan.
Bogor,
September
2009
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Purworejo, pada tanggal 22 Agustus 1970 sebagai
anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Soenarto dan Siti Fatimah.
Penulis menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 1983 di SDN 15 Palu,
pendidikan menengah pertama pada tahun 1986 di SMPN 1 Palu dan pendidikan
menengah atas pada tahun 1989 di SMAN 1 Palu. Tahun 1989 penulis diterima
sebagai mahasiswa pada Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas
Tadulako Palu, dan meraih gelar sarjana pada tahun 1994.
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR TABEL ... xiv
DAFTAR GAMBAR...
xvi
DAFTAR LAMPIRAN...
xvii
I. PENDAHULUAN ...
1
1.1. Latar Belakang...
1
1.2. Perumusan Masalah ...
4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ...
8
1.4. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian ...
8
II. TINJAUAN PUSTAKA ... 10
2.1. Usahatani Terpadu ...
10
2.2. Konsep Integrasi Tanaman - Ternak...
13
2.2.1. Integrasi Padi - Ternak ... 15
2.2.2. Integrasi Kelapa Sawit - Ternak ... 17
2.2.3. Integrasi Kakao - Ternak ... 18
2.2.4. Integrasi Jagung - Ternak ... 19
2.3. Penelitian Optimalisasi... 20
III. KERANGKA PEMIKIRAN ... 26
3.1. Konsep Hubungan Antara Dua Produk... 26
3.2. Model Produk Antara... 30
3.3. Konsep Pemecahan Masalah dengan Program Linier ... 33
3.4. Kerangka Konseptual... 37
IV. METODE PENELITIAN ... 39
4.1. Penentuan Waktu dan Lokasi Penelitian ... 39
4.2. Metode Pengambilan Sampel ... 40
4.4. Analisis Data ... 41
4.4.1. Analisis Pola Usahatani Optimal ... 42
4.4.1.1. Penentuan Aktivitas dalam Fungsi Tujuan ... 42
4.4.1.2. Pengukuran Kendala ... 45
4.4.2. Analisis Sensitivitas ... 51
4.4.3. Konsep dan Pengukuran Variabel... 52
V. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN
KARAKTERISTIK RESPONDEN ... 54
5.1. Lokasi dan Topografi ... 54
5.2. Keadaan Iklim ... 54
5.3. Kependudukan ... 55
5.4. Keadaan Pertanian ... 56
5.5. Keadaan Peternakan ... 58
5.6. Karakteristik Responden ... 59
5.7. Karakteristik Usahatani ... 60
VI. ANALISIS KERAGAAN USAHATANI TANAMAN DAN
TERNAK DI DAERAH PENELITIAN ... 64
6.1. Penguasaan Sumberdaya ... 64
6.1.1. Penggunaan Lahan dan Pola Tanam ... 64
6.1.2. Ketersediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja ... 67
6.1.3. Penggunaan dan Ketersediaan Modal Usahatani ... 71
6.2. Pendapatan Usahatani Petani Contoh ... 72
6.3. Input – Output Usahatani Pendukung Model Integrasi
Tanaman-Ternak ...
74
6.3.1. Input – Output Usahatani Padi ... 75
6.3.2. Input – Output Usahatani Kakao ... 80
6.3.3. Input - Output Usahatani Ternak ... 82
VII. PEMECAHAN OPTIMAL MODEL INTEGRASI TANAMAN–
TERNAK ... 84
7.1. Pola Usahatani ... 84
7.2.1. Sumberdaya Lahan ... 87
7.2.2. Sumberdaya Tenaga Kerja ... 88
7.2.3. Modal Usahatani ... 91
7.3. Nilai Ekonomi dan Pendapatan Model Integrasi Tanaman-Ternak 93
7.3.1. Nilai Ekonomi Model Integrasi Padi-Ternak ... 93
7.3.2. Nilai Ekonomi Model Integrasi Kakao-Ternak ... 96
7.3.3. Analisis Pendapatan Usahatani Model Integrasi
Tanaman-Ternak ...
97
7.4. Analisis Sensitivitas ... 99
7.4.1. Pengaruh Perubahan Harga terhadap Model Integrasi ... 100
7.5. Skenario Perubahan Produksi Kakao pada Model Integrasi
Kakao-Ternak...
104
VIII. KESIMPULAN DAN SARAN ... 107
8.1. Kesimpulan ...
107
8.2. Saran ... 108
DAFTAR PUSTAKA ...
109
DAFTAR TABEL
Nomor
Halaman
1.
Curah Hujan per Bulan di Kabupaten Donggala dan Kecamatan
Contoh Tahun 2006 ... 55
2.
Komposisi Penduduk di Kabupaten Donggala dan Kecamatan
Contoh Berdasarkan Kelompok Usia Produktif Tahun 2006 ... 56
3.
Luas Lahan Sawah di Kabupaten Donggala Berdasarkan Frekuensi
Penanaman Padi dalam Setahun dan Tanaman Non Padi untuk
Masing-Masing Jenis Irigasi ... 57
4.
Luas Lahan Kering Menurut Jenis Penggunaan di Kabupaten
Donggala ...
57
5.
Populasi Ternak di Kabupaten Donggala, Kecamatan Damsol dan
Kecamatan Sirenja ... 58
6.
Karakteristik Responden di Kabupaten Donggala ... 60
7.
Karakteristik Usahatani Responden ... 62
8.
Luas Lahan yang Dikuasai Petani Contoh Berdasarkan Jenis Lahan .. 65
9.
Pola Usahatani dan Pola Tanam yang Diterapkan Petani pada Setiap
Jenis Lahan Berdasarkan Waktu dalam Setahun ... 66
10.
Curahan Kerja pada Masing-Masing Cabang Usahatani Berdasarkan
Bulan dalam Setahun ... 68
11.
Pendapatan Petani Contoh dari Usahatani Tanaman pada Lahan
Sawah dan Lahan Kebun ... 73
12.
Pendapatan Petani Contoh dari Usahatani Ternak dalam Setahun ... 74
13.
Kandungan Bahan Kering Beberapa Bahan Baku Pakan Asal
Limbah Pertanian ... 75
14.
Input, Hasil Utama dan Hasil Ikutan Usahatani Padi Berdasarkan
Pola Tanam per Hektar Lahan ... 77
15.
Input, Hasil Utama dan Hasil Ikutan Usahatani Kakao... 79
16.
Input, Hasil Utama dan Hasil Ikutan Usahatani Ternak Sapi dan
17.
Pola Usahatani Hasil Pemecahan Optimal untuk Masing-Masing
Model Integrasi Tanaman-Ternak dan Tanpa Integrasi ... 84
18.
Penggunaan Lahan Berdasarkan Jenis Lahan pada Setiap Model
Integrasi Tanaman-Ternak dan Model Tanpa Integrasi ... 87
19.
Penggunaan Tenaga Kerja Keluarga dan Tenaga Kerja Luar
Keluarga Berdasarkan Model Integrasi Tanaman-Ternak... 89
20.
Penggunaan Modal Milik Petani Berdasarkan Jenis Modal pada
Model Integrasi Tanaman-Ternak dan Model Tanpa Integrasi ... 92
21.
Penggunaan Kredit Usahatani Berdasarkan Jenis Kredit pada Model
Integrasi Tanaman Ternak ... 93
22.
Pendapatan Berdasarkan Model Integrasi Tanaman-Ternak dan
Tanpa Integrasi ... 98
23.
Selang Kepekaan Perubahan Fungsi Tujuan pada Model Integrasi
Padi-Ternak ... 101
24.
Pendapatan dengan Skenario Tanpa Pasar Produk Antara pada
Model Integrasi Tanaman-Ternak dan Tanpa Integrasi ... 102
25.
Selang Kepekaan Kendala Sumberdaya Rumput pada Model
Integrasi Padi-Ternak dan Kakao-Ternak ... 103
26.
Pola Usahatani pada Integrasi Kakao-Ternak Kondisi Optimal Saat
Ini dan Skenario Perubahan Produksi Kakao ... 104
27.
Pendapatan Model Integrasi Kakao-Ternak Kondisi Optimal Saat Ini
DAFTAR GAMBAR
Nomor Halaman
1. Penentuan Kombinasi Optimum Dua Produk ... 28
2. Penentuan Kombinasi Optimum Produk Antara ... 31
3. Isokuan dari Program Linier ... 34
4. Kerangka Konseptual Penelitian ... 38
5. Bagan Alur Hasil Solusi Optimal Model Integrasi Padi-Ternak ... 94
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Halaman
1. Matrik Model Tanpa Integrasi ... 115
2. Matrik Model Integrasi Padi-Ternak ... 118
3. Matrik Model Integrasi Kakao-Ternak... 121
4. Hasil Solusi Optimal Tanpa Integrasi... 124
5. Hasil Solusi Optimal Integrasi Padi-Ternak ... 133
6. Hasil Solusi Optimal Integrasi Kakao-Ternak ... 146
I. PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Upaya peningkatan produksi tanaman pangan khususnya pada lahan sawah
melalui perluasan areal menghadapi tantangan besar pada masa akan datang.
Pertambahan jumlah penduduk yang menurut data Departemen Pertanian (2007)
sudah mencapai sekitar 224 juta jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata 1.15
persen per tahun, serta adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman,
industri, jalan dan penggunaan lainnya, menjadi alasan semakin sulitnya
memperluas areal usahatani lahan sawah. Peningkatan produksi selama ini pada
akhirnya lebih banyak dilakukan pada lahan subur beririgasi melalui peningkatan
mutu intensifikasi, diantaranya dengan menggalakkan penggunaan pupuk
anorganik. Konsumsi pupuk anorganik selama 15 tahun terakhir dilaporkan
meningkat dengan peningkatan 16 persen per tahun, yang sebagian besar
terdistribusi di sektor tanaman pangan, yaitu 72 persen pada padi sawah dan 13
persen palawija (Syam dan Sariubang, 2004).
dengan komponen utama adalah pengelolaan bahan organik. Pemanfaatan kotoran
sapi dan kambing sebagai pupuk organik memiliki peluang yang besar dalam
memperbaiki kesuburan lahan, mengingat petani pada umumnya selain
mengusahakan tanaman pertanian juga memelihara ternak sapi maupun kambing
sebagai salah satu cabang usahataninya.
Manajemen pemeliharaan usahatani ternak tersebut umumnya masih
dilakukan secara konvensional. Kendala utama yang dihadapi petani yang belum
memadukan usaha ini dengan tanaman pertanian adalah tidak tersedianya pakan
secara memadai terutama pada musim kemarau. Terlebih untuk daerah dengan
kondisi iklim yang cenderung kering, dimana musim kemarau juga berlangsung
lebih panjang. Disamping itu penanaman hijauan untuk pakan juga jarang
dilakukan petani karena keterbatasan lahan yang dimiliki.
Kesulitan pakan terutama pada musim kemarau dapat diatasi dengan
memanfaatkan limbah atau hasil samping tanaman pertanian, baik tanaman
pangan seperti jerami padi, jerami jagung, limbah kacang-kacangan maupun
limbah tanaman perkebunan seperti kulit buah kakao serta limbah sawit, yang
jumlahnya cukup melimpah pada saat panen. Setiap hektar lahan sawah
diperkirakan menghasilkan 4 ton jerami, yang setelah melewati proses fermentasi
diperkirakan dapat menyediakan pakan sapi sebanyak 2 ekor per tahun (Ditjen
Peternakan Departemen Pertanian, 2008).
domba), dimana konsep dasar dari sistem integrasi ini adalah adanya sinergisme
dari usahatani yang diintegrasikan. Ternak dan tanaman dalam hal ini mampu
memanfaatkan produk ikutan dari masing-masing komoditi (Ditjen Peternakan
Departemen Pertanian, 2008).
Sistem integrasi merupakan penerapan usahatani terpadu melalui
pendekatan
low external input
antara komoditas tanaman pertanian dengan ternak.
Melalui sistem integrasi ini efisiensi penggunaan input produksi dapat tercapai,
demikian pula risiko kegagalan dalam berusaha dapat diminimalisir. Beberapa
keuntungan penerapan sistem integrasi tanaman ternak adalah: (1) diversifikasi
penggunaan sumberdaya produksi, (2) menekan risiko usaha
mono-commodity,
(3) efisiensi tenaga kerja, (4) efisiensi penggunaan komponen produksi, (5)
mengurangi ketergantungan sumber energi kimia dan biologi serta sumberdaya
lainnya, (6) ekologi lebih lestari dan tidak menimbulkan polusi lingkungan, (7)
peningkatan hasil, dan (8) perkembangan rumahtangga yang lebih stabil
(Devendra, 1993).
dapat dilaksanakan integrasi ternak ruminansia dan tanaman pertanian (pangan
dan perkebunan), terutama dalam penyediaan bahan pakan ternak.
Peluang dilaksanakannya usahatani tanaman dan ternak secara terintegrasi
di Kabupaten Donggala cukup besar, mengingat daerah ini memiliki populasi
ternak sapi terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu 42 275 ekor dengan
rata-rata peningkatan populasi sebesar 0.1 persen per tahun, serta populasi ternak
kambing sebanyak 35 387 ekor, dengan rata-rata peningkatan populasi 8.13
persen per tahun (Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Sulawesi Tengah,
2007). Kondisi ini didukung dengan tersedianya lahan sawah seluas 33 112
hektar dan lahan perkebunan seluas 85 193 hektar (BPS Provinsi Sulawesi
Tengah, 2006). Komoditas tanaman perkebunan yang paling banyak diusahakan
adalah kakao, dengan luas areal 47 925.35 hektar, tanaman kelapa 25 426 hektar
kemudian tanaman perkebunan lain seperti kopi, cengkeh, lada dan vanili (BPS
Kabupaten Donggala, 2007).
Ketersediaan sumberdaya yang ada di daerah ini, memungkinkan untuk
mengusahakan tanaman dengan ternak secara terintegrasi. Namun yang menjadi
pertanyaan apakah dengan ketersediaan sumberdaya di tingkat petani sistem
integrasi ini juga dapat dilaksanakan? Untuk itu diperlukan suatu analisis
mengenai aspek ekonomi dari usahatani yang terintegrasi antara tanaman dan
ternak, yang berkaitan erat dengan keputusan petani dalam menentukan cabang
usahatani serta dalam mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya.
1.2. Perumusan Masalah
integrasi tanaman ternak yang dikembangkan petani di Jawa Tengah dan Jawa
Timur mampu mengurangi penggunaan pupuk anorganik 25-35 persen dan
meningkatkan produktivitas padi 20-29 persen. Hasil serupa juga dilaporkan Bulu
et al
. (2004) di Provinsi NTB bahwa model integrasi tanaman ternak yang
diterapkan petani mampu meningkatkan pendapatan sekitar 8.4 persen
dibandingkan jika tidak menerapkan model integrasi tanaman-ternak.
Sistem integrasi tanaman-ternak sudah pernah dilaksanakan di Provinsi
Sulawesi Tengah, yang merupakan program dari Departemen Pertanian. Sistem
integrasi padi-sapi telah dilaksanakan di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun
2000, sedangkan integrasi kakao-kambing telah dilaksanakan di Kabupaten
Donggala pada tahun 2004. Kegiatan pengkajian ini berlangsung dalam jangka
panjang, yaitu selama empat tahun. Berdasarkan laporan kegiatan tahun 2006,
dapat dinyatakan bahwa kegiatan pengkajian ini telah memberikan hasil
sebagaimana yang diharapkan. Pemberian pakan yang berasal dari fermentasi
kulit buah kakao dan hijauan unggul meningkatkan pertambahan bobot badan
harian ternak kambing dari 42.7 gram per ekor menjadi 73.3 gram per ekor.
Teknologi pengelolaan tanaman kakao dengan pengendalian hama dan penyakit,
pemupukan dan perbaikan pasca panen dapat meningkatkan produksi kakao dari
703 kg/ha/tahun menjadi 1 301.2 kg/ha/tahun.
kompos, yang dikembalikan ke lahan sawah maupun lahan kakao. Permasalahan
yang bersifat teknis maupun non teknis muncul dalam pelaksanaan program
integrasi tanaman ternak.
Penyediaan probiotik sebagai fermentor untuk membantu proses
pembuatan kulit buah kakao fermentasi, jerami fermentasi dan pupuk organik
yang terbatas, menjadi permasalahan teknis yang utama. Rendahnya produksi
kakao akibat terserang hama Penggerek Buah Kakao (PBK) menjadi alasan lain
mengapa petani tidak lagi melaksanakan usahatani kakao dan kambing secara
terintegrasi. Insentif yang diterima petani dari sistem usahatani ini tidak lagi
mampu menutupi biaya usahataninya, terutama untuk pengadaan probiotik.
Keberlanjutan penerapan sistem integrasi tanaman ternak secara swadaya
di tingkat petani memang masih perlu dipertanyakan. Mengapa petani tidak mau
memilih teknologi integrasi untuk diterapkan dalam sistem usahataninya perlu
untuk dicarikan jawabannya, jika sistem integrasi ini masih akan terus dijadikan
program untuk memperbaiki kondisi lahan pertanian serta mengatasi masalah
kesulitan pakan.
mengalokasikan tenaga kerjanya secara efisien. Keterbatasan lahan yang dikuasai
oleh petani menuntut petani untuk dapat lebih mendayagunakannya pada cabang
usahatani yang sesuai dengan kondisi lahan dengan jumlah ataupun luas
pengusahaan yang tepat, karena jika tidak hanya akan meningkatkan biaya
usahatani.
Selain faktor internal, faktor eksternal seperti ketersediaan pasar baik
untuk hasil usahatani maupun pasar limbah atau produk sampingan menjadi faktor
penentu keberhasilan sistem integrasi untuk diterapkan di tingkat petani.
Tambahan pendapatan yang dapat diperoleh dari hasil penjualan produk
sampingan menjadi daya tarik secara ekonomi. Namun jika pasar untuk limbah
tanaman maupun ternak ini tidak tersedia, maka insentif bagi petani dari sistem
integrasi menjadi lebih sedikit.
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah
dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini secara umum
adalah mengapa petani tidak mau melaksanakan sistem integrasi tanaman-ternak
sebagai sistem usahatani yang dijalankannya? Secara spesifik, permasalahan
dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :
1.
Apakah sumberdaya yang dimiliki petani memungkinkan untuk
dilaksanakannya usahatani tanaman dan ternak secara terintegrasi ?
2.
Bagaimana model integrasi yang dapat dibangun berdasarkan pilihan usaha
dan ketersediaan sumberdaya di tingkat petani?
4.
Jika terjadi perubahan faktor internal maupun eksternal dari usahatani
tanaman dan ternak yang terintegrasi, maka bagaimana pengaruhnya
terhadap alokasi sumberdaya dan tingkat pendapatan petani?
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1.
Membangun model integrasi tanaman-ternak berdasarkan pilihan usaha dan
ketersediaan sumberdaya di tingkat petani.
2.
Menganalisis kemungkinan penerapan sistem integrasi tanaman-ternak dilihat
dari nilai ekonomi dan ketersediaan sumberdaya petani.
3.
Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi tanaman-ternak.
Penelitian ini bermanfaat bagi para petani dalam memutuskan untuk
melakukan usahatani secara terintegrasi antara tanaman pangan maupun tanaman
perkebunan dengan ternak, sesuai dengan ketersediaan sumberdaya yang
dimilikinya. Bagi para penentu kebijakan dalam membentuk suatu program
pemerintah, respon terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi dapat
menjadi bahan masukan maupun rekomendasi bagi para penentu kebijakan dalam
merencanakan suatu program pengembangan sistem integrasi tanaman-ternak.
1.4. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian
per musim tanam, baik tanaman pangan maupun tanaman perkebunan, (2) jumlah
input untuk produksi ternak dan tanaman, (3) jumlah hasil usahatani ternak dan
tanaman, termasuk limbah dan pemanfataannya oleh ternak dan tanaman,
(4) alokasi waktu kerja bagi kegiatan usahatani, dan (5) pendapatan yang
diperoleh dari masing-masing komoditas.
Data dianalisis secara kuantitatif menggunakan
linear programming
dengan metode simpleks. Analisis data meliputi analisis primal, dual dan
sensitivitas. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan
usahatani dengan unit analisis rumahtangga petani.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Usahatani Terpadu
Salah satu upaya mengembangkan dan mempertahankan stabilitas
pendapatan petani adalah mengembangkan sistem usahatani terpadu (
farming
system
).
Farming system
adalah suatu konsep pengembangan pertanian yang
memandang usahatani sebagai suatu sistem. Dalam hal ini terdapat keterkaitan
antar cabang usahatani, baik dalam penggunaan input maupun dalam tingkat
output yang dihasilkan. Petani selalu dituntut untuk mampu memadukan berbagai
kombinasi cabang usahatani yang memberikan interaksi atau keterkaitan yang
saling mendukung.
Hardwoord (1979) menjelaskan bahwa
farming system
adalah paduan dari
proses biologis dan aktivitas pengelolaan sumberdaya untuk memproduksi
tanaman dan ternak. Menurut Shaner
et al.
(1982),
farming system
adalah suatu
yang unik dari pengaturan cabang usaha yang berimbang dari suatu usahatani.
Unik dalam arti kemampuan petani mengelola, mengendalikan dan memadukan
aspek agronomi dan aspek sosial ekonomi dengan memperhatikan aspek
lingkungan tertentu. Untuk memperoleh gambaran keberadaan
farming system
dalam lingkungan tertentu, maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan,
yaitu:
1.
Rumahtangga sebagai satu unit kesatuan. Rumahtangga merupakan elemen
kunci dalam riset
farming system
.
pembagian tanah, penggunaan tanah, hubungan antara pemilik dan penyewa,
kualitas tanah, ketersediaan air dan lokasi tanah, (2) tenaga kerja, yang
meliputi jumlah, umur, kelamin, anggota keluarga, tingkat produktivitas dan
kesehatan, pembagian waktu antara di luar dan di dalam usahatani, sifat dan
keinginan untuk bekerja sama dan saling membantu, (3) modal, mencakup
kekayaan baik berupa fisk maupun finasial seperti peralatan, pembangunan,
hasil yang dapat dijadikan uang tunai, ternak maupun kredit, dan (4)
pengelolaan, adalah keterampilan dalam mengorganisir dan memanfaatkan
tanah, tenaga kerja dan modal secara efisien.
3.
Cabang usaha dalam usahatani. Beberapa karakteristik yang perlu
diperhatikan dalam hubungan dengan cabang usaha antara lain: kebiasaan
bertani, interaksi antara cabang usaha satu dengan lainnya, kebutuhan biaya
dan tenaga kerja serta kebutuhan input produksi, pemanfaatan hasil produksi
dan pasaran hasil produksinya (Shaner
et al.,
1982).
Sistem usahatani ternak menururt Amir dan Knipcsheer (1989) adalah
khas dan merupakan suatu usaha yang layak sebagai perusahaan pertanian yang
dalam prakteknya dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik, biotik dan faktor sosial
ekonomi serta disesuaikan dengan tujuan rumahtangga petani, preferensi dan
sumberdaya atau faktor produksi yang dimiliki petani. Usaha peternakan rakyat
selalu dihadapkan pada berbagai keterbatasan sumberdaya antara lain lahan untuk
menyediakan pakan ternak, tenaga kerja dan modal. Pada usaha peternakan
tradisional umumnya input pakan tidak dibeli.
Usaha ternak ruminansia pada umumnya merupakan salah satu aktivitas
produksi atau cabang usaha yang terintegrasi dengan usahatani lainnya, terutama
usahatani tanaman pangan dan bersifat sebagai usaha yang saling terkait dan
mendukung atau sebagai usaha yang bersifat penunjang dan pelengkap dalam
sistem usahatani. Petani ternak tradisional lebih mementingkan nilai kegunaan
ternak bagi pemenuhan kebutuhan rumahtangganya (Sabrani, 1989). Hal ini
dilakukan petani atas dasar berbagai pertimbangan, antara lain sifat komplemen
antara cabang usahatani yang dijalankan serta harapan untuk meperoleh
pendapatan yang lebih besar. Selain itu diversifikasi usaha juga dilakukan sebagai
salah satu cara penanggulangan dalam menghadapi risiko kegagalan usaha seperti
kegagalan produksi.
proses pengambilan keputuasan. Tingkat perubahan akibat adanya adopsi
teknologi bervariasi secara lintas daerah karena terdapat perbedaan sumberdaya
pendukungnya (Schultz, 1984).
2.2. Konsep Integrasi Tanaman-Ternak
Ranaweera
et al.
(1993) menyatakan bahwa untuk memperkecil
kesenjangan (gap) antara pemenuhan kebutuhan hidup dan pertumbuhan
penduduk diperlukan suatu teknologi yang dapat menciptakan lingkungan stabil
dan dapat menopang meningkatnya kebutuhan manusia. Salah satu teknologi yang
dapat digunakan adalah dengan mengkombinasikan antara usahatani tanaman dan
usaha ternak atau dikenal dengan sistem integrasi tanaman-ternak.
Secara umum, konsep integrasi ternak dalam usahatani tanaman baik
tanaman perkebunan, pangan atau tanaman hortikultura adalah menempatkan dan
mengusahakan sejumlah ternak, dalam hal ini ternak ruminansia (sapi, kerbau,
kambing, domba) dan atau pseudoruminansia (kelinci, kuda), tanpa mengurangi
aktivitas dan produktivitas tanaman. Keberadaan ternak ini harus dapat
meningkatkan produktivitas tanaman sekaligus produktivitas ternaknya
(Direktorat Jendral Peternakan Deptan, 2008). Selanjutnya dikemukakan bahwa
komponen usahatani yang dipadukan harus saling bersinergis untuk mencapai
produksi yang optimal.
dengan usahatani lainnya juga merupakan suatu cara utama dalam intensifikasi
pertanian, walaupun peranan ternak disini masih merupakan komponen
pendukung dan pelengkap, bukan komponen utama dalam sistem integrasi-ternak.
Mengintegrasikan pemeliharaan ternak dengan kegiatan usahatani lainnya akan
memberikan efisiensi biaya yang cukup tinggi, sehingga dapat meningkatkan
penghasilan petani.
Seperti diketahui bahwa biaya operasional terbesar dari usaha ternak
adalah biaya pakan, yang meliputi 60-70 persen dari total biaya operasional.
Melalui sistem integrasi, biaya pakan dapat dikurangi dengan memanfaatkan
limbah tanaman serta hasil sampingan agroindustri, seperti jerami (padi dan
jagung), pucuk tebu, biji-bijian (kacang tanah dan
cowpea
), umbi-umbian (ketela
dan ubi jalar), bungkil biji minyak (kelapa sawit, kopra dan kapas), dedak dan
baggase. Hasil sampingan atau limbah dari ternak berupa kotoran juga sangat
bermanfaat bagi tanaman, yaitu untuk memperbaiki struktur tanah, mengurangi
daya serap air, mencegah
crusting
permukaan tanah (Makka, 2004).
Banyak model integrasi tanaman-ternak yang sudah dilakukan baik pada
tingkat usahatani yang selama ini sudah dilakukan, maupun berupa kajian dari
program-program pemerintah. Beberapa model integrasi tanaman-ternak
dipaparkan pada sub bab di bawah ini.
2.2.1. Integrasi Padi –Ternak
Daur ulang yang terjadi dalam sistem usahatani terpadu padi-ternak adalah
dari usaha budidaya tanaman menghasilkan jerami yang dapat dimanfaatkan
sebagai pakan serta dedak padi yang juga dapat dimanfaatkan sebagai konsentrat;
sedangkan dari usaha pemeliharaan ternak diperoleh limbah kandang berupa
kotoran ternak yang melalui proses sederhana akan dihasilkan pupuk organik yang
bermutu tinggi. Saling mengisi satu sama lain merupakan konsep LEISA (
Low
External Input Sustainable Agriculture
) yang dapat meminimalkan biaya produksi
(Reintjes
et al.,
1999)
Pemberian pupuk organik kotoran sapi dikombinasikan dengan pupuk
anorganik kepada tanaman padi di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan
memberikan produksi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan produksi padi
yang hanya memperoleh pemupukan organik. Produksi gabah kering panen untuk
perlakuan dengan pupuk anorganik dan kombinasi pupuk organik - anorganik
adalah sama, sebanyak 6.38 ton/hektar. Sementara padi dengan pemberian pupuk
organik saja memberikan produksi sebesar 3 ton/hektar (Syam dan Sariubang,
2001).
6.33-6.40 ton/hektar, sementara produksi padi yang hanya memperoleh pupuk
anorganik sebesar 6.20 ton perhektar. Penggunaan pupuk organik mampu
menghemat biaya pupuk sebesar Rp 342 000/hektar/musim tanam.
Pemanfaatan jerami fermentasi sebagai pakan ternak sapi yang dipelihara
pada lahan sawah irigasi di Sulawesi Tengah dengan komposisi 50 persen jerami
fermentasi (JF) dan 50 persen rumput alam (RA) mampu memberikan pendapatan
yang lebih tinggi yaitu Rp 7 600 per ekor/hari dengan RC rasio sebesar 2.19
dibandingkan dengan pemberian pakan dengan komposisi JF 45 persen dan RA
55 persen serta JF 40 persen dan RA 60 persen dengan pendapatan
masing-masing Rp 7 025/ekor/hari dan Rp 6 775/ekor per hari. Kotoran ternak yang
dihasilkan pada pemeliharaan ini berkisar 3.2-3.8 kg/ekor/hari. Pemanfaatan
kotoran sapi sebagai pupuk organik dikombinasikan dengan pupuk anorganik
dengan perbandingan 50 : 50 persen memberikan produksi gabah kering panen
sebesar 6.9 ton/hektar dan produksi jerami sebanyak 12.16 ton/hektar. Komposisi
pupuk ini memberikan produksi yang lebih tinggi dibandingkan komposisi pupuk
organik : anorganik 40 : 60 persen atau 30 : 70 persen.
Penggunaan jerami padi sebagai pakan dasar telah dicobakan pada ternak
domba di laboratorium Universitas Gajah Mada Yogyakarta untuk mengetahui
biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu kilogram bobot badan (
feed cost
per gain atau F/C
). Komposisi jerami padi 30 persen dan konsentrat 70 persen
keuntungan sebesar Rp 3 800.96 per kg bobot hidup (Purbowati
et al.,
2004).
Penggunaan jerami padi selain sebagai pakan ternak, juga dapat dijadikan pupuk
organik, sebagaimana hasil penelitian Suriadikarta dan Adimiharja (2001).
Penggunaan jerami sebagai pupuk organik pada tanah sawah dapat meningkatkan
efisiensi pupuk N dan P, serta hasil padi mencapai 7 ton gabah kering
giling/hektar. Pada sawah bukaan baru, penggunaan jerami dan dolomit dapat
meningkatkan produksi padi dari 4.6 ton/hektar menjadi 6.1 ton/hektar.
2.2.2. Integrasi Kelapa Sawit – Ternak
Integrasi pemeliharaan ternak sapi pada perkebunan kelapa sawit
memberikan keuntungan baik pada usaha ternak maupun usaha kelapa sawit,
sebagaimana yang telah dilaksanakan pada PT.Agricinal Bengkulu yang dikenal
dengan SISKA (Sistem Integrasi Sapi-Sawit Model Agricinal). Pada sistem
integrasi ini, ternak sapi digunakan sebagai penarik gerobak untuk mengangkut
TBS (Tandan Buah Segar) dari lokasi pemanenan ke tempat penampungan
sementara. Satu ekor sapi dapat menarik gerobak dengan daya angkut sampai 400
kg pada lahan yang permukaannya datar. Dampak positif yang dirasakan oleh
pemanen dengan sistem ini adalah jumlah panenan meningkat sehingga
produktivitas pemanen meningkat, yang ditandai dengan peningkatan pendapatan
sebesar Rp 500-600 ribu per bulan.
(3) terbinanya calon usahawan di bidang peternakan (Manurung, 2005).
Selanjutnya dikemukakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hijauan yang
terbatas di areal perkebunan, digunakan cacahan pelepah sawit dan daun sebagai
pengganti pakan hijuan, sementara sebagai pakan tambahan digunakan hasil
samping pengolahan buah sawit yang dikenal dengan
non oil solid
atau biasa
disebut solid. Dari hasil pengolahan sawit PT.Agricinal diperoleh
solid paste
,
yang kandungan protein kasarnya lebih tinggi serta kadar serat kasarnya lebih
rendah dari solid biasa.
Pemanfaatan hasil samping tanaman dan pengolahan kelapa sawit berupa
pelepah, solid dan bungkil kelapa sawit dengan imbangan 1:1:1 sebagai bahan
dasar pakan sapi potong memberikan pertambahan bobot hidup harian yang
terbaik serta harga ransum yang termurah untuk menghasilkan setiap kilogram
pertambahan bobot hidup (Mathius
et al
., 2004). Sedangkan penelitian pada
ternak domba yang dilakukan Doloksaribu
et al.
(2004) pada perusahaan
pembibitan domba di Kabupaten Toba Sumatera Utara, dengan skala 1 031 ekor
induk dan 33 ekor pejantan, menunjukkan bahwa usaha pembibitan domba yang
terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit pada skala komersial layak untuk
dikembangkan, ditunjukkan dengan nilai
benefit cost ratio
sebesar 1.2.
2.2.3. Integrasi Ternak-Kakao
suplemen garam dapur (NaCl) dengan komposisi hijauan terdiri dari rumput alam,
daun gamal, daun lamtoro serta kulit buah kakao. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pemberian suplemen pakan lengkap dalam bentuk blok garam jilat
memberikan dampak positif terhadap produktivitas ternak kambing Peranakan
Etawah baik jantan maupun betina, serta memberikan tambahan pendapatan per
tahun sebesar 85.7 persen lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang diperoleh
pada pemeliharaan kambing dengan pemberian garam dapur.
Penelitian sistem integrasi kambing-kakao juga dilakukan Bulo
et al.
(2004) di daerah Sulawesi Tengah, dimana hasil terbaik diperoleh pada
pemeliharaan kambing dengan introduksi teknologi menggunakan kandang
panggung dengan pemberian pakan 80 persen daun gamal, 20 persen daun kakao,
mineral dan garam. Secara finansial perlakuan ini layak untuk diusahakan karena
memberi keuntungan terbesar dibandingkan perlakuan lain yaitu dengan nilai
Return Cost Ratio
sebesar 1.63. Sejalan dengan penelitian tersebut, Priyanto
et al.
(2004) menemukan bahwa integrasi kambing-kakao di Lampung juga dapat
meningkatkan pendapatan melalui efisiensi biaya pupuk sebesar 40 persen, serta
penghematan tenaga kerja dalam pengambilan rumput sebesar 50 persen, karena
rumput telah diganti dengan hijauan tanaman pelindung (legum) dan kulit buah
kakao. Kontribusi usaha ternak kambing mencapai 17.45 persen dari total
pendapatan petani.
2.2.4. Integrasi Ternak-Jagung
yaitu varietas jagung putih (lokal), varietas Sukmaraga, Lamuru dan Semar-10
pada lahan kering di Kalimantan Tengah, menunjukkan bahwa varietas jagung
yang paling adaptif adalah semar-10 dengan dosis pemupukan urea 100 kg, SP36
100 kg dan kompos 1 500 kg, yang memberikan hasil 6.83 ton/hekar jagung
pipilan kering dengan RC rasio sebesar 2.6. Sementara rata-rata pertambahan
bobot badan ternak sapi yang diberikan pakan rumput dan jerami jagung dalam
kisaran normal.
Pemanfaatan limbah daun dan batang jagung, limbah ubi kayu berupa
ampas ubi kayu dan limbah padi berupa dedak sebagai pakan pokok sapi telah
banyak dilakukan oleh petani di daerah Deli Serdang Sumatera Utara. Hasil
penelitian Wasito
et al.
(2004) menunjukkan bahwa penggemukan sapi Brahman
atau Simental dengan pakan jerami jagung dan konsentrat ampas ubi kayu, dedak
halus, bungkil kelapa dan garam dapur selama tujuh bulan memberikan
keuntungan paling tinggi dengan nilai BC rasio di atas 1.3. Tingkat konsumsi
jerami jagung yang tertinggi adalah untuk varietas Pioner 12, yaitu sampai dengan
90 persen karena batangnya yang lunak dan rapuh, sehingga sisa pakan cenderung
sedikit.
2.3. Penelitian Optimalisasi
juta rupiah per tahun. Pendapatan ini diperoleh melalui aktivitas usaha tanaman,
memelihara sapi perah, menjual dan membeli hijauan pakan serta menjual dan
membeli pupuk kandang. Adapun kendala yang dihadapi petani adalah kendala
luas lahan, tenaga kerja dan modal.
Untuk mencapai pendapatan 2 juta rupiah pertahun, maka alternatif
kegiatan usahatani yang dilakukan adalah meningkatkan produktivitas dimana
dalam jangka panjang adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja,
produktivitas lahan dan meningkatkan produktivitas ternak. Sedangkan dalam
jangka pendek adalah menambah jumlah ternak. Alternatif lain adalah
meningkatkan harga produksi susu. Aktivitas produksi tanaman dilakukan dengan
alternatif luas lahan nol hektar, lebih kecil atau sama dengan 0.5 hektar dan lebih
kecil atau sama dengan 1 hektar. Dengan adanya kenaikan produksi susu, maka
solusi optimal untuk memperoleh pendapatan 2 juta pertahun, direkomendasikan
untuk mengusahakan ternak sapi perah 21.87 ekor untuk petani yang tidak
mengusahakan lahan pertanian. Sedangkan untuk petani yang mengusahakan
lahan pertanian 0.5 -1 hektar masing-masing direkomendasikan aktivitas produksi
ternak sapi perah sebanyak 14.74 ekor dan 8.19 ekor, dengan pola tanam rumput
monokultur.
mampu berkompetisi dalam hal pemanfaatan tenaga kerja petani dan modal usaha
secara lebih efisien dan menguntungkan.
Ilham dan Saktyanu (1998) menganalisis sistem usahatani terpadu dalam
menunjang pembangunan pertanian berkelanjutan dengan menggunakan model
linier, yang bertujuan untuk menganalisis perencanaan usahatani terpadu di
Kabupaten Magetan Jawa Timur, berkaitan dengan ketersediaan sumberdaya
lahan, tenaga kerja dan modal sesuai dengan kondisi biofisik dalam upaya
melaksanakan usahatani yang berkelanjutan.
Nenepath (2001) dalam penelitian diversivikasi ternak sapi potong dengan
menggunakan
linear programming
menunjukkan bahwa pada kondisi optimal,
usaha ternak sapi yang dikombinasikan dengan berbagai macam tanaman akan
memberikan tambahan pendapatan dengan jumlah ternak yang berbeda di dua
kecamatan penelitian, karena dipengaruhi luas lahan yang berbeda.
Hasil pemecahan solusi optimal memberikan peningkatan pendapatan dari
aktivitas usahatani aktual antara 11,81 persen pada petani dengan kepemilikan
lahan 0.05 – 0.09 hektar dan 52.77 persen pada petani dengan luas pengusahaan
lahan 0.50-1.99 hektar, dengan pendapatan asal ternak yang dominan.
Nefri (2000) melakukan penelitian pada peternakan sapi potong skala
industri. Untuk produksi pakan sapi berupa konsentrat digunakan program linier
yang meminimumkan biaya dengan keterbatasan sumberdaya yang tersedia.
Sedangkan untuk aktivitas produksi daging digunakan program tujuan ganda
goal
programming
untuk menyelesaikan permasalahan dengan banyak sasaran, yang
tidak dapat diselesaikan dengan
linear programming.
Untuk pengambilan
keputusan produksi dan pemasaran sapi potong maka kendala tujuan atau sasaran
yang ditetapkan adalah sasaran keuntungan, sasaran pemenuhan permintaan dan
sasaran pemenuhan kapasitas produksi. Sedangkan kendala fungsional yang
dihadapi adalah ketersediaan hijauan, ketersediaan konsentrat, kapasitas
penawaran daging beku, penjualan daging segar dan penjualan daging beku.
Hasil analisis tujuan ganda yang menempatkan sasaran keuntungan
sebagai prioritas pertama dan sasaran pemenuhan target penawaran serta target
produksi sebagai prioritas kedua dan ketiga memberikan solusi optimal berupa
produksi daging segar sebesar 5 399.372 kg dan produksi daging beku sebesar
180 kg yang didistribusikan ke masing-masing wilayah pemasaran.
sebesar 585.372 kg yang didistribusikan ke wilayah Bandung. Penelitian Howara
(2004) yang bertujuan menentukan pola usahatani padi-sapi yang optimal dengan
program linier di Kabupaten Majalengka dengan kendala lahan, benih, pupuk,
pakan sapi, tenaga kerja serta modal kerja, memberikan hasil bahwa pola tanam
yang memberikan hasil optimal adalah pada musim tanama I adan II menanam
padi, musim tanam III menanam padi, jagung dan kedelai. Selain pola tersebut
aktivitas memelihara ternak serta meminjam kredit pada musim tanam I dan II
merupakan solusi optimal yang dapat memberikan pendapatan maksimal.
Hasil analisis terhadap sumberdaya menunjukkan bahwa sumberdaya yang
terbatas atau langka adalah sumberdaya lahan pada musim tanam III, pupuk TSP
pada musim tanam I dan III, pupuk ZA pada musim tanam II dan III serta modal
pada musim tanam I dan II. Sehingga penambahan satu-satuan sumberdaya
tersebut akan menambah pendapatan sebesar nilai dualnya.
Penelitian yang mengkaji pengembangan ternak sapi potong dalam sistem
rumahtangga petani dengan menggunakan model
linear programming
(LP)
,
untuk
menentukan alokasi optimal penggunaan sumberdaya yang dimiliki petani serta
mengkaji pemanfaatan teknologi pakan, bibit unggul dan kebijakan kredit serta
harga output di empat tipologi wilayah di daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan
oleh Widiati (2003). Fungsi tujuan model LP adalah memaksimumkan pendapatan
rumahtangga petani berupa
cash flow
selama tiga tahun.
yang dihadapi adalah luas lahan garapan, jumlah ternak sapi, jumlah tenaga kerja
keluarga, jumlah tenaga kerja ternak, jumlah pupuk kandang yang dapat
dihasilkan, jumlah hijauan pakan yang dapat dihasilkan pada setiap pola tanam,
pemenuhan konsumsi keluarga dan kendala modal.
III. KERANGKA PEMIKIRAN
Aktivitas usahatani sangat terkait dengan kegiatan produksi yang
dilakukan petani, yaitu kegiatan memanfaatkan sejumlah faktor produksi yang
dimiliki petani dengan jumlah yang terbatas. Produksi merupakan suatu kegiatan
yang merubah input menjadi output. Kegiatan ini dalam ekonomi biasa disebut
fungsi produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan teknis yang merubah
input (sumberdaya) menjadi output (Debertin, 1986; Beattie and Taylor, 1985).
Produksi maksimal dapat dicapai jika petani melakukan aktivitas produksi
secara efisien, yaitu dengan sumberdaya yang terbatas dapat dihasilkan produksi
maksimal atau dengan jumlah sumberdaya yang minimal diperoleh produksi
dengan jumlah tertentu, sehingga konsep produksi sangat terkait dengan efisiensi.
Dalam kaitannya dengan konsep efisiensi teknis, suatu tingkat penggunaan faktor
produksi dikatakan lebih efisien dari tingkat pemakaian yang lain apabila dapat
memberikan rata-rata produksi (
Average Physical Product
) yang lebih besar
(Sugiarto
et al
., 2005). Pelaku ekonomi biasanya lebih memfokuskan perhatian
pada konsep efisiensi ekonomis dibandingkan efisiensi teknis. Dalam hal ini,
efisiensi ekonomis tercapai pada saat pemakaian input atau faktor produksi
memberikan keuntungan yang maksimum.
3.1. Konsep Hubungan Antara Dua Produk
mengusahakan tanaman pangan juga memelihara ternak. Sehingga dalam luasan
lahan tertentu, petani dihadapkan pada pilihan berapa luasan lahan yang sebaiknya
digunakan untuk menanam tanaman pangan serta berapa jumlah ternak yang dapat
dipelihara, sesuai dengan jumlah hijauan maupun limbah hasil pertanian yang
dapat disediakan dari luasan lahan tersebut.
Terbatasnya jumlah tenaga kerja keluarga, juga menuntut petani untuk
dapat mengalokasikan waktu kerja pada kegiatan tanaman dan memelihara ternak.
Dalam hal ini petani harus dapat menentukan berapa besar sebaiknya alokasi
waktu untuk masing-masing anggota keluarga yang dicurahkan pada setiap
kegiatan usahatani tersebut. Demikian pula untuk sumberdaya lainnya yang
digunakan sebagai input produksi.
Jika tujuan petani adalah memperoleh pendapatan maksimal dari hasil
tanaman serta memelihara ternak, maka petani dituntut untuk dapat
mengalokasikan masing-masing sumberdaya yang terbatas tersebut secara efisien.
Kondisi ini dapat digambarkan dengan Kurva Kemungkinan Produksi (KKP),
sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Kurva kemungkinan produksi ini
menunjukkan kombinasi dua produk yang dapat dihasilkan dari sejumlah input
tertentu, sesuai dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki petani.
Berdasarkan Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa usahatani tanaman dan
usahatani ternak dilakukan pada areal lahan yang sama sebagai input produksinya.
Dengan sejumlah input tertentu, jumlah ternak yang dapat dihasilkan ditunjukkan
sepanjang sumbu horisontal (y
1), dan jumlah tanaman yang dihasilkan adalah
sepanjang sumbu vertikal (y
2). Untuk menentukan berapa jumlah ternak dan
y
1’
0
maksimum, maka dapat digunakan garis
iso revenue.
Garis
iso revenue
ini
menunjukkan bahwa sepanjang garis tersebut memberikan jumlah penerimaan
yang sama, baik dari usaha tanaman maupun ternak. Kombinasi produksi ternak
dan produksi tanaman yang dapat memaksimumkan penerimaan adalah pada titik
A, dimana KKP bersinggungan dengan garis iso-r
evenue
. Jumlah ternak yang
diproduksi adalah sebanyak y
1’ dan jumlah tanaman yang diproduksi adalah y
2’.
y
2(Tanaman Pangan)
Kurva
Kemungkinan
Produksi
y
2’ A
Iso revenue-line
R=
p
1y
1+ p
2y
2 [image:46.612.149.494.254.501.2]Sumber : Diadopsi dari Debertin (1986)
Gambar 1. Penentuan Kombinasi Optimum Dua Produk
Sebagaimana dijelaskan oleh Debertin (1986), kondisi pada Gambar 1
dapat pula dituliskan secara matematis sebagai berikut :
Untuk menghasilkan produk y
1dan y
2dengan sejumlah input tertentu, maka
digunakan persamaan :
x
=
g(y
1,y
2)
………...…… (1)
dimana:
y
1= output ternak
y
2= output tanaman
g
= fungsi
transformasi
produk
Dijelaskan pula bahwa persamaan di atas bukan merupakan fungsi produksi,
demikian pula fungsi
g
tidak sama dengan fungsi produksi yang biasa dituliskan
dengan notasi
f.
Sedangkan persamaan penerimaan yang diperoleh dari usahatani tanaman
dan ternak adalah :
R= p
1y
1+ p
2y
2………..……….……… (2)
dimana:
R
=
penerimaan
p
1= harga output tanaman pangan
p
2= harga output ternak
y
=
jumlah
output
Sehingga untuk memaksimumkan penerimaan dengan sumberdaya tertentu yang
tersedia sebagaimana digambarkan dalam kurva kemungkinan produksi, melalui
persamaan lagrangian adalah :
L
=
p
1y
1+ p
2y
2+
θ
[ x - g(y
1,y
2)]
……… (3)
maka maksimisasi penerimaan dapat diperoleh dari turunan pertama yang sama
dengan nol, yaitu :
0
1 1 1=
−
=
y
g
p
Y
L
δ
δ
θ
δ
δ
………...………..……….. (4)
0
2 2 2=
−
=
y
g
p
Y
L
δ
δ
θ
δ
δ
………..………..………...(5)
0
)
,
(
1 2=
−
=
x
g
y
y
L
δλ
δ
……… ………..………..(6)
Dari persamaan (4) dan (5) diperoleh :
2 2 1
1
/
/
g
y
p
y
g
p
δ
δ
δ
δ
θ
=
=
atau
2 1 1 2
p
p
y
y
=
δ
δ
Dengan kata lain penerimaan maksimum dapat diperoleh jika
rate of product
transformation
(RPT) sama dengan rasio harga.
Dalam teori ekonomi hubungan produk-produk bisa bersifat kompetitif,
komplementer, suplementer dan produk gabungan (Doll & Orazem, 1978). Untuk
itu petani sebagai manajer pertanian harus mencoba untuk mengkombinasikan
produk-produk yang diproduksi dari sumberdaya yang terbatas untuk mengambil
keuntungan yang maksimum dari adanya hubungan yang komplementer atau
suplementer di antara produk-produk tersebut (Soekartawi
et al.,
1985)
3.2. Model Produk Antara
Konsep model produk antara dapat digunakan untuk menjelaskan konsep
integrasi, dimana input untuk usahatani ternak berasal dari output yang dihasilkan
oleh usahatani tanaman. Berbeda dengan konsep usahatani terpadu sebagaimana
yang dijelaskan pada Gambar 1, maka konsep integrasi lebih lengkap lagi,
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2, dimana produk yang dihasilkan
pertanian digunakan sebagai input untuk produk pertanian lainnya yang disebut
sebagai
intermediate product
atau produk antara.
Sejumlah input yang digunakan misalnya pada lahan tertentu, dihasilkan
output berupa hijauan (Z
1) sekaligus juga menghasilkan biji-bijian atau
grain
(Z
2). Sebagai contoh lain pada lahan sawah juga ditanami rumput untuk pakan
ternak sapi. Hasil yang diperoleh pada lahan sawah ini adalah dedak ataupun
jerami padi yang dapat digunakan sebagai input bagi ternak sapi untuk
menghasilkan daging, bersama-sama dengan rumput yang juga dihasilkan dari
areal persawahan. Pada konsep integrasi, Z
2dapat digambarkan sebagai produk
Z
1(Hijauan)
ini juga digunakan untuk menghasilkan hijauan. Produk sampingan sebagai output
digunakan sebagai input bagi ternak untuk menghasilkan
final product
berupa
daging
[image:49.612.132.502.163.415.2]Sumber : Debertin (1986)
Gambar 2. Penentuan Kombinasi Optimum Produk Antara
Gambar 2 memperlihatkan bahwa kombinasi output yang dihasilkan antara
hijauan dan biji-bijian adalah sepanjang Kurva Kemungkinan Produksi (KKP).
Hijauan dan biji-bijian yang dihasilkan oleh input lahan merupakan produk antara
yang dapat digunakan sebagai input bagi sapi untuk menghasilkan produk berupa
daging (Parakkasi, 1995). Kombinasi input hijauan dan biji-bijian yang digunakan
untuk memproduksi daging ditunjukkan sepanjang kurva isokuan.
Jika produk antara yang dihasilkan oleh tanaman tersebut tidak
diperjualbelikan atau dengan kata lain tidak ada pasar bagi produk antara, maka
kombinasi hijauan dan biji-bijian yang akan memberikan produksi daging yang
Z
2(Biji-bijian)
0
Isokuan produk daging dengan jual beli produk antara
Isokuan produk daging tanpa jual beli produk antara
Iso Revenue
KKP
C
A
Z
1cZ
1bZ
1aZ
2bZ
2apaling optimum adalah pada titik A, dengan jumlah hijauan yang dihasilkan
adalah sebanyak Z
1bdan biji-bijian sebanyak Z
2a, karena pada saat ini kurva
kemungkinan produksi bersinggungan dengan kurva isokuan.
Solusi optimum terletak pada titik tangen RPT (
Rate of Product
Transformation
) dari kombinasi produk antara (hijauan dan biji-bijian) yang
dihasilkan dari sejumlah input tertentu yang sama dengan MRTS (
Marginal Rate
of Technical Substitution
) dari kombinasi hijauan dan biji-bijian untuk
memproduksi sejumlah produk tertentu (daging) sebagai
final product
. Secara
sederhana dapat dikatakan bahwa RPT untuk memproduksi biji-bijian dan hijauan
sama dengan MRTS biji-bijian dan hijauan untuk memproduksi daging.
Jika terdapat pasar untuk produk antara, maka kombinasi optimum yang
memberikan pendapatan maksimum adalah pada titik B. Jika harga produk antara
dipersoalkan karena ada pasar untuk kegiatan penjualan dan pembelian hijauan
(Z
1) dan biji-bijian (Z
2), maka terdapat pertimbangan harga yang ditunjukkan
dengan adanya garis
iso revenue
, yaitu garis yang menunjukkan tingkat
pendapatan yang sama dari kombinasi produksi hijauan dan biji-bijian. Nilai
kombinasi produk 0Z
1adan 0Z
2csama dengan nilai kombinasi produk 0Z
1cdan
0Z
2ayang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi output daging pada
tingkat isokuan optimum daging . Tetapi produk hijauan yang dihasilkan petani
(0Z
1a) tidak mencukupi kebutuhan untuk memproduksi daging pada tingkat
isokuan optimum dari daging yaitu sebesar 0Z
1c. Di sisi lain terdapat kelebihan
biji-bijian yang dihasilkan yaitu sebanyak Z
2aZ
2c, karena yang dibutuhkan untuk
memproduksi daging hanya sebesar 0Z
2a. Dengan demikian, pada tingkat harga
Z
1aZ
1c. Dengan adanya jual beli produk antara ini akan merangsang petani untuk
meningkatkan output dibanding bila petani hanya menggunakan produk sendiri.
3.3. Konsep Pemecahan Masalah dengan Program Linier
Pemecahan masalah maksimisasi dapat dilakukan dengan program non
linier maupun dengan program linier. Menurut Debertin (1986), masalah
maksimisasi dengan kendala menggunakan fungsi lagrang merupakan salah satu
contoh dari masalah program non linier
.
Pada kasus ini, salah satu dari fungsi
tujuan atau kendala bersifat non linier, atau dapat pula keduanya bersifat non
linier. Sedangkan pada program linier
,
untuk masalah maksimisasi atau
minimisasi baik fungsi tujuan maupun kendalanya merupakan fungsi linier.
Tujuan mengoptimalkan alokasi sumberdaya disamping maksimisasi
keuntungan atau minimisasi biaya, juga tercapainya penggunaan sumberdaya atau
faktor produksi secara optimal, yang berarti tercapainya penggunaan sumberdaya
secara efisien. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara fungsi
produksi dengan program linier
.
Menurut Debertin (1986), program linier
merupakan fungsi linier, tetapi mempunyai tipe yang sangat khusus. Fungsi
produksi yang mendasari model program linier biasa disebut
fixed-proportion
production function
. Pada model ini antar input tidak dapat saling mensubstitusi
satu sama lain dan bersifat
constant return to scale
, sedangkan pada fungsi
produksi linier input dapat saling mensubstitusi. Secara grafis, hubungan antar
input pada program linier dapat dijelaskan melalui kurva isokuan sebagaimana
ditampilkan Gambar 3.
Gambar 3 menunjukkan kurva isokuan, dimana kombinasi input X
1dan X
2B’
C’
A
C
C’
B’
A
C
C’
B
produksi 1, 2 dan 3
.Pada titik A, B, dan C, Y
1dapat diproduksi hanya dengan
menggunakan satu aktivitas produksi yaitu teknik produksi 1 dengan
menggunakan kombinasi input X
1dan X
2, dengan proporsi masing-masing input
yang tetap pada titik A. Demikian pula untuk titik B dan C. Pada garis AB,
seluruh input yang digunakan harus dapat memenuhi persyaratan untuk teknik
produksi 1 dan 2, yang dapat menghasilkan output Y
1. Demikian pula untuk garis
BC, kombinasi input X
1dan X
2dapat menghasilkan output Y
1dengan
menggunakan gabungan aktivitas produksi dengan teknik 2 dan teknik 3. Dengan
cara yang sama, produksi Y
2dapat dihasilkan dengan teknik produksi 1, 2 dan 3,
dengan kombinasi input X
1dan X
2yang tetap pada titik A’, B’ dan C’.
[image:52.612.183.466.367.562.2]Sumber : Henderson and Quandt (1980)
Gambar 3. Isokuan dari Program Linier
Solusi yang diberikan dari pemecahan masalah dengan program linier
yang memberikan berapa jumlah output sebaiknya diproduksi dengan sejumlah
input tertentu sehingga memberikan penerimaan maksimum sebagaimana
Teknik produksi 1
Teknik produksi 3
Teknik produksi 2
X
2X
1Teknik produksi 1
Teknik produksi 3
Teknik produksi 2
X
2X
1Teknik produksi 1
Teknik produksi 3
Teknik produksi 2
X
2X
1A’
Y
1Y
2B’
A
C
C’
Teknik produksi 1
Teknik produksi 3
Teknik produksi 2
X
2dikemukakan sebelumnya, disebut dengan analisis masalah
primal
. Penyelesaian
masalah program linier sekaligus juga akan memberikan jawaban atas masalah
dual
yaitu alokasi sumberdaya yang dapat meminimalkan biaya. Jika tujuan utama
atau masalah primalnya adalah memaksimumkan keuntungan, maka masalah
dualnya adalah meminimalkan biaya. Masalah primal dan dual dalam linear
programming ini diuraikan lebih jelas dalam Taha (2003); Heady dan Candler
(1960).
Asumsi yang harus dipenuhi agar program linier dapat berlaku adalah:
1. Aktivitas input (sumberdaya) bersifat aditif, artinya jumlah hasil yang
diperoleh dari dua atau lebih aktivitas sama dengan jumlah hasil yang
diperoleh dari masing-masing aktivitas dan jumlah suatu input yang
digunakan harus sama dengan jumlah input yang digunakan oleh tiap-tiap
aktivitas.
2. Fungsi tujuan bersifat linier, artinya tidak ada pengaruh skala operasi atau
produksi pada saat
constant return to scale
.
3. Besarnya suatu aktivititas yang diusahakan tidak boleh negatif.
4. Besarnya input dan aktivitas dapat dipecah-pecah dan kontinyu.
5. Banyaknya aktivitas dan pembatas terhingga.
6. Hubungan aktivitas dan input yang digunakan merupakan hubungan linier.
7. Koefisien input-output, harga-harga input dan output serta besarnya faktor
pembatas telah diketahui dan tertentu atau deterministik.
Model matematik secara lengkap adalah sebagai berikut:
Fungsi Tujuan:
Dengan pembatas:
a
11X
1+ a
12X
2+ ……….. + a
1nXn b
1a
21X
1+ a
22X
2+ ……….. + a
2nXn b
2a
31X
1+ a
32X
2+ ……….. + a
3nXn b
3.
.
.
.
.
.
a
m1X
1+ a
m2X
2+ ……….. + a
mnXn b
mdimana:
i =
1,2,3,
…,.m
j =
1,2,3,….,
n
Z
= Fungsi
tujuan
C
j= Koefisien fungsi tujuan
X
j= Variabel keputusan
a
ij= Koefisien fungsi kendala
b
i= Nilai kendala atau batas sumberdaya yang tersedia
Pada tahap optimal terdapat beberapa penafsiran dari proses pemecahan
masalah dengan program linier menurut Soekartawi (1992); Nasendi dan Anwar
(1985), yaitu:
1.
Aktivitas yang masuk dalam program optimal akan memiliki
reduced cost
atau
opportunity cost
sama dengan nol. Hal ini berarti memperluas
pengusahaan yang masuk dalam program optimal sebesar satu unit tidak akan
merubah nilai program optimal.
2.
Untuk aktivitas yang tidak masuk dalam program optimal akan memiliki
reduced cost
tidak sama dengan nol. Jika satu unit aktivitas ini dimasukkan
dalam program optimal akan menurunkan nilai fungsi tujuan sebesar
opportunity cost
nya.
4.
Faktor produksi yang tidak habis terpakai, harga bayangannya menjadi sama
dengan nol. Penambahan satu unit faktor produksi ini ke dalam program
optimal tidak akan merubah ni