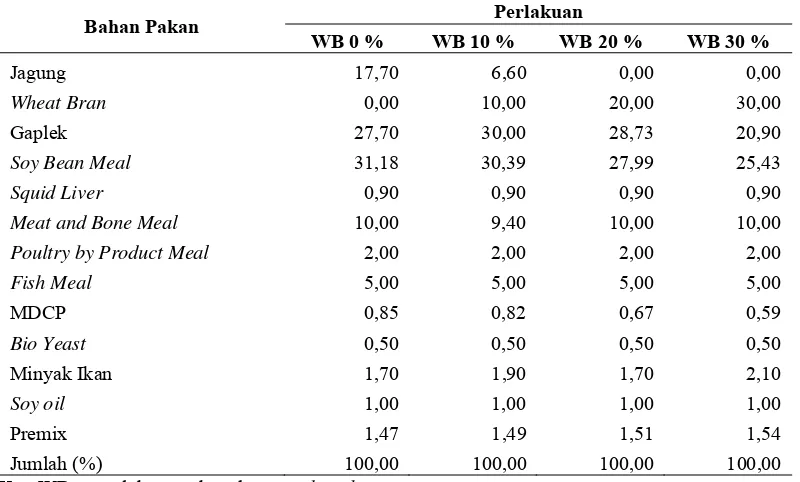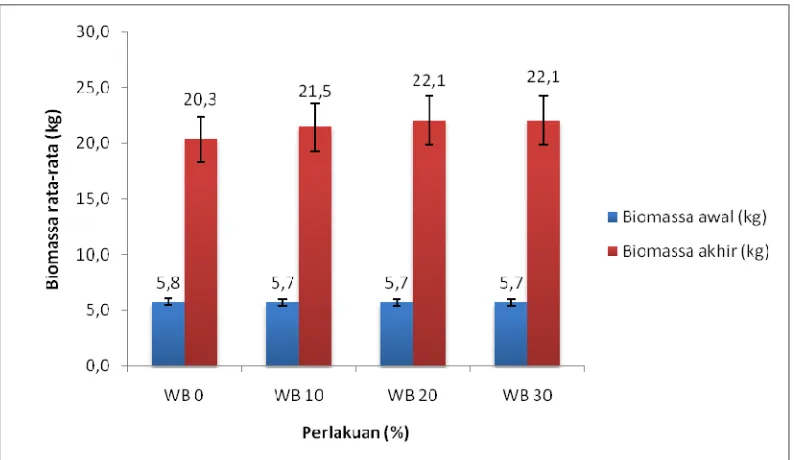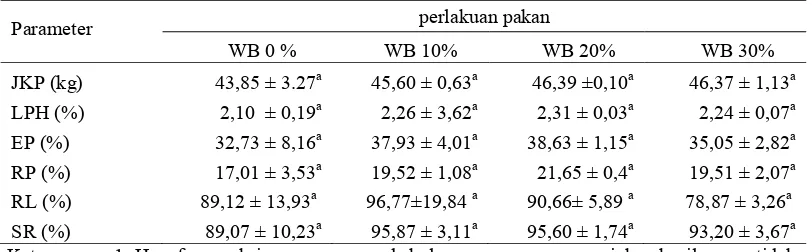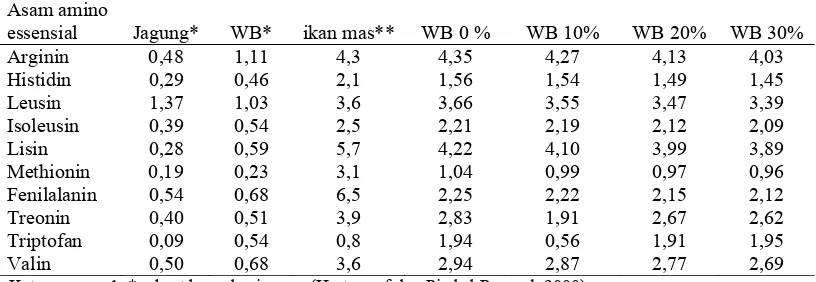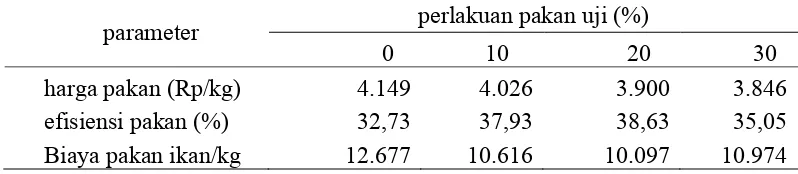PEMANFAATAN
WHEAT BRAN
DALAM PAKAN IKAN
MAS
Cyprinus carpio
FRIDA MARTA
PROGRAM STUDI ILMU AKUAKULTUR SEKOLAH PASCA SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER
INFORMASI
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis “Pemanfaatan wheat bran dalam pakan ikan mas Cyprinus carpio” adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.
Bogor, Maret 2012
ABSTRACT
FRIDA MARTA. Aquaculture Saince. Utilization of wheat bran in the diet of
common carp Cyprinus carpio. Under direction of DEDI JUSADI and NUR
BAMBANG PRIYO UTOMO.
Two experiments were conducted to evaluate the effect of wheat bran as a partial replacement of soybean meal and corn meal in the diet of common carp
Cyprinus carpio. In these experiments, four experimental diets contained 0%, 10%, 20%, or 30% wheat bran were used. In experiment I, a triplicate experiment was conducted using fish with an initial body weight of 23 ± 0,13 g. Fish were cultured in floating net cage with size of 2 x 2 x1 m3 at Cirata lake, with a density of 250 fish/cage. Fish fed on the diet at satiation for 60 days. In experiment II, the diets were subjected to indirect digestibility test by using 0,05% Cr2O3 as a tracer.
Two groups of fish with an initial body weight of 6 ± 0,12 g and 50 ± 0,18 g were held in aquaria 60 x 40 x 40 cm3 at density of 20 fish/aquaria. Feces were collected daily, 60 minutes after feeding, feces collection were done for 15 days. The results showed that utilization of wheat bran from 0 to 30% in the diet was not significantly affected the growth performance of fish, including protein retention, feed efficiency and daily growth rate. Those growth performance were in the range of 20,16 – 20,69%, 35,79 – 38,63%, and 93,44 – 98,03% respectively. Regardless of fish size, it was also found that protein digestibility of the diet was decreased when wheat bran was used in the diet at level of 20% or more. Based on the calculation of the price of diet to produce 1 kg of fish, it was found that the diet contain 20% of wheat bran had the most lowest production cost. It can be concluded that wheat bran can be used as a partial replacement of soy bean meal and fully replacement of corn meal for common carp up to 30%.
RINGKASAN
FRIDA MARTA. Pemanfaatan wheat bran dalam pakan ikan mas Cyprinus carpio. Dibimbing oleh DEDI JUSADI, NURBAMBANG PRIYO UTOMO.
Wheat Bran merupakan hasil samping dari industri pengolahan gandum menjadi tepung terigu. Selama ini penggunaan wheat bran terbatas hanya sebagai bahan pengisi untuk roti whole wheat dan pakan ternak ruminansia maupun kuda. Sementara penggunaannya dalam pakan ikan masih terbatas. Kandungan serat kasarnya yang relatif tinggi yaitu sekitar 11%, menyebabkan penggunaan wheat
bran dalam pakan ikan dibatasi. Seperti halnya hewan monogastrik lain,
kemampuan ikan dalam mencerna serat kasar dibatasi oleh kemampuan mikroflora dalam ususnya untuk mensekresikan selulosa. Meskipun serat kasarnya cukup tinggi, namun wheat bran memiliki beberapa kelebihan yaitu kandungan protein sekitar 15.7%, asam amino esensial yang lengkap serta mineral dan vitamin B1 yang tinggi, jika dibandingkan dengan jagung.
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya pada ikan nila, diketahui bahwa kecernaan wheat bran relatif tinggi, yaitu sebesar 75,20%. Hal ini coba dibuktikan pada ikan mas Cyprinus carpio dengan penggantian tepung jagung oleh wheat bran pada kadar 0%, 10%, 20% dan 30%.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan pemahaman
mengenai tingkat penggunaan wheat bran dalam pakan ikan mas serta
pengaruhnya terhadap kinerja pertumbuhan. Selanjutnya melakukan analisis daya cerna ikan mas terhadap pakan yang mengandung wheat bran tersebut, sehingga diharapkan proporsi jagung dan kedelai dalam pakan dapat dikurangi.
Penelitian ini terdiri dari 2 jenis pengujian, yaitu uji pertumbuhan dan uji kecernaan. Uji pertumbuhan dilaksanakan dari bulan Januari sampai Juni 2011. Hewan uji yang digunakan adalah ikan mas berukuran 23 ± 0,13 g berasal dari Subang. Pemeliharaan ikan dilakukan di dalam keramba jaring apung Cirata selama 60 hari menggunakan jaring berukuran 2 x 2 x 1 m3 berjumlah 12 buah dengan padat tebar 250 ekor tiap jaring. Pemberian pakan dilakukan secara at satiation dengan frekuensi 3 kali sehari, yaitu sekitar pukul 8 pagi, 12 siang dan 4 sore. Pakan yang digunakan terdiri dari 4 jenis, yaitu pakan dengan kandungan
wheat bran 0%, 10%, 20%, dan 30%. Perlakuan pakan disusun dengan menggunakan metode acak (random method).
Uji kecernaan dilakukan di Laboratorium percobaan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat selama ± 2 minggu. Ikan yang digunakan terdiri dari 2 kelompok ukuran, yaitu ikan mas ukuran kecil dengan bobot rata-rata 6 ± 0,12 g dan ikan mas dengan ukuran lebih besar dengan bobot rata-rata 50 ± 0,18 g. Masing-masing kelompok ikan disebar ke dalam 12 buah akuarium yang masing-masing berukuran 60 x 40 x 40 cm3 dan padat tebar 20 ekor / akuarium.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan wheat bran tidak
konsumsi pakan (43,85%; 45,60%; 46,39% dan 46,37%), laju pertumbuhan harian (2,22%; 2,29%; 2,33% dan 2,33%), efisiensi pakan (32,73%; 37,93%; 38,63% dan 35,05%), retensi protein (17,01%; 19,52%; 21,65% dan 19,51%), retensi lemak (89,12%; 96,77%; 90,66% dan 78,87%) serta kelangsungan hidup (89,07%; 95,87%; 95,60% dan 93,20%). Hal yang sama juga terjadi pada nilai kecernaan protein, yang memberikan hasil tidak berbeda nyata antar perlakuan baik pada ikan berukuran kecil maupun besar, sehingga dapat diketahui bahwa perbedaan ukuran ikan tidak menyebabkan perbedaan pada nilai kecernaan protein. Berbeda halnya dengan kecernaan total yang mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya kadar wheat bran dalam pakan. Nilai kecernaan total tertinggi diperoleh dari perlakuan wheat bran 0% dan 10%, baik pada ikan berukuran besar maupun ikan ukuran kecil. Sementara dari hasil analisis biaya diketahui bahwa
pakan dengan kandungan wheat bran 20% lebih ekonomis karena memberikan
biaya pakan terendah yaitu sebesar Rp. 10.097,-.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ikan mas mampu
menggunakan wheat bran sampai dengan 30% dalam pakan tanpa mempengaruhi
kinerja pertumbuhannya, tapi yang ekonomis 20%. Dalam hal ini kemampuan cerna ikan mas terhadap pakan yang mengandung wheat bran cukup tinggi, baik pada ikan mas berukuran kecil maupun besar dengan tingkat kecernaan protein pada kisaran 64,74 – 70,99% dan kecernaan total pada kisaran 41,78 – 57,66%.
© Hak Cipta milik IPB, tahun 2011
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB
PEMANFAATAN
WHEAT BRAN
DALAM PAKAN IKAN
MAS
Cyprinus carpio
FRIDA MARTA
Tesis
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada
Program Studi Ilmu Akuakultur
PROGRAM STUDI ILMU AKUAKULTUR SEKOLAH PASCA SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Judul Tesis : Pemanfaatan wheat bran dalam pakan ikan mas Cyprinus carpio
Nama : Frida Marta
NRP : C151080261
Disetujui
Komisi Pembimbing
Dr. Ir. Dedi Jusadi, M.Sc Dr. Ir. Nur Bambang Priyo Utomo, M.Si
Ketua Anggota
Diketahui
Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana
Ilmu Akuakultur
Prof. Dr. Ir. Enang Harris, MS Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc.Agr
PRAKATA
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat
dan karunia-Nya, sehingga tesis yang berjudul “Pemanfaatan wheat bran dalam
pakan ikan mas Cyprinus carpio” berhasil diselesaikan dengan sebaik-baiknya
melalui proses yang tidak mudah dan penuh perjuangan. Tesis ini disusun sebagai
salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Akuakultur
Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB).
Dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis hendak menyampaikan
banyak terima kasih kepada:
1. Komisi pembimbing Bapak Dr. Dedi Jusadi selaku dosen pembimbing
pertama dan Dr. Nur Bambang Priyo Utomo, selaku dosen pembimbing
kedua yang telah banyak memberikan arahan dan saran-sarannya selama
penyelesaian tesis ini.
2. PT. Suri Tani Pemuka yang telah memberikan izin dan fasilitas bagi saya
dalam melaksanakan penelitian ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan
bantuannya sehingga penelitian dan penulisan tesis ini dapat berjalan lancar.
3. Ungkapan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada seluruh keluarga
saya atas segala do’a, dorongan semangat dan kasih sayang yang tak terbatas,
terutama kedua orang tua saya, Papa Bpk. H. Suryadi Syuib, M. Hum, M.Pd.
dan mama Hj. Letmidoati, S.Pd. serta Suami tercinta Else Sandia Putra,
S.Farm, Apt. dan jagoan kecilku M. Fakhri Aljundi atas segala kasih dan
keikhlasannya.
Penulis sadar memiliki keterbatasan pemikiran, hingga memungkinkan
terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu kritik,
saran dan masukan dari semua pihak adalah hal yang paling berarti untuk
penyempurnaannya. Semoga tulisan ini bermanfaat.
Bogor, Maret 2012
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Payakumbuh, Sumatera Barat, pada tanggal 18 Maret
1983 sebagai anak kedua dari empat bersaudara, dari Ayah bernama Suryadi
Syuib dan ibu bernama Letmidoati. Tahun 2001 penulis lulus dari SMUN 1
Payakumbuh dan pada tahun yang sama diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB)
melalui jalur USMI. Penulis memilih program studi Teknologi dan Manajemen
Akuakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor di
Bogor. Pada tahun 2005 penulis menyelesaikan studi sarjana di IPB dan pada
tahun 2008 melanjutkan pendidikan di Sekolah Pascasarjana, Program Studi Ilmu
Akuakultur, Institut Pertanian Bogor (IPB).
Untuk menyelesaikan studi di sekolah pascasarjana, penulis melakukan
DAFTAR TABEL
Halaman
1 Komposisi pakan uji (%)... 11
2 Komposisi proksimat (% bobot kering) dan energi pakan uji... 11
3 Jumlah konsumsi pakan (JKP), laju pertumbuhan harian (LPH), efisiensi pakan (EP),retensi protein (RP), retensi lemak (RL) dan kelangsungan hidup (SR) ... 18
4 Komposisi asam amino pakan percobaan ... 21
5 Kecernaan protein dan Kecernaan total pakan uji ... 21
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
1 Prosedur analisis proksimat bahan pakan dan tubuh ikan uji ... 31
2 Prosedur analisis ... 35
3 Bobot biomasa awal dan akhir, kelangsungan hidup, konsumsi pakan, pertumbuhan relatif, dan efisiensi pakan pada juvenil ikan
kerapu tikus yang diberi pakan uji selama 60 hari masa pemeliharaan ... 36
4 Perhitungan retensi protein ... 37
5 Perhitungan retensi lemak ... 38
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Industri akuakultur saat ini masih dihadapkan pada permasalahan bahan
baku pakan, baik dari segi harga maupun ketersediaan atau kontinuitas dari bahan
pakan tersebut. Berdasarkan data yang ditulis oleh Hertanto (2011), diketahui
bahwa Indonesia sampai tahun 2011 ini masih mengimpor kedelai dan jagung,
karena produksi dalam negeri tidak mampu mencukupi jumlah permintaan yang
tinggi. Setiap tahun Indonesia masih mengimpor sekitar 1,4 sampai 1,6 juta ton
kedelai. Sedangkan kebutuhan nasional bisa mencapai 2,2 juta ton per tahun dan
Indonesia hanya produksi 600 sampai 800 ribu ton per tahunnya.
Tepung kedelai merupakan bahan baku nabati yang umum digunakan,
karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu kandungan protein yang tinggi
sebesar 43,20%, lemak 2% dan serat kasar 6.50% dengan kandungan asam amino
yang lengkap terutama methionin 1.38% dan lysin 6.28% serta kandungan energi
yang tinggi sebesar 4.518 kcal (Maina et al. 2002) dalam pakan. Namun, harganya
yang relatif mahal menyebabkan penggunaan kedelai mulai dibatasi dalam
komposisi pakan.
Sedangkan jagung dikenal sebagai produk nabati yang memiliki kandungan
energi tinggi 4.110 kcal, kandungan serat kasar rendah 2%, dan harganya relatif
murah. Namun, kandungan aflatoksin di dalam jagung dapat membahayakan bagi
ikan apabila penggunaannya dalam pakan tidak dibatasi (Tangendjaja dan
Rachmawati 2006).
Pemanfaatan produk samping industri pertanian sebagai salah satu alternatif
bahan penyusun pakan ikan belakangan ini mulai dilakukan. Selain karena alasan
ekonomi juga bersifat ramah lingkungan. Beberapa produk samping industri
pertanian seperti produk samping pengolahan zaitun (olive mill waste), dat ston
mill waste, barley bran dan wheat bran, diketahui dapat digunakan sebagai bahan
penyusun pakan ikan tanpa mempengaruhi kinerja pertumbuhan dan komposisi
Wheat Bran merupakan hasil samping dari industri pengolahan gandum
menjadi tepung terigu. Selama ini penggunaan wheat bran terbatas hanya sebagai
bahan pengisi untuk roti whole wheat, serta pakan ternak ruminansia dan kuda.
Sementara penggunaannya dalam pakan ikan masih terbatas. Kandungan serat
kasarnya yang relatif tinggi yaitu sekitar 11%, menyebabkan penggunaan wheat
bran dalam pakan ikan dibatasi. Seperti halnya hewan monogastrik lain,
kemampuan ikan dalam mencerna serat kasar dibatasi oleh kemampuan
mikroflora dalam ususnya untuk mensekresikan selulosa (Bureau et al. 1999).
Meskipun serat kasarnya cukup tingi, namun wheat bran memiliki beberapa
kelebihan yaitu kandungan protein sekitar 15.7%, asam amino esensial yang
lengkap serta mineral dan vitamin B1 yang tinggi, jika dibandingkan dengan
jagung (Hertrampf dan Piedad - Pascual 2000)
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maina et al. 2002,
diketahui bahwa ikan nila Oreochromis niloticus mampu mencerna protein dalam
wheat bran dengan tingkat kecernaan mencapai 75,20%. Hal ini coba dibuktikan
pada ikan mas Cyprinus carpio sebagai hewan omnivora yang dikenal memiliki
toleransi tinggi terhadap pakan nabati, sehingga diharapkan mampu mencerna
wheat bran pada level yang diberikan sebagi substitusi jagung sekaligus
meminimalkan proporsi tepung kedelai dalam pakan ikan. Pada penelitian ini
dicoba untuk mengkombinasikan tepung jagung, kedelai dan wheat bran dalam
penyusunan pakan ikan mas dengan tingkat penggunaan wheat bran pada pada
kadar 0%, 10%, 20% dan 30%.
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kadar wheat bran optimal
dalam pakan ikan mas serta pengaruhnya terhadap kinerja pertumbuhan melalui
analisis daya cerna.
Hipotesis
Penambahan wheat bran dengan dosis tertentu dalam komposisi pakan
dapat dimanfaatkan oleh ikan mas tanpa menyebabkan penurunan kinerja
TINJAUAN PUSTAKA
Kebutuhan Nutrisi Ikan Mas (Cyprinus carpio)
Ikan membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh
dalam proses kehidupannya, dalam hal ini makanan sebagai sumber nutrisi utama
harus dapat memenuhi seluruh komponen nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh ikan
dalam jumlah yang tepat dan seimbang. Kualitas makanan yang paling berperan
dalam pertumbuhan adalah kandungan protein dari pakan. Menurut Webster dan
Lim (2002), kadar protein yang optimal dalam menunjang pertumbuhan mas
Cyprinus carpio berkisar antara 30-41%.
Karbohidrat didalam pakan digunakan sebagai sumber energi bagi ikan
(Furuichi, 1988). Pada umumnya ikan kurang baik dalam memanfaatkan
karbohidrat dalam pakan. Berdasarkan hasil penelitian De Silva et al. (2002) ikan
mas mampu memanfaatkan karbohidrat secara efektif sebagai sumber energi.
Meskipun kemampuan ikan memanfaatkan karbohidrat rendah, namun
karbohidrat harus tersedia dalam pakan karena jika karbohidrat tidak tersedia
maka protein dan lemak akan dikatabolisme menjadi energi (Furuichi, 1988).
Lemak dan minyak merupakan sumber energi yang tinggi dalam makanan
ikan. Lemak juga berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K; dan sumber
asam lemak essensial, yaitu asam lemak linoleat dan asam lemak linolenat. Lemak
terutama dalam bentuk fosfolipid dapat berperan dalam struktur sel dan
memelihara fleksibilitas serta permeabilitas membran. Kebutuhan lemak ikan mas
berkisar antara 5-15 % (Webster and Lim 2002). Kandungan lemak yang berlebih
dalam pakan akan menyebabkan peningkatan jumlah simpanan lemak tubuh ikan
(Manjappa et al. 2002).
Kandungan Serat Kasar Dalam Pakan Ikan
Serat makanan termasuk dalam kelompok senyawa anti gizi. Senyawa
tersebut dapat menghambat penggunaan unsur gizi di dalam tubuh, dan bahkan
dapat dikatakan bahwa senyawa tersebut sangat merugikan, karena dapat
berikatan dengan protein, karbohidrat, lemak, dan beberapa mineral membentuk
dalam komposisi pakan ikan terutama diperoleh dari unsur karbohidrat. Serat
kasar merupakan sisa-sisa sel tumbuhan yang tahan terhadap reaksi hidrolisis
enzim-enzim saluran pencernaan, seperti lignin, selulosa, hemiselulosa, pentosan
dan senyawa karbohidrat kompleks lainnya (NRC 1993).
Seperti halnya hewan monogastrik lain, kemampuan ikan dalam mencerna
serat kasar dibatasi oleh kemampuan mikroflora dalam ususnya untuk
mensekresikan selulosa (Bureau et al. 1999). Jika jumlah serat kasar berlebih
dalam pakan akan menyebabkan proporsi makanan yang dapat tercerna menjadi
berkurang, seperti menurunkan penyerapan lemak (Sutardi 1997), sehingga total
bobot kering pakan juga berkurang.
Sementara itu Ribeiro et al. (2011) menemukan bahwa kadar serat kasar
yang tinggi terutama pada pakan yang mengandung tepung kedelai dapat
membatasi daya cerna ikan terhadap protein. Akibatnya daya cerna ikan terhadap
pakan yang diberikan akan menurun yang menyebabkan kinerjanya menjadi
kurang bagus (De Silva and Anderson 1995). Hal ini dibuktikan oleh Ali et al.
(2003) dimana terjadi penurunan kinerja pertumbuhan pada ikan nila O. niloticus
dengan semakin meningkatnya pemberian alfa alfa meal yang diikuti dengan
peningkatan kadar serat kasar dalam pakan. Lanna et al. (2004) mengemukakan
bahwa selain berpengaruh terhadap tingkat kecernaan pakan, keberadaan serat
kasar juga berpengaruh terhadap laju pengosongan lambung dan morfologi
kalenjar pencernaan ikan.
Walaupun fakta menunjukkan bahwa kandungan nutrisi dalam serat kasar
rendah, namun keberadaannya dalam pakan mutlak diperlukan. Kandungan serat
membentuk massa fisik pakan dan meningkatkan pelletability (NRC 1993).
Selulosa dan hemiselulosa sudah banyak digunakan sebagai agen pelarut (diluting
agent) dan filler terutama pada pakan penelitian (De Silva and Anderson 1995;
Jauncey 1998). Kandungan serat kasar dalam jumlah sedikit diketahui dapat
memacu gerak peristaltik usus, namun jika jumlahnya berlebih juga tidak bagus
karena menyebabkan proses penyerapan makanan menjadi tidak efisien (Guillame
et al 1999). Hal ini diperkuat oleh Sá et al. (2008), yang melaporkan bahwa
tanpa menimbulkan pengaruh negatif terhadap kinerja pertumbuhan pada juvenile
white sea bream Diplodus sargus.
Wheat Bran
Wheat Bran merupakan lapisan berserat di bawah kulit gandum yang
sebagian besar kandungan vitamin dan protein dari gandum terdapat di bagian ini.
Lapisan ini tidak mengandung wheat germ atau titik tumbuh dari gandum (New in
Hertrampf and Pascual 2000).
Gandum dan produk olahannya digunakan untuk pakan ikan dalam jumlah
yang terbatas, khususnya dalam bentuk wheat bran, wheat pollard dan wheat
midlings karena kandungan serat kasarnya yang tinggi (Akiyama et al. 1991).
Jumlah gandum atau produk olahannya yang digunakan dalam pakan ikan
nilainya lebih tinggi dibandingkan pada pakan udang atau crutacea.
Wheat Bran diperoleh sebagai hasil samping dari industri pengolahan
gandum menjadi tepung terigu. Wheat bran memiliki kandungan serat yang cukup
tinggi yaitu sekitar 11 % Maina et al. (2002). Hal ini menyebabkan
penggunaannya dalam pakan ikan masih terbatas. Selama ini penggunaan wheat
bran hanya sebagai bahan pengisi untuk roti whole wheat dan pakan ternak
ruminansia maupun kuda. Namun wheat bran juga memiliki beberapa kelebihan
yaitu kandungan protein sekitar 15.7%, asam amino esensial yang lengkap serta
mineral dan vitamin B1 yang tinggi (Hertrampf dan Piedad - Pascual 2000)
Penelitian mengenai pemanfaatan wheat bran sebagai salah satu bahan
penyusun pakan ikan masih sangat terbatas. Pada beberapa penelitian yang
dilakukan diperoleh data bahwa wheat bran mampu memberikan performa
pertumbuhan yang cukup bagus pada ikan pada kadar tertentu karena tingkat
kecernaan wheat bran cukup tinggi. Maina et al. (2002) memperoleh nilai
kecernaan protein wheat bran sampai pada level 75,20 % pada ikan nila
Oreochromis niloticus. Ribeiro et al. (2011) kemudian juga menemukan hal yang
tidak berbeda jauh, yaitu tingkat kecernaan protein wheat bran oleh nila sebesar
Jagung
Jagung merupakan salah satu bahan baku nabati yang umum digunakan
dalam pakan ikan maupun ternak. Penggunaan jagung dalam komposisi pakan
biasanya sebagai sumber energi karena jagung dikenal sebagai produk nabati yang
memiliki kandungan energi tinggi yaitu sebesar 4.110 kcal. Tingginya kandungan
energi jagung berkaitan dengan tingginya kandungan pati (> 60 %) biji jagung.
Selain itu jagung juga memiliki kandungan serat kasar yang relatif rendah (2 %)
sehingga cocok digunakan sebagai bahan baku pakan. (Tangendjaja dan
Rachmawati 2006)
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mutu protein jagung tergolong
rendah. Hal ini disebabkan karena jagung memiliki keterbatasan dalam kandungan
asam amino terutama lisin dan triptofan (Suarni dan Widowati 2009). Disamping
itu kandungan aflatoksin di dalam jagung dapat membahayakan bagi ikan apabila
penggunaannya dalam pakan tidak dibatasi (Tangendjaja dan Rachmawati 2006).
Sementara itu kandungan mineral dalam jagung dapat dimanfaatkan dengan baik
oleh ikan terutama magnesium dan fosfor (Hertrampf dan Piedad - Pascual 2000).
Namun jagung diketahui memiliki kandungan Ca dan P yang relatif rendah dan
sebagian besar P terikat dalam bentuk fitat sehingga tidak dapat dimanfaatkan
seluruhnya dalam pakan, terutama oleh ternak berperut tunggal (Tangendjaja dan
Rachmawati 2006).
Jagung diketahui memiliki tingkat kecernaan yang cukup tinggi sehingga
dapat dimanfaatkan dengan baik oleh ikan. Nilai kecernaan protein jagung pada
ikan mas diketahui sebesar 73,48 % (De Gani et al. 1997). Sedangkan kecernaan
total jagung pada ikan mas sebesar 78,10 % (Yamamoto et al. 1998).
Komposisi kimia jagung dapat bervariasi, kandungan protein dan asam
amino banyak dipengaruhi oleh genetik jagung dan kesuburan tanah, pemupukan,
dan iklim. Perubahan kandungan protein jagung umumnya berhubungan dengan
perubahan rasio antara kandungan protein dalam endosperm dan total protein
Kedelai
Kedelai dikenal sebagai bahan baku nabati yang memiliki nilai nutrisi
tinggi. Selain karena kandungan proteinnya yang tinggi yaitu sebesar 43,20 %,
lemak 2 % dan serat kasar 6,50 %. Kedelai juga diketahui memiliki kandungan
asam amino yang lengkap terutama methionin 1.38% dan lysin 6,28 % serta
kandungan energi yang tinggi sebesar 4.518 kcal (Maina et al. 2002) dalam pakan.
Namun kelemahannya, kedelai mengandung zat antinutrisi seperti tripsin
inhibitor yang dapat mengganggu pertumbuhan ikan. Menurut Handajani dan
Widodo (2010) menyatakan bahwa zat anti nutrisi tersebut dapat dinonaktifkan
secara perlahan melalui proses pemanasan dan pengeringan, sehingga tidak
membahayakan bagi ikan.
Penggunaan kedelai sebagai sumber protein dipengaruhi oleh beberapa
faktor, antara lain kualitas dan proses pembuatan tepung bungkil kedelai, bahan
yang digunakan dalam formulasi, perbedaan spesies ikan, ukuran ikan, dan sistem
budidaya (Elanvogan dan Shim 2000). Selanjutnya, Franchis et al. (2001)
menyatakan bahwa pembatasan yang paling penting adalah ketidakseimbangan
asam amino (terutam kekurangan dari metionin); palatabilitas rendah (rendah
dalam beberapa ikan; keberadaan dari asam fitat mengurangi fosfor dan
mineral-mineral lain; dan kehadiran dari penghambat tripsin yang menonaktifkan
pencernaan enzim tripsin dalam kecernaan protein).
Tingkat kecernaan protein kedelai pada ikan mas cukup tinggi yaitu
sebesar 83,7 % dan kecernaan energi sebesar 74,7 % (De Gani et al. 1997). Hal ini
menyebabkan tepung bungkil kedelai banyak digunakan sebagai pengganti tepung
ikan. Namun respon setiap spesies ikan berbeda terhadap penggunaan tepung
bungkil kedelai dalam pakan (Refstie et al. 2000). Pada ikan mas (Viola et al.,
1981a, 1981b, 1982) penggantian tepug ikan dengan tepung bungkil kedelai
sebanyak 45 % dapat dicapai dengan penambahan lemak (mencapai 10 %),
metionin (0,4 %), dan lisin (0,4-0,5 %) dalam pakan. Sementara pada Japanese
Flounder dapat memanfaatkan 45 % dari tepung ikan dengan bungkil kedelai
Kecernaan Nutrisi
Kecernaan didefinisikan sebagai bagian dari pakan yang diserap oleh
hewan (Lovell, 1989). Pakan yang masuk ke dalam saluran pencernaan akan
dicerna menjadi senyawa sederhana berukuran mikro, dimana protein dihidrolisis
menjadi asam-asam amino atau peptida sederhana, lemak menjadi gliserol dan
asam lemak dan karbohidrat menjadi gula sederhana (Halver 2002).
Kemampuan cerna ikan terhadap suatu jenis makanan bergantung kepada
faktor fisik dan kimia makanan, jenis makanan, umur ikan, sifat fisik dan kimia
air, serta jumlah enzim pencernaan pada sistem pencernaan gastrointestinal (NRC
1977). Kecernaan ini bervariasi dari spesies satu ke spesies yang lain. Secara
umum daya cerna untuk protein berkisar 70 – 90 %, dan untuk karbohidrat
bervariasi dari 5 – 15 % untuk tepung selulosa dan untuk glukosa 1 %.
Dalam proses pencernaan tidak semua komponen pakan yang dimakan
dapat dicerna menjadi bahan yang diserap, sebab pada kenyataannya ada sebagian
pakan yang tidak tercerna. Bagian tersebut akan dikeluarkan dari dalam tubuh
ikan berupa feses. Jadi pada prinsipnya penentuan nilai pencernaan suatu bahan
makanan adalah membandingkan kadar nutrien atau energi pakan dengan kadar
energi feses dinyatakan dalam satuan persen (Affandi et al . 1992).
Kecernaan pakan mulai menurun disebabkan oleh faktor-faktor lain yang
berhubungan dengan ketidaktepatan dalam hidrolisa dan penyerapan seperti
proses pencernaan tidak lancar atau formulasi pakan tidak tepat (Affandi et al.
1992). Faktor yang mempengaruhi laju pencernaan melalui usus sehingga
mengurangi kecernaan protein dan energi adalah serat kasar, jumlah konsumsi
pakan, ukuran ikan, suhu dan komponen non protein dalam pakan. Pakan yang
berbeda dapat mengakibatkan kecernaan makanan serta energi metabolisme yang
berbeda. Pakan yang berasal dari bahan nabati biasanya lebih sedikit dicerna
dibanding dengan bahan hewani. Bahan nabati umumnya memiliki serat kasar
yang sulit dicerna dan mempunyai dinding sel kuat yang sulit dipecahkan (Hepher
1988).
Pengukuran kecernaan ada dua cara, yaitu metode langsung dan metode
tidak langsung. Pada metode langsung yang diukur yaitu jumlah pakan yang
yaitu dengan menambahkan indikator dalam pakan dimana indikator tersebut
mempunyai sifat tidak dapat diserap dalam tubuh ikan, tidak beracun dan dapat
dianalisa dalam jumlah yang sedikit dan indikator yang mempunyai sifat tersebut
adalah Cromium oxide. Jumlah Cromium oxide yang digunakan dalam penentuan
kecernaan adalah 0,5-1,0%. Keuntungan dari menggunakan metode tidak
langsung ini adalah feses yang telah dikumpulkan dapat dianalisa kandungan
nutriennya sehingga dapat diketahui koefisien daya cerna suatu nutrien dalam
pakan tersebut (Takeuchi 1988).
BAHAN DAN METODE
Uji Pertumbuhan
Penelitian untuk uji pertumbuhan dilaksanakan dari bulan Januari sampai
Juni 2011. Hewan uji yang digunakan adalah ikan mas berukuran 23 ± 0,13 g
berasal dari Subang. Sebelum diberi perlakuan, ikan diadaptasikan terlebih dahulu
selama 1 minggu di dalam keramba. Selanjutnya ikan ditebar pada masing-masing
jaring perlakuan yang berukuran 2 x 2 x 1 m3 berjumlah 12 buah yang dipakai
sebagai unit percobaan dengan padat tebar 250 ekor tiap jaring. Pemeliharaan ikan
dilakukan di dalam keramba jaring apung Cirata selama 60 hari. Penempatan unit
perlakuan pakan disusun dengan menggunakan metode acak (random method)
(Steel dan Torrie, 1993).
Pemberian pakan dilakukan secara at satiation (sekenyangnya) dengan
mengamati respon makan ikan, yaitu jika ikan sudah mulai terlihat tidak terlalu
berminat terhadap pakan yang diberikan, maka pemberian pakan dapat dihentikan
atau bisa juga ditandai dengan keberadaan sisa pakan di perairan yang tidak
dikonsumsi oleh ikan (minimal 50%). Frekuensi pemberian pakan dilakukan 3
kali sehari, yaitu sekitar pukul 8 pagi, 12 siang dan 4 sore.
Pakan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 macam pakan
yang berbeda sesuai perlakuan, yaitu pakan dengan kandungan wheat bran 0%,
10%, 20%, dan 30%. Formulasi pakan perlakuan dapat dilihat pada Tabel 1.
Sementara untuk komposisi proksimat pakan bisa dilihat pada Tabel 2.
Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat komposisi pakan uji kandungan wheat
bran 0% sampai 30% mengganti jagung sebagai sumber energi utama dan
pengurangan proporsi tepung kedelai sebagai sumber protein nabati. Sumber
lemak dalam komposisi pakan diperoleh dari miyak ikan dan soy oil. Gaplek
dalam komposisi pakan sebagai penyumbang energi dan binder dalam pakan yaitu
sebesar 20,9-30%. Sumbangan protein hewani dalam komposisi pakan uji
disamakan, Sumber protein hewani yang digunakan yaitu terdiri dari Squid Liver
Mono-dicalcium phosphate) sumber fosfor dan kalsium, Bioyeast, dan premixdigunakan
sebagai bahan aditif dalam komposisi pakan.
Tabel 1. Komposisi bahan pakan penelitian
Bahan Pakan Perlakuan
WB 0 % WB 10 % WB 20 % WB 30 %
Jagung 17,70 6,60 0,00 0,00
Wheat Bran 0,00 10,00 20,00 30,00
Gaplek 27,70 30,00 28,73 20,90
Soy Bean Meal 31,18 30,39 27,99 25,43
Squid Liver 0,90 0,90 0,90 0,90
Meat and Bone Meal 10,00 9,40 10,00 10,00
Poultry by Product Meal 2,00 2,00 2,00 2,00
Fish Meal 5,00 5,00 5,00 5,00
Tabel 2. Hasil analisa proksimat (% berat kering) dan energi pada pakan uji
Komposisi proksimat Perlakuan 1) Bahan ekstrak tanpa nitrogen.
2) Gross energy 1 g protein = 5.6 kkal GE, 1 g BETN = 4.1 kkal GE, 1 g lemak = 9.4 kkal GE (Watanabe 1988). 3) Digestible energy 1 g protein= 3.5 kkal DE,1 g lemak= 8.1 kkalDE,1 g BETN= 2.5 kkal DE (NRC 1997). 4) Rasio energi/protein.
Pengamatan Harian
Pengamatan harian yang dilakukan meliputi pencatatan pemberian pakan
harian, jumlah ikan yang mati serta beberapa parameter kualitas air seperti suhu,
oksigen terlarut (DO), pH dan kecerahan. Pengukuran suhu, DO, pH dan
kecerahan dilakukan secara in situ pada pagi dan sore hari. Kisaran parameter air
yang terukur selama penelitian meliputi suhu 28-31 0C, pH 6,03-7,11, DO
1,88-5,40 ppm dan nilai kecerahan 95-147 cm. Sementara itu pengukuran bobot ikan
dilakukan setiap 2 minggu sekali. Penimbangan bobot dilakukan dengan cara
mengangkat setiap jaring dan menghitung semua ikan yang hidup pada
masing-masing jaring kemudian ditimbang bobotnya secara keseluruhan.
Analisis Statistik
Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap
dengan 4 perlakuan dan 3 kali ulangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan
menggunakan SPSS. Untuk melihat perbedaan perlakuan maka dilakukan uji
lanjut dengan Uji Duncan (Steel & Torrie 1995).
Parameter yang diukur
Dalam penelitian ini peubah yang diukur dan diamati adalah laju
pertumbuhan harian (LPH), efisiensi pakan (EP), konsumsi pakan (KP),
kelangsungan hidup (KL), retensi protein (RP), retensi lemak (RL), kecernaan
total dan kecernaan protein
1. Laju pertumbuhan harian
Laju pertumbuhan harian dihitung berdasarkan rumus Huisman (1987) :
Keterangan :
α : laju pertumbuhan harian individu
Wt : bobot rata-rata ikan pada waktu t (g)
W0 : bobot rata-rata ikan awal (g)
2. Efisiensi Pakan
Efisiensi pakan didefinisikan sebagai peningkatan bobot basah daging per
unit bobot pakan kering, Efisiensi pakan (EP) dianalisis berdasarkan rumus
Takeuchi (1988) :
Keterangan :
EP = Efisiensi pakan (%)
Wt = Biomassa ikan pada waktu t (g)
Wo = Biomassa ikan pada awal percobaan (g)
Wd = Biomassa ikan yang mati (g)
JKP = Jumlah (bobot) pakan yang dikonsumsi selama percobaan (g)
3. Jumlah Konsumsi Pakan
Jumlah konsumsi pakan ikan uji diketahui dengan cara menimbang jumlah
pakan yang dimakan oleh ikan uji selama penelitian.
4. Sintasan
Sintasan ikan uji didapatkan dengan menghitung jumlah individu ikan uji
yang hidup sampai akhir percobaan, Perhitungannya menggunakan rumus
Zonneveld et al. (1991) :
SR = Kelangsungan hidup ikan
Nt = Jumlah individu ikan uji pada t percobaan (ekor)
No = Jumlah individu ikan uji pada awal percobaan (ekor) EP (%) = [(Wt + Wd) – W0] x 100%
5. Retensi protein
Retensi protein merupakan gambaran dari banyaknya protein yang
diberikan, yang dapat diserap dan dimanfaatkan untuk pertumbuhan serta
dimanfaatkan tubuh untuk metabolisme harian (Halver, 1989). Nilai retensi
protein dihitung berdasarkan persamaan yang dikemukakan oleh Takeuchi (1988)
%
Retensi lemak merupakan seberapa besar lemak yang dapat disimpan di
dalam tubuh ikan. Nilai retensi lemak dapat dihitung berdasarkan persamaan yang
dikemukakan oleh Takeuchi (1988), yaitu:
L
F = Kandungan lemak tubuh pada akhir penelitian (g)
I = Kandungan lemak tubuh pada awal penelitian (g)
L = Jumlah lemak yang dimakan ikan (g)
7. Kecernaan Total (Sumber : Watanabe, 1988)
Kecernaan total menggambarkan daya cerna seluruh fraksi nutrien yang
Kecernaan total =
Keterangan :
a = % Cr2O3 dalam pakan%
a` = % Cr2O3 dalam feses
8. Kecernaan Protein
Kecernaan protein menggambarkan daya cerna fraksi protein yang
terkandung di dalam pakan.
Kecernaan protein =
Keterangan :
a = % Cr2O3 dalam pakan%
a` = % Cr2O3 dalam feses
b = % protein dalam pakan
b` = % protein dalam feses
Analisis Biaya
Perhitungan biaya pakan dilakukan dengan cara menghitung total biaya
bahan pakan formulasi dikalikan jumlah bahan pakan formulasi. Nilai yang
diperoleh menggambarkan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 kg
Uji Kecernaan
Ikan yang digunakan untuk uji kecernaan terdiri dari 2 kelompok ukuran,
yaitu ukuran kecil dengan bobot rata-rata 6 ± 0,12 g dan ikan dengan ukuran
lebih besar dengan bobot rata-rata 50 ± 0,18 g. Masing-masing kelompok ikan
disebar ke dalam 12 buah akuarium untuk tiap kelompoknya. Ikan dipelihara di
dalam akuarium dengan ukuran masing-masing 60 x 40 x 40 cm3 yang berada di
Laboratorium percobaan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat selama ± 2
minggu dengan padat tebar 20 ekor/akuarium. Pengelompokan ikan menjadi 2
ukuran tersebut bertujuan untuk melihat perbandingan daya cerna antara ikan
besar dengan ikan kecil terhadap pakan yang sama dengan perlakuan yang sama
antara kedua kelompok ikan tersebut.
Ikan uji pada masing-masing akuarium diberi pakan perlakuan yang sudah
ditambahkan 0,5 % Cr2O3 sebagai indikator kecernaan (Watanabe, 1988). Pada
hari ke lima setelah ikan diberi pakan, feses ikan mulai dikumpulkan kemudian
disimpan dalam botol film. Feses yang sudah terkumpul tersebut disimpan dalam
lemari pendingin (freezer) untuk menjaga kesegarannya.
Setelah terkumpul cukup banyak, feses dikeringkan di dalam oven bersuhu
110°C selama 4 – 6 jam. Penanganan faeces ini dilakukan mengikuti metode
Takeuchi (1988). Selanjutnya dilakukan analisis kandungan protein dan Cr2O3
terhadap feses yang sudah dikeringkan tadi dengan bantuan alat spektrofotometer
yang memiliki panjang gelombang 350 nm. Pengukuran kadar Cr2O3 dalam feses
dilakukan di Lab Nutrisi Ikan, Departemen Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Laju pertumbuhan sebagai fungsi dari bobot tubuh, yaitu adanya perubahan
bobot tubuh ikan pada akhir dan awal penelitian seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 1. Biomassa di akhir penelitian berkisar antara 20,3 – 22,1 kg.
Peningkatan biomassa yang terjadi sebesar 3,53 – 3,84 kali lipat.
Gambar 1. Perubahan biomassa rata-rata individu ikan mas perlakuan wheat bran
dengan kadar berbeda (0%, 10%, 20%, dan 30%).
Berdasarkan data pertumbuhan dapat diketahui bahwa peningkatan bobot
tubuh yang terjadi hampir sama di setiap perlakuan dengan rata-rata bobot tubuh
akhir yang dapat dicapai sebesar 20,3- 22,1 kg. Pertumbuhan ini dapat terjadi dan
dicapai dengan pemanfaatan pakan dari lingkungannya, kemudian dengan proses
metabolisme diubah menjadi organ-organ tubuh (Effendi 1997). Dengan demikian
dapat diketahui bahwa pakan perlakuan yang diberikan mampu dicerna dan
Tabel 3. Jumlah konsumsi pakan (JKP), laju pertumbuhan harian (LPH), efisiensi pakan (EP),retensi protein (RP), retensi lemak (RL) dan kelangsungan hidup (SR) ikan mas setelah dipelihara selama 60 hari.
Parameter Keterangan : 1.Huruf superskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukan hasil yang tidak berbeda nyata ( P>0.05).
2. Nilai yang tertera merupakan nilai rata-rata dan standar deviasi.
Perlakuan wheat bran ternyata tidak berpengaruh terhadap kinerja
pertumbuhan ikan mas (Tabel 3). Pengurangan tepung bungkil kedelai (Soybean
meal) dan penggantian jagung di dalam formulasi pakan oleh wheat bran
menghasilkan kinerja pertumbuhan yang sama.
Hal ini diduga disebabkan karena keempat komposisi pakan perlakuan
yang digunakan bersifat isoenergi dan isoprotein dengan nilai masing-masing
berada pada kisaran 2.444,3 – 2.505,12 kkal/kg dan 28,11 - 29,26 %. Nilai
tersebut masih berada dalam kisaran nilai energi yang dibutuhkan ikan mas
(2.500 – 2.850 kkal/kg) dan kebutuhan protein ikan mas sebesar 27 - 32 %
(Webster and Lim 2002). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keempat
pakan perlakuan yang digunakan memiliki kualitas nutrisi yang hampir sama,
meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam komposisi bahan pakan terutama
kandungan serat kasar yang mengalami peningkatan dari 3,16 – 5,96 %. Namun
nilai efisiensi pakan dan jumlah konsumsi pakan yang hampir sama ( 32,73 –
38,63 % dan 43,85 – 46,39 %) menunjukkan bahwa peningkatan serat kasar yang
disebabkan oleh penambahan wheat bran sampai 30% tersebut masih berada
dalam kisaran toleransi ikan mas untuk menunjang pertumbuhannya. Seperti
halnya hewan monogastrik lain, kemampuan ikan dalam mencerna serat kasar
dibatasi oleh kemampuan mikroflora dalam ususnya untuk mensekresikan
menyebabkan proporsi makanan yang dapat tercerna menjadi berkurang, seperti
menurunkan penyerapan lemak (Sutardi 1997), sehingga total bobot kering pakan
juga berkurang. Akibatnya daya cerna ikan terhadap pakan yang diberikan akan
menurun yang menyebabkan kinerja pertumbuhannya menjadi kurang bagus (De
Silva and Anderson 1995)
Hal yang sama juga terlihat pada nilai retensi protein yang tidak
menunjukkan perbedaan signifikan antar perlakuan. Nilai retensi protein yang
diperoleh pada penelitian ini sebesar 17,01-21,65 %. Nilai retensi protein tersebut
tergolong rendah jika dibandingkan dengan nilai retensi protein yang diperoleh
dari hasil penelitian Herizon (2004) sebesar 25,3-27,3 % yang melakukan
penelitian terhadap ikan mas dalam wadah akuarium. Namun jika dibandingkan
dengan pertumbuhan ikan mas pada beberapa KJA sekitar pada waktu
pemeliharaan yang bersamaan, diketahui bahwa kondisi ikan mas pada waktu
tersebut rata-rata memang tidak terlalu bagus. Berdasarkan informasi yang
diperoleh dari petani sekitar, nilai FCR ikan mas pada waktu tersebut berkisar
antara 2,8-3,2. Kondisi ini diduga turut dipengaruhi oleh faktor curah hujan yang
tinggi pada waktu pemeliharaan. Selama penelitian juga sempat terjadi kematian
pada beberapa ikan di sekitar KJA akibat terinfeksi jamur. Dengan demikian dapat
diketahui bahwa selain faktor perbedaan komposisi pakan, perbedaan kondisi
lingkungan atau kualitas air pada wadah penelitian juga sangat berpengaruh
terhadap kinerja pertumbuhan yang diperoleh.
Kualitas air dalam akuarium cenderung lebih stabil karena kondisinya
dapat dikontrol. Berbeda halnya dengan keramba, kondisinya lebih fluktuatif
karena bergatung pada lingkungan atau keadaan alam setempat. Berdasarkan
beberapa penelitian terhadap kualitas air di Waduk Cirata dengan rentang waktu
dari tahun 1987 – 2006 yang dipublikasikan oleh Garno (2010), diketahui bahwa
terjadi penurunan kualitas air setiap tahunnya disebabkan meningkatnya bahan
pencemar, baik berupa bahan organik maupun anorganik yang berasal dari luar
dan dalam badan air. Konsentrasi N-anorganik setiap tahunnya hampir selalu
lebih besar dari 0,300 mgN/L dan konsentrasi P-fosfat selalu lebih besar dari
0,010 mgP/L. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Garno (2002)
besar dari 0,016 mgP/L dan total nitrogen anorganik (NH4+-N + NO3-N + NO2-N)
selalu lebih besar dari 0,711 mgN/L. Kondisi ini menurut Hendersen et al. (1987)
akan sangat mudah mengalami ledakan pertumbuhan (blooming) plankton.
Dengan kata lain, Waduk Cirata telah tercemar berat oleh nutrien sehingga
tergolong pada perairan hypertrofik. Status hypertrofik ini menyebabkan
timbulnya lapisan anaerob di dalam badan air akibatnya kandungan senyawa
anorganik beracun (NH3 dan H2S) cenderung lebih tinggi.
Sudradjat (2010) juga melaporkan bahwa kadar ammoniak (NH3) di
Waduk Cirata telah melebihi baku mutu untuk perikanan dengan kisaran nilai
0,00 – 1,870 mg/l. Hal ini diduga akibat terjadinya penguraian nitrogen dalam
kondisi anaerob. Fakta lain dikemukakan oleh Komarawidjaja (2005) yang
melaporkan bahwa ikan budidaya (Cyprinus carpio) yang dipelihara dalam KJA
pertumbuhannya tidak normal, dimana pertumbuhan panjang lebih dominan
dibandingkan pertumbuhan berat ikan, disebabkan karena berkurangnya pakan
alami di perairan waduk dan meningkatnya akumulasi senyawa toksik. Secara
umum terjadi penurunan produksi ikan budidaya setiap tahunnya di Waduk
Cirata, seperti yang dilaporkan oleh Abery et al. (2005) bahwa produksi ikan pada
tahun 1995 sekitar 2300 kg per KJA, namun pada tahun 2002 produksi turun
sekitar 400 kg per KJA. Kualitas air yang buruk menyebabkan pemanfaatan
energi ikan lebih banyak untuk kebutuhan metabolisme dan pemeliharaan tubuh
dibandingkan pertumbuhan.
Nilai retensi protein yang kecil menunjukkan bahwa ikan lebih banyak
menggunakan protein sebagai sumber energinya sehingga protein yang tersimpan
menjadi lebih sedikit. Akibatnya energi untuk pertumbuhan juga sedikit yang
berimplikasi pada rendahnya nilai laju pertumbuhan harian yang diperoleh pada
penelitian ini, yaitu berkisar antara 2,10 – 2,24. Hal ini sesuai dengan pendapat
yang dikemukakan oleh Handajani dan Widodo (2010), yaitu apabila sumbangan
energi dari bahan non protein tersebut rendah, maka protein akan didegradasi
untuk menghasilkan energi, sehingga fungsi protein sebagai nutrien pembangun
Tabel 4. Komposisi asam amino essensial pakan percobaan (% protein)
Keterangan : 1. * wheat bran dan jagung (Hertrampf dan Piedad-Pascual, 2000). 2. ** asam amino ikan mas Ketola (1980) dalam Pillay and Kutty (2005).
Berdasarkan data hasil perhitungan pada Tabel 4, menunjukkan bahwa
masing-masing perlakuan memiliki pola asam amino yang hampir sama dengan
pola asam amino yang dibutuhkan ikan mas, sehingga kinerja pertumbuhan yang
diperoleh juga relatif sama antar perlakuan. Pola asam amino tersebut
menggambarkan kualitas bahan pakan yang digunakan. Semakin mendekati pola
asam amino yang dibutuhkan ikan berarti semakin baik kualitas bahan pakan yang
digunakan.
Tabel 5 Kecernaan total dan kecernaan protein pakan uji dengan kandungan
wheat bran yang berbeda
Pakan Uji Kecernaan Total Kecernaan Protein Ikan kecil Ikan besar Ikan kecil Ikan besar
WB 0% 56,25±0,96 b 57,25±0,98 b 67,80±1,49 a 68,30±1,35 a
WB 10% 53,22±4,75 b 57,66±4,75 b 70,99±3,23 a 70,61±4,25 a
WB 20% 44,80±2,15 a 53,18±3,97 a 65,23±1,56 a 64,74±2,18 a
WB 30% 41,78±2,71 a 47,39±2,71 a 65,16±2,01 a 65,53±3,07 a
Keterangan : 1) Huruf yang berbeda pada kolom yang sama untuk kecernaan total menunjukkan pengaruh
perlakuan yang berbeda nyata (p 0.05).
2) Huruf yang sama pada kolom yang sama untuk kecernaan protein menunjukkan pengaruh
perlakuan yang tidak berbeda nyata (p > 0.05).
3)
Nilai yang tertera merupakan nilai rata-rata±standar deviasi.
Kemampuan ikan dalam mencerna pakan yang diberikan dinyatakan dalam
bentuk nilai kecernaan. Kecernaan menjadi kriteria untuk menentukan bahan baku
yang sesuai digunakan dalam komposisi pakan ikan (Merican 2007). Berdasarkan
kecernaan protein antar perlakuan dengan perbedaan kandungan wheat bran yang
diberikan. Hal ini disebabkan karena tingkat kecernaan wheat bran yang tinggi
sehingga mampu dicerna dengan baik oleh ikan. Sebagai perbandingan nilai
kecernaan protein kedelai dan jagung pada ikan mas masing-masing sebesar 83,7
% dan 73,48 % dengan kecernaan energi sebesar 74,7 % serta 58,07 % (De Gani
et al. 1997). Sementara itu, Maina et al. (2002) yang memperoleh nilai kecernaan
protein wheat bran sampai pada level 75,20% pada ikan nila Oreochromis
niloticus. Ribeiro et al. (2011) kemudian juga menemukan hal yang tidak berbeda
jauh, yaitu tingkat kecernaan protein wheat bran oleh nila sebesar 82,87 %.
Pada penelitian ini diperoleh nilai kecernaan protein yang lebih rendah
yaitu berada pada kisaran 65,16 – 70,99 %. Kondisi ini bisa terjadi karena
perbedaan spesies ikan dan komposisi pakan yang digunakan dalam penelitian,
sehingga menyebabkan perbedaan dalam hal kapasitas pencernaan ikan
(Masagounder et al. 2009). Kadar serat kasar yang tinggi terutama pada pakan
yang mengandung tepung kedelai dapat membatasi daya cerna ikan terhadap
protein (Ribeiro et al 2011). Hal ini disebabkan karena keterbatasan mikroflora
dalam ususnya untuk mensekresikan selulosa (Bereu et al. 1999).
Sedangkan nilai kecernaan total menurun seiring dengan meningkatnya
kadar wheat bran dalam pakan. Nilai kecernaan total tertinggi diperoleh dari
perlakuan wheat bran 0 % dan 10 %, baik pada ikan berukuran besar maupun ikan
ukuran kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan wheat bran dalam
komposisi pakan dapat menyebabkan peningkatan kandungan serat kasar dimana
kadar serat pakan naik dari 3,16 menjadi 5,96 % seiring dengan meningkatnya
proporsi wheat bran dalam komposisi pakan. Peningkatan kadar serat kasar dalam
pakan menyebabkan kecernaan pakan menjadi menurun. Hal ini sesuai dengan
pendapat Sutardi (1997), yang menyatakan bahwa apabila serat kasar terdapat
dalam jumlah berlebih dalam pakan akan mempengaruhi penyerapan unsur nutrisi
lain, seperti menurunkan penyerapan lemak, membatasi jumlah makanan yang
dapat dicerna sehingga menurunkan kecernaan nutrisi. Lanna et al. (2004)
mengemukakan bahwa selain berpengaruh terhadap tingkat kecernaan pakan,
keberadaan serat kasar juga berpengaruh terhadap laju pengosongan lambung dan
Pada penelitian ini peningkatan serat kasar yang disebabkan oleh
penambahan wheat bran sampai kadar 30% tidak menyebabkan penurunan kinerja
pertumbuhan. Hal ini disebabkan karena penurunan nilai kecernaan total tidak
menyebabkan penurunan konsumsi protein, dimana nilai retensi protein antar
perlakuan relatif sama yang didukung oleh tingkat kecernaan protein yang tinggi
dan tidak berbeda secara signifikan pada keempat perlakuan. Sehingga dapat
dikatakan bahwa komposisi pakan penelitian cukup baik dalam menunjang
pertumbuhan ikan mas. Kondisi ini sedikit berbeda dari hasil penelitian Sá et al
(2008) yang melaporkan bahwa peningkatan serat berupa alfa-alfa meal dalam
pakan dapat menurunkan konsumsi protein tanpa menimbulkan pengaruh negatif
terhadap kinerja pertumbuhan juvenile white sea bream Diplodus sargus.
Perbedaan ini bisa disebabkan karena perbedaan komposisi serta sumber serat
kasar yang digunakan dalam pakan penelitian.
Sementara itu perbedaan ukuran ikan yang digunakan dalam penelitian ini
ternyata tidak menyebabkan perbedaan tingkat kecernaan protein dan kecernaan
total pakan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Klahan et al. (2008) yang
melakukan pengujian daya cerna pakan terhadap 3 kelompok ukuran ikan nila,
yaitu 5,7 g, 35, 8 g dan 91,2 g. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa ikan
nila yang berukuran lebih kecil dan sedang (5,7 g dan 30,8 g) memiliki daya cerna
protein lebih baik dibandingkan ikan yang berukuran besar (91,2 g). Sedangkan
pada penelitian ini ukuran ikan yang digunakan terdiri dari 2 kelompok ukuran
yaitu 6 g dan 50 g, sehingga masih termasuk dalam kisaran ikan kecil dan sedang
berdasarkan pengelompokan Klahan et al. (2008).
Hasil uji in vitro yang dilakukan Klahan et al. (2008), ditemukan bahwa
terdapat perbedaan aktivitas enzim pada tingkat ukuran ikan yang berbeda. Ikan
dengan ukuran kecil sampai sedang memiliki aktivitas enzim protease dan lipase
yang lebih tinggi (0,436 – 0,440 U min-1 mg protein-1 dan 0,039 – 0,061 U min-1
mg protein-1), sedangkan ikan dengan ukuran lebih besar lebih tinggi aktivitas
enzim amilase dalam tubuhnya (0,539 mU min-1 mg protein-1). Sehingga
didapatkan bahwa ikan dengan ukuran kecil dan sedang lebih baik dalam
Tabel 6. Data harga pakan, efisiensi pakan, dan biaya pakan uji per kg
parameter perlakuan pakan uji (%)
0 10 20 30
harga pakan (Rp/kg) 4.149 4.026 3.900 3.846
efisiensi pakan (%) 32,73 37,93 38,63 35,05
Biaya pakan ikan/kg 12.677 10.616 10.097 10.974
Kegiatan budidaya tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan
keuntungan. Pakan merupakan biaya variabel produksi terbesar dalam usaha
budidaya. Kemampuan baik dalam mengelola pakan sangat menentukan
keuntungan budidaya karena biaya pakan dapat mencapai 70% dari total biaya
produksi (Al-Asgah et al. 2011). Oleh karena itu perlu dicari sumber bahan baku
alternatif termurah salah satunya yaitu wheat bran untuk menekan biaya pakan.
Berdasarkan data hasil analisa biaya (Tabel 6) menunjukkan bahwa pakan dengan
kandungan wheat bran 20% memiliki gain cost (penambahan biaya) terendah
dibandingkan pakan perlakuan lainnya yaitu sebesar Rp 10.097,-.
Hal ini mengindikasikan bahwa ikan mas mampu memanfaatkan pakan
dengan kadar wheat bran 20 % secara efektif sehingga mencapai tingkat
keseimbangan yang lebih baik antara peningkatan bobot tubuh dengan
penambahan biaya pakan yang dibutuhkan. Dengan demikian dapat diperoleh
gambaran bahwa penggunaan wheat bran 20 % dalam pakan ikan mas dari segi
ekonomi lebih menguntungkan dibandingkan pakan perlakuan lainnya sehingga
mampu mensubstitusi peran jagung sekaligus mengurangi proporsi penggunaan
tepung bungkil kedelai dan selanjutnya dapat meminimalkan biaya produksi
KESIMPULAN
Ikan mas mampu menggunakan wheat bran sampai dengan 30% dalam
pakan tanpa mempengaruhi kinerja pertumbuhannya, baik pada ikan mas
berukuran kecil maupun besar dengan tingkat kecernaan protein pada kisaran
64,74 – 70,99 % dan kecernaan total pada kisaran 41,78 – 57,66 %. Namun yang
Lampiran 1 Prosedur analisis proksimat bahan pakan dan tubuh ikan uji
A. Kadar Protein
Tahap Oksidasi
1. Sampel ditimbang sebanyak 0.5 gram dan dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl.
2. Katalis (K2SO4+CuSo4.5H2O) dengan rasio 9:1 ditimbang sebanyak 3 gram
dan dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl.
3. 10 ml H2SO4 pekat ditambahkan ke dalam labu Kjeldahl dan kemudian labu
tersebut dipanaskan dalam rak oksidasi/digestion pada suhu 400oC selama 3-4
jam sampai terjadi perubahan warna cairan dalam labu menjadi hijau bening.
4. Larutan didinginkan lalu ditambahkan air destilasi 100 ml. Kemudian larutan
dimasukkan ke dalam labu takar dan diencerkan dengan Aquades sampai
volume larutan mencapai 100 ml. Larutan sampel siap untuk didestilasi.
Tahap Destilasi
1. Beberapa tetes H2SO4 dimasukkan ke dalam labu, sebelumnya labu diisi
setengahnya dengan Aquades untuk menghindari kontaminasi oleh ammonia
lingkungan. Kemudian didihkan selama 10 menit.
2. Erlenmeyer diisi 10 ml H2SO4 0.05 N dan ditambahkan 2 tetes indicator methyl
red diletakkan di bawah pipa pembuangan kondensor dengan cara dimiringkan
sehingga ujung pipa tenggelam dalam cairan.
3. 5 ml larutan sampel dimasukkan ke dalam tabung destilasi melalui corong
yang kemudian dibilas dengan Aquades dan ditambahkan 10 ml NaOH 30%
lalu dimasukkan melalui corong tersebut dan ditutup.
4. Campuran alkaline dalam labu destilasi disuling menjadi uap air selama 10
menit terjadi pengembunan pada kondensor.
5. Labu erlenmeyer diturunkan hingga ujung pipa kondensor berada di leher labu,
diatas permukaan larutan. Kondensor dibilas dengan Aquades selama 1-2
menit.
Tahap Titrasi
1. Larutan hasil destilasi ditritasi dengan larutan NaOH 0.05 N.
2. Volume hasil titrasi dicatat.
Lanjutan Lampiran 1. Prosedur analisis proksimat...
Kadar Protein (%) = 0.0007 * x (Vb – Vs) x 6.25 ** x 20 x 100% S
Keterangan : Vb = Volume hasil titrasi blanko (ml)
Vs = Volume hasil titrasi sampel (ml)
S = Bobot sampel (gram)
* = Setiap ml 0.05 NaOH ekivalen dengan 0.0007 gram Nitrogen
** = Faktor Nitrogen
B. Kadar Lemak
Metode ekstraksi Soxhlet
1. Labu ekstraksi dipanaskan dalam oven pada suhu 110o dalam waktu 1 jam.
Kemudian didiinginkan dalam desikator selama 30 menit dan ditimbang bobot
labu tersebut (X1)
2. Sampel ditimbang sebanyak 3-5 gram (A), dan dimasukkan ke dalam
selongsong tabung filter dan dimasukkan ke dalam soxhlet dan pemberat
diletakkan di atasnya.
3. N-hexan 100-150 ml dimasukkan ke dalam soxhlet sampai selongsong
terendam dan sisa N-hexan dimasukkan ke dalam labu.
4. Labu yang telah dihubungkan dengan soxhlet dipanaskan di atas water bath
sampai cairan yang merendam sampel dalam soxhlet berwarna bening.
5. Labu dilepaskan dan tetap dipanaskan hingga N-hexan menguap.
6. Labu dan lemak yang tersisa dipanakan dalam oven selama 15-60 menit,
kemudian didinginkan dalam desikator selama 15-30 menit dan ditimbang (X2)
Metode Folch
1. Labu silinder dioven terlebih dahulu pada suhu 110oC selama 1 jam,
didinginkan dalam desikaotr selama 30 menit kemudian ditimbang (X1).
2. Sampel ditimbang sebanyak 2-3 gram (A) dan dimasukkan ke dalam gelas
homogenize dan ditambahkan larutan kloroform / methanol (20xA) , sebagian
disisakan untuk membilas pada saat penyaringan.
3. Sampel dihomogenizer selama 5 menit setelah itu disraing dengan vacuum
Lanjutan Lampiran 1. Prosedur analisis proksimat ...
4. Sampel yang telah disaring tersebut dimasukkan dalamlabu pemisah yang
telah diberi larutan MgCl2 0.03 N(0.2xC), kemudian dikocok dengan kuat
minimal selama 1 menit kemudian ditutup dengan aluminium foil dan
didiamkan selama 1 malam.
5. Lapisan bawa yang terdapat dalam labu pemisah disaring ke dalam labu
silinder kemudian dievaporator sampai kering. Sisa kloroform / methanol yang
terdpat dalam labu ditiup dengan menggunakan vacuum setelah itu ditimbang
(X2)
Kadar Lemak (%) = X2 –X1 x 100%
A
C. Kadar Air
1. Cawan dipanaskan dalam oven pada suhu 100oC selama 1 jam dan
kemudian dimasukkan dalam dessikator selama 30 menit dan ditimbang
(X1)
2. Bahan ditimbang 2-3 gram (A)
3. Cawan dan bahan dipansakan dalam oven pada suhu 110oC selama 4 jam
kemudian dimasukkan dalam desikator selam 30 menit dan ditimbang (X2)
Kadar Air (%) = (X1+A)-X2 x 100%
A
D. Kadar Abu
1. Cawan dipanaskan dalam oven pada suhu 100oC selama 1 jam dan kemudian
dimasukkan dalam desikator selama 30 menit dan ditimbang (X1)
2. Bahan ditimbang 2-3 gram (A)
3. Cawan dan bahan dipansakan dalam tanur pada suhu 600oC sampai mnejadi
abu kemudian dimasukkan dalam desikator selam 30 menit dan ditimbang (X2)
Kadar Abu (%) = X2 –X1 x 100%
Lanjutan Lampiran 1. Prosedur analisis proksimat ...
E. Kadar Serat Kasar
1. Kertas filter dipanaskan dalam oven selama 1 jam pada suhu 110oC setelah itu
didinginkan dalam desikator selama 15 menit dan ditimbang (X1)
2. Sampel ditimbang sebnayak 0.5 gram (A) dimasukkan kedalam Erlenmeyer
250 ml
3. H2SO4 0.3 N sebanyak 50 ml ditambahkan ke dalam Erlenmeyer kemudian
dipanaskan di atas pembakar Bunsen selama 30 menit. Setelah itu NaOH 1.5 N
sebanyak 25 ml ditambahkan ke dalam Erlenmeyer dan dipanskan kembali
selama 30 menit.
4. Larutan dan bahan yang telah dipanaskan kemudian disraing dalam corong
Buchner dan dihubungkan pada vacuum pump untuk mempercepat filtrasi.
5. Larutan dan bahan yang ada pada corong Buchner kemudaian dibilas secara
berturut-turut dengan 50 ml air panas, 50 ml H2SO4 0.3 N, 50 ml air panas, dan
25 ml acetone.
6. Kertas saring dan isinya dimasukkan dalam cawan porselin, lalu dipanaskan
dalam oven 105-110oC selama 1 jam kemudian didinginkan dalam desikator
5-15 menit dan ditimbang (X2).
7. Setelah itu dipanaskan dalam tanur 600oC hingga berwarna putih atau menjadi
abu (± 4 jam). Kemudian dimasukkan dalam oven 105-110oC selama 15 menit,
didinginkan dalam desikator selama 5-15 menit dan ditimbang (X3).
Kadar Serat Kasar (%) = (X2 – X1 – X3) x 100%
Lampiran 2 Prosedur analisa Cr2O3
Timbang 0,1-0,2 g sampel/bahan, masukkan kedalam labu kjedahl.
Tambahkan 5 ml nitric acid pekat kedalam labu. Panaskan dengan hati-hati
selama 30 menit sampai volume larutan menjadi ± 1 ml. Setelah dingin,
tambahkan 3 ml perchloric acid pekat kedalam labu kemudian panaskan kembali.
Setelah asap putih terlihat dan larutan berubah dari hiaju menjadi kuning atau
orange, campuran dipanaskan selama ± 10 menit. Dinginkan, lalu encerkan
sampai volume 100 ml. Nilai absorban larutan ditentukan oleh spektrofotometer
dengan panjang gelombang 350 nm.
Skema Kerja
0,1-0,2 g sampel (berisi 1-3 mg Cr2O3)(A)
5 ml nitric acid pekat
Labu kjedahl
Panaskan hingga larutan tersisa ± 1 ml
Labu didinginkan
Tambahkan 3 ml perchloric acid (70%)
Panaskan kembali hingga berwarna jingga
Panaskan selama 10 menit
Labu didinginkan
Encerkan menggunakan gelas ukur sampai 100 ml
Lampiran 3. Bobot biomasa awal dan akhir, kelangsungan hidup, konsumsi pakan, pertumbuhan relatif dan efisiensi pakan pada ikan mas yang diberi pakan uji selama 60 hari masa pemeliharaan
Parameter Ulangan Perlakuan wheat bran
0 % 10 % 20 % 30 %
Bobot biomas awal (g) 1 5780,00 5750,00 5720,00 5700,00 2 5740,00 5700,00 5750,00 5700,00 3 5770,00 5700,00 5770,00 5780,00
Rata-rata 5.763,33 5.716,67 5.746,67 5.726,67
SD 20,82 28,87 25,17 46,19
Bobot biomas panen (g) 1 24.000,00 24.000,00 23.000,00 23.000,00 2 22.000,00 21.000,00 24.000,00 20.000,00 3 15.000,00 24.000,00 24.000,00 23.000,00
Rata-rata 20.333,33 23.000,00 23.666,67 22.000,00
SD 4.725,82 1.732,05 577,35 1.732,05
Konsumsi pakan (g) 1 46720,00 46200,00 46330,00 47690,00 2 45560,00 45860,00 46530,00 44930,00 3 39280,00 44730,00 46320,00 46490,00
Rata-rata 43.853,33 45.596,67 46.393,33 46.370,00
SD 4.002,87 769,57 118,46 1.383,91
Pertumbuhan relatif (%) 1 96,17 98,17 96,46 96,87 2 87,89 89,91 100,27 88,69 3 75,53 96,56 97,36 94,44
Rata-rata 86,53 94,88 98,03 93,33
SD 10,38 4,38 1,99 4,20
Efisiensi pakan (%) 1 39,00 39,50 37,30 36,28 2 35,69 33,36 39,22 31,83 3 23,50 40,91 39,36 37,04
Rata-rata 32,73 37,93 38,63 35,05
Lampiran 4.Data retensi protein tubuh ikan uji
parameter ulangan Pakan uji
wB 0 % WB 10 % WB 20 % WB 30%
Biomassa ikan awal (g) 1 5780 5750 5720 5700
2 5740 5700 5750 5700
3 5770 5700 5770 5780
Biomassa ikan akhir (g) 1 24000 24000 23000 23000 2 22000 21000 24000 20000 3 15000 24000 24000 23000 Protein ikan: protein tubuh total awal (g) 1 756,02 752,10 748,18 745,56
2 750,79 745,56 752,10 745,56 3 754,72 745,56 754,72 756,02 protein tubuh total akhir (g) 1 3445,45 3408,44 3510,60 3593,75
2 3086,60 3211,23 3631,42 2914,00 3 2236,50 3432,00 3586,08 3293,60 jumlah protein yang disimpan
dalam tubuh (g) 1 2689,42 2656,34 2762,43 2848,19 2 2335,81 2465,67 2879,32 2168,44 3 1481,78 2686,44 2831,36 2537,58 Pakan ikan
Konsumsi pakan (g) 1 46720 46200 46330 47690 2 45560 45860 46530 44930 3 39280 44730 46320 46490 kadar protein pakan(%) 1 28,71 29,26 28,11 27,77
2 28,71 29,26 28,11 27,77 3 28,71 29,26 28,11 27,77 jumlah protein pakan yang
dikonsumsi(g) 1 13413,312 13517,856 13025,506 13243,824 2 13080,276 13418,374 13081,735 12477,354
3 11277,288 13087,742 13022,694 12910,576 retensi protein (%) 1 20,05 19,65 21,21 21,51
2 17,86 18,38 22,01 17,38 3 13,14 20,53 21,74 19,66
rata-rata 17,01 19,52 21,65 19,51
Lampiran 5.Data retensi lemak tubuh ikan uji
parameter ulangan
pakan uji
wB 0 % WB 10 % WB 20 % WB 30%
Biomassa ikan awal (g) 1 5780 5750 5720 5700
2 5740 5700 5750 5700
3 5770 5700 5770 5780
Biomassa ikan akhir (g) 1 24000 24000 23000 23000 2 22000 21000 24000 20000
Kadar lemak tubuh akhir( %) 1 11,58 10,17 11,61 12,71 2 12,32 11,85 12,02 13,66 3 12,50 13,48 12,48 13,14 Lemak tubuh total awal (g) 1 59,49 57,78 62,49 56,49 2 57,78 55,64 56,49 57,35 3 57,35 55,64 55,64 57,78 Lemak tubuh total akhir (g) 1 390,96 252,5 362,76 339,29 2 381,47 253,92 289,14 454,56 3 389,14 328,06 363,73 396,55 jumlah lemak yang tersimpan
dalam tubuh (g) 1 331,47 194,72 299,27 282,8 2 323,69 198,28 232,65 397,21 3 331,79 272,42 308,09 338,77 Pakan ikan
Konsumsi pakan (g) 1 46720 46200 46330 47690 2 45560 45860 46530 44930
dikonsumsi (g) 1 2515,64 2511,40 2777,41 3342,85 2 2453,18 2492,92 2789,40 3149,39 3 2115,03 2431,49 2776,81 3258,74 retensi lemak (%) 1 97,33 84,06 84,33 77,67 2 97,00 86,62 91,69 76,37 3 73,03 119,64 95,97 82,56
rata-rata 89,12 96,77 90,66 78,87
Lampiran 6. Hasil uji statistik terhadap beberapa parameter biologi
a. Tabel sidik ragam untuk laju pertumbuhan spesifik (α)
ANOVA
b.Tabel sidik ragam untuk efisiensi pakan (EP)
ANOVA
c. Tabel sidik ragam untuk nilai konsumsi pakan (FCR)
ANOVA
d. Tabel sidik ragam untuk retensi protein
e. Tabel sidik ragam untuk retensi lemak
f. Tabel sidik ragam untuk kecernaan protein ikan kecil
ANOVA
g. Tabel sidik ragam untuk kecernaan protein ikan besar
ANOVA
h. Tabel sidik ragam untuk kecernaan total ikan kecil
Uji Duncan
i. Tabel sidik ragam untuk kecernaan total ikan besar
ANOVA
Perlakuan 204,76 3 68,25 8,35 0,01