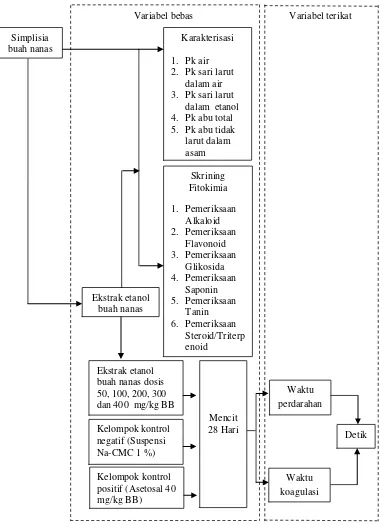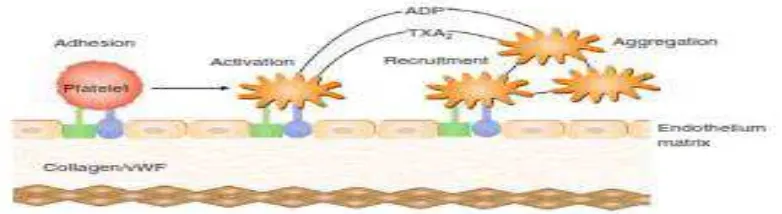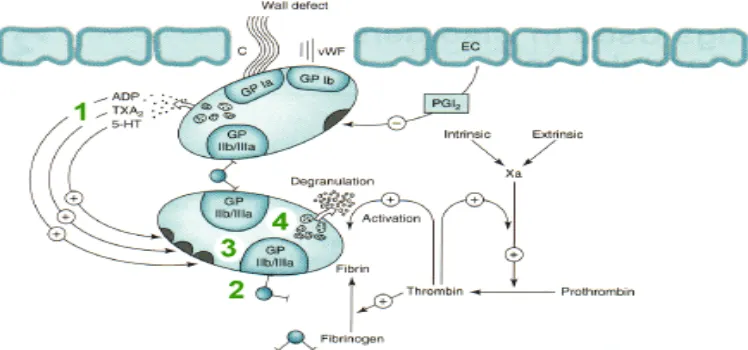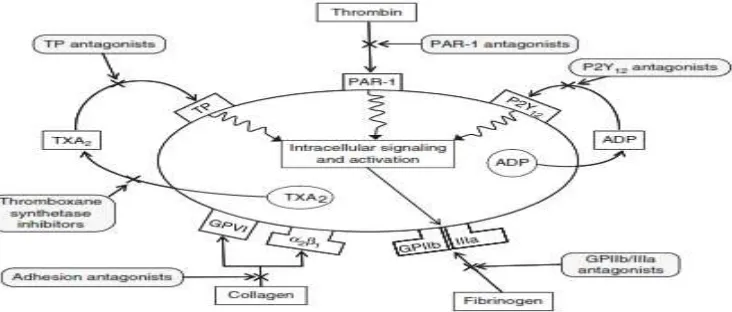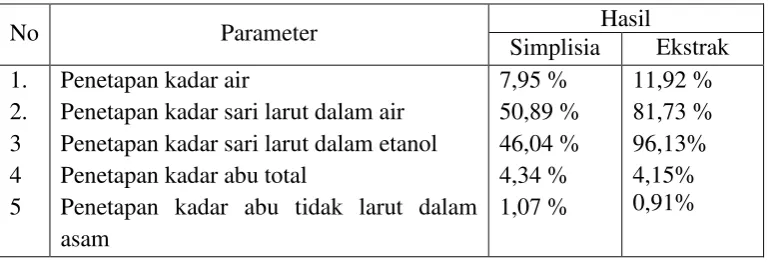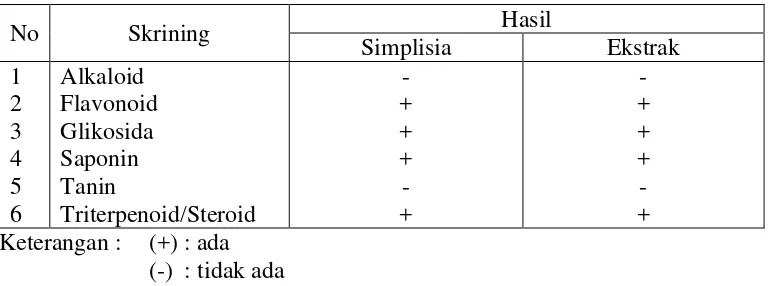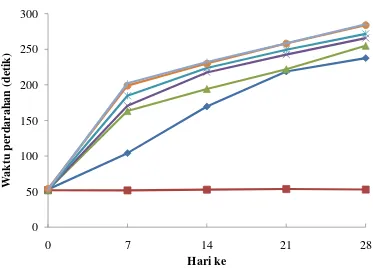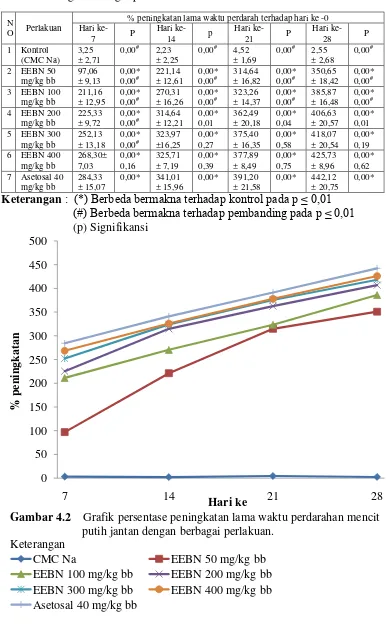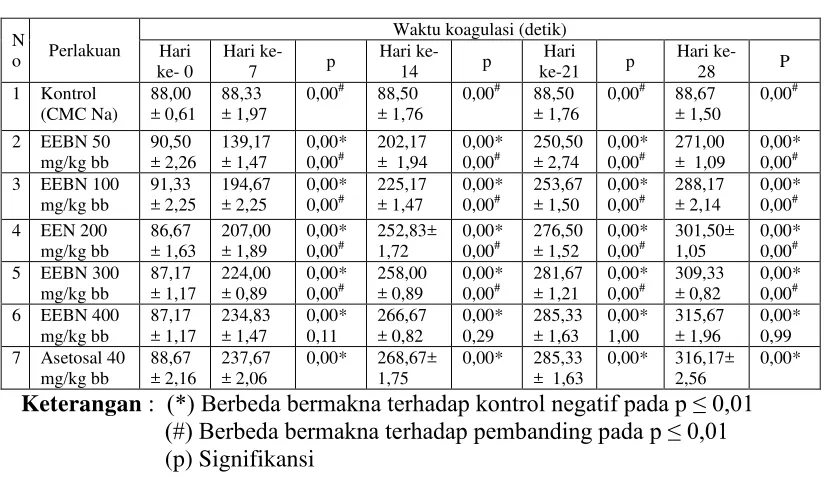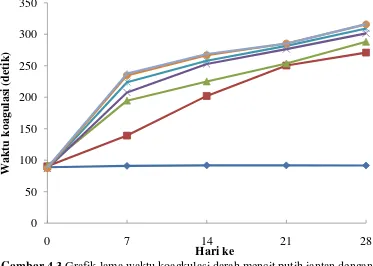EFEK ANTIAGREGASI PLATELET EKSTRAK ETANOL
BUAH NANAS (
Ananas comusus
Merr) PADA MENCIT
PUTIH JANTAN
SKRIPSI
OLEH:
MARDIAN RAKASIWI
NIM 101524003
PROGRAM EKSTENSI SARJANA FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
EFEK ANTIAGREGASI PLATELET EKSTRAK ETANOL
BUAH NANAS (
Ananas comusus
Merr) PADA MENCIT
PUTIH JANTAN
SKRIPSI
Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Farmasi
Universitas Sumatera Utara
OLEH:
MARDIAN RAKASIWI
NIM 101524003
PROGRAM EKSTENSI SARJANA FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
PENGESAHAN SKRIPSI
EFEK ANTIAGREGASI PLATELET EKSTRAK ETANOL
BUAH NANAS (
Ananas comusus
Merr) PADA MENCIT
PUTIH JANTAN
OLEH:MARDIAN RAKASIWI NIM 101524003
Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara
Pada Tanggal: Oktober 2013
Disetujui Oleh: Pembimbing I, Panitia Penguji,
Aminah Dalimunthe, S.Si., M.Si., Apt. Prof. Dr. Sumadio Hadisahputra, Apt. NIP 197806032005012004 NIP 195311281983031002
Aminah Dalimunthe, S.Si., M.Si., Apt.
Pembimbing II, NIP 197806032005012004
Prof. Dr. Urip Harahap, Apt. Drs. Saiful Bahri, M.S., Apt. NIP 195301011983031004 NIP 195208241983031001
Marianne, S.Si., M.Si., Apt. NIP 198005202005012006
Medan, Oktober 2013 Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara
Dekan,
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan
skripsi ini yang berjudul “Efek Antiagregasi Platelet Ekstrak Etanol Buah Nanas
(Ananas comusus Merr) Pada Mencit Putih Jantan”. Skripsi ini diajukan sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas
Farmasi Universitas Sumatera Utara.
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus tiada terhingga kepada
Ayahanda Bakhtiar dan Ibunda Akmar tercinta, serta kepada Adik Tiara Martini,
Trisma Liliani atas doa, dorongan dan semangat baik moril maupun materil
kepada penulis selama masa perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi
ini.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada Ibu Aminah Dalimunthe, S.Si., M.Si., Apt., dan Bapak
Prof. Dr. Urip Harahap, Apt., yang telah membimbing penulis dengan penuh
kesabaran, tulus dan ikhlas selama penelitian hingga selesainya penulisan skripsi
ini.
Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Sumadio Hadisahputra, Apt., sebagai Dekan Fakultas
Farmasi yang telah memberikan bantuan dan fasilitas selama masa
2. Bapak Drs. Wiryanto, M.S., Apt., sebagai dosen wali yang telah
membimbing penulis selama masa pendidikan.
3. Bapak Prof. Dr. Sumadio Hadisahputra, Apt., Bapak Drs. Saiful Bahri,
M.S., Apt., Ibu Marianne, S.Si., M.Si., Apt., sebagai dosen penguji yang
telah memberikan saran dan kritikan kepada penulis hingga selesainya
penulisan skripsi ini.
4. Seluruh staf pengajar, pegawai tata usaha, kakak-kakak, abang-abang dan
teman-teman yang telah membantu selama penelitian hingga selesainya
penulisan skripsi ini.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki
banyak kekurangan, oleh karena itu sangat diharapkan kritikan dan saran yang
dapat menyempurnakan skripsi ini.
Medan, Oktober 2013
Penulis,
Efek Antiagregasi Platelet Ekstrak Etanol Buah Nanas
(Ananas comusus Merr) Pada Mencit Putih Jantan
ABSTRAK
Platelet membentuk trombus, pada kondisi normal trombus dapat larut dengan spontan, apabila tidak larut, trombus akan menghambat sirkulasi darah ke organ-organ tubuh penting. Obat antiplatelet digunakan untuk menurunkan agregasi platelet dan menghambat trombosis. Obat antiplatelet standar adalah asetosal dosis rendah 75-300 mg/hari. Penelitian sebelumnya dan beberapa literatur mengatakan, enzim bromelin pada nanas berfungsi sebagai antiagregasi platelet dan fibrinolitik. Sehingga peneliti terterik untuk meneliti buah nanas sebagai antiagregasi platelet.
Untuk mengetahui karakterisasi, golongan senyawa kimia simplisia dan ekstrak. Selain itu untuk mengetahui waktu perdarahan dan koagulasi darah mencit.
Penelitian ini meliputi karakterisasi, skrining fitokimia simplisia dan ekstrak, dan uji antiagregasi platelet dengan menggunakan metode waktu perdarahan dan waktu koagulasi. Penelitian ini menggunakan 7 kelompok perlakuan. Kelompok dibagi atas kelompok kontrol negatif (Na CMC 1%), kelompok kontrol positif (asetosal 40 mg/kg bb), dan kelompok perlakuan dengan variasi dosis diberi ekstrak etanol buah nanas dosis 50, 100, 200, 300 dan 400 mg/kg bb.
Hasil karakterisasi simplisia yang diperoleh memenuhi persyaratan simplisia, hasil karakterisasi ekstrak dapat diperoleh sebagai acuan karakterisasi ekstrak. Hasil skrining fitokimia simplisia dan ekstrak etanol buah nanas menunjukkan adanya kandungan bioaktif senyawa golongan flavonoid, glikosida, saponin, triterpenoid/steroid. Hasil uji antiagregasi platelet menunjukkan bahwa ekstrak etanol buah nanas dosis 50, 100, 200, 300 mg/kg bb menunjukkan efek memperlama waktu perdarahan dan koagulasi, efek yang dihasilkan berbeda bermakna (p ≤ 0,01) terhadap Na CMC 1% dan asetosal, sedangkan ekstrak etanol buah nanas 400 mg/kg bb menunjukan hasil yang berbeda bermakna (p ≤ 0,01) dengan Na CMC 1%, tetapi tidak berbeda bermakna dengan asetosal 40 mg/kg bb dengan waktu perdarahan, 198,83 ± 0,75 detik; 229,83 ± 0,75 detik; 258,00 ± 0,89 detik; 283,83 ± 1,17 detik (p > 0,01) dan waktu koagulasi darah 234,83 ± 1,47 detik; 266,67 ± 0,82 detik; 285,33 ±1,63 detik; 315,67 ± 1,96 detik (p > 0,01).
Ekstrak etanol buah nanas mampu memperlama waktu perdarahan dan koagulasi sehingga dapat dijadikan sebagai antiagregasi platelet.
Platelet Antiaggregation Effect of Ethanolic Extract of Pineapple
(Ananascomusus Merr) to Male White Mice
ABSTRACT
Platelet thrombus formed, in normal conditions thrombus may dissolve spontaneously, if it does not dissolve, thrombus will inhibit blood circulation to vital organs. Antiplatelet drugs used to reduce platelet aggregation and prevent thrombosis. Standard antiplatelet drug is low-dose acetosal 75-300 mg/day. Earlies studies and several literature state that bromelin enzyme in pineapple function as platelet antiaggregation and fibrinolytic. Therefore, researchers is interested to investigate platelet antiaggregation effects of pineapple.
To determine characterization, class of chemical compounds botanicals and extracts crude. In addition to determine the bleeding time and blood coagulation mice.
This research involved characterization, Phytochemical screening of botanicals and extracts, platelet antiaggregation test using bleeding time and coagulation time. This study used seven treatment groups. The group divided to negative control group (CMC Na 1%), positive control group (acetosal 40 mg/kg bw), and treatment groups with various doses given ethanolic extract of pineapple doses of 50, 100, 200, 300 and 400 mg/kg bw.
Botanicals characterization results obtained the requirements of botanicals, extrac characterization results can be usu as reference extract characterization. The results of botanicals and ethanol extract of pineapple phytochemical screening showed there were bioactive compounds classified as flavonoid, glycosides, saponins, and triterpenoids/steroids. The test results showed that platelet antiaggregation ethanolic extract of pineapple doses of 50, 100, 200, 300 mg/kg bw showed effects prolong bleeding time, effects resulting had significantly difference (p ≤ 0.01) for CMC Na 1% and acetosal, whereas ethanolic extract of pineapple 400 mg/kg bw showed effects had significant difference (p < 0.01) compared to CMC Na 1%, however didn’t have significant difference compared to acetosal 40 mg/kg bw with bleeding time, 198.83 ± 0.75 second; 229.83 ± 0.75 second; 258.00 ± 0.89 second; 283.83 ± 1.17 second (p > 0.01) and coagulation time, 234.83 ± 1.47 second; 266.67 ± 0.82 second; 285.33 ±1.63 second; 315.67 ± 1.96 second (p > 0.01).
Ethanol extract pineapple fruit can prolong bleeding time and coagulation that can be used as antiplatelets aggregation.
DAFTAR ISI
Halaman
JUDUL ... i
LEMBAR PENGESAHAN ... iii
KATA PENGANTAR ... iv
ABSTRAK ... vi
ABSTRACT ... vii
DAFTAR ISI ... viii
DAFTAR TABEL ... xii
DAFTAR GAMBAR ... xiii
DAFTAR LAMPIRAN ... xiv
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1Latar Belakang ... 1
1.2Kerangka Pikir penelitian ... 4
1.3Perumusan Masalah ... 5
1.4Hipotesis ... 5
1.5Tujuan Penelitian ... 6
1.6Manfaat Penelitian ... 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 7
2.1 Uraian Tanaman Nanas ... 7
2.2 Efek Farmakologi Tumbuhan ... 7
2.3 Ekstraksi ... 8
2.4.1 Aktivitas Platelet ... 13
2.5 Pembentukan Bekuan Darah di Dalam Tubuh ... 16
2.5.1 Proses Pembentukan Bekuan Darah ... 17
2.6 Antiplatelet (Antitrombotik) dan Trombolitik (fibrinolitik) ... 17
2.6.1 Antiplatelet (Antitrombotik) ... 18
2.6.2 Trombolitik (Fibrinolitik) ... 20
BAB III METODE PENELITIAN ... 23
3.1 Alat-alat ... 23
3.2 Bahan-bahan ... 23
3.3 Hewan Percobaan ... 24
3.4 Pengumpulan dan Pengolahan Sampel ... 24
3.4.1 Pengambilan Sampel ... 24
3.4.2 Identifikasi Tanaman ... 24
3.4.3 Pengolahan Sampel ... 24
3.5 Pembuatan Ekstrak Etanol Buah Nanas (EEBN) ... 25
3.6 Karakterisasi Simplisia ... 25
3.6.1 Penetapan Kadar Air ... 25
3.6.2 Penetapan Kadar Sari Larut Air ... 26
3.6.3 Penetapan Kadar Sari Larut Etanol ... 26
3.6.4 Penetapan Kadar Abu Total ... 27
3.6.5 Penetapan Kadar Abu Tidak Larut Asam ... 27
3.7 Karakterisasi ekstrak etanol buah nanas (EEBN) ... 27
3.8 Skrining Fitokimia Simplisia ... 28
3.8.2 Pemeriksaan Flavonoid ... 28
3.8.3 Pemeriksaan Glikosida ... 29
3.8.4 Pemeriksaan Saponin ... 30
3.8.5 Pemeriksaan Tanin ... 30
3.8.6 Pemeriksaan Steroid/triterpenoid ... 30
3.9 Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Buah Nanas (EEBN) .... 30
3.10 Pembuatan Suspensi Bahan Uji ... 31
3.10.1 Pembuatan Suspensi Na CMC 1% ... 31
3.10.2 Pembuatan Suspensi Asetosal ... 31
3.10.3 Pembuatan Suspensi Ekstrak Etanol Buah Nanas .... 32
3.11 Uji Antiagregasi Pletelet ... 32
3.11.1 Pengukuran Waktu Perdarahan ... 32
3.11.2 Pengukuran Waktu Koagulasi ... 33
3.12 Analisis Data ... 33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 34
4.1 Idendifikasi Tanaman ... 34
4.2 Karakteristik Simplisia dan Ekstrak Etanol Buah Nanas ... 34
4.3 Skrining Fitokimia ... 36
4.4 Uji Antiagregasi Platelet Ekstrak Etanol Buah Nanas ... 37
4.4.1 Uji Waktu Perdarahan ... 37
4.4.2 Uji Waktu Koagulasi ... 42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 49
5.1 Kesimpulan ... 49
DAFTAR PUSTAKA ... 51
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 4.1 Hasil Karakterisasi simplisia dan eksrak
etanol buah nanas ... 34
Tabel 4.2 Hasil skrining fitokimia simplisia dan ekstrak
etanol buah nanas ... 37
Tabel 4.3 Waktu perdarahan mencit putih jantan
dengan berbagai perlakuan ... 38
Tabel 4.4 Persentase peningkatan lama waktu perdarahan mencit ... 39
Tabel 4.5 Waktu koagulasi darah mencit ... 43
Tabel 4.6 Persentase peningkatan lama waktu koagulasi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 Skema Kerangka Pikir Penelitian ... 4
Gambar 2.1 Peran platelet membentuk trombus ... 12
Gambar 2.2 Proses agregat platelet pada pembuluh darah ... 16
Gambar 2.3 Cara penghambatan agregasi platelet ... 18
Gambar 4.1 Grafik lama waktu perdarahan mencit ... 38
Gambar 4.2 Grafik persentase peningkatan lama waktu perdarahan ... 39
Gambar 4.3 Grafik lama waktu koagulasi darah mencit ... 43
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1 Hasil Identifikasi Tanaman ... 55
Lampiran 2 Gambar Sampel ... 56
Lampiran 3 Gambar Bahan dan Objek Penelitian ... 58
Lampiran 4 Perhitungan Karakterisasi Simplisia ... 61
Lampiran 5 Perhitungan Karakterisasi Ekstrak Etanol Buah Nanas ... 64
Lampiran 6 DataHasil Uji Waktu Perdarahan dan Koagulasi Darah Mencit ... 67
Efek Antiagregasi Platelet Ekstrak Etanol Buah Nanas
(Ananas comusus Merr) Pada Mencit Putih Jantan
ABSTRAK
Platelet membentuk trombus, pada kondisi normal trombus dapat larut dengan spontan, apabila tidak larut, trombus akan menghambat sirkulasi darah ke organ-organ tubuh penting. Obat antiplatelet digunakan untuk menurunkan agregasi platelet dan menghambat trombosis. Obat antiplatelet standar adalah asetosal dosis rendah 75-300 mg/hari. Penelitian sebelumnya dan beberapa literatur mengatakan, enzim bromelin pada nanas berfungsi sebagai antiagregasi platelet dan fibrinolitik. Sehingga peneliti terterik untuk meneliti buah nanas sebagai antiagregasi platelet.
Untuk mengetahui karakterisasi, golongan senyawa kimia simplisia dan ekstrak. Selain itu untuk mengetahui waktu perdarahan dan koagulasi darah mencit.
Penelitian ini meliputi karakterisasi, skrining fitokimia simplisia dan ekstrak, dan uji antiagregasi platelet dengan menggunakan metode waktu perdarahan dan waktu koagulasi. Penelitian ini menggunakan 7 kelompok perlakuan. Kelompok dibagi atas kelompok kontrol negatif (Na CMC 1%), kelompok kontrol positif (asetosal 40 mg/kg bb), dan kelompok perlakuan dengan variasi dosis diberi ekstrak etanol buah nanas dosis 50, 100, 200, 300 dan 400 mg/kg bb.
Hasil karakterisasi simplisia yang diperoleh memenuhi persyaratan simplisia, hasil karakterisasi ekstrak dapat diperoleh sebagai acuan karakterisasi ekstrak. Hasil skrining fitokimia simplisia dan ekstrak etanol buah nanas menunjukkan adanya kandungan bioaktif senyawa golongan flavonoid, glikosida, saponin, triterpenoid/steroid. Hasil uji antiagregasi platelet menunjukkan bahwa ekstrak etanol buah nanas dosis 50, 100, 200, 300 mg/kg bb menunjukkan efek memperlama waktu perdarahan dan koagulasi, efek yang dihasilkan berbeda bermakna (p ≤ 0,01) terhadap Na CMC 1% dan asetosal, sedangkan ekstrak etanol buah nanas 400 mg/kg bb menunjukan hasil yang berbeda bermakna (p ≤ 0,01) dengan Na CMC 1%, tetapi tidak berbeda bermakna dengan asetosal 40 mg/kg bb dengan waktu perdarahan, 198,83 ± 0,75 detik; 229,83 ± 0,75 detik; 258,00 ± 0,89 detik; 283,83 ± 1,17 detik (p > 0,01) dan waktu koagulasi darah 234,83 ± 1,47 detik; 266,67 ± 0,82 detik; 285,33 ±1,63 detik; 315,67 ± 1,96 detik (p > 0,01).
Ekstrak etanol buah nanas mampu memperlama waktu perdarahan dan koagulasi sehingga dapat dijadikan sebagai antiagregasi platelet.
Platelet Antiaggregation Effect of Ethanolic Extract of Pineapple
(Ananascomusus Merr) to Male White Mice
ABSTRACT
Platelet thrombus formed, in normal conditions thrombus may dissolve spontaneously, if it does not dissolve, thrombus will inhibit blood circulation to vital organs. Antiplatelet drugs used to reduce platelet aggregation and prevent thrombosis. Standard antiplatelet drug is low-dose acetosal 75-300 mg/day. Earlies studies and several literature state that bromelin enzyme in pineapple function as platelet antiaggregation and fibrinolytic. Therefore, researchers is interested to investigate platelet antiaggregation effects of pineapple.
To determine characterization, class of chemical compounds botanicals and extracts crude. In addition to determine the bleeding time and blood coagulation mice.
This research involved characterization, Phytochemical screening of botanicals and extracts, platelet antiaggregation test using bleeding time and coagulation time. This study used seven treatment groups. The group divided to negative control group (CMC Na 1%), positive control group (acetosal 40 mg/kg bw), and treatment groups with various doses given ethanolic extract of pineapple doses of 50, 100, 200, 300 and 400 mg/kg bw.
Botanicals characterization results obtained the requirements of botanicals, extrac characterization results can be usu as reference extract characterization. The results of botanicals and ethanol extract of pineapple phytochemical screening showed there were bioactive compounds classified as flavonoid, glycosides, saponins, and triterpenoids/steroids. The test results showed that platelet antiaggregation ethanolic extract of pineapple doses of 50, 100, 200, 300 mg/kg bw showed effects prolong bleeding time, effects resulting had significantly difference (p ≤ 0.01) for CMC Na 1% and acetosal, whereas ethanolic extract of pineapple 400 mg/kg bw showed effects had significant difference (p < 0.01) compared to CMC Na 1%, however didn’t have significant difference compared to acetosal 40 mg/kg bw with bleeding time, 198.83 ± 0.75 second; 229.83 ± 0.75 second; 258.00 ± 0.89 second; 283.83 ± 1.17 second (p > 0.01) and coagulation time, 234.83 ± 1.47 second; 266.67 ± 0.82 second; 285.33 ±1.63 second; 315.67 ± 1.96 second (p > 0.01).
Ethanol extract pineapple fruit can prolong bleeding time and coagulation that can be used as antiplatelets aggregation.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
Salah satu faktor penting dalam proses penggumpalan darah adalah
platelet atau lebih dikenal dengan nama trombosit. Platelet adalah sel yang tidak
berinti, besarnya antara 3-2 mikron, berbentuk lonjong dan pipih seperti cakram.
Pada keadaan tertentu platelet dapat berubah menjadi bulat dengan tepi yang
tidak rata karena tonjolan yang disebut pseudopod. Fungsi utama platelet adalah
membentuk sumbat mekanis selama respon hemostatik normal terhadap luka
vaskular (Erlianti, 1999).
Trombosis adalah pembentukan suatu massa abnormal akibat proses
penggumpalan pada sistem pembuluh darah makhluk hidup. Massa abnormal ini
dinamakan trombus. Pada kondisi tubuh normal, trombus dapat larut dengan
spontan tetapi apabila tidak larut, kemungkinan trombus akan terlepas dan
terbawa oleh darah ke paru-paru. Jika tejadi pada pembuluh arteri, trombus akan
menghambat sirkulasi darah ke organ-organ tubuh penting, dan terjadi pada
pembuluh darah otak akan menyebabkan timbulnya penyakit stroke (Erlianti,
1999).
Trombosis dan aterosklerosis terjadi akibat gaya hidup tidak seimbang
serta tingginya konsumsi gula dan lemak. Kondisi ini dapat menyebabkan
penyakit arteri perifer, infarksi miokardial, dan stroke. Selain memperbaiki
Obat-obat antiplatelet digunakan untuk menurunkan agregasi platelet dan
menghambat trombosis. Obat antiplatelet standar adalah asetosal, yang
digunakan dalam dosis yang lebih rendah 75-300 mg per hari (Heinrich, dkk.,
2009).
Selain asetosal bahan makanan seperti nanas juga memiliki efek
antiplatelet, di Indonesia nanas ditanam di kebun-kebun, perkarangan rumah,
dan tempat- tempat yang cukup mendapat sinar matahari pada ketinggian 1-1300
meter di atas permukaan laut. Buah nanas rasanya enak, asam sampai manis, dan
dapat digunakan untuk memberi cirta rasa (Yuniarti, 2008).
Buah nanas dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kulit buah, daging
buah dan hati buah. Salah satu fungsi buah nanas adalah melangsingkan tubuh
manusia, dengan cara meluruhkan timbunan lemak yang berlebihan. Buah nanas
mengandung senyawa kimia yang bervariasi konsentrasinya tergantung daerah
pertumbuhan, kondisi sebelum panen dan sesudah panen. Buah nanas
mengandungvitamin dan mineral, diantaranya vitamin A, vitamin C, kalsium,
fosfor, magnesium, besi, natrium, kalium, dekstrosa, sukrosa, dan enzim
bromelain (Dalimartha, 2000; Yuniarti, 2008; Anonim, 2009).
Masyarakat memanfaatkan buah nanas untuk berbagai macam obat
tradisional. Pada penelitian terdahulu menurut Caesarita (2011), ekstrak air buah
nanas dapat digunakan sebagai penghambat bakteri Staphylococcus aureus dan
antifungi (Daniswara, 2008). Bromelin merupakan suatu enzim golongan
protease yang dihasilkan dari ekstraksi air buah nanas yang dapat mendegradasi
menghambat penggumpalan platelet (agregasi platelet), dan mempunyai
aktivitas fibrinolitik (Bhattacharyya, 2008; Dalimartha, 2000; Maurer, 2001;
Uma, dkk., 2012; Yuniarti, 2008). Penelitian sebelumnya telah meneliti efek
antiagregasi platelet ekstrak air buah nanas (Metzig, dkk., 1999). Karena itu
peneliti tertarik untuk melakukan uji efek antiagregasi platelet pada buah nanas
dengan ekstrak etanol sebagai pelarut polar dan non polar, dan dengan
menggunaan etanol 96% sebagai pelarut akan mempermudah dalam proses
1.2 Krangka Pikir Penelitian
Adapun krangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.1:
Gambar 1.1 Skema kerangka pikir penelitian
1.3 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian adalah:
a. apakah karakteristik simplisia buah nanas memenuhi persyaratan
simplisia dan apakah dengan melakukan karakterisasi ekstrak etanol
buah nanas dapat diperoleh karakteristik ekstrak etanol buah nanas.
b. apakah golongan senyawa kimia yang terkandung dalam simplisia dan
ekstrak etanol buah nanas.
c. apakah ekstrak etanol buah nanas mampu memperlama waktu
perdarahan mencit putih jantan.
d. apakah ekstrak etanol buah nanas mampu memperlama waktu koagulasi
darah mencit putih jantan.
1.4 Hipotesis
Berdasarkan perumusan masalah di atas maka hipotesis penelitian adalah:
a. karakteristik simplisia buah nanas memenuhi persyaratan simplisia dan
karakteristik ekstrak etanol buah nanas dapat diperoleh dengan
karakterisasi ekstrak etanol buah nanas.
b. golongan senyawa kimia yang terdapat dalam simplisia dan ekstrak
etanol buah nanas adalah flavonoid, glikosida, saponin,
steroid/triterpenoid.
c. ekstrak etanol buah nanas mampu memperlama waktu perdarahan mencit
putih jantan.
d. ekstrak etanol buah nanas mampu memperlama waktu koagulasi darah
1.5 Tujuan Penelitian
Berdasarkan hipotesis di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk:
a. mengetahui karakteristik simplisia buah nanas dan karakteristik ekstrak
etanol buah nanas.
b. mengetahui golongan senyawa kimia yang terkandung dalam simplisia
dan ekstrak etanol buah nanas.
c. mengetahui waktu perdarahan mencit putih jantan setelah diberikan
ekstrak etanol buah nanas.
d. mengetahui waktu koagulasi darah mencit putih jantan setelah diberi
ekstrak etanol buah nanas.
1.6 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk:
a. memberikan informasi karakteristik simplisia dan ekstrak etanol buah
nanas, serta golongan senyawa kimia yang terkandung di dalamnya.
b. memberikan informasi tentang efek antiagregasi platelet dari ekstrak
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Uraian Tanaman Nanas
Di Indonesia, nanas ditanam di kebun-kebun, pekarangan, dan
tempat-tempat lain yang cukup mendapat sinar matahari pada ketinggian 1- 1.300 meter
di atas permukaan laut. Nanas merupakan tanaman buah yang selalu tersedia
sepanjang tahun. Herbal tahunan atau dua tahunan, terdapat tunas merayap pada
bagian pangkalnya. Daun berkumpul pada roset akar dan pada bagian
pangkalnya melebar menjadi pelepah. Helaian daun berbentuk pedang, tebal,
liat, ujung lancip menyerupai duri, tepi berduri tempel yang membengkok ke
atas, sisi bawah bersisik putih, berwarna hijau atau hijau kemerahan. Bunga
majemuk tersusun dalam bulir yang sangat rapat, letaknya terminal dan
bertangkai panjang. Buahnya bulat panjang, berdaging, berwarna hijau, jika
masak warna menjadi kuning. Buah nanas rasanya enak, asam sampai manis.
Buahnya selain dimakan secara langsung, bisa juga diawetkan dengan cara
direbus dan diberi gula, dibuat selai, atau sirup. Kandungan kimia buah nanas
adalah vitamin A dan vitamin C, kalsium, fosfor, magnesium, besi, natrium,
kalium, dekstrosa, sukrosa, dan enzim bromelain (Dalimartha, 2000; Yuniarti,
2008).
2.2 Efek Farmakologi Tumbuhan
Menurut Dalimartha (2000), Buah nanas berkhasiat mengurangi keluarnya
antiradang, peluruh kencing (diuretik), peluruh haid, membersihkan jaringan
kulit yang mati, mengganggu pertumbuhan sel kanker, menghambat
penggumpalan trombosit (agregasi platelet), dan mempunyai aktivitas
fibrinolitik. Masyarakat memanfaatkan buah nanas untuk berbagai macam obat
tradisional. Pada penelitian terdahulu menurut Casearita (2011) ekstrak air buah
nanas dapat digunakan sebagai penghambat bakteri Staphylococcus aureus,
antifungi (Daniswara, 2008). Bromelin merupakan suatu enzim golongan
protease yang dihasilkan dari ekstraksi air buah nanas yang dapat mendegradasi
kolagen daging, sehingga dapat mengempukkan daging (Utami, dkk., 2011),
menghambat penggumpalan trombosit (agregasi platelet), dan mempunyai
aktivitas fibrinolitik (Maurer, 2001; Dalimartha, 2000; Bhattacharyya, 2008;
Yuniarti, 2008; Uma, dkk., 2012).
2.3 Ekstraksi
Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut
sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair (Depkes
RI., 2000).
Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat
aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai,
kemudian pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan
sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Depkes RI., 1995).
Jenis ekstraksi yang tepat sudah tentu bergantung pada tekstur dan
kandungan air bahan tumbuhan yang diekstraksi dan pada jenis senyawa yang
pendahuluan. Bahan dapat dimaserasi dalam pelarut, kemudian disaring
(Harborne, 1987).
Proses awal pembuatan ekstrak adalah tahapan pembuatan serbuk
simplisia kering (penyerbukan). Dari simplisia dibuat serbuk simplisia dengan
peralatan tertentu sampai derajat kehalusan tertentu (Depkes RI., 2000).
Selanjutnya ekstraksi dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti maserasi,
perkolasi, sokletasi, refluks, infus, digesti, dekok dengan menggunakan pelarut
yang sesuai (Anief, 2000; Depkes RI., 2000; Syamsuni, 2006).
a. maserasi
Maserasi adalah suatu cara penyarian simplisia dengan cara merendam
simplisia tersebut dalam pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau
pengadukan pada temperatur kamar.
b. perkolasi
Perkolasi adalah suatu cara penyarian simplisia menggunakan perkolator
dimana simplisianya terendam dalam pelarut yang selalu baru dan umumnya
dilakukan pada temperatur kamar. Prosesnya terdiri dari tahapan pengembangan
bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan dan
c. refluks
Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya
dalam jangka waktu tertentu dimana pelarut akan terkondensasi menuju
pendingin dan kembali kelabu.
d. sokletasi
Sokletasi adalah ekstraksi kontinu menggunakan alat soklet, dimana
pelarut akan terkondensasi dari labu menuju pendingin, kemudian jatuh
membasahi sampel dan mengisi bagian tengah alat soklet. Tabung sifon juga
terisi dengan larutan ekstraksi dan ketika mencapai bagian atas tabung sifon,
larutan tersebut akan kembali ke dalam labu.
e. digesti
Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada
temperatur yang lebih tinggi dari temperatur kamar, umumnya dilakukan pada
suhu 40-60oC.
f. infus
Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur 90oC selama 15
menit.
g. dekok
Dekok adalah ekstraksi pada suhu 90oC menggunakan pelarut air selama
2.4 Platelet
Platelet disebut juga trombosit berbentuk cakram kecil dengan diameter 1
sampai 4 mikrometer. Trombosit dibentuk di sumsum tulang dari megakariosit,
yaitu sel yang sangat besar dalam susunan hematopoietik dalam sumsum,
megakariosit pecah menjadi trombosit kecil, baik disumsum tulang atau segera
setelah memasuki darah, khususnya ketika memasuki kapiler. Kosentrasi normal
trombosit dalam darah adalah antara 150.000 dan 300.000 per mikroliter.
Membran sel trombosit juga penting di permukaannya terdapat lapisan
glikoprotein yang mencegah pelekatan dengan endotel normal dan justru
menyebabkan pelekatan dengan daerah dinding pembuluh yang cedera, terutama
pada sel-sel endotel yang cedera, dan bahkan melekat pada jaringan yang
terbuka di bagian dalam pembuluh. Selain itu membran platelet mengandung
banyak fosfolipid yang mengaktifkan berbagai mediator pada proses pembekuan
darah. Trombosit merupakan struktur yang aktif. Waktu paruh hidupnya dalam
darah 8 sampai 12 hari, jadi setelah beberapa minggu setelah tugas
fungsionalnya berahir, trombosit itu kemudian diambil dari sirkulasi, terutama
oleh sistem makrofak jaringan. Lebih dari separuh trombosit diambil oleh
makrofag dalam limpa, yaitu pada waktu darah melewati kisi-kisi trabekula yang
rapat (Guyton dan Hall, 2007).
Menurut Mutschler (1991), di dalam platelet ini terdapat sejumlah granul,
yang di dalamnya terdapat antara lain faktor pembeku darah. Fungsinya adalah:
b. zat mediator yang dibebaskan dari platelet, terutama tromboksan A2,
menyebabkan vasokonstriksi yang cepat dalam daerah pembuluh yang
terluka.
c. dengan hancurnya platelet akan dibebaskan faktor platelet, yang bersama
dengan faktor plasma akan menyebabkan pembekuan. Merangsang penarikan
(retraksi) gumpalan darah.
Platelet memberikan respon pada trauma vaskular karena proses aktivasi
yang menyangkut 3 tahap yaitu: adesi pada sisi luka, pelepasan granul
intraselular, dan agregasi trombosit, peran platelet membetuk trombus dapat
dilihat pada Gambar 2.1.
Gambar 2.1 Peran platelet membentuk trombus (Groos dan Weitz, 2009).
Secara normal, trombosit beredar dalam darah dalam bentuk tidak aktif,
tetapi menjadi aktif karena berbagai rangsangan (Mycek, dkk., 2001), disamping
itu platelet juga merapatkan celah-celah pembuluh pada daerah yang tak terluka
di dalam kapiler. Karena platelet juga mempunyai kemampuan fagositosis,
sehingga berperan pada proses pertahanan tubuh organisme (Mutschler, 1991).
Fungsi platelet darah diatur oleh tiga kategori substansi. Kelompok
pertama terdiri atas agen-agen yang dibentuk diluar platelet yang berinteraksi
thrombin dan prostacyclin. Kategori kedua terdiri atas agen-agen yang dibentuk
di dalam platelet yang berinteraksi dengan reseptor-reseptor membran, misalnya,
ADP, Prostaglandin D2, Prostglandin E2, dan serotonin. Kategori ketiga terdiri
atas agen-agen yang dibentuk di dalam platelet yang bekerja di dalam platelet,
misalnya, prostglandin endoperoxide dan thromboxane A2,
nukleotida-nukleotida siklis cAMP dan cGMP, dan ion kalsium. Dari daftar agen-agen ini
beberapa target obat-obat penghambat platelet telah diidentifiksikan:
penghambat metabolisme prostaglandin seperti asetosal, penghambat agregasi
platelet yang diinduksi ADP seperti clopidogrel, ticlopidine, dan penyakatan
reseptor-reseptor GP IIb/IIIa pada platelet-platelet seperti abciximab, tirofiban,
dan eptifibatide (Katzung, 2002).
2.4.1 Aktivasi Platelet
Menurut Mycek, dkk., (2001), membran luar platelet mengandung
berbagai reseptor yang berfungsi sebagai sensor peka atas sinyal-sinyal
fisiologik yang ada dalam plasma. Reseptor yang terdapat di membran dapat
dirangsang oleh sinyal-sinyal kimia tertentu. Rangsangan sinyal kimia ini dibagi
menjadi dua golongan, pertama digolongkan sebagai aktivasi platelet, yang
memacu agregasi platelet dan seterusnya melepaskan granul yang berada dalam
platelet. Sementara golongan yang ke dua digolongkan sebagai penghambat
platelet, yang menghambat agregasi pletelet dan pelepasan granul yang berada
dalam platelet. Sinyal kimia inilah yang menentukan apakah platelet tetap dalam
keadaan tenang atau menjadi aktif.
i. peningkatan kadar protasiklin: Dalam pembuluh yang normal dan tidak
rusak, platelet bergerak bebas, karena keseimbangan sinyal kimia
menunjukkan sistem vaskular tidak mengalami kerusakan. Sebagai
contoh prostasiklin, dibentuk oleh sel endotel yang intak dan dilepaskan
ke dalam plasma, terikat pada reseptor membran spesifik platelet yang
bergabung dengan sintesis siklik adenosin monofosfat (cAMP) sebagai
masenjer intraseluler. Peningkatan kadar cAMP intraseluler
menghammbat aktivitas platelet dan pelepasan zat agregasi platelet.
ii. penurunan kadar trombin dan tromboksan plasma: Membran pletelet
mengandung reseptor yang dapat mengikat trombin, tromboksan dan
kolagen lepas. Jika terisi, tiap jenis reseptor ini akan memacu sejumlah
reaksi yang menyebabkan lepasnya granula intraselular ke dalam
sirkulasi sehingga terjadi agregasi platelet. Namun, pada pembuluh
normal yang intak, kadar trombin dan tromboksan yang beredar rendah
dan endotel yang intak menutup kolagen yang ada dalam lapisan
subendotel, akibatnya reseptor platelet yang bersangkutan akan kosong
dan tetap tidak aktif. Dengan demikian aktivitas platelet dan agregasi
tidak terjadi.
b. Sinyal kimia yang memacu agregasi platelet antara lain adalah:
i. penurunan kadar prostasiklin: Sel-sel endotel yang rusak akan
menghasilkan prostasiklin lebih sedikit, yang menyebabkan pengurangan
platelet berkurang. Sehingga kadar cAMP intraseluler yang rendah
menyebabkan agregasi platelet.
ii. kolagen terekspos: Dalam beberapa detik setelah kerusakan vaskular,
platelet melengket dan menutupi kolagen subendotel. Reseptor pada
permukaan platelet diaktifkan oleh kolagen jaringan ikatan yang
mendasari, yang memacu pelepasan granula platelet berisi ADP dan
serotonin. Proses ini kadang-kadang disebut sebagai reaksi pelepasan
platelet, dan platelet tersebut selanjutnya diaktifkan. Reseptor fibrinogen
terdapat pada permukaan platelet dan kemudian firinogen akan bekerja
sebagai jembatan antara kedua platelet dapat dilihat pada Gambar 2.2.
iii. peningkatan sintesis tromboksan: Stimulasi platelet oleh trombin,
kolagen dan ADP menyebabkan aktivitas enzim fosfolipase membran
platelet, yang membebaskan asam arakidonat dan fosfolipid membran.
Asam arakidonat pertama diubah menjadi prostaglandin H2 oleh
siklooksigenase, suatu enzim yang dinonaktifkan oleh aspirin secara
ireversibel. Prostaglandin H2 dimetabolisme menjadi tromboksan A2,
yang dilepaskan ke dalam plasma. Tromboksan A2 yang dihasilkan akan
menempel pada reseptor platelet lain sehingga terjadi agregasi platelet,
yang selanjutnya memacu proses penyumbatan dan penting untuk
pembentukan sumbatan hemostatik secara cepat dapat dilihat pada
Gambar 2.2 Proses agregat platelet pada pembuluh darah (Fitzakerley, 2012).
2.5 Bentuk Pembekuaan Darah di Dalam Tubuh
Menurut Harahap dan Sumadio (1995) ada dua bentuk pembekuan darah
di dalam tubuh, yaitu trombus dan embolus. Trombus adalah pembekuan darah
yang melekat pada dinding pembuluh darah, hal ini terjadi terutama disebabkan
adanya inflamasi (kerusakan) saluran darah. Sudiono dan Yuwono (2003)
mengatakan, trombus merupakan benda padat yang terdiri dari unsur-unsur
(elemen) darah di dalam pembuluh darah atau jantung sewaktu masih hidup,
unsur-unsur darah ini adalah platelet, fibrin, eritrosit dan leukosit. Proses
pembentukan trombus disebut trombosis. Sedangkan embolus adalah pecahnya
trombus yang dapat menyumbat saluran darah kecil yang mengakibatkan
penghambatan aliran darah atau sering disebut embolisme. Embolisme
pulmonari adalah emboli yang terjadi pada pembuluh darah pulmonari (Harahap
dan Sumadio, 1995). Trombus dan embolus ini berbahaya karena dapat
menyumbat pembuluh dan jaringan akan mengalami kekurangan oksigen dan
2.5.1 Proses Pembentukan Bekuan Darah
Normalnya, darah yang mengalir tetap cair karena terdapat keseimbangan
tertentu yang sangat komplek. Pada keadaan tertentu, keseimbangan ini dapat
terganggu sehingga terjadi trombosis. Pembentukan trombus dimulai dengan
melekatnya platelet-platelet pada perrmukaan endotel pembuluh darah atau
jantung. Jika terjadi suatu kerusakan pada platelet, akan dilepaskan suatu zat
tromboplastin. Zat inilah yang akan merangsang proses pembentukan beku
darah. Tromboplastin akan mengubah protrombin yang terdapat didalam darah
menjadi trombin, yang kemudian bereaksi dengan fibrinogen menjadi fibrin.
Fibrin seperti jala yang menahan eritrosit dan leukosit, selain itu trombin juga
menyebabkan pecahnya platelet sehingga terbentuk lebih banyak tromboplastin.
Dengan adanya darah yang mengalir melalui tempat itu, faktor-faktor
pembekuan yang dikeluarkan platelet akan terbawa oleh aliran darah sehingga
tidak terjadi proses pembekuan pada tempat itu, tetapi hanya terjadi suatu
trombus (Sudiono dan Yuwono, 2003). Menurut Dewoto (2008), terjadinya
proses pembentukan bekuan darah ini dikarenakan beberapa faktor, diantanya
adalah faktor pembuluh darah, faktor platelet dan faktor pembekuan darah.
2.6 Antiplatelet (Antitrombotik) dan Trombolitik (Fibrinolitik)
Platelet menjadi sumbat hemostasis awal di tempat perlukaan pembuluh
darah, selain itu platelet berperan pada pembentukan trombus. Obat yang
digunakan untuk mencegah dan pengobatan tromboemboli adalah golongan
antikoagulan, antitrombosit dan trombolitik. Antikoagulan digunakan untuk
agregasi trombosit sehingga dapat menyebabkan terhambatnya pembentukan
trombus yang terutama sering ditemukan pada sistem arteri. Trombolitik berbeda
dengan antikoagulan yang mencegah terbentuk dan meluasnya tromboemboli,
trombolitik melarutkan trombus yang sudah terbentuk (Dewoto, 2008).
2.6.1 Antiplatelet (antitrombotik)
Penghambat agregasi platelet untuk mengurangi pembentukan agregat
dilakukan dengan cara menghambat aktivasi platelet dengan berbagai cara, yaitu
menghambat pembentukan TXA2 dan pemberian antagonis resepor-reseptor
yang ada di membran platelet, yang dapat dilihat pada Gambar 2.3.
Gambar 2.3 Cara penghambatan agregasi platelet (Groos dan Weitz, 2009).
Zat-zat ini terbukti dalam mencegah dan mengobati penyakit
kardiovaskular oklusif, mempertahankan cangkok vaskular dan keutuhan arteri,
antikoagulan kurang berguna dalam pencegahan trombosis arteri. Karena dalam
pembuluh darah yang memiliki aliran lebih cepat. Trombus terutama terdiri dari
platelet dengan sedikit fibrin. Obat platelet mengurangi agregasi platelet dan
trombosis arteri. Pada arteri dengan ateroma, plak yang sangat mungkin
fibrosa tipis. Rupturnya selubung tersebut membuat kolagen subendotel terpapar
sehingga mengaktivasi platelet dan menyebabkan agregasi. Keadaan tersebut
melepaskan tromboksan A2 (TXA2), Adenosin difosfat (ADP), dan
5-hidroksitriptamin (5HT) menyebabkan agregasi platelet selanjutnya,
vasokontriksi, dan aktivasi kaskade pembekuan. Obat antiplatelet, khususnya
asetosal, telah terbukti dapat mengurangi risiko infark miokard pada pasien
dengan angina tidak stabil, meningkatkan ketahanan hidup pasien yang pernah
mengalami infark miokard, dan menurunkan risiko stroke pada pasien dengan
serangan iskemik sementara ( Mycek, dkk., 2001; Neal, 2006).
Peristiwa yang menjadi kunci pada aktivasi dan agregasi platelet adalah
peningkatan kalsium sitoplasma. Hal ini menyebabkan perubahan konformasi
reseptor GPIIb/IIIa inaktif pada membran plasma menjadi reseptor yang
memiliki afinitas yang tinggi terhadap fibrinogen, yang membentuk ikatan silang
di antara platelet, dan menyebabkan agregasi. TXA2, trombin, dan 5HT
mengaktivasi fosfolipase C, dan inositol-1,4,5-trisfosfat (InsP3) yang dihasilkan
menstimulasi pelepasan kalsium dari retikulum endoplasma. ADP menghambat
adenilat siklase dan penurunan adenosin monofosfat siklik (cAMP)
meningkatkan kalsium sitoplasma kembali. Semua obat antiplatelet bekerja satu
arah untuk menghambat jalur aktivasi platelet yang tergantung kalsium (Neal,
2006).
Tromboemboli merupakan salah satu penyebab sakit dan kematian yang
misalnya trauma, kebiasaan merokok, pembedahan, kehamilan atau akibat
obat-obat yang mengandung estrogen (Dewoto, 2008).
Aspirin menghambat sintesis tromboksan A2 (TXA2) di dalam platelet dan
protasiklin (PGI2) di pembuluh darah dengan menghambat secara ireversibel
enzim siklooksigenase terjadi karena aspirin mengasetilasi enzim tersebut,
aspirin dosis kecil hanya dapat menekan pembentukan TXA2, sebagai
antitrombotik dosis efektif aspirin 80-320 mg perhari (Dewoto, 2008). TXA2
merupakan penginduksi kuat agregasi platelet, sel endotel dinding pembuluh
darah menghasilkan prostglandin, PGI2 (Prostasiklin), yang kemungkinan
merupakan antagonis fisiologis dari TXA2. PGI2 menstimulasi reseptor yang
berbeda pada platelet dan mengaktivasi adenilat siklase. Peningkatan cAMP
yang terjadi kemudian berhubungan dengan penurunan kalsium intraseluler dan
inhibisi agregasi platelet (Neal, 2006).
2.6.2 Trombolitik (Fibrinolitik)
Menurut Majerus dan Tollefsen (2008), terapi obat trombolitik
(fibrinolitik) cenderung melarutkan trombus, sistem fibrinolitik melarutkan
bekuan darah intravaskular sebagai hasil kerja plasmin, yakni suatu enzim yang
mencerna fibrin. Plasminogen, suatu prekursor yang tidak aktif, diubah menjadi
plasmin dengan pemutusan ikatan peptida tunggal. Plasmin merupakan suatu
protease yang relatif nonspesifik, senyawa ini mencerna bekuan fibrin dan
protein plasma lainnya, termasuk beberapa faktor koagulan. Dipasaran terdapat
plasmin aktivator seperti jaringan plasmin aktivtor(t-PA), Streptokinase,
Menurut Mycek, dkk., (2001), sifat-sifat umum obat trombolitik dapat
dilihat seperti dibawah ini:
a. kerja: Obat-obat trombolitik mempunyai sifat-sifat yang sama. Semua
bekerja langsung atau tidak mengubah plasminogen menjadi plasmin yang
selanjutnya mencairkan fibrin sehingga melarutkan trombus. Dalam setiap
kasus, pelarutan dan reperfusi bekuan sering terjadi jika terapi dimulai lebih
awal setelah pembentukan bekuan, karena bekuan akan menjadi lebih
resisten untuk lisis jika semakin lama. Trombin lokal yang meningkat dapat
terjadi jika melarutnya bekuan, sehingga menyebabkan agregasi platelet
meningkat dan terjadi trombosis. Cara yang dilakukan untuk mencegah hal
ini adalah dengan pemberian obat antiplatelet seperti aspirin.
b. pemberian obat: Untuk infark miokard, pemberian obat intrakoroner paling
dipercaya untuk mencapai rekanalisasi. Namun, kateterisasi jantung
mungkin tidak dapat dilakukan dalam 2-6 jam, dan jika melewati waktu
tersebut pertolongan miokard yang penting tidak mungkin lagi. Sebab itu,
obat trombolitik biasanya diberikan inravena, karena cara ini cepat, tidak
mahal dan tidak mempunyai risiko kateterisasi.
c. penggunaan dalam terapi: semua digunakan untuk pengobatan trombosis
vena profunda dan embolisme paru berat, obat trombolitik sekarang
digunakan lebih sering untuk mengobati infark miokard akut dan trombosis
arteri perifer dan emboli untuk menghindari pembekuan dalam kateter dan
efek samping: obat-obat trombolitik tidak membedakan fibrin trombus yang
tidak diinginkan dan fibrin sumbatan hemostatik yang menguntungkan. Karena
itu, perdarahan merupakan efek samping utama. Misalnya, suatu lesi yang
semula tidak berbahaya, seperti ulkus peptikum, dapat mengalami perdarahan
setelah suntikan obat trombolitik. Obat-obat ini merupakan kontraindikasi untuk
BAB III
METODE PENELITIAN
Metode pada penelitian ini adalah penelitian eksperimental. Penelitian
eksperimen (eksperimental) bertujuan untuk mencari pengaruh variabel tertentu
terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol. Penelitian ini meliputi
pengumpulan bahan tumbuhan, identifikasi sampel, pembuatan simplisia,
karekterisasi simplisia, pembuatan ekstrak etanol nanas, karekterisasi ekstrak
etanol nanas, penyiapan hewan percobaan, pengujian efek antiagregasi platelet
dengan menentukan waktu perdarahan dan waktu koagulasi menggunakan
rancangan acak lengkap (RAL). Analisis data berdasarkan metode analisis
variasi (ANAVA) dengan tingkat kepercayaan 99%, untuk melihat perbedaan
nyata antara perlakuan menggunakan program SPSS (Statistical Product and
Service Solution).
3.1 Alat-alat
Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat-alat gelas, pisau
dapur, kertas perkamen, neraca kasar, neraca listrik, rotary evaporator, spuit,
oral sonde, oven, pipet kapiler, stopwach, kertas saring, silet, dan pinset.
3.2 Bahan
Bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah buah nanas segar, α
-naftol, amil alkohol, asam asetat anhidridat, asam klorida pekat, asam nitrat
pekat, asam sulfat pekat, besi (III) klorida, bismut (III) nitrat, iodium,
sulfat anhidrat, raksa (II) klorida, serbuk magnesium, timbal (II) asetat, toluena,
etanol 96%, tablet asetosal (Aspilets®), CMC Na dan aquades.
3.3 Hewan Percobaan
Hewan percobaan yang digunakan untuk penelitian ini adalah mencit putih
(Mus musculus) jantan berumur 2-3 bulan dan bobot badan 25-35 g yang didapat
dari Laboratorium Farmakologi, Fakultas Farmasi, Universitas Sumatra Utara.
Medan.
3.4 Pengumpulan dan Pengolahan Sampel
3.4.1 Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel dilakukan secara purposif tanpa membandingkan
dengan tumbuhan yang sama dari daerah lain. Sampel diambil dari Pasar
tradisional Melati Sunggal di Kota Medan.
3.4.2 Identifikasi Tanaman
Identifikasi tanaman buah nanas dilakukan oleh Herbarium Medanense
(Meda), Universitas Sumatera Utara, Medan.
3.4.3 Pengolahan Sampel
Buah nanas dibersihkan dengan air hingga bersih kemudian bagian daging
nanas dipisahkan dari kulitnya, lalu dagingnya dipotong-potong, ditimbang, lalu
diangin-anginkan selama 1 hari, selanjutnya dikeringkan di lemari pengering
dengan suhu 30-40oC, setelah kering buah nanas diserbukan dan ditimbang
3.5 Pembuatan Ekstrak Etanol Buah Nanas (EEBN)
Serbuk simplisia dimaserasi dengan etanol, dilakukan dengan cara 10
bagian simplisia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan kedalam bejana,
kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan etanol, ditutup dan dibiarkan selama
5 hari terlindung dari cahaya, sambil berulang-ulang diaduk. Setelah 5 hari sari
diserkai (saring), ampas diperas. Ampas ditambah cairan penyari secukupnya
diaduk dan diserkai, sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian.
Bejana ditutup, dibiarkan ditempat sejuk, terlindung dari cahaya, selama 2 hari.
Kemudian endapan dipisahkan. Hasil maserat yang diperoleh dikumpulkan dan
dipekatkan dengan bantuan alat rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak
etanol (Depkes RI., 1986).
3.6 Karakterisasi Simplisia Buah Nanas
Pemeriksaan karakteristik simplisia ini meliputi pemeriksaan penetapan
kadar air, penetapan kadar sari larut dalam air, penetapan kadar sari larut dalam
etanol, penetapan kadar abu total, dan penetapan kadar abu tidak larut dalam
asam (WHO, 1998; Depkes RI., 1995).
3.6.1 Penetapan Kadar Air
Penetapan kadar air dilakukan menurut metode Azeotropi (destilasi
toluena) (WHO, 1998).
Cara kerja:
Dimasukkan 200 ml toluena dan 2 ml air suling ke dalam labu alas bulat,
lalu didestilasi selama 2 jam. Setelah itu, toluena dibiarkan mendingin selama 30
Kemudian ke dalam labu tersebut dimasukkan 5 g serbuk simplisia yang telah
ditimbang seksama, labu dipanaskan hati-hati selama 15 menit. Setelah toluena
mendidih, kecepatan tetesan diatur lebih kurang 2 tetes tiap detik sampai
sebagian besar air terdestilasi, kemudian kecepatan tetesan dinaikkan hingga 4
tetes tiap detik. Setelah semua air terdestilasi, bagian dalam pendingin dibilas
dengan toluena. Destilasi dilanjutkan selama 5 menit, kemudian tabung
penerima dibiarkan mendingin pada suhu kamar. Setelah air dan toluena
memisah sempurna, volume air dibaca dengan ketelitian 0,05 ml. Selisih kedua
volume air yang dibaca sesuai dengan kandungan air yang terdapat dalam bahan
yang diperiksa. Kadar air dihitung dalam persen (WHO, 1998; Depkes RI.,
1995).
3.6.2 Penetapan Kadar Sari Larut dalam Air
Sebanyak 5 g serbuk yang telah dikeringkan, dimaserasi selama 24 jam
dalam 100 ml air-kloroform (2,5 ml kloroform dalam air suling sampai 1 liter)
dalam labu bersumbat sambil dikocok sesekali selama 6 jam pertama, kemudian
dibiarkan selama 18 jam, lalu disaring. Sejumlah 20 ml filtrat pertama diuapkan
sampai kering dalam cawan penguap yang berdasar rata yang telah ditara dan
sisa dipanaskan pada suhu 105oC sampai bobot tetap. Kadar dalam persen sari
yang larut dalam air dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan (Depkes
RI., 1979).
3.6.3 Penetapan Kadar Sari Larut dalam Etanol
Sebanyak 5 g serbuk yang telah dikeringkan, dimaserasi selama 24 jam
6 jam pertama, kemudian dibiarkan selama 18 jam. Kemudian disaring cepat
untuk menghindari penguapan etanol. Sejumlah 20 ml filtrat diuapkan sampai
kering dalam cawan penguap yang berdasar rata yang telah dipanaskan dan
ditara. Sisa dipanaskan pada suhu 105oC sampai bobot tetap. Kadar dalam
persen sari yang larut dalam etanol 96% dihitung terhadap bahan yang telah
dikeringkan (Depkes RI., 1979).
3.6.4 Penetapan Kadar Abu Total
Sebanyak 2 g serbuk yang telah digerus dan ditimbang seksama
dimasukkan dalam krus porselin yang telah dipijar dan ditara, kemudian
diratakan. Krus dipijar perlahan-lahan sampai arang habis, pijaran dilakukan
pada suhu 600oC selama 3 jam kemudian didinginkan dan ditimbang sampai
diperoleh bobot tetap. Kadar abu dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan
(Depkes RI., 1979).
3.6.5 Penetapan Kadar Abu Tidak Larut dalam Asam
Abu yang diperoleh dalam penetapan kadar abu dididihkan dalam 25 ml
asam klorida encer selama 5 menit, bagian yang tidak larut dalam asam
dikumpulkan, disaring melalui kertas saring, dipijarkan, kemudian didinginkan
dan ditimbang sampai bobot tetap. Kadar abu yang tidak larut dalam asam
dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan (Depkes RI., 1979).
3.7 Karakterisasi Ekstrak Etanol Buah Nanas (EEBN)
Karakterisasi Ekstrak Etanol Buah Nanas yang dilakukan adalah:
a. penetapan kadar air
c. penetapan kadar sari larut dalam etanol
d. penetapan kadar abu total
e. penetapan kadar abu tidak larut dalam asam
adapun cara kerja dari penetapan kadar ini, dilakukan sama seperti cara kerja
pada karakterisasi simplisia.
3.8 Skrining Fitokimia Simplisia Buah Nanas
Skrining fitokimia meliputi pemeriksaan senyawa golongan alkaloid,
flavonoid, glikosida (Depkes RI., 1979), saponin (Depkes RI., 1979; Farnsworth,
1966), tanin dan triterpenoid/steroid (Farnsworth, 1966).
3.8.1 Pemeriksaan Alkaloid
Serbuk simplisia ditimbang sebanyak 0,5 g kemudian ditambahkan 1 ml
asam klorida 2 N dan 9 ml air suling, dipanaskan di atas penangas air selama 2
menit, didinginkan dan disaring. Filtrat yang diperoleh dipakai untuk tes
alkaloid. Diambil 3 tabung reaksi, lalu ke dalamnya dimasukkan 0,5 ml filtrat.
Pada masing-masing tabung reaksi:
a. ditambahkan 2 tetes pereaksi Mayer
b. ditambahkan 2 tetes pereaksi Bouchardat
c. ditambahkan 2 tetes pereaksi Dragendorff.
Alkaloid positif jika terjadi endapan atau kekeruhan pada dua dari tiga
percobaan diatas.
3.8.2 Pemeriksaan Flavonoid
Serbuk simplisia ditimbang 10 g, lalu ditambahkan 10 ml air panas,
ditambahkan 0,1 g serbuk magnesium dan 1 ml asam klorida pekat dan 2 ml
amil alkohol. Dikocok dan dibiarkan memisah. Flavonoid positif jika terjadi
warna merah atau kuning atau jingga pada lapisan amil alkohol.
3.8.3 Pemeriksaan Glikosida
Serbuk simplisia ditimbang sebanyak 3 g, lalu disari dengan 30 ml
campuran etanol 96%-air (7:3) dan 10 ml asam klorida 2 N, direfluks selama 2
jam, didinginkan dan disaring. Diambil 20 ml filtrat, ditambahkan 25 ml air
suling dan 25 ml timbal (II) asetat 0,4 M, dikocok, didiamkan selama 5 menit,
lalu disaring. Filtrat disari dengan 20 ml campuran kloroform-isopropanol (3:2)
sebanyak 3 kali. Pada kumpulan sari ditambahkan natrium sulfat anhidrat,
disaring, dan diuapkan pada suhu tidak lebih dari 50oC. Sisanya dilarutkan
dengan 2 ml metanol.
Larutan sisa digunakan untuk percobaan berikut:
a. diuapkan 0,1 ml larutan percobaan diatas penangas air, pada sisa
ditambahkan pereaksi Liebermann-Bouchardat, terjadi warna biru atau hijau
yang menunjukkan adanya glikosida.
b. dimasukkan 0,1 ml larutan percobaan dalam tabung reaksi, diuapkan di atas
penangas air. Pada sisa ditambahkan 2 ml air dan 5 tetes pereaksi molish.
Ditambahkan hati-hati 2 ml asam sulfat pekat, terbentuk cincin berwarna
ungu pada batas cairan menunjukkan adanya ikatan gula.
c. percobaan terhadap gula pereduksi yaitu sampel disari dengan cara merebus
fehling B sama banyak kemudian dipanaskan, terbentuk endapan berwarna
merah bata menunjukkan adanya gula pereduksi.
3.8.4 Pemeriksaan Saponin
Serbuk simplisia ditimbang sebanyak 0,5 g dan dimasukkan ke dalam
tabung reaksi, lalu ditambahkan 10 ml air panas, didinginkan, kemudian dikocok
kuat-kuat selama 10 menit. Jika terbentuk busa setinggi 1-10 cm yang stabil
tidak kurang dari 10 menit dan tidak hilang dengan penambahan 1 tetes asam
klorida 2 N menunjukkan adanya saponin.
3.8.5 Pemeriksaan Tanin
Serbuk simplisia ditimbang sebanyak 1 g, dididihkan selama 3 menit
dalam air suling lalu didinginkan dan disaring. Pada filtrat ditambahkan 1-2 tetes
pereaksi besi (III) klorida 1% b/v. Jika terjadi warna biru kehitaman atau hijau
kehitaman menunjukkan adanya tanin.
3.8.6 Pemeriksaan Steroid/triterpenoid
Serbuk simplisia ditimbang sebanyak 1 g, dimaserasi dengan 20 ml n
-heksan selama 2 jam, disaring. Filtrat diuapkan dalam cawan penguap dan pada
sisanya ditambahkan pereaksi asam sulfat pekat melalui dinding cawan. Apabila
terbentuk warna ungu atau merah yang berubah menjadi biru ungu atau biru
hijau menunjukkan adanya triterpenoid/steroid.
3.9 Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Buah Nanas (EEBN)
Skrining fitokimia untuk ekstrak etanol buah nanas meliputi pemeriksaan
senyawa golongan alkaloid, flavonoid, glikosida (Depkes RI., 1979), saponin
(Farnsworth, 1966). Adapun cara kerja skrining fitokimia EEBN yang
dilakukan, sama seperti skrining fitokimia yang dilakukan terhadap simplisia.
3.10Pembuatan Suspensi Bahan Uji
Sebelum dilakukan pengujian terhadap hewan percobaan, bahan uji seperti
CMC Na, asetosal dan ekstrak yang telah diperoleh dari ekstraksi buah nanas
dibuat dalam bentuk suspensi untuk diberikan secara oral pada mencit. Suspensi
adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak
larut, terdispersi dalam cairan pembawa (Depkes RI., 1979).
3.10.1 Pembuatan Suspensi Na CMC 1%
Aquadest dididihkan kemudian dimasukkan ke dalam lumpang. Na CMC
ditaburkan di atas aquadest di dalam lumpang, diamkan selama 15 menit.
Setelah Na CMC mengembang, sediaan digerus cepat hingga terbentuk masa
yang homogen dan transparan. Kemudiaan ditambahkan aquadest sedikit demi
sedikit sambil di gerus. Sediaan kemudiaan dimasukkan ke dalam labu ukur,
cukupkan volume dengan aquadest hingga didapatkan konsentrasi yang
diinginkan. Pada penelitian ini digunakan suspensi Na CMC dengan konsentrasi
1%.
3.10.2 Pembuatan Suspensi Asetosal 4 mg/ml
Tablet asetosal 80 mg/ tablet digerus, Serbuk tablet asetosal yang telah
ditimbang 80 mg tadi dimasukkan ke dalam lumpang, kemudian ditambahkan
suspensi Na CMC 1% sebanyak 20 ml dan digerus hingga merata. Sediaan
suspensi Na CMC 1% ke dalam labu hingga dicapai batas volume untuk
mendapatkan konsentrasi 4 mg/ml.
3.10.3 Pembuatan Suspensi Ekstrak Etanol Buah Nanas
Ekstrak etanol buah nanas ditimbang sesuai dengan konsentrasi yang
diinginkan. Kemudaian dimasukkan ke dalam lumpang, dan ditambahkan
suspensi Na CMC 1% lalu digerus hingga merata. Sediaan suspensi ekstrak
etanol buah nanas dimasukkan ke dalam labu ukur, kemudian ditambahkan
suspensi Na CMC 1% ke dalam labu hingga dicapai batas volume untuk
mendapatkan konsentrasi yang diinginkan.
3.11 Uji Efek Antiagregasi Platelet
Pada pengujian ini, mencit putih jantan dibagi menjadi 7 kelompok,
kelompok 1 adalah kontrol negatif (suspensi natrium karboksimetilselulosa 1%),
kelompok 2 kontrol positif (asetosal 40 mg/kg BB), kelompok 3, 4, 5, 6, 7
adalah kelompok perlakuan dengan variasi dosis. Masing-masing kelompok
terdiri atas 6 ekor mencit. Pengujian dilakukan dengan memberikan bahan uji
kepada mencit setiap hari satu kali pemberian, selama 28 hari berturut-turut
secara oral dengan menggunakan oral sonde, pada dosis 50 mg/kg BB, 100
mg/kg BB, 200 mg/kg BB, 300 mg/kg BB, 400 mg/kg BB. Parameter yang
digunakan yaitu waktu perdarahan dan waktu koagulasi yang diukur pada hari ke
7, 14, 21 dan 28 (Sukandar a, dkk., 2008).
3.11.1 Pengukuran Waktu Perdarahan
Waktu perdarahan adalah interval waktu antara timbulnya tetes pertama
Cara yang dilakukan adalah ujung ekor mencit dibersihkan dengan alkohol 70%,
lalu ekor mencit dilukai secara melintang dengan pisau pemotong yang diberi
pembatas pada jarak 2 cm dari ujung ekor, sepanjang 2 mm dan sedalam 1 mm,
darah yang keluar diserap dengan kertas penyerap dengan interval waktu 1 detik
(Sukandar b, dkk., 2008; Yasa, dkk., 2012).
3.11.2 Pengukuran Waktu Koagulasi
Waktu koagulasi adalah waktu yang diperlukan untuk terbentuknya
benang fibrin, uji ini untuk melihat perubahan fibrinogen menjadi fibrin. Cara
yang dilakukan adalah darah dari ujung ekor diserap dengan pipa kapiler selama
30 detik. Pipa kapiler dipatahkan setiap interval 15 detik, yang diamati adalah
waktu awal terbentuknya benang fibrin darah mencit pada pipa kapiler yang
telah dipatahkan dengan interval waktu pengamatan 1 detik hingga waktu
koagulasi ditentukan. Adanya efek ditunjukkan dengan semakin panjangnya
waktu koagulasi jika dibandingkan dengan kontrol negatif (Sukandar b, dkk.,
2008).
3.12 Analisis Data
Data hasi penelitian dianalisis dengan metode analisis variasi (ANAVA)
one way dengan tingkat kepercayaan 99% dan Analisis statistik ini
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Identifikasi Tanaman
Hasil identifikasi tumbuhan dilakukan di “Herbarium Medanense”
Universitas Sumatera Utara, Medan, menyebutkan bahwa tumbuhan yang
digunakan adalah tumbuhan Nanas (Ananas comusus Merr), famili
Bromeliaceae. Hasil identifikasi tumbuhan dapat dilihat pada Lampiran 1.
4.2 Karakteristik Simplisia dan Ekstrak Etanol Buah Nanas (EEBN)
Hasil karakterisasi serbuk simplisia buah nanas dan ekstrak etanol buah
nanas dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Hasil karakterisasi serbuk simplisia dan ekstrak etanol buah nanas.
No Parameter Hasil
Simplisia Ekstrak 1.
2. 3 4 5
Penetapan kadar air
Penetapan kadar sari larut dalam air Penetapan kadar sari larut dalam etanol Penetapan kadar abu total
Penetapan kadar abu tidak larut dalam asam
7,95 % 50,89 % 46,04 % 4,34 % 1,07 %
11,92 % 81,73 % 96,13% 4,15% 0,91%
Hasil karakterisasi simplisia buah nanas menunjukkan hasil penetapan
kadar air diperoleh lebih kecil dari 10% yaitu 7,9%. kelebihan air dalam bahan
tanaman obat akan mendorong pertumbuhan mikroba, keberadaan jamur atau
serangga, serta mendorong kerusakan karena terjadi proses hidrolisis (Trease,
Penetapan kadar sari dilakukan terhadap dua pelarut, yaitu dalam air dan
etanol. Hasil karakterisasi simplisia buah nanas menunjukkan kadar sari yang
larut dalam air tidak kurang dari 37% yaitu sebesar 50,89%, sedangkan kadar
sari yang larut dalam etanol tidak kurang dari 3% yaitu sebesar 46,04%. Kadar
sari yang larut dalam air lebih besar dari kadar sari yang larut dalam etanol
karena senyawa bersifat polar lebih banyak larut di dalam pelarut air dari etanol,
dan senyawa yang tidak larut di pelarut air akan larut di dalam pelarut etanol.
Air dapat melarutkan zat lain yang tidak diperlukan seperti gom, pati, protein,
lemak, lendir dan lain-lain, hal ini yang menyebabkan tingginya kadar sari yang
larut dalam air dari tanaman yang dilarutkan (Depkes RI., 1986).
Penetapan kadar abu pada simplisia buah nanas menunjukkan kadar abu
total sebesar 4,34% dan kadar abu tidak larut dalam asam sebesar 1,07%, kadar
yang diperoleh memenuhi persyaratan, karena persyaratan kadar abu untuk buah
nanas tidak lebih dari 9% dan persyaratan kadar abu yang tidak larut dalam asam
tidak lebih dari 2,5% (Depkes RI., 1979). Penetapan kadar abu dimaksudkan
untuk mengetahui kandungan mineral internal (abu fisiologis) yang berasal dari
jaringan tanaman itu sendiri, dan eksternal (abu non-fisiologis) yang merupakan
residu dari luar seperti pasir dan tanah yang terdapat di dalam sampel (Depkes
RI., 2000; WHO, 1998). Kadar abu tidak larut asam untuk menunjukkan jumlah
silika, khususnya pasir yang ada pada simplisia dengan cara melarutkan abu total
dalam asam klorida (WHO, 1998).
Standar karakterisasi ekstrak belum tercantum dalam monografi parameter
sebagai acuan untuk karakteristik ekstrak etanol buah nanas (EEBN). Hasil
karakterisasi ekstrak etanol buah nanas yang diperoleh menunjukkan hasil
penetapan kadar air sebesar 11,92%, jika dibandingkan dengan simplisia kadar
air pada ekstrak lebih besar karena kemungkinan dalam proses pembuatan
ekstrak, air yang tidak diharapkan baik dari pelarut maupun dari udara masuk ke
dalam ekstrak.
Penetapan kadar sari dilakukan terhadap dua pelarut, yaitu dalam air dan
etanol. Hasil karakterisasi ekstrak etanol buah nanas, menunjukkan kadar sari
yang larut dalam air sebesar 81,73% dan kadar sari yang larut dalam etanol
sebesar 96,13%, dari hasil karakterisasi yang di dapat, kadar sari yang larut
dalam etanol lebih besar dari kadar sari yang larut dalam air, karena
kemungkinan ekstrak buah nanas yang didapatkan dari ekstraksi dengan
menggunakan pelarut etanol, sehingga sari yang tertarik pada saat ekstraksi
sebagian besar adalah senyawa yang larut dalam etanol. Itulah sebabnya kadar
sari yang larut dalam etanol lebih besar. Penetapan kadar abu pada ekstrak etanol
buah nanas, menunjukkan kadar abu total sebesar 4,15%, dan kadar abu tidak
larut dalam asam sebasar 0,91%.
4.3 Skrining Fitokimia
Skrining fitokimia serbuk simplisia buah nanas dan ekstrak etanol buah
nanas dilakukan untuk mendapatkan informasi golongan senyawa metabolit
sekunder yang terdapat di dalamnya. Adapun pemeriksaan yang dilakukan
terhadap simplisia dan ekstrak etanol buah nanas adalah pemeriksaan golongan