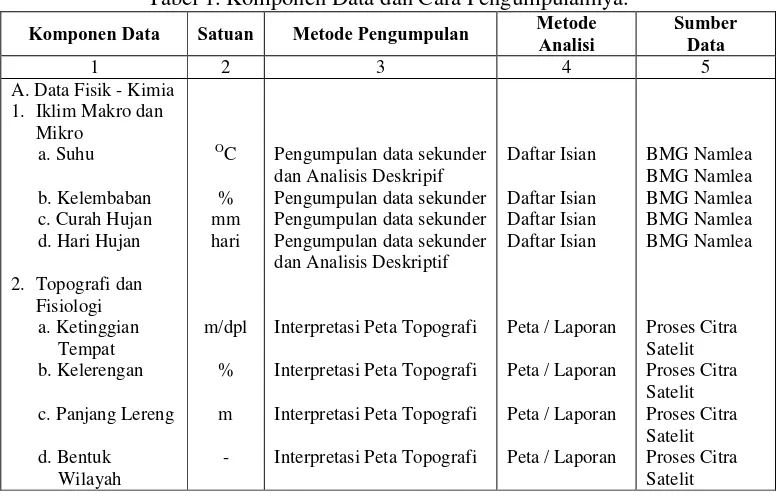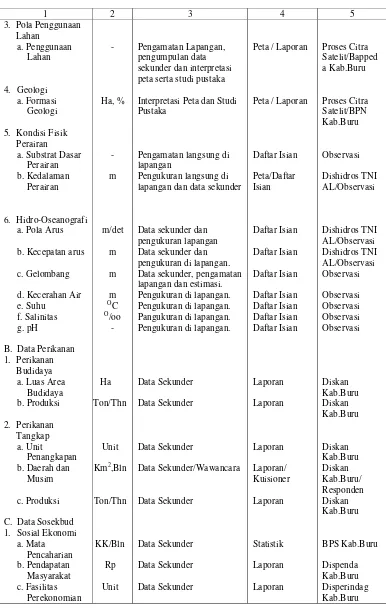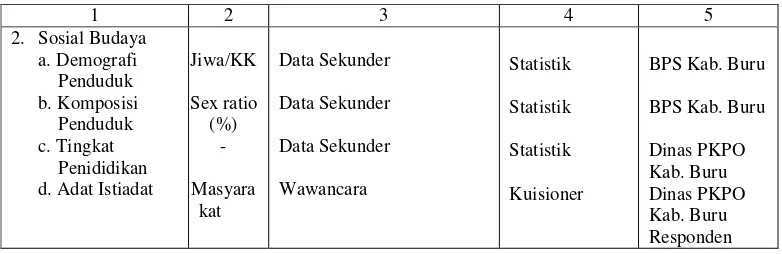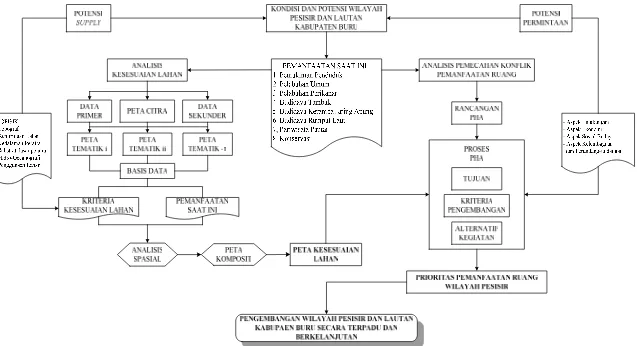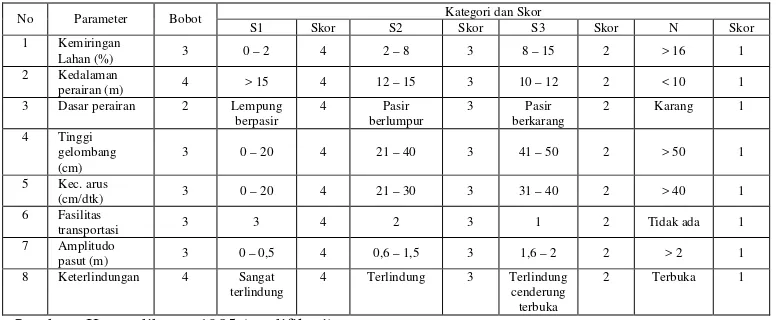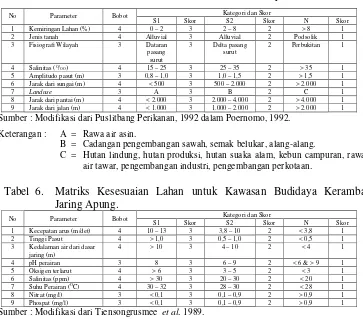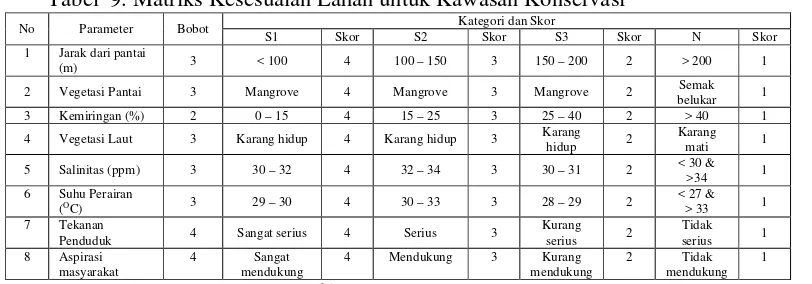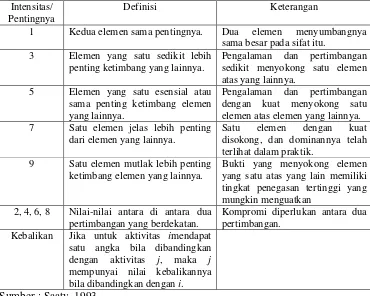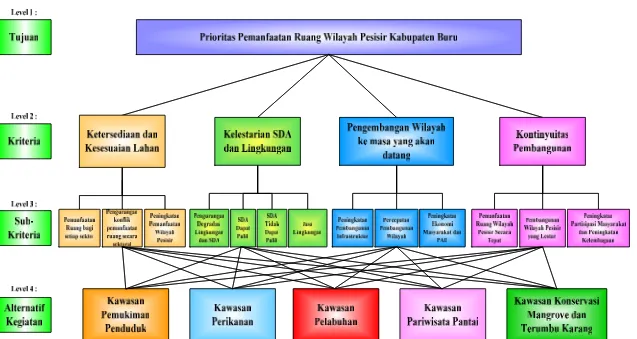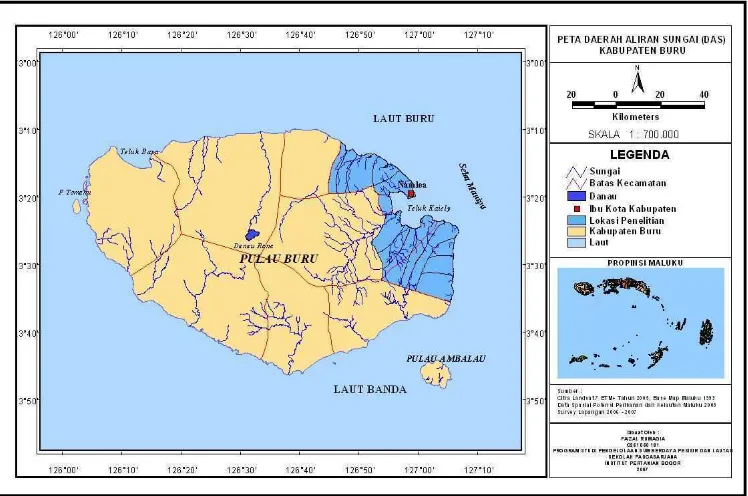DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN BURU, MALUKU
FAIZAL RUMAGIA
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Buru, Maluku. Dibimbing oleh SANTOSO RAHARDJO dan AGUSTINUS M. SAMOSIR.
Kabupaten Buru sebagai salah satu kabupaten yang baru dimekarkan di Propinsi Maluku akibat pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, memiliki potensi yang besar dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan lautan yang dimilikinya.
Penelitian tentang Analisis Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Buru, Maluku, bertujuan untuk menganalisis kesesuain lahan untuk pemanfaatan wilayah pesisir bagi beberapa
peruntukan, dan menganalisis pendapat stakeholder dalam penentuan prioritas
kebijakan pemanfataan wilayah pesisir berdasarkan pada skenario kebijakan menurut alternatif pemanfaatannya di Kabupaten Buru.
Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui hasil survei, observasi dan wawancara secara langsung di lapangan. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan dari dinas atau instansi terkait. Untuk menganalisis kesesuaian lahan bagi pemanfaatan wilayah pesisir digunanakan metode Sistem Informasi Geografis (SIG) dan untuk analisis pemecahan konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir digunakan metode Proses Hierarki Analitik (PHA). Hasil analisis kesesuaian lahan menggunakan SIG menunjukkan bahwa wilayah pesisir Kabupaten Buru memiliki peluang untuk berbagai program pembangunan bagi pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, seperti : kawasan pemukiman penduduk, kawasan pelabuhan umum, kawasan pelabuhan perikanan, kawasan budidaya air payau dengan tambak konvensional, kawasan budidaya keramba jaring apung, kawasan budidaya rumput laut, dan kawasan konservasi untuk mangrove dan terumbu karang. Hasil analisis pemecahan konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir menggunakan PHA menunjukkan bahwa kriteria yang berpegaruh besar terhadap tujuan analisis pemecahan konflik adalah ketersediaan dan kesesuaian lahan, dan priorias pertama bagi alternatif pengembangan ruang wilayah pesisir Kabupaten Buru adalah pengembangan kawasan perikanan.
Kata Kunci: Kabupaten Buru, wilayah pesisr, pemanfaan ruang, SIG, otonomi daerah, PHA, starategi kebijakan.
of Decentralization in Buru Regency, Moluccas. Supervised by SANTOSO RAHARDJO and AGUSTINUS M. SAMOSIR.
Buru regency as one of the newest region in Moluccas province, as the implementation on decentralization laws, have a big potential in development and management of their coastal zone.
The research about Analysis of Coastal Zone Utilization on the Implementation of Decentralization in Buru Regency, Moluccas, aim to analyzing land use for coastal zone utilization for various utilization, and to analyzing the opinion of stakeholder on determination of policy priority of coastal zone utilize based to the policy scenario according to alternative of coastal utilization in Buru Regency.
Primary data obtained directly from the source through survey result, observation and direct interview in the research area. Secondary data obtained from study of bibliography and from related institution. To analyze the land use for coastal zone utilization was determinate using the Geography Information System (GIS) and for land use resolving conflict determinate by Analytical Hierarchy Process (AHP). The land use analysis result using the GIS showed that coastal zone of Buru Regency have an opportunity for various developing program for coastal zone development and management, such as the settlement area, public port, fishery port, estuary pond aquaculture, lift net pond aquaculture, sea weed aquaculture, coastal tourism, also mangrove and coral reef conservation. The land use resolving conflict result shown that the most contribute criteria for the aim of the land use resolving was the availability and agreeable of the land, and the first priority for the alternative development of the coastal zone in Buru Regency are the fishery area.
Keyword: Buru Regency, Coastal zone, Land use, GIS, Decentralization, AHP, Policy strategic.
@ Hak Cipta milik IPB, Tahun 2008 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
DI KABUPATEN BURU, MALUKU
FAIZAL RUMAGIA
Tesis
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada
Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2008
Nama : Faizal Rumagia
NRP : C251050161
Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan
Disetujui
Komisi Pembimbing
Ir. Santoso Rahardjo, M.Sc Ir. Agustinus M. Samosir, M.Phil
Ketua Anggota
Diketahui
Ketua Departemen Dekan Sekolah Pascasarjana
Manajenem Sumberdaya Perairan
Dr. Ir. Sulistiono, M.Sc Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS
Tanggal Ujian : Tanggal Lulus :
Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di
Kabupaten Buru, Maluku adalah hasil karya saya sendiri dan belum diajukan
dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang
berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari
penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di
bagian akhir tesis ini.
Bogor, Januari 2008
Faizal Rumagia NRP C251050161
sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul Analisis
Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di
Kabupaten Buru, Maluku.
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:
1. Ir. Santoso Rahardjo, M.Sc dan Ir. Agustinus M. Samosir, M.Phil selaku ketua
dan anggota komisi pembimbing, atas semua bantuan dan bimbingan yang
telah diberikan kepada penulis mulai dari awal penelitian hingga tersusunnya
tesis ini.
2. Pemerintah Kabupaten Buru, DPRD Kabupaten Buru, Camat dan Kepala Desa
pada lokasi penelitian, civitas akademika Universitas Iqra Buru, masyrakat
dan semua pihak di Kabupaten Buru yang terkait dengan penyusunan tesis ini,
yang telah dengan ikhlas membantu penulis selama melakukan penelitian.
3. Ayahanda H. Umar Rumagia (Rahimakumullah), Ibunda Hj. Syarifah
Rumagia, Kakak Fatmah S. Rumagia, S.Pi dan Adik Abd. Gafur Rumagia,
S.Pi beserta istri serta kedua keponakan tersayang Khodijah dan Hudzaifah,
atas segala doa, kasih sayang, pengertian dan pengorbanan yang telah di
berikan dalam setiap langkah dan kehidupan penulis.
4. Mahasiswa SPs-IPB Program Studi SPL-IPB angkatan 12, khususnya Dinand,
Haikal, Angga, Yusuf, Widhi, dan Evi, atas semua persahabatan, motivasi dan
bantuannya selama penulis menempuh pendidikan. Keluarga kanda
Drs. Abunaim, M.Sc, keluarga besar “BENZIN”, Yeni, Mba Eka, Nico, Adith,
Ancu, Yona, Andin, Santi, Sylvi, dan semua pihak yang telah memberikan
bantuan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan di IPB.
Semoga tesis ini bermanfaat.
Bogor, Januari 2008
Faizal Rumagia
H. Umar Rumagia dan ibu Hj. Syarifah Rumagia, sebagai anak kedua dari tiga
bersaudara.
Menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak pada tahun 1984 di
TK Al Fatah Ambon, dilanjutkan dengan pendidikan dasar ke SDN 6 Ambon
yang diselesaikan pada tahun 1991, pendidikan menengah di SLTP Negeri 4
Ambon diselesaikan pada tahun 1993, kemudian menyelesaikan pendidikan
menengah atas pada SMA Negeri 1 Ambon pada tahun 1996. Tahun 2001 penulis
berhasil menyelesaikan pendidikan Strata Satu pada Jurusan Pemanfaatan
Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Muslim
Indonesia Makassar. Sejak tahun 2001 sampai dengan 2003 penulis mengabdi
sebagai Asisten Dosen pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas
Iqra Buru, dan dalam tahun 2003 penulis diangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan
Muslim Buru Universitas Iqra Buru dan ditugaskan pada Fakultas Perikanan dan
Ilmu Kelautan. Tahun 2005 penulis melanjutkan studi strata dua pada Program
Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Sekolah Pascasarjana Institut
Pertanian Bogor. Selama mengikuti pendidikan Strata Dua, penulis terlibat aktif
dalam organisasi kemahasiswaan IPB, khususnya pada Forum Mahasiswa
Pascasarjana Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan
Institut Pertanian Bogor (Wacana Pesisir IPB) sebagai Sekretaris Umum Wacana
Pesisir IPB periode 2006 – 2007.
PRAKATA ... viii
DAFTAR ISI ... x
DAFTAR TABEL ... xiii
DAFTAR GAMBAR ... xv
DAFTAR LAMPIRAN ... xviii
PENDAHULUAN ... 1
Latar Belakang ... 1
Rumusan Masalah ... 3
Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 4
Alur Pendekatan Studi ... 4
TINJAUAN PUSTAKA ... 7
Pengertian Wilayah Pesisir ... 7
Pengertian PengelolaanWilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan ... 8
Penataan Ruang Wilayah Pesisir ... 9
Pengertian Otonomi Daerah/Desentralisasi ... 11
Kelembagaan dan Perundang-undangan Pengelolaan Wilayah Pesisir ... 13
Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam Penataan Ruang Wilayah Pesisir ... 15
Proses Pemecahan Konflik Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir ... 17
METODE PENELITIAN ... 21
Lokasi dan Waktu Penelitian ... 21
Pengumpulan Data ... 21
Analisis Data ... 28
Analisis Kesesuaian Lahan ... 28
Analisis Pemecahan Konflik Pemanfaatan Ruang ... 34
GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN ... 39
Gambaran Umum Kabupaten Buru ... 39
Fisiologi, Topografi dan Geomorfologi ... 40
Hidrologi dan Tanah ... 42
Iklim ... 44
Kondisi Fisik Perairan Kabupaten Buru ... 44
Kedalaman Perairan ... 44
Pasang Surut ... 45
Arus ... 45
Kondisi Kimia Perairan Kabupaten Buru ... 49
Klorofil-a ... 49
Oksigen Terlarut (DO) ... 50
pH Perairan ... 50
Nutrient ... 51
Fosfat dan Silikat ... 51
Logam Berat ... 52
Prasarana Wilayah ... 52
Prasarana Transportasi ... 52
Prasarana Air Bersih ... 54
Prasarana Pengairan dan Irigasi ... 54
Prasarana Listrik dan Komunikasi ... 54
Prasarana Perekonomian ... 55
Potensi Sumberdaya Perikanan ... 57
Perikanan Budidaya ... 57
Perikanan Tangkap ... 59
Potensi Ekosistem Pesisir dan Laut ... 62
Ekosistem Mangrove ... 62
Ekosistem Padang Lamun ... 62
Ekosistem Terumbu Karang ... 63
Domografi dan Sosial Budaya ... 64
Kelembagaan Penataan Ruang Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kabupaten Buru ... 65
HASIL DAN PEMBAHASAN ... 67
Dampak Kegiatan Pembukaan Dataran Atas Terhadap Pesisir Kabupaten Buru ... 67
Analisis Kesesuaian Lahan ... 68
Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Pemukiman Penduduk ... 68
Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Pelabuhan Umum ... 73
Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai ... 77
Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Budidaya Air Payau dengan Tambak Konvensional ... 81
Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Budidaya Keramba Jaring Apung ... 84
Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Budidaya Rumput Laut ... 85
Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Pariwisata Pantai ... 87
Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Konservasi ... 92
Peta Komposit Kesesuaian Lahan ... 96
Analisis Pemecahan Konflik Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir ... 99
Tujuan ... 99
Prioritas Kedua : Kawasan Konservasi ... 114
Prioritas Ketiga : Kawasan Pelabuhan ... 115
Prioritas Keempat : Kawasan Pemukiman Penududuk ... 117
Prioritas Kelima : Kawasan Pariwisata Pantai ... 118
Skenario Kebijakan ... 120
Pembahasan Komprehensif ... 122
KESIMPULAN DAN SARAN ... 127
Kesimpulan ... 127
Saran ... 129
1. Komponen Data dan Cara Pengumpulannya ... 24
2. Matriks Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Pemukiman Penduduk ... 30
3. Matriks Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Pelabuhan Umum ... 30
4. Matriks Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai ... 31
5. Matriks Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Budidaya Tambak ... 31
6. Matriks Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Budidaya Keramba Jaring Apung ... 31
7. Matriks Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Budidaya Rumput Laut ... 32
8. Matriks Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Pariwisata Pantai ... 32
9. Matriks Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Konservasi ... 32
10. Skala Banding Secara Berpasangan ... 35
11. Dimensi Spasial Wilayah Ekologis Kabupaten Buru ... 40
12. PDRB Kabupaten Buru Tahun 2001 – 2003 Berdasarkan Harga Konstan Tahun 1999 ... 56
13. Distribusi Infrastruktur Ekonomi Perikanan pada Kabupaten Buru ... 56
14. Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Perikanan Budidaya menurut Uraian Kegiatan Budidaya di Kabupaten Buru sejak Tahun 2002 – 2006 ... 58
15. Jumlah Jenis Perahu Penangkap Ikan di Kabupaten Buru dari Tahun 2002 – 2006 ... 61
16. Kondisi Alat Tangkap Ikan di Kabupaten Buru dari Tahun 2002 – 2006 ... 61
17. Skala Prioritas Kriteria terhadap Tujuan dalam Penentuan Prioritas Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten Buru... 101
19. Skala Prioritas Berdasarkan Kriteria Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan dalam Penentuan Prioritas Pemanfaatan
Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 105
20. Skala Prioritas Berdasarkan Kriteria Pengembangan Wilayah ke Masa yang Akan Datang dalam Penentuan Prioritas
Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 107
21. Skala Prioritas Berdasarkan Kriteria Kontinyuitas
Pembangunan dalam Penentuan Prioritas Pemanfaatan Ruang
Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 108
22. Skala Prioritas Altrenatif Kegiatan Berdasarkan Kriteria dalam Penentuan Prioritas Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten
1. Alur Pendekatan Studi ... 5
2. Peta Lokasi Penelitian ... 22
3. Alur Sistematika Proses Penelitian ... 27
4. Diagram Hierarki Analisis Prioritas Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 38
5. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Buru ... 40
6. Peta Wilayah Ekologis Kabupaten Buru ... 42
7. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Buru ... 43
8. Kondisi Sedimentasi di Perairan Teluk Kaiely Kabupaten Buru... 49
9. Peta Jaringan Transportasi Kabupaten Buru dan Propinsi Maluku.... 53
10. Peta Zona Penangkapan Ikan Kabupaten Buru ... 60
11. Potensi Hutan Mangrove pada Wilayah Ekologis Teluk Kaiely Kabupaten Buru... 63
12. Potensi Terumbu Karang pada Wilayah Ekologis Teluk Kaiely Kabupaten Buru ... 64
13. Peta Kesesuaian Lahan Untuk Kawasan Pemukiman Penduduk di Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 71
14. Peta Kesesuaian Lahan Untuk Kawasan Pelabuhan Umum di Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 75
15. Peta Kesesuaian Lahan Untuk Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai di Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 80
16. Peta Kesesuaian Lahan Untuk Kawasan Budidaya Air Payau dengan Tambak Konvensional di Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 83
17. Peta Kesesuaian Lahan Untuk Kawasan Budidaya Keramba Jaring Apung di Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 86
20. Peta Kesesuaian Lahan Untuk Kawasan Konservasi Mangrove dan
Terumbu Karang di Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 94
21. Peta Komposit Kesesuaian Lahan di Wilayah Pesisir
Kabupaten Buru ... 97
22. Diagram Batang Skala Prioritas Kriteria terhadap Tujuan dalam Penentuan Prioritas Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten
Buru ... 101
23. Grafik Skala Prioritas Pengembangan Kriteria Ketersediaan dan Kesesuaian Lahan terhadap Alternatif Pengembangan Kawasan di
Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 105
24. Grafik Skala Prioritas Pengembangan Kriteria Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan terhadap Alternatif
Pengembangan Kawasan di Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 106
25. Grafik Skala Prioritas Pengembangan Kriteria Pengembangan Wilayah ke Masa yang Akan Datang terhadap Alternatif
Pengembangan Kawasan di Wilayah Pesisir Kabupaten Buru... 108
26. Grafik Skala Prioritas Pengembangan Kriteria Kontinyuitas Pembangunan terhadap Alternatif Pengembangan Kawasan di
Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 109
27. Diagram Batang Skala Prioritas Alternatif Kegiatan
Berdasarkan Kriteria dalam Penentuan Prioritas Pemanfaatan
Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 110
28. Grafik Analisis Sensitivitas Pendapat Gabungan Responden ... 120
29. Model Dinamika Analisis Sensivitas Pendapat Gabungan
1. Data Kondisi Biofisik Perairan Pesisir Kabupaten Buru
Pada 28 Stasiun Pengamatan ... 136
2. Penilaian Responden untuk Analisis Pemecahan Konflik
Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 138
3. Bobot dan Prioritas Alternatif Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir
Kabupaten Buru ... 142
4. Model Skenario Kebijakan Bila Terjadi Perubahan pada Setiap
Kriteria Pemanaatan Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 143
5. Kuisioner Data Government Stakeholder ... 147
6. Kuisioner Data Non-Government Stakeholder ... 152
Latar Belakang
Pengembangan dan peningkatan sumberdaya alam Indonesia untuk
pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, kini semakin ditingkatkan
sebagai salah satu konsekuwensi dari keterpurukan ekonomi bangsa akibat krisis
yang telah berlangsung sejak tahun 1997. Salah satu sektor yang menjadi harapan
percepatan perbaikan ekonomi tersebut adalah sektor perikanan dan kelautan,
yang diharapakan dapat menjadi andalan dalam pengembangan sumberdaya alam
di Indonesia.
Sejalan dengan digulirkannya sistem desentralisasi pembangunan melalui
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang disempurnakan dengan UU
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan sendirinya telah
mengakibatkan terjadinya perubahan paradigma pengelolaan terhadap
sumberdaya perikanan dan kelautan dari pusat ke daerah, dan menjadi tanggung
jawab pemerintah daerah bersama jajarannya yang terkait beserta masyarakat
setempat.
Secara umum dapat dilihat bahwa potensi wilayah pesisir dan lautan di
dareah-daerah menjadi potensi yang penting dalam pengelolaan sumberdaya
perikanan dan kelautan dimasa depan, mengingat luas wilayah laut Indonesia
adalah 62 % dari luas wilayah nasional, belum lagi ditambah dengan wilayah ZEE
seluas 2,7 juta km per segi, serta ditunjang oleh kekayaan dan keanekaragaman
hayati dan jasa-jasa lingkungan yang dapat diberikannya, sehingga menempatkan
sumberdaya pesisir dan lautan memiliki nilai ekonomis dan ekologi yang tinggi.
Sebagaimana yang tersirat dalam pembangunan yang berkelanjutan, bahwa
pembangunan suatu kawasan akan bersifat berkesinambungan (sustainable)
apabila laju pembangunan beserta segenap dampak yang ditimbulkan secara
keseluruhan tidak melebihi daya dukung atau kemampuan lingkungan kawasan
tersebut. Karena itu ketersediaan ruang (space) yang sesuai (suitable) untuk
kegiatan ekonomi seperti kegiatan perikanan, pariwisata, industri maritim, dan
kegiatan ekonomi lainnya di wilayah pesisir dapat mendukung pembangunan yang
Propinsi Maluku dikenal sebagai propinsi seribu pulau, yang memiliki garis
pantai cukup panjang, memegang tanggung jawab yang sangat besar terhadap
pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang dimilikinya, mengingat luas
wilayahnya hampir 70% merupakan wilayah laut. Hal tersebut juga dirasakan
oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Buru yang merupakan salah
satu kabupaten yang baru dibentuk, dalam mempercepat pembangunan di
daerahnya dalam pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini.
Dengan diberlakukannnya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, maka sejak tanggal 12 Oktober
1999 Kabupaten Buru secara resmi terbentuk. Sejalan dengan pemekaran wilayah
tersebut maka sebagai kabupaten yang baru, Kabupaten Buru diperhadapkan
dengan berbagai kebutuhan yang mendasar yang perlu dibentuk dan dibangun
secara terencana yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah
yang dibuat oleh pemerintah, baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten sendiri
dalam mengoptimalkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Buru.
Merujuk pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Tahun
2002 – 2006, Pemerintah Daerah Kabupaten Buru telah menetapkan beberapa
kebijakan dan strategi yang akan dikembangkan, antara lain penataan ruang
wilayah, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan sarana dan
prasarana pendukung pembangunan wilayah, pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan serta peningkatan peranan kelembagaan.
Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang telah
ditetapkan dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang
menyebutkan bahwa pengelolaan sumberdaya alam diserahkan kepada pemerintah
daerah, pada kenyataannya banyak menimbulkan konflik dalam pelaksaannya.
Konflik tersebut umumnya merupakan konflik antara kepentingan konservasi dan
pembangunan ekonomi di kawasan pesisir dan laut, terutama pada wilayah yang
memiliki potensi dan intensitas pembangunan yang tinggi. Kondisi seperti ini juga
dirasakan terjadi di wilayah pesisir dan lautan Kabupaten Buru, sehingga menjadi
menjabarkan dan melaksanakan berbagai kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya alam yang dimiliki oleh kabupaten ini, terutama kebijakan dalam
pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan lautnya.
Dalam rangka mendukung dan mengimplementasikan rencana strategis
pembangunan daerah dan pola dasar pembangunan daerah Kabupaten Buru, maka
penelitian Analisis Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Dalam Pelaksanaan
Otonomi Daerah Di Kabupaten Buru, Maluku ini dirasa perlu dilakukan untuk
mengetahui sampai sejauh mana kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir,
dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Buru dalam
pengembangan wilayah pesisir dengan prinsip keterpaduan dan keberlanjutan.
Rumusan Masalah
Pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir Kabupaten Buru sebagai bagian
dalam pelaksanaan pembangunan daerah, telah memberikan pengaruh yang besar
terhadap pemanfaatan ruang wilayah pesisir di daerah ini. Peningkatan
pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir Kabupaten Buru, telah
mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan lingkungan pesisir, baik dari aspek
sumberdaya alam maupun pada pola pemanfaatan ruang untuk berbagai sektor
pembangunan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan dan
terjadinya konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir Kabupaten Buru.
Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan
pemanfaatan ruang wialayah pesisir Kabupaten Buru antara lain sebagai berikut :
1. Terjadinya degradasi wilayah pesisir sebagai akibat dari pemanfaatan ruangan
yang kurang sesuai antara para pengguna potensi sumberdaya pesisir dan
lautan (stakeholder) yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada fungsi
pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam, sehingga mempengaruhi pola
pembangunan wilayah pesisir dan lautan di Kabupaten Buru.
2. Belum tersedianya analisis kesesuaian lahan yang memadai bagi pemanfaatan
ruang wilayah pesisir Kabupaten Buru, sehingga mengakibatkan pola
pemanfaatan ruang yang bersifat sektoral, yang berpengaruh terhadap
3. Adanya konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir antar stakeholder yang
memerlukan penyelesaian melalui penentuan prioritas pemanfaatan ruang
wilayah pesisir Kabupaten Buru, sehingga menghasilkan pola pembangunan
wilayah pesisr yang berkelanjutan.
Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Menganalisis penyebab degradasi lingkungan melalui penentuan kesesuaian
lahan untuk pemanfaatan wilayah pesisir bagi pemukiman penduduk,
pelabuhan umum, pelabuhan perikanan, budidaya tambak, budidaya keramba
jaring apung, budidaya rumput laut, pariwisata pantai, serta konservasi
mangrove dan terumbu karang di Kabupaten Buru.
2. Menganalisis dan menyelesaikan konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir
dengan penentuan prioritas kebijakan pemanfaatan wilayah pesisir melalui
penilaian terhadap pendapat stakeholder (pemerintah,masyarakat dan swasta)
yang berperan dalam pemanfaatan wilayah pesisir di Kabupaten Buru
Manfaat yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah dapat menjadi
masukan dan acuan bagi pengambil keputusan dalam menyusun kebijakan dan
program pembangunan serta sebagai pertimbangan dan arahan dalam
pengembangan dan perencanaan bagi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir
dan lautan yang berkelanjutan (sustained development) di Kabupaten Buru dalam
konteks otonomi daerah.
Alur Pendekatan Studi
Berdasarkan karakteristik dan dinamika dari kawasan pesisir, potensi dan
permasalahan pembangunan serta kebijakan pemerintah untuk sektor kelautan,
maka dalam upaya mencapai pembangunan kawasan pesisir secara optimal dan
berkelanjutan, diperlukan adanya suatu bentuk pengelolaan wilayah pesisir secara
terpadu dan berkelanjutan.
Penataan ruang wilayah pesisir dan laut Kabupaten Buru didasarkan pada
kondisi potensi supply, potensi permintaan dan pemanfaatan saat ini. Potensi
biologi dan mempunyai interaksi sama lain yang dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Potensi permintaan meliputi kondisi
sosial ekonomi masyarakat serta stakeholder lainnya yang dalam
perkembangannya membutuhkan pasokan sumberdaya alam yang memadai serta
pengaturan pemanfaatan agar dapat terjamin kelestariannya. Unsur pemanfaatan
saat ini antara lain pemukiman penduduk, pelabuhan umum, pelabuhan perikanan,
budidaya perikanan, pariwisata pantai, dan konservasi, merupakan faktor penentu
yang perlu diketahui untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah
penyempurnaan pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Buru.
Selanjutnya dengan menggunakan kriteria kesesuaian lahan, dilakukan
analisis terhadap ketiga komponen penentu tersebut yaikni potensi supply, potensi
permintaan dan pemanfaatan saat ini, untuk menetapkan kawasan yang sesuai
dengan kondisi sumberdaya alam dan kebutuhan manusia dalam konteks
pembangunan berwawasan lingkungan. Alur pendekatan studi yang digunakan
seperti terlihat pada Gambar 1.
Penataan ruang pesisir dan laut dapat dilakukan melalui empat tahapan,
yaitu : (i) penataan ruang pesisir secara menyeluruh bagi berbagai peruntukan,
yakni bagi kawasan preservasi, konservasi dan pemanfaatan secara intensif,
(ii) penataan ruang pessir yang diperuntukan bagi kawasan pemanfaatan secara
intensif untuk berbagai kegiatan pembangunan yang dimaksudkan untuk
menghindari terjadinya benturan dan tumpang tidih berbagai kegiatan
pembangunan, (iii) penataan ruang pesisir dengan lahan atas untuk menghidari
adanya dampak yang dapat menurunkan (degradasi) ekosistem dan aktivitas
pembangunan diwlayah pessir dan laut, dan (iv) penempatan setiap kegiatan
pembangunan sesuai dengan kebutuhan biofisik dari kegiatan tersebut. Dengan
demikian, dapat dipahami bahwa analisis kesesuaian lahan merupakan salah satu
cara yang dapat memberikan kontribusi positif bagi perencanaan pengelolaan
wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Buru. Perencanaan pengeloalaan didasarkan
pada hasil analisis kesesuaian lahan yang mengintegrasikan biogeofisik kawasan
TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Wilayah Pesisir
Wilayah pesisir adalah suatu daerah peralihan antara daratan dan lautan.
Apabila ditinjau dari garis pantai (coastline), maka suatu wilayah pesisir memiliki
dua macam batas yaitu : batas yang sejajar garis pantai (longshore) dan batas yang
tegak lurus terhadap garis pantai (cross-shore), atau merupakan daerah pertemuan
antara daratan dan lautan, dimana batas di daratan meliputi daerah-daerah yang
tergenang air maupun yang tidak tergenang dengan air yang masih dipengaruhi
oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut, gelombang, muka laut,
suhu dan salinitas (Dahuri el al., 2004; Bengen, 2001; Djais et al., 2003; Kay and
Alder, 1999; The World Bank, 1993).
Wilayah pesisir (coastal zone) merupakan daerah yang unik, karena pada
daerah ini hanya bisa dijumpai pasang surut, hutan mangrove, terumbu karang,
hempasan gelombang, perairan pantai, dan pulau-pulau penghalang pantai. Akibat
dari keberagaman dan perubahan yang sering terjadi di wilayah pesisir,
kebanyakan negara menyatakan bahwa daerah pesisir merupakan daerah yang
memerlukan perhatian khusus. Lebih jauh disebutkan pula bahwa, sebagai daerah
transisi antara daratan dan lautan, wilayah pesisir merupakan daerah yang
memiliki beberapa habitat yang produktif dan berharga dari biosfer, seperti
estuari, laguna, lahan basah pesisir, dan ekosistem terumbu karang. Daerah ini
juga merupakan daerah yang memiliki dinamika sumberdaya alam yang besar
dimana proses transfer energi alami banyak terjadi dan kelimpahan yang besar
dari organisme alami juga dapat ditemukan di wilayah ini (Clark, 1996; Fabbri,
1998; Dutton and Hotta, 1995).
Pendefinisian wilayah pesisir dilakukan atas tiga pendekatan, yaitu
pendekatan ekologis, pendekatan administratif, dan pendekatan perencanaan.
Dilihat dari aspek ekologis, wilayah pesisir adalah wilayah yang masih
dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, dimana ke arah laut mencakup wilayah
yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan seperti sedimentasi. Dilihat
dari aspek administratif, wilayah pesisir adalah wilayah yanag secara administrasi
yang mempunyai hulu, dan kearah laut sejauh 12 mil dari garis pantai untuk
Provinsi atau 1/3 dari 12 mil untuk Kabupaten/Kota. Sedangkan dilihat dari aspek
perencanaan, wilayah pesisir adalah wilayah perencanaan pengelolaan dan
difokuskan pada penanganan isu yang akan ditangani secara bertanggung jawab
(Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir, 2001).
Pengertian Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan
Konsep pengelolaan wilayah secara berkelanjutan merujuk pada
perencanaan wilayah yang membutuhkan keterpaduan antara perencanaan
ekonomi, perencanaan fisik dan dan perencanaan lingkungan. Konsep pengelolaan
wilayah ini akan menjelaskan bagaimana konsep keterpaduan wilayah dalam
aktifitas pembangunan yang dilaksanakan. Konsep pengelolaan berkelanjutan
wilayah ini dibentuk dari empat konsep dasar yang saling berkaitan satu dengan
lainnya, yakni : (1) Wilayah merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri dari
berbagai kepentingan yang kompleks terhadap pemanfaatan wilayah, (2) Sebuah
wilayah dapat dikarakteristikkan berdasarkan pada struktur dan fungsinya, (3)
Struktur dan fungsi wilayah memiliki pengaruh bagi keuntungan ekonomi dan
pembiayanya, dan (4) Bentuk keberhasilan dari suatu wilayah, dapat dinilai dari
kegunaanya dalam memenuhi kebutuhan manusia, melalui pengukuran rasio
keuntungan ekonomi yang dihasilkan oleh wilayah tersebut dan biaya ekonomi
yang digunakan dalam pengelolaan wilayah tersebut (Laak, 1992; Dahuri et al.
2004; Darmawan, 2000).
Clark (1996) menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu
merupakan suatu kegiatan perencanaan untuk mengelola sumberdaya pesisir
melalui partisipasi atau keterlibatan oleh sektor-sektor ekonomi, lembaga
pemerintah, dan lembaga-lembaga non-pemerintah yang memiliki keterkaitan
dengan pengelolaan wilayah pesisir tersebut. Lebih jauh dinyatakan juga bahwa,
tujuan utama dari pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan secara terpadu
(Intergrated Coastal Zone Management / ICZM) adalah untuk mengkoordinasikan
dan mengoptimalkan sektor ekonomi wilayah pesisir untuk jangka panjang dalam
rangka memperoleh keuntungan sosial-ekonomi jangka panjang, termasuk
didalamnya penyelesaian terhadap permasalahan dan proses ekonomi yang
Dimensi keterpaduan dalam Pengelolaan Peisir Terpadu / Integrated
Coastal Management (ICM) meliputi lima aspek, yaitu (1) keterpaduan sektor, (2)
keterpaduan wilayah/ekologis, (3) keterpaduan stakeholder dan tingkat
pemerintahan, (4) keterpaduan antar berbagai disiplin ilmu, dan (5) keterpaduan
antar negara (Cincin-Sain, 1993; Turner et al., 1999).
Secara mendasar, pembangunan berkelanjutan (sustainable development)
adalah sebuah proses perubahan dalam eksploitasi sumberdaya, pengarahan
terhadap investasi, orientasi penggunaan teknologi pembangunan, dan perubahan
institusional yang berlangsung secara harmonis. Keberlanjutan, sebagaimana yang
didefinisikan, merupakan tujuan baru dalam pengelolaan wilayah. Karena adanya
keterkaitan yang erat antara pembangunan sosial dan ekonomi dengan keberadaan
sumberdaya, terkadang tujuan dari keberlanjutan pembangunan wilayah tersebut
disusun sebagai, pembangunan lingkungan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan
(Lier, 1992).
Dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu, mengintegrasikan antara
kegiatan pemerintah, swasta dan masyarakat, perencanaan vertikal dan horisontal,
ekosistem darat dan laut, sains dan manajemen, merupakan proses pengelolaan
sumberdaya alam pesisir yang mengacu pada pengelolaan yang berkelanjutan dan
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdomisili di wilayah
tersebut. Oleh karenanya pengelolaan dan pemanfaatan ruang wilayah pesisir
Kabupaten Buru harus terintegrasi dan harus melibatkan semua sektor serta
stakeholders yang ada, sehingga dapat mencapai pembangunan yang
berkelanjutan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir
khususnya dan masyarakat Kabupaten Buru pada umumnya
Penataan Ruang Wilayah Pesisir
Menurut Budiharsono (2001), ruang merupakan hal yang penting dalam
pembangunan wilayah. Konsep ruang mempunyai beberapa unsur, yaitu : (1)
jarak; (2) lokasi; (3) bentuk; dan (4) ukuran. Konsep ruang sangat berkaitan erat
dengan waktu, karena pemanfaatan bumi dan segala kekayaannya membutuhkan
organisasi/pengaturan ruang dan waktu. Unsur-unsur tersebut di atas secara
tata ruang sebagai instrumen publik adalah perskripsi spasial secara langsung dan
tidak langsung.
Pola pemanfaatan ruang selalu berkaitan dengan aspek-aspek sebaran
sumberdaya dan aktifitas pemanfaatannya menurut lokasi, setiap aktifitas
menyebar dengan luas yang beda dan tingkat penyebaran yang
berbeda-beda pula. Secara lebih tegas, penataan ruang dilakukan sebagai upaya : (1)
Optimasi pemanfaatan sumberdaya (mobilisasi dan alokasi pemanfaatan
sumberdaya): (Prinsip efisiensi dan produktifitas); (2) Alat dan wujud distribusi
sumberdaya: azas pemerataan, keberimbangan dan keadilan; dan (3)
Keberlanjutan (sustainabillity) (Rustiadi et al. 2005; Nugroho dan Dahuri, 2004;
Tarigan, 2005).
Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota disusun oleh pemerintah daerah
setempat. Rencana ini merupakan kebijakan pemerintah yang menetapkan lokasi
dan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, pola jaringan prasarana,
dan wilayah-wilayah yang diprioritaskan pengembangannya. Bagi
Kabupaten/Kota yang wilayahnya terdiri dari wilayah daratan, wilayah pesisir,
dan wilayah laut, maka untuk melaksanakan pembangunan daerahnya harus
mampu melihat ketiga wilayah tersebut sebagai satu kesatuan (Hardjowigeno et
al. 2001).
Tata ruang wilayah pesisir dikelompokan melalui pengaturan penggunaan
lahan wilayah di dalam unit-unit yang homogen ditinjau dari keseragaman fisik,
non-fisik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Wilayah pesisir
paling dikenal sebagai daerah peralihan antara ekosistem daratan dan lautan
dimana merupakan kawasan dipermukaan bumi yang paling padat dihuni oleh
umat manusia (Dahuri et al., 1997, 2004; Sugandhy, 1993).
Fungsi penataan ruang dalam kebijakan pengembangan daerah adalah : (1)
sebagai matra ruang dari kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam
Rencana Strategis Pembangunan Daerah, (2) merupakan pedoman untuk
menetapkan lokasi bagi kegiatan pembangunan dalam pemanfaatan ruang yang
dituangkan dalam Rencana Tata Ruang, dan (3) sebagai alat untuk
yang memerlukan ruang, sehingga dapat menyelaraskan setiap program antar
sektor yang terlibat (Djais et al, 2003).
Pengertian Otonomi Daerah/Desentralisasi
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa, "Otonomi Daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan".
Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya dalam arti
daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan
pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam
Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk
memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan
masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Pemerintah
Republik Indonesia, 2004).
Salam (2003) menyatakan bahwa, secara filosofi, penyelenggaraan otonomi
daerah merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian
masyarakat dan pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu sasaran akhir
penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat dan
pemerintah daerah serta mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Sementara itu juga dikemukakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan
kekuasaan (wewenang, hak, kewajiban dan tanggung jawab) sejumlah urusan
pemerintah dari pemerintah pusat ke daerah otonom sehingga daerah otonom itu
dapat melakukan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan dalam masalah-masalah pengelolaan pembangunan untuk mendorong
dan meningkatkan kinerja pembangunan.
Secara teoritis, terdapat tiga sendi otonomi daerah, yaitu pembagian
kekuasaan (sharing of power), distribusi pendapatan (distribution of income), dan
pemberdayaan (empowering). Ketiga sendi otonomi daerah tersebut relatif telah
terakomodasi, baik dalam UU Pemerintahan Daerah maupun UU Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Muchsan, 2000 diacu dalam
Menurut Rondinelli (1993), desentralisasi dan otonomi daerah adalah
upaya-upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan masyarakat
melalui peran serta proaktif kelompok masyarakat miskin yang dapat
terlaksanakan secara efektif. Lebih jauh juga dikemukakan bahwa, kebijakan
desentralisasi dapat memberikan keuntungan, yaitu (i) memberikan sumbangan
untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang luas, (ii) meningkatkan efektifitas
administrasi, (iii) mempromosikan efisiensi ekonomi dan manejerial, (iv)
meningkatkan respon pemerintah menghadapi beragam kebutuhan dari
pemerintahan; (v) memajukan ketahanan dan penentuan diri sendiri diantara
organisasi dan kelompok-kelompok di daerah yang merupakan representasi
kepentingan politik yang absah, dan (vi) memajukan cara yang memadai untuk
mendesain dan mengimplementasikan program dan proyek pembangunan daerah.
Dahuri (1999) menyatakan bahwa, berlakunya otonomi daerah merupakan
peluang mengoptimalkan pengelolaan wilayah pesisir bagi pemerintah daerah, dan
memberikan wewenang dalam hal : (1) adanya yuridiksi untuk mendapatkan
tambahan dari sumberdaya alam hayati dan non hayati dan dapat menggali
potensi-potensi lainnya yang ada di wilayah pesisir, (2) dalam menata dan
melakukan pembangunan wilayah, pemerintah daerah dapat melakukannya sesuai
dengan kemampuan wilayah pesisir serta pembangunan sarana dan prasarana.
Dimasa otonomi daerah, optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan lautan
dapat berhasil karena : (i) Pengelolaan sumberdaya wilayah di dekatkan pada
pelaku dan stakeholder terdekat (masyarakat dan daerah), (ii) Penghargaan dan
akomodasi terhadap kearifan lokal dan hukum-hukum adat setempat,
(iii) Transparansi dalam alokasi dan penetapan kebijaklan ruang dan sumberdaya,
(iv) Pelibatan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan,
(v) Meningkatnya rasa memiliki masyarakat terhadap sumberdaya yang ada di
wilayah pesisir (Idris, 2001).
Pendekatan desentralisasi pengelolaan dalam Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir Secara Terdapadu (Integrated Coastal Zone Management/ICZM) adalah
dengan memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk
melakukan pengelolaan pada wilayah pesisir di daerahnya, melalui pengaturan
kegiatan konservasi, ekonomi, dan kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat yang
berperan dalam pengelolaan wilayah pesisirnya (Clark, 1996).
Kelembagaan dan Perundang-undangan Pengelolaan Wilayah Pesisir
Sesuai dengan amanat GBHN 1999 – 2004, arah kebijakan pembangunan
daerah adalah untuk : (a) Mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi,
lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga
swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia; (b) Melakukan kajian tentang berlakunya otonomi
daerah bagi propinsi, kabupaten/kota dan desa; dan (c) Mewujudkan perimbangan
keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan
daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta
pengelolaan sumberdaya.
Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan bahwa pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan,
pengawasan, pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor,
antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta
antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Lebih jauh dalam Undang-undang ini juga disebutkan bahwa, pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan,
pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam
memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah
secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteran masyarakat dan
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan secara
terpadu yang dikoordinasi oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.
Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, disebutkan bahwa zona adalah ruang yang
penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan
pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan
potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang
berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir. Zonasi adalah rencana
yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan
disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan
yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak oleh dilakukan serta
kegiatan yang hanya dapat dilakukan serta memperoleh izin.
Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
disebutkan bahwa Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan,
dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk
lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang. Penataan
ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan
tata ruang. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga menyebutkan bahwa wewenang
pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelengaraan penataan ruang
meliputi: (a) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan
penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; (b)
pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; (c) pelaksanaan penataan
kawasan straregis kabupaten/kota; dan (d) kerja sama penataan ruang antar
kabupaten/kota.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:
KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir
Terpadu, dinyatakan bahwa, untuk melaksanakan penyusunan Pengelolaan Pesisir
Terpadu, maka diperlukan kelembagaan tersendiri yang berperan membantu
instansi perencana yang ada, seperti Bappeda provinsi atau kabupaten/kota.
Kelembagaan ini bersifat lintas sektor dan tidak permanen (adhoc) yang dibentuk
pengendalian Program PPT-nya akan dikoordinasikan Bappeda bersama Dinas
Perikanan dan Kelautan serta instansi teknis atau unit pelaksana teknis di daerah.
Ruang lingkup perencanaan tata ruang wilayah pesisir terkait erat dengan
batasan wilayah pesisir. Ditinjau dari garis pantai, maka suatu wilayah pesisir
memiliki dua kategori batas yaitu batas yang sejajar dengan garis pantai
(longshore) dan batas yang tegak terhadap garis pantai (crosshore). Lingkup
perencanaan wilayah dapat dilihat dari pendekatan karakter administratif dan
pendekatan berdasarkan ekobiogeografis (Departemen Kelautan dan Perikanan,
2002; Ditjen Bangda Depdagri, 1998).
Sebagai akhir proses perencanaan, rencana tata ruang yang telah disetujui
bersama oleh pemerintah, DPRD dan masyarakat harus diundangkan dan dimuat
dalam lembaran negara. Rencana Tata Ruang bukanlah akhir dari proses tetapi
awal dari proses pengaturan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan. Untuk
itu Rencana Tata Ruang Nasional lebih banyak berupa kriteria dan pola
pengelolaan kawasan lindung, budidaya dan kawasan tertentu, sedangkan
Rencana Tata Ruang Kabupaten berupa pedoman pengendalian pemanfaatan
ruang kabupaten.
Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam Penataan Ruang Wilayah Pesisir
Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu sistem komputer yang
mempunyai kemampuan pemasukan, pengambilan, analisis data, dan tampilan
data geografis yang sangat berguna bagi pengambil keputusan. Sistem komputer
ini terdiri dari perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) dan
manusia (personal) yang dirancang untuk efisien memasukkan, menyimpan,
memperbaharui, memanipulasi, menganalisa, dan menyajikan semua jenis
informasi yang berorientasi geografis (ESRI, 1990; Purwanto, 2001).
Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu teknologi baru yang pada
saat ini menjadi alat bantu (tools) yang sangat esensial dalam menyimpan,
memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan kembali kondisi-kondisi alam
dengan bantuan data atribut dan data spasial (Prahasta, 2005; Purwadhi, 1998;
Burrough, 1986).
Dahuri et al. 2004 menyatakan bahwa, informasi yang dibutuhkan untuk
secara berkelanjutan adalah informasi yang digunakan untuk : (1) Menyusun tata
ruang kelautan, (2) Penentuan tingkat pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat
pulih, (3) Penentuan tingkat kerusakan lingkungan (dalam bentuk pencemaran,
erosi/abrasi, perubahan bentang alam, dan lain-lain) yang dapat ditolerir oleh
sistem lingkungan setempat.
Burrough (1986), menyatakan bahwa, Sistem Informasi Geografis (SIG)
merupakan sistem informasi yang bersifat terpadu, karena data yang dikelola
adalah data spasial. Dalam SIG data grafis di atas peta dapat disajikan dalam dua
model data spasial yaitu model data raster dan model data vektor. Model data
vektor menyajikan data grafis (titik, garis, poligon) dalam struktur format vektor.
Struktur data vektor adalah suatu cara untuk membandingkan informasi garis dan
areal ke dalam bentuk satuan-satuan data yang mempunyai besaran, arah dan
keterkaitan satu sama lainnya.
Sistem Informasi Geografis (SIG) mempunyai kemampuan analisis
keruangan (spatial analysis) maupun waktu (temporal analysis). Dengan
kemampuan tersebut SIG dapat dimanfaatkan dalam perencanaan apapun karena
pada dasarnya semua perencanaan akan terkait dengan dimensi ruang dan waktu.
Dengan demikian setiap perubahan, baik sumberdaya, kondisi maupun jasa-jasa
yang ada di wilayah perencanaan akan terpadu dan terkontrol secara baik (Rais et
al. 2004).
Gunawan (1998) menjelaskan bahwa, SIG umumnya dipahami memiliki
kontribusi besar dalam pengelolaan wilayah pesisir, yakni (1) membantu
memfasilitasi berbagai pihak sektoral, swasta dan Pemda yang merencanakan
sesuatu, dapat dipetakan dan diintegrasikan untuk mengetahui pilihan-pilihan
manajemen dan alternatif perencanaan yang paling optimal., (2) merupakan alat
yang digunakan untuk menunjang pengelolaan sumberdaya pesisir yang
berwawasan lingkungan.
Dengan menggunakan SIG, kita dengan mudah dan cepat dapat melakukan
analisis keruangan (spatial analysis) dan pemantauan terhadap perubahan
lingkungan wilayah pesisir. Kemampuan SIG dalam analisis keruangan dan
ruang (pemetaan potensi) wilayah pesisir yang sesuai dengan daya dukung
lingkungannya.
Kelebihan SIG jika dibandingkan dengan sistem pengelolaan data dasar
yang lain adalah kemampuannya untuk menyajikan informasi spasial maupun non
spasial secara bersama-sama dalam bentuk vektor, raster ataupun data tabular
(Barus dan Wiradisastra, 2000).
Proses Pemecahan Konflik Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir
Proses pemecahan konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir, dapat
dilakukan dengan menentukan prioritas pengembangan wilayah melalui
penentuan kriteria-kriteria pemanfaatan dan pengelolaan yang berkelanjutan.
Proses pemecahan konflik ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode
Proses Hirarki Analitik (AHP).
Proses Hirarki Analitik (Analitical Hierarchy Process /AHP) adalah salah
satu alat analisis dalam pengambilan keputusan yang baik dan fleksibel. Metode
ini berdasarkan pada pengalaman dan penilaian dari pelaku/pengambil keputusan.
Metode yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty dua puluh tahun yang lalu,
terutama sekali membantu pengambil keputusan untuk menentukan kebijaksanaan
yang akan diambil dengan menetapkan prioritas dan membuat keputusan yang
paling baik ketika aspek kualitatif dan kuantitatif dibutuhkan untuk
dipertimbangkan.
Proses Hirarki Analitik (PHA) adalah suatu proses “rasionalitas sistematik”.
Dengannya kita dimungkinkan untuk mempertimbangkan suatu persoalan sebagai
satu keseluruhan dan mengkaji interaksi serempak dari berbagai komponennya di
dalam suatu hirarki (Saaty, 1991). Selanjutnya dikemukakan pula bahwa, PHA
menangani persoalan kompleks sesuai dengan interaksi-interaksi pada persoalan
itu sendiri. PHA dapat digunakan untuk merangsang timbulnya gagasan untuk
melaksanakan tindakan kreatif, dan untuk mengevaluasi keefektifan tindakan
tersebut. Selain itu, untuk membantu para pemimpin menetapkan informasi apa
yang patut dikumpulkan guna mengevaluasi pengaruh faktor-faktor relefan dalam
Marimin (2005) menyatakan bahwa, Analitical Hierarchy Process (AHP)
memiliki banyak keunggulan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan,
karena dapat digambarkan secara grafis, sehingga mudah dipahami oleh semua
pihak yang telibat dalam pengambilan keputusan. Dengan AHP, proses keputusan
kompleks dapat diuraikan menjadi keputusan-keputusan lebih kecil yang dapat
ditangani dengan mudah. Selain itu, AHP juga menguji konsistensi penilaian, bila
terjadi penyimpangan yang terlalu jauh dari nilai konsistensi sempurna, maka hal
ini menunjukkan bahwa penilaian perlu diperbaiki, atau hirarki harus distruktur
ulang.
Analisis kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik
pemanfaatan ruang yang terjadi, dengan cara memilih/menentukan prioritas
kegiatan/penggunaan lahan yang optimal, menggunakan pendekatan proses hirarki
analitik (AHP) dengan bantuan perangkat lunak “Expert Choice” (Saaty, 1991;
Tomboelu et al. 2000). Untuk dapat memberikan solusi yang diinginkan, ada 4
(empat) aspek yang dipertimbangkan, yaitu : aspek ekonomi, lingkungan, sosial
dan teknologi. Dari keempat aspek tersebut terdapat beberapa faktor yang sangat
mempengaruhi keputusan pada pemilihan atau penetapan prioritas penggunaan
lahan dalam pemanfaatan ruang yang akan dikembangkan, selanjutnya disusun
struktur hirarki fungsionalnya.
Menurut Permadi (1992), kelebihan Proses Hirarki Analitik (PHA) lebih
disebabkan oleh fleksibilitasnya yang tinggi terutama dalam pembuatan hirarki.
Sifat fleksibilitas tersebut membuat model PHA dapat menangkap beberapa tujuan
dan beberapa kriteria sekaligus dalam sebuah model atau sebuah hirarki. Bahkan
model tersebut bisa juga memecahkan masalah yang mempunyai tujuan-tujuan
yang saling berlawanan, kriteria-kriteria yang saling berlawanan, dan tujuan serta
kriteria yang saling berlawanan dalam sebuah model. Karenanya, keputusan yang
dilahirkan dari model PHA tersebut sudah memperhitungkan berbagai tujuan dan
berbagai kriteria yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan satu dengan
yang lainnya. Masalah-masalah seperti konflik, perencanaan, proyeksi, alokasi
sumberdaya, adalah beberapa dari banyak masalah yang dapat diselesaikan
Saaty (1991) mengemukakan bahwa tahapan dalam analisis data sebagai
berikut : (1) identifikasi sistem, (2) penyusunan struktur hirarki, (3) membuat
matriks perbandingan/komparasi berpasangan (pairwise comparison),
(4) menghitung matriks pendapat individu, (5) menghitung pendapat gabungan,
(6) pengolahan horisontal, (7) pengolahan vertikal, dan (8) revisi pendapat.
Selanjutnya Saaty (1991), menyatakan juga bahwa beberapa keuntungan
menggunakan PHA sebagai alat analisis adalah sebagai berikut :
1. PHA memberi model tunggal yang mudah dimengerti, luwes untuk beragam
persoalan yang tidak terstruktur.
2. PHA memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan sistem
dalam memecahkan persoalan kompleks.
3. PHA dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam satu
sistem dan tidak memaksakan pemikiran linier.
4. PHA mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah-milah
elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan
mengelompokan unsur yang serupa dalam setiap tingkat.
5. PHA memberi suatu skala dalam mengukur hal-hal yang tidak terwujud untuk
mendapatkan priorits.
6. PHA melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang
digunakan dalam menetapkan berbagai prioritas.
7. PHA menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap
alternatif.
8. PHA mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor sistem
dan memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-tujuan
mereka.
9. PHA tidak memaksakan konsensus tetapi mensintesis suatu hasil yang
representatif dari penilaian yang berbeda-beda.
10.PHA memungkinkan orang memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan
Poerwowidagdo (2003), menyatakan bahwa di dalam penyelesaian
persoalan dengan PHA terdapat tiga prinsip dasar yang harus di perhatikan, yaitu:
(i) menggambarkan dan menguraikan secara hirarki, yaitu memecah-mecah
persoalan menjadi unsur-unsur terpisah, (ii) pembedaan prioritas dan sintesis atau
penetapan prioritas, yaitu menentukan peringkat elemen-elemen menurut relatif
kepentingannya, dan (iii) konsistensi logis, yaitu menjamin bahwa semua elemen
dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan
METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini mengambil tempat di wilayah pesisir dari 3 (tiga) kecamatan
di Kabupaten Buru Propinsi Maluku, yakni : Kecamatan Namlea, Kecamatan
Waeapo dan Kecamatan Batabual. Pemilihan ketiga lokasi ini dikarenakan ketiga
lokasi tersebut berada pada satu kesatuan wilayah ekologis, yakni wilayah
ekologis Teluk Kaiely. Selain itu, ketiga kecamatan tersebut merupakan daerah
yang memiliki potensi pengembangan wilayah pesisir yang sangat besar.
Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih sepuluh bulan, mulai dari bulan
Juli 2006 sampai dengan April 2007. Untuk jelasnya lokasi studi dapat dilihat
pada Gambar 3.
Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan
dan pengukuran serta wawancara langsung di lapangan, serta studi kepustakaan
bagi data-data penunjang penelitian. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data
primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
sumbernya melalui hasil survei, observasi dan wawancara secara langsung di
lapangan. Data Primer, merupakan data ekologi yang meliputi
komponen-komponen fisika, kimia dan biologi, yang terdiri dari :
1) Data komponen fisik antara lain : komponen fisik kawasan pesisir yang
menyangkut data tentang, kedalaman perairan, kecerahan perairan, temperatur,
salinitas, kecepatan arus, gelombang dan pasang surut.
2) Data komponen kimia antara lain : pH, nitrat, nitrit, fosfat dan klorofil-a.
3) Data komponen biologi antara lain : data ekosistem wilayah pesisir seperti
ekosistem mangrove (luas dan tingkat pemanfaatannya, dan sebagainya),
terumbu karang, padang lamun (luasannya), dan vegetasi pantai lainnya.
Alat yang digunakan dalam pengumpulan data primer ini antara lain : hand GPS,
grabs, meteran, stop watch, palem pasut, secchi disk, thermometer, refractometer,
pH meter (lakmus). Sementara lokasi stasiun pengamatan dapat dilihat dalam
Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian 2
Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan data dari dinas atau
instansi terkait seperti Bappeda, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan,
Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, BPS dan dinas-dinas terkait lainnya di
Kabupaten Buru. Data Sekunder yang terdiri dari :
(1) Data geologi, fisiologi, hidrologi, iklim, tata air, kemampuan lahan
(kelerengan dan kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, drainase, erosi tanah,
sedimentasi)
(2) Data Sosial Ekonomi dan Budaya, yang meliputi : data luas desa/kecamatan
yang menjadi lokasi penelitian, jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga,
tingkat pendidikan, pendapatan, mata pencaharian, dan juga kelembagaan
yang terdapat di daerah penelitian seperti koperasi, dan tempat pendaratan
ikan (TPI).
(3) Data Kelembagaan dan Perundang-undangan serta peraturan daerah yang
berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir di lokasi penelitian.
(4) Data pemanfaatan ruang seperti peruntukan untuk kegiatan perikanan
(budidaya tambak, budidaya rumput laut, keramba jaring apung, dan
sebagainya), pariwisata, pemukiman, dan konservasi.
(5) Data Penunjang, yang meliputi : literatur-literatur penunjang dan peta-peta
yang terkait dengan penelitian, seperti :
Peta rupa bumi Kabupaten Buru.
Peta wilayah admistrasi Kabupaten Buru.
Peta wilayah perairan Kabupaten Buru.
Peta topografi dan batimetri Kabupaten Buru.
Peta pola pemanfaatan lahan Kabupaten Buru.
Citra Satelit Landsat 7 ETM+ Kabupaten Buru
Pengambilan responden dilakukan secara purposive dengan pertimbangan
responden adalah aktor/pengguna lahan yang dianggap memiliki keahlian atau
yang memiliki kemampuan dan mengerti permasalahan terkait, serta yang dapat
mempengaruhi pengambilan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak
Metode pengambilan responden dalam rangka menggali informasi/pendapat
stakeholders adalah metode expert judgement (Pendapat Pakar). Pakar ditentukan
secara purposive sampling. Pakar responden berjumlah 16 orang, yang merupakan
key persons (tokoh kunci) yang mewakili kelompok-kelompok stakeholders yang
diperoleh pada saat identifikasi stakeholders. Kelompok stakeholders ini meliputi
setiap unsur yang terkait dengan pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Buru,
yaitu dari unsur birokrasi yang diwakili oleh Bupati Kabupaten Buru, Ketua
DPRD Kabupaten Buru, Kepala Bappeda Kabupaten Buru, Kepala-kepala Dinas
Teknis terkait (Kadis. Perikanan, Kadis. Kehutanan, Kadis. Perhubungan, Kadis.
Pendidikan), Camat dari ketiga kecamatan pada lokasi penelitian dan unsur
Kepala Desa yang diwakili oleh Kepala Desa Masarete, akademisi yang diwakili
oleh Universitas Iqra Buru, kelompok nelayan yang diwakili oleh ketua koperasi
nelayan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli pada pengelolaan
pesisir dan masyarakat umum, unsur pengusaha yang diwakili oleh pengusaha
perikanan, dan unsur masyarakat umum yang diwakili oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Kabupaten Buru.
Jenis data, satuan pengukuran, metode pengumpulan dan metode analisis
serta bahan/alat yang digunakan dalam penelitian ini, disajikan dalam Tabel 1
[image:41.612.125.514.457.705.2]berikut ini.
Tabel 1. Komponen Data dan Cara Pengumpulannya.
Komponen Data Satuan Metode Pengumpulan Metode
Analisi
Sumber Data
1 2 3 4 5
A. Data Fisik - Kimia 1. Iklim Makro dan
Mikro a. Suhu
b. Kelembaban c. Curah Hujan d. Hari Hujan
2. Topografi dan Fisiologi
a. Ketinggian Tempat b. Kelerengan
c. Panjang Lereng
d. Bentuk Wilayah O C % mm hari m/dpl % m -
Pengumpulan data sekunder dan Analisis Deskripif Pengumpulan data sekunder Pengumpulan data sekunder Pengumpulan data sekunder dan Analisis Deskriptif
Interpretasi Peta Topografi
Interpretasi Peta Topografi
Interpretasi Peta Topografi
Interpretasi Peta Topografi
Daftar Isian
Daftar Isian Daftar Isian Daftar Isian
Peta / Laporan
Peta / Laporan
Peta / Laporan
Peta / Laporan
Tabel 1. (Lanjutan)
1 2 3 4 5
3. Pola Penggunaan Lahan
a. Penggunaan Lahan
4. Geologi a. Formasi
Geologi
5. Kondisi Fisik Perairan
a. Substrat Dasar Perairan b. Kedalaman
Perairan
6. Hidro-Oseanografi a. Pola Arus
b. Kecepatan arus
c. Gelombang
d. Kecerahan Air e. Suhu
f. Salinitas g. pH
B. Data Perikanan 1. Perikanan
Budidaya a. Luas Area
Budidaya b. Produksi
2. Perikanan Tangkap
a. Unit
Penangkapan b. Daerah dan
Musim
c. Produksi
C. Data Sosekbud 1. Sosial Ekonomi
a. Mata Pencaharian b. Pendapatan Masyarakat c. Fasilitas Perekonomian - Ha, % - m m/det m m m O C O /oo - Ha Ton/Thn Unit
Km2,Bln
Ton/Thn KK/Bln Rp Unit Pengamatan Lapangan, pengumpulan data sekunder dan interpretasi peta serta studi pustaka
Interpretasi Peta dan Studi Pustaka
Pengamatan langsung di lapangan
Pengukuran langsung di lapangan dan data sekunder
Data sekunder dan pengukuran lapangan Data sekunder dan pengukuran di lapangan. Data sekunder, pengamatan lapangan dan estimasi. Pengukuran di lapangan. Pengukuran di lapangan. Pangukuran di lapangan. Pengukuran di lapangan.
Data Sekunder Data Sekunder Data Sekunder Data Sekunder/Wawancara Data Sekunder Data Sekunder Data Sekunder Data Sekunder
Peta / Laporan
Peta / Laporan
[image:42.612.126.512.98.706.2]Tabel 1. (Lanjutan)
1 2 3 4 5
2. Sosial Budaya a. Demografi
Penduduk b. Komposisi
Penduduk c. Tingkat
Penididikan d. Adat Istiadat
Jiwa/KK
Sex ratio (%)
-
Masyara kat
Data Sekunder
Data Sekunder
Data Sekunder
Wawancara
Statistik
Statistik
Statistik
Kuisioner
BPS Kab. Buru
BPS Kab. Buru
Dinas PKPO Kab. Buru Dinas PKPO Kab. Buru Responden
Perencanaan pengeloalaan didasarkan pada hasil analisis kesesuaian lahan
yang mengintegrasikan biogeofisik kawasan pesisir dan lautan Kabupaten Buru.
Alur sistematika proses penelitian yang dilaksanakan dapat dilihat pada Gambar 3
[image:43.612.124.515.104.231.2]Gambar 3. Alur Sistematika Proses Penelitian 2