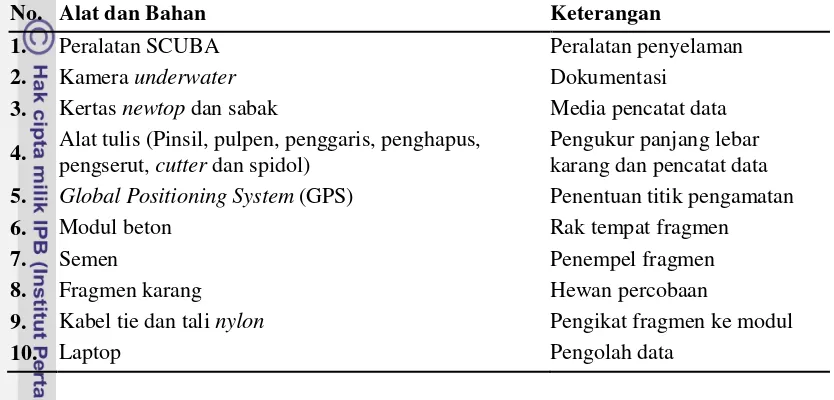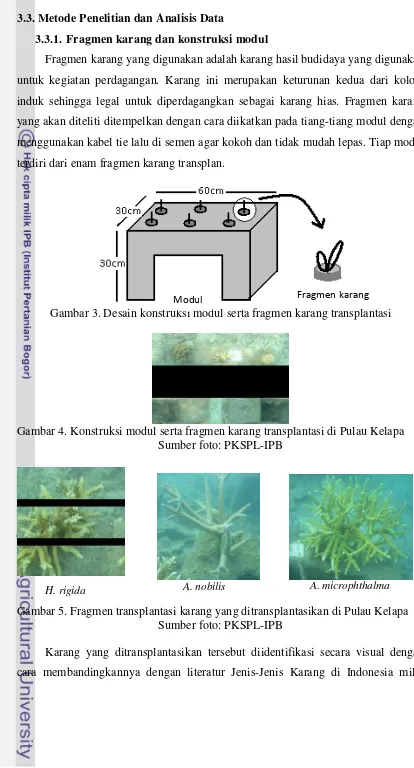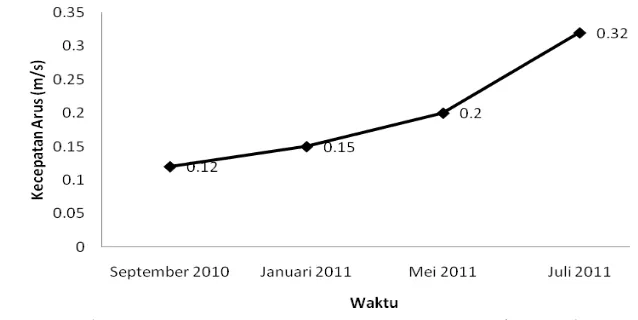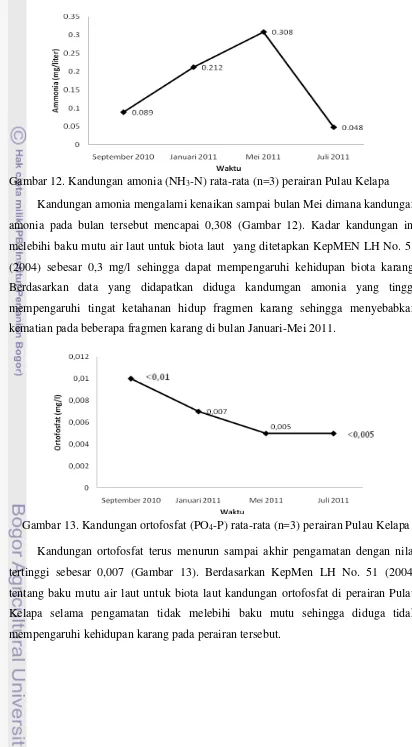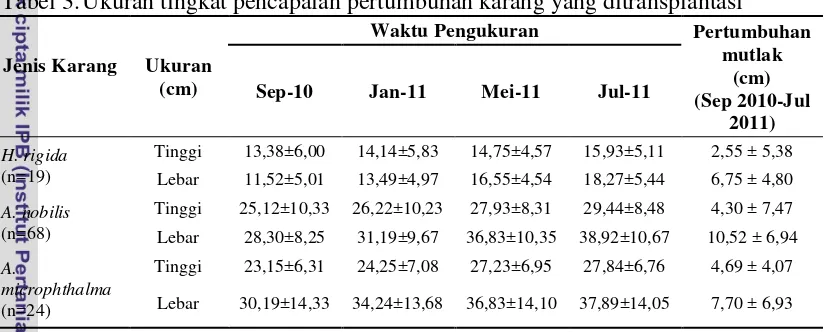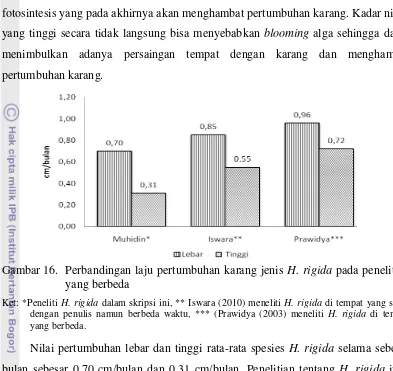1.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kepulauan Seribu merupakan salah satu ekosistem laut di perairan utara
Jakarta yang didominasi oleh ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan daratan
pulau-pulau karang yang menjadi habitat penting berbagai jenis biota perairan laut
(Anonymous 1991; 1994; 1997; dan 2002 in Sachoemar 2008). Kepulauan Seribu
memiliki beragam jenis biota, diantaranya 8 jenis lamun, 64 marga karang keras,
242 jenis ikan terumbu, dan 141 spesies makrobentos (Estradivari et al. 2007).
Sebagian besar masyarakat Kepulauan Seribu dan nelayan masyarakat utara
Jakarta bergantung hidupnya pada sumberdaya terumbu karang di Kepulauan Seribu
(Napitupulu et al. 2006). Namun, tekanan lingkungan baik yang bersifat alami maupun antropogenik semakin banyak terjadi dan menyebabkan degradasi terhadap
keberadaan ekosistem terumbu karang di Kepulauan ini, diantaranya pencemaran
minyak yang terjadi pada tahun 2003-2004 dimana sebanyak 78 pulau di Taman
Nasional Kepulauan Seribu terkena dampaknya (Taman Nasional Kepulauan Seribu
2004), polusi, perikanan berlebih dan merusak, serta perubahan fungsi habitat (Yusri
& Estradivari 2007; Suharsono 2005; dan Ongkosongo 1986 in Setyawan et al.
2011, LAPI-ITB 2001). Kepulauan Seribu juga sangat rentan terhadap ancaman
pencemaran dari daratan, mengingat secara osenografis lokasinya berhubungan
langsung dengan Teluk Jakarta tempat bermuaranya 13 sungai yang melintasi Kota
Jakarta yang padat pemukiman dan industri (Anna 1999 in Sachoemar 2008).
Peningkatan suhu permukaan laut atau El-Nino juga mengancam terumbu karang
Kepulauan Seribu (Suharsono 1998). Pada tahun 1997-1998, sekitar 90-95%
terumbu karang Kepulauan Seribu hingga kedalaman 25 meter mengalami kematian
akibat El-Nino, meskipun sekitar 20-30% tutupan karang hidup mengalami
pemulihan dua tahun kemudian (Burke et al 2002). Penelitian yang dilakukan oleh
yayasan Terumbu Karang Indonesia (TERANGI) menemukan tutupan karang keras
Kepulauan Seribu pada tahun 2009 hanya sebesar 34,3%.
Besarnya kerusakan terumbu karang yang terjadi membutuhkan penanganan
yang tepat agar ekosistem terumbu karang tersebut bisa pulih dengan cepat. Salah
menggunakan teknik transplantasi karang. Transplantasi karang adalah suatu teknik
penanaman dan pertumbuhan koloni karang baru dengan metode fragmentasi,
dimana benih karang diambil dari suatu induk koloni tertentu (Harriot dan Fisk
1988).
Beberapa karang yang telah diteliti diantaranya jenis karang bercabang
Acropora di Pulau Lancang dan di sebelah utara Pulau Pari oleh Boli (1994) dengan
tingkat pertumbuhan rata-rata 1 cm/bulan. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat
Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) IPB dengan Asosiasi Karang Keras dan Ikan
hias Indonesia (AKKII) mendapatkan karang jenis Trachyphyllia geofforoyi dan
Wellsophyllia radiate yang mempunyai life form masif pada kedalaman 12 meter
mempunyai pertumbuhan tinggi sebesar 0,73 mm/bulan dan 0,56 mm/bulan dan
pertumbuhan lebar 0,93 mm/bulan dan 1,22 mm/bulan atau kurang dari 1 cm/bulan
sedangkan karang bercabang Acropora formosa pada kedalaman 10 meter
mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi dan lebar sebesar 0,76 cm/bulan dan 1,15
cm/bulan dan pada kedalaman 3 meter mempunyai tingkat pertumbuhan lebih besar
yaitu 1,14 cm/bulan dan 1,88 cm/bulan (Sadarun 1999). Menurut Supriharyono
(2007) spesies dengan life form branching umumnya mempunyai tingkat
pertumbuhan sangat cepat yaitu bisa >2 cm/bulan sedangkan coral massive
tumbuhnya sangat lambat yaitu hanya <1 cm/tahun.
Salah satu pulau di Kepulauan Seribu adalah Pulau Kelapa yang merupakan
pusat pemerintahan Kelurahan Pulau Kelapa. Pulau ini mempunyai jumlah
penduduk terbesar diantara semua pulau di Kepulauan Seribu dan memiliki
kepadatan penduduk terbesar kedua setelah Pulau Panggang (Noor 2003; Estradivari
et al. 2007). Tingginya jumlah penduduk di Pulau ini mempengaruhi kondisi
ekosistem terumbu karang sehingga diperlukan upaya transplantasi karang untuk
memperbaiki kondisi ekosistem terumbu karang dan meningkatkan penutupan
terumbu karang tersebut sehingga diharapkan akan memberikan pengaruh positif
terhadap terumbu karang di Kepulauan Seribu.
1.2. Rumusan Masalah
Degradasi terumbu karang di Kepulauan Seribu salah satunya di Pulau Kelapa
memerlukan langkah nyata untuk bisa memperbaiki kerusakan tersebut. Salah satu
karang agar ekosistem terumbu karang bisa cepat pulih. Secara skematis, proses
pemulihan ekosistem terumbu karang disajikan pada Gambar 1.
Gambar 1. Skema pemulihan ekosistem terumbu karang
1.3. Tujuan
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui laju pertumbuhan karang serta
parameter yang mempengaruhi transplantasi karang jenis H. rigida, A. nobilis, dan
A. microphthalma di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, sehingga bisa diketahui
tingkat keberhasilan dari metode transplantasi karang terhadap jenis yang ditanam. Faktor alami:
1. Pemanasan global 2. Sedimentasi
Ekosistem terumbu karang Degradasi ekosistem
terumbu karang
Rehabilitasi terumbu karang
Transplantasi karang
Ekosistem pulih Pemilihan jenis karang:
1. H. rigida 2. A. nobilis
3. A. microphthalma Faktor antropogenik: 1. Tumpahan minyak 2. Limbah antropogenik 3. Perubahan fungsi habitat 4. Penangkapan ikan
merusak dan berlebih
2.
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Biologi Karang
Karang tergolong dalam jenis makhluk hidup (hewan) yaitu sebagai individu
organisme atau komponen dari masyarakat hewan (Rahmawaty 2004). Dalam
bentuk yang paling sederhana, karang hanya bisa terdiri dari sebuah polip yang
mempunyai bentuk seperti tabung dengan mulut di bagian atas yang dikelilingi oleh
tentakel (Burke et al 2002).
Terumbu karang (coral reefs) merupakan kumpulan masyarakat (binatang)
karang, yang hidup di dasar perairan, yang berupa batuan kapur (CaCO3), dan
mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk menahan gaya gelombang laut
(Supriharyono 2007). Terumbu karang merupakan ekosistem yang terdapat khas di
daerah tropis. Terumbu terbentuk dari endapan-endapan masif kalsium karbonat
yang dihasillkan oleh organisme karang pembentuk terumbu (karang hermatifik)
dari filum Cnidaria, ordo Sclerectinia yang hidup bersimbiosis dengan alga
zooxanthellae dan sedikit tambahan alga berkapur dan organisme lain yang
mengsekresi kalsium karbonat (Bengen 2001).
Karang yang ada di dunia terbagi dua kelompok karang, yaitu karang
hermatifik dan karang ahermatifik. Perbedaan kedua kelompok karang ini terletak
pada kemampuan karang hermatifik dalam menghasilkan terumbu. Kemampuan
menghasilkan terumbu ini disebabkan oleh adanya sel-sel tumbuhan yang
bersimbiosis di dalam jaringan karang hermatifik yang dinamakan zooxanthellae.
Hasil samping dari aktivitas fotosintesis tersebut adalah berupa endapan kalsium
karbonat, yang struktur dan bentuk bangunannya khas.
2.1.1. Cara makan dan sistem reproduksi
Thamrin (2006) menyatakan pada umumnya karang mempunyai tentakel yang
berkontraksi atau dapat menarik dan menjulur yang berfungsi untuk menangkap
mangsa dari perairan dan sebagai alat pertahanan diri. Namun, kebutuhan energi dan
makanan karang sebagian besar tergantung pada simbionnya yaitu zooxanthellae
yang hidup di dalam jaringan endodermis karang. Sebagian besar jenis karang
Kebutuhan karang terbesar disuplai oleh simbionnya zooxanthellae, bahkan Veron
(1993) in Thamrin (2006) menyatakan kebutuhan karang yang berasal dari
simbionnya zooxanthellae mencapai sekitar 98%, bahkan ada yang memperkirakan
hampir mencapai 100% dengan kisaran antara 75-99% (Tackett dan Tackett 2002 in
Thamrin 2006). Apabila dirinci maka sumber makanan karang dapat dikelompokkan
menjadi dua, yaitu:
1. Zooplankton yang melayang dalam air.
2. Menerima hasil fotosintesis zooxanthellae
Thamrin (2006) mengelompokkan mekanisme bagaimana mangsa yang
ditangkap karang mencapai mulut kedalam tiga cara, yaitu:
1. Mangsa ditangkap lalu dibawa oleh tentakel ke mulut.
2. Mangsa ditangkap lalu terbawa ke mulut oleh gerakan silia di sepanjang
tentakel.
3. Mesentrial filament yang berasal dari rongga perut juga dimanfaatkan untuk
menangkap partikel makanan disamping digunakan untuk pencernaan.
Sistem reproduksi karang dilakukan baik dengan seksual maupun aseksual.
Sebagian besar reproduksi karang dilakukan dengan cara ovipar. Perkembangan
gamet karang ditemukan dalam dua kelompok, yaitu sebagian besar bersifat
hermafrodit dan sebagian kecil bersifat gonochoric. Mekanisme reproduksi melalui
fertilisasi disusul embriogenesis di dalam tubuh dan ada juga yang melakukan
spawning yang disusul fertilisasi dan embriogenesis di dalam kolom air (Thamrin
2006). Menurut Thamrin (2006) tipe perkembangan gamet dan tempat terjadinya
fertilisasi dan embryogenesis pada karang dipengaruhi lingkungan dan letak lintang
dimana karang tersebut berada. Namun, secara umum jumlah terbesar jenis karang
mempunyai perkembangan gamet secara hermafrodit dengan fertilisasi serta
embryogenesis terjadi di dalam kolom air atau dengan spawning. Waktu reproduksi
pada kebanyakan spesies karang antara menjelang malam sampai tengah malam
(Harrison et al. 1994; Shlesinger & Loya 1985; Babcock et al. 1986; dan Szmant
1986 in Rani et al. 2005). Umumnya waktu pemijahan terjadi dalam suatu periode
tertentu setelah matahari terbenam pada setiap populasi, dan waktu pemijahan pada
umumnya konsisten dari tahun ke tahun (Harrison et al. 1984 dan Babcock et al
Cara reproduksi A. nobilis bersifat pemijah hermafrodit (Spawning
hermafrodit) yang merupakan tipe umum dari karang skleraktinia (Harrison and
Wallace 1990; Richmond and Hunter 1990; Richmond 1997 in Rani et al. 2005).
Berdasarkan penelitian Rani dan Jamaluddin (2005) di Pulau Baranglompo,
Makasar, diketahui pemijahan A. nobilis bersifat hermafrodit simultan (broadcast
spawning simultaneous hermaphrodite). A. nobilis mengeluarkan kemasan gamet
dalam satu paket buntelan telur-sperma (egg-sperm bundles) secara perlahan
(lambat) melalui mulut polip dengan sedikit sentakan selama 5-15 menit. Jumlah
telur dari tiap buntelan berkisar 5-13 butir (n=38) dengan ukuran sel telur berkisar
289-785 µm dengan rata-rata sebesar 416±24,06 µm (n=46). Polip di bagian tengah
lebih sinkron mengeluarkan gamet dibandingkan dengan apikal atau bagian basal
cabang. Penelitian Rani et al. (2005) menunjukkan waktu pemijahan A. nobilis
terjadi pada saat bulan purnama (tiga malam) dan bulan baru atau gelap (empat
malam).
2.1.2. Pertumbuhan dan bentuk koloni karang Acropora
Laju pertumbuhan pada tiap koloni karang bisa berbeda satu dengan yang
lainnya tergantung kepada spesies, umur koloni, dan lokasi terumbu tersebut.
Namun, koloni yang muda dan kecil cenderung tumbuh lebih cepat daripada koloni
yang lebih tua, koloni yang besar dan bercabang (Nybakken 1992). Raymond et al.
(2006) menyatakan karang dengan bentuk submasif dan masif biasanya
menampilkan pertumbuhan lebih lambat tapi lebih baik dalam bertahan hidup.
Sedangkan spesies dengan bentuk percabangan yang halus dan foliose memiliki
tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi namun buruk dalam bertahan hidup.
Nybakken (1992) menyatakan bahwa lokasi karang juga mempengaruhi
bentuk pertumbuhan dari spesies karang. Spesies karang yang terdapat di tempat
yang lebih dalam memiliki bentuk yang lebih tipis dan kurus, hal ini mungkin
disebabkan oleh proses kalsifikasi yang kurang optimal. Arus menyebabkan bentuk
cabang mempunyai penyesuaian arah tertentu sedangkan gerakan gelombang
menyebabkan spesies bercabang mempunyai cabang yang lebih pendek dan tumpul.
English et al. (1994) membagi karang batu berdasarkan bentuk
pertumbuhannya menjadi dua yaitu karang Acropora dan non-Acropora.
karang batu tersebut. Karang Acropora mempunyai axial dan radial koralit
sedangkan karang non-Acropora hanya mempunyai radial saja. Selain itu,
pengelompokkan ini didasarkan pada jumlah kelompok karang Acropora yang
menurut Thamrin (2006) umumnya merupakan salah satu kelompok karang yang
sangat dominan pada suatu perairan.
Genera karang Acropora umumnya memiliki bentuk morfologi koloni yang
bercabang dan salah satu komponen utama pembangun terumbu karang.
Pertumbuhan karang bercabang berlangsung lebih cepat pada bagian ujung cabang
tanpa zooxanthellae dibandingkan dengan bagian basal (Goreau 1959; Pearse &
Muscatine 1971; Oliver 1984; dan Rinkevich & Loya 1984 in Rani et al. 2005).
2.2. Faktor Pembatas Pertumbuhan Karang
Keanekaragaman, penyebaran, dan pertumbuhan hermatifik karang
tergantung pada lingkungannya. Kondisi ini pada kenyataannya tidak selalu tetap,
akan tetapi seringkali berubah karena adanya gangguan, baik yang berasal dari alam
atau aktivitas manusia. Gangguan dapat berupa faktor fisika, kimia, maupun
biologis. Faktor-faktor fisika-kimia yang diketahui dapat mempengaruhi kehidupan
dan /atau laju pertumbuhan karang antara lain cahaya matahari, suhu, salinitas, pH
dan sedimen. Sedangkan faktor biologis, biasanya berupa predator atau
pemangsanya (Supriharyono 2007).
Titik kompensasi binatang karang terhadap cahaya adalah pada intensitas
cahaya antara 200-700 f.c. atau umumnya terletak antara 300-500 f.c. (Kanswisher
dan Wainwright 1967 in Iswara 2010). Birkeland (1997) menyatakan pada
umumnya terumbu karang ditemukan pada perairan dengan suhu 18-36 °C, tetapi menurut Nybakken (1992) terumbu karang dapat mentolerir suhu sampai 36-40 °C. Pada daerah tropis suhu rata-rata tahunan untuk perkembangan optimal terumbu
karang adalah 25-30 °C, sedangkan salinitas air laut yang normal untuk kehidupan karang hermatifik adalah 32-350/00 (Nybakken 1992), meskipun menurut Suharsono
(1996) pada salinitas ekstrem seperti di Teluk Persia 460
/00 dan di Laut Hindia
Selatan 260
/00terumbu karang masih dapat hidup.
Padatan tersuspensi (kekeruhan) berhubungan dengan kecerahan perairan.
siklus hidup hewan karang. Sedimen berpengaruh terhadap pertumbuhan binatang
karang baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung sedimen
adalah dengan menutupi polip karang sehingga menyebabkan kematian pada karang.
Sedangkan pengaruh tidak langsung yaitu menghalangi penetrasi cahaya sehingga
mengganggu fotosintesis (Bak 1978 in Supriharyono 2007). Selain itu, sedimen
yang tinggi memaksa karang untuk mengeluarkan energi lebih guna menghalau
sedimen tersebut yang mengakibatkan turunnya laju pertumbuhan karang (Pastorok
dan Bilyard 1985 in Supriharyono 2007). Tingkat kekeruhan yang normal bagi
terumbu karang berkisar antara 0-10 mg/liter (Rogers 1990, Larcombe et al. 1995 in
Thamrin 2006).
Arus diperlukan karang untuk memperoleh makanan dalam bentuk
zooplankton, oksigen, serta dalam membersihkan permukaan karang dari sedimen
(Thamrin 2006; Stoecker 1978 in Estradivari at al. 2009). Rachmawati (2001) in
Wibowo (2009) menyatakan bahwa gelombang yang cukup kuat akan menghalangi
pengendapan sedimen pada koloni karang. Karang sendiri memiliki kemampuan
dalam membersihkan permukaan tubuhnya (koloninya) dari sedimen, tetapi dalam
jumlah yang sangat terbatas. sehingga jenis karang yang ditemukan dalam perairan
yang memiliki tingkat sedimentasi yang tinggi hanya terbatas pada jenis karang
tertentu.
Amonium tidak bersifat toksik (innocuous) namun pada suasana alkalis (pH
tinggi) lebih banyak ditemukan amonia yang tak terionisasi (unionized) dan bersifat
toksik (Tebbut 1992 in Effendi 2003). Karang biasanya hidup pada perairan dengan
nutrien anorganik yang rendah (Grover 2003 in Wibowo 2009). Nutrien yang tinggi
di perairan dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman dan alga pada perairan
tersebut juga meningkat. Biomassa makroalga yang besar dapat menutupi karang
sehingga memiliki efek seperti halnya penutupan karang oleh partikel sedimen yang
besar (Rachmawati 2001 in Wibowo 2009).
2.3.Klasifikasi dan Ciri-Ciri Karang yang Diteliti
Menurut Wells (1954) in Suharsono (2008) klasifikasi hewan karang
pembentuk terumbu yang ditransplantasikan sebagai berikut:
Kingdom : Animalia
Kelas : Anthozoa
Sub kelas : Zoantharia
Ordo : Scleractinia
Famili : Merulinidae
Genus : Hydnophora
Spesies : H. rigida
Famili : Acroporidae
Genus : Acropora
Spesies : A. nobilis
A. microphthalta
Famili Merulinidae terdiri dari tiga genera, yaitu Merulina, Scapophyllia, dan
Hydnophora. Semua genera Famili Merulinidae memiliki zooxanthellae dan
berbentuk koloni. Struktur rangkanya mirip Faviidae tetapi sangat difusi dan tanpa
paliform. Lembah pemisah antar koralit dangkal dan kabur atau seperti menyebar.
Semua genera menyebar dan berada di indo-Pasifik (Veron 2000). Famili
Merulinidae mempunyai koloni masif, merayap atau lembaran. Adanya alur-alur
saling bersatu, begitu juga struktur koralit (Suharsono 2008).
Berdasarkan Suharsono (2008) Hydnophora memiliki koloni merayap, masif
atau bercabang. Marga ini dicirikan dengan adanya struktur hydnophore yaitu
bentuk kerucut-kerucut kecil yang terbentuk dari dinding antara koralit yang
terpecah-pecah. Hydnophore ini menutupi seluruh permukaan sehingga marga ini
mudah dikenali. Genus Hydnophora terdiri dari lima jenis dan tersebar di seluruh
perairan Indonesia. H. rigida memiliki karakter koloni bercabang dengan koralit
berbentuk hydnophoroid kecil dengan sebaran yang tidak teratur. Warna hijau atau
coklat muda. Jenis ini tersebar di seluruh peraiaran Indonesia dan sangat umum
dijumpai di lereng terumbu. Sedangkan menurut Veron (2000) H. rigida memiliki
ciri-ciri koloni terdiri dari cabang-cabang yang tidak teratur, biasanya memiliki
lapisan encrusting atau rata pada bagian bawah atau dasar koloni. Monticules
biasanya berfungsi membentuk tonjolan seperti gunung ke arah sisi. Cabang utama
memiliki panjang 7-12 mm. Berwarna krim atau hijau.
Acroporidea terdiri atas empat genus, yaitu Montipora, Astreopora,
terbanyak dan hampir ditemukan menyebar di seluruh wilayah perairan Indonesia.
Suharsono (2008) menyatakan bahwa ketiga marga Acropora, Anacropora, dan
Montipora mempunyai ciri yang hampir sama yaitu koralit kecil, tanpa kolumella,
septa sederhana dan tidak mempunyai struktur tertentu dan koralit dibentuk secara
ekstratentakular. Marga keempat Astreopora agak berbeda yaitu ukuran koralit lebih
besar, septa berkembang dengan baik dan dengan kolumella yang sederhana. Genus
Acoropora biasanya mempunyai bentuk pertumbuhan bercabang (branching),
tabulate, digitate dan kadang-kadang berbentuk encrusting atau submasif. Genus
Acropora memiliki bentuk percabangan sangat bervariasi dari karimbosa, arboresen,
kapitosa dan lain-lainnya. Ciri khas dari marga ini adalah mempunyai axial dan
radial koralit. Bentuk radial koralit juga bervariasi dari bentuk tubular basiform, dan
tenggelam. Marga ini mempunyai 113 jenis, tersebar di perairan Indonesia. Menurut
Veron (2000) selain memiliki dua tipe koralit, yaitu axial dan radial Acropora tidak
mempunyai kolumela, dinding koralit dan koenesteumnya poros serta tentakelnya
hanya keluar di malam hari.
A. nobilis memiliki bentuk percabangan arboresen, radial koralit terdiri dari
dua ukuran besar dan kecil dengan bukaan demidiate. Warna coklat muda dan coklat
keabu-abuan. Hidup di tempat dangkal, umum dijumpai dan tersebar di seluruh
perairan Indonesia (Suharsono 2008). Selain itu, A. nobilis memiliki cabang silinder
yang tegak dan besar dengan ketinggian dapat mencapai sekitar lima meter, cabang
basal horizontal hanya berkembang di perairan dangkal. Radial koralit mempunyai
ukuran dan bentuk bermacam-macam. Warna krim, cokelat, biru, kuning, dan hijau.
Warna koloni individu seragam kecuali pada ujung cabang berwarna sedikit pucat.
A. microphthalma memiliki karakteristik dengan tinggi koloni dapat mencapai lebih
dari dua meter dan percabangan yang luas, arboresen, kecil, ramping, dan lurus.
Subcabang rapi dan teratur, radial koralit kecil, banyak, dan ukuran sama. Warna
umumnya pucat abu-abu, kadang pucat coklat atau krim (Veron 2000).
2.4. Transplantasi Karang
Transplantasi karang adalah kegiatan untuk memperbayak koloni karang
melalui fragmentasi spesimen yang berasal dari habitat alam atau sumber lainnya
dengan cara melekatkan fragmen tersebut pada media buatan dan menumbuhkan
mendefinisikan transplantasi karang sebagai suatu teknik penanaman dan
pertumbuhan koloni karang baru dengan metode fragmentasi, dimana benih karang
diambil dari suatu induk koloni tertentu, sedangkan menurut Hariot dan Fisk (1988)
transplantasi karang adalah pencangkokan atau pemotongan karang hidup untuk
ditanam di tempat lain atau di tempat yang karangnya telah mengalami kerusakan.
Transplantasi karang bertujuan untuk mempercepat regenerasi terumbu
karang yang telah mengalami kerusakan atau untuk memperbaiki daerah terumbu
karang yang rusak, terutama untuk meningkatkan keragaman dan persen penutupan
(Hariot dan Fisk 1998 in Soedharma dan Arafat 2007). Selain itu, masih menurut
Hariot dan Fisk (1998) in Sandy (2000) dijelaskan bahwa tranplantasi dapat
digunakan untuk merehabilitasi terumbu karang secara cepat, karena waktu yang
dibutuhkan antara beberapa bulan sampai satu tahun dengan tingkat keberhasilan
50-100%. Tujuan transplantasi karang menurut Dirjen PHKA (2008) adalah untuk
mempercepat regenerasi dari terumbu karang sehingga dapat dimanfaatkan untuk
perdagangan dan peningkatan kualitas habitat karang.
Transplantasi karang telah dipelajari dan dikembangkan sebagai teknologi
pilihan dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang terutama pada daerah-daerah
yang memiliki nilai ekonomi tinggi (Hariot dan Fisk 1988). Tranplantasi karang
telah digunakan di beberapa Negara untuk merehabilitasi ekosistem terumbu karang
yang telah rusak seperti di Filipina transplantasi karang telah diterapkan untuk
menyembuhkan ekosistem terumbu karang yang telah mengalami kerusakan akibat
penangkapan ikan dengan bahan peledak (Auberson 1982), Singapura menggunakan
tranplantasi karang untuk menyimpan (menyelamatkan) spesies yang habitatnya
direklamasi (Plucer-Rosario and Randall 1987), sedangkan di Florida transplantasi
karang telah digunakan untuk mempercepat dan memperbanyak tutupan ekosistem
terumbu karang (Gittings et al. 1988) dan di Taman Laut Great Barrier Reef,
tranplantasi karang digunakan untuk mempercepat regenerasi ekosistem terumbu
karang akibat serangan achantaster plancii (Harriot dan Fisk 1988).
2.4.1. Transplantasi karang di Indonesia
Penelitian mengenai transplantasi karang terhadap beberapa jenis karang telah
banyak dilakukan seperti penelitian terhadap tingkat keberhasilan hidup karang
in Johan et al. 2008). Penelitian terhadap transplantasi karang jenis Acropora
sebanyak 40 sampel dari sebelas spesies karang dengan menggunakan substrat
buatan (keramik) di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta (Sadarun 1999).
Penelitian tingkat keberhasilan transplantasi karang batu di Pulau Pari, Kepulauan
Seribu, Jakarta dengan meggunakan tiga jenis karang genus Acropora yaitu
Acropora Donei, Acropora Acuminata dan A. Formosa (Johan et al. 2008).
Karang yang ditransplantasikan mempunyai kecepatan pertumbuhan yang
berbeda-beda. Supriharyono (2007) menyatakan bahwa karang dengan life form
branching umumnya mempunyai tingkat pertumbuhan sangat cepat yaitu bisa >2
cm/bulan sedangkan coral masif tumbuhnya sangat lambat yaitu hanya <1 cm/tahun.
Sadarun (1999) mendapatkan pertumbuhan karang branching dari jenis Acropora
yongei dan Acropora digitifera yang ditranplantasikan di Pulau Pari, Kepulauan
Seribu selama lima bulan mempunyai pertumbuhan rata-rata sebesar 0,4 cm dan 0,1
cm.
2.4.2. Metode transplantasi karang
Jaap (1999) in Prawidya (2003) menyatakan bahwa tujuan utama transplantasi
karang adalah mempercepat pemulihan ekosistem terumbu karang. Transplantasi
dinyatakan sukses dari sudut pandang biologis dengan tingkat ketahanan hidup
berkisar antara 50-100% (Harriot dan Fisk 1998 in Herdiana 2001). Menurut Harriot
dan Fisk (1988), karang yang paling cocok untuk tranplantasi adalah karang
Acropora bercabang seperti halnya yang pernah mereka lakukan di Samudera
Pasifik. Hal ini karena karang Acropora memiliki tingkat ketahanan hidup yang
besar, sangat indah, kecepatan pertumbuhan yang tinggi, dan kemampuan yang
bersar dalam hal menutupi daerah ekosistem terumbu karang yang kosong.
Adverland (2001) menjelaskan bahwa hal yang harus diperhatikan dalam
teknik pengembangbiakan karang adalah koloni yang dikembangkan haruslah koloni
yang sehat dan pemotongan koloni hendaknya memperhatikan arah arus untuk
menghindari penutupan koloni akibat pelendiran koloni. Alat yang digunakan untuk
memotong fragmen dari induknya juga berbeda-beda tergantung dari bentuk
pertumbuhan koloni. Untuk koloni yang bentuk koloninya bercabang, digunakan
sebaiknya gergaji besi. Arah potongan karang juga menentukan laju pertumbuhan
jangka panjang koloni tersebut.
Menurut Clark dan Edwards (1995) in Sadarun (1999), untuk mengurangi
stress, karang yang akan ditarnsplantasi dilepaskan secara hati-hati dan ditempatkan
dalam wadah plastik berlubang serta proses pengangkutan dilakukan di dalam air.
Sebaiknya operasi ini hanya menghabiskan waktu ±30 menit untuk setiap tumpukan
karang yang akan dipindahkan. Harriot dan Fisk (1988) menjelaskan bahwa
pengangkutan karang transplantasi di atas deck kapal yang terlindung selama kurang
dari satu jam, tidak berbeda nyata dengan pengangkutan dalam air. Bila terkena
udara selama dua jam, keberhasilan karang yang ditranplantasi berkisar 50-90%,
sedangkan bila terkena udara selama tiga jam, maka keberhasilan karang yang
ditransplantasi berkisar 40-70%.
Fragmen transplan harus terikat dengan kokoh agar tidak mudah terlepas
akibat pengaruh arus dan gelombang. Hal ini dapat dilakukan dengan melekatkan
fragmen pada semen yang keras dengan menggunakan lem epoxy atau tali pengikat
kabel (cable tie) (Jaap 1999 in Prawidya 2003). Vaughan (1916) in Prawidya (2003)
menggunakan semen untuk melekatkan karang batu di Pantai Florida dan Pantai
Goulding di Bahama untuk meneliti laju pertumbuhannya, sedangkan untuk area
transplantasi yang arus dan gelombangnya kuat, digunakan pemberat untuk menahan
base atau substrat transplan. Menurut Adverlund (2001) untuk karang yang
perambatannya pada substrat relatif cepat, dapat digunakan lem super-glue untuk
penempelannya, sedangkan untuk jenis karang yang perambatannya pada substrat
relatif lama, sebaiknya digunakan lem epoxi.
Karang untuk transplantasi harus diambil dari tempat yang sama dengan
tempat pelaksanaan transplantasi terutama dalam hal pergerakan air, kedalaman, dan
turbiditas. Koral dari daerah tubir (reef slope) yang dangkal, jernih, dan
bergelombang tidak akan tumbuh dengan baik pada perairan yang keruh dan tenang
(Maragos 1974 in Sadarun 1999). Menurut Moore (1958) in Herdiana (2001), ketika
sebuah koloni dipisahkan menjadi dua bagian dan kemudian ditempatkan pada
habitat yang berbeda maka laju pertumbuhan dan tingkat ketahanan hidup akan lebih
baik pada daerah dimana jenis itu banyak ditemukan. Yap dan Gomez (1984) in
musim panas. Oleh karena itu, sebaiknya hindari pelaksanaan kegiatan transplantasi
karang pada musim-musim disaat karang sedang stres.
2.5. Keadaan Umum Lokasi Penelitian
Secara astronomis Kepulauan Seribu terletak antara 06000’40” dan 05054’40”
Lintang Selatan dan 106040’45” dan 109001’19” Bujur Timur. Wilayah Administrasi
Kepulauan Seribu yang terletak di sebelah Utara Teluk Jakarta terdiri atas 105 pulau
yang sebagian besar tidak berpenduduk. Perairan Kepulauan Seribu memiliki
kedalaman yang cukup bervariasi dimana kedalaman yang cukup dalam terdapat di
sebelah utara Pulau Pari dan utara Pulau Semak Daun dengan kedalaman hingga 70
meter. Dasar rataan karang perairan Kepulauan Seribu terdiri dari komponen pasir,
karang mati, hingga karang batu hidup (Estradivari et al. 2007). Suhu permukaan air
laut di Kepulauan Seribu berkisar 25,7-31,0 °C dengan rerata sebesar 29,1 ºC, sedangkan pH menunjukkan rerata sebesar 7,4 dengan kisaran antara 7,0 sampai 8,3.
Rerata salinitas sebesar 28,6o/oo dengan kisaran antara 23,3-30,3o/oo. Kecepatan arus
permukaan berkisar antara 0,01 sampai 0,15 m/s dengan rerata sebesar 0,07 m/s.
Kecerahan berkisar antara 3,88 sampai 9,42 m dengan rerata 6,33 m. Rerata oksigen
terlarut sebesar 7,11 mg/l dengan kisaran antara 6,10-7,96 mg/l (Setyawan et al.
2011).
Salah satu pulau di Kepulauan Seribu adalah Pulau Kelapa dengan luas sekitar
13,09 ha. Pulau ini merupakan pulau yang mempunyai penduduk sangat padat
dengan kepadatan 354 orang/ha pada tahun 2002 dan merupakan pusat pemerintahan
Kelurahan Pulau Kelapa yang berjumlah 36 pulau. Kualitas perairan Pulau Kelapa
berdasarkan pengamatan Bapepalda DKI Jakarta dan LAPI ITB pada tahun 2001
didapatkan suhu perairan pulau kelapa sebesar 30,2 ºC, Turbiditas 3, pH 7,94,
salinitas 34,40/00, dan DO 5,9 mg/ltr. Pengamatan yang dilakukan Seawatch-BPPT
pada bulan November dan Desember 1998 mencatat kecepatan arus pada kisaran 0,6
cm/dtk hingga 77,3 cm/dtk dengan rata-rata kecepatan sebesar 23,6 cm/dtk dengan
dominasi arah arus kearah timur-timur laut. Tinggi gelombang di Pulau Kelapa
berdasarkan pengamatan Seawatch Indonesia pada bulan Nopember 1998-Agustus
1999 pada kisaran 0,05-1,03 meter dengan periode gelombang berkisar antara
3.
METODE PENELITIAN
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan selama sebelas bulan dimulai dari bulan September
2010 sampai bulan Juli 2011. Pengambilan data dilakukan sebanyak empat kali yaitu
pada bulan September 2010, Januari 2011, Mei 2011, dan Juli 2011. Pelaksanaan
penelitian terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap pengumpulan data, observasi
lapangan, serta pengolahan, dan analisis data. Selanjutnya dilakukan pengambilan
data pertumbuhan fragmen karang transplantasi berupa ukuran dimensi lebar dan
tinggi fragmen karang serta kualitas air dari lokasi transplantasi tersebut.
Lokasi penelitian berada di Pulau Kelapa, Kelurahan Pulau Kelapa, Kepulauan
Seribu (Gambar 2). Penelitian ini merupakan kerjasama antara Pusat Kajian
Sumberdaya Pesisir dan Lautan-Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) dengan
China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) yang telah berlangsung sejak
tahun 2008.
3.2.Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan meliputi alat selam, alat tulis untuk mencatat
di dalam air, bahan modul dan transplant dan alat untuk menempel transplan ke
modul, alat untuk menentukan posisi serta alat dokumentasi.
Tabel 1. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian
No. Alat dan Bahan Keterangan
1. Peralatan SCUBA Peralatan penyelaman
2. Kamera underwater Dokumentasi
3. Kertas newtop dan sabak Media pencatat data 4. Alat tulis (Pinsil, pulpen, penggaris, penghapus,
pengserut, cutter dan spidol)
Pengukur panjang lebar karang dan pencatat data
5. Global Positioning System (GPS) Penentuan titik pengamatan
6. Modul beton Rak tempat fragmen
7. Semen Penempel fragmen
8. Fragmen karang Hewan percobaan
9. Kabel tie dan tali nylon Pengikat fragmen ke modul
10. Laptop Pengolah data
Untuk mendukung data penelitian, diambil juga data parameter perairan yang
meliputi parameter fisika dan kimia. Metode analisis yang digunakan untuk
parameter tersebut meliputi metode secara in-situ dan ex-situ. Metode analisis in-situ
dilakukan secara langsung pada saat di lokasi penelitian sedangkan ex-situ dilakukan
di Laboratorium Produktifitas Lingkungan (Proling) Manajemen Sumberdaya
Perairan, Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
Tabel 2. Parameter fisika dan kimia perairan yang diamati serta alat yang digunakan No. Parameter Satuan Alat yang digunakan Metode
1. Suhu 0C Termometer raksa In-situ
2. Salinitas 0/00 Refraktometer Ex-situ 3. Kecerahan 0/0 Secchi disk In-situ
4. Kekeruhan NTU Turbidimeter Ex-situ
5. Kecepatan arus m/s Floating droudge dan
stopwatch In-situ
6. Kedalaman M Depth gauge In-situ
7. Nutrien (Ammonia,
Ortofosfat, Nitrat) mg/l Spektrofotometer Ex-situ
8. Laju sedimentasi mg/cm2 /hari
Sediment trap, kertas millipore, vacuum pump, timbangan analitik
H. rigida A. nobilis A. microphthalma
3.3. Metode Penelitian dan Analisis Data
3.3.1. Fragmen karang dan konstruksi modul
Fragmen karang yang digunakan adalah karang hasil budidaya yang digunakan
untuk kegiatan perdagangan. Karang ini merupakan keturunan kedua dari koloni
induk sehingga legal untuk diperdagangkan sebagai karang hias. Fragmen karang
yang akan diteliti ditempelkan dengan cara diikatkan pada tiang-tiang modul dengan
menggunakan kabel tie lalu di semen agar kokoh dan tidak mudah lepas. Tiap modul
terdiri dari enam fragmen karang transplan.
Gambar 3. Desain konstruksi modul serta fragmen karang transplantasi
Gambar 4. Konstruksi modul serta fragmen karang transplantasi di Pulau Kelapa Sumber foto: PKSPL-IPB
Gambar 5. Fragmen transplantasi karang yang ditransplantasikan di Pulau Kelapa Sumber foto: PKSPL-IPB
Karang yang ditransplantasikan tersebut diidentifikasi secara visual dengan
cara membandingkannya dengan literatur Jenis-Jenis Karang di Indonesia milik
Suharsono (2008) dan Coral of the world milik Veron (2000). Fragmen karang yang
ditransplantasikan yaitu jenis H. rigida sebanyak 19 fragmen dengan ukuran tinggi
rata-rata 13,38 cm dan lebar 11,52 cm, A. nobilis sebanyak 68 fragmen dengan
ukuran tinggi rata-rata 25,12 cm dan lebar 28,30 cm, dan A. microphthalma
sebanyak 24 fragmen dengan ukuran tinggi rata-rata 23,15 cm dan lebar 30,19 cm.
Jumlah fragmen yang ditransplantasikan memiliki jumlah yang berbeda karena
keterbatasan ketersediaan fragmen di lapangan, selain itu penelitian ini merupakan
evaluasi dari proyek kerjasama antara PKSPL dengan CNOOC dalam rangka
merehabilitasi lingkungan yang rusak sehingga jumlah fragmen disesuaikan dengan
jumlah fragmen yang telah disediakan.
3.3.2. Pengamatan pertumbuhan karang
Pengamatan fragmen karang dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan
menggunakan penggaris dan jangka sorong di dalam air. Pengamatan meliputi
dimensi pertambahan lebar (lebar terlebar) dan pertambahan tinggi (tinggi tertinggi)
dimana pengukuran dilakukan secara langsung menggunakan alat SCUBA (Self
Contained Underwater Breathing Apparatus). Kelangsungan hidup fragmen karang
dihitung dengan cara mencatat setiap fragmen karang yang mati atau mengalami
pemutihan.
Untuk menghitung pencapaian pertumbuhan karang yang ditransplantasikan
dilakukan dengan menggunakan rumus yang mengacu pada Ricker (1975) sebagai
berikut:
β = Lt-Lo Keterangan :
β = Pertambahan panjang/tinggi fragmen karang
Lt = Rata-rata panjang/tinggi fragmen karang setelah bulan ke-t Lo = Rata-rata panjang/tinggi fragmen karang pada bulan ke-0
Untuk laju pertumbuhan karang yang ditransplantasikan, rumus yang
digunakan adalah sebagai berikut (Ricker 1975):
Keterangan:
α = Laju pertambahan panjang atau lebar fragmen karang transplantasi Li+1 = Rata-rata panjang atau tinggi fragmen pada waktu ke-i+1
Lt = Rata-rata panjang atau tinggi fragmen pada waktu ke-i Ti+1 = Waktu ke-i+1
t = Waktu ke-i
Tingkat kelangsungan hidup pada karang yang ditransplantasi dihitung dengan
menggunakan rumus yang mengacu pada Ricker (1975) sebagai berikut :
Keterangan :
SR = Tingkat Kelangsungan Hidup (Survival Rate) Nt = Jumlah individu pada akhir penelitian
No = Jumlah individu pada awal penelitian
3.3.3. Pengukuran parameter fisika kimia perairan
Parameter fisika kimia perairan yang diambil meliputi suhu, salinitas,
kecerahan, kekeruhan, kecepatan arus, kedalaman, nutrient (ammonia, ortofosfat,
nitrat), dan laju sedimentasi. Pengambilan data dilakukan setiap tiga bulan sekali
sesuai dengan pengambilan data fragmen karang.
Pengukuran parameter fisika berupa suhu, kecepatan arus, kedalaman perairan,
dan kecerahan perairan dilakukan secara langsung (insitu). Sedangkan salinitas,
sedimentasi, kekeruhan, dan nutrient (ammonia, ortofosfat, dan nitrat) dilakukan
secara tidak langsung (exsitu). Parameter suhu dilakukan dengan menggunakan
thermometer air raksa dengan cara dicelupkan ke perairan kemudian dilihat nilai
suhu perairannya, kecepatan arus dengan menggunakan floating droudge dan
stopwatch dimana floating droudge dilempar keperairan dan dihitung menggunakan
stopwatch. Waktu dihitung saat pertama kali floating droudge menyentuh air sampai
miring (logaritma) dari jarak floating droudge terhadap kapal dan tinggi antar ujung
tali saat floating droudge dijatuhkan dengan permukaan air.
Parameter kecerahan menggunakan secchi disc dengan cara merata-ratakan
nilai kedalaman saat secchi disk mulai menghilang/tidak terlihat dalam air (d1)
dengan saat secchi disk mulai terlihat ketika diangkat (d2). Nilai kedalaman tersebut
dibagi dua kemudian dikalikan 100 persen. Pengukuran kedalaman dengan melihat
depth gauge pada peralatan SCUBA.
Contoh air untuk pengukuran secara ex situ dilakuakn dengan menggunakan
botol contoh pada kedalaman 1-4 meter, kemudian air contoh tersebut disimpan
dalam cool box yang diberi es batu lalu dianalisis di Laboratorium Produktifitas
Lingkungan, Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan
Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Salinitas diukur dengan hand
refraktometer. Kekeruhan dengan turbidimeter dan nutrient diukur dengan
spektrofotometri. Laju sedimentasi diukur dengan cara menyaring partikel-partikel
tersuspensi yang terdapat di dalam sediment trap dengan menggunakan kertas
millipore dibantu dengan vacuum pump, lalu di oven pada suhu 105 0C untuk
4.
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Kondisi Fisika dan Kimia Perairan
Parameter fisika dan kimia perairan sangat mempengaruhi kehidupan biota
laut khususnya terumbu karang. Parameter yang tidak sesuai dengan baku mutu
normal untuk karang akan mempengaruhi pertumbuhan terumbu karang. Dalam
kondisi perubahan parameter yang ekstrim dapat menyebabkan stress dan kematian
pada karang.
4.1.1. Cahaya
Cahaya memiliki peranan penting untuk kegiatan fotosintesis alga
zooxanthellae yang bersimbiosis dengan karang. Nilai kecerahan pada penelitian ini
bernilai 100% yang artinya penetrasi cahaya sampai ke dasar perairan sehingga akan
mendukung proses fotosintesis (Nybakken 1992). Selain itu, menurut Nybakken
(1992) cahaya matahari digunakan juga sebagai sumber energi untuk melakukan
proses kalsifikasi sehingga karang bisa tumbuh dengan cepat.
4.1.2. Salinitas
Salinitas suatu perairan sangat dipengaruhi oleh curah hujan dan masukan air
tawar dari daratan. Menurut Nybakken (1992), salinitas air laut yang normal untuk
kehidupan karang hermatifik adalah 32-350/00 dan berkisar antara 33-34 0
/00
(Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 tahun 2004).
Salinitas di perairan Pulau Kelapa berfluktuasi dengan kisaran salinitas
29-320/00. Nilai salinitas menurun pada bulan Januari 2011 kemudian naik sampai pada
salinitas 320/00 di bulan Mei dan Juli 2011. Hal ini diduga disebabkan oleh tingginya
curah hujan memasuki musim barat sehingga nilai salinitas semakin rendah dengan
nilai terendah pada bulan Januari 2011 kemudian naik lagi memasuki musim timur
karena berkurangnya curah hujan. Menurut Rachmawati (2001) in Wibowo (2009)
penurunan salinitas perairan laut dapat disebabkan oleh pasokan air tawar, badai,
dan hujan. Kisaran salinitas pada bulan September dan Desember yang berada di
bawah kisaran normal untuk pertumbuhan karang dapat menyebabkan pertumbuhan
karang terganggu dan tidak optimal.
4.1.3. Suhu
Suhu adalah salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam
kehidupan karang. Berdasarkan Bikerland (1997) terumbu karang umumnya
ditemukan pada perairan dengan suhu 18-36 ºC.
Gambar 8. Fluktuasi suhu rata-rata (n=3) perairan Pulau Kelapa
Suhu perairan pada lokasi penelitian di Pulau Kelapa berkisar antara 28-30,6
ºC. Suhu perairan berfluktuasi pada tiap pengambilan data dan menunjukkan tren
menurun dari bulan September 2010 sampai Juli 2011. Menurut Nybakken (1992)
kisaran suhu optimal untuk pertumbuhan karang berkisar antara 25-30 ºC,
sedangkan menurut Dirjen PHKA (2008) 26-30 ºC dan menurut KepMen LH No.51
(2004) baku mutu suhu perairan untuk terumbu karang berkisar antara 28-30 ºC.
Pada bulan September 2010 sampai Mei 2011 suhu perairan masih dalam batas
optimal untuk pertumbuhan karang sedangkan pada bulan Juli 2011 suhu perairan di
Perubahan suhu bulan Mei ke Juli menunjukkan kenaikan sebesar 2 ºC dimana
kenaikan ini cukup signifikan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan karang.
Studi yang dilakukan Coles & Jokie (1978) dan Neudecker (1981) in Supriharyono
(2007) menunjukkan perubahan suhu perairan secara mendadak sekitar 4-6 ºC dapat
mengurangi pertumbuhan karang, bahkan mematikannya.
Penurunan suhu perairan dapat disebabkan oleh kurang optimalnya intensitas
penyinaran matahari. Curah hujan yang meningkat pada bulan Desember
berpengaruh terhadap intensitas penyinaran matahari dan mempengaruhi kondisi
saat pengambilan data. Meningkatnya curah hujan juga dapat menyebabkan
masuknya sedimen-sedimen dari daratan sehingga meningkatkan kekeruhan perairan
yang berakibat pada terhambatnya penetrasi cahaya matahari karena terhalang oleh
sedimen. Berkurangnya cahaya matahari akan berpengaruh terhadap penurunan
suhu. Sebaliknya, pada bulan Juli curah hujan semakin berkurang sehingga penetrasi
cahaya matahari menjadi optimal dan berakibat pada meningkatnya suhu perairan.
4.1.4. Kekeruhan
Kekeruhan terjadi karena banyaknya padatan tersuspensi atau sedimen dalam
perairan, menurut Thamrin (2006) padatan tersuspensi ini akan mempengaruhi
sepanjang siklus hidup hewan karang. Anna (1999) in Sachoemar (2008)
menyatakan Kepulauan Seribu juga sangat rentan terhadap ancaman pencemaran
dari daratan, mengingat secara osenografis lokasinya berhubungan langsung dengan
Teluk Jakarta tempat bermuaranya 13 sungai yang melintasi Kota Jakarta yang padat
pemukiman dan industri Kekeruhan di perairan Pulau Kelapa selama pengamatan
September 2010 sampai Juli 2011 memiliki nilai yang berfluktuasi. Nilai kekeruhan
tertinggi terjadi pada bulan Januari 2011 dan terendah terjadi pada Mei 2011 dengan
kisaran antara 0,28 NTU-0,70 NTU (Gambar 9). Kekeruhan yang tinggi pada bulan
Januari 2011 diduga disebabkan oleh tingginya curah hujan sebagai efek dari musim
barat sehingga mengakibatkan terjadinya pengadukan partikel-partikel terlarut yang
terdapat pada kolom perairan serta partikel yang mengendap di dasar perairan.
Selain itu, hujan yang turun juga menyebabkan partikel-partikel dari daratan (run
off) terbawa ke perairan sehingga meningkatkan nilai kekeruhan perairan. Letak
Kepulauan Seribu seperti yang diungkapkan Anna (1999) in Sachoemar (2008)
tempat bermuaranya 13 sungai yang melintasi Kota Jakarta. Hal ini memberikan
pengaruh terhadap masukan sedimen ke perairan sehingga menyebabkan
meningkatnya kekeruhan di Kepulauan Seribu.
Gambar 9. Kekeruhan rata-rata (n=3) perairan Pulau Kelapa
Partikel tersuspensi atau sedimen ini dapat mempengaruhi kehidupan karang
baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pengaruh langsung sedimen adalah
dengan menutupi polip karang sehingga menyebabkan kematian pada karang.
Sedangkan pengaruh tidak langsung yaitu menghalangi penetrasi cahaya sehingga
mengganggu fotosintesis (Bak 1978 in Supriharyono 2007). Selain itu, sedimen
yang tinggi memaksa karang untuk mengeluarkan energi lebih guna menghalau
sedimen tersebut yang mengakibatkan turunnya laju pertumbuhan karang (Pastorok
dan Bilyard 1985 in Supriharyono 2007).
4.1.5. Kecepatan arus
Arus memiliki peranan penting terutama dalam menyuplai makanan bagi
karang, oksigen serta membantu karang membersihkan diri dari sedimen (Thamrin
2006; Stoecker 1978 in Estradivari at al. 2009). Kecepatan arus rata-rata di lokasi penelitian meningkat pada setiap pengambilan data dengan kisaran antara 0,12 m/s
sampai 0,32 m/s (Gambar 10). Nilai kecepatan arus yang meningkat diduga
disebabkan oleh pergantian musim yaitu dari musim barat ke musim timur. Musim
timur memiliki arus dan gelombang yang lebih besar dibandingkan pada musim
barat sehingga kecepatan arus terus meningkat terutama memasuki bulan Juli 2011
yang memiliki kecepatan sebesar 0,32 m/s naik sekitar 0,12 m/s dibandingkan bulan
Gambar 10. Kecepatan arus rata-rata (n=3) perairan Pulau Kelapa
Kecepatan arus dan turbulensi akan berpengaruh terhadap morfologi dan
komposisi taksonomi ekosistem terumbu karang. Karang yang berada pada perairan
dengan gelombang yang cukup kuat memiliki bentuk pertumbuhan masif atau
bercabang dengan cabang yang sangat tebal dan ujung yang datar. Sedangkan pada
perairan yang tenang, koloni karang yang terbentuk cenderung memanjang dan
bercabang dengan cabang yang lebih ramping (Rachmawati 2001 in Wibowo 2009).
4.1.6. Nutrien (ammonia, nitrat, dan ortofosfat)
Terumbu karang umumnya hidup pada perairan yang miskin unsur hara
dengan kadar nutrien terbatas. Hanya beberapa spesies saja yang dapat beradaptasi
pada lingkungan yang kaya unsur hara salah satunya Stylophora pistillata. Walker &
Ormund (1982) in Supriharyono (2007) mengatakan bahwa spesies Stylophora
pistillata memiliki ketahanan hidup pada perairan yang kaya akan unsur hara. Hal
ini sesuai dengan penelitian Wibowo (2009) di perairan Pulau Karya yang
mendapatkan tingkat kelangsungan hidup sebesar 100%, sedangkan sebagian besar
spesies karang tidak dapat beradaptasi terhadap perairan yang kaya akan unsur hara.
Kandungan unsur hara yang tinggi dapat merangsang pertumbuhan alga sehingga
dapat menginvasi karang-karang disekitarnya dan menyebabkan terganggunya
kehidupan karang bahkan dapat menyebabkan kematian pada karang (Estradivari et
al. 2009) Kadar nutrien yang keberadaannya sangat penting dan mempengaruhi
kehidupan karang diantaranya nitrogen (N) yang biasanya dalam bentuk nitrat (NO3
Gambar 11. Kandungan nitrat (NO3-N) rata-rata (n=3) perairan Pulau Kelapa
Kandungan nitrat rata-rata di perairan Pulau Kelapa menunjukkan kenaikan
pada bulan Januari 2011 kemudian turun sampai bulan Juli (Gambar 11). Salah satu
faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kenaikan kandungan unsur hara pada
perairan adalah sedimentasi (Supriharyono 2007). Sedimen yang masuk ke perairan
membawa unsur hara salah satunya adalah nitrat sehingga kandungan nitrat menjadi
naik. Pengamatan pada bulan Januari menunjukkan nilai sedimentasi yang tinggi,
tertinggi dibandingkan dengan pengamatan pada bulan lainnya. Hal ini menandakan
peningkatan laju sedimentasi berpengaruh terhadap kandungan nitrat pada perairan
Pulau Kelapa. Selain itu, tingginya kandungan nitrat pada bulan Januari 2011 juga
dapat disebabkan oleh adanya proses nitrifikasi amonia menjadi nitrat yang dipicu
oleh besarnya kadar oksigen sehingga menyebabkan kandungan nitrat di perairan
meningkat (Effendi 2003 in Wibowo 2009), sedangkan kandungan amonia menjadi
berkurang pada bulan tersebut (lihat Gambar 12). Menurut effendi (2003) nitrat
merupakan bentuk utama nitrogen di perairan alami dan merupakan nutrien utama
bagi pertumbuhan tanaman dan alga dan dapat dimanfaatkan secara langsung. Hal
ini sesuai dengan kondisi pada saat pengamaratan bulan Januari 2011 dimana alga
sangat melimpah termasuk yang menempel pada modul bahkan sampai menutupi
Gambar 12. Kandungan amonia (NH3-N) rata-rata (n=3) perairan Pulau Kelapa
Kandungan amonia mengalami kenaikan sampai bulan Mei dimana kandungan
amonia pada bulan tersebut mencapai 0,308 (Gambar 12). Kadar kandungan ini
melebihi baku mutu air laut untuk biota laut yang ditetapkan KepMEN LH No. 51
(2004) sebesar 0,3 mg/l sehingga dapat mempengaruhi kehidupan biota karang.
Berdasarkan data yang didapatkan diduga kandumgan amonia yang tinggi
mempengaruhi tingat ketahanan hidup fragmen karang sehingga menyebabkan
kematian pada beberapa fragmen karang di bulan Januari-Mei 2011.
Gambar 13. Kandungan ortofosfat (PO4-P) rata-rata (n=3) perairan Pulau Kelapa
Kandungan ortofosfat terus menurun sampai akhir pengamatan dengan nilai
tertinggi sebesar 0,007 (Gambar 13). Berdasarkan KepMen LH No. 51 (2004)
tentang baku mutu air laut untuk biota laut kandungan ortofosfat di perairan Pulau
Kelapa selama pengamatan tidak melebihi baku mutu sehingga diduga tidak
4.2. Pertumbuhan Karang
4.2.1. Tingkat pencapaian pertumbuhan dan pertumbuhan mutlak
Tingkat pencapaian pertumbuhan karang merupakan pertumbuhan ukuran
karang baik panjang maupun lebar karang pada setiap waktu pengamatan. Dalam
penelitian ini waktu pengamatan dilakukan selama sebelas bulan yaitu dari bulan
September 2010 sampai Juli 2011 dengan jumlah pengambilan sebanyak empat kali
terhadap tiga jenis karang yaitu H. rigida, A. nobilis dan A. microphthalma.
Tabel 3. Ukuran tingkat pencapaian pertumbuhan karang yang ditransplantasi
Jenis Karang Ukuran (cm)
Waktu Pengukuran Pertumbuhan
mutlak (cm) (Sep 2010-Jul
2011)
Sep-10 Jan-11 Mei-11 Jul-11
H. rigida
(n=19)
Tinggi 13,38±6,00 14,14±5,83 14,75±4,57 15,93±5,11 2,55 ± 5,38
Lebar 11,52±5,01 13,49±4,97 16,55±4,54 18,27±5,44 6,75 ± 4,80
A. nobilis
(n=68)
Tinggi 25,12±10,33 26,22±10,23 27,93±8,31 29,44±8,48 4,30 ± 7,47
Lebar 28,30±8,25 31,19±9,67 36,83±10,35 38,92±10,67 10,52 ± 6,94
A.
microphthalma
(n=24)
Tinggi 23,15±6,31 24,25±7,08 27,23±6,95 27,84±6,76 4,69 ± 4,07
Lebar 30,19±14,33 34,24±13,68 36,83±14,10 37,89±14,05 7,70 ± 6,93
Pertumbuhan mutlak yang dicapai fragmen H. rigida dari bulan September
2010 sampai Juli 2011 sebesar 2,55±5,38 cm untuk pertumbuhan tinggi dan
6,75±4,80 cm untuk pertumbuhan lebar (Gambar 14). Fragmen ini memiliki tingkat
pertumbuhan terendah diantara ketiga fragmen yang diteliti baik untuk pertumbuhan
tinggi maupun lebarnya. Pencapaian pertumbuhan fragmen A. nobilis sebesar
4,33±7,40 cm untuk pertumbuhan tinggi dan 10,62±6,94 cm untuk lebar dimana
pertumbuhan lebar A. nobilis merupakan pertumbuhan lebar terbesar diantara
ketiganya. Sedangkan tingkat pertumbuhan fragmen A. microphthalma sebesar
4,69±4,67 cm untuk dimensi tinggi dan 7,70±6,93 cm untuk dimensi lebar dimana
pertumbuhan dimensi tinggi Acropora ini merupakan yang terbesar diantara
pertumbuhan tinggi ketiga fragmen yang diteliti.
Besarnya nilai standar deviasi pada dimensi pertumbuhan lebar dan tinggi
ketiga fragmen disebabkan oleh adanya variasi nilai yang besar pada tiap fragmen.
Beberapa fragmen memiliki nilai yang sangat tinggi namun ada pula fragmen karang
yang mempunyai nilai sangat kecil (Lihat di lampiran 1, 2, dan 3). Perbedaan nilai
didapatkan untuk pertumbuhan dimensi lebar maupun tinggi pada ketiga fragmen
baik pada nilai pertumbuhan mutlak maupun nilai laju pertumbuhannya. Adanya
gangguan lingkungan terutama alga yang disebabkan oleh adanya nutrien (nitrat dan
ortofosfat) yang cukup tinggi pada perairan membuat pertumbuhan karang
terhambat. Beberapa fragmen karang pada saat pengamatan di lapangan tertutup
oleh alga baik tertutup sebagian bahkan seluruhnya (Gambar 21 dan lampiran 7).
Pertumbuhan lebar memiliki nilai lebih besar dibandingkan pertumbuhan
tinggi pada ketiga fragmen yang diteliti baik pada H. rigida, A. nobilis, maupun A.
microphthalma. Hal ini mengindikasikan bahwa pola pertumbuhan ketiga jenis
karang tersebut cenderung melebar. Pola pertumbuhan seperti ini diduga disebabkan
oleh faktor cahaya dimana untuk mendapatkan asupan cahaya yang maksimal
karang berusaha untuk memperluas jaringan karangnya sehingga bisa mendapatkan
lebih banyak cahaya.
Gambar 14. Pertumbuhan mutlak lebar dan tinggi fragmen karang selama sebelas bulan (September 2010-Juli 2011).
Faktor kedalaman, gelombang dan pasang surut juga mempengaruhi pola
pertumbuhan fragmen karang tersebut. Lokasi transplantasi berada pada daerah tubir
dan termasuk daerah zona intertidal dimana daerah ini banyak dipengaruhi aktifitas
pasang surut air laut dan gelombang. Beberapa modul tempat fragmen karang
terletak pada kedalaman yang sangat dangkal (kurang dari satu meter dengan
kedalaman maksimal 4 meter) sehingga diduga untuk beradaptasi terhadap aktifitas
pasang surut tersebut fragmen karang cenderung tumbuh dengan pola melebar.
Nybakken (1992) menyatakan bahwa pada daerah yang dangkal dengan
pasokan cahaya yang cukup serta terkena gelombang yang besar akan menyebabkan
Rachmawati (2001) in Wobowo (2009) menyatakan bahwa pada daerah yang
memiliki gelombang yang cukup kuat bagian ujung sebelah luar terumbu akan
membentuk karang masif atau bentuk bercabang dengan cabang yang sangat tebal
dan ujung yang datar.
Penelitian yang dilakukan Iswara (2010) terhadap jenis karang H. rigida di
lokasi yang sama selama enam bulan mendapatkan pola pertumbuhan yang juga
cenderung melebar. Tingkat pencapaian pertumbuhan yang dicapai sebesar 6 cm
untuk lebar dan 3,8 cm untuk tinggi. Berdasarkan waktu yang digunakan dalam
penelitian, maka secara umum tingkat pencapaian pertumbuhan pada penelitian
Iswara (2010) lebih besar dibandingkan dengan penelitian ini. Adanya perbedaan
waktu kegiatan transplantasi dan perbedaan perlakuan menyebabkan hasil yang
berbeda pada pertumbuhan fragmen karang.
Penelitian Prawidya (2003) terhadap spesies H. rigida selama lima bulan
namun di tempat yang berbeda mendapatkan nilai pertumbuhan mutlak untuk lebar
sebesar 5,02 cm dan untuk tinggi sebesar 3,59 cm. Hasil yang didapatkan Prawidya
menunjukkan nilai yang lebih besar untuk pertumbuhan tinggi namun lebih rendah
untuk pertumbuhan lebar jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh
penulis.
Herdiana (2001) melakukan penelitian terhadap jenis karang A.
microphthalma dan Acropora intermedia yang mempunyai struktur dan life form
mirip dengan A. nobilis di Perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, selama lima
bulan. Berdasarkan penelitian tersebut, didapatkan tingkat pencapaian pertumbuhan
A. microphthalma sebesar 3,64±0,34 cm untuk tinggi dan 5,61±0,24 cm untuk lebar.
Berdasarkan hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa pola pertumbuhan A.
microphthalma yang ditranplantasikan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu memiliki
pola yang sama yaitu cenderung melebar. Penelitian Herdiana (2001) terhadap
A.intermedia yang ditransplatasikan di Pulau Pari memiliki pola yang sama dengan
A. nobilis yang ditransplantasikan di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, yaitu
cenderung melebar. Nilai pertumbuhan yang didapatkan sebesar 1,04±0,06 cm untuk
tinggi dan 6,19±0,37 cm untuk lebar.
Kondisi lingkungan memberikan pengaruh terhadap morfologi terumbu
branching arborescent pertumbuhan seharusnya lebih dominan tinggi dibandingkan
lebar, namun pengamatan dilapangan menunjukkan hasil yang berbeda.
Pertumbuhan kedua jenis karang tersebut menunjukan pola pertumbuhan yang lebih
cenderung melebar atau horizontal daripada vertikal. Hal yang sama juga terjadi
terhadap karang spesies H. rigida yang memiliki pola pertumbuhan lebih besar lebar
daripada tinggi.
Pada pengamatan spesies Acropora humilis, Acropora austera, dan Acropora
bruegemani dilokasi dan waktu yang sama menunjukan pola yang juga cenderung
melebar pada A. humilis dan A. austera, sedangkan pada A. bruegemani lebih
cenderung ke pertumbuhan tinggi. Pertumbuhan mutlak A. humilis sebesar 5,1±2,92
cm untuk lebar dan 3,1±1,92 cm untuk tinggi, A. austera sebesar 7,1±4,01 cm untuk
lebar dan 6,5±3,76 cm, serta A. brueguemani sebesar 4,0±2,66 cm dan 4,2±2,89 cm
untuk lebar dan tinggi.
4.2.3. Laju pertumbuhan karang
Laju pertumbuhan karang yang diukur meliputi laju pertumbuhan untuk
dimensi tinggi dan lebar fragmen dimana pengukuran dilakukan setiap rentang
waktu yang ditentukan. Data laju pertumbuhan tinggi dan lebar yang didapatkan
kemudian dirata-ratakan dan dibagi rentang waktu perbulan untuk menghasilkan laju
pertumbuhan rata-rata perbulan.
Laju pertumbuhan rata-rata baik tinggi dan lebar secara umum untuk ketiga
fragmen karang bervariasi. Pada jenis H. rigida pertumbuhan tinggi rata-rata dan
lebar rata-rata menunjukkan nilai yang cenderung naik (Gambar 15). Laju
pertumbuhan tinggi rata-rata terbesar terjadi pada bulan Mei-Juli 2011 sebesar
0,59±1,54 cm dan terendah pada bulan Januari-Mei 2011 sebesar 0,15±1,16
cm/bulan. Laju pertumbuhan lebar rata-rata tertinggi terjadi pada bulan yang sama
dengan tinggi yaitu Mei-Juli 2011 sebesar 0,86±1,55 cm/bulan dan terendah pada
bulan September-Januari 2011 sebesar 0,46±0,45 cm/bulan. Pada fragmen jenis A.
nobilis pertumbuhan rata-rata tinggi terbesar terjadi pada bulan Mei-Juli 2011
sebesar 0,74±1,14 cm/bulan dan terendah pada September 2010-Januari 2011
sebesar 0,37±0,61 cm/bulan, sedangkan pertumbuhan rata-rata lebar terbesar terjadi
pada bulan Januari-Mei 2011 sebesar 1,39±1,70 cm/bulan dan terendah pada
microphthalama pertumbuhan rata-rata tinggi terbesar terjadi pada Januari-Mei 2011
sebesar 0,81±0,44 cm/bulan dan terendah pada bulan Mei-Juli 2011 sebesar
0,29±1,12 cm/bulan sedangkan pertumbuhan rata-rata lebar terbesar terjadi pada
bulan Januari-Mei 2011 sebesar 1,39±0,42 cm/bulan dan terendah pada bulan
September 2010-Januari 2011 dengan laju pertumbuhan sebesar 0,77±1,45 cm/bulan
[image:32.595.116.504.217.367.2](Gambar 18).
Gambar 15. Laju pertumbuhan rata-rata tinggi dan lebar fragmen H. rigida (x±sd)
Laju pertumbuhan tinggi H. rigida menurun pada bulan Januari-Mei 2011
sedangkan laju pertumbuhan lebar mengalami kenaikan. Hal ini diduga pada bulan
Januari-Mei 2011 sebagian besar energi yang dihasilkan oleh karang lebih banyak
digunakan untuk pertumbuhan ke arah samping atau lebar sehingga laju
pertumbuhan lebar mengalami kenaikan dan laju pertumbuhan tinggi mengalami
penurunan. Pertumbuhan dominan ke arah samping menunjukkan adaptasi karang
untuk mempertahankan hidupnya terutama untuk mendapatkan sinar matahari
dengan memperbanyak polip karang sehingga fragmen karang dapat tetap hidup
meskipun kondisi lingkungan kurang mendukung.
Pada bulan Mei-Juli laju pertumbuhan baik lebar maupun tinggi fragmen
karang H. rigida mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan dengan bulan
Januari-Mei 2011. Pada bulan Mei-Juli 2011, energi yang dihasilkan oleh karang
digunakan secara seimbang sehingga laju pertumbuhan baik lebar maupun tingginya
mengalami kenaikan. Besarnya laju pertumbuhan pada bulan Mei-Juli 2011
didukung oleh kondisi lingkungan perairan yang cukup baik.
Beberapa faktor lingkungan yang mendukung pertumbuhan karang pada bulan
menunjukkan nilai yang paling besar pada bulan Mei-Juli 2011 (Gambar 10). Arus
memberikan dampak positif terhadap karang seperti yang diungkapkan Thamrin
2006; Stoecker 1978 in Estradivari et al. 2009 bahwa arus membantu menyuplai
makanan untuk karang dalam bentuk zooplankton, membawa oksigen, serta
membantu mebersihkan karang dari sedimen. Nitrat, ortofosfat, dan ammonia pada
bulan Juli 2011menunjukkan nilai yang kecil yaitu sebesar 0,007 untuk nitrat,
sedangkan ortofosfat sebesar 0,048 dan ammonia memiliki nilai di bawah 0,005.
Nilai ini masih di bawah nilai baku mutu untuk kehidupan karang yang ditetapkan
oleh KepMen LH No. 51 tahun 2004 sehingga sangat mendukung untuk kehidupan
dan pertumbuhan karang. Kandungan nitrat dan ortofosfat yang tinggi pada suatu
perairan dan menstimulir pertumbuhan alga secara berlebihan sehingga dapat
mengganggu kehidupan karang, sedangkan ammonia bersifat racun terhadap biota
perairan termasuk karang (Effendi 2003). Salinitas pada bulan Mei dan Juli 2011
memiliki nilai sebesar 32o/oo, menurut Nybakken (1992) dan Ramimohtarto dan
Juwana (1999) nilai salinitas ini sesuai untuk kehidupan karang. Kekeruhan pada
bulan Mei dan Juli 2011 memiliki nilai yang sangat kecil (paling rendah
dibandingkan nilai kekeruhan pada pengamatan-pengamatan sebelumnya) dan masih
di bawah baku mutu sesuai KepMen LH No. 51 tahun 2004 sehingga sangat cocok
untuk kehidupan karang. Kekeruhan yang tinggi pada suatu perairan disebabkan
oleh adanya sedimen yang tinggi pada perairan tersebut. Sedimen yang terlalu tinggi
dapat berdampak negatif terhadap karang seperti yang diungkapkan oleh Bak (1978)
in Supriharyono (2007) bahwa sedimen dapat menutupi polip karang sehingga
menyebabkan kematian pada karang, selain itu menurut Pastorok dan Bilyard (1985)
in Supriharyono (2007) sedimen yang tinggi memaksa karang mengelurkan energi
lebih untuk menghalau sedimen tersebut sehingga mengakibatkan turunnya laju
pertumbuhan karang.
Pada bulan Januari-Mei 2011 faktor lingkungan kurang mendukung untuk
pertumbuhan fragmen karang sehingga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan
fragmen H. rigida. Salinitas pada bulan ini berada diluar kisaran normal untuk
karang sehingga dapat mengganggu pertumbuhan karang. Selain itu, kekeruhan pada
bulan Januari menunjukkan nilai yang tinggi dimana kekeruhan yang tinggi
Sedimen yang tinggi dapat menutup polip karang sehingga mengganggu proses
fotosintesis yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan karang. Kadar nitrat
yang tinggi secara tidak langsung bisa menyebabkan blooming alga sehingga dapat
menimbulkan adanya persaingan tempat dengan karang dan menghambat
[image:34.595.106.499.100.471.2]pertumbuhan karang.
Gambar 16. Perbandingan laju pertumbuhan karang jenis H. rigida pada penelitian yang berbeda
Ket: *Peneliti H. rigida dalam skripsi ini, ** Iswara (2010) meneliti H. rigida di tempat yang sama dengan penulis namun berbeda waktu, *** (Prawidya (2003) meneliti H. rigida di tempat yang berbeda.
Nilai pertumbuhan lebar dan tinggi rata-rata spesies H. rigida selama sebelas
bulan sebesar 0,70 cm/bulan dan 0,31 cm/bulan. Penelitian tentang H. rigida juga
pernah dilakukan oleh Iswara (2010) di lokasi yang sama dengan penelitin ini
(Gambar 16). Kegiatan transplantasi yang dilakukan Iswara (2010) selama enam
bulan diperoleh data pertumbuhan panjang rata-rata sebesar 0,85 cm/bulan untuk
lebar dan 0,55 cm/bulan untuk tinggi. Penelitian lain dilakukan Prawidya (2003)
terhadap H. rigida di Pulau Pari, Kepulauan Seribu selama lima bulan mendapatkan
pertumbuhan tinggi dan lebar sebesar 0,72 dan 0,96 cm/bulan. Berdasarkan data
tersebut, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan rata-rata spesies H. rigida yang
dilakukan oleh Iswara (2010) dan Prawidya (2003) memiliki pertumbuhan yang
lebih besar baik untuk lebar maupun tingginya. Waktu, lokasi, serta perlakuan yang
berbeda diduga memberikan pengaruh yang berbeda pula terhadap pertumbuhan
karang H. rigida.
Laju pertumbuhan rata-rata A. nobilis mengalami kenaikan pada bulan
nobilis sudah bisa beradaptasi terhadap kondisi lingkungan sehingga energi yang
dihasilkan dapat digunakan dengan optimal untuk pertumbuhan dan berakibat pada
naiknya pertumbuhan tinggi dan lebar fragmen karang. kondisi lingkungan yang
kurang mendukung pada bulan Januari-Mei 2011 tidak terlalu memberikan pengaruh
negatif terhadap laju pertumbuhan fragmen A. nobilis. Hal ini diduga karena genus
Acropora merupakan genus karang yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi,
selain itu berdasarlan Supriharyono (2007) life form atau bentuk pertumbuhan
karang yang berupa branching sangat mendukung untuk pertumbuhan karang
dimana karang dengan life form branching mempunyai tingkat pertumbuhan yang
cepat yaitu bisa mencapai diatas dua centimeter perbulan.
Gambar 17. Laju pertumbuhan tinggi dan lebar rata-rata fragmen jenis A. nobilis (x±sd)
Laju pertumbuhan rata-rata lebar A. nobilis mengalami penurunan pada bulan
Mei-Juli 2011 sedangkan laju pertumbuhan tinggi mengalami kenaikan yang cukup
besar. Distribusi energi pada bulan Mei-Juli 2011 lebih banyak digunakan karang
untuk pertumbuhan tinggi dibandingkan lebar sehingga laju pertumbuhan tinggi
lebih besar. Selain itu, adanya kompetisi ruang menyebabkan pertumbuhan karang
terutama pertumbuhan lebar pada A. nobilis menjadi terhambat sehingga karang
lebih menggunakan energinya untuk pertumbuhan tinggi sebagai salah satu cara
untuk mempertahankan hidupnya.
Faktor gelombang memberikan pengaruh penting terhadap laju pertumbuhan
lebar fragmen karang. Menurut Moor (1958) in Radisho (1997) sifat dari habitat
memiliki pengaruh yang besar terhadap tipe pertumbuhan dan jenis karang. Daerah
yang terkena gelombang pada daerah ujung sebelah luar dari daerah terumbu diisi
ujung yang datar. Pada perairan sebelah dalam yang terlindung, dihuni oleh jenis
yang berbentuk lembaran dan bercabang dengan cabang yang lebih ramping.
Kondisi di lokasi penelitian pada bulan Mei dan Juli 2011 menunjukkan gelombang
yang cukup besar. Hal ini berkaitan dengan pengaruh musim dimana bulan tersebut
merupakan musim peralihan dari musim barat ke musim timur sehingga gelombang
cukup besar yang berpengaruh terhadap tipe pertumbuhan fragmen karang.
Laju pertumbuhan rata-rata A. nobilis selama sebelas bulan pengamatan
sebesar 0,52 cm/bulan untuk tinggi dan 1,06 cm/bulan untuk lebar. Penelitian yang
dilakukan Herdiana (2001) terhadap karang jenis Acropora intermedia yang
mempunyai struktur dan life form mirip dengan A. nobilis di Pulau Pari, Kepulauan
Seribu, selama lima bulan mendapatkan rata-rata pertumbuhan lebar dan tinggi
sebesar 1,54±0,09 cm/bulan dan 1,04±0,06 cm/bulan. Berdasarkan hasil yang
didapatkan, dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan lebar dan tinggi rata-rata A.
intermedia yang ditransplantasikan di Pulau Pari lebih besar dibandingkan dengan A.
nobilis yang ditransplantasikan di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Adanya
perbedaan waktu dan lama dan lokasi penelitian memberikan pengaruh yang
berbeda terhadap laju pertumbuhan karang.
Gambar 18. Laju pertumbuhan tinggi dan lebar rata-rata fragmen jenis A.microphthalma (x±sd)
Laju pertumbuhan rata-rata lebar A. microphthalma menurun pada bulan
Januari-Mei 2011 sedangkan laju pertumbuhan rata-rata tinggi mengalami kenaikan.
Hal ini diduga pada bulan Jan-Mei 2011 sebagian besar energi yang dihasilkan oleh
karang lebih banyak digunakan untuk pertumbuhan tinggi dibandingkan lebar
sehingga laju pertumbuhan tinggi mengalami kenaikan sedangkan laju pertumbuhan
microphthalma diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan laju pertumbuhan tinggi lebih besar daripada lebar. Berdasarkan suharsono (2008) life
form arborescent adalah salah satu karakteristik bentuk pertumbuhan karang seperti
pohon dimana arah pertumbuhan umumnya dominan mengarah ke atas.
Pada bulan Mei-Juli 2011 laju pertumbuhan rata-rata lebar dan tinggi A.
microphthalma mengalami penurunan. Laju pertumbuhan tinggi yang menurun
diduga berkaitan dengan faktor kedalaman. Lokasi penelitian yang berada pada
daerah perairan yang cukup dangkal menyebabkan karang tidak mengembangkan
pertumbuhan tingginya untuk menghindari terpapar karang oleh udara bebas
terutama ketika perairan surut. Laju pertumbuhan rata-rata lebar yang menurun
diduga berkaitan dengan adanya kompetisi ruang yang menyebabkan pertumbuhan
karang terutama pertumbuhan lebar pada A. microphthalma menjadi terhambat.
Adanya faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan pada lebar dan tinggi A.
microphthalma menyebabkan karang mengalokasikan energinya untuk pertumbuhan
cabang-cabang baru. Suharsono (2008) dan Veron (2000) mengatakan bahwa salah
satu karakteristik A. microphthalma adalah mempunyai cabang yang kecil dan
ramping. Percabangan yang kecil dan ramping pada A. microphthalma ini
menyebabkan spesies