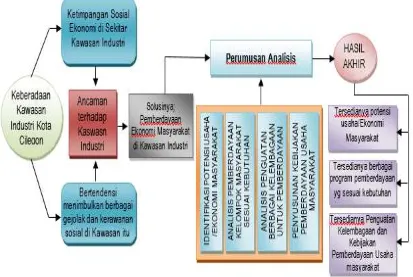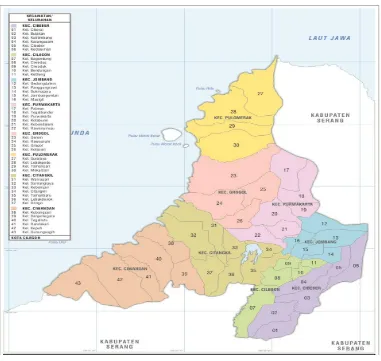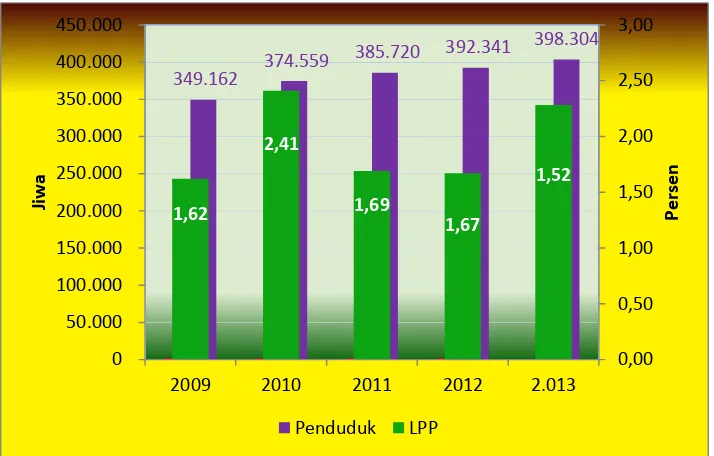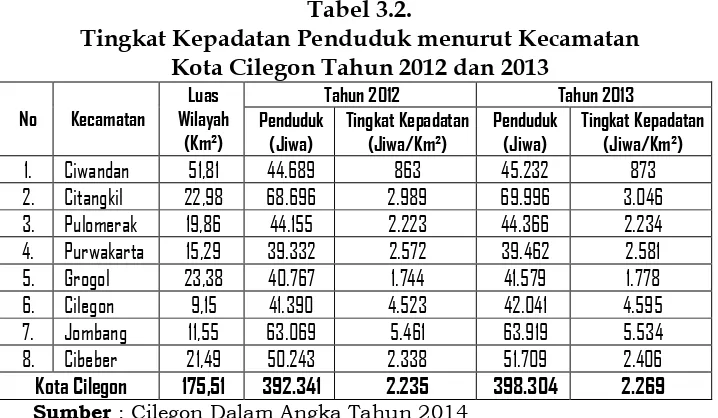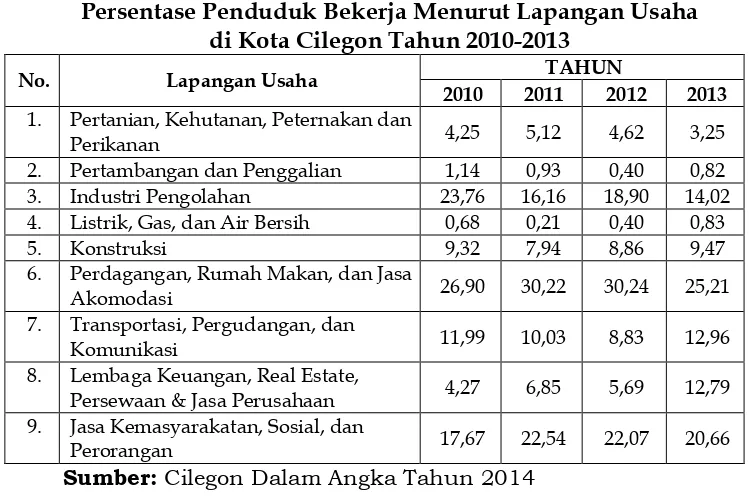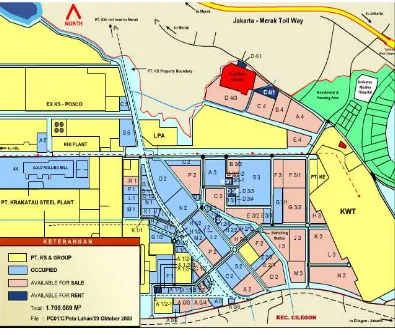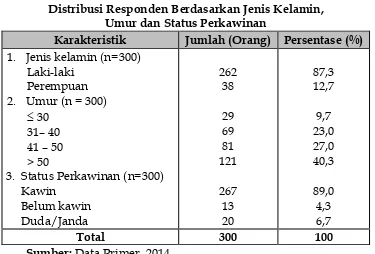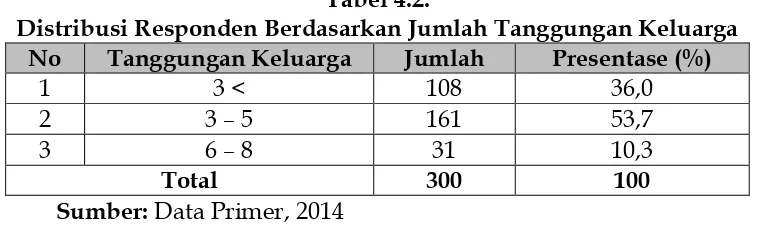LAPORAN AKHIR
KAJIAN PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
DI KAWASAN INDUSTRI KOTA CILEGON
KAJIAN PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
DI KAWASAN INDUSTRI KOTA CILEGON
Tim Peneliti:
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas tersusunnya Laporan Akhir ini. Laporan ini merupakan laporan tahap akhir dalam Pekerjaan Kajian Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Industri Kota Cilegon, yang diselenggarakan oleh Bagian Perekonomian Bappeda Kota Cilegon Tahun Anggaran 2014.
Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan Kajian dimaksud adalah untuk menyusun dokumen kajian penguatan ekonomi masyarakat di kawasan industri yang mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam setiap langkah pembangunan ekonomi, sedangkan pemerintah memberikan fasilitas dan pendampingan kepada masyarakat dalam melaksanakan program ekonomi-produktifnya.
Tim Konsultan mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa seluruh proses penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak terlepas dari arahan dan bantuan berbagai pihak yang telah membantu dengan tulus dan iklas. Atas dasar itulah, dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya, perkenankanlah pada kesempatan ini Tim Konsultan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Kepala Bappeda Kota Cilegon yang telah memberi kepercayaan penuh kepada Konsultan, khususnya Tim Peneliti untuk dapat berkontribusi dan berperan serta dalam penelitian ini.
Ucapan terima kasih juga Tim Peneliti sampaikan kepada Dinas Sosial, CCSR, dan Bappeda Kota Cilegon dan BPS Kota Cilegon terutama atas data-data penelitiannya, dan Kelompok Masyarakat yang telah bersedia menjadi objek observasi, dan memberikan berbagai keterangan, untuk memperkaya dan melengkapi kesempurnaan dari Kajian ini.
Tim Konsultan menyadari bahwa Laporan Akhir Kajian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga Kami berharap adanya masukan dan saran yang bersifat kontrukstif, agar supaya kajian ini menjadi lebih sempurna dan nantinya dapat di jadikan bahan pijakan untuk mengambil keputusan yang strategis terkait Kajian Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Industri Kota Cilegon.
Cilegon, Desember 2014
HALAMAN JUDUL ... i
KATA PENGANTAR ... ii
DAFTAR ISI ... iii
DAFTAR TABEL ... v
DAFTAR GAMBAR ... vii
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1. Latar Belakang ... 1
1.2. Tujuan dan Sasaran Kajian ... 3
1.3. Ruang Lingkup Kajian ... 4
1.4. Output Kajian ... 5
1.5. Kerangka Kajian ... 5
1.6. Pendekatan Studi ... 7
BAB II TINJAUAN TEORITIS ... 9
2.1. Investasi dan Penanaman Modal ... 9
2.2. Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri ... 12
2.3. Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan ... 14
2.4. Konsep Pemberdayaan Ekonomi ... 21
2.5. Pengembangan Ekonomi Lokal ... 25
2.6. Kemitraan (Partnership) ... 28
BAB III KONDISI EKSISTING WIYAH STUDI ... 32
3.1. Karakteristik Wilayah Kota Cilegon ... 32
3.2. Data Kependudukan Kota Cilegon ... 34
3.3. Kawasan Industri di Kota Cilegon ... 41
3.3.1. Kawasan Industri KIEC ... 45
BAB IV HASIL SURVEY DATA LAPANGAN ... 52
4.1. Survei Lapangan Kepada Masyarakat di Kawasan Industri... 52
4.1.1. Karakteristik Responden ... 55
4.1.2. Kondisi Sosial Masyarakat di Wilayah Studi ... 57
4.1.3. Kondisi Ekonomi Masyarakat di Wilayah Studi ... 63
4.1.4. Keberadaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ... 67
4.1.5. Kondisi Social Capital Masyarakat di Wilayah Studi ... 73
4.1.6. Tanggapan Masyarakat di Wilayah Studi terhadap Pemberdayaan Ekonomi yang dilakukan Pemerintah Daerah ... 78
4.1.7. Bantuan Program dan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Diharapkan dari Pemerintah Daerah dan atau Perusahaan ... 84
4.2. Survei Institusional pada Dinas SKPD di Kota Cilegon Terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Telah dilakukan ... 89
4.2.1. Dinas Ketenagakerjaan ... 89
4.2.2. Dinas Koperasi dan UMKM ... 91
4.2.3. Dinas Industri dan Perdagangan ... 91
4.2.4. Badan BPMKP ... 92
4.2.5. Dinas Pertanian ... 93
4.3. Survei Institusional ke Pengelola Kawasan Industri KIEC dan Pengelola CCSR Kota Cilegon .. 95 4.3.1. Corporate Social Responsibility PT KIEC ... 95 4.3.2. Corporate Social Responsibility PT KS dan Group ... 100 4.3.3. Program Corporate Social Responsibility oleh
Lembaga CCSR Kota Cilegon ... 111
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ... 120
5.1. Analisis Potensi dan Masalah Perekonomian Masyarakat di Sekitar Kawasan Industri ... 120 5.1.1. Analisis Potensi Perekonomian Masyarakat di
Sekitar Kawasan Industri ... 120 5.1.1.1. Pendekatan Potensi Industri yang Ada
di Wilayah Sekitar ... 120 5.1.1.2. Pendekatan Potensi SDA yang Ada di
Wilayah Sekitar ... 126 5.1.1.3. Pendekatan Potensi Jenis Usaha yang
Ada di Wilayah Sekitar ... 131 5.1.2. Analisis Masalah Perekonomian Masyarakat di
Sekitar Kawasan Industri ... 134 5.1.2.1. Pergereseran Struktur Ekonomi dari
Pertanian Menuju Industri tidak Diantisipasi dengan Peningkatan Pendidikan/Keahlian ... 134 5.1.2.2. Tenaga Kerja Lokal di Sekitar Kawasan
Tersisih dan Kalah Bersaing dengan Pendatang akibat Keterbatasan Keahlian dan Pendidikan ... 135 5.1.2.3. Keberadaan Tenaga Kerja Outsoursing
membatasi Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja Lokal di Sekitar Kawasan ... 137 5.1.2.4. Kurangnya Kepemilikan Aset dan
5.2. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat di
Kawasan Industri Kota Cilegon ... 139
5.2.1. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dalam Pengembangan UEP ... 145
5.2.2. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar ... 147
5.2.3. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dalam Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal .... 150
5.2.4. Penguatan Kelembagaan dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Pembangunan ... 153
5.3. Merumuskan Kebijakan Pemberdayaan Usaha Masyarakat Bersama di Kawasan Industri ... 154
5.3.1. Program Peningkatan SDM Potensial sesuai Kebutuhan dan Potensi Perekonomian Masyarakat Sekitar ... 156
5.3.2. Program Peningkatan Akses Masyarakat kepada Sumber Permodalan ... 161
5.3.3. Program Peningkatan Dukungan Bahan Baku dan Peralatan Produksi bagi Wirausaha Baru, Kelompuk Usaha Bersama Masyarakat maupun Usaha Kecil yang sudah ada ... 164
5.4. Rencana Tindak Berdasarkan Perumusan Kebijakan Tentang Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Industri ... 166
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ... 171
6.1. Kesimpulan ... 171
6.2. Rekomendasi ... 176
Tabel Judul Tabel Halaman
3.1. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cilegon ... 33
3.2. Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Cilegon Tahun 2012 dan 2013 ... 36
3.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Cilegon Tahun 2013... 36
3.4. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Ciegon Tahun 2011-2013 ... 38
3.5. Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, dan TPT di Kota Cilegon Tahun 2009- 2013 ... 40
3.6. Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha di Kota Cilegon Tahun 2010-2013 ... 41
4.1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur dan Status Perkawinan ... 55
4.2. Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga ... 57
4.3. Distribusi Jumlah Anak dalam Keluarga Pada Keseluruhan Responden di Wilayah Studi ... 58
4.4. Distribusi pendidikan anak 12 tahun ke Atas Pada Wilayah Studi ... 59
4.5. Distribusi Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Pendidikan .. 61
4.6. Status Tempat Tinggal, Sumber Kebutuhan Air Bersih, Kelengkapan Sarana MCK Dan Sarana Penerangan ... 62
4.7. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan ... 63
4.8. Usaha yang Telah Dijalankan Masyarakat di Wilayah Studi . 64
4.9. Lamanya (Pengalaman) Menjalankan Usaha ... 65
4.11. Distribusi Rata-rata Pengeluaran Keluarga Per Bulan
Masyarakat di Wilayah Studi ... 67
4.12. Bantuan Program Pemberdayaan yang Pernah Diterima ... 68
4.13. Besarnya Bantuan Permodalan yang Diterima Responden .... 70
4.14. Sumber Permodalan Responden ... 72
4.15. Frekuensi Kegiatan Gotong Royong Masyarakat di Wilayah Studi ... 74
4.16. Aktivitas Kegiatan Gotong Royong Masyarakat ... 75
4.17. Sikap Keterbukaan Masyarakat Terhadap Pendatang ... 76
4.18. Kondisi Modal Sosial Masyarakat di Wilayah Studi ... 77
4.19. Keberadaan Program Pemberdayaan Masyarakat Lokal dari Pemerintah Daerah ... 79
4.20. Ketepatan Program Pemberdayaan Masyarakat ... 80
4.21. Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan ... 81
4.22. Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan ... 82
4.23. Proses Pendampingan yang Berkelanjutan ... 83
4.24. Keberlanjutan Usaha Yang Mendapatkan Bantuan ... 83
4.25. Hambatan Pengembangan Potensi Ekonomi pada Wilayah Studi ... 85
4.26. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang diharapkan dari PEMDA ... 86
4.27. Usulan Pelatihan yang Berpotensi Ekonomi Pada Wilayah Studi ... 87
4.28. Usulan Bantuan Peralatan Produksi yang Mendukung Usaha yang telah Ada Pada Wilayah Studi ... 88
4.29. Daerah Penerima Program PKBL PT KS ... 102
4.30. Pinjaman Dana Bergulir Bagi Usaha Kecil Berdasarkan Sektor dalam Program Kemitraan PT KS ... 104
4.32. Program Prioritas Lembaga CCSR Tahun 2011 - 2013 ... 113
4.33. Besaran Nilai CSR untuk Program Prioritas pada Tahun 2011 - 2013... 115
4.34. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Program Prioritas pada tahun 2011 ... 115
4.35. Nilai CSR yang disalurkan/dikeluarkan untuk Program Tambahan pada tahun 2011 - 2013 ... 116
5.1. PDRB Kota Cilegon ADHK 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2013 (Juta Rupiah) ... 121
5.2. Produksi Komoditi Hasil Pertanian Masyarakat Sekitar Kawasan Industri Tahun 2013 ... 127
5.3. Jumlah Ternak yang Dipelihara Penduduk Sekitar Kawasan Industri Kota Cilegon Tahun 2013 ... 128
5.4. Jumlah Usaha dan Jumlah Unggas yang Diusahakan oleh Penduduk Sekitar Kawasan Industri Kota Cilegon Tahun 2013 ... 129
5.5. Jumlah dan Nilai Produksi Budidaya Kolam Ikan Lele oleh Penduduk Sekitar Kawasan Industri Kota Cilegon Tahun 2013 ... 129
5.6. Jumlah Kegiatan Usaha/Perdagangan yang Ada di Sekitar Kawasan Industri Kota Cilegon Tahun 2013 ... 131
5.7. Kelembagaan yang Ada di Masyarakat ... 142
Gambar Judul Gambar Halaman
1.1. Kerangka Kajian Penguatan Ekonomi Masyarakat di
Kawasan Industri Kota Cilegon ... 6
3.1. Peta Administratif Kota Cilegon ... 33
3.2. Data Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Cilegon
Tahun 2009 – 2013 ... 35 3.3. Gambar Kawasan Industri KIEC I dan KIEC II ... 47
3.4. Peta Kawasan Industri KIEC I dan KIEC II ... 48
3.5. Fasilitas Pergudangan di Kawasan Industri Taman Cipta
1.1. Latar Belakang Kajian
Sebagai kota industri, perkembangan industri di Kota Cilegon
ditandai dengan keberadaan industri besar yang sangat strategis untuk
mendorong perekonomian baik dalam skala nasional maupun daerah.
Namun, sejalan dengan pertumbuhan Kota Cilegon sebagai kota industri
secara tidak langsung menimbulkan permasalahan baru, yaitu timbulnya
ketimpangan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan
industri. Ketimpangan stratifikasi sosial ekonomi masyarakat di kawasan
industri akan berdampak pada timbulnya gejolak dan kerawanan sosial,
dimana kondisi ini terlihat dari tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh dan
kriminalitas yang mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat di
sekitar kawasan industri.
Kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai basis dari
sistem ekonomi kerakyatan merupakan salah satu solusi strategis guna
mengantisipasi timbulnya hambatan-hambatan dan permasalahan sosial
ekonomi masyarakat di kawasan industri. Paradigma pemberdayaan usaha
masyarakat dimaksud adalah sistem pengembangan ekonomi terintegrasi
(hulu-hilir) dan berkelanjutan yang berada dalam lingkup pembangunan
sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat.
Paradigma pembangunan seperti ini berpijak pada kemampuan
masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraannya dengan bertumpu pada
kemampuan sendiri dan atau kelompok. Pembangunan ekonomi berbasis
pembangunan berorientasi pada manusia dan masyarakat. Pembangunan
ekonomi berbasis kemampuan masyarakat perlu dirumuskan untuk
optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dan teknologi maju yang murah,
sederhana, dan efektif disertai penataan dan pengembangan
kelembagaannya. Pembangunan dengan paradigma baru ini diharapkan
dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menjadi pendorong
pertumbuhan sektor non-pertanian.
Pembangunan ekonomi berbasis kemampuan masyarakat patut
mengedepankan potensi kawasan dan kemampuan masyarakatnya.
Keunggulan komparatif yang berupa sumberdaya perlu diiringi dengan
peningkatan keunggulan kompetitif yang diwujudkan melalui penciptaan
sumberdaya manusia dan masyarakat pelaku usaha yang semakin
profesional di setiap kawasan. Masyarakat pelaku usaha, terutama tinggal
di sekitar kawasan industri, sebagai sasaran pemberdayaan masyarakat,
perlu terus dibina dan didampingi untuk dapat menjadi manusia/pelaku
usaha yang semakin maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.
Terkait dengan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan industri khususnya dan
umumnya dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi Kota
Cilegon, maka Pemerintah Kota Cilegon melalui Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Cilegon (BAPPEDA) pada tahun anggaran
2014 melaksanakan kegiatan Kajian Penguatan Ekonomi Masyarakat di
1.2. Tujuan dan Sasaran Kajian
Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Kajian Penguatan Ekonomi
Masyarakat di Kawasan Industri Kota Cilegon adalah untuk menyusun
dokumen kajian penguatan ekonomi masyarakat di kawasan industri yang
mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam setiap langkah
pembangunan ekonomi, sedangkan pemerintah memberikan fasilitas dan
pendampingan kepada masyarakat dalam melaksanakan program
ekonomi-produktifnya.
Berpijak dari tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai dari
pelaksanaan kegiatan Kajian Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kawasan
Industri Kota Cilegon ini adalah sebagai berikut :
1. Teridentifikasinya potensi usaha/ekonomi masyarakat di sekitar
kawasan industri dan permasalahan-permasalahan yang timbul;
2. Teranalisanya upaya pemihakan dan pemberdayaan kelompok
masyarakat, dimana pemberdayaan masyarakat dilakukan sesuai
dengan potensi, aspirasi, dan kebutuhannya;
3. Mempertajam arah pembangunan untuk rakyat melalui penguatan
kelembagaan pembangunan, baik kelembagaan masyarakat,
kelembagaan Koperasi-UKM, maupun kelembagaan birokrasi;
4. Terumuskannya suatu kebijakan pemberdayaan usaha masyarakat
bersama di kawasan industri yang mengarah pada peningkatan
memanfaatkan rekayasa teknologi tepatguna untuk meningkatkan
produktivitas, pendapatan, kesejahteraan masyarakat serta menghapus
kemiskinan.
1.3. Ruang Lingkup Kajian
Adapun ruang lingkup kegiatan yang akan ditempuh dalam rangka
pelaksanaan kegiatan Kajian Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kawasan
Industri Kota Cilegon meliputi tahapan sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan dan Desk Study
2. Tahap Survey dan Kompilasi Data
a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data tentang potensi
perekonomian di sekitar kawasan industri.
b. Melakukan pengidentifikasian faktor masalah eksternal dan internal
tentang potensi perekonomian di kawasan industri
c. Tinjauan teoritis tentang kajian penguatan ekonomi masyarakat di
kawasan industri
3. Tahap analisa dan perumusan rencana tindak
a. Melakukan analisis potensi dan masalah perekonomian masyarakat
di sekitar kawasan industri.
b. Merumuskan rencana penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat
di kawasan industri.
c. Merumuskan kebijakan pemberdayaan usaha masyarakat bersama di
tentang penguatan ekonomi masyarakat di kawasan industri.
4. Tahap pelaporan
a. Penyusunan draft laporan pendahuluan/ ekspose/diskusi draft
laporan pendahuluan.
b. Penyusunan draft laporan akhir, ekspose/diskusi draft laporan akhir.
1.4. Output Kajian
Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan Kajian Penguatan
Ekonomi Masyarakat di Kawasan Industri Kota Cilegon adalah berupa
dokumen kajian yang memuat potensi dan permasalahan perekonomian
masyarakat di kawasan industri, kelembagaan, kebijakan, serta strategi
penaganan dalam bentuk rencana tindak, sehingga dapat mendukung
upaya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
di kawasan industri Kota Cilegon pada masa mendatang.
1.5. Kerangka Kajian
Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam kajian Penguatan
Ekonomi Masyarakat di Kawasan Industri Kota Cilegon ini, yaitu; untuk
menyusun dokumen kajian penguatan ekonomi masyarakat di kawasan
industri yang mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam setiap
langkah pembangunan ekonomi, sedangkan pemerintah memberikan
fasilitas dan pendampingan kepada masyarakat dalam melaksanakan
pelaksanaan kajian digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1.1.
Kerangka Kajian Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Industri Kota Cilegon
Berdasarkan kerangka kerja sebagaimana Gambar 1.1. tersebut,
maka Kajian Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Industri Kota
Cilegon, dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Teridentifikasinya potensi usaha/ekonomi masyarakat di sekitar
kawasan industri dan permasalahan-permasalahan yang timbul;
2. Teranalisanya upaya pemihakan dan pemberdayaan kelompok
masyarakat, dimana pemberdayaan masyarakat dilakukan sesuai
kelembagaan pembangunan, baik kelembagaan masyarakat,
kelembagaan Koperasi-UKM, maupun kelembagaan birokrasi;
4. Terumuskannya suatu kebijakan pemberdayaan usaha masyarakat
bersama di kawasan industri yang mengarah pada peningkatan
kemampuan dan profesionalitas masyarakat untuk dapat
memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan berkelanjutan dengan
memanfaatkan rekayasa teknologi tepat guna untuk meningkatkan
produktivitas, pendapatan, kesejahteraan masyarakat serta menghapus
kemiskinan.
1.6. Pendekatan Studi
Jenis data yang telah dikumpulkan untuk analisis, terdiri atas data
primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil
observasi langsung pada instansi terkait yang memiliki data tentang objek
kajian. Sumber data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka, review
peraturan, dan inventarisasi data-data publikasi dari dinas, lembaga,
badan, atau biro yang terkait dengan studi ini.
Setelah data terkumpul, maka dilakukan tabulasi, penyusunan dan
pemilihan data, sehingga data yang akan dipakai untuk keperluan analisis
merupakan data yang benar dan relevan. Pemilihan data dilakukan sesuai
dengan jenis dan tingkat kepentingan informasi yang dibutuhkan melalui
serangkaian proses pemilihan data, agar didapatkan suatu data yang valid
dan akurat yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan Kajian
berikut;
A. Pendekatan Kondisi Obyektif
Dimaksud dengan pendekatan kondisi obyektif adalah pendekatan
yang berbasis kondisi lapangan, baik dari segi data potensi
usaha/ekonomi masyarakat di sekitar kawasan industri dan maupun
permasalahan-permasalahan yang timbul.
B. Pendekatan Daya Dukung Kelembagaan
Pendekatan ini dimaksudkan untuk menganalisis daya dukung
kelembagaan, mengenai penguatan kelembagaan pembangunan, baik
kelembagaan masyarakat, kelembagaan Koperasi-UKM, maupun
kelembagaan birokrasi.
C. Pendekatan Problem Solving
Pendekatan ini dimaksudkan untuk menganalisis berbagai
permasalahan yang dihadapi masyarakat di kawasan industri Kota
Cilegon dan upaya pemihakan dan pemberdayaan kelompok
masyarakat khususnya pada masyarakat di kawasan industri Kota
Cilegon, dimana pemberdayaan masyarakat tersebut harus dilakukan
sesuai dengan potensi, aspirasi, dan kebutuhannya.
D. Pendekatan Peraturan Perundangan
Pendekatan ini dimaksudkan untuk menganalisis peraturan
perundangan terkait dengan peran dan fungsi yang dapat diambil oleh
berbagai instansi terkait dalam penguatan ekonomi masyarakat di
2.1. Investasi dan Penanaman Modal
Investasi merupakan satu bagian penting dari pembangunan
ekonomi, terutama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Melalui investasi, akan tersedia berbagai sarana produksi, yang dapat
dioptimalkan dalam menghasilkan output dan nilai tambah sehingga akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Kegiatan investasi sendiri secara umum dapat dilakukan oleh dua
sektor utama, yaitu sektor pemerintah dan sektor swasta. Sebagian besar
investasi pemerintah umumnya dialokasikan untuk membiayai
pembangunan fisik maupun non fisik yang tidak dapat dibiayai dan
dilaksanakan oleh masyarakat. Pada saat ini, kemampuan dan kapasitas
pemerintah untuk membangun sarana produksi dan infrastruktur,
umumnya relatif terbatas untuk direalisasikan. Hal demikian terkait
dengan kelangkaan modal di sektor pemerintah.
Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal,
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing
untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman
modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan
usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan
oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing
sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam
negeri.
Tujuan penyelenggaraan penanaman modal (Pasal 3 Ayat 2 huruf h
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal), antara
lain untuk:
a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b. Menciptakan lapangan kerja;
c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan
menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari
luar negeri; dan
h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, disebutkan
kewajiban bagi setiap penanam modal, yaitu:
a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan
penanaman modal; dan
e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan dalam huruf c
di atas adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan
penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi,
seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya
masyarakat setempat
Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas
tinggi pada skala nasional (Pasal 30 Ayat 7 huruf b Undang-undang Nomor
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Pemerintah dan Pemerintah
Daerah terus mendorong penanaman modal di bidang Industri untuk
memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya
nasional maupun daerah dalam rangka pendalaman struktur Industri
nasional/daerah dan peningkatan daya saing Industri (pasal 109 ayat 1
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian).
Untuk mendorong penanaman modal sebagaimana di atas, Menteri
menetapkan kebijakan yang memuat paling sedikit mengenai:
a. Strategi penanaman modal;
b. Prioritas penanaman modal;
c. Lokasi penanaman modal;
d. Kemudahan penanaman modal; dan
e. Pemberian fasilitas.
Lokasi penanaman modal bagi kegiatan industri dilakukan pada
Definisi kawasan industri dikemukakan dalam Pasal (1) angka 2
Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri,
yaitu; kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi
dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola
oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha
Kawasan Industri.
Definisi kawasan peruntukan industri dikemukakan dalam Pasal (1)
angka 5 dalam peraturan perundangan yang sama, yaitu; kawasan
peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi
kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna
tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
di bidang usaha Industri di wilayah Indonesia. Perusahaan Industri yang
akan menjalankan Industri setelah Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku
(sejak 3 Maret 2009), wajib berlokasi di kawasan industri. Kewajiban
berlokasi di kawasan industri, dikecualikan bagi (Pasal 7 Ayat 1dan 2
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009) :
a. Perusahaan Industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses
produksinya memerlukan lokasi khusus.
daerah kabupaten/kota yang belum memiliki Kawasan Industri atau
yang telah memiliki Kawasan Industri namun seluruh kaveling
industri dalam kawasan industrinya telah habis.
Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2009,
disebutkan tujuan dari pembangunan kawasan industri, yaitu untuk:
a. Mengendalikan pemanfaatan ruang;
b. Meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan
lingkungan;
c. Mempercepat pertumbuhan Industri di daerah;
d. Meningkatkan daya saing Industri;
e. Meningkatkan daya saing investasi; dan
f. Memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan
infrastruktur, yang terkoordinasi antar sektor terkait.
Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang
mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pasal 20 Peraturan Pemerintah RI
Nomor 24 Tahun 2009). Dalam Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri
Perindustrian RI Nomor: 05/M-IND/PER/2/2014 tentang tata cara
pemberian izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan
industri, disebutkan;
1. Perusahaan kawasan industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan
usaha mikro, kecil dan menengah minimal 2% (dua persen) dari luas
atas tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh usaha mikro, kecil dan
menengah, dapat digunakan oleh perusahaan industri lainnya
sepanjang lahan untuk perusahaan industri lainnya tersebut sudah
tidak tersedia.
2.3. Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan
Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan atau Corporate Social
Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara
sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke
dalam operasinya dan interaksinya dengan stokeholders, yang melebihi
tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004). Menurut
Pearce dan Robinson (2008:72) tanggung jawab sosial terdiri atas:
a. Tanggung jawab ekonomi (economic responsibilities) yang dimana tugas
manajer sebagai agen dari pemilik perusahaan, untuk memaksimalkan
kekayaan pemegang saham.
b. Tanggung jawab hukum (legal responsibilities) mencerminkan kewajiban
perusahaan untuk mematuhi undang-undang yang mengatur aktivitas
bisnis.
c. Tanggung jawab etika (ethical responsibilities) mencerminkan gagasan
perusahaan mengenai perilaku bisnis yang benar dan layak.
d. Tanggung jawab diskersi (discretionary responsibilities) merupakan
tanggung jawab yang secara sukarela diambil oleh suatu bisnis yang
mencakup hubungan masyarakat, kewargaan yang baik, dan tanggung
diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia (Irawan, 2004)
melalui empat model berikut:
a. Keterlibatan langsung, dimana perusahaan menjalankan program CSR
secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau
menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk
menjalankan tugas ini, perusahaan biasanya menugaskan salah satu
pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau public affair manager
atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation.
b. Melalui yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan, dimana
perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau
grupnya. Disini perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau
dana abadi yang dapat digunakan untuk operasional yayasan.
c. Bermitra dengan pihak lain, dimana perusahaan menyelenggarakan
CSR melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi non pemerintah,
instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam
mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
d. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium, perusahaan
turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga
sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium
yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya
akan secara proaktif mencari kerjasama dari berbagai kalangan dan
pertanggungjawaban sosial perusahaan, tertuang dalam peraturan sebagai
berikut;
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor;
PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha
Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha
Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor; PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha
Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan
Gas Bumi, kewajiban perusahaan untuk membangun masyarakat di sekitar
(CSR), tertuang dalam Pasal 11 ayat (3) huruf p dan Pasal 40 ayat (5),
sebagai berikut;
1. Kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk
ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan
hak-hak masyarakat adat (Pasal 11 ayat (3) huruf p UU 22/2001).
2. Selain itu, dalam Pasal 40 ayat (5) undang-undang yang sama, juga
dikatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang
melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (kegiatan usaha
hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam
mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.
Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal, kewajiban perusahaan untuk melakukan pertanggungjawaban
sosial diatur dalam Pasal 15 huruf b; Pasal 16; dan Pasal 34, yaitu;
1. Pasal 15 huruf b Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan
bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggungjawab
sosial. Dimaksud dengan tanggungjawab sosial menurut penjelasan
Pasal 15 huruf b undang-undang yang sama adalah tanggung jawab
yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap
menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan
lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
2. Pasal 16 undang-undang yang sama juga mengatur bahwa setiap
penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian
lingkungan hidup dimana hal tersebut juga merupakan bagian dari
jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk
melaksanakan tanggungjawab sosial, maka berdasarkan penanam
modal dapat dikenai sanksi adminisitatif berupa: peringatan tertulis;
pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha dan/atau
fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau
fasilitas penanaman modal. Selain dikenai sanksi administratif, penanam
modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, kewajiban perusahaan untuk melakukan pertanggungjawaban
sosial terdapat dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74, yaitu;
1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan
untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat,
baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat
pada umumnya (Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun
2007).
2. Pasal 74 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, dinyatakan bahwa;
a. Pertanggungjawaban sosial wajib untuk perseroan yang
menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan
kewajaran.
c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sosial akan dikenai
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terkait.
Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama Pasal 68,
disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
berkewajiban:;
a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat
waktu;
b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dikemukakan
hal berikut;
a. Dalam Pasal 4, dikatakan bahwa tanggungjawab sosial dilaksanakan
oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah
mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja
tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran
pelaksanaan tanggungjawab sosial tersebut dimuat dalam laporan
tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor; PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan
Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina
Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara Nomor: PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan
Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan,
menjelaskan tentang;
1. Berdasarkan Pasal 2 Permen BUMN 5/2007, Persero dan Perum wajib
melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan
Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat
melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan
Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN
5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
2. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk
meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan
mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 6 Permen
kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana
BUMN (Pasal 1 angka 7 Permen BUMN 5/2007).
2.4. Konsep Pemberdayaan Ekonomi
Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan
(empowerment) berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau
keberdayaan (Suharto, 2005; 57). Pemberdayaan pada hakekatnya adalah
upaya pemberian daya atau peningkatan keberdayaan. Dengan demikian,
pemberdayaan merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat agar
mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan.
Beberapa ahli saat ini telah mengkonotasikan pemberdayaan untuk
masyarakat kelas bawah (grassroot) yang umumnya dinilai tidak berdaya,
sehingga pemberdayaan didefinisikan sebagai upaya untuk terus-menerus
meningkatkan harkat dan martabat masyarakat kelas bawah yang tidak
mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.
Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
upaya membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan. Itu berarti
bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk memandirikan, lewat
perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki.
Suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau
lebih dari beberapa variabel. Pertama, memiliki kemampuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. Kedua,
Keempat, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam
mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya. (Hotmatua Daulay
dan Mulyanto, 2001).
Permberdayaan dibidang ekonomi merupakan upaya untuk
membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan
membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta
berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah
unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam
pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai
kemajuan.
Pemberdayaan ekonomi dapat diartikan sebagai upaya untuk
meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dari kondisi tidak
mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan
keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun
kemandirian masyarakat di bidang ekonomi.
Menurut Warta Demografi (1997U), upaya pemberdayaan dapat
dilihat dari tiga sisi. Pertama, pemberdayaan dengan menciptakan
suasana atau atau iklim yang memungkinkan potensi ekonomi
masyarakat berkembang. Artinya, setiap anggota masyarakat dapat
secara alamiah memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan
menuju kehidupan yang lebih baik.
Kedua, pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi
ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka
sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi,
informasi, lapangan kerja, dan pasar.
Ketiga, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi
masyarakat berarti berupaya melindungi untuk mencegah terjadinya
persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan
kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum
berkembang.
Menurut Kartasasmita (1996), pemberdayaan masyarakat adalah
sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai
sosial, yang harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu;
1. Menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi
masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi
bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat
dikembangkan. Hakikat kemandirian dan keberdayaan rakyat
adalah keyakinan bahwa rakyat memiliki potensi untuk
mengorganisasikan dirinya sendiri dan potensi kemandirian
individu perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan rakyat berakar
kuat pada proses kemandirian kemandirian setiap individu yang
kemudian meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik di
tingkat lokal maupun nasional.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan
menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai
masukan, menyediakan prasarana dan sarana, baik fisik maupun
membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses
pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah makin
terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat.
Peran program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan
melalui bantuan dana yang dapat diciptakan dari kegiatan sosial
ekonomi dengan menganut beberapa prinsip sebagai berikut
(Gunawan Sumodiningrat, 1999):
1. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok
sasaran (acceptable).
2. Dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggung
jawabkan (accountable).
3. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat
untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (profitable).
4. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat (sustainable).
5. Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah
digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang
lebih luas (replicable).
Sumodiningrat (1999) juga mengemukakan indikator
keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program
pemberdayaan masyarakat yang mencakup:
1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan
penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang
kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya.
4. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin
berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin
kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi
kelompok, serta makin luasnya interaksi sosial dengan kelompok
lain.
Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan
pendapatan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga
miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan
sosial dasarnya.
2.5. Pengembangan Ekonomi Lokal (Local Economic Development)
Edward J. Blakely (1994), mendefenisikan Local Economic
Development “= f (natural resources, labor, capital, investment,
entrepreneurships, transport, communication, industrial composition, technology,
size, export market, international economic situation, local government capasity,
national dan state government spending and development supports). All of these
factors may be important. However, the economic development practitioner is never
certain which factor has the greatest weight in any given situation”. Lebih lanjut
beliau menyebutkan bahwa “... The central feature of locally based economic
development is in the emphasis on endogenous development using the potensial of
local human and physical resources to create new employment opportunities and to
Economi Development (LED) is the process by which public, business and non
governmental sector partners work collectively to create better conditions for
economic growth and employment generation”. The aim is to improve the quality
of life for all. Practicing local economic development means working directly to
build the economic strength of all local area to improve its economic future and the
quality of life of its inhabitats. Prioritizing the local economy is crucial if
communities today depends upon them being able to adopt to the fast changing and
increasingly competitive market environment”.
Berdasarkan sudut pandang masyarakat, pengembangan ekonomi
lokal diartikan sebagai upaya untuk membebaskan masyarakat dari semua
keterbatasan yang menghambat usahanya guna membangun
kesejahteraannya. Kesejahteraan tersebut dapat diartikan secara khusus
sebagai jaminan keselamatan bagi adat istiadat dan agamanya, bagi
usahanya, dan bagi harga dirinya sebagai mausia. Semua jaminan tersebut
tidak dapat diperoleh dari luar sistem masyarakat karena tidak
berkelanjutan, dan oleh karena itu harus diupayakan dari sistem masarakat
itu sendiri yang kerap kali disebut kemandirian.
Dengan demikian, pembangunan ekonomi lokal merupakan upaya
pemberdayaan masyarakat ekonomi dalam suatu wilayah dengan
bertumpukan kepada kekuatan lokal, baik itu kekuatan nilai lokasi, sumber
daya alam, sumber daya manusia, teknologi, kemampuan manajemen
kelembagaan (capacity of institutions) maupun aset pengalaman
masyarakat telah menumbuhkan aspirasi dan tuntutan baru dari
masyarakat untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik.
Aspirasi dan tuntutan masyarakat itu dilandasi oleh hasrat untuk lebih
berperan serta dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur
dan sejahtera. Dalam ekonomi yang makin terbuka, ekonomi makin
berorientasi pada pasar, peluang dari keterbukaan dan persaingan pasar
belum tentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang kemampuan
ekonominya lemah. Dalam keadaan ini harus dicegah terjadinya proses
kesenjangan yang makin melebar, karena kesempatan yang muncul dari
ekonomi yang terbuka hanya dapat dimanfaatkan oleh wilayah, sektor, dan
golongan ekonomi yang lebih maju. Secara khusus perhatian harus
diberikan dengan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat melalui
pembangunan ekonomi lokal.
Pengembangan ekonomi lokal erat kaitannya dengan
pemberdayaan sumberdaya manusianya, lembaganya dan lingkungan
sekitarnya. Untuk mengembangkan ekonomi lokal tidak cukup hanya
dengan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusianya, tetapi juga
diperlukan adanya lembaga yang terlatih untuk mengelola sumberdaya
manusia yang sudah maju, dan memerlukan lingkungan yang kondusif
untuk memungkinkan lembaga ekonomi lokal tersebut berkembang.
Pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan lembaga
kemitraan semua stakeholders (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat)
dan mitra usaha. Untuk selanjutnya, komunikasi multi arah menjadi
kebutuhan dasar dalam pengembangan lembaga kemitraan tersebut.
2.6. Kemitraan (Partnership)
Kemitraan pada hakekatnya merupakan wujud yang ideal dalam
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kemitraan
didasari atas hubungan antar pelaku yang bertumpu pada ikatan usaha
yang saling menunjang dan saling menguntungkan serta saling
menghidupi berdasarkan asas kesetaraan dan kebersamaan. Dengan
kemitraan diharapkan dapat menumbuhkan dan menjamin keberlanjutan
jaringan kelembagaan untuk mendukung inisiatif lokal dalam
pengembangan ekonomi lokal (Haeruman, 2001).
Sejalan dengan itu, Edward J. Blakely (1994) menguraikan
Public-Private-Partnerships : “No matter what organizational structure is selected,
public agencies and private firms have to enter into new relationships to make the
development process work. This approach is much more than the public sector
merely offering cooperation to the private sector to facilitate economic activities for
private gain; it is far more than occaional meetings between the municipal council
and local business organizations, such as the chamber of commerce. Although these
activities are important, and perhaps integral to good business/government
relations, they do not constitute true partnerships among the sectors. Partnerships
are shared commitments to pursue common economic objectives jointly determined
dikenal. Dalam pola ini diharapkan suatu lembaga mampu berfungsi
sebagai penampung aspirasi para anggota kemitraan tersebut. Perlu diingat
bahwa salah satu fungsi dari lembaga kemitraan adalah arus mampu
mencerminkan keikutsertaan para anggotanya (participatory approach) dan
mengikutsertakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam
pembangunan di daerah mereka masing-masing.
Berdasarkan pengalaman yang lalu, keikutsertaan sektor swasta dan
wakil dari masyarakat sangat berperan dalam meningkatkan dinamika
suatu kemitraan. Bahkan kalau perlu lembaga kemitraan tersebut dipimpin
oleh wakil dari swasta atau wakil dari masyarakat. Hal ini akan sangat
mempengaruhi keinerja dari kemitraan itu sendiri. Dengan prinsip “duduk
sama rendah dan berdiri sama tinggi”, para anggota akan lebih untuk
mengutarakan berbagai masalah atau tantangan yang dianggap menjadi
ganjalan dalam membangun daerahnya. Banyak pengamat menunjukkan
bahwa kecenderungan didunia usaha sekarang bukan kepada membangun
usaha yang semakin besar, tapi kepada unit usaha kecil atau menengah dan
independen sehingga menjadi lincah dan cepat tanggap dalam menghadapi
perkembangan dan perubahan yang cepat di pasar. Peluang pasar akan
terdiri bukan atas peningkatan permintaan yang besar, melainkan atas
peluang-peluang kecil.
Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua
pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan
sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam
menjalankan etika bisnis. Dalam konteks ini pelaku-pelaku yang terlibat
langsung dalam kemitraan tersebut harus memiliki dasar-dasar etika bisnis
yang dipahami bersama dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam
menjalankan kemitraan. Hal ini erat kaitannya dengan peletakan
dasar-dasar moral berbisnis bagi pelaku-pelaku kemitraan. Pemahaman etika
bisnis sebagai landasan moral dalam melaksanakan kemitraan merupakan
suatu solusi dalam mengatasi kurang berhasilnya kemitraan yang ada
selama ini. Komposisi kemitraan itu sangat bervariasi, tetapi merupakan
representasi pelaku ekonomi seperti produsen, pedagang, eksportir,
pengolah, pemerintah daerah/pusat, perguruan tinggi, lembaga riset lain,
lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya.
Lebih lanjut, Herman Haeruman (2001) mengelaborasi kemitraan
sebagai suatu proses. Proses yang dimulai dengan perencanaan, kemudian
rencana itu diimplementasikan dan selanjutnya dimonitor serta dievaluasi
terus-menerus oleh pihak yang bermitra. Dengan demikian terjadi alur
tahapan pekerjaan yang jelas dan teratru sesuai dengan sasaran yang ingin
dicapai. Karena kemitraan merupakan suatu proses maka keberhasilannya
diukur dengan pencapaian nilai tambah yang didapat oleh pihak yang
bermitra baik dari segi material maupun non-material, nilai tambah ini
akan berkembang terus seusai dengan meningkatnya tuntutan untuk
mengadaptasi berbagai perubahan yang terjadi. Singkatnya, nilai tambah
sensitif dan menunjukkan komitmen dan empatinya tidak saja terhadap
apa yang menjadi tujuan forum kemitraan bersangkutan tetapi terutama
terhadap apa yang menjadi tujuan masing-masing individu. Dengan kata
lain, setiap anggota harus sensitif terhadap apa yang menjadi tujuan forum
kemitraan, tujuannya sendiri, serta tujuan individual identik dengan
mencabut akar kemitraan itu sendiri (The Peter F. Drucker Foundation,
1996; Austin, 2000; The Jean Monnet Program, 2001).
Secara sederhana, Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal
atau disingkat dengan akronim “KPEL” adalah suatu pendekatan untuk
mendorong aktivitas ekonomi melalui pembentukan kemitraan
masyarakat-swasta-pemerintah dan memfokuskan pada pembangunan
aktivitas kluster ekonomi, sehingga terbangun keterkaitan (linkage) antara
pelaku-pelaku ekonomi dalam satu wilayah atau region (perdesaan/
kota/kecamatan/kabupaten/propinsi) dengan market (pasar lokal,
nasional dan pasar internasional) (UNDP, UN-HABITAT dan BAPPENAS,
2002). KPEL juga merupakan instrumen untuk mendukung terciptanya : 1).
pembangunan ekonomi yang mendayagunakan sumber daya lokal; 2)
peningkatan pendapatan dan penciptaan peluang lapangan kerja; 3).
perencanaan yang terintergrasi-baik vertikal dengan horizontal maupun
3.1. Karakteristik Wilayah Kota Cilegon
Kota Cilegon merupakan Wilayah hasil pemekaran dan batasan
ruang lingkup wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
1999, luas wilayah administrasi 17.550,0 Ha dengan 8 kecamatan
(Kecamatan Ciwandan, Citangkil, Pulomerak, Grogol, Purwakarta, Cilegon,
Jombang, dan Cibeber) yang terdiri atas 43 kelurahan.
Secara administrasi, Kota Cilegon mempunyai batas-batas sebagai
berikut :
Sebelah Barat : Selat Sunda
Sebelah Utara : Kabupaten Serang
Sebelah Timur : Kabupaten Serang
Sebelah Selatan : Kabupaten Serang
Secara administratif, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Cilegon,
maka wilayah administrasi Kota Cilegon terbagi kedalam 8 (delapan)
Kecamatan dan 43 Kelurahan. Pembagian wilayah serta jumlah
kecamatan dan kelurahan di Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel di
Tabel 3.1.
Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cilegon
No. Kecamatan Pusat Kecamatan
Luas Jumlah
Kelurahan
Km2 %
1. Ciwandan Tegal Ratu 51,81 29,52 6 2. Citangkil Kebonsari 22,98 13,09 7 3. Pulomerak Tamansari 19,86 11,32 4 4. Purwakarta Purwakarta 15,29 8,71 6
5. Grogol Grogol 23,38 13,32 4
6. Cilegon Ciwaduk 9,15 5,21 5
7. Jombang Jombang Wetan 11,55 6,58 5 8. Cibeber Kalitimbang 21,49 12,24 6
Kota Cilegon 175,51 100,00 43
Sumber : Cilegon Dalam Angka Tahun 2014
Jika dipetakan, maka peta administratif Kota Cilegon, sebagaimana
terlihat pada Gambar 3.3. berikut ini;
Gambar 3.1.
Secara astronomis, Kota Cilegon terletak diantara koordinat
5º52’24”–6º04’07” Lintang Selatan (LS) dan 105º54’05”–106º05’11” Bujur
Timur (BT). Sedangkan secara geografis Kota Cilegon berada dalam lingkup
Kota Cilegon di bagian barat Provinsi Banten yang berbatasan langsung
dengan Provinsi Sumatera.
3.2. Data Kependudukan Kota Cilegon
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2009-2013) jumlah penduduk
Kota Cilegon mengalami kenaikkan. Proses perkembangan jumlah
penduduk dari 349.162 jiwa pada tahun 2009 menjadi 398.304 jiwa pada
tahun 2013 dicirikan dengan proses pertumbuhan yang relatif stagnan dari
tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.4. di bawah.
Relatif tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Cilegon selain
karena adanya pertambahan penduduk secara alami, namun juga
dipengaruhi oleh peristiwa migrasi penduduk yang masuk sebagai pencari
kerja maupun tenaga kerja yang merupakan implikasi atas
bertumbuhkembangnya kondisi perekonomian Kota Cilegon, khususnya
Sumber : CDA Kota Cilegon Tahun 2014
Gambar 3.2.
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Cilegon Tahun 2009-2013
Seiring dengan pertumbuhan penduduk tersebut, kepadatan
penduduk di Kota Cilegon juga mengalami peningkatan dari 2.235
jiwa/km2 pada tahun 2012 menjadi 2.269 jiwa/km2 pada tahun 2013.
Konsentrasi kepadatan penduduk pada tahun 2013 tertinggi terjadi di
Kecamatan Jombang yang mencapai sebesar 5.534 jiwa/km2, sedangkan
Kecamatan Ciwandan merupakan kecamatan yang terendah kepadatan
penduduknya yakni mencapai sekitar 873 jiwa/km2. Tingginya kepadatan
penduduk di Kecamatan Jombang dikarenakan kecamatan ini merupakan
kawasan pusat permukiman penduduk, sebaliknya Kecamatan Ciwandan
yang kepadatannya rendah dikarenakan kecamatan ini wilayahnya
didominasi oleh kawasan perindustrian. 349.162
374.559 385.720 392.341
398.304
2009 2010 2011 2012 2.013
Per
sen
Ji
wa
Tabel 3.2.
Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Kota Cilegon Tahun 2012 dan 2013
No Kecamatan
Luas Wilayah
(Km²)
Tahun 2012 Tahun 2013 Penduduk
Sumber : Cilegon Dalam Angka Tahun 2014
Jika diperhatikan dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki
terhadap perempuan (sex rasio) di Kota Cilegon, terlihat bahwa pada tahun
2013 sex rasionya sebesar 104, yang berarti bahwa jumlah penduduk
laki-laki 4% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sex
rasio terbesar terdapat di Kecamatan Purwakarta yakni sebesar 107,
sedangkan terendah terdapat di Kecamatan Cibeber yakni sebesar 102.
Tabel 3.3.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Cilegon Tahun 2013
No. Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Sex Ratio (%) Laki-laki Perempuan Total
1. Ciwandan 23.303 21.929 45.232 106 Kota Cilegon 203.502 194.802 398.3041 104
Dilihat dari komposisi umur penduduk di Kota Cilegon, jumlah
penduduk usia 15 tahun ke atas (usia produktif) mengalami kenaikkan dari
tahun ke tahun. Tingginya persentase penduduk usia produktif tersebut
merupakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki Kota Cilegon yang
seharusnya menjadi sumber daya yang bisa di dayagunakan.
Secara umum struktur penduduk menurut kelompok umur dapat
dikelompokan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok usia 0-14 tahun, 15-64
tahun dan 65 tahun ke atas atau kelompok usia produktif dan non
produktif. Penduduk non produktif yang merupakan gabungan antara
penduduk muda (0 - 14 tahun) dengan usia tua (65 tahun ke atas) pada
tahun 2013 mencapai 40,32 %, sementara itu penduduk yang termasuk
dalam usia produktif (15-64 tahun) sebesar 59,68 %. Mengingat persentase
penduduk usia produktif yang cukup tinggi, apabila diimbangi dengan
kualitas yang baik akan menjadi sumber daya penting bagi pembangunan.
Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap
sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih
tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain
itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi
sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah
penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini
dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada
penduduk berusia produktif terhadap penduduk non produktif. Meskipun
tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan atau Angka Beban
Ketergantungan (ABK) semacam ini memberikan gambaran ekonomis
penduduk dari sisi demografi.
ABK merupakan perbandingan antara penduduk usia non produktif
dengan penduduk usia produktif, dimana pada tahun 2013 angkanya yaitu
67,56 atau dapat dikatakan bahwa setiap 100 orang produktif akan
menanggung 67-68 orang non produktif atau kurang lebih 2 berbanding 1.
Meskipun demikian secara total komposisi umur penduduk produktif dan
nonproduktif di Kota Cilegon masih tergolong wajar dan cukup
menguntungkan, karena kelompok usia produktif yang cukup besar
sementara umur non produktif relatif kecil.
Tabel 3.4.
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Cilegon Tahun 2011-2013
No Kelompok Umur
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
L P L P L P
Isue penting yang terkait dengan pemberdayaan penduduk usia
produktif utamanya adalah mengenai ketenagakerjaan, yang dalam hal ini
adalah terkait dengan keadaan angkatan kerja, struktur ketenagakerjaan,
dan pengangguran.
Pada tahun 2013, sekitar 60,23% dari seluruh penduduk usia kerja
merupakan tenaga kerja aktif dalam kegiatan ekonomi atau disebut dengan
angkatan kerja. Jumlah ini menurun sekitar 5,51% dibanding tahun 2012.
Persentase angkatan kerja yang diistilahkan dengan Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan pasokan tenaga kerja yang
tersedia untuk memproduksi barang dan jasa di Kota Cilegon. Pada tahun
2013 TPAK laki-laki sebesar 82,30%, lebih tinggi daripada TPAK
perempuan sebesar 37,18% karena penduduk laki-laki umumnya pencari
nafkah utama di keluarga. Rendahnya TPAK perempuan disebabkan
kegiatan utama perempuan umumnya mengurus rumahtangga
dibandingkan menjadi angkatan kerja (bekerja atau mencari kerja).
Prosentase dari jumlah pengangguran terhadap total jumlah angkatan kerja
diistilahkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT), yang pada tahun
2012 angkanya mencapai 11,30%dan pada tahun 2012 dapat ditekan
menjadi sebesar 7,16% atau terjadi penurunan sebesar 4,14 %.
Makin menurunnya TPT, menunjukan bahwa Pemerintah Daerah
secara perlahan dapat mengatasi masalah pengangguran. Hal ini tidak
terlepas dari adanya sinergitas antara seluruh stakeholder pembangunan.
menganggur, diupayakan dapat disokong oleh peningkatan investasi di
Kota Cilegon, yang dalam hal ini sangat bergantung pada stabilitas
keamanan di daerah dan aspek perizinan terkait dengan kemudahan
birokrasi.
Tabel 3.5.
Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, dan TPT di Kota Cilegon Tahun 2009-2013
Tahun
Sumber: Cilegon Dalam Angka Tahun 2014
Disamping itu, peningkatkan kualitas SDM juga harus
dikedepankan. Untuk mengurangi terjadinya mismatch dalam pasar kerja,
perlu adanya link and match antara pendidikan dan lapangan pekerjaan
yang tersedia. Mengacu kepada visi jangka panjang Pemerintah Daerah
Kota Cilegon sebagai kota industri, perdagangan dan jasa, maka muatan
pendidikan seyogyanya lebih diarahkan kepada tiga sektor tersebut.
Berdasarkan data penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, ketiga
sektor tersebut merupakan yang paling banyak menyerap tenaga kerja.
Selain upaya menumbuhkan lapangan kerja, pengurangan
pengangguran juga harus dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi
masyarakat, melalui penumbuhan jiwa wirausaha (entrepreneurship),
dan menengah. Perlu dukungan ruang juga bagi pengembangan industri
kecil serta peningkatan kemitraan antara industri kecil/menengah dan
besar, tidak hanya melalui dukungan permodalan, tetapi juga lebih kepada
keselarasan produk dan pendampingan peningkatan kualitas SDM.
Tabel 3.6.
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Cilegon Tahun 2010-2013
No. Lapangan Usaha TAHUN
2010 2011 2012 2013
1. Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan
Perikanan 4,25 5,12 4,62 3,25
2. Pertambangan dan Penggalian 1,14 0,93 0,40 0,82 3. Industri Pengolahan 23,76 16,16 18,90 14,02 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,68 0,21 0,40 0,83 5. Konstruksi 9,32 7,94 8,86 9,47 6. Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa
Akomodasi 26,90 30,22 30,24 25,21 7. Transportasi, Pergudangan, dan
Komunikasi 11,99 10,03 8,83 12,96 8. Lembaga Keuangan, Real Estate,
Persewaan & Jasa Perusahaan 4,27 6,85 5,69 12,79 9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan
Perorangan 17,67 22,54 22,07 20,66 Sumber: Cilegon Dalam Angka Tahun 2014
3.3. Kawasan Industri di Kota Cilegon
Definisi kawasan industri sebagaimana dikemukakan dalam Pasal
(1) angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri (sering disebut Industrial Estate), yaitu; kawasan tempat
pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana
penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan