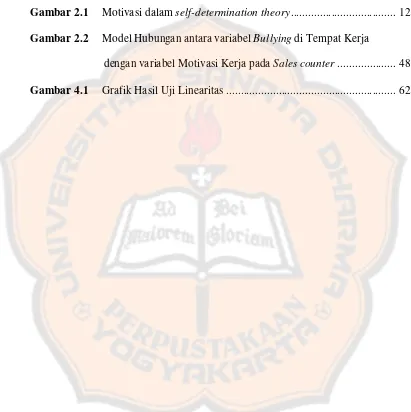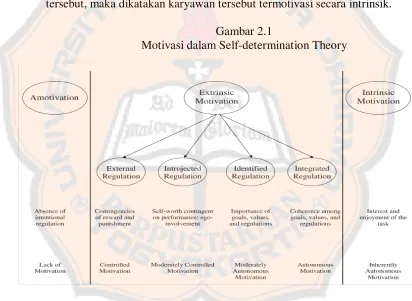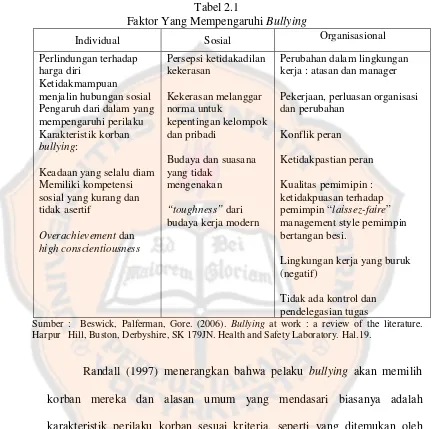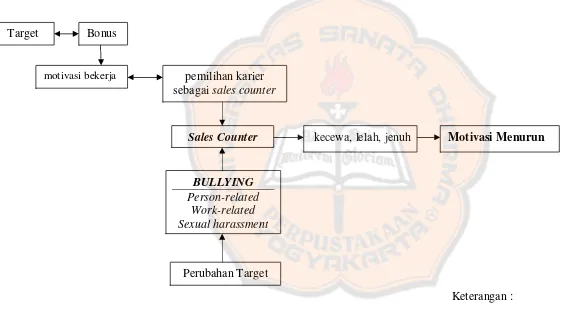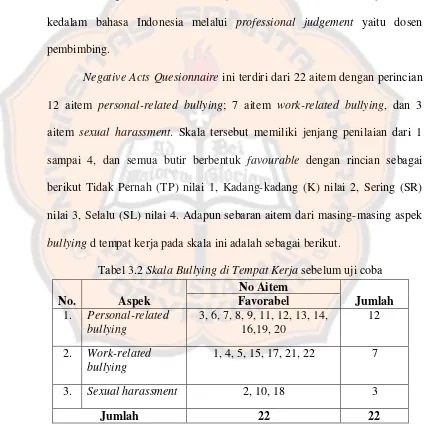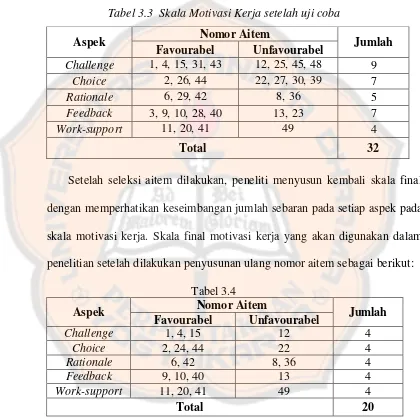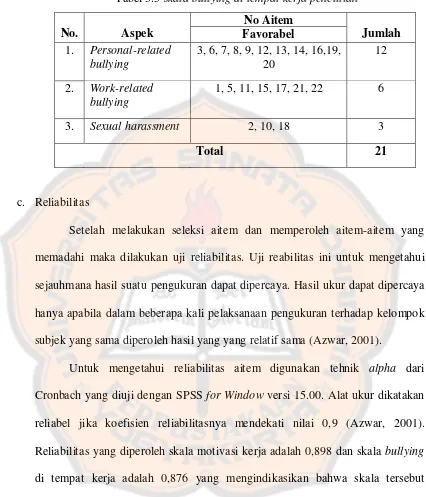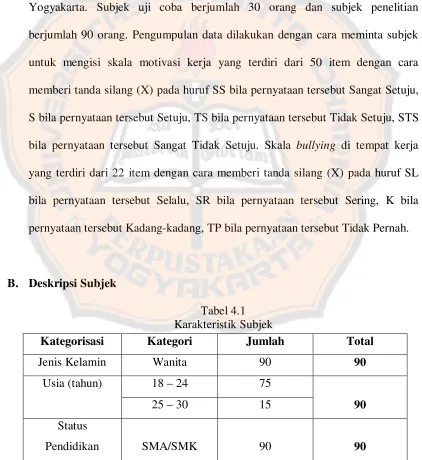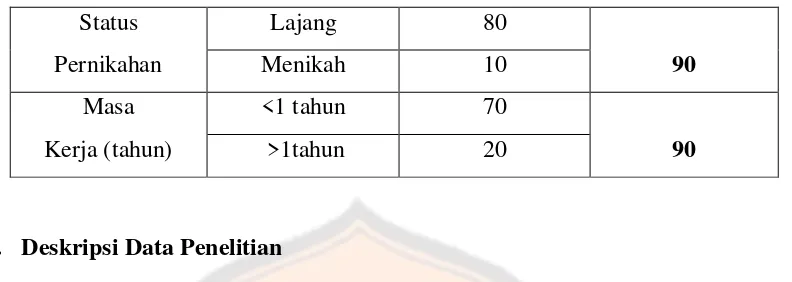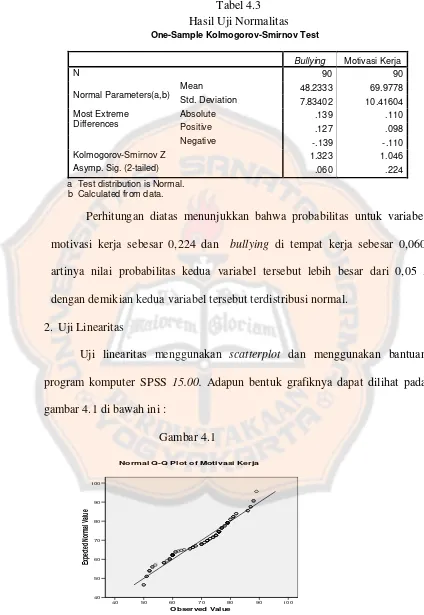HUBUNGAN ANTARA BULLYING DI TEMPAT KERJA
DENGAN MOTIVASI KERJA PADA SALES COUNTER
KENDARAAN BERMOTOR HONDA DI YOGYAKARTA
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi
Program Studi Psikologi
Oleh:
Hellen Windari
NIM: 04 9114 042
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI JURUSAN PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
iv MOTTO
“Terimalah didikanku lebih dari pada perak,
dan pengetahuan lebih dari pada emas pilihan.”
(Amsal 8:10)
“Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Ia akan seperti pohon yang ditanam ditepi air,
yang mer ambatkan akar-akarnya ke tepi batang air,
dan yang tidak mengalami datangnya panas ter ik,
yang daunnya tetap hijau,
yang tidak kuatir dalam tahun kering,
dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.”
v
KUPERSEMBAHKAN KARYA INI KEPADA :
Tuhan Yesus Kristus
Papah dan M amah
ka’N anda
L eonard
vii
HUBUNGAN ANTARA BULLYING DI TEMPAT KERJA DENGAN
MOTIVASI KERJA PADA SALES COUNTER KENDARAAN BERMOTOR
HONDA DI YOGYAKARTA
Hellen Windari
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara bullying di tempat kerja dengan motivasi kerja. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan negatif antara bullying di tempat kerja dengan motivasi kerja pada sales counter. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, jumlah sampel uji coba sebanyak 30 karyawan dan jumlah sampel penelitian sebanyak 90 karyawan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis skala, yaitu skala bullying di tempat kerja dengan hasil uji reliabilitas 0,876 dan skala motivasi kerja dengan hasil uji reliabilitas 0,898. Hasil analisis data dengan menggunakan teknik korelasi product moment menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara bullying di tempat kerja dengan motivasi kerja pada sales counter dengan hasil koefisien korelasi -0,557. Hal ini berarti semakin tinggi bullying di tempat kerja maka semakin rendah motivasi kerja yang dialami sales counter kendaraan bermotor honda di Yogyakarta.
viii
THE CORRELATION BETWEEN WORKPLACE BULLYING AND WORK MOTIVATION ON SALES COUNTER HONDA MOTORCYCLE
IN YOGYAKARTA
Hellen Windari
ABSTRACT
This research aims to determine the correlation between workplace bullying and work motivation. The hypothesis in this research is that there is a negative correlation between workplace bullying and work motivation for sales counters. This is a correlation research. The technique of samples collecting is the purposive sampling, with 30 workers as the try out subjects and 90 workers as the research subjects. The method of data collecting in this research is 2 scales, namely workplace bullying scale and work motivation scale. Level of reliability for workplace bullying scale is 0,876 while for work motivation scale is 0,898. The result of data analysis, using Pearson’s Product Moment correlation technique, indicates that there is a negative correlation between workplace bullying and work motivation for sales counters, with the result of coefficient is -0,557. This means that the higher the workplace bullying is, the lower the possibility of work motivation happens to the sales counters. On the contrary, the lower the workplace bullying is, the higher the possibility of work motivation happens to the sales counters.
x
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kasih dan bimbinganNya kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Dengan kasih dan pendampinganNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Hubungan Antara Bullying Di Tempat Kerja dengan Motivasi Kerja pada Sales counter Kendaraan Bermotor Honda di Yogyakarta.
Penulis juga menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini secara langsung. Oleh karena itu dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :
1. Ibu Dr. Christina Siwi Handayani selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyusun skripsi ini.
2. Ibu Titik Kristiyani, M.Psi. selaku Kepala Program Studi Psikologi Universitas Sanata Dharma yang telah berkenan membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu P. Henrietta PDADS., S.Psi., M.A. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.
xi
5. Ibu Dra. Lusia Pratidarmanastiti, MS. sebagai dosen pembimbing akademik yang telah membantu menyelesaikan kesulitan dalam masalah akademik peneliti.
6. Papah dan Mamah terkasih, yang telah sabar mendampingi dan memberikan fasilitas baik secara material maupun spiritual kepada penulis selama menempuh pendidikan sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis ini.
7. Kakak’ku Nanda Utami yang selalu memberikan motivasi dan dukungan agar penulis selalu semangat mengerjakan skripsi dan akhirnyaa selesai jugaa.. thank sist!
8. Leonard Emanuel yang selalu sabar menemani dalam suka duka ketika mengerjakan skripsi ini. Makasih sayang..
9. Kakak dan adek sepupu : Bhebe, Ica, Oboy, Nyenyen, ka’Jhon, ka’Cheko yang telah memberikan support moral. Thank all of you !
10. Sahabat-sahabatku : Wiwin, Nino, Lia, Tanti, mba’Linda, Joe, ka’Mula, Steven, Cindy, Rendi, Okky, Steve, ka’Donny, ka’Kris, ci’Nita, ci’Vinda, ka’Rey, mba’Anna, O’of, Didis, Ria dan Kiki. Terima kasih banyak telah menjadi teman terbaik dan memberikan dukungan tiada henti bagi penulis.
11. Ka’Yofi Setyo Tanoyo yang telah berbaik hati membimbing penulis dalam penulisan skripsi serta membantu dalam penyebaran skala penelitian di dealer-dealer Honda di Yogyakarta.
xii
13. Semua karyawan beserta staff Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma (mas’Gandung, mba’Nanik, mas’Doni, mas’Muji dan pak’Gie terima kasih banyak atas bantuannya).
14. Teman-teman almamater Psikologi angkatan 2004 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih untuk masa-masa kebersamaan yang telah dilalui di Fakultas Psikologi Sanata Dharma.
15. Seluruh sales counter dealer Honda di Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner. Terima kasih banyak telah membantu proses pengerjaan skripsi penulis.
16. GBI Generasi Baru, ex.zona 1 dan cell WOG (Ellen, bg’Hendrik, Yanto, Bebi, Dina, Lamtua, Nita, Irna, Santi, Maria). Terima kasih atas pengajaran dan kasih yang luar biasa selama ini bagi penulis. WOG... exellent exellent exellent !
Penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritik terhadap kekurangan ataupun kesalahan pada karya tulis ini sehingga di masa yang akan datang penulis dapat menulis dengan lebih baik.
Yogyakarta, 23 September 2011
xiii
DAFTAR ISI
Hal
HALAMAN JUDUL ... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii
HALAMAN PENGESAHAN ... iii
HALAMAN MOTTO ... iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ... v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... vi
ABSTRAK ... vii
ABSTRACT ... viii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ... ix
KATA PENGANTAR ... x
DAFTAR ISI ... xiii
DAFTAR TABEL ... xvi
DAFTAR GAMBAR ... xvii
DAFTAR LAMPIRAN ... xviii
BAB I PENDAHULUAN ... 1
A. . Latar Belakang Masalah ... 1
B. . Rumusan Masalah ... 7
C. . Tujuan Penelitian ... 8
D. . Manfaat Penelitian ... 8
xiv
2. . Manfaat Praktis ... 8
BAB II LANDASAN TEORI ... 9
A. . Motivasi Kerja ... 9
1. . Definisi Motivasi Kerja ... 9
2. . Teori Self-Determination Theory ... 11
3. . Aspek-aspek Self-Determination Theory ... 15
4. . Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja ... 18
B. . Bullying di Tempat Kerja ... 21
1. . Definisi Bullying di Tempat kerja ... 21
2. Bentuk-bentuk Bullying di Tempat Kerja ... 24
3. . Aspek-aspek Bullying di Tempat Kerja ... 31
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bullying di Tempat Kerja ... 33
5. . Dampak Bullying di Tempat Kerja ... 40
C. Dinamika Hubungan antara Bullying di Tempat Kerja dan Motivasi Kerja ... 42
D. . Hipotesis Penelitian ... 47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 49
A.Jenis Penelitian ... 49
B. Variabel Penelitian ... 49
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian ... 49
D.Subjek Penelitian ... 52
xv
F. .. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur ... 55
1. . Validitas ... 55
2. . Seleksi Aitem... 55
3. . Reliabilitas ... 57
G. . Metode Analisis Data ... 58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 59
A. . Pelaksanaan Penelitian ... 59
B. . Deskripsi Subjek ... 59
C. Deskripsi Data Penelitian ... 60
D. . Analisis Data ... 61
1. Uji Normalitas ... 61
2. Uji Linearitas ... 62
3. Uji Hipotesis ... 63
E. .. Pembahasan... 64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 68
A.Kesimpulan ... 68
B. Saran ... 68
DAFTAR PUSTAKA ... 69
xvi
DAFTAR TABEL
Hal.
Tabel 2.1 Faktor yang mempengaruhi bullying ... 34
Tabel 3.1 Skala motivasi kerjasebelum diuji coba ... 53
Tabel 3.2 Skala bullying di tempat kerja sebelum diuji coba ... 54
Tabel 3.3 Skala motivasi kerjasetelah uji coba ... 56
Tabel 3.4 Skala motivasi kerja penelitian ... 56
Tabel 3.5 Skala bullying di tempat kerja penelitian ... 57
Tabel 4.1 Karakteristik Subjek ... 59
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif ... 60
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas ... 62
xvii
DAFTAR GAMBAR
Hal.
Gambar 2.1 Motivasi dalam self-determination theory ... 12
Gambar 2.2 Model Hubungan antara variabel Bullying di Tempat Kerja
dengan variabel Motivasi Kerja pada Sales counter ... 48
1 BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perusahaan pada era globalisasi mengalami kesulitan untuk maju lebih
cepat. Persaingan yang ketat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
dinamika konsumen, merupakan faktor eksternal yang menghalangi perusahaan
untuk maju dengan cepat. Untuk mengatasi hal tersebut diatas, perusahaan harus
mempunyai keunggulan bersaing yang dapat diciptakan melalui analisis
terhadap lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan. Namun, yang
lebih penting bagaimana lingkungan internal dapat dikelola dengan baik,
terutama sumber daya manusia dalam perusahaan (Ninawati, 2002).
Salah satu perkembangan industri di Indonesia yang semakin meningkat
belakangan ini yaitu industri otomotif. Hal ini ditandai dengan maraknya
pabrikan dan produsen saling bersaing menciptakan produk-produk unggulan
mereka yang diharapkan mampu menguasai pasar. Munculnya produk-produk
baru di pasaran saat ini membuat pebisnis di bidang kendaraan semakin
tertantang untuk meningkatkan penjualannya. Hal ini dikarenakan semakin
ketatnya persaingan antara dealer-dealer penyedia kendaraan bermotor.
(Bataviase, 2010)
Yogyakarta sebagai ibukota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
merupakan pasar potensial bagi pelaku bisnis sepeda motor. Tingginya minat
dalam industri sepeda motor. Krisna Murti selaku Unit Sales Supervisor PT.
Astra Internasional-Honda area Yogyakarta, Kedu dan Banyumas, mengatakan
penjualan motor Honda jenis matic masih mendominasi penjualan antara lain
motor Honda Beat dengan memberi kontribusi mencapai 50%, Honda Vario
sekitar 40%, dan Honda Scoopy sekitar 20% (Tabloid Otoarea, Juni 2011).
Tingginya permintaan pasar menuntut perusahaan Honda terus
melakukan peningkatkan dalam meningkatkan omzet penjualannya. Dalam hal
ini perusahaan harus memiliki strategi pemasaran yang handal agar dapat
mencapai tujuan yang diinginkan yaitu peningkatan penjualan. Castells (1996)
mengemukakan bahwa daya saing yang tinggi dan kemampuan menciptakan
laba merupakan faktor penentu utama dari inovasi teknologi dan produktivitas
yang tinggi dalam perusahaan. Perusahaan jenis ini hanya dapat diwujudkan jika
didukung oleh knowledge workers (Connoly et al., dalam Jaffar 2000). Horton
(Marpaung, 2000) juga mengungkapkan bahwa organisasi yang sukses adalah
memiliki karyawan yang sukses dalam menjalankan pekerjaannya. Oleh karena
itu organisasi harus dapat menciptakan sumber daya yang memiliki kualitas dan
mutu yang baik.
Menurut Siregar (2006), karyawan dan perusahaan tidak dapat
dipisahkan. Karyawan memegang peran utama dalam menjalankan roda
kehidupan perusahaan. Apabila karyawan memiliki produktifitas dan motivasi
kerja yang tinggi , maka laju roda pun akan berjalan lancar, yang akhirnya akan
menghasilkan kinerja dan pencapaian yang baik bagi perusahaan. Dengan
menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai visi dan
misi yang telah ditetapkan, sehingga karyawan sebagai sumber daya manusia
memiliki kontribusi yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi. Beer, et
al. (1990, hal. 164) juga mengatakan segala macam bentuk peningkatan
produktivitas tidak akan bisa memberikan hasil yang maksimal bila dalam diri
karyawan tidak ada motivasi kerja. Motivasi kerja senantiasa ada dalam diri
karyawan, namun bergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhi
motivasi kerja menjadi tinggi atau sebaliknya menjadi rendah.
Keberhasilan penjualan pada perusahaan Honda tidak lepas dari
kerjasama tim antara perusahaan dan karyawannya. Dalam memasarkan dan
menarik konsumen untuk melakukan pembelian, perusahaan Honda memiliki
strategi penjualan melalui salah satu tenaga pemasar yaitu sales counter.
Perusahaan menempatkan sales counter sebagai bagian front office yaitu ujung
tombak bagi perusahaan dan penentu citra perusahaan. Pada umumnya sales
counter kendaraan bermotor Honda adalah wanita didasarkan persyaratan
lowongan pekerjaan untuk menjadi sales counter beberapa perusahaan atau
dealer Honda pada media cetak dan media elektronik. Pemilihan gender wanita
dikarenakan pembawaan diri yang lebih menarik dan luwes. Sales counter
merupakan konsultan yang bertugas menjual produk barang maupun jasa,
menangani penjualan pada saat customer datang ke kantor serta mencapai target
penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Tingginya tingkat penjualan tidak lepas dari penentuan target penjualan
kepada perusahaan retailer lainnya. Jika dihubungkan dengan sales counter
motor Honda, target penjualan adalah sebuah motivator kerja bagi divisi
marketing di perusahaan retailer. Namun menurut pengakuan beberapa sales
counter melalui wawancara langsung, mereka mengatakan kurang memiliki
motivasi kerja setelah beberapa bulan bekerja pada perusahaan tempat mereka
bekerja dikarenakan terus meningkatnya target penjualan yang harus mereka
capai. Berdasarkan wawancara langsung dengan staff Human Resources
Development pada salah satu dealer sepeda motor Honda di Yogyakarta,
diperoleh informasi bahwa pada setiap bulan terjadi peningkatan target
penjualan. Beliau mengatakan rata-rata penjualan setiap bulan adalah 500 hingga
600 unit sepeda motor di Yogyakarta. Beliau menjelaskan lebih lanjut mengenai
peningkatan target bahwa dalam sebuah perusahaan dealer terdapat 3 hingga 5
sales counter, dengan target penjualan 150 unit sepeda motor masing-masing
dealer setiap bulannya, jika 4 hingga 5 perusahaan dealer saja sudah dapat
mencapai target penjualan. Beliau juga menambahkan bahwa tercapainya target
penjualan menentukan besarnya bonus atau reward yang didapatkan divisi
marketing sehingga terkadang demi mendapatkan bonus yang besar, seorang
kepala cabang dapat menaikan target penjualan bagi bawahannya.
Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa desain organisasi yang bersifat
top down atau memiliki hierarki yang cukup rigid sangat mempengaruhi
perilaku bullying untuk muncul. Menurut Hoel dan Cooper (2002),
permasalahan yang terjadi di perusahaan Honda dapat dikategorikan sebagai
ditentukan. Hal tersebut berkaitan dengan kepemilikan power dalam organisasi
yang berjenjang, sehingga besar kecenderungan seseorang melakukan
penyalahgunaan wewenang untuk mewujudkan tujuan mereka (Kidwell dan
Martin, 2005). Liefooghe dan Davey (2001) menyatakan organisasi dengan
desain hierarki atau top-down management sangat tergantung kepada kepatuhan,
loyalitas pada organisasi, serta alasan yang langsung mengarahkan perilaku
karyawan pada saat melakukan tugasnya. Kepemilikan power yang dimiliki oleh
atasan sangat kuat, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan power,
yang berakibat pada munculnya perilaku bullying.
Menurut sebuah studi yang dilakukan Workplace Bullying Institute
(2000) di Bellingham, Washington, 16 persen pekerja di Amerika Serikat
ditindas di kantor. Studi itu diterbitkan tahun 2000 lalu atas 1100 pekerja
menunjukkan kasus penindasan di tempat kerja jumlahnya lebih tinggi
ketimbang pelecehan seksual maupun diskriminasi rasial. Sementara itu,
menurut penelitian yang diterbitkan Universitas Negeri Arizona dan Universitas
New Mexico, pekerja yang ditindas umumnya merasa suasana kantor tak
ubahnya sebuah medan pertempuran atau tengah bermimpi buruk (Tabloid
Bintang Indonesia No.816/XVI, Desember 2006).
Manufacturing Science Finance (1995) menjabarkan beberapa tindak
perilaku bullying berupa pemaksaan kehendak, melakukan tekanan,
penyalahgunaan wewenang, pengintimidasian, perilaku usil, penghinaan dengan
menggunakan kekuasaan secara tidak lazim yang menyebabkan korban merasa
diri yang berakibat menimbulkan stres. Bentuk kekerasan psikologis ini
membawa konsekuensi serius, seperti tingginya angka depresi di antara
karyawan dan stres kerja yang tinggi menyebabkan penurunan produktifitas
kerja pada karyawan.
Menurut Rayner, Hoel dan Cooper (2002), serta Dumiane (1993),
beragam motif tindak perilaku bullying banyak dilakukan oleh pimpinan
terhadap karyawan. Meskipun ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa
bullying memiliki dampak positif bagi organisasi (Dumaine, 1993; Vega dan
Debra, 2003). Sejalan dengan hal tersebut, Archer (1999) menambahkan bahwa
perilaku bullying juga berfungsi sebagai motivator dalam melakukan suatu
tindakan, dalam penelitiannya menunjukkan hubungan yang positif antara
bullying dengan motivasi. Namun sebagian besar peneliti dan literatur
menunjukkan bahwa bullying memiliki dampak negatif, baik pada individu
maupun organisasi. Hal tersebut juga diutarakan Jimenez, Munoz, dan Gammara
(2007) bahwa bullying memberikan pengaruh yang negatif, seperti hubungan
antara bullying dengan kepuasan kerja memiliki (r = -0.24 hingga -0.44),
bullying dengan psychologycal health (r = 0.31 hingga -0.52), dan bullying
dengan psychosomatic complains (r= 0.32). Hanya saja belum diketahui secara
pasti apakah dampak negatif bullying mampu mempengaruhi motivasi kerja
pada lingkungan dan budaya yang berbeda seperti di Indonesia.
Berdasarkan riset yang dilakukan sebelumnya, peneliti tertarik
melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan bullying terhadap motivasi
penjualan motor Honda pada tahun 2009, merk Honda menduduki posisi teratas
(tempointeraktif.com). Jika dilihat dari struktur organisasi dalam perusahaan
Astra Honda Motor, pimpinan perusahaan secara keseluruhan mengontrol
seluruh kegiatan perusahaan, kemudian kepala cabang dan supervisor yang
memiliki wewenang lebih tinggi daripada sales counter, misalnya memberi
perintah, pelimpahan tugas, menggunakan otoritas, dan lainnya, sedangkan sales
counter hanya bertugas untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh level
diatasnya atau pimpinan setempat. Selain persyaratan sales counter dalam suatu
perusahaan adalah wanita, korban penindasan di kantor umumnya terjadi pada
wanita. Menurut studi Workplace Bullying Institute (2000), 80 persen wanita
menjadi korban penindasan di kantor.
Indonesian Anti Bullying (2010) menyatakan bahwa karyawan yang tidak
memiliki wewenang cenderung menjadi korban bullying dari pimpinan ataupun
lingkungannya. Adanya rasa ketidakberdayaan dan emosional negatif dalam
perusahaan akan berdampak kegagalan memberikan kontribusi kemampuan
kerja terbaik, tidak memberikan ide ekstra atau feedback dalam menghadapi
masalah-masalah organisasi dimana dalam hal ini bullying terjadi ketika adanya
ketidakseimbangan kekuasaan antara dua orang dalam situasi konflik.
B. Rumusan Masalah
Permasalahan yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah apakah
terdapat hubungan antara bullying di tempat kerja dengan motivasi kerja sales
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan bullying di
tempat kerja dengan motivasi kerja sales counter.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :
1. Manfaat teoritis berupa referensi ilmiah dalam perkembangan ilmu
pengetahuan, khususnya dalam bidang Psikologi Industri dan Organisasi,
dimana hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur untuk
penelitian yang relevan di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis sebagai bahan refleksi dan evaluasi bagi perusahaan dan
karyawan mengenai perilaku bullying yang secara sadar atau tidak sadar dapat
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Motivasi Kerja
1. Definisi Motivasi Kerja
Secara harafiah motivasi berasal dari kata ”movere”, yang berarti
dorongan atau daya bergerak untuk berpindah. Hal tersebut diberikan kepada
individu agar mampu mencapai turjuan tertentu. Sebagai kekuatan
pendorong, motivasi memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai (a) Energi sebagai
penyebab individu melakukan tindakan; (b) Tingkah laku yang langsung ke
arah pencapaian tujuan khusus; dan (c) Menyokong usaha yang telah
dilakukan dalam mencapai tujuan (Steers dan Porter, 1996).
Pengertian motivasi tidak lepas dari motif. Chaplin (2002) dalam
kamus psikologi menerangkan motif adalah (a) Suatu keadaan ketegangan
individu, yang mengembangkan, memelihara dan mengarahkan tingkah laku
menuju pada suatu tujuan atau sasaran; (b) Alasan mendasar individu bagi
tingkah lakunya; (c) Alasan tidak disadari bagi suatu tingkah laku; (d)
Dorongan atau perangsang; (e) Sikap yang menuntun tingkah laku.
Chaplin (2002) menyatakan bahwa motif adalah sesuatu yang
melatarbelakangi individu untuk berbuat mencapai tujuan tertentu, sedangkan
motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan
untuk bekerja. Kuat lemahnya motivasi kerja seorang karyawan menentukan
besar kecilnya prestasi karyawan tersebut (As’ad, 2003). Siagian (1995)
menambahkan motif adalah keadaan kejiwaan yang mendorong,
mengaktifkan atau menggerakkan. Motif kemudian akan mengarahkan serta
menyalurkan perilaku, sikap dan tingkah laku individu demi suatu pencapaian
tujuan, baik tujuan organisasi maupun pribadi. Dari penjelasan tersebut
Siagian (1995) menyimpulkan bahwa dalam motivasi terdapat tiga komponen
yaitu kebutuhan, dorongan, dan tujuan.
Motivasi adalah sesuatu yang dimiliki seseorang untuk bertindak atau
melakukan sesuatu, motivasi bisa digambarkan sebagai tujuan secara
langsung dalam berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu (Hodson, 2001).
Robbins (1996) menjelaskan motivasi sebagai satu proses yang menghasilkan
suatu intensitas, arah dan ketekunan individu dalam usaha untuk mencapai
suatu tujuan. Motivasi umum berkaitan dengan upaya ke arah setiap tujuan,
namun pada penelitian ini difokuskan pada tujuan organisasi agar
mencerminkan minat tunggal dalam perilaku yang berkaitan dengan kerja.
Ketiga unsur kunci dalam definisi motivasi adalah intensitas, tujuan dan
ketekunan.
Intensitas menyangkut seberapa keras seseorang berusaha. Hal
tersebut merupakan unsur yang paling difokuskan dalam pokok bahasan
motivasi. Intensitas yang tinggi akan membawa hasil yang diinginkan,
kecuali jika upaya tersebut diarahkan pada suatu tujuan yang menguntungkan
organisasi, sehingga harus dipertimbangkan kualitas dari upaya dan juga
intensitasnya. Upaya tersebut diusahakan agar mampu mengarah pada
mengukur berapa lama individu dapat mempertahankan usahanya.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka disimpulkan bahwa individu yang
termotivasi tetap bertahan pada pekerjaan cukup lama untuk mencapai tujuan.
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peneliti menarik kesimpulan
bahwa motivasi kerja adalah dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang,
baik yang berasal dari dalam dan dari luar dirinya untuk melakukan suatu
pekerjaan dengan semangat tinggi menggunakan semua kemampuan dan
ketrampilan yang dimiliki individu tersebut.
2. Teori Self-Determination
Teori self-determination merupakan salah satu teori motivasi kerja
yang dikembangkan oleh Ryan dan Deci untuk mengetahui bagaimana sebuah
perilaku itu muncul (Markland, Ryan, Tobin, Rollnick, 2005). Teori ini
dikembangkan dari eksperimen dan investigasi di lapangan tentang efek dari
lingkungan seperti rewards, pujian, atau sesuatu yang secara langsung yang
mempengaruhi motivasi intrinsik (Deci dan Ryan, 1980).
Teori self-determination mengusulkan tiga jenis motivasi yang
berbeda yakni motivasi intrinsik (motivasi yang muncul dari diri), motivasi
ekstrinsik (muncul dari luar diri) dan amotivation (Deci dan Ryan, 1985;
Ryan dan Deci, 2000), seperti yang tertuang dalam gambar 2.1.
Pengelompokkan didasarkan pada apakah dan untuk apa perilaku seseorang
ditentukan, yakni untuk memahami motivasi otonomi (otonomous motivation)
Motivasi intrinsik mengacu pada suatu tugas, dan itu merupakan suatu
hal yang penting, karena suatu kepuasan atau kesenangan akan diperoleh dari
tugas yang dikerjakannya (Deci, Eghrari, Patrick, dan Leone, 1994). Jika
karyawan termotivasi secara intrinsik, ia akan melaksanakan tugas dengan
perilaku tanpa mengharapkan suatu pujian atau tanpa menghiraukan kendala
yang ada di luar dirinya. Sebagai contoh, jika seorang customer service
melayani pelanggan karena ia menyukai dan mendapat kesenangan dari hal
tersebut, maka dikatakan karyawan tersebut termotivasi secara intrinsik.
Gambar 2.1
Motivasi dalam Self-determination Theory
Sumber : Gagne, M. & Deci, E.L. (2005). Self-determinatin Theory and Work Motivation.
Journal of Organizational Behavior. Willey Interscience, 26, 331-362.
Jika seorang karyawan melaksanakan tugas dengan perilaku yang
muncul di luar dirinya dan sifatnya sebagai bantuan, maka karyawan tersebut
termotivasi secara ekstrinsik (Deci dan Ryan, 1985). Walaupun motivasi
ketidakpastian yang ada di luar diri karyawan (Halter, 1978), teori
self-determination mengusulkan hal tersebut sebagai fakta, sepanjang hal itu
merupakan suatu rangkaian dari self-regulation (pengaturan diri). Gagne dan
Deci menyebutkan empat jenis motivasi ekstrinsik dari sudut pandang teori
self-determination, yakni:
1) Pengaturan dari luar diri (external regulation) sama dengan motivasi
ekstrinsik sebagaimana diutarakan pada literatur lama. Motivasi jenis ini
terjadi manakala perilaku diatur oleh beberapa kendala atau
penghargaan/pujian dari luar diri (Deci dan Ryan, 1985). Sebagai contoh,
motivasi akan terjadi pada seorang mahasiswa membaca suatu jurnal,
karena diwajibkan oleh dosen pembimbing tesis mahasiswa tersebut.
2) Introjection Regulation yakni tidak menerima pengaturan dari luar
secara penuh akan tapi sebagian dari diri (Ryan dan Deci, 2000). Sumber
motivasi yang datang dari luar dan dalam diri individu tersebut kemudian
menghasilkan suatu perilaku (Deci dan Ryan, 1991). Diantaranya
beberapa perilaku dilakukan untuk menghindari rasa bersalah atau
adanya rasa ketertarikan pada individu tersebut. Perlu digarisbawahi
internalisasi jenis ini bukan merupakan dari kasus motivasi otonom, hal
ini disebabkan adanya pembatasan internalisasi peristiwa yang terjadi di
luar dirinya. Sebagai contoh, seorang mahasiswa menamatkan
pendidikan untuk membuktikan bahwa dirinya mampu mencapai derajat
yang lebih tinggi dan ini menandakan bahwa ia telah melakukan regulasi
3) Identification Regulation adalah penerimaan yang dilakukan manakala
individu telah dapat menghargai suatu pengaturan atau tujuan suatu
perilaku dan menerima tindakan yang secara pribadi berharga. Walaupun
aktivitas masih dilakukan dengan pertimbangan yang disebabkan oleh
keadaan di luar diri individu tersebut. Namun secara internal diatur dan
ditentukan oleh dirinya (Deci dan Ryan, 1985; Ryan dan Deci, 2000).
Menurut contoh sebelumnya, mahasiswa menamatkan sekolah
disebabkan ia merasa sekolah membantu dalam mempersiapkan karirnya
di masa depan, maka ia telah melakukan identification regulation.
4) Integration Regulation adalah individu menganggap perilaku yang ia
lakukan merupakan bagian dari dirinya, meskipun hal tersebut berasal
dari luar, namun secara keseluruhan ia memiliki kebebasan dan perasaan
penuh terhadap penentuan perilaku yang dilakukannya (Gagne dan Deci,
2005). Sebagai contoh, seorang perawat memiliki tugas melakukan
perawatan kepada pasien untuk menjaga pasien tersebut tetap bersih dan
sehat, munculnya perilaku perawat tersebut karena telah terintegrasi
secara menyeluruh dengan aspek-aspek yang ada dalam pekerjaan dan
kehidupannya, sehingga perilaku menjaga pasien merupakan hal yang
umumnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari perawat tersebut.
Deci dan Ryan (1985) tertantang untuk memahami perilaku manusia
pada jenis motivasi ketiga (mereka menyebutnya amotivation) yang harus
dipertimbangkan. Motivasi jenis ini serupa dengan konsep ketidakberdayaan
terjadi manakala individu tidak tahu dengan pasti antara tindakan yang
mereka lakukan dan hasil yang mereka capai. Pengalaman individu yang
amotivated, mereka merasa tidak punya kompetensi dan tidak adanya
pengendalian diri atas hasil yang akan dicapai atau hasil yang dipikirkan
dalam memotivasi perilaku manusia. Perilaku amotivated sangat kurang
dalam menentukan sesuatu yang seharusnya bisa ditentukannya sendiri.
Individu yang amotivated merasa tidak kompeten dan dengan begitu mereka
merasa tidak akan bisa mengendalikan hasil yang akan dicapainya (Ryan
dan Deci, 2000; Vallerand dan Fortier, 1998). Suatu contoh amotivation
dapat terjadi pada seorang mahasiswa yang telah menamatkan sekolahnya,
akan tetapi dia tidak bisa melihat hubungan antara usaha yang dilakukannya
pada saat kuliah dengan hasil setelah dia menamatkan kuliahnya.
Gagne dan Deci (2005) merujuk pada beberapa kajian literatur yang
telah diungkapkan sebelumnya mengenai teori self-determination
disimpulkan bahwa motivasi intrinsik, identification regulation, integration
regulation (bentuk motivasi ekstrinsik) diberi label motivasi otonomi
(autonomous motivation), sedangkan introjection dan external regulation
dipertimbangkan sebagai kontrol motivasi (control motivation).
3. Aspek-aspek Self-Determination Theory
Grenberg (1996) mengemukakan adanya tiga komponen pokok
motivasi, yaitu : (a) daya, yakni kekuatan atau tenaga dalam diri manusia
pada situasi yang ditargetkan dan bukan pada situasi lain; (c) pemeliharaan,
yakni melibatkan pemeliharaan terhadap beberapa tugas dan secepatnya
mengakhiri tugas lainnya. Teori motivasi kerja memperhatikan tingkah laku
pekerja selama jangka waktu tertentu.
Terdapat empat aspek pokok motivasi kerja dari Robbins (1996) serta
Berry dan Houston (1993), yaitu: (a) penggerak, berkaitan dengan alasan
mengapa individu melakukan suatu pekerjaan; (b) penuntun; berkaitan
dengan alasan mengapa individu mengerjakan jenis pekerjaan tertentu; (c)
ketekunan, berkaitan dengan alasan mengapa individu masih tetap
mengerjakan pekerjaan tersebut; (d) intensitas, berkaitan dengan seberapa
keras individu berusaha.
Porter dan Lawler (1968) mengemukakan dua model motivasi kerja
yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Dalam konsep self-determination
theory, Deci dan Ryan (1985) mengemukakan bahwa motivasi intrinsik
merupakan dorongan yang ada dalam diri individu dan tidak membutuhkan
dukungan dari luar untuk memunculkan perilaku, dalam hal ini seseorang
yang termotivasi secara intrinsik akan mendapatkan kepuasan dan
kenikmatan yang berasal dari dalam diri (dari perilaku yang dilakukan
individu tersebut). Sisi lain motivasi ekstrinsik adalah sebuah dorongan yang
berasal dari luar, sehingga perilaku yang muncul bukan karena keinginan
sendiri (Deci dan Ryan, 1985). Dimensi dari ekstrinsik dan intrinsik memiliki
pengaruh terhadap motivasi yang muncul pada diri karyawan, sehingga
perilaku (Vallerand, 2001). Dalam penelitian ini aspek-aspek yang diambil
merujuk pada teori self-determination, dimana dimensi eksternal memberikan
gambaran tentang perilaku-perilaku yang muncul dipengaruhi oleh
faktor-faktor dari luar, kemudian melalui regulasi tertentu menjadi termotivasi baik
secara otonomi maupun kontrol sehingga perilaku tersebut bisa terlihat dan
diamati dengan seksama melalui penelitian (Gagne dan Deci, 2005).
Menurut pandangan Gagne dan Deci (2005), teori self-determination
memiliki tiga dimensi eksternal, yaitu job content, job contex, dan work
climate, dengan aspek-aspeknya berupa :
(a) Challenge : Tantangan merupakan perangsang kuat bagi manusia
jika dihubungkan dengan pekerjaan. Melalui
tantangan dalam bekerja, seseorang dapat lebih
terdorong untuk menyelesaikan suatu pekerjan.
(b) Choice : adalah cara seseorang mengevaluasi dan memilih
beberapa set pilihan. Jika seseorang dapat memilih
maka pilihan yang diambil adalah pilihan yang terbaik
menurutnya yang akan menimbulkan motivasi positif
dalam menjalankan pilihan tersebut.
(c) Rationale : menggunakan nalar sebagai dasar pemikiran untuk
menentukan hal seperti pendapat, perbuatan,
penilaian, dan sebagainya.
(d) Feedback : informasi tentang hasil pembelajaran yang fungsinya
menerima positif atau negatif feedback, tergantung
bagaimana ia dapat menerima dan menggunakan
sebagai motivasi dalam bekerja.
(e) Work support : Work support dalam pandangan self determination
theory digambarkan sebagai sebuah kesatuan
lingkungan kerja yang memberikan dukungan
terhadap pencapaian sebuah perilaku, dan ini bisa
berupa dukungan terhadap tempat kerja maupun pola
manajemen.
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja
Dalam perkembangannya, para peneliti melihat motivasi kerja dapat
dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor. Hodson (2001) mengutarakan tiga
faktor yang mempengaruhi motivasi kerja :
a. Kebutuhan akan prestasi
Dorongan seseorang untuk sukses dan meraih kesuksesan pekerjaan
dengan efektif dan efisien.
b. Kebutuhan akan kekuatan
Individu yang ingin meningkatkan status maka ia membutuhkan kekuatan
agar dapat mengontrol dirinya sendiri dan orang lain dalam pekerjaannya
c. Kebutuhan akan kerjasama
Hubungan di tempat kerja yang membutuhkan penerimaan dari rekan kerja
Faktor yang mempengaruhi motivasi juga dikemukakan oleh
Sastrohadiwiryo (2003) yang menambahkan bahwa motivasi karyawan
ditentukan oleh perangsang. Perangsang tersebut merupakan penggerak
motivasi kerja sehingga mempengaruhi perilaku karyawan. Sastrohadiwiryo
(2003) mengemukakan unsur-unsur penggerak motivasi karyawan, yaitu:
a. Prestasi kerja (Job Achievement)
Individu yang menginginkan prestasi kerja sebagai suatu kebutuhan
(need) dapat mendorong pencapaian sasaran. Dipboye, Smith, dan
Howell (1994) mengemukakan pendapat Mc Cleland bahwa tingkat need
of achievement (N-Ach) yang telah menjadi naluri kedua merupakan
kunci keberhasilan individu. N-Ach juga dikaitkan dengan sikap positif,
keberanian mengambil resiko dengan perhitungan (calculated
risk/non-gambling) untuk mencapai suatu sasaran.
b. Penghargaan (Recognition)
Penghargaan dan pengakuan (recognation) atas suatu kerja individu
mampu menjadi perangsang yang kuat. Pengakuan atas suatu kinerja
akan memberikan kepuasan batin yang lebih tinggi daripada penghargaan
dalam bentuk materi atau hadiah. Penghargaan atau pengakuan dalam
bentuk piagam atau medali dapat menjadi perangsang yang lebih kuat.
c. Tantangan (Challenge)
Tantangan yang dihadapi merupakan perangsang kuat bagi manusia
untuk mengatasinya. Sasaran tidak menantang atau mudah, tidak mampu
Tantangan demi tantangan biasanya akan menimbulkan kegairahan untuk
mengatasinya.
d. Tanggung Jawab (Responsibility)
Adanya rasa memiliki (self-belonging) akan menimbulkan motivasi
untuk turut bertanggung jawab.
e. Pengembangan (Development)
Pengembangan kemampuan individu baik dari pengalaman kerja atau
kesempatan untuk maju merupakan perangsang yang kuat bagi karyawan
untuk bekerja lebih giat atau bergairah. Apalagi jika pengembangan
perusahaan selalu dikaitkan dengan kinerja atau produktivitas karyawan.
f. Keterlibatan (Involvement)
Rasa ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dapat diwujudkan
dalam bentuk kotak saran bagi karyawan yang dijadikan masukan
manajemen perusahaan.
g. Kesempatan (Opportunity)
Kesempatan untuk maju dalam bentuk jenjang karier yang terbuka, dari
tingkat bawah hingga manajemen puncak merupakan perangsang kuat
B. Bullying di Tempat Kerja
1. Definisi Bullying di Tempat Kerja
Bullying di tempat kerja merupakan bagian dari perilaku menyimpang
organisasi. Telah banyak penelitian yang mengungkap perilaku bullying di
tempat kerja, namun masing-masing peneliti memiliki sudut pandang yang
berbeda, meskipun pada akhirnya mengacu pada jenis perilaku yang kurang
lebih sama. Pernyataan tersebut senada dengan Rayner (1999) yang
menyatakan bahwa belum ada konklusi bersama untuk mendefenisikan
bullying di tempat kerja secara nyata. Hal tersebut diperkuat oleh Gruys
(1999) bahwa untuk memperoleh pemahaman mengenai bentuk perilaku
menyimpang di tempat kerja diperlukan penelitian secara menyeluruh,
mengingat rentang perilaku menyimpang bersifat luas dan mencakup
berbagai macam dimensi. Pada bagian ini, akan diuraikan beberapa definisi
perilaku bullying ditempat kerja diakhiri dengan definisi yang diacu pada
penelitian ini.
Field (1997) dan manufacturing science finance / MSF (1995),
mengemukakan bullying di tempat kerja mengarah pada penyalahgunaan
kekuasaan, namun dalam hal ini bukan berarti faktor superioritas selalu
menjadi pemicu tindak bullying. Field (1997) dan Adams (1992) menemukan
bahwa bullying tidak selalu diikuti oleh kekerasan fisik. Perilaku bullying
dapat berupa intimidasi verbal, seperti merendahkan orang lain atau bersifat
kekanak-kanakan yang sifatnya mengganggu orang lain. Selain itu pegawai
kategori perilaku bullying. Manufacturing Science Finance (1995)
menjabarkan beberapa tindak perilaku bullying berupa pemaksaan kehendak,
melakukan tekanan, penyalahgunaan wewenang, pengintimidasian, perilaku
usil, penghinaan dengan menggunakan kekuasaan secara tidak lazim yang
menyebabkan korban merasa tidak bahagia, tercurangi, terhina, tersinggung
dan merendahkan kepercayaan diri yang berakibat menimbulkan stress.
Bernardi (2001) mendefinisikan bullying sebagai perilaku tidak
senonoh dan tidak bermoral yang ditujukan kepada pegawai lainnya.
Tindakan tersebut meliputi perbuatan sesuka hati tanpa memperdulikan orang
lain, memberikan kritik tajam dan menganggap rendah atau menyudutkan
pegawai lain agar terlihat tidak kompeten. Tidak hanya itu, bullying juga
meliputi perilaku mengkritik segala kegiatan orang lain, perilaku mengancam
kepada seseorang yang bersifat intimidasi, mengejek, dan juga memandang
rendah kemapuan kerja seseorang (Victorian Work Cover Authority, 2001).
Hampir serupa dengan definisi-definisi sebelumnya, Rayner, Hoel dan
Cooper (2002) mengartikan bullying sebagai bentuk perlakuan yang tidak
diinginkan, seperti melakukan tekanan, penghinaan dan pelecehan, baik
ditujukan pada individu ataupun kelompok. Ditambahkan oleh Vega dan
Comer (2003), perilaku menggoda lawan jenis atau sekedar gurauan yang
kotor dan rasisme termasuk dalam pelecehan yang mengarah pada tidak
perilaku bullying. Perilaku tersebut memiliki kecenderungan sifat yang tidak
dapat diprediksi, irasional dan mengarah pada ketidakadilan. Pada akhirnya,
yang secara bertahap membuat pegawai mengalami krisis kepercayaan diri,
gangguan kesehatan dan mental (Rayner, Hoel dan Cooper, 2002).
Namie (2003) mengaitkan definisi bullying dengan intensitasnya,
yaitu perilaku kekerasan yang berulang kali ditujukan dengan sengaja kepada
individu dan menyebabkan penderitaan, baik secara fisik maupun ekonomi.
Dalam proses bisnis, perilaku tersebut terkadang juga melibatkan kontrol dari
pelaku bullying yang mengarah pada sikap merendahkan kekuasaan individu
lainnya. Perilaku yang muncul dapat berupa penghinaan, pemaksaan
kehendak, tekanan atau intervensi lain yang dapat menyebabkan performa
kerja atau lingkungan kerja menjadi tidak nyaman (Einarsen, 1999).
Meskipun terjadi perlawanan, implementasi dilapangan menunjukkan
bullying secara sengaja tetap dilakukan bahkan berulangkali.
Bullying dalam lingkungan kerja memiliki kecenderungan melukai
dan mengandung unsur kesengajaan, baik terhadap teman sejawat dan juga
level dibawahnya. Bullying juga didefinisikan sebagai bentuk
penyalahgunaan kekuasaan (Smith dan Sharp, 1994). Hal yang menarik
adalah fakta yang menunjukkan bahwa bullying di tempat kerja secara sadar
dilakukan oleh orang dewasa yang notabene mengerti akan akibat
perilakunya (Vega dan Comer, 2003).
Dari sebagian besar definisi yang telah diutarakan, ada benang merah
didalamnya yaitu bullying di tempat kerja memiliki bentuk perilaku seperti
pemaksaan kehendak, melakukan tekanan, penyalahgunaan wewenang,
yang dianggap lemah secara sistematik dan berulang. Bullying bukan
merupakan aksi tunggal yang kemudian hilang, perilaku ini dilakukan untuk
meraih tujuan yang biasanya dilakukan secara agresif pada lingkungan kerja
(Randall, 1997). Chazan (1989) menemukan dalam penelitiannya bahwa
adanya dorongan pada seseorang yang akan melakukan bullying untuk
memilih targetnya.
2. Bentuk-bentuk Bullying di tempat kerja.
Beberapa penelitian telah menjabarkan bentuk-bentuk perilaku
bullying pada tempat kerja. Randall (1997) membedakan bullying kedalam
dua jenis. Pertama, bullying yang tidak bertahan lama dalam organisasi
karena dinilai sangat merugikan dan menghambat kinerja. Korban dengan
cepat mengetahui mereka telah menjadi sasaran agresivitas, sehingga perilaku
tersebut hilang dengan sendirinya. Kedua, bullying yang berhasil dan
bertahan lama karena dinilai mampu memberikan kontribusi terhadap
perubahan perilaku karyawan, bahkan hingga dinilai sebagai karyawan
teladan.
Hoel dan Cooper (2001), mengemukakan sebagian besar perilaku
bullying dapat dimasukkan dalam dua kategori umum, yaitu personal-related
bullying dan work-related bullying.
Kategori pertama adalah personal-related, dengan manifestasi di lapangan
a. Ignoring / excluding / silent treatment / isolating.
Perilaku yang dilakukan berupa pengacuhan, tidak mengikutsertakan
korban dalam kegiatan, tutup mulut terhadap korban, serta mengucilkan
korban dari kelompoknya.
b. Malicious rumours or gossip.
Menyebarkan kata-kata tak sedap tentang korban dan menyebarkan rumor
yang tidak benar tentang kehidupan korban.
c. Belittling remarks / undermining integrity / lies told about you / sense of
judjement.
Memberikan komentar yang tidak mengenakkan, merendahkan integritas,
mengutarakan sesuatu yang tidak benar, dan memberikan penilaian yang
tidak objektif terhadap korban.
d. Questioned / opinions marginalized.
Mempertanyakan atau mengesampingkan opini yang dikemukakan oleh
korban.
e. Public humuliation (making someone look stupid)
Mempermalukan korban di depan umum, misalnya dengan membuat
korban tampak lebih bodoh dari pelaku bullying dan menganggap dirinya
lebih berkualitas daripada korban.
f. Ridiculing Dajk/ insulting / teasing / jokes / ‘funny suprises’ / sarcasm.
Membodohi, mencela, meledek, menertawakan, atau membuat kejutan
g. Shouted or yelled at / ‘ Bawling out’.
Berbicara dengan suara yang keras dan membantak terhadap korban, serta
memanggil nama tanpa rasa hormat.
h. Threats of violence (or threats in general).
Mengancam korban dengan menggunakan kekerasan ataupun secara
verbal.
i. Insulting comments made about your private life.
Memberikan komentar yang menghina kehidupan pribadi korban.
j. Physical attacts.
Melakukan kontak fisik yang bertendensi untuk menyerang.
k. Attacking person beliefs, attitudes, lifestyle / appearance / devaluing with
ref to gender / accusations of being mentally disturbed.
Menyerang kepercayaan, sikap, dan gaya hidup seseorang dengan maksud
untuk merusak danmenganggu kesehatan mental seseorang.
l. Persistent critism (often in front of others).
Memberikan kritik yang selalu merendahkan dan mengurangkan
kemampuan seseorang dan seringkali dilakkukan di depan yang lainnya.
m.Using obscene / offensive language / gestures/ material.
Menggunakan bahasa, bahasa tubuh, dan barang yang tidak selayaknya
n. Ganging up colleagues/ client encouraged to criticise you or spy on you /
witch.
Merusak hubungan dengan teman dengan cara memata-matai korban
ataupun memberikan keterangan yang tidak benar tentang korban.
o. Hunt / dirty tricks campaign/ singled out.
Memburu korban atau melakukan tipu daya yang ditujukan secara personal
kepada korban.
p. Intimidation / acting in condescending or superior manner intruding on
privacy (spying, stalking, harassed by calls etc when on leave / weekends).
Melakukan intimidasi dalam kehidupan pribadi yang mengarah kepada
penyalahgunaan kekuasaan termasuk memata-matai, berteriak dan
kekerasan ketika memanggil korban.
q. Sexual approaches /offers (unwanted) or unwanted physical contact.
Pendekatan yang bertujuan seksual dan kontak fisik yang tidak diinginkan
yang mengarah pada tindakan seksual.
r. Verbal abuse
Kekerasan verbal yang ditujukan kepada korban dalam kehidupan
sehari-hari.
s. Innacurate accusation.
Dengan sengaja melakukan tuduhan tanpa ada bukti-bukti dan fakta yang
mendukung prasangka pelaku bullying.
t. Insinuative glances / gestures / dirty looks.
u. Tampering with personal effect.
Melakukan tindakan yang memberikan kerugian korban, sepeti mencuri
atau merusak barang-barang.
v. Encouraged to fell guilty.
Memberikan nasihat dan perintah sehingga korban merasa sangat bersalah
terhadap perilaku yang telah dilakukan.
Bentuk kategori yang kedua adalah work-related, dengan manifestasi di
lapangan sebagai berikut :
a. Giving unachieveable tasks / impossible deadline / overloading / demands
/ ‘setting up to fail’ / unmanageable workloads.
Korban mendapatkan tugas yang tidak mungkin diselesaikan atau tenggat
waktu pengerjaan yang tidak masuk akal, memberikan beban kerja yang
berlebihan dan dengan sengaja membuat korban untuk gagal, serta
memberikan pekerjaan yang tidak mungkin terselesaikan dengan baik.
b. Meaningless tasks / unpleasant jobs / belittling person ability /
undermined.
Memberikan tugas yang tidak menantang, pekerjaan yang kurang
menyenangkan, serta merendahkan kemampuan korban.
c. Witholding information deliberately / info goes missing / concealing
information / failing to return calls / failing to pass on messages.
Dengan sengaja menahan informasi yang seharusnya diberikan dalam
d. Undervaluing contribution / no credit where due / taking credit for work
that is not their own.
Tidak menganggap kontribusi korban dalam penyelesaian tugas, serta
mengambil keuntungan dari orang lain dalam penyelesaian tugas.
e. Constant criticism.
Memberikan kritik yang tidak membangun terhadap pekerjaan yang
dilakukan korban.
f. Under work / working below competence / removing responsibility /
demotion.
Memberikan pekerjaan di bawah kompetensi yang dimiliki korban dan
mengambil tanggung jawab milik korban untuk pelaku bullying.
g. Unreasonable / inappropriate monitoring.
Pengawasan terhadap pekerjaan yang terlalu berlebihan dan cenderung
tidak masuk akal.
h. Offensive administrative penal sanction e. g., denying leave.
Memberikan sangsi yang sangat memberatkan kepada korban seperti tidak
boleh cuti pergi, cuti sakit dll.
i. Exclude / isolate / views ignored.
Tidak dianggap dalam sebagai bagian dalam kelompok; pendapat dan
pandangannya tidak dihiraukan.
j. Changing goalposts / targets.
Mengganti tujuan dan target secara sepihak dan tidak menghiraukan
k. Not providing enough training / resources.
Korban tidak mendapatkan training, dan pelatihan, serta sumber daya yang
cukup dalam pelaksanaan pekerjaan.
l. Reducing opportunities for expression / interupting when speaking.
Mengurangi kesempatan korban untuk mengungkapkan pendapat atau
melakukan pemotongan pada saat korban berbicara.
m. Negative attact on person for no reason / sabotage.
Dengan sengaja melakukan pembajakan terhadap hasil kerja korban
dengan kekerasan.
n. Making threats / hints about job security.
Membuat ancaman yang berhubungan dengan rasa aman dalam bekerja.
o. No support from manager.
Korban tidak mendapat tanggapan dan dukungan dari atasan dalam
melakukan aktivitas yang berhubungan dengan penyelesaian tugas.
p. Abuse / threats.
Kekerasan dan ancaman pada saat bekerja.
q. Judging wrongly.
Memberikan penilaian yang salah tentang pekerjaan yang dilakukan oleh
korban.
r. Lack of clarity re-Role.
s. Not trusting.
Tidak percaya dalam melakukan sesuatu yang berhubungan dengan
pekerjaan.
Sejalan dengan hal tersebut, Manufacturing Science Finance (1995)
menambahkan bentuk dari bullying yang kerap muncul dan terjadi adalah
sebagai berikut : (a) Memberikan tugas dengan deadline yang tidak masuk
akal; (b) Dengan tiba-tiba mengubah tanggungjawab seseorang terhadap area
permasalahannya, dan memberikan beberapa tugas yang harus dilakukan
dengan segera; (c) Mengacuhkan serta membuat menjadi terisolasi pada saat
berbicara; (d) Menunda informasi yang seharusnya diberikan atau
didelegasikan dengan seksama; (e) Membuat gosip yang tak sedap dan
cenderung merugikan; (f) Kritik yang membunuh dan menghukum.
3. Aspek-aspek Bullying di Tempat Kerja
Beberapa peneliti memberikan gambaran dan konsep beragam
mengenai aspek-aspek perilaku bullying di tempat kerja, yang dapat
digunakan sebagai dasar pembuatan item-item pengukuran perilaku tersebut.
Leyman (1990b) mengemukakan ada lima aspek dalam perilaku bullying di
tempat kerja yaitu (a) Social isolation; (b) Frequent Task change; (c)
Violence or threats of violence; (d) Attack on person Integrity; dan (e) Direct
or indirect criticism. Lebih lanjut Neidl (1995) menunjukkan empat aspek
kerja yaitu (a) Personal harrasment behaviors; (b) Social isolation; (c)
Work-related measures; dan (d) Physical violence.
Einarsen dan Hoel (2001) menekankan ada tiga aspek penting dari
perilaku bullying di tempat kerja yaitu (a) Work-related bullying; (b)
Personal-related bullying; dan (c) Physical intimidating. Berdasarkan tiga hal
tersebut, Einarsen dan Hoel (2001) mengembangkan alat ukur perilaku
bullying di tempat kerja dengan nama Negative Acts Questionnaire (NAQ).
Alat ukur tersebut terbukti paling sering digunakan oleh para peneliti untuk
melakukan pengukuran terhadap perilaku bullying di tempat kerja dan telah
terbukti teruji di beberapa negara dan bersifat cross-cultural (Jimenez,
Munoz, Gammara, 2007). Penggunaan skala Negative Acts Questionnaire
dapat digunakan pada penelitian yang berhubungan dengan kesehatan mental
karyawan, psychosocial lingkungan kerja dan kepemimpinan sebuah
organisasi (Einarsen, Hoel, Notelaers, 2009).
Dalam penelitian ini akan menggunakan alat ukur Negative Acts
Questionnaire versi Jepang yang telah dikembangkan oleh Takaki (2009).
Bullying di tempat kerja akan diukur berdasar nilai total item-item dari skala
bullying di tempat kerja yang terdiri dari tiga aspek yaitu (a) Personal-related
bullying yaitu intimidasi yang mengarah pada kehidupan pribadi individu;
(b) Work-related bullying yaitu intimidasi yang menyangkut pekerjaan
individu; dan (c) Sexual Harassment yaitu intimidasi yang mengarah pada
4. Faktor yang Mempengaruhi Bullying di Tempat Kerja.
Banyak penelitian yang telah mengupas faktor-faktor yang terkait
dengan perilaku bullying di tempat kerja. Beswick, Palferman, Gore (2006)
mengemukakan hasil penelitian Hoel, Salin, Neuman, Baron, Zapf dan
Einarsen yang menyatakan bahwa terdapat karakter individu (individual),
interaksi sosial (social interaction) dan lingkungan kerja (organizational)
yang mempengaruhi bullying, seperti yang tertuang dalam tabel 2.2 .
Sejalan dengan hal tersebut, Mantel (1994) mengemukakan
karakteristik individu yang potensial akan melakukan bullying, merujuk pada
sikap dan perilaku individual : (a) Menunjukkan ketidakpedulian terhadap
lingkungan kerja karena merasa tidak dianggap dan tidak diperlakukan adil;
(b) Kurang mampu bersosialisasi, sehingga rendah dukungan sosial; (c)
menunjukkan harga diri yang rendah; (d) Sulit mendapat bantuan orang lain;
(e) Memiliki ketertarikan terhadap senjata atau perangkat kemiliteran; (f)
Sulit untuk melakukan pengelolaan emosi; (g) Memiliki sejarah mengancam
dan berperilaku agresif kepada supervisor dan karyawan lainnya; (h)
Kehidupan keluarga yang kurang harmonis; (i) Menimbulkan rasa tidak
nyaman karyawan lain; (j) argumen sering bertolak belakang dengan
karyawan-karyawan lain; (k) Memiliki cacat fisik ataupun emosi (atau
bahkan keduanya) dan menolak untuk melakukan treatment; (l) Menunjukkan
stress yang tinggi dalam melakukan pekerjaan; (m) Laki-laki usia 30-40
sering berubah; (o) Memiliki sejarah penggunaan obat dan alkohol; (p) Harpur Hill, Buston, Derbyshire, SK 179JN. Health and Safety Laboratory. Hal.19.
Randall (1997) menerangkan bahwa pelaku bullying akan memilih
korban mereka dan alasan umum yang mendasari biasanya adalah
karakteristik perilaku korban sesuai kriteria, seperti yang ditemukan oleh
Aquino dan Lamertz (2004) dan Smith (2003). Berikut ini adalah kriteria
seseorang yang kemungkinan besar akan menjadi korban bullying : (a)
Self-esteem rendah; (b) Kemampuan menyelesaikan tugas rendah; (c)
memiliki banyak teman, terutama teman dengan kekuasaan (power) yang
tinggi; (f) Penurut dan patuh; (g) Tidak mandiri dan cenderung tertutup.
Kidwell dan Martin (2005) menyebutkan bahwa faktor situasional dan
organisasional yang mengarah pada munculnya perilaku bullying mencakup
desain organisasi dan kondisi pekerjaan, tekanan untuk mencapai suatu tujuan
atau target, sistem kontrol dan imbalan organisasi, serta budaya organisasi.
Desain organisasi yang bersifat top down atau memiliki hierarki yang
cukup rigid sangat mempengaruhi perilaku bullying untuk muncul. Hal
tersebut berkaitan dengan kepemilikan power dalam organisasi akan
berjenjang, sehingga besar kecenderungan seseorang melakukan
penyalahgunaan wewenang untuk mewujudkan tujuan mereka (Kidwell dan
Martin, 2005). Liefooghe dan Davey (2001) menyatakan organisasi dengan
desain hierarki atau top-down management, sangat tergantung kepada
kepatuhan, loyalitas pada organisasi, serta alasan yang langsung
mengarahkan perilaku karyawan pada saat melakukan tugasnya. Kepemilikan
power yang dimiliki oleh atasan sangat kuat, sehingga memungkinkan
terjadinya penyalahgunaan power, yang berakibat pada munculnya perilaku
bullying.
Sistem imbalan dalam organisasi mempunyai fungsi utama untuk
memotivasi pegawai, namun juga memiliki konsekuensi terhadap munculnya
perilaku bullying di tempat kerja. Sistem imbalan yang berdasarkan prestasi
kerja akan mendorong pegawai untuk memiliki target tertentu agar gaji yang
tekanan bagi pegawai untuk dapat mencapai target atau tujuan tertentu.
Dalam usaha pencapaian tersebut, motivasi untuk bekerja dapat meningkat,
namun begitu pula kecenderungan untuk berperilaku menyimpang. Bila
individu mencapai target, maka dia akan mengalami kepuasan. Namun bila
dia gagal mencapai target maka dia akan mengalami ketidakpuasan. Reaksi
yang bisa muncul adalah mengusahakan pencapaian target dengan segala
cara, termasuk melakukan bullying atau mengaku telah mencapai target
meskipun sebetulnya dia tidak berhasil (Kidwel dan Martin, 2005).
Leafooghe dan Davey (2001) menjelaskan beberapa faktor yang
menyebabkan organizational bullying atau institutional bullying; salah
satunya adalah adanya sikap pengawasan yang terlalu ketat terhadap perilaku
kerja pegawai. Dalam hal ini, sistem kontrol yang terlalu ketat mampu
menyebabkan perilaku bullying muncul. Ditegaskan Kidwel dan Martin
(2005) bahwa tekanan untuk mencapai tujuan dan target dalam organisasi,
memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam memunculkan perilaku
bullying. Berkaitan dengan keinginan organisasi untuk mewujudkan tujuan
yang telah dibentuk dengan segala cara, kemudian menjadikan lingkungan
kerja menjadi hyper-competitive stress, menjadikan lingkungan kerja lahan
subur sebagai munculnya konflik dan perilaku bullying (Heames dan Harvey,
2006).
HAS (2002) mengemukakan bahwa perubahan dalam organisasi
memberikan hubungan pada munculnya perilaku bullying di tempat kerja dan
tersebut adalah pergantian manager, kepemilikan perusahaan/organisasi,
reorganisasi perusahaan dan penambahan teknologi baru. Namun demikian,
regeneralisasi akan hal tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan seksama
karena setiap peneliti melihat bullying dari sudut pandang yang berbeda
(Rayner, 1997).
Baron dan Neuman (1996) menambahkan, bahwa perbedaan
perubahan dalam organisasi dapat mempengaruhi kemarahan, ketegangan
(terutama meningkat saat di depan monitor), persepsi ketidakadilan (terutama
pada saat ada pemotongan gaji), perilaku negatif (berkaitan dengan kondisi
fisik yang kurang nyaman), serta frustasi. Palferman, Beswick, Gore (2006)
mengemukakan terdapat empat faktor lain dalam organisasi yang memicu
perilaku bullying untuk muncul, diantaranya work business, kontrak kerja,
leadership, proseedur keadilan dan pengawasan.
Size business, diduga juga memberikan sumbangsih terhadap
munculnya bullying di tempat kerja, namun demikian belum ada bukti nyata
sebagai penguat hal tersebut. HAS (2002) percaya bahwa pegawai baru,
sementara, kontrak, merupakan sasaran empuk sebagai korban perilaku
bullying. Pada lingkup bisnis yang besar dan global, maka kemungkinan
besar perilaku tersebut tidak terlihat dan justru tidak tumbuh di sana.
Einarsen, Hoel, Zapt, dan Cooper (2003) dalam penelitiannya
menemukan bahwa pegawai pada kontrak yang berbeda akan mengalami
intensitas bullying yang berbeda. Sebagai contoh, pekerja part-time akan
tetap. Knorz dan Zapt (1996) menambahkan bahwa hal tersebut terjadi karena
pegawai part-time tidak memiliki banyak waktu untuk bersosialisasi dan
melakuakan resolusi konflik, sehingga mengakibatkan tidak memiliki
hubungan sosial yang terbuka atau bahkan cenderung terisolasi. Hanya saja,
tidak semua peneliti sejalan dengan hal tersebut. Hoel dan Cooper (20002)
menemukan sebaliknya bahwa pegawai dengan kontrak full-timer lebih
dipilih sebagai korban bullying karena pegawai part-time tidak memiliki
interaksi sosial yang banyak, sehingga mereka tidak dianggap sebagai
ancaman dalam melanggengkan dominasi atau kontrol terhadap
sumber-sumber yang ada.
Gaya kepemimpinan dalam organisasi memiliki pengaruh terhadap
munculnya perilaku bullying. Gaya kepemimpinan autocratic tidak
memberikan kesempatan pada bawahan untuk ikut dalam penyelesaian
konflik dan hal tersebut merujuk kepada munculnya perilaku bullying
(O’moore, Seyne, McGuire, dan Smith, 1998). Hoel dan Cooper (2000)
menjelaskan lebih lanjut adanya hubungan antara bullying dengan gaya
manajemen seperti autocratic, laissez-faire, non-contingen, dan divisive.
Grenberg dan Barling (1998) menemukan dua faktor dalam
lingkungan kerja yang mampu menjadi prediksi munculnya perilaku agresi
melawan atasan. Pertama, ketidakmampuan untuk mempersepsi prosedur
keadilan dengan cara pengawasan terhadap pegawai yang mengarah pada
tindak bullying. Faktor kedua adalah konsumsi alkohol serta sejarah perilaku