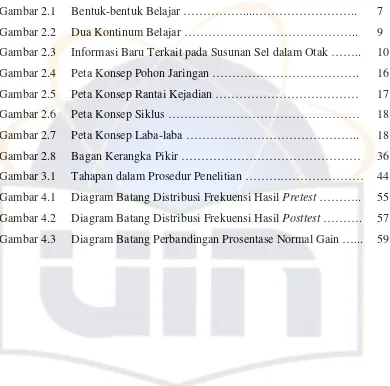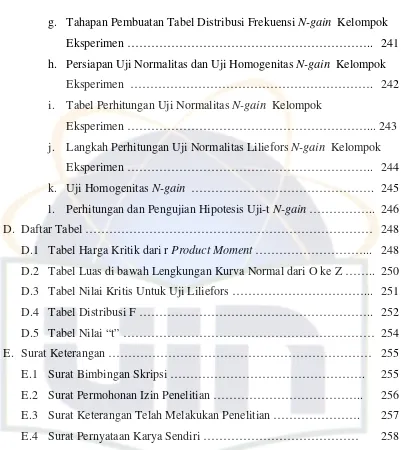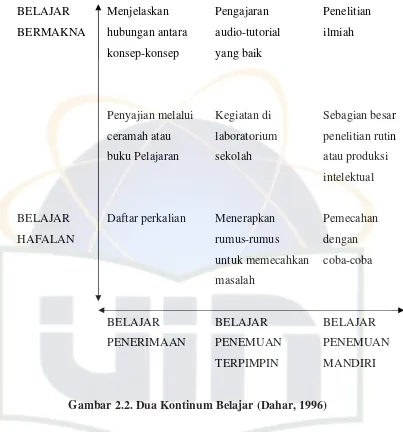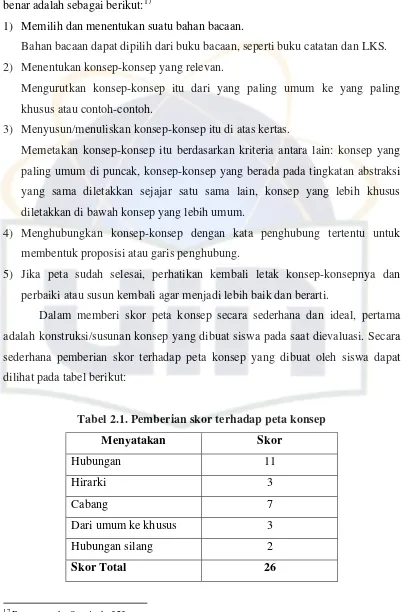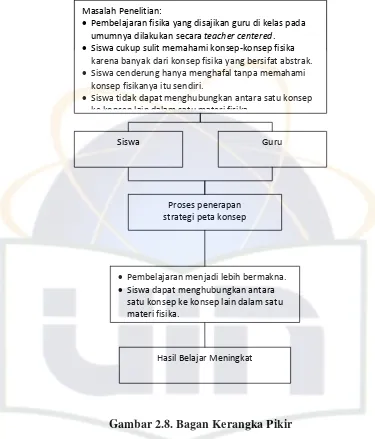SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Disusun Oleh:
ARI NURHAYATI
105016300573
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQASAH
Skripsi yang berjudul “Pengaruh Strategi Peta Konsep (Concept Mapping) Terhadap
Hasil Belajar Fisika Siswa, Studi Quasi Eksperimen di MTs Al-Mukhsin Cibinong”,
disusun oleh Ari Nurhayati, NIM. 105016300573, diajukan kepada Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan telah dinyatakan lulus
dalam Ujian Munaqasah pada tanggal 12 Agustus 2010 dihadapan dewan penguji. Oleh
karena itu, penulis berhak memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada bidang
Pendidikan Fisika.
Jakarta, 12 Agustus 2010
Panitia Ujian Munaqasah
Tanggal Tanda Tangan
Ketua Panitia (Ketua Jurusan Pendidikan IPA)
Baiq Hana Susanti, M.Sc --- …………...
NIP. 1970 0209 200003 2 001
Sekretaris (Sekretaris Jurusan Pendidikan IPA)
Nengsih Juanengsih, M. Pd --- …………...
NIP. 1979 0510 2006 0420
Penguji I
Ir. Mahmud M. Siregar, M.Si --- …………...
NIP. 1954 0310 1988 031001
Penguji II
Erina Hertanti, M.Si --- …………...
NIP. 1972 0419 199903 2 2002
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A
Natural Science Education, Faculty of Tarbiya’ and Teacher Training, State Islamic University (of UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
The aims of this research was to determine the influence of concept mapping strategy to student’s physics achievement. This research has been done at MTs Al-Mukhsin Cibinong-Bogor, on Januari 2010. The method in this research is quasi-experiment. We used Cluster Sampling to take sample in this research. The sample divided into experiment and control classes. Experiment class is Instrument is used multiple choice test (0-1 score), with 28 question and 4 alternative answers. The result of this research are tested through a statistical tes of “t”. Based on calculations obtained for tcount value was 2.79 greater than 2.00 at ttable level α = 0.05 of significance. It can be concluded that Ha stating that there is influence between concept mapping strategy to student’s physics achievement. It means that alternative hypothesis (Ha), which told that there are an influence between concept mapping strategy to the student physics achievement, has been accepted.
ABSTRAK
Ari Nurhayati, “Pengaruh Strategi Peta Konsep Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa”. Skripsi, Program Studi Pendidikan Fisika, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi peta konsep terhadap hasil belajar fisika siswa. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Januari 2010 di MTs Al-Mukhsin Cibinong-Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi-eksperimen. Sampel diambil dua kelas, menggunakan cluster sampling dan dibagi menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Instrumen penelitian ini adalah instrumen tes pilihan ganda dengan skor 0-1 sebanyak 28 soal dengan 4 pilihan jawaban. Hasil penelitian ini diuji dengan melalui statistik uji “t”. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai thitung sebesar 2.79 ternyata lebih
besar dari ttabel sebesar 2.00 pada taraf signifikansi α = 0.05. Sehingga hipotesis
alternative (Ha) yang menyatakan terdapat pengaruh strategi peta konsep terhadap hasil belajar fisika siswa, diterima.
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan
Oleh :
ARI NURHAYATI 105016300573
Di bawah Bimbingan
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. Zulfiani, M.Pd Iwan Permana Suwarna, M.Pd NIP. 1976 0309 200501 2002 NIP. 1978 0504 2009 11013
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
yang telah banyak mengaruniai penulis dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya
sehingga dapat terselesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Strategi Peta Konsep
(Concept Mapping) Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa. Tak lupa shalawat
beserta salam tercurah kepada Rasulullah SAW, sang pembuka gerbang gelap
kejahilan menuju jalan yang penuh cahaya dengan ilmu pengetahuan.
Selanjutnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak sedikit kesulitan
dan hambatan yang dihadapi selama penulisan skripsi ini. Namun, atas bimbingan
dan motivasi dari berbagai pihak penulis menyadari bahwa keberhasilan dan
kesempurnaan merupakan sebuah proses yang harus dijalani. Oleh sebab itu, pada
kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak
yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, diantaranya:
1. Bapak Prof Dr. Dede Rosyada, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Ibu Baiq Hana Susanti, M.Sc., selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPA.
3. Ibu Dr. Zulfiani, M.Pd., selaku pembimbing I dan Bapak Iwan Permana
Suwarna, M.Pd., selaku pembimbing II yang penuh kesabaran dan keikhlasan
dalam membimbing penulis selama ini.
4. Seluruh dosen Jurusan IPA yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan
serta bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan, semoga ilmu
yang telah Bapak dan Ibu berikan mendapat keberkahan dari Allah SWT.
5. Kepala Sekolah, Guru, dan Staf di MTs Al-Mukhsin yang telah memberikan
izin penulis untuk melakukan penelitian.
6. Teristimewa untuk Kedua orang tua yang telah memberikan segalanya kepada
penulis baik moril maupun materil serta curahan kasih sayang yang tiada henti
sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Hanya Allah SWT yang dapat
membalasnya, semoga penulis dapat memberikan yang terbaik untuk kalian.
7. Saudara-saudaraku, teteh, aa, ade, dan keponakan yang selalu memberikan
motivasi kepada penulis.
8. Teman-temanku di kelas IPA Fisika angkatan 2005, yang tidak biasa penulis
sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas persahabatan dan
dukungannya, semoga kita kompak selalu.
Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Akhirnya tiada untaian kata yang berharga kecuali ucapan
Alhamdulillahirabbil’alamin atas rahmat, karunia, dan ridha-Nya. Semoga skripsi
ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Amiin.
Jakarta, Juni 2010
Penulis
Daftar Isi ………. iii
Daftar Tabel ………. . v
Daftar Gambar ………. vi
Daftar Lampiran………. vii
BAB I PENDAHULUAN……… 1
A. 1 B. Identifikasi Masalah ………. 4
Latar Belakang ………..……… Pembatasan Masalah………. Tujuan Penelitian……….. BAB II SKRIPSI TEORETIS, KERANGKA PIKIR Deskripsi Teoretis ………. 2. Hakikat Peta Konsep………... ……… 13
d. Jenis-jenis Peta Konsep………. f. Cara Menyusun dan Menilai Peta Konsep yang Dibuat g. Manfaat Strategi Peta Konsep……….. C. 4 D. Perumusan Masalah ………. 5
E. 5 F. Manfaat Penelitian……….... 6
DE DAN PENGAJUAN HIPOTESIS ……… 7
A. 7 1. Hakikat Belajar Bermakna………... 7
12 a. Pengertian Konsep……….... 12
b. Pengertian Peta Konsep……… c. Ciri-ciri Peta Konsep ……… 15
16 e. Kegunaan Peta Konsep ……… 19
Siswa……… 22
24
3. Ha 27
a. Hakikat Belajar ………. 27
kikat Hasil Belajar Fisika ……… Hakikat Hasil Belajar………. bungan Peta Konsep dengan Hasil Belajar …… B. c. IPA dan Pembelajaran Fisika………. 31
4. Hu 33 Kerangka Pikir ……….. 34
C. Penelitian yang Relevan………. 36
Pengajuan Hipotesis……… 40
41 Waktu dan Tempat Penelitian ……… 41
B. Metode Penelitian ……….. 41
Populasi dan Sampel ……….. 42
Variabel Penelitian ……… 43
E. Prosedur Penelitian ……… 43
Instrumen Penelitian ……….. 45
H. Hip 53
E. Keterbatasan Penelitian……….. 67
Tabel 2.1 ian Skor Terhadap Peta Konsep ………..………...
Tabel 3.1
Tabel 3.2 i Instrumen Hasil Belajar Fisika ………
Tabel 3.3
Tabel 3.4 asi Daya Beda ………
Tabel 3.5
Tabel 4.1 Pemusatan dan Penyebaran Data Hasil Pretest ……….
Tabel 4.2
Tabel 4.3 ean N-Gain Kelompok Kontrol dan Eksperimen ………
Tabel 4.4
Tabel 4.5 rmalitas Hasil Pretest ………..
Tabel 4.6
Tabel 4.7 ngan Uji Homogenitas Hasil Pretest ………...
Tabel 4.8
Tabel 4.9 amaan Dua Rata-rata Hasil Pretest dan Posttest ……….
Pember 24
Desain Penelitian ……… 41
Kisi-kis 45
Klasifikasi Tingkat Kesukaran ………... 48
Klasifik … 49
Klasifikasi N-Gain ………. 52
Ukuran 55
Ukuran Pemusatan dan Penyebaran Data Hasil Posttest ………. 56
Data M 58
Kategori Nilai N-Gain Kelompok Kontrol dan Eksperimen ….. 58
Uji No 60
Uji Normalitas Hasil Pretest ……….. 60
Perhitu 61
Perhitungan Uji Homogenitas Hasil Posttest ……….. 61
Uji Kes 62
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1
asi Baru Terkait pada Susunan Sel dalam Otak …….. 10
ambar 2.4 Peta Konsep Pohon Jaringan ………. 16
ambar 2.5 Peta Konsep Rantai Kejadian ……… 17
ambar 2.6 Peta Konsep Siklus ……… 18
Gambar 2.7 Peta Konsep Laba-laba ……….. 18
ambar 2.8 Bagan Kerangka Pikir ……… 36
ambar 3.1 Tahapan dalam Prosedur Penelitian ……… 44
. Bentuk-bentuk Belajar ………....……….. 7
Gambar 2.2 Dua Kontinum Belajar ……….. 9
Gambar 2.3 Inform G G G G G Gambar 4.1 Diagram Batang Distribusi Frekuensi Hasil Pretest ……….. 55
Gambar 4.2 Diagram Batang Distribusi Frekuensi Hasil Posttest ………. 57
Gambar 4.3 Diagram Batang Perbandingan Prosentase Normal Gain ….. 59
. Instrumen Penelitian dan Uji Coba Instrumen Penelitian
A.1 Kisi-kisi Instrumen Tes Hasil Belajar ………... 72
A.2 Soal Uji Coba Instrumen Penelitian Tes Hasil Belajar ……….. 88
A.3 Kunci Jawaban Soal Uji Coba Instrumen Penelitian Tes Hasil Belajar………. 98
A.4 Validitas Instrumen Penelitian Tes Hasil Belajar ……….. 99
A.5 Reliabilitas Instrum ajar ……….. 101
A.6 Tingkat Kesukaran Instrumen Penelitian Tes Hasil Belajar ……….. 104
A.7 Distribusi Daya Pembeda Instrumen Penelitian Tes Hasil Belajar … 106 r. 8 l b e R RPP Pertemuan Kedua ……… RPP Pertemuan Ketiga ……… R en Penelitian Tes Hasil Bel A.8 Rekapitulasi Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian Tes Hasil Belaja 10 A.9 Soal Instrumen Penelitian Tes Hasil Belajar yang Dipakai dalam Pene itian ……….. 110
A.10 Kunci Jawaban Soal Penelitian Tes Hasil Belajar ……… 117
B. Perangkat Pembelajaran B.1 Sila us ……….. 118
B.2 Pem taan SK, KD, dan Indikator ………. 124
B.3 RPP Kelompok Eksperimen ………... 129
B.5 Peta Konsep ………... 198
b. Peta Konsep Siswa Pertemuan Kedua ……… 205
c. Peta Konsep Siswa Pertemuan Ketiga ……… 206
d. Peta Konsep Siswa Pertemuan Keempat ……… 207
e. Peta Konsep Siswa Pertemuan Kelima ……….. 208
ompok 214 rmalitas dan Uji Homogenitas Pretest Kelompok m C. Uji Analisis Data C.1 Hasil Penelitian Pretest Kelompok Kontrol dan Eksperimen …….. 209
a. Data Hasil Penelitian Skor Pretest Kelompok Kontrol ……… 209
b. Tahapan Pembuatan Tabel Distribusi Frekuensi Pretest Kel Kontrol ………... 210
c. Persiapan Uji Normalitas dan Uji Homogenitas Pretest Kelompok Kontrol ……… 211
d. Tabel Perhitungan Uji Normalitas Pretest Kelompok Kontrol ... 212
e. Langkah Perhitungan Uji Normalitas Liliefors Pretest Kelompok Kontrol ……… 213
f. Data Hasil Penelitian Skor Pretest Kelompok Eksperimen …… g. Tahapan Pembuatan Tabel Distribusi Frekuensi Pretest Kelompok Eksperimen ………. 215
h. Persiapan Uji No Eksperimen ……… 216
i. Tabel Perhitungan Uji Normalitas Pretest Kelompok Eksperimen 217 j. Langkah Perhitungan Uji Normalitas Liliefors Pretest Kelompok Eksperimen ……….. 218
k. Uji Homogenitas Pretest ……….. 219
C.3 Hasil Penelitian N-gain Kelompok Kontrol dan Eksperimen ………
asil Penelitian Skor N-gain Kelompok Kontrol ………... 235
8
e.
f. Data Hasil Penelitian Skor N-gain Kelompok Eksperimen ….. 240 b. Tahapan Pembuatan Tabel Distribusi Frekuensi Posttest Kelompok
Kontrol ……… 223
c. Persiapan Uji Normalitas dan Uji Homogenitas Posttest Kelompok
Kontrol ……… 224
d. Tabel Perhitungan Uji Normalitas Posttest Kelompok Kontrol .. 225
e. Langkah Perhitungan Uji Normalitas Liliefors Posttest Kelompok
Kontrol ……… 226
f. Data Hasil Penelitian Skor Posttest Kelompok Eksperimen ….. 227
g. Tahapan Pembuatan Tabel Distribusi Frekuensi Posttest Kelompok
Eksperimen ………. 228
h. Persiapan Uji Normalitas dan Uji Homogenitas Posttest Kelompok
Eksperimen ……… 229
i. Tabel Perhitungan Uji Normalitas Posttest Kelompok
Eksperimen………. 230
j. Langkah Perhitungan Uji Normalitas Liliefors Posttest Kelompok
Eksperimen ……….. 231
k. Uji Homogenitas Posttest ……… 232
l. Perhitungan dan Pengujian Hipotesis Uji-t Posttest ……… 233
235
a. Data H
b. Tahapan Pembuatan Tabel Distribusi Frekuensi N-gain Kelompok
Kontrol ………. 236
c. Persiapan Uji Normalitas dan Uji Homogenitas N-gain Kelompok
Kontrol ………. 237
d. Tabel Perhitungan Uji Normalitas N-gain Kelompok Kontrol … 23
Langkah Perhitungan Uji Normalitas Liliefors N-gain Kelompok
Kontrol ………. 239
x
g. Tahapan Pembuatan Tabel Distribusi Frekuensi N-gain Kelompok
Eksperimen ……….. 241
h. Persiapan Uji Normalitas dan Uji Homogenitas N-gain Kelompok Eksperimen ………. 24
Tabel Perhitungan Uji Normalitas N-gain Kelompok Eksperimen ………... 24
Langkah Perhitungan Uji Normalitas Liliefors N-gain Kelompok Eksperimen ……….. 244
k. Uji Homogenitas N-gain ………. 245
Perhitungan dan Pengujian Hipotesis Uji-t N-gain ……….. 246
r Tabel ……… 248
Tabel Harga Kritik dari r Product Moment ………... 248
D.2 Tabel Luas di bawah Lengkungan Kurva Normal dari O ke Z …….. 250
Tabel Nilai Kritis Untuk Uji Liliefors ………... 251
Tabel Distribusi F ……….. 252
254 Keterangan ……… 25
at Bimbingan Skripsi ………. 255
Surat Permohonan Izin Penelitian ……….. 256
Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian ………. 2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam kehidupan, pendidikan memegang peranan penting karena
pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan
SDM. Oleh karena itu, banyak perhatian khusus diarahkan kepada
perkembangan dan kemajuan pendidikan guna meningkatkan mutu dan
kualitas pendidikan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
kualitas pendidikan adalah dengan mengelola komponen-komponen
pendidikan dengan baik.
Ada tiga komponen penentu dalam kegiatan belajar mengajar
diantaranya: komponen pertama adalah input yang terdiri dari peserta didik,
guru sebagai pendidik; komponen kedua adalah proses yang dipengaruhi oleh
lingkungan dan instrumen pengajaran; komponen ketiga hasil yaitu dampak
dari interaksi antara pendidik dengan peserta didik dan didukung oleh proses.1
Dari ketiga komponen tersebut antara yang satu dengan lainnya saling
bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan pendidikan.
Nasution mengatakan bahwa kualitas pendidikan banyak bergantung
pada kualitas guru dalam membimbing proses belajar mengajar. Oleh karena
itu, guru merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan dalam
mengajar, sehingga guru harus menguasai strategi mengajarnya. Guru sebagai
komponen penting dalam transformasi pendidikan mempersiapkan bahan
pelajaran kemudian melaksanakan dan mengembangkannya. Tugas tersebut
dimulai dari merumuskan tujuan, mengembangkan dan memilih materi,
menemukan strategi pembelajaran, mempersiapkan media, dan evaluasi. Jadi,
dapat disimpulkan bahwa salah satu keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari
keterampilan guru dalam memilih strategi pembelajaran dalam proses belajar
mengajar.
1
2
Fisika merupakan salah satu cabang IPA yang mengkaji tentang
berbagai fenomena alam dan memegang peranan yang sangat penting dalam
perkembangan sains, teknologi dan konsep hidup harmonis dengan alam. Oleh
karena itu, pembelajaran fisika di sekolah harus benar-benar dikelola dengan
baik dan mendapat perhatian yang lebih agar dapat menjadi landasan yang
kuat bagi peranan tersebut.
Mahardika mengungkapkan beberapa alasan pentingnya belajar fisika.
Alasan yang dapat disimpulkan dari Mahardika adalah Fisika dipandang
sebagai kumpulan pengetahuan, disiplin kerja yang dapat menghasilkan
sejumlah kemahiran untuk membantu pengembangan bekal kerja di berbagai
bidang profesi yang lebih luas. Berdasarkan alasan tersebut, maka fisika
begitu penting untuk dipelajari karena dapat berfungsi sebagai salah satu mata
pelajaran untuk membekali sumber daya manusia yang dapat mendukung
kemajuan bangsa.
Hasil diskusi peneliti dengan guru IPA di MTs Al-Mukhsin Cibinong
diperoleh hasil. Pertama, siswa cukup sulit memahami konsep-konsep fisika
karena banyak dari konsep yang bersifat abstrak. Kedua, siswa cenderung
hanya menghafal tanpa memahami konsep fisikanya itu sendiri. Ketiga, siswa
tidak dapat menghubungkan antara satu konsep satu ke konsep lain dalam satu
materi fisika. Keempat, interaksi di dalam kelas hanya terjadi antara guru dan
siswa saja sedangkan interaksi antara siswa jarang terjadi, baik dalam diskusi
maupun diskusi kelompok.
Berdasarkan fakta di atas dapat dilihat bahwa pembelajaran fisika
banyak dilakukan dengan memberi konsep fisika tanpa melalui pengolahan
potensi yang ada pada diri siswa. Dengan kata lain siswa belajar menghafal
konsep bukan menguasai konsep sehingga siswa tidak dapat memahami
keterkaitan antara konsep yang dipelajarinya dan pembelajaran fisikapun
menjadi kurang bermakna dengan tidak terbentuk kontruksi konsep fisika
bahwa salah satu keluhan dalam dunia pendidikan adalah siswa hanya
menghafal tanpa memahami benar isi pelajaran.2
Salah satu cara yang dapat mendorong siswa untuk belajar secara
“bermakna” adalah melalui “peta konsep”. Peta konsep adalah suatu strategi
yang dapat membantu para siswa melihat dan memahami keterkaitan antar
konsep yang telah dikuasainya. Strategi peta konsep sangat efektif untuk
membantu siswa belajar bermakna, yaitu memahami hubungan logika antara
konsep yang satu dengan konsep yang lain. Peta konsep yang baik adalah
yang dibuat sendiri oleh siswa. Di samping itu peta konsep bersifat fleksibel,
artinya dapat sederhana dan dapat pula kompleks, dapat linier atau bercabang
dan dapat pula hierarkis. Pembelajaran dengan membuat peta konsep dapat
meningkatkan pemahaman suatu konsep dengan baik, karena siswa aktif
dalam kegiatan belajar mengajar dan guru berperan aktif sebagai fasilitator
atau moderator.
Strategi peta konsep dalam pembelajaran sains sangat membantu siswa
dalam proses belajarnya. Pemahaman siswa jadi memadai dalam menentukan
hubungan antara keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lain. Struktur
kognitif siswa dibangun secara hieararkis dengan konsep-konsep dari yang
bersifat umum ke khusus. Namun strategi peta konsep akan lebih bermakna
jika siswa menyadari adanya kaitan konsep diantara kumpulan konsep-konsep
yang saling berhubungan. Dengan menggunakan peta konsep siswa
diharapkan dapat mengungkapkan seluruh pengetahuannya mengenai konsep
fisika, terutama konsep tata surya.
Materi pada konsep tata surya banyak berupa pemahaman konsep,
menjelaskan hubungan antar konsep yang satu dengan konsep yang lainnya
yang bersifat hierarkis, sehingga konsep tata surya lebih mudah dipahami
dengan baik oleh peserta didik apabila menggunakan strategi peta konsep. Hal
inilah yang mendasari penulis untuk menulis skripsi dengan judul “Pengaruh Strategi Peta Konsep (Concept Mapping) Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa”. Penelitian ini ingin mencari jawaban tentang pengaruh pembelajaran
2
4
dengan menggunakan strategi peta konsep terhadap hasil belajar fisika siswa
pada konsep Tata Surya.
B. Identifikasi Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat
diidentifikasikan masalah sebagai berikut :
1. Pembelajaran fisika yang disajikan guru di kelas pada umumnya dilakukan
secara teacher centered.
2. Siswa cenderung hanya menghafal tanpa memahami konsep fisikanya itu
sendiri.
3. Siswa tidak dapat menghubungkan antara satu konsep satu ke konsep lain
dalam satu materi fisika.
4. Hasil belajar fisika siswa rendah.
C. Pembatasan Masalah
Semua permasalahan yang diuraikan di atas tidak mungkin untuk
diteliti semua karena keterbatasan penelitian ini. Di samping itu, semua
variabel dalam penelitian ini tidak memungkinkan untuk dikontrol semua.
Oleh karena itu, dalam penelitian perlu dilakukan pembatasan masalah.
Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Hasil belajar fisika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil tes
kognitif saja. Adapun ranah kognitif yang dinilai adalah berdasarkan
taksonomi Bloom yang sudah direvisi oleh Madaus, dkk3 yaitu Ingatan
(C1), Pemahaman (C2), Penerapan (C3), dan analisis (C4).
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang dijadikan bahan
analisis dalam penelitian ini hanya dibatasi pada penerapan strategi peta
konsep saja. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar hanya
dijadikan sebagai acuan pengambilan kesimpulan saja.
3
3. Konsep materi pelajaran yang diberikan kepada masing-masing kelompok
selama eksperimen adalah konsep tata surya yang diajarkan pada semester
genap kelas IX.
D. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah dan batasan masalah
di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana
pengaruh penggunaan strategi peta konsep (concept mapping) terhadap hasil
belajar fisika siswa pada konsep Tata Surya di MTs Al-Mukhsin?”
Untuk memperjelas perumusan masalah di atas, penulis membuat
beberapa pertanyaan penelitian, diantaranya:
1. Bagaimanakah hasil belajar fisika siswa sebelum pembelajaran
berlangsung?
2. Bagaimanakah hasil belajar fisika siswa setelah pembelajaran
berlangsung?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan strategi peta konsep
(concept mapping) terhadap hasil belajar fisika siswa pada konsep Tata Surya
di MTs AL-Mukhsin Cibinong.
F. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa
pihak yang terlibat langsung terhadap penelitian ini, yaitu:
1. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk
meningkatkan hasil belajar fisika dan dapat mengurangi kebosanan selama
pembelajaran berlangsung.
2. Bagi guru mata pelajaran fisika, hasil penelitian ini diharapkan dapat
6
agar mudah diserap dan dimengerti oleh siswa yang memiliki kemampuan
dan minat yang berbeda satu dengan lainnya.
3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru
dalam bidang penelitian pendidikan dan model-model pembelajaran yang
akan menjadi bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata setelah
menyelesaikan studi.
4. Bagi peneliti lain, sebagai bahan studi lebih lanjut mengenai pemanfaatan
strategi peta konsep (concept mapping) khususnya untuk konsep tata
BAB II
DESKRIPSI TEORETIS, KERANGKA PIKIR,
DAN PENGAJUAN HIPOTESIS
A. Deskripsi Teoritik
1. Hakikat Belajar Bermakna
Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi,
seperti yang dinyatakan oleh gambar berikut:1
Belajar hafalan Belajar bermakna 1. Materi disajikan 1. Materi disajikan
dalam bentuk final dalam bentuk final
2. Siswa menghafal 2. Siswa
materi yang memasukkan disajikan materi ke dalam struktur kognitif
1. Materi ditemukan 1. Siswa
oleh siswa menemukan materi
Secara penerimaan
Secara penemuan Siswa dapat
mengasimilasi materi pelajaran
2. Siswa menghafal 2. Siswa
materi memasukkan materi ke dalam
struktur kognitif
Dimensi I Dimensi II
Gambar 2.1. Bentuk-bentuk Belajar (Dahar, 1996)
1
8
Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi
pelajaran disajikan pada siswa, melalui penerimaan dan penemuan. Dimensi
kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada
struktur kognitif yang telah ada. Struktur kognitif adalah fakta-fakta,
konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat siswa.
Pada tingkat pertama dalam belajar, informasi dapat dikomunikasikan
pada siswa baik dalam bentuk belajar penerimaan yang menyajikan informasi
dalam bentuk final, maupun dengan bentuk belajar penemuan yang mengharuskan
siswa menemukan sendiri sebagian atau seluruh materi yang akan diajarkan. Pada
tingkat kedua, siswa menghubungkan atau mengaitkan informasi itu pada
pengetahuan (berupa konsep-konsep atau lain-lain) yang telah dimilikinya, dalam
hal ini terjadi belajar bermakna. Akan tetapi, siswa itu dapat juga hanya
mencoba-coba menghafalkan informasi baru itu, tanpa menghubungkannya pada
konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitifnya, dalam hal ini terjadi belajar
hafalan.
Kedua dimensi, yaitu penerimaan/penemuan dan hafalan/bermakna tidak
menunjukkan dikotomi sederhana, melainkan merupakan suatu kontinum. Kedua
kontinum itu diperlihatkan pada gambar berikut:2
2
BELAJAR Menjelaskan Pengajaran Penelitian
BERMAKNA hubungan antara audio-tutorial ilmiah
konsep-konsep yang baik
Penyajian melalui Kegiatan di Sebagian besar
ceramah atau laboratorium penelitian rutin
buku Pelajaran sekolah atau produksi
intelektual
BELAJAR Daftar perkalian Menerapkan Pemecahan
HAFALAN rumus-rumus dengan
untuk memecahkan coba-coba
masalah
BELAJAR BELAJAR BELAJAR
PENERIMAAN PENEMUAN PENEMUAN
TERPIMPIN MANDIRI
Gambar 2.2. Dua Kontinum Belajar (Dahar, 1996)
Dari gambar di atas dapat dilihat sepanjang garis mendatar dari kiri ke
kanan berkurangnya penerimaan, dan bertambahnya belajar penemuan, sedangkan
sepanjang garis vertikal dari bawah ke atas berkurangnya belajar hafalan, dan
terbentuknya belajar bermakna dapat berjalan dengan baik pada belajar penemuan
maupun penerimaan.
Ausubel menyatakan bahwa banyak ahli pendidikan menyamakan belajar
penerimaan dengan belajar hafalan, sebab mereka berpendapat bahwa belajar
bermakna hanya bila siswa menemukan sendiri pengetahuan, kalau diperhatikan
gambar 2.2 tersebut, maka belajar penerimaan pun dapat dibuat bermakna, yaitu
10
penemuan rendah kebermaknaannya dan merupakan belajar hafalan, yakni
memecahkan suatu masalah hanya dengan coba-coba seperti menebak suatu
teka-teki. Belajar penemuan yang bermakna sekali hanyalah terjadi pada penelitian
yang bersifat ilmiah.
Menurut Ausubel, yang terpenting dalam belajar ialah belajar bermakna.
bagi Ausubel, belajar bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi
baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang.
Walaupun kita tidak mengetahui mekanisme biologi tentang memori atau
disimpannya pengetahuan, kita mengetahui bahwa informasi disimpan di
daerah-daerah tertentu dalam otak. Banyak sel otak yang terlibat dalam penyimpanan
pengetahuan itu. Dengan berlangsungnya belajar, dihasilkan perubahan-perubahan
sel-sel otak, terutama sel-sel yang telah menyimpan informasi yang mirip dengan
informasi yang sedang dipelajari. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:3
Gambar 2.3. Informasi Baru Terkait pada Susunan Sel dalam Otak
3
Dalam belajar bermakna informasi baru diasimilasikan pada
subsumer-subsumer relevan yang telah ada dalam struktur kognitif. Belajar bermakna yang
baru berakibatkan pertumbuhan dan modifikasi subsumer-subsumer yang telah
ada itu. Tergantung pada sejarah pengalaman seseorang, maksudnya informasi
baru a, b, c dikaitkan pada konsep-konsep relevan dalam struktur kognitif
(subsumer) A, B, C sehingga A mengalami diferensiasi lebih banyak dari pada B
atau C.
Menurut Ausubel dan juga Novack (1977), ada tiga kebaikan dari belajar
bermakna, yaitu:
a. Informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat.
b. Informasi yang tersubsumsi berakibatkan peningkatan diferensiasi dari
subsumer-subsumer, jadi memudahkan proses belajar berikutnya untuk materi
pelajaran yang mirip.
c. Informasi yang dilupakan sesudah subsumer obliteratif atau subsumer yang
telah rusak, sehingga mempermudah belajar hal-hal yang mirip, walaupun
telah terjadi ”lupa”.
Faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut
Ausubel (1963) ialah struktur kognitif yang ada, stabilitas dan kejelasan
pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Sifat-sifat
striktur kognitif menentukan validitas dan kejelasan arti-arti yang timbul waktu
informasi baru masuk ke dalam struktur kognitif baru, demikian pada sifat proses
interaksi yang terjadi. Jika struktur kognitif itu stabil, jelas dan diatur dengan baik,
maka arti-arti yang shahih dan jelas itu atau tidak meragukan akan timbul dan
cenderung bertahan. Tetapi sebaliknya, jika struktur kognitif itu tidak stabil,
meragukan, dan tidak teratur, maka struktur kognitif itu cenderung menghambat
belajar.
Prasyarat-prasyarat dari belajar bermakna adalah sebagai berikut :
a. Materi yang akan dipelajari harus bermakna secara potensial,
b. Anak yang akan belajar atau siswa harus bertujuan untuk melaksanakan
belajar bermakna, jadi mempunyai kesiapan dan niat untuk belajar bermakna
12
2. Hakikat Peta Konsep a. Pengertian Konsep
Di dalam hidupnya manusia selalu melakukan kegiatan mengamati.
Pengamatan terhadap sesuatu akan menimbulkan pengalaman dan pengetahuan.
Pengalaman yang menarik tentang sesuatu akan menimbulkan keingintahuan lebih
lanjut sehingga dilakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui
sesuatu itu lebih lagi. Pada saat itu terbentuklah persepsi sampai terjadinya
asosiasi diantara persepsi disebut konseptualisasi (pembentukan konsep).
Konsep adalah suatu ide atau gagasan abstrak yang memungkinkan
seseorang dapat mengklasifikasikan objek-objek atau peristiwa-peristiwa dan
memungkinkan pula untuk menentukan apakah objek-objek tertentu merupakan
contoh dari gagasan tersebut.4
Menurut Amien (1990), konsep merupakan suatu gagasan atau ide yang
didasarkan pada pengalaman tertentu yang relevan dan yang dapat
digeneralisasikan.5 Lebih lanjut dikatakan bahwa suatu konsep akan terbentuk
apabila dua atau lebih objek dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri umum, bentuk
dan sifatnya.
Konsep dapat didefinisikan dalam berbagai hal seperti berikut:
1) Konsep adalah gambaran dari ciri-ciri suatu objek sehingga dapat
membedakan dengan objek lainnya.
2) Konsep merupakan suatu abstraksi yang mewakili suatu kelas objek-objek
kejadian. Kegiatan-kegiatan yang memiliki atribut yang sama.
3) Konsep merupakan pembentukan mental dalam mengelompokan kata-kata
dengan penjelasan tertentu yang dapat diterima secara umum.
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa
konsep merupakan suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri karakter yang
4
Zainal Abidin, 2004. Pemahaman Konseptual dan Prosedural dalam Belajar Matematika, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, No. 17 Vol.2, h. 59.
5
sama dari sekelompok objek dan fakta, baik merupakan suatu proses, peristiwa
atau fenomena di alam yang membedakannya dari kelompoknya.
b. Pengertian Peta Konsep
Dalam bukunya yang berjudul Education Psychology : A Cognitive view.
Ausubel mengemukakan sebuah pernyataannya yang berbunyi :
“The most important single factor influencing learning is what the learner
already knows. Ascertain this and teach him accordingly” (Ausubel, 1968)
Pernyataan itu berbunyi : faktor yang paling penting yang mempengaruhi
belajar ialah apa yang telah diketahui siswa. Yakinlah ini dan ajarkan ia demikian.
Pernyataan Ausubel inilah yang menjadi inti teori belajarnya. Jadi, agar terjadi
belajar bermakna maka Ausubel sangat menekankan agar para guru mengetahui
konsep-konsep yang telah dimiliki para siswa. Tetapi, Ausubel belum
menyediakan suatu alat atau cara yang sesuai yang digunakan guru untuk
mengetahui apa yang telah diketahui para siswa. Berkenaan dengan itu Novak
(1985) dalam bukunya learning how to learn mengemukakan bahwa hal itu dapat
dilakukan dengan pertolongan peta konsep atau pemetaan konsep.6
Penggunaan strategi peta konsep dikembangkan oleh Joseph D. Novack,
seorang professor dari Universitas Cornell pada tahun 1970, sebagai cara untuk
meningkatkan pembelajaran bermakna dalam sains. Kerja Novack mengenai peta
konsep ini didasarkan pada teori Ausebel (teori asimilasi) yang menekankan pada
pentingnya pengetahuan awal dalam memudahkan mempelajari konsep-konsep
baru.7 Teori Ausebel ini adalah mengenai pembelajaran bermakna yang
menekankan bahwa pengetahuan baru bergantung pada apa yang sudah diketahui.
Peta konsep adalah istilah yang digunakan oleh Novak dan Gowin (1984)
tentang strategi/pendekatan yang digunakan oleh guru untuk membantu siswa
6
Ratna Wilis Dahar, Teori-teori Belajar, (Jakarta : Erlangga, 1996), h.122.
7
Eric Plotnic,. 2004, Concept Mapping a graphical system for understanding the relationship
14
mengorganisasikan konsep pelajaran yang telah dipelajari berdasarkan arti dan
hubungan antar komponennya.8
Menurut Novak seperti dikutip Lehman, et al., (1985) dalam Manulu,
pemetaan konsep adalah “A relatively structured visual means of representing
concept and their interrelationship” atau sebuah cara memvisualisasikan struktur
konsep-konsep secara relatif dan hubungan antara suatu konsep-konsep.
Menurut Jonassen, memetakan konsep adalah visualisasi kerangka
konseptual untuk pembuatan konsep pengatahuan lebih tegas/eksplisit dan
menuntut pelajar untuk memperhatikan hubungan antar konsep.9
Menurut Dahar (1988) dalam Pasaribu, peta konsep adalah alat peraga
untuk memperlihatkan hubungan antara beberapa konsep yang telah tersusun,
membuat peta konsep yang lengkap, maka pengajar dapat memutuskan bagaimana
dari peta konsep yang telah dibuat akan diajarkan dan bagaimana yang terpaksa
(sementara) diabaikan.10
Peta konsep adalah suatu gambar (visual) yang tersusun atas
konsep-konsep yang saling berkaitan sebagai hasil dari pemetaan konsep-konsep. Pemetaan
konsep merupakan suatu proses yang melibatkan identifikasi konsep-konsep dari
suatu proses yang melibatkan identfikasi konsep-konsep dari suatu materi
pelajaran dan pengaturan konsep-konsep tersebut dalam suatu hirarki, mulai dari
yang paling umum, kurang umum dan konsep-konsep yang lebih spesifik.11
Peta konsep adalah sebuah alat yang praktis untuk dapat belajar
memahami pelajaran penuh makna yang mudah dipahami dan suatu kreasi dari
kerangka pikir pengetahuan yang tidak hanya memanfaatkan dari pengetahuan
8
Peter G. Markow : Student’s Perception and Effects on Achievement. Journal of research in science teaching’ vol 35 no.9, h.1016.
9
Eric Plotnic, Op cit, h.2.
10
Abidin Pasaribu, “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Guru Fisika melalui Teknik Peta Konsep”, dalam Jurnal Forum Kependidikan, FKIP Universitas Sriwijaya, Palembang, Tahun ke-22, No. 1, September 2002, h.3.
11
Kadir, “Efektivitas Strategi Peta Konsep dalam Pembelajaran Sains dan Matematika”, dalam
yang ada akan tetapi dapat menyimpan pengetahuan untuk peride waktu tertentu
yang lama.12
Peta konsep merupakan diagram yang memaparkan suatu informasi dalam
bentuk hubungan antar konsep yang bermakna, penggunaan peta konsep dapat
diterapkan dalam berbagai tahap pembelajaran termasuk pada persiapan
pembelajaran. Membuat peta konsep pada prosesnya membutuhkan pembuatan
yang ektif merefleksikan pemahamannya terhadap materi yang diajarkan.13
Menurut Maria, peta konsep merupakan suatu grafik yang terdiri dari
tangkai yang mewakili konsep yang terstruktur. Peta konsep ini dapat digunakan
untuk : (1) tugas yang berhubungan dengan struktur pengetahuan siswa, (2) suatu
format tanggapan siswa, (3) penilaian.14
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peta konsep merupakan
strategi yang dapat digunakan untuk pembelajaran, membantu siswa dalam
mengorganisasikan konsep pelajaran berdasarkan arti dan hubungan antar
komponennya, hubungan antara satu konsep dengan konsep yang lain sehingga
apa yang dipelajari oleh siswa akan lebih bermakna lebih mudah diingat dan lebih
mudah dipahami untuk mengungkapkan kembali apa yang telah ada di dalam
struktur kognitif siswa bila diperlukan.
c. Ciri-ciri Peta Konsep
Dahar mengemukakan ciri-ciri peta konsep sebagai berikut:
1) Peta konsep (pemetaan konsep) adalah suatu cara untuk memperlihatkan
konsep-konsep dan proposisi-proposisi suatu bidang studi, apakah itu bidang
studi fisika, kimia, biologi, matematika dan lain-lain. Dengan membuat sendiri
peta konsep siswa “melihat” bidang studi itu lebih jelas, dan mempelajari
bidang studi itu lebih bermakna.
12
Joseph D. Novak and Alberto J. Canas, “The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct Them”, 2006 dalam http://champ.ihmc.us/publications/research papers/Theory Underlying Concept Maps,Pdf.
13
Diah Aryulina, “ Perbaikan Bimbingan PPL dengan Menerapkan Teknik Peta Konsep”, dalam
Jurnal Forum Kependidikan, FKIP Universitas Sriwijaya, Palembang, Tahun ke-22 No.2, Maret 2003, h.99.
14
16
2) Suatu peta konsep merupakan suatu gambar dua dimensi dari suatu bidang
studi atau suatu bagian dari bidang studi. Ciri inilah yang memperlihatkan
hubungan-hubungan proposisional antara konsep-konsep. Hal inilah yang
membedakan belajar bermakna dari belajar dengan cara mencatat pelajaran
tanpa memperlihatkan hubungan antara konsep-konsep, dan dengan demikian
hanya memperlihatkan gambar satu dimensi saja. Peta konsep bukan hanya
menggambarkan konsep-konsep yang penting, melainkan juga hubungan
antara konsep-konsep itu.
3) Ciri yang ketiga adalah mengenai cara menyatakan hubungan antara
konsep-konsep. Tidak semua konsep memiliki bobot yang sama. Ini berarti, bahwa
ada beberapa konsep yang lebih inklusif dari pada konsep-konsep lain.
4) Ciri keempat adalah hirarki. Bila dua atau lebih konsep digambarkan di bawah
suatu konsep yang lebih inklusif, terbentuklah suatu hirarki pada peta konsep
tersebut.
d. Jenis-jenis Peta Konsep
Menurut Nur (2000), peta konsep ada empat macam yaitu: pohon jaringan
(network tree), rantai kejadian (events chain), peta konsep siklus (cycle concept
map), dan peta konsep laba-laba (spider concept map).15
1) Pohon Jaringan (network tree)
Gambar 2.4. Peta Konsep Pohon Jaringan
15
Ide-ide pokok dibuat dalam persegi empat, sedangkan beberapa kata yang
lain dituliskan pada garis-garis penghubung. Garis-garis pada peta konsep
menunjukan hubungan antara ide-ide itu. Kata-kata yang dituliskan pada garis
penghubung memberikan hubungan antara konsep-konsep. Pada saat
mengkonstruksi suatu pohon jaringan, tulislah topik itu dan daftar konsep-konsep
utama yang berkaitan dengan topik itu. Daftar dan mulailah dengan menempatkan
ide-ide atau konsep-konsep dalam suatu susunan dari umum ke khusus.
Cabangkan konsep-konsep yang berkaitan itu dari konsep utama dan berikan
hubungannya pada garis-garis itu.
Pohon jaringan cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal
berikut:
a) Menunjukkan sebab akibat.
b) Suatu hierarki.
c) Prosedur yang bercabang.
Istilah-istilah yang berkaitan yang dapat digunakan untuk menjelaskan
hubungan-hubungan.
2) Rantai Kejadian (event chain)
Gambar 2.5. Peta Konsep Rantai Kejadian
Peta konsep rantai kejadian dapat digunakan untuk memberikan suatu
urutan kejadian, langkah-langkah dalam suatu prosedur, atau tahap-tahap dalam
suatu proses. Dalam membuat rantai kejadian, pertama-tama temukan satu
kejadian yang mengawali rantai itu. Kejadian ini disebut kejadian awal.
Kemudian, temukan kejadian berikutnya dalam rantai itu dan lanjutkan sampai
18
Rantai kejadian cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal berikut:
a) Memberikan tahap-tahap suatu proses.
b) Langkah-langkah dalam suatu prosedur linier.
c) Suatu urutan kejadian.
3) Peta Konsep Siklus (cycle concept map)
Gambar 2.6. Peta Konsep Siklus
Dalam peta konsep siklus, rangkaian kejadian tidak menghasilkan suatu
hasil akhir. Kejadian terakhir pada rantai itu menghubungkan kembali ke kejadian
awal. Seterusnya kejadian akhir itu menhubungkan kembali ke kejadian awal
siklus itu berulang dengan sendirinya dan tidak ada akhirnya. Peta konsep siklus
cocok diterapkan untuk menunjukan hubungan bagaimana suatu rangkaian
kejadian berinteraksi untuk menghasilkan suatu kelompok hasil yang
berulang-ulang.
4) Peta Konsep Laba-laba (spider concept map)
Peta konsep laba-laba dapat digunakan untuk curah pendapat. Dalam
melakukan curah pendapat ide-ide berasal dari suatu ide sentral, sehingga dapat
memperoleh sejumlah besar ide yang bercampur aduk. Banyak dari ide-ide
tersebut berkaitan dengan ide sentral namun belum tentu jelas hubungannya satu
sama lain. Kita dapat memulainya dengan memisah-misahkan dan
mengelompokkan istilah-istilah menurut kaitan tertentu sehingga istilah itu
menjadi lebih berguna dengan menuliskannya di luar konsep utama. Peta konsep
laba-laba cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal berikut:
a) Tidak menurut hirarki, kecuali berada dalam suatu kategori
b) Kategori yang tidak paralel
c) Hasil curah pendapat.
e. Kegunaan Peta Konsep
Dalam pendidikan, peta konsep dapat diterapkan untuk berbagai tujuan,
antara lain : 16
1) Menyelidiki apa yang telah diketahui siswa
Dalam mencapai proses belajar bermakna membutuhkan usaha yang
sungguh-sungguh dari pihak siswa untuk menghubungkan pengetahuan baru
dengan konsep-konsep relevan yang telah mereka miliki. Untuk memperlancar
proses ini, baik guru maupun siswa perlu mengetahui tempat awal konseptual.
Dengan kata lain perkataan guru harus mengetahui konsep-konsep apa yang telah
dimiliki siswa waktu pelajaran baru akan dimulai, sedangkan para siswa
diharapkan dapat menunjukan dimana mereka berada, atau konsep-konsep apa
yang telah mereka miliki dalam menghadapi pelajaran baru itu. Dengan
menggunakan peta konsep guru dapat melaksanakan apa yang telah dikemukakan
diatas, dan dengan demikian para siswa diharapkan akan mengalami belajar
bermakna.
16
Ratna Wilis Dahar, Op cit., h.129.
20
Salah satu pendekatan yang dapat digunakan guu untuk maksud ini ialah
dengan memilih satu konsep utama (key concept) dari pokok bahasan baru yang
akan dibahas. Para siswa diminta untuk menyusun peta konsep yang
memperlihatkan semua konsep yang dapat mereka kaitkan pada konsep utama itu,
serta memperlihatkan pula hubungan-hubungan antara konsep-konsep yang
mereka gambar itu. Dengan melihat hasil peta konsep yang telah disusun para
siswa itu, guru dapat mengetahui sampai berapa jauh pengetahuan para siswa
mengenai pokok bahasan yang akan diajarkan itu, dan inilah yang dijadikan titik
tolak pengembangan selanjutnya.
Pendekatan lain yang dapat digunakan guru ialah memilih beberapa
konsep penting dari pokok bahasan yang akan diajarkan. Para siswa kemudian
disuruh menyusun peta konsep dengan menghubungkan konsep-konsep itu. Lalu
para siswa diminta untuk menambahkan konsep dan mengaitkan
konsep-konsep itu hingga membentuk proposisi yang bermakna. Dari peta-peta konsep-konsep
yang dihasilkan oleh para siswa, guru dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan
para siswa tentang pokok bahasan yang akan diajarkan.
2) Mempelajari cara belajar
Bila seorang siswa dihadapkan pada suatu bab dari buku pelajaran, ia tidak
akan begitu saja memahami apa yang dibacanya. Dengan diminta untuk menyusun
peta konsep dari isi bab itu, ia akan berusaha untuk mengeluarkan konsep-konsep
dari apa yang dibacanya, menempatkan konsep yang paling inklusif pada puncak
peta konsep yang dibuatnya, kemudian mengurutkan konsep-konsep yang lain
yang kurang inklusif pada konsep yang paling inklusif, demikian seterusnya. Lalu
ia mencari kata atau kata-kata penghubung untuk mengaitkan konsep-konsep itu
menjadi proposisi-proposisi yang bermakna. Lebih dari itu ia akan berusaha
mengingat konsep-konsep lain dari pelajaran yang lampau, atau menerapkan
konsep-konsep yang sedang dihadapinya ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan
cara demikian ia telah berusaha benar untuk memahami isi pelajaran itu. Belajar
Tetapi perlu disadari bahwa belajar bermakna baru terjadi bila pembuatan
peta konsep itu bukan untuk memenuhi keinginan guru, jadi seakan-akan mau
menyenangkan guru, melainkan harus timbul dari keinginan siswa untuk mau
memahami isi pelajaran bagi dirinya sendiri. Siswa benar-benar harus mempunyai
kesiapan dan minat untuk belajar bermakna, seperti dikatakan oleh Ausubel. Sikap
ini harus dimiliki para siswa agar belajar bermakna dapat terjadi. Jadi, peta konsep
berfungsi untuk menolong siswa mempelajari cara belajar.
Oleh karena peta konsep itu mengungkapkan konsep-konsep dan
proposisi-proposisi yang dimiliki seseorang, maka guru dan siswa, demikian pula
siswa dan siswa dapat mengadakan diskusi untuk saling mengemukakan mengapa
suatu hubungan proposional itu baik atau sahih. Dengan cara ini dapat diketahui
kekurangan-kekurangan dalam mengaitkan konsep-konsep, dan guru dapat
menyarankan agar siswa bersangkutan lebih baik belajar.
3) Mengungkapkan konsepsi salah
Selain kegunaan-kegunaan yang telah disebutkan di atas, peta konsep
dapat pula mengungkapkan konsepsi salah (misconception) yang terjadi pada
siswa. Konsepsi salah biasanya timbul karena terdapat kaitan antara
konsep-konsep yang mengakibatkan proposisi yang salah. Konsepsi salah yang biasa
dijumpai pada siswa ialah bahwa mereka melihat zat padat atau zat cair terbentuk
dari molekul-molekul yang padat atau molekul-molekul “berupa air”. Tetapi
setelah mereka menyadari, bahwa molekul-molekul dikelilingi oleh ruang kosong,
dan bahwa tingkat wujud dihubungkan dengan suhu dan pola ikatan antara
molekul-molekul, maka mereka menyesuaikan pendapat lama mereka dengan
pendapat baru mereka (jadi terjadi penyesuaian integratif); es berubah menjadi
cair bila dipanaskan, bukan karena molekul-molekulnya berubah, yaitu dari padat
menjadi cair, melainkan karena ikatan-ikatan antara molekul-molekulnya putus.
Dan bila banyak energi diberikan, molekul-molekul itu dapat “beterbangan”,
membentuk gas yang akan memuai tak terhingga bila tempat molekul-molekul itu
22
4) Alat evaluasi
Penerapan peta konsep dalam pendidikan salah satunya adalah sebagai
alat evaluasi. Selama ini alat-alat evaluasi yang dikenal oleh guru dan siswa
terutama berbentuk tes objektif atau tes essai. Walaupun cara evaluasi ini akan
terus memegang peranan dalam dunia pendidikan. Menurut Dahar, peta konsep
sebagai alat evaluasi didasarkan atas tiga prinsip dalam teori kognitif Ausubel,
yaitu :
a) Struktur kognitif diatur secara hierarkis dengan konsep-konsep dan
proposisi-proposisi yang lebih inklusif, lebih umum superordinat terhadap
konsep-konsep dan proposisi-proposisi yang kurang inklusif dan lebih khusus.
b) Konsep-konsep dalam struktur kognitif mengalami diferensiasi progresif.
Prinsip Ausubel ini menyatakan bahwa belajar bermakna merupakan proses
yang kontinyu, dimana konsep-konsep baru memperoleh lebih banyak arti
dengan dibentuknya lebih banyak kaitan-kaitan proporsional. Jadi
konsep-konsep tidak pernah tuntas dipelajari, tetapi selalu dipelajari, dimodifikasi dan
dibuat lebih inklusif.
c) Prinsip penyesuaian integratif menyatakan bahwa belajar bermakna akan
meningkat apabila siswa menyadari akan perlunya kaitan-kaitan baru antara
segmen-segmen konsep atau proposisi. Dalam peta konsep penyesuaian
integratif ini diperlihatkan dengan kaitan-kaitan silang antara segmen-segmen
konsep.
Karena peta konsep bertujuan untuk memperjelas pemahaman suatu
bacaan, sehingga dapat dipakai sebagai alat evaluasi dengan cara meminta siswa
untuk membaca peta konsep dan menjelaskan hubungan antara konsep satu
dengan konsep yang lain dalam satu peta konsep.
f. Cara Menyusun dan Menilai Peta Konsep yang dibuat Siswa
Untuk menyusun peta konsep tidaklah sulit. Guru dan siswa dapat belajar
menyusunnya dalam waktu yang relatif singkat. Menurut Arnaudin, et.al (1984)
dalam Rusmansyah, lama waktu 3 x 20 menit diselingi dengan pekerjaan rumah
Beberapa langkah yang harus diikuti untuk membuat peta konsep dengan
benar adalah sebagai berikut:17
1) Memilih dan menentukan suatu bahan bacaan.
Bahan bacaan dapat dipilih dari buku bacaan, seperti buku catatan dan LKS.
2) Menentukan konsep-konsep yang relevan.
Mengurutkan konsep-konsep itu dari yang paling umum ke yang paling
khusus atau contoh-contoh.
3) Menyusun/menuliskan konsep-konsep itu di atas kertas.
Memetakan konsep-konsep itu berdasarkan kriteria antara lain: konsep yang
paling umum di puncak, konsep-konsep yang berada pada tingkatan abstraksi
yang sama diletakkan sejajar satu sama lain, konsep yang lebih khusus
diletakkan di bawah konsep yang lebih umum.
4) Menghubungkan konsep-konsep dengan kata penghubung tertentu untuk
membentuk proposisi atau garis penghubung.
5) Jika peta sudah selesai, perhatikan kembali letak konsep-konsepnya dan
perbaiki atau susun kembali agar menjadi lebih baik dan berarti.
Dalam memberi skor peta konsep secara sederhana dan ideal, pertama
adalah konstruksi/susunan konsep yang dibuat siswa pada saat dievaluasi. Secara
sederhana pemberian skor terhadap peta konsep yang dibuat oleh siswa dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.1. Pemberian skor terhadap peta konsep
Menyatakan Skor
Hubungan 11
Hirarki 3
Cabang 7
Dari umum ke khusus 3
Hubungan silang 2
Skor Total 26
17
24
g. Manfaat Strategi Peta Konsep
Dalam pembelajaran, penggunaan peta konsep dapat memberikan
beberapa manfaat yaitu:18
1) Bagi guru
a) Membantu untuk mengerjakan apa yang telah diketahui dalam bentuk
yang lebih sederhana, merencanakan dan memulai suatu topik
pembelajaran, serta mengolah kata kunci yang akan digunakan dalam
pembelajaran.
b) Membantu untuk mengingat kembali dan merevisi konsep pembelajaran,
membuat pola catatan kerja dan belajar yang sangat baik untuk keperluan
presentasi.
c) Membantu untuk mendiagnosis apa-apa yang telah diketahui para siswa
dalam bentuk struktur yang mereka bangun dalam bentuk kata-kata.
d) Membantu untuk mengetahui adanya miskonsepsi dari para siswa,
contohnya dalam ujian akan tergambar kemampuan siswa mengolah
idenya dalam bentuk grafik ataupun penggunaan visual yang representatif.
e) Membantu untuk mengecek pemahaman siswa akan konsep yang
dipelajari, dimana peta konsep yang dibuat siswa benar atau masih salah.
f) Membantu untuk memperbaiki kesalahan konsep yang diterima siswa
sebagai dasar untuk pembelajaran selanjutnya sehingga akhirnya efektif
untuk merubah kesalahan konsep yang diterima siswa.
g) Membantu untuk merencanakan instruksional pembelajaran dan
evaluasinya ataupun untuk mengukur keberhasilan tujuan instruksional
pembelajaran.
2) Bagi siswa
a) Membantu untuk mengidentifikasi kunci konsep,
menaksir/memperkirakan hubungan pemahaman dan membantu dalam
pembelajaran lebih lanjut.
18
b) Membantu membuat susunan konsep pelajaran menjadi lebih baik
sehingga mudah untuk keperluan ujian.
c) Membantu menyediakan sebuah pemikiran untuk menghubungkan konsep
pembelajaran.
d) Membantu untuk berpikir lebih dalam dengan ide siswa dan menjadikan
para siswa mengerti benar akan pengetahuan yang diperolehnya.
e) Mengklarifikasikan ide yang telah diperoleh siswa tentang sesuatu dalam
bentuk kata-kata.
f) Membuat suatu struktur pemahaman dari bagaimana semua fakta-fakta
(yang baru dan eksis) dihubungkan dengan pengetahuan berikutnya.
g) Belajar bagaimana mengorganisasi sesuatu mulai dari informasi, fakta, dan
konsep ke dalam suatu konteks pemahaman, sehingga terbentuk
pemahaman yang baik dan menuliskannya dengan benar.
Selanjutnya menurut Novak dan Gowin (1977) dalam Arif, penerapan peta
konsep pada proses pembelajaran diharapkan memungkinkan:19
1) Informasi yang dipelajari akan lebih lama diingat.
2) Informasi yang tersubsumsi mengakibatkan peningkatan deferensiasi dari
subsumer, sehingga memudahkan proses belajar berikutnya untuk materi yang
mirip.
3) Meskipun informasi yang telah terabsumsi tidak dapat dipanggil lagi dari
memori atau telah terjadi lupa disebabkan karena subsumsi obliteratif
(subsumsi rusak), tetapi telah meninggalkan efek residual pada subsumer,
sehingga mempermudah belajar hal-hal yang mirip selanjutnya.
Sehubungan dengan itu, pemetaan konsep bukan saja menunjukkan
susunan konsep-konsep tetapi menunjukkan juga perkaitan antara konsep. Oleh
karena itu, proses pembentukan gagasan dalam pikiran siswa melalui peta konsep
mampu melatih syaraf-syaraf otak untuk berfikir secara lebih kritis dan melatih
kesadaran tentang konsep yang sedang dipelajari (metakognitif). Tidak berlebihan
jika peta konsep dikatakan sebagai alat yang dapat mendorong dan mengubah
19
Arif Sholahuddin, “Implementasi Teori Ausubel pada Pembelajaran Kimia Karbon”, dalam
26
beberapa pola berfikir dan memperbaiki teknik pemikiran dalam proses
pembelajaran para siswa. Inilah yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan
pembelajaran lebih bermakna.
Menurut Michael Michalko, dalam buku terlarisnya Cracking Creativity,
peta konsep akan:
1) mengaktifkan seluruh otak,
2) membereskan akal dari kekusutan mental,
3) memungkinkan kita berfokus pada pokok behasan,
4) membantu menunjukkan hubungan antara bagian-bagian informasi yang
saling terpisah,
5) memberi gambaran yang jelas pada keseluruhan dan perincian,
6) memungkinkan kita mengelompokkan konsep, membantu kita
membandingkannya dan,
7) mensyaratkan kita untuk memusatkan perhatian pada pokok bahasan yang
membantu mengalihkan informasi tentangnya dari ingatan jangka pendek ke
ingatan jangka panjang.20
Dengan demikian peta konsep lebih memberdayakan pada proses berpikir
analisis dan logika dari pembuatan peta konsep tersebut. Sehingga peta konsep
dapat memberikan hubungan yang penting khususnya teori belajar dan mengajar.
Maka belajar yang efektif dan bermakna dapat berlangsung bila
hubungan-hubungan dapat dibangun antara konsep-konsep baru dengan konsep-konsep yang
telah terbentuk di dalam struktur kognitif siswa. Selain itu peta konsep dalam
proses belajar mengajar dikelas dapat mengurangi kefasipan siswa dan memacu
minat serta partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar yang bermakna.
Dalam proses belajar siswa mendapatkan pertambahan materi berupa
informasi mengenai teori, gejala, fakta ataupun kejadian-kejadian. Informasi yang
diperoleh akan diolah oleh siswa. Proses pengolahan informasi melibatkan kerja
sistem otak, sehingga informasi yang diperoleh dan telah diolah akan menjadi
suatu ingatan. Ingatan merupakan suatu proses biologi, yaitu pemberian
kode-kode terhadap informasi dan pemanggilan informasi kembali ketika informasi
20
tersebut dibutuhkan. Pada dasarnya ingatan adalah sesuatu yang membutuhkan
jati diri manusia dan membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Ingatan
memberikan titik-titik rujukan pada masa lalu dan perkiraan pada masa depan.
Ingatan merupakan reaksi elektrokimia yang rumit yang diaktifkan melalui
beragam saluran inderawi dan disimpan dalam jaringan saraf yang sangat rumit
dan unik di seluruh bagian otak. Ingatan dibentuk melalui berfikir, bergerak dan
mengalami hidup (rangsangan inderawi). Semua pengalaman yang dirasakan akan
disimpan dalam otak, kemudian akan diolah dan diurutkan oleh struktur dan
proses otak mengenai nilai dan kegunaannya.
3. Hakikat Hasil Belajar Fisika a. Hakikat Belajar
Belajar yaitu suatu perubahan di dalam kepribadian yang mengatakan diri
sebagai suatu pola baru dari reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan,
kepandaian atau suatu pengertian. Jadi, definisi belajar dari beberapa elemen:21
1) Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku dimana perubahan itu
dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik tetapi pada kemungkinan
mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk.
2) Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau
pengalaman dalam arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh
pertumbuhan atau tidak dianggap sebagai hasil belajar seperti
perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seorang bayi.
3) Belajar adalah perubahan relatif mantap, harus merupakan akhir dari pada
suatu periode waktu yang cukup panjang.
4) Belajar merupakan perubahan tingkah laku yang menyangkut berbagai aspek
kepribadian, baik fisik maupun psikis seperti: perubahan dalam pengertian,
pemecahan suatu masalah, berpikir, keterampilan, kecakapan, kebiasaan
ataupun sikap.
21
28
Menurut Hilgard (1984):22
Learning is the proses by which an activity originates or is changed through training procedures (whetherin the laboratory or in the natural environment) as distinguisbed from change by factors not anributableto training.”
Sebagai proses pengaturan, kegiatan belajar mengajar tidak terlepas dari
ciri-ciri tertentu yang menurut Edi Suardi sebagai berikut:23
1) Belajar mengajar memiliki tujuan.
2) Ada suatu prosedur (jalannya interaksi) yang direncanakan.
3) Kegiatan belajar mengajar ditandai dengan satu penggarapan materi yang
khusus.
4) Ditandai dengan aktivitas anak didik.
5) Dalam kegiatan belajar mengajar guru berperan sebagai pembimbing.
6) Dalam kegiatan belajar mengajar membutuhkan disiplin.
7) Ada batas waktu.
8) Evaluasi.
Belajar terjadi lebih efektif apabila: 24
1) Dalam lingkungan yang nyaman secara fisik dan psikis bagi wajib belajar.
Nyaman fisik: sarana dan prasarana belajar yang memadai dan
menyenangkan.
Nyaman psikis: hubungan saling percaya, saling menghargai, saling
membantu, bebas menyatakan pendapat, dan menerima perbedaan diantara
wajib belajar dan pendidik.
2) Wajib belajar merasakan kebutuhan belajar.
Wajib belajar menganggap tujuan belajar sebagai tujuannya sendiri.
3) Wajib belajar terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan belajar.
Wajib belajar aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
belajar.
22
Sumadi Surya Brata. Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Rajawali Pers. 2006).h. 232.
23
Syaiful Bahri Djamarah. Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: Rineka Cipta. 2002) Cet.2, h.46.
24
4) Berpusat pada pengalaman.
Wajib belajar mengalami secara langsung atau tidak langsung proses belajar
dan menggunakan pengalamannya secara tepat.
5) Wajib belajar menerima umpan balik yang tepat untuk menilai keberhasilan
mereka mencapai tujuan.
Pembelajaran fisika akan lebih bermakna apabila diimbangi dengan
strategi belajar yang tepat. Dalam hal ini pemilihan pendekatan pembelajaran
sebagai alat hasil belajar siswa. Pembelajaran harus melibatkan siswa secara aktif
dalam belajar, terlebih lagi jika mereka dapat bekerja sama dan saling membantu
untuk mencapai tujuan pembelajaran.
b. Hakikat Hasil Belajar
Bila terjadi proses belajar, maka terjadi juga proses mengajar. Jika sudah
terjadi proses/interaksi antara yang mengajar dengan yang belajar. Dari proses
belajar mengajar ini akan diperoleh hasil yang pada umumnya disebut hasil
pengajaran, atau dengan istilah tujuan pembelajaran atau hasil belajar. Agar hasil
belajar biasa seoptimal mungkin pembelajaran harus benar-benar terorganisasi
dengan baik.
Hasil belajar adalah indikasi yang menunjukan upaya penguasaan
pengetahuan (kognitif) siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan guru
melalui kegiatan ko-kulikuler (pekerjaan rumah) dan tes ulangan.
Sedangkan Benyamin Bloom secara garis besar membagi menjadi
beberapa ranah, yaitu: ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Pada
penelitian ini, penulis hanya akan mengungkapkan hasil belajar pada ranah
kognitif saja.
Ranah kognitif ini merupakan ranah yang lebih melibatkan kegiatan
mental/otak. Pada ranah kognitif terdapat enam jenjang proses berpikir, yaitu:
1) Ingatan (knowledge)
Jenjang hafalan (ingatan) meliputi kemampuan menyatakan kembali fakta,
30
2) Pemahaman (comprehension)
Jenjang pemahaman meliputi kemampuan menangkap arti dari informasi yang
diterima, misalnya dapat menafsirkan bagan, diagram, atau grafik,
menerjemahkan suatu pernyataan verbal ke dalam rumusan matematis atau
sebaliknya, meramalkan berdasarkan kecenderungan tertentu (ekstrapolasi dan
interpolasi), serta mengungkapkan suatu konsep atau prinsip dengan kata-kata
sendiri.
3) Penerapan (application)
Jenjang penerapan ialah kemampuan menggunakan prinsip, aturan, metode
yang dipelajarinya pada situasi baru atau pada situasi konkrit.
4) Analisis (analysis)
Jenjang analisis meliputi kemampuan menguraikan suatu informasi yang
dihadapi menjadi komponen-komponennya sehingga struktur informasi serta
hubungan antar komponen informasi tersebut menjadi gelas.
5) Sintesis (syntesis)
Jenjang sintesis ialah kemampuan untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang
terpisah-pisah menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. Termasuk ke
dalamnya kemampuan merencanakan eksperimen, menyusun karangan
(laporan praktikum, artikel, rangkuman), menyusun cara baru untuk
mengklasifikasikan obyek-obyek, peristiwa, dan informasi lainnya.
6) Evaluasi (evaluation)
Jenjang evaluasi ialah kemampuan untuk mempertimbangkan nilai suatu
pernyataan, uraian, pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan.
Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan
berhasil, setiap guru harus memiliki pandangan. Namun untuk menyamakan
persepsi sebaiknya berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat ini yang telah
disempurnakan, antara lain bahwa : “suatu proses belajar mengajar tentang suatu
bahan pelajaran dinyatakan berhasil apabila Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
dapat tercapai.25
25
Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar tersebut
dapat dilakukan melalu tes prestasi belajar. Menurut Purwanto, tes hasil belajar
adalah tes yang digunakan untuk menilai-nilai pelajaran yang telah diberikan oleh
guru kepada murid-muridnya, untuk dosen dan mahasiswanya dalam waktu
tertentu.26
Tes hasil belajar merupakan cara yang dipergunakan atau prosedur yang
ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, yang
berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa
pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh
testee, sehingga atas dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut
dapat dihasilkan nilai yang melambangkan prestasi siswa.27 Jadi, agar
memperoleh gambaran daya serap siswa untuk meningkatkan tingkat keberhasilan
belajar siswa serta tingkat penguasaan pengetahuan tertentu perlu diukur dengan
alat evaluasi.
c. IPA dan Pembelajaran Fisika
Ilmu pengetahuan alam atau sains (science) diambil dari kata latin scientia
yang arti harfiahnya adalah pengetahuan, tetapi kemudian berkembang menjadi
khusus Ilmu Pengetahuan Alam atau Sains. Sund dan Trowbribge merumuskan
bahwa Sains merupakan kumpulan pengetahuan dan proses. 28 Sedangkan Kuslan
Stone menyebutkan bahwa Sains adalah kumpulan pengetahuan dan cara-cara
untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu.
Sains merupakan produk dan proses yang tidak dapat dipisahkan. “Real
Science is both product and process, inseparably joint” (Agus. S. 2003: 11).29
Sains sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para ilmuan
untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang
gejala-gejala alam. Langkah tersebut adalah merumuskan masalah, merumuskan
26
Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pendidikan, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), h.43.
27
Sudijono Anas, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), h. 164.
28
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu Pengetahuan Alam (3 Juni 2010)
29