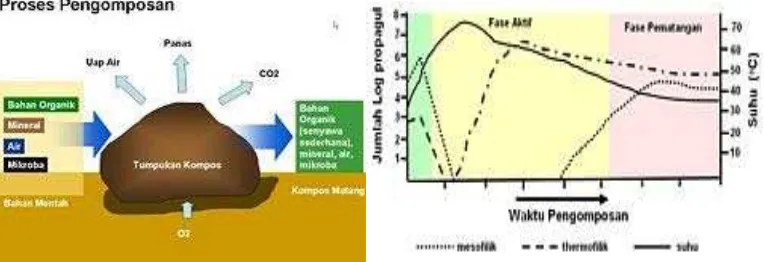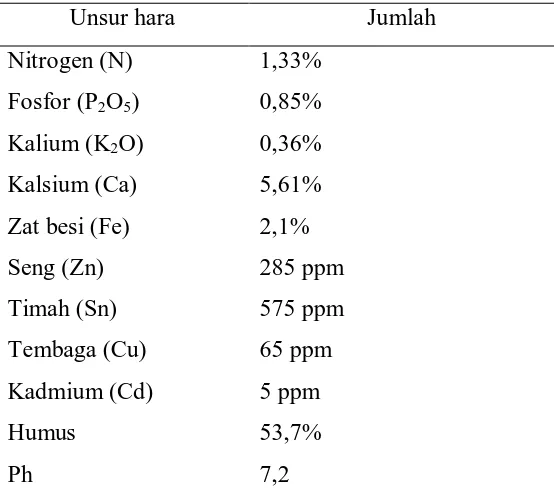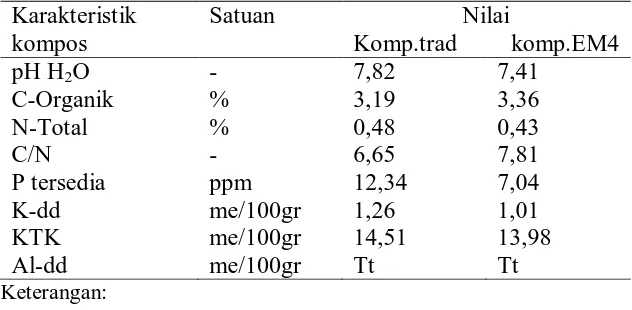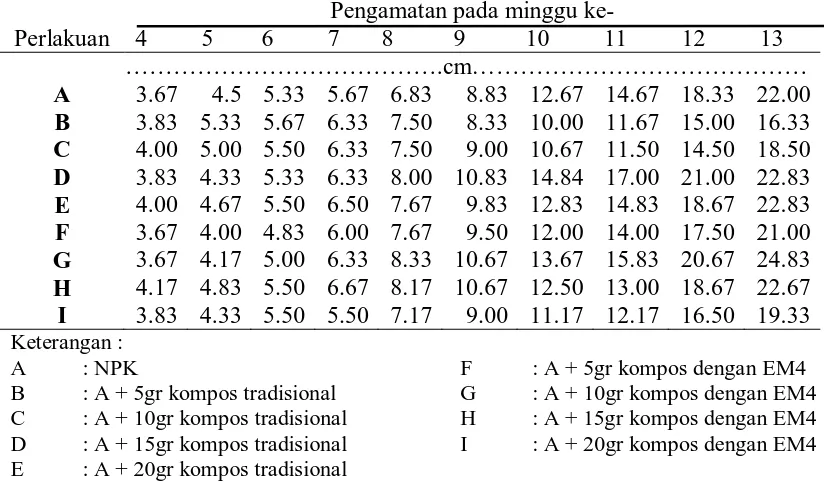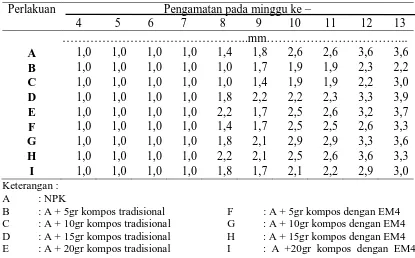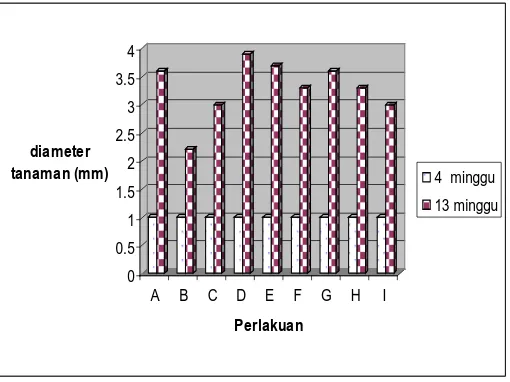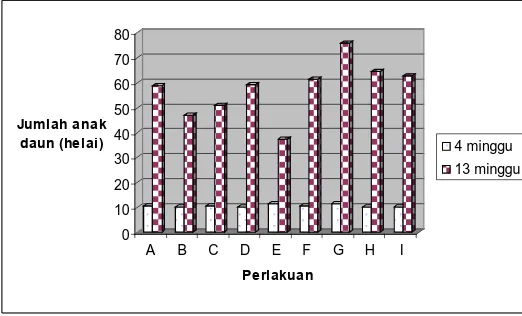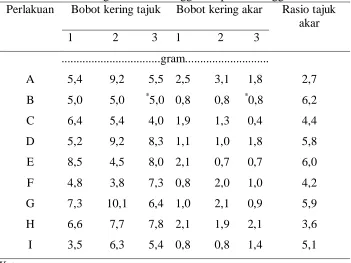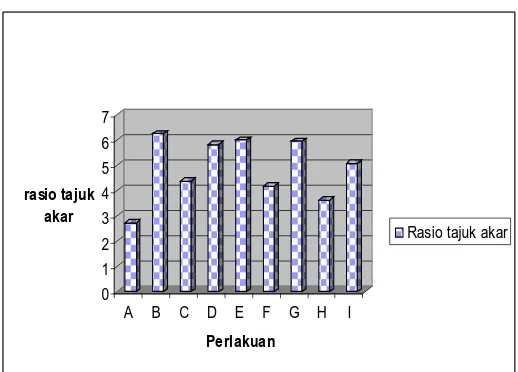KUALITAS KOMPOS SAMPAH KOTA DAN APLIKASINYA
PADA MEDIA TANAH LAHAN KRITIS UNTUK
BIBIT SENGON ( Paraserianthes falcataria)
SKRIPSI
OLEH :
NOVITA HASIBUAN
051202038
DEPARTEMEN KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
KUALITAS KOMPOS SAMPAH KOTA DAN APLIKASINYA
PADA MEDIA TANAH LAHAN KRITIS UNTUK
BIBIT SENGON ( Paraserianthes falcataria)
SKRIPSI
Oleh :
NOVITA HASIBUAN
051202038/ BUDIDAYA HUTAN
Skripsi sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan
Sidang di Fakultas Pertanian ,Universitas Sumatera Utara
DEPARTEMEN KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
LEMBAR
PENGESAHAN
Judul Penelitian : Kualitas Kompos Sampah Kota Dan Aplikasinya Pada Media Tanah Lahan Kritis Untuk Bibit Sengon
(Paraserianthes falcataria)
Nama : Novita Hasibuan
NIM : 051202038
Departemen : Kehutanan
Program Studi : Budidaya Hutan
Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing,
Dr. Deni Elfiati, SP, MP Dr.Ir. Hamidah Hanum SP. MP
Ketua Anggota
Mengetahui,
ABSTRACT
NOVITA HASIBUAN: Waste Compost Quality City And Its Application In the Media Area of Critical For Sengon Seeds (Paraserianthes falcataria), led by Dr. DENI ELFIATI SP.MP and Dr.Ir. HAMIDAH HANUM SP.MP
. Critical land in Indonesia reached 28 million hectares are located in forest area and nonhutan. So it is required afforestation by planting crops and added sengon biowaste compost town. This study aimed to compare the quality of municipal solid waste compost and the compost bin without EM4, EM4 and cities with the effect of municipal solid waste compost and the compost bin with EM4 EM4 city without the seeds sengon applied to the soil media critical land. This research was conducted in November 2009 - April 2010 in the House of gauze, Faculty of Agriculture, USU, using completely randomized factorial design. The results showed that the quality of municipal solid waste compost with better EM4 compared with urban waste compost without EM4 (traditional). Height growth, stem diameter and number of leaves on seedlings sengon children (Paraserianthes falcataria) is better contained in the G treatment (NPK +10 g compost with EM4), and treatment of H (g compost with NPK +15 EM4) compared with treatments without compost EM4 (traditional). Treatment G (NPK +10 g compost with EM4), H (g compost with NPK +15 EM4), D (NPK +15 gr traditional compost) and E (NPK +20 gr traditional composting) is better than the control treatment.
ABSTRAK
NOVITA HASIBUAN : Kualitas Kompos Sampah Kota Dan Aplikasinya Pada Media Lahan Kritis Untuk Bibit Sengon (Paraserianthes falcataria), dibimbing oleh Dr. DENI ELFIATI SP.MP dan Dr.Ir. HAMIDAH HANUM SP.MP.
Lahan kritis di Indonesia mencapai 28 juta hektar yang terdapat pada kawasan hutan dan nonhutan. Sehingga diperlukan usaha penghijauan dengan menanam tanaman sengon dan ditambah pupuk kompos sampah organik kota. Penelitian ini bertujuan membandingkan kualitas kompos sampah kota tanpa EM4 dan kompos sampah kota dengan EM4 dan pengaruh pemberian kompos sampah kota dengan EM4 dan kompos sampah kota tanpa EM4 pada bibit sengon yang diaplikasikan ke media tanah lahan kritis. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2009 - April 2010 di Rumah kasa, Fakultas Pertanian USU, menggunakan rancangan acak lengkap non faktorial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kompos sampah kota dengan EM4 lebih baik dibandingkan dengan kompos sampah kota tanpa EM4 (tradisional). Pertumbuhan tinggi, diameter batang dan jumlah anak daun pada bibit sengon (Paraserianthes falcataria) yang lebih baik terdapat pada perlakuan G (NPK+10 gr kompos dengan EM4) dan perlakuan H (NPK+15 gr kompos dengan EM4) dibandingkan dengan perlakuan pemberian kompos tanpa EM4 (tradisional). Perlakuan G (NPK+10 gr kompos dengan EM4), H (NPK+15 gr kompos dengan EM4), D (NPK+15 gr kompos tradisional) dan E (NPK+20 gr kompos tradisional) lebih baik daripada perlakuan kontrol.
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Duri – Riau pada tanggal 25 Mei 1985 dari ayah R.
Hasibuan dan Ibu R. Sihombing. Penulis merupakan anak keempat dari empat
bersaudara.
Pendidikan formal yang ditempuh selama ini :
1. Pendidikan Dasar di SD N 002 Duri – Riau, Lulus tahun 1998
2. Pendidikan Lanjutan di SLTP Santo Yosef Duri – Riau, Lulus tahun 2001
3. Pendidikan Menengah di SMA N 2 Mandau Duri – Riau, Lulus tahun 2004
4. Tahun 2005 diterima pada Program Studi Budidaya Hutan Departemen
Kehutanan Universitas Sumatera Utara.
Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif sebagai anggota Himpunan
Mahasiswa Kehutanan dan pernah menjadi anggota KMK USU tahun 2005/2006.
Penulis pernah melakukan Praktik Pengenalan Pengelolahan Hutan (P3H)
pada 2 lokasi berbeda yaitu di hutan mangrove Batubara dan hutan pegunungan Lau
Kawar. Selain itu penulis juga pernah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
di IUPHHK PT. Andalas Merapi Timber, Kabupaten Solok Selatan – Sumatera Barat
dan akhir kuliah penulis melaksanakan penelitian dengan judul Kualitas Kompos
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
berkat dan anugrahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini
tepat pada waktu yang telah ditentukan. Judul ini penelitian ini adalah Kualitas
Kompos Sampah Kota Dan Aplikasinya Pada Media Tanah Lahan Kritis Untuk Bibit
Sengon (Paraserinthes falcataria).
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya
kepada kedua orang tua penulis yang telah membesarkan, memelihara dan mendidik
penulis selama ini. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada ibu Dr. Deni
Elfiati SP.MP dan Dr.Ir. Hamidah Hanum SP.MP selaku ketua dan anggota komisi
pembimbing yang telah membimbing dan memberikan berbagai masukan berharga
kepada penulis dari mulai menetapkan judul, melakukan penelitian, sampai pada
ujian akhir. Khusus untuk Bapak Paris Sembiring di Pembibitan Sembiring Pasar V,
penulis menyampaikan banyak terima kasih atas bantuannya selama penulis
melaksanakan penelitian.
Disamping itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada staf pengajar
dan pegawai Di Program Studi Budidaya Hutan Departemen Kehutanan, serta semua
rekan mahasiswa stambuk ’04 dan ’05 yang tidak dapat disebutkan satu per satu di
sini yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi
ini bermanfaat.
Medan, Juni 2010
DAFTAR ISI
Hal.
ABSTRAK... i
ABSTRAT... ... ii
RIWAYAT HIDUP... iii
KATA PENGANTAR... iv
DAFTAR ISI... v
DAFTAR TABEL... vii
DAFTAR GAMBAR... viii
DAFTAR LAMPIRAN... ix
PENDAHULUAN Latar Belakang... 1
Tujuan Penelitian... 4
Hipotesis Penelitian... 4
Manfaat Penelitian... 4
TINJAUAN PUSTAKA Definisi Lahan Kritis... 5
Ciri – Ciri Lahan Kritis... 5
Tujuan Rehabilitas Lahan Kritis... 6
Kompos sampah kota... 7
Botani Sengon... 13
Habitat sengon... 14
METODOLOGI PENELITIAN A. Perbedaan Kualitas Kompos Lokasi dan Waktu Penelitian... 15
Alat dan Bahan... 15
Prosedur penelitian... 15
B. Pengaplikasian kompos pada bibit sengon Lokasi dan Waktu Penelitian... 18
Alat dan Bahan... 18
Metode Penelitian... 18
Prosedur pelaksanaan penelitian... 20
HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Kualitas kompos... 23
Pertambahan tinggi... 23
Pertambahan diameter batang... 25
Pertambahan jumlah anak daun...26
Bobot kering tajuk dan akar... 28
Rasio tajuk akar... 28
Pembahasan Pembahasan... 29
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan... 33
DAFTAR TABEL
No.
Hal.
1. Kandungan unsur hara dalam kompos...12
2. Data analisis kompos...23
3. Rataan pertambahan tinggi tanaman sengon ...24
3. Rataan diameter batang tanaman sengon...25
4. Rataan pertambahan jumlah anak daun...27
DAFTAR GAMBAR
No. Hal.
1. Proses pengomposan... 8
2. Diagram perbedaan tinggi sengon...25
3. Diagram perbedaan diameter batang sengon...26
4. Diagram peebedaan jumlah anak daun sengon...27
DAFTAR LAMPIRAN
No. Hal.
1. Skema penanaman di rumah kasa...36
2. Prosedur menghitung kadar air kering udara...37
3. Data tinggi tanaman sengon umur 4 minggu – 13 minggu...38
4. Data analisis sidik ragam tinggi sengon umur 13 minggu...38
5. Data diameter tanaman sengon umur 4 minggu – 13 minggu...39
6. Data analisis sidik ragam diameter tanaman sengon umur 13 minggu...39
7. Data jumlah anak daun tanaman sengon umur 4 minggu – 13 minggu...40
8. Data analisis sidik ragam jumlah anak daun sengon umur 13 minggu...40
9. Hasil analisis tanah...41
10.Data komposisi Effective Microorganisms 4 (EM4)...41
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pada tahun 1991, lahan tidak produktif atau juga diistilahkan sebagai lahan
kritis menempati areal seluas 28 juta hektar. Dari luasan itu 13 juta hektar terdapat di
areal lahan kering non hutan. Dari luasan ini yang berhasil dihijaukan dan
dikonservasi baru sekitar 500.000 hektar tiap tahunnya. Hal ini terutama disebabkan
rendahnya kemampuan masyarakat untuk melakukan usaha konservasi dan
penghijauan sendiri (BPDAS-Pemalijratun, 2007).
Lahan kritis di Indonesia telah mencapai 28 juta hektar yang terdapat di
kawasan hutan dan nonhutan. Namun pendekatan berdasarkan Daerah Aliran Sungai
mempunyai potensi baik untuk dijadikan basis pengelolaan lahan kritis itu. Hal ini
beranjak dari kenyataan bahwa terjadinya erosi umumnya bisa diketahui dengan
pendekatan perubahan pola aliran sungai. Hampir semua sungai besar di tanah air
dapat digolongkan ke dalam DAS – DAS kritis. Bukti dari hal ini adalah terjadinya
banjir yang melanda banyak Daerah Aliran Sungai di seluruh tanah air yang merusak
tidak hanya daerah permukaan penduduk tetapi areal pertanian (Setiadi, 2001).
Tanah menjadi kritis karena tidak adanya tanaman yang tumbuh di Permukaan
tanah sehingga terkikisnya lapisan atas tanah yang merupakan media tumbuhnya
tanaman. Dengan hilangnya lapisan tanah atas itu maka terjadi pula kehilangan unsur
hara yang merupakan nutrisi tanaman yang tumbuh di tanah itu.
Atas dasar itu semakin nyata bahwa masalah lahan kritis sebetulnya tidak bisa
dipisahkan dengan kualitas pengelolaan lahan atau tanaman. Dan memang telah
banyak bukti menunjukkan bahwa lahan yang tidak dikelola sebagaimana mestinya
pasti mengalami pemunduran kesuburannya. Pemunduran itu selain melalui
pengurasan unsur hara melalui pembakaran pada waktu pembukaan lahan, juga sering
terjadi melalui erosi tanah oleh air hujan, angin, dan atau dibeberapa negara oleh
salju. Kehilangan unsur hara tersebut dapat menurunkan produktivitas lahan. Bila
suatu lahan produktivitasnya telah rendah maka lahan itu akan ditinggalkan dan
tergolong tidak produktif. Lahan yang tidak produktif dan telah mengalami kerusakan
secara fisik, kimia, atau biologi untuk selanjutnya merupakan istilah yang digunakan
untuk lahan kritis.
Pada lahan kritis di Indonesia, seiring dengan perjalanan waktu kadar bahan
organik tanah cenderung menurun yang akan menurunkan kesuburan tanah. Untuk itu
perlu penggunaan bahan organik dalam pengelolaan lahan, salah satu sumber bahan
organik yang potensial adalah sampah kota. Melalui pengomposan dengan
memanfatkan bantuan mikroba dekomposer diharapkan terjadi percepatan waktu
pengomposan sampah kota dan diperoleh kompos dengan kwalitas yang lebih baik.
Kompos diketahui mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Kompos
mengandung hara makro dan mikro namun secara umum kadarnya rendah bergantung
dari jenis bahan organiknya, Oleh karena itu diperlukan sumber hara lain yang
berkadar hara tinggi yang dapat meningkatkan kadar hara kompos.
Tanaman sengon mampu memperbaiki struktur tanah dari lahan kritis karena
akar sengon relatif menguntungkan dibandingkan akar pohon lainnya. Akar
tunggangnya cukup kuat menembus ke dalam tanah. Semakin besar pohonnnya
semakin dalam akar tunggangnya menembus ke dalam tanah. Sementara itu, akar
rambutnya tidak terlalu besar, tidak rimbun dan tidak menonjol ke permukaan tanah.
Akar rambut tersebut justru dimanfaatkan oleh pohon induknya untuk menyimpan zat
nitrogen, oleh karena itu tanah di sekitar pohon sengon akan menjadi subur. Dengan
melihat sifat – sifat kelebihan akar sengon maka sungguh tepat jika sengon ditanam
di tepi kawasan yang mudah terkena erosi. Sistem perakaran sengon banyak
mengandung nodul akar sebagai hasil simbiosis dengan bakteri Rhizobium. Hal ini
menguntungkan bagi akar dan sekitarnya. Keberadaan nodul akar dapat membantu
porositas tanah dan penyediaan unsur nitrogen dalam tanah. Dengan demikian pohon
sengon dapat membuat tanah disekitarnya menjadi lebih subur (Hieronymus, 1992).
Pengomposan adalah proses dekomposisi terkendali secara biologis terhadap
limbah padat organik diubah menyerupai tanah seperti halnya humus atau mulsa.
Kompos telah dipergunakan secara meluas selama ratusan tahun dalam menangani
Sampah adalah bahan sisa, baik bahan-bahan yang sudah tidak digunakan lagi
(bahan bekas) maupun bahan yang sudah diambil bagian utamanya dan ditinjau dari
segi sosial ekonomi tidak ada harganya serta dari segi lingkungan dapat menyebabkan
pencemaran atau gangguan kelestarian. Jumlah dan komposisi sampah yang
dihasilkan dalam suatu kota ditentukan oleh beberapa faktor yaitu: (1) jumlah
penduduk dan tingkat pertumbuhannya; (2) tingkat pendapatan dan pola konsumsi
masyarakat; (3) pola penyediaan kebutuhan hidup penduduknya; (4) iklim dan musim
(Setiadi, 2001).
Oleh karena itu, penelitian Kualitas Kompos Sampah Kota Dan Aplikasinya
Pada Media Tanah Lahan Kritis Untuk Bibit Sengon (Paraserianthes falcataria)
Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Membandingkan kualitas kompos sampah kota tanpa EM4 dan kompos
sampah kota dengan EM4.
2. Membandingkan pengaruh pemberian kompos sampah kota tanpa EM4 dan
kompos sampah kota dengan EM4 pada bibit sengon yang diaplikasikan ke
media tanah dari lahan kritis.
Hipotesis Penelitian
Hipotesis penelitian ini adalah :
1. Kualitas kompos sampah kota tanpa EM4 berbeda dengan kompos sampah
kota dengan EM4.
2. Pemberian kompos sampah kota berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit
sengon.
Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Untuk memanfaatkan sisa – sisa sampah organik di kota medan sebagai
kompos.
TINJAUAN PUSTAKA
Definisi Lahan Kritis
Lahan kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga
kehilangan atau berkurang fungsinya (fungsi produksi dan pengatur tata air).
Menurunnya fungsi tersebut akibat dari penggunaan lahan yang kurang atau tidak
memperhatikan teknik konservasi tanah sehingga menimbulkan erosi, tanah longsor
dan berpengaruh terhadap kesuburan tanah, tata air dan lingkungan
(BPDAS-Pemalijratun, 2007).
Lahan yang kritis memiliki potensi erosi yang sangat tinggi yang
mengakibatkan lapisan – lapisan tanah tersebut terbawa hilang, sehingga dalam
pelaksanaan konservasinya secara generatif harus menggunakan tanaman yang
mampu menahan pengikisan tanah, meresapkan air dan mengembalikan totalitas
daripada lahan kritis tersebut (Setiawan, 2003).
Lahan kritis mempunyai keterbatasan seperti sifat fisik, kimia, dan biologi
tanah yang tidak baik serta topografi lahan yang kurang mendukung dalam
berusahatani. Untuk meningkatkan produktivitas lahan kering ada beberapa cara yang
perlu dilakukan seperti pemakaian varietas tanaman unggul, penerapan pola tanam
yang sesuai dengan curah hujan, perbaikan teknik budidaya tanaman, serta usaha
konservasi lahan sehingga kelestarian lahan dapat dijaga (Suprapto, 2000).
Ciri – Ciri Tanah Kritis
Ciri-ciri tanah kritis untuk budidaya tanaman yaitu tidak Subur dan miskin humus.
Dimana tanah tidak subur adalah tanah yang sedikit mengandung mineral/hara yang
dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Sedangkan tanah yang miskin humus
umumnya kurang baik untuk dijadikan lahan pertanian karena tanahnya kurang subur.
Tanah Humus adalah tanah yang telah bercampur dengan daun dan ranting pohon
Tujuan Rehabilitas Lahan Kritis
Menurut Setiadi (2001) langkah awal yang penting di dalam melaksanakan
rehabilitas lahan kritis adalahan mengidentifikasi kendala – kendala utama yang akan
berpengaruh dalam menetapkan tujuan dari penggunaan lahan tersebut mencakup :
(a). Protektif yakni meningkatkan stabilitas lahan, mempercepat penutupan tanah dan
mengurangi surface run off dan erosi tanah.
(b). Produktif yakni mengarah pada peningkatan kesuburan tanah ( soil fertility) yang
lebih produktif sehingga bisa diusahakan tanaman yang tidak saja menghasilkan
kayu tetapi juga menghasilkan produk non-kayu (rotan, getah, obat-obatan dan
buah-buahan) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya.
(c). Konservatif yakni kegiatan untuk membantu mempercepat terjadinya suksesi
secara alami kearah peningkatan biodiversity spesies lokal serta penyelamatan
dan pemanfaatan jenis – jenis tanaman potensial lokal yang telah langka.
Menurut Setiadi (2001) kendala utama dalam melakukan aktivitas rehabilitasi
pada lahan kritis adalah kondisi lahanya yang kritis bagi pertumbuhan tanaman.
Kondisi ini secara langsung akan mempengaruhi kualitas pertumbuhan tanaman dan
tingkat keberhasilannya dalam melaksanakan rehabilitasi. Untuk dapat mengatasi
masalah ini maka karakteristik fisik, kimia dan biologi tanah perlu diketahui sehingga
bisa diupayakan cara-cara perbaikannya yaitu :
a.Sifat Fisika Tanah
Sifat fisik tanah adalah sifat yang bertanggung jawab atas peredaran udara,
panas, air dan zat terlarut melalui tanah. Beberapa sifat fisika dapat mengalami
penggarapan tanah. Sifat fisika tanah yan penting adalah tekstur tanah, struktur tanah,
komposisi mineral, porositas, stabilitas, konsistensi, warna maupun suhu tanah. Sifat
tanah berperan dalam aktivitas perakaran tanaman, baik dalam hal absorbsi unsur
hara, air maupun oksigen juga sebagai pembatas gerakan akar tanaman (Hakim et
al.1986).
b. Sifat Kimia Tanah
Sifat kimia tanah adalah semua peristiwa yang bersifat kimia yang terjadi
inilah yang menentukan ciri dan sifat tanag yang akan terbentuk dan berkembang
(Hakim et al.1986).
Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh pH tanah melalui dua cara yaitu :
pengaruh langsung ion hidrogen dan pengaruh tidak langsung yakni tidak tersedianya
unsur hara tertentu dan adanya unsur – unsur yang beracun. Dari hasil penelitian di
Amerika latin diketahui bahwa batas maksimum dari pH tanah untuk berbagai jenis
tanaman yang masih perlu diberi kapur adalah pada pH 6. Batas pH yang dimaksud
menunjukan bahwa diatas pH ini tanaman yang bersangkutan tidak lagi memerlukan
kapur dan sebaliknya bila pH tanah dibawah nilai tersebut pertumbuhanya akan
terganggu.
c. Sifat Biologi Tanah
Hilangnya lapisan tanah dan serasah sebagai sumber Carbon (C) untuk
menyokong kelangsungan hidup mikroba tanah potensial merupakan salah satu
penyebab utama menurunnya populasi dan aktivitas mikroba tanah yang berfungsi
penting dalam penyediaan unsur – unsur hara (Setiadi, 2001).
Kompos sampah kota
Kompos adalah sampah organik yang telah mengalami proses pelapukan atau
dekomposisi akibat adanya interaksi mikroorganisme yang bekerja didalamnya.
Bahan – bahan organik yang biasa dipakai bisa berupa dedaunan, rumput, jerami, sisa
ranting atau dahan pohon, kotoran hewan, kembang yang telah gugur, air kencing
hewan, dan sampah dapur (Redaksi Agromedia, 2007).
Sampah pasar sebagai bagian dari sampah kota diharapkan memiliki tingkat
keamanan yang lebih tinggi daripada penggunaan kompos sampah kota yang selama
ini digunakan. Namun untuk dapat bermanfaat bagi perbaikan tanah dan produksi
tanaman maka sampah pasar harus mengalami proses pengomposan. Lamanya waktu
pengomposan berpengaruh terhadap kualitas kompos yang dihasilkan. Sehubungan
dengan upaya mendapatkan bahan baku kompos yang baik untuk produksi sayur
organik, perlu dilakukan penelitian mengenai lama waktu pengomposan sampah
hewan yang banyak digunakan dewasa ini (Redaksi Agromedia, 2007).
Pemberian kompos dapat memperbaiki struktur tanah. Pada tanah pasiran,
pemberian kompos dapat meningkatkan daya ikat partikel tanah. Sedangkan pada
tanah yang berat dapat mengurangi ikatan partikel tanah sehingga strukturnya
menjadi remah. Kompos dapat meningkatkan kapasitas menahan air, aktivitas
mikroorganisme di dalam tanah dan ketersediaan unsur hara tanah. Tetapi
penggunaan kompos yang mutunya rendah misalnya belum cukup matang dapat
mengakibatkan kerusakan tanaman karena C/N yang terlalu tinggi atau amonia yang
dihasilkannya. Jika C/N kompos yang diberikan ke dalam tanah terlalu tinggi
mengakibatkan tanaman kekurangan nitrogen (Sutejo, 2004).
Secara kimia, kompos dapat meningkatkan kapasitas kation (KTK),
ketersedian unsur hara, dan ketersedian asam humat. Asam humat akan membantu
meningkatkan proses pelapukan bahan mineral. Secara biologi, kompos yang tidak
lain bahan organik ini merupakan sumber makanan bagi mikroorganisme tanah.
Dengan adanya kompos, fungi, bakteri serta mikroorganisme menguntungkan lainnya
akan berkembang lebih cepat. Banyaknya mikroorganisme tanah yang
menguntungkan dapat menambah kesuburan tanah (Razali, 2008).
Pengomposan merupakan proses perombakan (dekomposisi) dan stabilisasi
bahan organik oleh mikroorganisme dalam keadaan lingkungan terkendali dengan
hasil akhir humus atau kompos. Hal ini bisa dilihat pada gambar dibawah :
Sumber :Nurhayati (2010)
Ada dua mekanisme proses pengomposan yakni pengomposan secara aerobik
dan pengomposan secara anerobik. Dimana pengomposan secara aerobik
membutuhkan oksigen dan air untuk merombak bahan organik
Mikroba aerob
Bahan organik CO2 + H2O + unsur hara + humus + energi
Pengomposan secara anaerobik berjalan tanpa adanya oksigen, yang
melibatkan mikroorganisme anaerob. Bahan baku yang dikomposkan secara anaerob
biasanya berupa bahan organik yang berkadar air tinggi (Suhut dan Salundik, 2006).
Faktor yang memepengaruhi proses pengomposan yaitu :
● Rasio C/N
Proses pengomposan akan berjalan baik jika rasio C/N bahan organik yang
dikomposkan sekitar 25 -35. Rasio C/N yang terlalu tinggi akan menyebabkan proses
pengomposan berlangsung lambat. Dimana keadaan ini disebabkan mikroorganisme
yang terlibat dalam proses kekurangan nitrogen. Sedangkan jika terlalu rendah akan
menyebabkan kehilangan nitrogen dalam bentuk ammonia yang selanjutnya akan
teroksidasi.
● Suhu pengomposan
Suhu optimum bagi pengomposan adalah 40 – 60oC dengan suhu maksimum
75 oC. Jika suhu pengomposan mencapai 40 oC, aktivitas mikroorganisme mesofil
akan digantikan oleh mikroorganisme termifil. Jika suhu mencapai 60 oC, fungi akan
berhenti bekerja dan proses pengomposan dilanjutkan oleh aktinomisetes serta strain
bakteri pembentuk spora (spore forming bacteria).
Suhu yang tinggi ini merupakan keadaan yang baik untuk menghasilkan kompos
yang steril karena selama suhu pengomposan lebih dari 60 oC (dipertahankan selama
tiga hari) mikroorganisme pathogen, parasit, dan benih gulma akan mati.
● Tingkat keasaman (pH)
Pengaturan pH selama proses pengomposan perlu dilakukan. Pada awal
pengomposan, reaksi cenderung agak asam karena bahan organik yang dirombak
menghasilkan asam – asam organik sederhana. Namun akan mulai naik sejalan
bahan yang dikomposkan terlalu asam, pH dapat dinaikkan dengan cara
menambahkan bahan yang bereaksi asam (mengandung nitrogen) seperti urea atau
kotoran hewan.
● Jenis mikroorganisme yang terlibat
Mikroorganisme diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu psikrofil, mesofil, dan
termofil. Mikroorganisme mesofil dapat hidup pada suhu 25 - 40 oC, Mikroorganisme
psikrofil dapat hidup pada suhu kurang dari 20 oC, Mikroorganisme termofil dapat
hidup pada suhu 65 oC. Namun yang terlibat dalam proses pengomposan yaitu
miroorganisme termofil dan mesofil.
Proses pengomposan bisa dipercepat dengan menambahkan aktivator yang
kandungan bahannya berupa mikroorganisme (kultur bakteri), enzim, dan asam
humat. Mikroorganisme yang ada dalam aktivator ini akan merangsang aktivitas
mikrooraganisme yang ada dalam bahan kompos sehingga cepat berkembang.
Akibatnya, mikroorganisme yang terlibat dalam pengomposan semakin banyak dan
proses dekomposisi akan semakin cepat.
● Aerasi
Aerasi (pengaturan udara) yang baik ke semua bagian tumpukan bahan kompos
sangat penting untuk menyediakan oksigen bagi mikroorganisme dan membebaskan
CO2 yang dihasilkan. Karbondioksida yang dihasilkan harus dibuang agar tidak
menimbulkan zat beracun yang merugikan mikroorganisme sehingga bisa
menghambat aktivitasnya.
Dimana pengaturan aerasi dilakukan dengan cara membalikkan tumpukan bahan
kompos secara teratur. Selain itu, bisa juga dengan pergerakan udara secara alami
kedalam tumpukan kompos melalui saluran aerasi yang dibuat dari batang bambu.
● Kelembaban (RH)
kelembaban opotimum untuk proses pengomposan aerobik sekitar 50 – 60 %
setelah bahan organic dicampur. Kelembapan campuran baha kompos yang rendah
(kekurangan air) akan menghambat proses pengomposan dan akan menguapkan
nitrogen ke udara. Namun jika kelembapannya tinggi (kelebihan air) proses
dalam tumpukan bahan kompos akan terganggu. Pori – pori udara yang ada dalam
tumpukan bahan kompos akan diisi air dan cenderung menimbulkan kondisi
anaerobik.
● Struktur bahan baku
Sifat bahan organik juga tergantung dari sifat bahan yang akan dikomposkan.
Sifat bahan tanaman tersebut antara lain jenis tanaman, umur, dan komposisi kimia
tanaman. Semakin muda umur tanaman, proses dekomposisi akan berlangsung lebih
cepat. Hal ini disebabkan kadar airnya masih tinggi, kadar nitrogen tinggi, imbangan
C/N yang sempit, serta kandungan lignin yang rendah.
● Ukuran bahan baku
Semakin kecil ukuran bahan (5-10 cm), proses pengomposan berlangsung
semakin cepat. Hal ini karena adanya peningkatan luas permukaan bahan untuk
”diserang” mikroorganisme. Ukuran bahan yang kurang dari 5 cm akan mengurangi
pergerakan udara yang masuk ke dalam timbunan dan pergerakan CO2 yang keluar.
Sebaliknya, ukuran bahan yang terlalu besar meyebabkan luas permukaan yang
”diserang” akan menurun sehingga proses dekomposisi berlangsung lambat bahkan
bisa berhenti sama sekali.
● Pengadukan (Homogenisasi)
Bahan baku kompos terdiri dari campuran berbagai bahan organik yang memiliki
sifat terdekomposisi berbeda (ada yang mudah dan ada yang sukar terdekomposisi).
Apabila campuran bahan ini tidak diaduk maka proses dekomposisi tidak berjalan
secara merata. Akibatnya, kompos yang dihasilkan kurang bagus (Suhut dan
Salundik, 2006).
Standar kualitas kompos biasanya diidentikkan dengan kandungan unsur hara
yang ada didalamnya, kadarnya sangat tergantung dari bahan baku atau proses
pengomposan. Kompos dikatakan bagus dan siap diaplikasikan jika tingkat
kematanganya sempurna. Kompos yang matang biasa dikenali dengan
memperhatikan keadaan bentuk fisiknya sebagai berikut :
1. Jika diraba, suhu tumpukan bahan yang dikomposkan sudah dingin,
2. Tidak mengeluarkan bau busuk lagi.
3. Bentuk fisiknya sudah menyerupai tanah yang berwarna kehitaman.
4. Jika dilarutkan kedalam air, kompos yang sudah matang tidak akan larut.
5. Struktur remah, tidak menggumpal
Jika dianalisi di Laboratorium, kompos yang sudah matang akan memiliki ciri
sebagai berikut :
1. Tingkat kemasaman (pH) kompos agak asam sampai netral (6,5 -7,5).
2. Memiliki C/N sebesar 10-20.
3. Kapasitas tukar kation (KTK) tinggi, mencapai 110 me / 100gram.
4. Daya absorbsi (penyerapan) air tinggi
5. Mengandung unsure hara seperti yang tertera pada tabel 1.
Tabel 1. Kandungan unsur hara dalam kompos yaitu :
Unsur hara Jumlah
Sumber : Nan Djuarni, Kristian dan Budi ( 2005) dalam Suhut dan Salundik,2006.
Kesuburan dan kegemburan tanah akan terjaga jika kita selalu menambahkan
bahan organik, salah satunya. Pemakaian kompos sangat dianjurkan karena dapat
memperbaiki produktivitas tanah, baik secara fisik, kimia ataupun biologi tanah.
Secara fisik, kompos bisa menggemburkan tanah, memperbaiki aerasi dan drainase,
mencegah erosi dan longsor, mengurangi tercucinya nitrogen terlarut, serta
memperbaki daya olah tanah (Suhut dan Salundik, 2006).
Botani Sengon
Sengon yang dalam bahasa Latin disebut Albizia falcataria, termasuk famili
Mimosaceae, keluarga petai – petaian. Kadang – kadang sengon disebut pula
” albisia” yang sesungguhnya berasal dari bahasa Latin tersebut. Di Indonesia, sengon
memiliki beberapa nama daerah seperti berikut ini :
● Jawa : jeunjing, jeunjing laut (sunda), kalbi, sengon landi, sengon laut atau sengon sabrang (jawa)
● Maluku: seia (ambon), sikat (banda), tawa (Ternate) dan gosui (tidore)
Tajuk tanaman sengon berbentuk menyerupai payung yang tidak rimbun
daunnya. Kita ketahui daun sengon tersusun majemuk menyirip ganda sedangkan
anak daunnya kecil – kecil dan mudah rontok ; daunnya yang rontok itu justru cepat
meningkatkan kesuburan tanah. , Warna daun sengon hijau pupus, berfungsi untuk
memasak makanan dan sekaligus sebagai penyerap nitrogen (N2) dan karbon dioksida
(CO2) dari udara bebas.
Bunga tanaman sengon tersusun dalam bentuk malai berukuran sekitar 0,5 –
1cm, berwarna putih kekuning-kuningan dan sedikit berbulu. Setiap kuntum bunga
mekar terdiri dari bunga jantan dan bunga betina, dengan cara penyerbukan yang
dibantu oleh angin atau serangga. Buah sengon berbentuk polong, pipih, tipis, dan
panjangnya sekitar 6 – 12 cm. Setiap polong buah berisi 15 – 30 biji. Bentuk biji
mirip perisai kecil dan jika sudah tua biji akan berwarna coklat kehitaman,agak keras,
Habitat Sengon
Tanaman Sengon dapat tumbuh baik pada tanah Regosol, Aluvial, dan Latosol
yang bertekstur lempung berpasir atau lempung berdebu dengan kemasaman tanah
sekitar pH 6-7. Ketinggian tempat yang optimal untuk tanaman sengon antara 0 – 800
m dpl. Walapun demikian tanaman sengon ini masih dapat tumbuh sampai ketinggian
1500 m di atas permukaan laut. Sengon termasuk jenis tanaman tropis, sehingga
untuk tumbuhnya memerlukan suhu sekitar 18 ° – 27 °C. Curah hujan mempunyai
beberapa fungsi untuk tanaman, diantaranya sebagai pelarut zat nutrisi, pembentuk
gula dan pati, sarana transpor hara dalam tanaman, pertumbuhan sel dan
pembentukan enzim, dan menjaga stabilitas suhu. Tanaman sengon membutuhkan
batas curah hujan minimum yang sesuai, yaitu 15 hari hujan dalam 4 bulan terkering,
namun juga tidak terlalu basah, dan memiliki curah hujan tahunan yang berkisar
antara 2000 – 4000 mm. Kelembaban juga mempengaruhi setiap tanaman. Reaksi
setiap tanaman terhadap kelembaban tergantung pada jenis tanaman itu sendiri.
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini terdiri dari 2 tahap yaitu penelitian tentang perbedaan kualitas
kompos dan pengaplikasian kompos sampah kota pada bibit sengon.
A. PERBEDAAN KUALITAS KOMPOS Lokasi dan Waktu penelitian
Pengomposan sampah kota dilaksanakan di Tempat Pengeringan Tanah,
Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan bulan September sampai
November 2009.
Alat dan Bahan
Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah cangkul, sekop, ember, terpal
atau plastik besar, tali plastik, kamera dan alat tulis lainnya yang mendukung
penelitian.
Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah Bahan organik (rumput,
sayuran, buah – buahan), Kotoran ternak (kotoran sapi), tanah dari lahan kritis di
Simalingkar B , pupuk dolomit dari pasar 7 Padang Bulan, air, dan EM4.
Metode penelitian
Faktor perlakuan yang diuji terdiri dari 2 faktor yaitu Kompos sampah kota
tanpa EM4 dan Kompos sampah kota dengan EM4. Dan dilanjutkan dengan uji T.
Pelaksanaan penelitian
1. Pengomposan Sampah kota berupa sampah organik secara tradisional
Bahan :
● Bahan organik (rumput, sayuran, buah – buahan, ampas makanan) masing –
masing 30 kg
● Kotoran ternak (kotoran sapi) 10 kg
● Tanah dari lahan kritis di Simalingkar B sebanyak 20 kg
● Pupuk dolomit sebanyak 250 gram
Teknik pembuatan :
1. Semua bahan disiapkan
2. Bahan organik dicacah hingga ukurannya lebih kecil (sekitar 2 cm)
3. Cacahan bahan organik dicampurkan dengan kotoran ternak, tanah topsoil,
dan pupuk dolomit lalu disiram dengan air sedikit demi sedikit sambil diaduk
– aduk menggunakan sekop hingga semua bahan tercampur rata. Penambahan
air dilakukan sampai kadar air campuran bahan 40 – 60%. Tandanya, jika
campuran bahan tadi digenggam lalu dilepaskan lagi akan tetap menggumpal
tetapi jika disentuh jari akan pecah.
4. Campuran bahan ditumpukan di atas lantai semen, lalu ditancapkan bambu
yang sudah diberi lubang pada tumpukan bahan untuk memberikan sirkulasi
udara. Tumpukan tersebut harus dibalik setiap minggu. Jika pada dua minggu
pertama, tumpukan bahan terlalu kering harus disiram kembali. Pada minggu
selanjutnya, tumpukan bahan kompos tidak perlu disiram lagi.
5. Diperiksa kematangan kompos dengan cara mengamati warnanya akan hitam
dan masih basah atau lembab maka kompos yang dihasilkan bagus.
6. Kompos yang sudah jadi dikering anginkan dengan cara menebar tipis
ditempat yang ternaungi (jangan terkena sinar matahari langsung).
7. Kompos yang sudah kering digiling atau diayak hingga ukurannya seragam
dan halus.
2. Pengomposan Sampah kota berupa sampah organik dengan aktivator EM4 (Bokashi)
Bahan :
● Bahan organik (rumput, sayuran, buah – buahan, ampas makanan)
masing-masing 30 kg
● Kotoran ternak (kotoran sapi) sebanyak 10 kg
● EM4 50 ml
Teknik pembuatan :
1. Semua bahan cair dicampurkan (EM4 dan air) dan diaduk rata
2. Bahan organik dicacah hingga ukurannya lebih kecil dan dicampur dengan
kotoran ternak.
3. Campuran bahan padat disiram dengan larutan EM4, diaduk – aduk hingga
larutan bercampur merata. Kadar air campuran bahan sekitar 30-40% yang
ditandai dengan tidak adanya tetesan air jika bahan digenggam dan akan
mekar jika genggaman bahan dilepas.
4. Campuran bahan ditumpukan diatas tempat kering dengan ketinggian 40 – 50
cm lalu ditutup dengan plastik atau terpal. Campuran bahan kompos juga bisa
difermentasi dalam ember atau kantong plastik.
5. Suhu tumpukan bahan kompos dipertahankan 40 – 500C. Suhu bahan kompos
harus dikontrol setiap hari dengan cara mengaduk – aduk bahan tersebut agar
suhunya tidak tinggi.
6. Proses pengomposan dengan bantuan aktivator EM4 berlangsung selama 30
hari. Setelah 30 hari kompos matang dan siap digunakan.
Parameter yang diamati dari pengomposan ini yaitu kualitas kompos dengan
menganalisis kandungan hara seperti C-organik, Ntotal, pH, C/N, P tersedia, K-dd,
B. APLIKASI KOMPOS PADA BIBIT SENGON Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Kasa, Fakultas Pertanian Universitas
Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan bulan November 2009 sampai Maret
2010.
Alat dan Bahan
Alat – alat yang akan digunakan pada penelitian ini adalah label nama,
polibag, bak kecambah, ajir, handspray, kamera dan alat tulis.
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih sengon, air, pasir
steril, pupuk majemuk NPK, dan contoh tanah dari lahan kritis di Simalingkar B.
Metode Penelitian
Metode yang digunakan yaitu RAK (Rancangan Acak Kelompok) non
faktorial. Dimana terdapat 9 kombinasi yang digunakan yaitu :
A = NPK
Dimana 9 kombinasi diulang sebanyak 3 kali sehingga didapat 27 sampel contoh
untuk penelitian.
Menurut Sastrosupadi (2000) model Rancangan Acak Kelompok (RAK)
faktorial yang digunakan percobaan.di dalam percobaan ini adalah :
Y
ij =µ + Bi + Kj +
ε
ij
Keterangan :
Yij = Nilai pengamatan kompos ke-i dan blok ke-j
µ = rataan umum
Bi = pengaruh blok ke-i
Kj = pengaruh kompos ke-j
εij = galat blok ke-i , kompos ke-j
selanjutnya dilakukan Analisis data dengan uji F hipotesis dengan kriteria
adalah :
● jika F hitung > F tabel 5%, maka perlakuan berpengaruh nyata
artinya hipotesis penelitian (H1) diterima pada taraf uji 5%.
● jika F hitung < F tabel 5%, maka perlakuan berpengaruh tidak nyata Artinya (H0) diterima atau hipotesis penelitian salah (ditolak).
apabila hasil analisis sidik ragam menunjukkan adanya perbedaan yang nyata maka
Pelaksanaan penelitian
Pelaksanaan analisis tanah dan kompos dilakukan di Labotarorium Central, Fakultas
Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa
kegiatan yaitu :
1. Penyediaan tanah
Tanah yang digunakan pada penelitian merupakan tanah bagian atas yang diambil
dengan kedalaman 0 – 20cm. Jenis tanah yang digunakan adalah jenis Ultisol
yang diambil dari daerah Simalingkar secara komposit. Tanah terlebih dahulu
dikering anginkan selama 1 – 3 hari, lalu diayak dengan ayakan 20 mesh
kemudian dianalisis. Analisis tanah meliputi pH, C-organik, N-total, C/N, P
tesedia, K-dd, KTK dan Al-dd. Tanah dimasukkan ke polibag 1 kg/polibag dan
disusun. Hal ini dapat dilihat pada lampiran 1.
2. Pengomposan sampah kota
Kompos sampah kota didapat dari sampah pasar tepatnya di pajak pagi pasar
V yang terdiri dari sampah jenis sayur-sayuran dan buah-buahan.Dimana
bahan- bahan ini dipotong kecil- kecil seperti dadu. Kemudian diberi
perlakuan yaitu memakai EM4 dan tanpa EM4. Kemudian kompos dengan
EM4 ditutup selama 1 bulan sedangkan kompos tanpa EM4 ditutup selama 1
bulan 20 hari. Setelah itu kompos dikering anginkan selama 1 hari lalu diayak
memakai ayakan 20 mesh. Setelah diayak kompos dianalisis. Analisis kompos
meliputi pH, C-organik, N-total, C/N, P tesedia, K-dd, KTK dan Al-dd.
3. Pengukuran kadar air kering udara dan kadar air kapasitas lapang
Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui jumlah air penyiraman setiap
perlakuan. Prosedur pengukuran kadar kering udara dan kapasitas lapang
dapat dilihat pada lampiran 2.
4. Penyedian bibit
Bibit didapat dari tempat Pembibitan Sembiring di pasar 7 Padang Bulan.
Dimana bibit berumur 1 bulan 10 hari dengan tinggi rata- rata hampir sama
5. Pencampuran media tumbuh
Media tanam yang digunakan adalah kompos sampah kota dan tanah dari
Simalingkar B dengan perbandingan yang telah ditentukan lalu dilakukan
pencampuran sesuai dengan perbandingan tersebut. Kemudian komposisi
media dimasukkan dalam polibag dengan 9 kombinasi perlakuan dengan 3
kali ulangan. Selanjutnya dilakukan masa inkubasi selama 3 hari untuk
menyatunya tanah dengan kompos.
6. Pemindahan bibit ke media tanam dan pemberian pupuk
Bibit yang telah disediakan dipindahkan ke dalam polibag yang telah diisi
dengan tanah dicampur dengan kompos sesuai perbandingan. Kemudian
diberi pupuk NPK dengan dosis 12 butir setiap polibag. Hal ini disesuaikan
dari rekomendasi pembibitan sengon.
7. Penyiraman dan Pemeliharaan
Setelah bibit dipindahkan ke polibag tanaman kemudian disiram sesuai
dengan takaran air yang didapat dari analisis data pengukuran kadar air.
Penyiraman dilakukan dengan menggunakan aqua cup tetapi disesuaikan
dengan kondisi di lapangan. Jika media masih lembab maka tidak perlu
disiram karena akan menyebabkan busuk akar. Kemudian dilakukan
penyiangan pada tanaman ketika rumput atau gulma mulai muncul agar tidak
mengganggu perakaran tanaman.
8. Parameter pengamatan
a. Pertambahan tinggi
Tinggi tanaman diukur seminggu sekali dengan menggunakan penggaris.
Pengukuran tinggi tanaman ini dimulai dari bagian batang tanaman diatas
permukaan tanah sampai pucuk daun yang tertinggi.
b. Pertambahan diameter
Pengukuran diameter dilakukan seminggu sekali dengan menggunakan
jangka sorong. Setiap melakukan pengukuran diameter tanaman dilakukan
c. Jumlah daun
Jumlah daun juga diukur seminggu sekali dengan menghitung jumlah
daun yang ada pada tanaman.
d. Bobot kering tajuk dan bobot kering akar
Pada saat tanaman berumur 13 minggu setelah tanam maka dilakukan
pemotongan bagian atas tanaman (batang dan daun). Untuk mendapatkan
rasio tajuk akar, bagian atas tanaman (batang dan daun) dicuci dengan air
dan dibiarkan kering. Kemudian dimasukkan ke dalam amplop yang telah
diberi lobang dan label sesuai dengan perlakuan. Kemudian diovenkan
selama 24 jam dengan suhu 600C – 800C. Hal diatas juga dilakukan pada
bagian bawah tanaman (akar) dimana bagian akar dipisahkan, dicuci
dengan air dan dibiarkan kering. Kemudian dimasukkan ke dalam amplop
yang telah diberi lobang dan label sesuai dengan perlakuaan. Kemudian
diovenkan selama 24 jam dengan suhu 600C -800C.Lalu ditimbang berat
kering dari bagian atas tanaman (batang dan daun) dan bagian bawah
tanaman(akar) tersebut. Setelah itu dicatat data yang didapat dan dihitung
dengan menggunakan rumus rasio tajuk akar
e. Rasio tajuk akar
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Kualitas kompos
Hasil penelitian didapat bahwa kualitas kompos yang baik yaitu kompos
sampah kota dengan EM4. Dimana pH kompos dengan EM4 adalah 7,41 sedangkan
pH kompos tradisional 7,82. Dan nilai C/N nya lebih tinggi dari nilai C/N pada
kompos tradisional yaitu 7,81 sedangkan kompos tradisional 6,65. Hal ini sesuai
dengan Suhut dan Salundik (2006) yang menyatakan bahwa kompos yang baik dan
sudah matang tingkat keasamannya (pH) berkisar antara 6,5 – 7,5 dan memiliki C/N
sebesar 10-20. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Data analisis kompos dengan EM4 dan kompos tanpa EM4
Karakteristik
Komp.trad : kompos sampah kota secara tradisional Komp.EM4: kompos sampah kota dengan EM4 tt : tidak terdeteksi
Pertambahan Tinggi
Hasil pengukuran dan analisis sidik ragam tinggi tanaman sengon terdapat
pada lampiran 3 dan 4 didapat tidak berpengaruh nyata terhadap pertambahan tinggi
tanaman sengon. Dimana rataan tinggi tanaman sengon umur 4 minggu sampai 13
Tabel 3. Data rataan tinggi tanaman sengon umur 4 minggu – 13 minggu
Dengan memberikan beberapa dosis kompos sampah kota terhadap bibit
sengon dapat dilihat bahwa rataan tinggi yang lebih tinggi terdapat pada dosis
perlakuan G (NPK + 10 gr kompos sampah kota dengan EM4) yaitu 24,83 cm yang
didapat pada waktu 13 minggu dimana pada saat awal penanaman tinggi bibit sengon
yaitu 3,67cm. Dan dapat dilihat bahwa semakin tinggi dosis yang diberikan maka
tinggi tanaman semakin berkurang. Jadi tanaman sengon akan tumbuh baik apabila
diberikan dosis yaitu 10 gr kompos sampah kota dengan EM4. Dari tabel diatas dapat
juga diambil kesimpulan bahwa dosis yang baik untuk pertumbuhan tanaman sengon
terdapat pada perlakuan D (NPK+15 gr kompos tradisional), E (NPK + 20gr kompos
tradisional), G (NPK+ 10gr kompos dengan EM4) dan perlakuan H (NPK+ 15 gr
kompos EM4) lebih baik dibandingkan dengan perlakuan Kontrol. Jadi tinggi
tanaman sengon lebih baik dengan menggunakan kompos dibandingkan dengan
0
Gambar 2.Diagram perbedaan tinggi tanaman sengon umur 4 minggu dan 13 minggu pada perlakuan kompos sampah kota
Pertambahan diameter batang
Hasil pengukuran dan analisis sidik ragam diameter tanaman terdapat pada
lampiran 5 dan 6 didapat bahwa aplikasi kompos tidak berpengaruh nyata terhadap
diameter tanaman sengon. Dimana rataan diameter tanaman sengon umur 4 minggu
sampai 13 minggu dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Rataan diameter batang tanaman sengon umur 4 minggu – 13 minggu
Keterangan :
Perlakuan Pengamatan pada minggu ke –
36
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian beberapa dosis kompos sampah
kota terhadap bibit sengon yang baik terdapat pada perlakuan D (NPK+15 gr kompos
tradisional) dan perlakuan E (NPK+ 20 gr kompos tradisional) dibandingkan dengan
perlakuan pada kontrol dan perlakuan pemberian kompos dengan EM4. Hal ini dapat
dilihat pada gambar 3.
Gambar 3. Diagram perbedaan diameter batang tanaman sengon umur 4 minggu dan 13 minggu pada perlakuan kompos sampah kota
Pertambahan jumlah anak daun
Hasil pengukuran dan analisis sidik ragam jumlah anak daun terdapat pada
lampiran 7 dan 8 didapat bahwa aplikasi kompos tidak berpengaruh nyata terhadap
jumlah anak daun tanaman sengon. Dimana rataan jumlah anak daun tanaman sengon
umur 4 minggu sampai 13 minggu dapat dilihat pada tabel 5.
37
Dari tabel 5. diatas dapat disimpulkan bahwa pada umur 4 minggu dan 5 minggu
jumlah anak daun berkurang. Hal ini terjadi dikarenakan terjadinya keguguran daun. Dan
pemberian beberapa dosis kompos sampah kota dengan EM4 menghasilkan jumlah anak
daun pada perlakuan G (NPK + 10 gr kompos dengan EM4), perlakuan H(NPK+15 gr
kompos dengan EM4), perlakuan I (NPK +20gr kompos dengan EM4) dan perlakuan F
(NPK+5gr kompos dengan EM4) lebih banyak dari pada perlakuan kontrol dan
pemberian kompos tanpa EM4 terhadap bibit sengon. Hal ini dapat dilihat pada gambar
4.
Gambar 4. Diagram perbedaan jumlah anak daun tanaman sengon umur 4 minggu dan 13minggu pada perlakuan kompos sampah kota
Bobot kering tajuk dan Bobot kering akar
Hasil penelitian didapat bobot kering tajuk yang tinggi terdapat pada perlakuan G
38
yaitu 22,7. Untuk bobot kering akar yang tinggi terdapat pada perlakuan kontrol. Hal ini
disebabkan jumlah akar tunggang pada perlakuan kontrol lebih banyak daripada jumlah
akar tunggang pada perlakuan dosis. Hal ini dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. Data bobot kering tajuk, bobot kering akar tanaman sengon dan rasio tajuk akar tanaman sengon umur 4 minggu sampai 13 minggu
Perlakuan Bobot kering tajuk Bobot kering akar Rasio tajuk akar
Berdasarkan hasil analisis data didapat bahwa rasio tajuk akar yang paling besar
yaitu terdapat pada dosis perlakuan B (NPK + 5gr kompos sampah kota secara
tradisional) yaitu sebesar 6,25 dan rasio tajuk akar yang paling sedikit terdapat pada dosis
perlakuan A (NPK). Data ini didapat dari hasil pembagian antara rataan berat tajuk dan
39
Gambar 5. Diagram perbedaan rasio tajuk akar bibit sengon umur 4 minggu sampai 13 minggu pada perlakuan kompos sampah kota
Pembahasan
Hasil proses pengomposan didapat bahwa kualitas kompos yang baik yaitu
kompos sampah kota dengan EM4. Dimana pH kompos dengan EM4 adalah 7,41
sedangkan pH kompos tradisional 7,82. Dan nilai C/N nya lebih tinggi dari nilai C/N
pada kompos tradisional yaitu 7,81 sedangkan kompos tradisional 6,65. Hal ini sesuai
dengan pernyataan Suhut dan Salundik (2006) yang mengatakan bahwa kompos yang
baik dan sudah matang tingkat keasamannya (pH) berkisar antara 6,5 – 7,5 dan memiliki
C/N sebesar 10-20 dan untuk KTK sebesar 110me/100g. Sedangkan untuk hasil analisis
kompos nilai C/N yang didapat pada kompos tanpa EM4 yaitu 6,65 dan kompos dengan
EM4 yaitu 7,81.Untuk KTK nya sebesar 14,51 (me/100g). Padahal nisbah C/N dari bahan
organik merupakan faktor yang sangat penting dalam pengomposan. Transformasi
organik menjadi pupuk didominasi oleh proses mikrobiologi dan dipengaruhi nisbah C/N
bahan yang ada dalam residu kompos. Selama proses pengomposan mikroorganisme,
diperlukan sumber karbon untuk menyediakan energi dan bahan untuk membentuk sel-sel
baru serta memerlukan nitrogen (N) untuk mensintesis protein. Agar optimal, keperluan
karbon dan nitrogen untuk pengomposan adalah 30-40. Dan untukkandungan C-Organik
pada kompos turun karena bahan organik mengalami dekomposisi yang dibantu
mikroorganisme yang diberikan yaitu EM-4. Dimana komposisi dari EM4 dapat dilihat
pada lampiran 10. Pada proses dekomposisi secara aerobik, mikroorganisme yang
40
nitrogen, fosfor, sulfur dan unsur lainnya, untuk mensintesa protoplasma sel mereka.
Karbon berguna sebagai sumber energi dan pembangun protoplasma selnya, jumlah
karbon yang diasimilasi lebih besar dibandingkan nitrogen. Umumnya sekitar 2/3 dari
karbon dibebaskan sebagai CO2 dan 1/3 bagian bersenyawa dengan nitrogen dalam sel
hidup mikroorganisme.
Secara kimia, kompos dapat meningkatkan kapasitas kation (KTK), ketersedian
unsur hara, dan ketersedian asam humat. Asam humat akan membantu meningkatkan
proses pelapukan bahan mineral. Secara biologi, kompos yang tidak lain bahan organic
ini merupakan sumber makanan bagi mikroorganisme tanah. Dengan adanya kompos,
fungi, bakteri serta mikroorganisme menguntungkan lainnya akan berkembang lebih
cepat. Banyaknya mikroorganisme tanah yang menguntungkan dapat menambah
kesuburan tanah.
Pada hasil pengomposan, kandungan unsur hara yang ada dalam kompos yang
diteliti rendah . Hal ini disebabkan saat proses pengomposan kandungan N pada sayur
yang masih segar 1,29 % namun setelah pengomposan 30 hari menjadi 1,11%.
Kandungan C-Organik pada sayur yang masih segar 14,42 %, setelah mengalami
pengomposan selama 45 hari menjadi 13,65 %, Kandungan K pada sayur yang masih
segar 0,00058%, setelah mengalami pengomposan selama 30 hari menjadi 1,22 persen.
Padahal kita ketahui bahwa kandungan unsur hara Nitrogen (N) yang baik dalam kompos
yaitu 1,33%. Sehingga saat proses pengomposan berlangsung kompos yang dihasilkan
tidak terlalu baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutedjo (2004) yang menyatakan
bahwa jika kadar N cukup tinggi, maka kompos cukup baik sebagai sumber hara, tetapi
kadar unsur mikro (Fe, Mn, Cu dan Za) tidak boleh terlalu tinggi.
Pada saat proses pengomposan, kompos sampah kota dengan EM4 berlangsung
dengan cepat dibandingkan dengan proses pengomposan sampah kota tanpa EM4. Hal ini
diakibatkan faktor penggunaan EM4, dimana EM4 adalah kultur campuran dari
mikroorganisme bermanfaat dan hidup secara alami serta digunakan sebagai inokulan
sehingga terdapat keragaman mikroorganisme tanah. Hal ini dapat meningkatkan kualitas
tanah, kesehatan tanah, pertumbuhan serta kualitas tanaman. EM4 sangat efektif untuk
menginokulasi sampah seperti sampah organik, untuk mempercepat penguraian sampah
41
Actinomycetes dan bakteri fotosintesis, mampu bersimbiosis satu dengan yang lain
sehingga efektif dalam menguraikan sampah. Manfaat EM-4 Pertanian yaitu
memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah, mempercepat proses fermentasi pada
pembuatan kompos, meningkatkan ketersediaan nutrisi tanaman, serta menekan aktivitas
serangga hama dan mikroorganisme patogen dan meningkatkan dan menjaga kestabilan
produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi. Sehingga tanaman pada perlakuan
pemberian kompos EM4 lebih tahan terhadap serangan hama dibandingkan dengan
tanaman pada kontrol dan perlakuan pemberian kompos tradisional. Hal ini dapat
dibuktikan dengan pada minggu ketiga, tanaman sengon pada perlakuan kontrol terkena
serangan hama dan kemudian disusul minggu keempat tanaman sengon dengan perlakuan
pemberian kompos tradisional.
Hasil analisis sidik ragam pada lampiran 4, 6 dan 8 didapat bahwa pemberian
kompos sampah kota terhadap sengon tidak berpengaruh nyata, baik dilihat dari tinggi,
diameter batang dan jumlah anak daun. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor
yang mempengaruhi yaitu faktor kompos berupa kualitas kompos, kandungan hara, sifat
kompos dan pemberian dosis dan faktor dari tanaman sengon, dimana sengon merupakan
tanaman yang fast growing dan tanaman toleran.
Dari beberapa perlakuan didapat bahwa tinggi tanaman dan jumlah anak daun
yang baik terdapat pada perlakuan G (NPK+ 10gr kompos dengan EM4) dan H (NPK+15
gr kompos dengan EM4). Sedangkan dari pengamatan diameter didapat bahwa diameter
tanaman sengon yang baik terdapat pada perlakuan D(NPK +15 gr kompos tradisional)
dan E (NPK+20 gr kompos tradisional). Hal ini menunjukan bahwa tanaman sengon akan
tumbuh dengan baik pada dosis perlakuan D, E, G, dan perlakuan H . Sedangkan menurut
Hieronymus (1992) menyatakan bahwa tanaman sengon dapat tumbuh baik pada tanah
Regosol, Aluvial, dan Latosol dengan pH 6-7. Sementara dari hasil analisis tanah pada
lampiran 9 didapat bahwa pH contoh tanah dari Simalingkar B sebesar 4,65. Oleh karena
itu kompos ini dapat diaplikasikan ke tanah lahan kritis untuk memperbaiki struktur tanah
42
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
43
1. Kualitas kompos sampah kota dengan EM4 lebih baik dari kompos sampah kota
tanpa EM4
2. Pertumbuhan bibit sengon pada perlakuan G (NPK+ 10 gr kompos dengan EM4),
H (NPK+15 gr kompos dengan EM4), D (NPK+ 15 gr kompos tradisional) dan E
(NPK+20 gr kompos tradisional) lebih baik dibandingkan dengan bibit yang
hanya diberi NPK saja.
Saran
Untuk menghasilkan bibit sengon yang baik pada media tanah lahan kritis perlu
diaplikasikan kompos sampah kota sesuai dengan dosis pada perlakuan G (NPK+ 10 gr
kompos dengan EM4) dan H (NPK+15 gr kompos dengan EM4), atau pada D (NPK+ 15
gr kompos tradisional) dan E (NPK+20 gr kompos tradisional).
DAFTAR PUSTAKA
BPDAS-Pemalijratun. 2007. Lahan Kritis
pemalijratun.net/index.php.article lahan-kritis:wilayah-kerja. [13 Maret 2009]
44
Hakim , N.M.Y. Nyakpa, A.M. Lubis, S.E. Nugroho, M.A.Diha, Go, Ban Hong, H.H. Bailey.1986. Dasar – dasar Ilmu Tanah. Universitas Lampung.
.
Hasibuan, B.E. 2006. Pengolalaan Tanah dan Air, Lahan marginal. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Medan
Hieronymus, B. 1992.Budidaya Sengon. Kanisius. Yogyakarta.
Isroi. 2008. Kompos. Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia. Bogor.
Mawar, D. 2008. Pengaruh Pembalikan, OrgadeK Dan Nitrogen Terhadap Laju Pengomposan Sampah Organik Serta Kualitas Kompos Yang Terbentuk Dalam Rangka Perbaikan Kebersihan Lingkungan Hidup. http://library.usu.ac.id. [26 Februari 2009]
Nurhayati. 2010. Pemanfaatan Kompos Sampah Pasar untuk Budidaya Sawi Organik.UISU. Medan. http://www.bitra.or.id. [ 7 Juni 2010]
Razali. 2008. Pengomposan Dan Pengaruh Pemberian Kompos, Pupuk Biologi Serta Amandemen Terhadap Pertumbuhan, Ketersediaan Dan Serapan Hara Tanaman Kedelai Pada Tanah Ultisol Langkat.
Redaksi Agromedia. 2007. Petunjuk Pemupukan. Agromedia. Jakarta
Sastrosupadi, A.2000. Rancangan percobaan praktis di bidang pertanian edisi revisi. Kanisius. Yogyakarta.
Setiadi,Y. 2001. Peran Mikoriza Arbuskula Untuk Merehabilitas Lahan Kritis Pasca Tambang. Makalah Disamapaikan Pada Workshop Cendawan Mikoriza Arbuskula Pada Tanaman Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan. Tanggal 5 -10 Oktober 1998. PAU Bioteknologi IPB. Bogor.
Setiawan. A.I. 2003. Penghijauan Lahan Kritis. Penebar Swadaya. Jakarta.
Suhut, S dan Salundik. 2006. Meningkatkan Kualitas Kompos. Agromedia. Jakarta.
Suprapto. 2000. Berbagai Masukan Teknologi Untuk Meningkatkan Produktivitas Lahan Marginal.http://:www.pustaka.deptan.go.id.[13 Maret 2009]
45
Lampiran 1. Skema penanaman di rumah kasa
A2
A1 A3
46
C1
C2 C3
D1 D2 D3
E1 E2 E3
F1 F2 F3
G1 G3
H3 H1
G2
H2
47
Lampiran 2. Prosedur menghitung kadar air kering udara
Adapun langkah – langkah yang dilakukan sebagai berikut :
b. Ditimbang 10 gr tanah kering udara dan dimasukkan ke dalam cawan.
c. Dimasukkan cawan ke dalam oven selama 5 jam pada suhu 1050C.
d. Kemudian dimasukkan ke dalam desikator pendingin lalu ditimbang dan akhirnya
diperoleh data berat kering konstan.
e. Kemudian dihitung persentase kadar air kering udara dengan rumus
BTKU – BTKO
% KA = X 100% BTKO
Ket :
% KA : persentase kadar air
BTKU : Berat tanah kering udara
BTKO : Berat tanah kering diovenkan
Selanjutnya dilakukan pengukuran kadar air kapasitas lapang tanah unttuk menentukkan
jumlah air yang akan diberikan pada tanaman. Prosedur pengukuran kadar air kapasitas
lapang adalah sebagai berikut :
a. Disiapkan gelas ukur dengan ukuran 300 ml
b. Pasir dimasukkan kedalam gelas ukur sebanyak 1/3 dari gelas ukur.
c. Pipet plastik diletakkan ditengah – tengah gelas ukur diatas pasir.
d. Tanah kering udara dimasukkan ke dalam gelas ukur sebanyak 2/3 dari gelas ukur.
e. Dimasukkan air sedikit demi sedikit sampai batas permukaan pasir.
f. Gelas ukur ditutup dengan plastik dan diberi lubang pada pipet.
g. Dibiarkan selama 24 jam.
h. Diambil tanah pada bagian tengah sebanyak 10 gr kemudian diletakkan pada cawan
timbang yang bersih dan kering.
i. Cawan timbang yang berisi 10 gram kemudian dimasukkan kedalam oven selama 24
jam pada suhu 1050C.
j. Dikeluarkan dari oven kemudian cawan beserta tanahnya diletakkan ke dalam
desikator pendingin lalu ditimbang.
k. Dihitung kadar air tanah berdasarkan bobot kering oven dengan suhu 1050C dengan
rumus sebagai berikut:
BTKL : Berat tanah awal
Lampiran 3. Data tinggi tanaman sengon umur 4 minggu – 13 minggu
Perlakuan Ulangan Pengamatan pada minggu ke-
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
49
Lampiran 5. Data diameter tanaman sengon umur 4 minggu – 13 minggu
Perlakuan Ulangan Pengamatan pada minggu ke-
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lampiran 6. Data analisis sidik ragam diameter tanaman sengon umur 13 minggu
Sumber
50
Lampiran 7. Data jumlah anak daun tanaman sengon umur 4 minggu – 13 minggu
Perlakuan Ulangan Pengamatan pada minggu ke-
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lampiran 8. Data analisis jumlah anak daun tanaman sengon umur 13 minggu
Sumber
51
Lampiran 9. Hasil analisis tanah
Lampiran 10. Data komposisi Effective Microorganisms 4 (EM4)
Lab. Fak.MIPA IPB Bogor,2006
Lab. EMRO INC,Japan 2007
Karakteristik tanah Satuan nilai kriteria
52
Lampiran 11. Data analisis bobot kering akar dan bobot kering tajuk Bobot kering tajuk