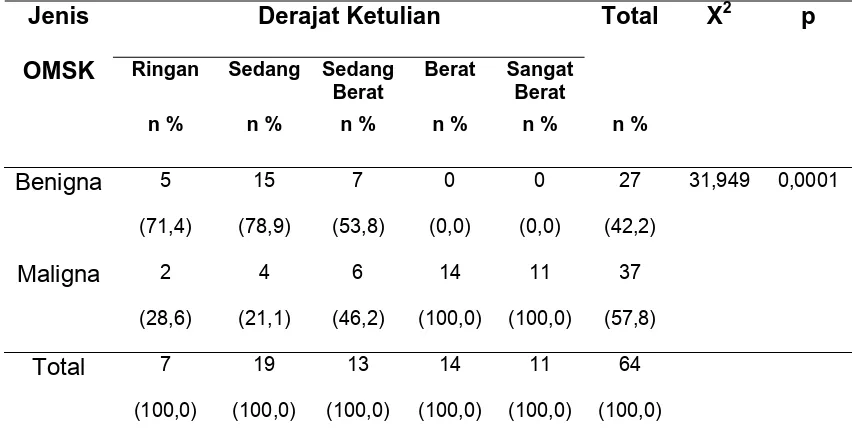HUBUNGAN JENIS OTITIS MEDIA SUPURATIF
KRONIS (OMSK) DENGAN GANGGUAN
PENDENGARAN
Tesis
Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah satu
Syarat untuk Mencapai Spesialis dalam Bidang
Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok
Bedah Kepala Leher
Oleh : SRI MELLA TALA
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS BIDANG
ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK
BEDAH KEPALA LEHER
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Lembar Pengesahan
Tanggal 29 September 2010
Disetujui untuk diajukan ke sidang ujian oleh:
Pembimbing 1
Dr. Adlin Adnan, Sp.THT-KL NIP: 195609111984032001
Pembimbing 2
Prof. Askaroellah Aboet, dr. Sp. THT-KL(K) NIP: 194603051975031001
Pembimbing 3
Dr. Andrina Y.M. Rambe, Sp. THT-KL NIP: 195401261984031001
Diketahui oleh
Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara
Medan, 29 September 2010
Tesis dengan judul
HUBUNGAN JENIS OTITIS MEDIA SUPURATIF
KRONIS (OMSK) DENGAN GANGGUAN
PENDENGARAN
Diketahui Oleh :
Ketua Departemen Ketua Program Studi
Prof. Abdul Rachman Saragih,dr.Sp.THT-KL(K) Prof. Askaroellah Aboet dr.Sp.THT-KL(K)
Telah disetujui dan diterima baik oleh pembimbing
Ketua
dr. Adlin Adnan, Sp.THT-KL
Anggota
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan Bismillahirahmanirrahim, saya sampaikan rasa
syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karuniaNya saya
dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat dalam
menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh Spesialis dalam bidang Ilmu
Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok dan Bedah kepala leher di Fakultas
Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan. Saya menyadari penulisan
tesis ini masih jauh dari sempurna, baik isi maupun bahasannya. Walaupun
demikian, mudah-mudahan tulisan ini dapat menambah perbendaharaan
penelitian tentang Hubungan Jenis Otitis Media Supuratif Kronis (OMSK) dengan Gangguan Pendengaran.
Dengan telah selesainya tulisan ini, pada kesempatan ini dengan tulus
hati saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan
setinggi-tingginya kepada yang terhormat :
dr. Adlin Adnan, Sp.THT-KL atas kesediaannya sebagai ketua pembimbing
penelitian ini, begitu juga kepada Prof. Askaroellah Aboet, dr. Sp.THT-KL(K),
dr. Andrina Y.M. Rambe, Sp.THT-KL sebagai anggota pembimbing dan dr.
Arlinda Sari Wahyuni, MKes sebagai konsultan ahli. Ditengah kesibukan
beliau , dengan penuh perhatian dan kesabaran, telah banyak memberi
bantuan, bimbingan, saran dan pengarahan yang sangat bermanfaat kepada
Dengan telah berakhirnya masa pendidikan saya, pada kesempatan
yang berbahagia ini perkenankanlah saya menyampaikan penghargaan dan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
Yang terhormat Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof.
Syahril Pasaribu, dr. SpA(K) DTM&H dan mantan Rektor Universitas
Sumatera Utara, Prof. Chairuddin Panusunan Lubis, dr. SpA(K) DTM&H yang
telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program
Pendidikan Dokter Spesialis di Departemen THT-KL Fakultas Kedokteran
Universitas Sumatera Utara.
Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera
Utara Prof. Gontar Alamsyah Siregar, dr. Sp.PD(KGEH) dan mantan Dekan
Fakultas Kedokteran USU Prof. Sutomo Kasiman, dr. Sp.JP(K) dan Prof T.
Bahri Anwar, dr. SpJP(K) atas kesempatan yang diberikan kepada saya
untuk mengikuti program pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran USU.
Yang terhormat Bapak Direktur RSUP H. Adam Malik Medan, Direktur
RS Tembakau Deli Medan, Direktur RSUD Lubuk Pakam dan Direktur Rumkit
TK I Medan dan Direktur RSUD F.L. Tobing Sibolga yang telah mengizinkan
dan telah memberikan kesempatan pada saya untuk menjalani masa
pendidikan di rumah sakit yang beliau pimpin.
Yang terhormat Ketua Departemen / Staf Radiologi FK.USU / RSUP.
H.Adam Malik Medan, Ketua Departemen / Staf Anestesi FK.USU RSUP.
H.Adam Malik Medan, Ketua Departemen / Staf Patologi Anatomi FK.USU
stase asisten di bagian tersebut dan kami ucapkan terima kasih
sebanyak-banyaknya.
Yang terhormat Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Telinga Hidung
Tenggorok dan Bedah Kepala Leher Fakultas Kedokteran USU Prof. Abdul
Rachman Saragih, dr. Sp.THT-KL(K) dan Ketua Program Studi Ilmu
Kesehatan THT-KL Fakultas Kedokteran USU, Prof. Askaroellah Aboet, dr.
Sp.THT-KL(K) yang telah memberikan izin, kesempatan dan ilmu kepada
saya dalam mengikuti pendidikan spesialisasi sampai selesai.
Yang terhormat supervisor di jajaran Departemen THT-KL Fakultas
Kedokteran USU/RSUP. H.Adam Malik Medan, dr. Asroel Aboet, Sp.THT-KL,
Prof. Ramsi Lutan, dr. Sp.THT-KL(K), dr. Yuritna Haryono, Sp.THT-KL (K),
Prof. Askaroellah Aboet, dr. Sp.THT-KL(K), Prof. Abdul Rachman Saragih,
dr. Sp.THT-KL(K), dr. Muzakkir Zamzam, SpTHT-KL(K), dr. Mangain
Hasibuan, SpTHT-KL, dr.T.Sofia Hanum, Sp.THT-KL (K), Dr. Dr. Delfitri
Munir, SpTHT-KL(K), dr.Linda I Adenin,Sp.THT-KL, dr.Hafni,Sp.THT-KL (K),
dr. Ida Sjailandrawati Hrp, SpTHT-KL, dr.Adlin Adnan,Sp.THT-KL, dr. Rizalina
A. Asnir, Sp.THT-KL, (Almh) dr. Ainul Mardhiah, Sp.THT-KL, dr. Siti Nursiah,
Sp.THT-KL, dr. Andrina Y.M. Rambe, Sp.THT-KL, dr.Harry Agustaf Asroel,
Sp.THT-KL, dr. Farhat, Sp.THT-KL, dr. T. Siti Hajar Haryuna, Sp.THT-KL, dr.
Aliandri, Sp.THT-KL, dr. Asri Yudhistira, Sp.THT-KL, dr. Devira Zahara,
SpTHT-KL, dr. H.R. Yusa Herwanto, SpTHT-KL, dr. M. Pahala Hanafi
Harahap, SpTHT-KL, dan dr. Ferryan Sofyan, SpTHT-KL MKes Terima kasih
Yang tercinta teman-teman sejawat PPDS Ilmu Kesehatan THT-KL
Fakultas Kedokteran USU, atas bantuan, nasehat, saran maupun
kerjasamanya selama masa pendidikan.
Yang terhormat perawat/paramedis dan seluruh karyawan/karyawati
RSUP H. Adam Malik Medan , khususnya Departemen/SMF THT-KL yang
selalu membantu dan bekerjasama dengan baik dalam menjalani tugas
pendidikan dan pelayanan kesehatan selama ini.
Yang mulia dan tercinta Ayahanda Zulfikri Tala, S.H. dan Ibunda
Nirwisna Martias, S.H. ananda sampaikan rasa hormat dan terima kasih
yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas kasih
sayang yang telah diberikan dan dilimpahkan kepada ananda sejak dalam
kandungan, dilahirkan, dibesarkan dan diberi pendidikan yang baik serta
diberikan suri tauladan yang baik hingga menjadi landasan yang kokoh dalam
menghadapi kehidupan ini, dengan memanjatkan doa kehadirat Allah SWT,
Ya Allah ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, serta kasihilah
mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak kecil.
Yang tercinta Bapak mertua dr. H. Moeharman Idham, SpPD KPTI
(Alm) dan Ibu mertua Hj. Sulastri yang selama ini telah memberikan dorongan
dan restu untuk selalu menuntut ilmu setinggi-tingginya.
Kepada suamikuku tercinta dr. Marwan Moeharman, serta buah hati
kami tersayang Muhammad Zaki Moeharman, tiada kata yang lebih indah
yang dapat saya ucapkan selain ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya
yang tiada henti-hentinya kepada ayahanda sehingga dengan ridho Allah
SWT akhirnya kita sampai pada saat yang berbahagia ini.
Kepada Kakak dan Abang ipar penulis mengucapkan terima kasih atas
limpahan kasih sayang dan tak henti-hentinya memberikan dorongan serta
doa kepada penulis.
Kepada seluruh kerabat dan handai taulan yang tidak dapat kami
sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan kami ucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya.
Akhirnya izinkanlah saya mohon maaf yang setulus-tulusnya atas
segala kesalahan dan kekurangan kami selama mengikuti pendidikan ini,
semoga segala bantuan, dorongan, petunjuk yang diberikan kepada kami
selama mengikuti pendidikan kiranya mendapat balasan yang berlipat ganda
dari Allah SWT, Yang maha pemurah, maha pengasih dan maha penyayang.
Amin.
Medan, September 2010 Penulis
HUBUNGAN JENIS OTITIS MEDIA SUPURATIF KRONIS (OMSK) DENGAN GANGGUAN PENDENGARAN
Abstrak
Latar Belakang: Otitis Media Supuratif Kronis (OMSK) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang terbesar pada beberapa populasi di dunia yang
menyebabkan gangguan pendengaran. Sebagian dari pasien OMSK datang
oleh karena ketulian yang sudah mengganggu komunikasi atau sudah
disertai tanda-tanda komplikasi. Gangguan pendengaran yang terjadi dapat
bervariasi dan beratnya ketulian dapat dipengaruhi oleh jenis dari OMSK itu
sendiri, besar dan letak perforasi membran timpani dan juga lamanya sakit.
Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan jenis OMSK, lamanya sakit
dan jenis perforasi membran timpani dengan gangguan pendengaran.
Metode Penelitian: Penelitian dilakukan dengan studi potong lintang (cross sectional study) di Departemen THT-KL FK USU / RSUP H. Adam Malik
Medan, secara Non Probability Consecutive Sampling mulai bulan Mei 2009.
Dilakukan pemeriksaan THT rutin dan audiometri nada murni terhadap
penderita OMSK untuk menentukan jenis dan derajat ketuliannya. Data
dianalisa dengan uji Chi Square, Anova dan uji korelasi Spearman dengan
tingkat kemaknaan 5%.
Hasil Penelitian: Dari 47 sampel penderita OMSK didapat 64 telinga yang diperiksa, jenis OMSK yang terbanyak diderita adalah jenis maligna
konduktif sebanyak 40 telinga (62,5%) diikuti oleh tuli campur sebanyak 23
telinga (35,9%) dan tuli saraf sebanyak satu telinga (1,6%). Dijumpai
hubungan yang bermakna antara jenis OMSK, lamanya sakit dan jenis
perforasi membran timpani dengan gangguan pendengaran (p < 0,05).
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara jenis OMSK, lamanya sakit dan jenis perforasi menbran timpani dengan gangguan
pendengaran.
Kata Kunci: Jenis OMSK, lama sakit, jenis perforasi membran timpani, gangguan pendengaran.
Abstract:
Background: Chronic Suppurative Otitis Media (CSOM) is a major problem in some population in the world causing hearing impairment. Most of CSOM
patients seek medical attention because of communication difficulty caused
by hearing impairment. The hearing impairment can be vary due to type of
CSOM, size and location of the tympanic membrane perforation and also the
length of the disease. The aim of this study is to learn correlation of type of
CSOM, length of the disease and type of tympanic membrane perforation with
hearing impairment.
Study Design and Method: This is a cross sectional study performed in ENT-HNS Department of Medical School of University of Sumatera Utara / H.
Adam Malik Hospital. Sample was collected by Non Probability Consecutive
examination and Pure Tone Audiometry to determine type and degree of
hearing impairment. Data was analysed by Chi Square Test, Anova and
Spearman’s Correlation Test.
Results: From 47 sample of CSOM patients we found 64 examinated ears, the most type of CSOM was malignant type about 37 ears (57,8%). The most
type of hearing impairment was conductive hearing loss about 40 ears
(62,5%) followed by mix hearing loss about 23 ears (35,9%) and one of
sensoryneural hearing loss (1,6%). Significance correlation was found
between CSOM type, length of the disease, and type of tympanic membrane
perforation with hearing impairment.
Conclusion: Significance correlation was found between CSOM type, length of the disease, and type of tympanic membrane perforation with hearing
impairment.
DAFTAR ISI
2.1 Embriologi Telinga Tengah………... 10
2.1.1 Perkembangan membran timpani ………. 11
2.1.2 Perkembangan tulang-tulang pendengaran…… 13
2.2 Anatomi Telinga Tengah ………... 15
2.3 Fungsi Telinga Tengah ………. 19
2.4 Fisiologi Pendengaran ……….. 20
2.5 Otitis Media Supuratif Kronis ……… 21
2.5.1 Definisi ……… 21
2.5.10 Penatalaksanaan ………. 34
2.7 Audiometri Nada Murni ……… 39
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL ……… 44
BAB 4 METODE PENELITIAN ……….. 45
4.1 Rancangan Penelitian ………. 45
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ………. 45
4.2.1 Lokasi penelitian ………. 45
4.2.2 Waktu penelitian ………. 45
4.3 Populasi, Sampel, Besar Sampel, Teknik Pengambilan Sampel ………... 46
4.3.1 Populasi ……… 46
4.3.2 Sampel Penelitian ……….. 46
4.3.3 Besar Sampel ………... 47
4.3.4 Teknik Pengambilan Sampel ... 47
4.4 Variabel Penelitian ……….. 48
4.4.1 Klasifikasi Variabel Penelitian ……….. 48
4.4.2 Definisi Operasional Variabel ……….. 48
4.5 Bahan/Alat Penelitian ………. 50
4.6 Pelaksanaan Penelitian …...……….. 50
4.7 Kerangka Kerja ………... 51
4.8 Cara Analisis Data ……….. 51
BAB 5 ANALISIS HASIL PENELITIAN... 52
BAB 6 PEMBAHASAN ………... . 62
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN ……… ………. . 69
7.1 Kesimpulan ………. . 69
KEPUSTAKAAN ……… 70
LAMPIRAN ………... 76
Lampiran 1 Data Sampel Penelitian ……… 76
HUBUNGAN JENIS OTITIS MEDIA SUPURATIF KRONIS (OMSK) DENGAN GANGGUAN PENDENGARAN
Abstrak
Latar Belakang: Otitis Media Supuratif Kronis (OMSK) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang terbesar pada beberapa populasi di dunia yang
menyebabkan gangguan pendengaran. Sebagian dari pasien OMSK datang
oleh karena ketulian yang sudah mengganggu komunikasi atau sudah
disertai tanda-tanda komplikasi. Gangguan pendengaran yang terjadi dapat
bervariasi dan beratnya ketulian dapat dipengaruhi oleh jenis dari OMSK itu
sendiri, besar dan letak perforasi membran timpani dan juga lamanya sakit.
Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan jenis OMSK, lamanya sakit
dan jenis perforasi membran timpani dengan gangguan pendengaran.
Metode Penelitian: Penelitian dilakukan dengan studi potong lintang (cross sectional study) di Departemen THT-KL FK USU / RSUP H. Adam Malik
Medan, secara Non Probability Consecutive Sampling mulai bulan Mei 2009.
Dilakukan pemeriksaan THT rutin dan audiometri nada murni terhadap
penderita OMSK untuk menentukan jenis dan derajat ketuliannya. Data
dianalisa dengan uji Chi Square, Anova dan uji korelasi Spearman dengan
tingkat kemaknaan 5%.
Hasil Penelitian: Dari 47 sampel penderita OMSK didapat 64 telinga yang diperiksa, jenis OMSK yang terbanyak diderita adalah jenis maligna
konduktif sebanyak 40 telinga (62,5%) diikuti oleh tuli campur sebanyak 23
telinga (35,9%) dan tuli saraf sebanyak satu telinga (1,6%). Dijumpai
hubungan yang bermakna antara jenis OMSK, lamanya sakit dan jenis
perforasi membran timpani dengan gangguan pendengaran (p < 0,05).
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara jenis OMSK, lamanya sakit dan jenis perforasi menbran timpani dengan gangguan
pendengaran.
Kata Kunci: Jenis OMSK, lama sakit, jenis perforasi membran timpani, gangguan pendengaran.
Abstract:
Background: Chronic Suppurative Otitis Media (CSOM) is a major problem in some population in the world causing hearing impairment. Most of CSOM
patients seek medical attention because of communication difficulty caused
by hearing impairment. The hearing impairment can be vary due to type of
CSOM, size and location of the tympanic membrane perforation and also the
length of the disease. The aim of this study is to learn correlation of type of
CSOM, length of the disease and type of tympanic membrane perforation with
hearing impairment.
Study Design and Method: This is a cross sectional study performed in ENT-HNS Department of Medical School of University of Sumatera Utara / H.
Adam Malik Hospital. Sample was collected by Non Probability Consecutive
examination and Pure Tone Audiometry to determine type and degree of
hearing impairment. Data was analysed by Chi Square Test, Anova and
Spearman’s Correlation Test.
Results: From 47 sample of CSOM patients we found 64 examinated ears, the most type of CSOM was malignant type about 37 ears (57,8%). The most
type of hearing impairment was conductive hearing loss about 40 ears
(62,5%) followed by mix hearing loss about 23 ears (35,9%) and one of
sensoryneural hearing loss (1,6%). Significance correlation was found
between CSOM type, length of the disease, and type of tympanic membrane
perforation with hearing impairment.
Conclusion: Significance correlation was found between CSOM type, length of the disease, and type of tympanic membrane perforation with hearing
impairment.
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Otitis Media Supuratif Kronis (OMSK) merupakan masalah kesehatan
masyarakat yang terbesar pada beberapa populasi di dunia, yang dapat
menyebabkan morbiditas dan mortalitas. Penyakit ini berdampak nyata pada
kerugian ekonomi dan sosial. Hal ini umumnya terjadi pada komunitas miskin
pada suatu negara berkembang dan tentunya menimbulkan kerugian pada
negara berkembang (WHO, 1996).
Otitis Media Supuratif Kronis (OMSK) adalah radang kronis telinga
tengah dengan perforasi membran timpani dan riwayat keluarnya sekret dari
telinga (otorea) lebih dari tiga bulan baik terus menerus ataupun hilang timbul
(Telian dan Schmalbach, 2002). Penyakit ini merupakan salah satu penyakit
infeksi kronis bidang THT di Indonesia yang masih sering menimbulkan
ketulian dan kematian (Djaafar, 2001).
Terjadinya otitis media akut menjadi awal penyebab OMSK yang
merupakan invasi mukoperiosteum organisme yang virulen, terutama berasal
dari nasofaring yang terdapat paling banyak pada masa anak-anak (Kenna
dan Latz, 2006).
Angka kejadian OMSK jauh lebih tinggi di negara-negara sedang
berkembang dibandingkan dengan negara maju, karena beberapa hal
kepadatan penduduk serta masih ada pengertian masyarakat yang salah
terhadap penyakit ini sehingga mereka tidak berobat sampai tuntas (Mills,
1997; Djaafar, 2003).
Berdasarkan hasil survei epidemiologi yang dilakukan di tujuh propinsi
di Indonesia tahun 1994-1996, didapati bahwa prevalensi OMSK secara
umum adalah 3,8%. Disamping itu pasien OMSK merupakan 25% dari pasien
yang berobat di poliklinik THT rumah sakit di Indonesia. Angka kejadian
OMSK yang rendah, di negara maju ditemukan pada pemeriksaan berkala,
pada anak sekolah yang dilakukan oleh School Health Service di Inggris
Raya sebesar 0,9%, tetapi prevalensi OMSK yang tinggi juga masih
ditemukan pada ras tertentu di negara maju, seperti Native American Apache
8,2%, Indian Kanada 6%, dan Aborigin Australia 25% (Djaafar, 2005). Data
poliklinik THT RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2006 menunjukkan pasien
OMSK merupakan 26% dari seluruh kunjungan pasien (Aboet, 2007),
sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 sebesar 28 dan 29%.
Survei prevalensi diseluruh dunia, yang walaupun masih bervariasi
dalam hal definisi penyakit, metode sampling serta mutu metodologi,
menunjukkan beban dunia akibat OMSK melibatkan 65–330 juta orang
dengan telinga berair, 60% di antaranya (39–200 juta) menderita kurang
pendengaran yang signifikan (Aboet, 2007).
Pasien OMSK yang datang ke RSCM Jakarta (2001) kurang lebih 90%
berasal dari masyarakat sosioekonomi lemah. Namun demikian sebagian
dokter umum, dokter THT, atau diobati sendiri berulang-ulang dengan obat
tetes. Sebagian dari pasien ini datang oleh karena ketulian yang sudah
mengganggu komunikasi atau sudah disertai tanda-tanda komplikasi
(Djaafar, 2001).
Gangguan pendengaran yang terjadi dapat bervariasi. Pada umumnya
gangguan pendengaran yang terjadi berupa tuli konduktif namun dapat pula
bersifat tuli saraf atau tuli campuran apabila sudah terjadi gangguan pada
telinga dalam misalnya akibat proses infeksi yang berkepanjangan atau
infeksi yang berulang. Beratnya ketulian bergantung kepada besar dan letak
perforasi membran timpani serta keutuhan dan mobilitas sistem
penghantaran suara di telinga tengah (Djaafar, 2004). Perforasi yang lebih
besar dapat menyebabkan lebih banyak kehilangan suara yang
ditransmisikan ke telinga dalam (Maqbool, 1993). Suri dkk dalam
penelitiannya terhadap penderita OMSK tipe benigna di R.S. Sardjito
Yogyakarta menjumpai adanya hubungan yang bermakna antara besarnya
perforasi dengan derajat ketulian (Suri, Soekardono & Hulu, 1999). Hal yang
sama juga dijumpai oleh Rambe dalam penelitiannya terhadap penderita
OMSK di RSUP. H. Adam Malik Medan, bahwa terdapat hubungan yang
bermakna antara besarnya perforasi dengan derajat ketulian (Rambe, 2002).
Pada OMSK tipe maligna biasanya didapat tuli konduktif berat karena
putusnya rantai tulang pendengaran, tetapi seringkali kolesteatoma bertindak
sebagai penghantar suara ke foramen ovale sehingga gangguan
(Djaafar, 2004). Pasien akan merasakan pendengaran yang makin buruk
apabila liang telinga dipenuhi oleh sekret dan akan berkurang apabila sekret
dibersihkan (Ramalingam, 1990).
Pada kenyataannya, gangguan pendengaran pada OMSK tidak
seluruhnya tuli konduktif murni. Tidak sedikit penderita OMSK menderita tuli
sensorineural atau tuli campur. Setiap kali ada infeksi didalam telinga tengah,
maka ada kemungkinan produk-produk infeksi akan menyebar melalui
fenestra rotundum ke telinga dalam, dan akan mengakibatkan ketulian
sensorineural (Sari dan Samiharja, 1999).
Rambe pada penelitiannya yang dilakukan antara April 2002 – Juli
2002 di RSUP. H. Adam Malik Medan terhadap 94 sampel telinga penderita
OMSK, mendapatkan jenis gangguan pendengaran yang terbanyak dijumpai
adalah tuli konduktif sebanyak 75 telinga (79,8%), tuli campur sebanyak 16
telinga (17%) dan tuli saraf sebanyak 3 telinga (3,2%) (Rambe, 2002).
Wisnubroto pada penelitian retrospektif di RS. Soetomo Surabaya
antara tahun 1999 – 2002, dari data rekam medis penderita OMSK yang
telah menjalani pembedahan telinga, tercatat hanya ada 475 rekam medis
yang dilengkapi hasil audiogram prabedah. Yang mengalami tuli konduktif
terdiri dari 93 (19,6%) kasus OMSK reversibel, 140 (29,5%) kasus OMSK
benigna dan 115 (24,2%) sebagian kasus OMSK maligna. Sisanya sebanyak
127 (26,7%) kasus OMSK maligna sudah mengalami tuli perseptif berat
Morisson (1969) melaporkan bahwa 25% dari kasus dengan
peradangan telinga tengah mengalami tuli sensorineural (Yeoh, 1997).
English et al (1973) pada penelitian terhadap 404 pasien dengan
OMSK, menjumpai adanya suatu hubungan antara lamanya penyakit dengan
derajat tuli sensorineural (Yeoh, 1997).
Cusimano et al (1989) juga melaporkan bahwa lamanya penyakit
mempunyai pengaruh terhadap terjadinya tuli sensorineural dan tidak
dijumpai adanya hubungan dengan umur sewaktu terjadinya serangan (Yeoh,
1997).
Nani dkk pada penelitiannya untuk mendeteksi ketulian sensorineural
terhadap penderita OMSK unilateral di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo
Ujung Pandang antara April 1996 – September 1996 menemukan dari 22
penderita yang ditemukan, terdapat 9 (40,9%) kasus yang terdeteksi adanya
ketulian sensorineural (Nani, Mangape & Sedjawidada, 1996).
De Azevedo et al pada penelitiannya terhadap 115 penderita OMSK
dengan dan tanpa kolesteatoma, mendapatkan 78 penderita OMSK dengan
kolesteatoma dan sebanyak 15 penderita (13%) mengalami tuli sensorineural
(De Azevedo et al, 2007).
Data subdivisi otologi THT-KL RSCM Jakarta antara Januari 2002 –
Desember 2006, dari 212 penderita OMSK tipe maligna yang menjalani
pembedahan telinga, didapatkan 53 penderita (25%) mengalami tuli
Insiden tuli campur (mixed hearingloss = MHL) pada OMSK telah
dilaporkan oleh banyak penulis. Paparella et al, sebagaimana dikutip oleh
Shenoi (1987) mendapatkan 279 kasus MHL diantara 500 telinga dengan
OMSK. Gardenghi melaporkan insiden MHL pada OMSK adalah 42%.
Sementara Bluvesteis melaporkan insiden MHL pada OMSK ini adalah 38%.
Nani (1996) melaporkan terdapat sekitar 5% dari 22 penderita OMSK
mengalami MHL. Di RSUP Dr. Kariadi Semarang, insiden MHL juga pernah
dilaporkan oleh Pradipto sebesar 12,75% dan Dullah (1996) mendapatkan
MHL sebanyak 44,5% dari 54 telinga dengan OMSK (Sari dan Samiharja,
1999).
Santoso dan Ahadiah pada penelitiannya terhadap penderita OMSK
tipe maligna dengan komplikasi ekstrakranial antara Januari 2004 –
Desember 2006 di RS. Dr. Soetomo Surabaya, mendapatkan dari 163
penderita ditemukan 56 penderita (34,36%) mengalami komplikasi
ekstrakranial dan jenis ketulian yang terbanyak ditemukan adalah MHL
(46,43%) (Santoso dan Ahadiah, 2007).
Terjadinya MHL pada OMSK ini menunjukkan bahwa lesi fungsional
telah terjadi di telinga tengah dan juga telinga dalam (Sari dan Samiharja,
1999).
Djafaar dalam penelitiannya yang dilakukan antara 1991–1993 di
RSCM Jakarta, menjumpai dari 145 pasien OMSK tipe berbahaya yang
berobat ditemukan 88 penderita (60%) tuli konduktif sedang berat, 8 orang
berat, dan sisanya 31 penderita (22%) tidak ada audiogramnya (Djaafar,
2001).
Evaluasi audiometri penting untuk menentukan fungsi konduktif dan
fungsi koklea. Dengan menggunakan audiometri nada murni pada hantaran
udara dan tulang, besarnya kerusakan tulang-tulang pendengaran dapat
diperkirakan, dan manfaat dari operasi rekonstruksi telinga tengah terhadap
perbaikan pendengaran dapat ditentukan (Ballenger, 1997; Djaafar, 2000).
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti
tertarik untuk mengetahui hubungan antara jenis OMSK dengan gangguan
pendengaran.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas,
dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana hubungan jenis
OMSK dengan gangguan pendengaran?
1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1. Tujuan Umum
Mengetahui hubungan jenis OMSK dengan gangguan pendengaran.
1.3.2. Tujuan Khusus
a. Mengetahui hubungan antara jenis OMSK dengan jenis dan
derajat ketulian.
derajat ketulian.
c. Mengetahui hubungan antara jenis perforasi membran timpani
dengan jenis dan derajat ketulian.
1.4 Hipotesa
a. Ada hubungan antara jenis OMSK dengan jenis dan derajat
ketulian.
b. Ada hubungan antara lamanya sakit dengan jenis dan derajat
ketulian.
c. Ada hubungan antara jenis perforasi membran timpani dengan
jenis dan derajat ketulian.
1.5 Manfaat Penelitian
a. Untuk memotivasi penderita OMSK agar dilakukan operasi
Mastoidektomi dan Timpanoplasti.
b. Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan rekonstruksi
dari telinga tengah.
c. Sebagai pengembangan keilmuan di bidang Ilmu Penyakit
BAB 2
TINJAUAN KEPUSTAKAAN
2.1 Embriologi Telinga Tengah
Telinga tengah berasal dari bagian endoderm kantong faringeal
pertama, disamping itu bersama-sama dengan telinga luar, telinga tengah
juga mempunyai komponen mesodermal dari lengkung faringeal pertama dan
kedua. Kavum timpani dibentuk dari kantong faringeal pertama. Kantong
faringeal ini telah nyata terlihat pada minggu ke–3 perkembangan dan pada
minggu ke–6 telah memanjang dan menjadi pipih pada ujung distalnya dan
bersandar pada lekuk brankial pertama. Jaringan ikat segera tumbuh diantara
kedua permukaan yang saling berdekatan tersebut dan akan membentuk
tunika propria membran timpani dan manubrium maleus. Menjelang minggu
ke–8, fundus kantong faringeal yang telah mendatar akan meluas
membentuk awal ruang telinga tengah. Ruang ini hanya terdapat pada
setengah bagian bawah telinga tengah sedang sisanya berisi jaringan ikat
(Austin, 1997).
Pada akhir bulan ke–2, bagian proksimal kantong tersebut mengecil
dan memanjang disebabkan oleh karena pertumbuhan kepala dan
membentuk tuba eustachius sejati. Tuba eustachius mempunyai panjang
17-18 mm dan terletak mendatar pada saat lahir dan menjadi dua kali lebih
panjang yaitu sekitar 35 mm serta terletak dengan posisi 450 pada usia
2.1.1 Perkembangan membran timpani
Membran timpani dibentuk oleh pertemuan antara meatal plug dengan
bagian endodermal resesus tubo timpanikus. Daerah pertemuan tersebut
miring, sehingga membuat membran timpani terletak miring sesuai dengan
sumbu dari liang telinga luar (Anson, 1991). Saraf korda timpani, handle dari
stapes dan lapisan mesoderm terdapat diantara meatal plug dan resesus
tubo timpanikus (Anson, 1991; Wright, 1997).
Membran timpani terdiri dari tiga lapisan :
1. Lapisan luar : lapisan epitel berasal dari ektodermal yang
merupakan lanjutan dari kulit liang telinga luar
2. Lapisan tengah : lapisan fibrosa berasal dari mesodermal yang
berisi korda timpani dan manibrium maleus
3. Lapisan dalam : lapisan mukosa berasal dari endodermal yang
merupakan lanjutan dari membran mukosa telinga tengah
(Anson, 1991; Wright, 1997).
Pada awal minggu ke – 12 di dalam rongga telinga tengah, terbentuk
a. Sakus antikus yang akan membentuk kantong anterior dari Von
Troltsch
b. Sakus medius membentuk resesus epitimpanikus dan
mengalami pneumatisasi pada bagian petrosa dari tulang
temporal
c. Sakus superior membentuk kantong posterior dari Von Troltsch
dan ruang inkuidal inferior serta mengalami pneumatisasi pada
bagian mastoid tulang temporal
d. Sakus posterior (sakus postikus), meluas ke posterior
membentuk tonjolan foramen rotundum, tonjolan foramen ovale
dan sinus timpanikus (Wright, 1997).
Lipatan mukosa kavum timpani terbentuk ketika kantong-kantong
mukosa tersebut berhubungan satu sama lain. Pada saat terbentuk kavum
timpani berisi cairan mukoid yang secara perlahan-lahan diabsorbsi. Pada
saat lahir kavum timpani dan struktur tang terdapat didalamnya sebagaimana
telinga dalam telah mempunyai bentuk dan ukuran dewasa (Wright, 1997).
2.1.2 Perkembangan tulang-tulang pendengaran
Stapes, maleus dan inkus berasal dari mesodermal dari dua buah
berkembang secara ekstra mukosa walaupun dia tetap berada di dalam
kavum timpani. Tulang rawan lengkung faringal I (tulang rawan Meckel’s)
terletak sebelah anterior dari resesus tubo timpanikus (kantong faringeal I)
dan tulang rawan lengkung faringeal II (tulang rawan Reichert’s) terletak
sebelah posterior dari resesus tubo timpanikus (Anson, 1991). Bagian
superior dari tulang rawan Meckel’s membentuk maleus, inkus, ligamentum
maleus anterior dan ligamentum speno-mandibular (Austin, 1997).
Pada mulanya maleus dan inkus berupa massa yang tunggal,
kemudian pada minggu ke–8 dari kehidupan fetus terpisah dengan
terbentuknya sendi diantara maleus dan inkus tersebut. Tulang rawan
lengkung ke II (Reichert’s) membentuk manubrium maleus dan prosesus
longus dari inkus. Prosesus anterior meleus terbentuk secara terpisah dari
tulang membran, manubrium maleus meluas ke bawah dan terjepit diantara
ektoderm celah faringeal pertama dengan resesus tubo timpanikus
sepanjang saraf korda timpani, akhirnya tertanam di dalam setengah atas
dari membran timpani. Muskulus tensor timpani juga berasal dari mesodermal
lengkung faringeal pertama sehingga mempunyai hubungan dengan maleus
(Austin, 1997).
Ujung atas dari tulang rawan Reichert’s membentuk sebagian besar
stapes, prosesus stiloideus, ligamentum stilohioid dan bagian atas dari badan
hioid. Fiksasi kongenital dari stapes terjadi oleh karena kegagalan pemisahan
telapak kaki stapes (segretion of the foot plate) dari otik kapsul dan harus
Selama minggu ke–4 embriologi, lengkung kedua mesodermal
membentuk blastema yang oleh saraf ketujuh dibagi menjadi stapes,
interhiale dan laterohiale. Pada minggu ke–5 dan ke–6 arteri stapedius yang
merupakan arteri dari lengkung brankial ke–2 menembus stapes primitif dan
berubah bentuk menjadi lingkaran, kemudian arteri ini mengalami regresi tapi
sering juga persisten, inilah yang sering mengakibatkan perdarahan pada
saat operasi telinga tengah. Dalam minggu ke–8 sendi inkudostapedial
terbentuk dan pada minggu ke–10 stapes digambarkan berbentuk seperti
sanggurdi. Tulang interhiale akhirnya menjadi muskulus stapedius beserta
tendonnya sedangkan hubungan antara laterohiale dengan kapsul otik
mebentuk dinding anterior kanalis fasialis dari prosesus piramidalis (Wright,
1997).
Proses terbentuknya inkus dimulai pada usia 16 minggu, leher maleus
terbentuk usia 17 minggu dan stapes usia 19 minggu. Bentuk dan ukuran
maleus, inkus dan stapes sama pada saat lahir dan dewasa. Manubrium
maleus tidak pernah menjadi tulang dan tetap sebagai tulang rawan.
Perubahan bentuk dari maleus dan inkus berlanjut setelah lahir dengan
pembentukan tulang sekunder dan tersier sedangkan stapes tetap
(Wright, 1997).
2.2 Anatomi Telinga Tengah
Telinga adalah organ fungsi pendengaran dan pengatur
telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam (Soetirto, Hendarmin,
Bashiruddin, 2004). Telinga tengah terdiri dari membran timpani, kavum
timpani, tuba eustachius dan prosesus mastoideus (Dhingra, 2007).
Membran Timpani
Membran timpani dibentuk dari dinding lateral kavum timpani yang
memisahkan liang telinga luar dari kavum timpani. Membran timpani ini
berbentuk oval dan mempunyai ukuran panjang vertikal rata-rata 9-10 mm,
dan diameter antero-posterior kira-kira 8-9 mm, tebal kira-kira 0,1 mm.
Membran ini tipis, licin dan berwarna putih mutiara (Dhingra, 2007).
Membran timpani terdiri dari tiga lapisan, lapisan luar terdiri dari epitel
skuamosa, bagian medial merupakan lanjutan dari mukosa telinga tengah.
Lapisan tengah merupakan lapisan fibrosa yang terdiri dari dua lapisan yaitu
lapisan radial dan sirkuler (sirkumferensial). Lapisan dalam dilapisi epitel
kuboidal (Yates dan Anari, 2008).
Secara anatomis membran timpani dibagi dalam dua bagian yaitu:
1. Pars Tensa, merupakan bagian terbesar dari membran timpani
merupakan suatu permukaan yang tegang dan bergetar dengan
sekelilingnya yang menebal dan melekat di anulus timpanikus
pada sulkus timpanikus pada tulang dari tulang temporal.
2. Pars Flaksida atau membran Sharpnell, letaknya di bagian atas
dua lipatan yaitu plika maleolaris anterior (lipatan muka) dan plika
maleolaris posterior (lipatan belakang) (Dhingra, 2007).
Kavum Timpani
Kavum timpani mempunyai bentuk ireguler, bagian lateral terdapat
lekukan, antara dinding lateral dan dinding medial kavum timpani terisi udara.
Kavum timpani terdiri dari tiga bagian yaitu supero-inferior berhubungan
dengan membran timpani disebut epitimpani atau atik, yang terletak dipinggir
atas dari membran timpani. Setentang membran timpani adalah mesotimpani
dan dibawah pinggir membran timpani disebut hipotimpani (Colman, 1993;
Yates dan Anari, 2008).
Kavum timpani mempunyai enam dinding yaitu bagian atap, lantai,
dinding lateral, dinding medial, dinding anterior dan dinding posterior (Helmi,
2005; Dhingra, 2007).
Atap kavum timpani dibentuk oleh lempengan tulang yang tipis disebut
tegmen timpani. Tegmen timpani memisahkan telinga tengah dari fossa
media (Helmi, 2005; Dhingra, 2007).
Lantai kavum timpani dibentuk oleh tulang tipis yang memisahkan
lantai kavum timpani dari bulbus vena jugularis yang dinding superiornya
dibatasi oleh lempeng tulang yang mempunyai ketebalan yang bervariasi,
bahkan kadang-kadang hanya dibatasi oleh mukosa dengan kavum timpani
Dinding medial kavum timpani memisahkan kavum timpani dari telinga
dalam, ini juga merupakan dinding lateral dari telinga dalam. Dinding ini pada
mesotimpani menonjol kearah kavum timpani yang disebut promontorium.
Tonjolan ini oleh karena didalamnya terdapat koklea (Helmi, 2005; Dhingra,
2007).
Dinding posterior kavum timpani dekat keatap, mempunyai satu
saluran disebut aditus yang menghubungkan kavum timpani dengan antrum
mastoid melalui epitimpani. Pada bagian posterior ini, dari medial ke lateral
terdapat eminensia piramidalis yang terletak di bagain supero-medial dinding
posterior, kemudian sinus posterior yang membatasi eminensia piramidalis
dengan tempat keluarnya korda timpani (Helmi, 2005; Dhingra 2007).
Dinding anterior kavum timpani sebagian besar berhadapan dengan
arteri karotis, dibatasi lempengan tulang tipis. Dibagian atas dinding anterior
terdapat semikanal nervus tensor timpani yang terletak persis di atas muara
tuba eustachius (Helmi, 2005; Dhingra, 2007).
Membran timpani merupakan dinding lateral kavum timpani,
sedangkan dibagian epitimpani dinding lateralnya adalah skutum yaitu
lempeng tulang yang merupakan bagian pars skuamosa tulang temporal
(Helmi, 2005; Dhingra, 2007).
Isi kavum timpani terdiri dari :
1. Tulang-tulang pendengaran (maleus, inkus, stapes).
3. Saraf korda timpani, merupakan cabang dari nervus fasialis masuk
ke kavum timpani dari kanalikulus posterior yang menghubungkan
dinding lateral dan posterior.
4. Saraf pleksus timpanikus adalah berasal dari nervus timpani cabang
dari nervus glosofaringeus dan dengan nervus karotikotimpani yang
berasal dari pleksus simpatetik di sekitar arteri karotis interna
(Dhingra, 2007).
Tuba Eustachius
Tuba eustachius disebut juga tuba auditori atau tuba faringotimpani
bentuknya seperti huruf S. Tuba ini merupakan saluran yang
menghubungkan antara kavum timpani dengan nasofaring (Helmi, 2005).
Tuba eustachius terdiri dari dua bagian yaitu bagian tulang yang
terdapat pada bagian belakang dan pendek (sepertiga bagian) dan bagian
tulang rawan yang terletak pada bagian depan dan panjang (duapertiga
bagian) (Helmi, 2005).
Fungsi tuba eustachius adalah sebagai ventilasi telinga yang
mempertahankan keseimbangan tekanan udara didalam kavum timpani
dengan tekanan udara luar, drainase sekret yang berasal dari kavum timpani
menuju ke nasofaring dan menghalangi masuknya sekret dari nasofaring
menuju ke kavum timpani (Healy dan Rosbe, 2003; Helmi, 2005).
Prosesus mastoideus baru terbentuk pada usia satu tahun, antrum
mastoideum adalah ruangan pertama dan yang terbesar yang terdiri dari
sel-sel mastoid. Sel-sel-sel ini berhubungan satu dengan lain dan pertumbuhan dari
sel-sel mastoid tiap orang berbeda. Pneumatisasi prosesus mastoideus
menurut tipe perkembangannya dibagi atas prosesus mastoideus sklerotik,
diploik dan pneumatik. Bila drainase tidak baik pada mastoid akan mudah
terjadi radang (Helmi, 2005).
2.3 Fungsi Telinga Tengah
Telinga tengah sangat penting karena berfungsi sebagai penghantar
gelombang suara dari telinga luar ke telinga dalam. Suara yang ditangkap
dan dikumpulkan oleh pinna (daun telinga) diarahkan ke liang telinga,
kemudian diteruskan ke membran timpani. Gelombang suara ini membentuk
suatu tekanan yang kemudian menggetarkan membran timpani. Getaran ini
akan menggerakkan tulang-tulang pendengaran (maleus, inkus, stapes).
Pergerakan tulang-tulang pendengaran ini selanjutnya akan menggetarkan
foramen ovale sehingga mengakibatkan bergetarnya cairan yang berada di
telinga dalam. Dari peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa telinga tengah
berfungsi merubah getaran suara di udara yang ditangkap oleh membran
timpani, menjadi getaran mekanis pada tulang-tulang pendengaran dan
selanjutnya melalui foramen ovale merubah getaran cairan di dalam labirin
2.4 Fisiologi Pendengaran
Proses mendengar diawali dengan ditangkapnya energi bunyi oleh
daun telinga dalam bentuk gelombang yang dialirkan melalui udara atau
tulang ke koklea. Gelombang tersebut menggetarkan membran timpani,
diteruskan ke telinga tengah melalui rangkaian tulang pendengaran yang
akan mengamplifikasi getaran melalui daya ungkit tulang-tulang
pendengaran. Energi getar yang telah diamplifikasi ini akan diteruskan ke
stapes yang menggerakkan tingkap lonjong sehingga perilimfe pada skala
vestibuli bergerak. Getaran diteruskan melalui membran Reisner yang
mendorong endolimfe, sehingga akan menimbulkan gerak relatif antara
membran basilaris dan membran tektoria. Proses ini merupakan rangsang
mekanik yang menyebabkan terjadinya defleksi stereosilia sel-sel rambut,
sehingga kanal ion terbuka dan terjadi pelepasan ion bermuatan listrik dari
badan sel. Keadaan ini menimbulkan proses depolarisasi sel rambut,
sehingga melepaskan neurotransmiter kedalam sinapsis yang akan
menimbulkan potensial aksi pada saraf auditorius, lalu dilanjutkan ke nukleus
auditorius sampai ke korteks pendengaran di lobus temporalis (Soetirto,
Hendarmin & Bashiruddin, 2004).
2.5 Otitis Media Supuratif Kronis 2.5.1 Definisi
Otitis Media Supuratif Kronis (OMSK) adalah radang kronis telinga
telinga (otorea) lebih dari tiga bulan baik terus menerus ataupun hilang timbul
(Acuin, 2002; Telian dan Schmalbach, 2002). Penyakit ini merupakan salah
satu penyakit infeksi kronis bidang THT di Indunesia yang masih sering
menimbulkan ketulian dan kematian (Djaafar, 2001).
2.5.2 Kekerapan
Angka kejadian OMSK jauh lebih tinggi di negara-negara sedang
berkembang dibandingkan dengan negara maju, karena beberapa hal
misalnya higiene yang kurang, faktor sosioekonomi, gizi yang rendah,
kepadatan penduduk serta masih ada pengertian masyarakat yang salah
terhadap penyakit ini sehingga mereka tidak berobat sampai tuntas (Mills,
1997; Djaafar, 2003).
Berdasarkan hasil survei epidemiologi yang dilakukan di tujuh propinsi
di Indonesia tahun 1994-1996, didapati bahwa prevalensi OMSK secara
umum adalah 3,8%. Disamping itu pasien OMSK merupakan 25% dari pasien
yang berobat di poliklinik THT rumah sakit di Indonesia. Angka kejadian
OMSK yang rendah, di negara maju ditemukan pada pemeriksaan berkala,
pada anak sekolah yang dilakukan oleh School Health Service di Inggris
Raya sebesar 0,9%, tetapi prevalensi OMSK yang tinggi juga masih
ditemukan pada ras tertentu di negara maju, seperti Native American Apache
8,2%, Indian Kanada 6%, dan Aborigin Australia 25% (Djaafar, 2005). Data
OMSK merupakan 26% dari seluruh kunjungan pasien (Aboet, 2007),
sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 adalah 28 dan 29%.
Survei prevalensi diseluruh dunia, yang walaupun masih bervariasi
dalam hal definisi penyakit, metode sampling serta mutu metodologi,
menunjukkan beban dunia akibat OMSK melibatkan 65–330 juta orang
dengan telinga berair, 60% di antaranya (39–200 juta) menderita kurang
pendengaran yang signifikan (Aboet, 2007).
2.5.3 Patogenesis
Hingga saat ini patogenesis OMSK masih belum diketahui dengan
jelas. Goodhill dan Paparella menyatakan bahwa OMSK merupakan penyakit
yang sebagian besar sebagai komplikasi infeksi saluran pernapasan bagian
atas, kelanjutan dari otitis media akut yang tidak sembuh. Kemungkinan
besar proses primer terjadi pada sistem tuba eustachius, telinga tengah dan
selulae mastoidea. Proses ini khas, berjalan perlahan-lahan secara kontinu
dan dinamis, berakibat hilangnya sebagian mambran timpani sehingga
memudahkan proses menjadi kronik (Ballenger, 1997; Sheahan, Donnelly &
Kane, 2001). Faktor-faktor yang menyebabkan proses infeksi menjadi kronik
sangat bervariasi, antara lain :
1. Gangguan fungsi sistem tuba eustachius yang kronik akibat
infeksi hidung dan tenggorok yang kronik atau berulang, atau
2. Perforasi membran timpani yang menetap.
3. Terjadinya metaplasia skuamosa atau perubahan patologik yang
menetap pada telinga tengah.
4. Gangguan aerasi telinga tengah atau rongga mastoid yang
sifatnya menetap. Hal ini disebabkan oleh jaringan parut,
penebalan mukosa, polip, jaringan granulasi atau
timpanoslerosis.
5. Faktor-faktor konstitusi dasar seperti alergi, kelembaban umum
atau perubahan mekanisme pertahanan tubuh (Ballenger, 1997;
Antonelli, 2006).
2.5.4 Patologi
Infeksi kronis maupun infeksi akut berulang pada hidung dan
tenggorok dapat menyebabkan gangguan fungsi tuba eustachius sehingga
rongga timpani mudah mengalami gangguan fungsi hingga infeksi dengan
akibat mengeluarkan sekret terus-menerus atau hilang timbul (Adhikari,
2007).
Peradangan pada membran timpani menyebabkan proses kongesti
vaskuler, sehingga terjadi suatu daerah iskemi, selanjutnya terjadi daerah
nekrotik yang berupa bercak kuning, yang bila disertai tekanan akibat
penumpukan sekret dalam rongga timpani dapat mempermudah terjadinya
perforasi membran timpani. Perforasi yang menetap akan menyebabkan
kanalis auditorius eksternus dan dari luar dapat dengan bebas masuk ke
dalam rongga timpani, menyebabkan infeksi mudah berulang atau bahkan
berlangsung terus-menerus. Keadaan kronik ini lebih berdasarkan waktu dan
stadium daripada keseragaman gambaran patologi. Ketidakseragaman
gambaran patologi ini disebabkan oleh proses yang bersifat kambuhan atau
menetap, efek dari kerusakan jaringan, serta pembentukan jaringan parut
(Lasisi, 2008; Lin, Lin, Lee et al, 2009).
Selama fase aktif, epitel mukosa mukosa mengalami perubahan
menjadi mukosa sekretorik dengan sel goblet yang mengekskresi sekret
mukoid atau mukopurulen. Adanya infeksi aktif dan sekret persisten yang
berlangsung lama menyebabkan mukosa mengalami pross pembentukan
jaringan granulasi dan atau polip. Jaringan patologis dapat menutup
membran timpani, sehingga menghalangi drainase, menyebabkan penyakit
menjadi persisten (Kenna dan Latz, 2006).
Perforasi membran timpani ukurannya bervariasi. Pada proses
penutupannya dapat terjadi pertumbuhan epitel skuamosa masuk ke telinga
tengah, kemudian terjadi proses deskuamasi normal yang akan mengisi
telinga tengah dan antrum mastoid, selanjutnya membentuk kolesteatoma
akuisita sekunder, yang merupakan media yang baik bagi pertumbuhan
kuman patogen dan bakteri pembusuk. Kolesteatoma ini mampu
menghancurkan tulang di sekitarnya termasuk rangkaiain tulang
pendengaran oleh reaksi erosi dari enzim osteolitik atau kolegenase yang
proses penutupan membran timpani dapat juga terjadi pembentukan
membran atrofi dua lapis tanpa unsur jaringan ikat, dimana membran bentuk
ini akan cepat rusak pada periode infeksi aktif (Kenna dan Latz, 2006; Bhat
dan Manjunath, 2007).
2.5.5 Etiologi
OMSK dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :
a. Lingkungan
Hubungan penderita OMSK dan faktor sosial ekonomi belum jelas,
tetapi mempunyai hubungan erat antara penderita dengan OMSK
dan sosioekonomi, dimana kelompok sosioekonomi rendah
memiliki insiden yang lebih tinggi. Tetapi sudah hampir dipastikan
hal ini berhubungan dengan kesehatan secara umum, diet dan
tempat tinggal yang padat.
b. Genetik
Faktor genetik masih diperdebatkan sampai saat ini, terutama
apakah insiden OMSK berhubungan dengan luasnya sel mastoid
yang dikaitkan sebagai faktor genetik. Sistem sel-sel udara
mastoid lebih kecil pada penderita otitis media, tapi belum
diketahui apakah hal ini primer atau sekunder.
Secara umum dikatakan otitis media kronis merupakan kelanjutan
dari otitis media akut atau otitis media dengan efusi, tetapi tidak
diketahui faktor apa yang menyebabkan satu telinga dan bukan
yang lainnya berkembang menjadi keadaan kronis.
d. Infeksi
Bakteri yang diisolasi dari mukopus atau mukosa telinga tengah
baik aerob ataupun anaerob menunjukkan organisme yang
multipel. Organisme yang terutama dijumpai adalah gram negatif,
bowel-type flora dan beberapa organisme lainnya.
e. Infeksi saluran napas atas
Banyak penderita mengeluh sekret telinga sesudah terjadi infeksi
saluran nafas atas. Infeksi virus dapat mempengaruhi mukosa
telinga tengah dan menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh
terhadap organisme yang secara normal berada dalam telinga
tengah, sehingga memudahkan pertumbuhan bakteri.
f. Autoimun
Penderita dengan penyakit autoimun akan memiliki insiden lebih
besar terhadap otitis media kronis.
Penderita alergi mempunyai insiden otitis media kronis yang lebih
tinggi dibanding yang bukan alergi.
h. Gangguan fungsi tuba eustachius.
Pada otitis media supuratif kronis aktif, tuba eustachius sering
tersumbat oleh edema tetapi apakah hal ini merupakan fenomena
primer atau sekunder masih belum diketahui (Ballenger, 1997;
Kenna dan Latz, 2006; Akinpelu, Amusa, Komolafe et al, 2007).
2.5.6 Klasifikasi
Secara klinis OMSK dapat dibagi atas dua tipe yaitu:
a. Tipe Tubotimpanal
Disebut juga tipe aman/benigna, karena jarang menimbulkan
komplikasi yang berbahaya. Biasanya tipe ini didahului oleh
gangguan fungsi tuba yang menyebabkan kelainan di kavum
timpani. Tipe ini disebut juga dengan tipe mukosa karena proses
peradangannya biasanya hanya pada mukosa telinga tengah.
Perforasi pada tipe ini biasanya letaknya sentral.
b. Tipe Atikoantral
Disebut juga tipe maligna/berbahaya karena dapat menimbulkan
dapat juga terjadi proses erosi tulang atau kolesteatoma, granulasi
atau osteitis. Perforasi letaknya marginal atau atik (Ballenger,
1997, Lasisi, Olaniyan, Mulbi et al, 2007).
2.5.7 Gejala dan Tanda a. Telinga berair (otore)
Otore (aural discharge) merupakan manifestasi otitis media
kronis yang paling sering dijumpai (Mills, 1997). Pada OMSK tipe
benigna, cairan yang keluar biasanya bersifat mukopurulen yang tidak
berbau busuk. Keluarnya sekret biasanya hilang timbul. Sedangkan
pada OMSK tipe maligna, sekret yang keluar bersifat purulen dan
berbau busuk, berwarna abu-abu kotor kekuning-kuningan oleh karena
adanya kolesteatoma yang menyebabkan proses degenerasi epitel
dan tulang (Mills, 1997; Djaafar, 2004).
Keluarnya sekret dapat didahului oleh infeksi saluran nafas atas
atau kontaminasi dari liang telinga luar setelah mandi atau berenang
(Mills, 1997). Sekret yang bercampur darah berhubungan dengan
adanya jaringan granulasi dan polip telinga dan merupakan tanda
adanya kolesteatoma yang mendasarinya. Suatu sekret yang encer
tanpa disertai rasa nyeri mengarahkan kemungkinan suatu
tuberkulosis (Paparella, Adams & Levine, 1997).
Pada umumnya dijumpai tuli konduktif namun dapat pula
bersifat campuran. Gangguan pendengaran mungkin ringan sekalipun
proses patologi sangat hebat, karena daerah yang sakit ataupun
kolesteatoma dapat menghantarkan bunyi dengan efektif ke fenestra
ovale (Paparella, Adams & Levine, 1997).
c. Nyeri
Nyeri tidak lazim dikeluhkan penderita OMSK, dan bila ada
merupakan suatu tanda yang serius. Nyeri dapat berarti adanya
ancaman komplikasi akibat hambatan pengaliran sekret, terpaparnya
duramater atau dinding sinus lateralis atau ancaman pembentukan
abses otak (Paparella, Adams & Levine, 1997).
d. Vertigo
Hal ini merupakan gejala serius lainnya. Gejala ini memberikan
kesan adanya suatu fistula, berarti ada erosi pada labirin tulang dan
sering terjadi pada kanalis semisirkularis horizontal (Paparella, Adams
& Levine, 1997; Helmi, 2005).
e. Perforasi membran timpani
Perforasi membran timpani dapat bersifat sentral, subtotal, total,
atik ataupun marginal. Pada perforasi atik atau marginal perlu dicurigai
adanya kolesteatoma. Jaringan granulasi atau polip dapat juga
Tanda-tanda klinis OMSK tipe maligna:
a. Terdapat abses atau fistel retroaurikuler.
b. Terdapat polip atau jaringan granulasi di liang telinga luar yang berasal
dari dalam telinga tengah.
c. Terlihat kolesteatoma pada telinga tengah terutama di epitimpani.
d. Sekret berbentuk nanah dan berbau khas (aroma kolesteatoma).
e. Terlihat bayangan kolesteatoma pada foto Rontgen mastoid (Djaafar,
2004).
2.5.8 Diagnosis
Diagnosis OMSK dapat ditegakkan berdasarkan :
a. Anamnesis
Anamnesis yang lengkap sangat membantu menegakkan
diagnosis OMSK. Biasanya penderita datang dengan riwayat otore
menetap atau berulang lebih dari tiga bulan. Penurunan pendengaran
juga merupakan keluhan yang paling sering. Terkadang penderita juga
mengeluh adanya vertigo dan nyeri bila terjadi komplikasi.
b. Pemeriksaan otoskopi
Pemeriksaan otoskopi dapat melihat lebih jelas lokasi perforasi,
kondisi sisa membran timpani dan kavum timpani. OMSK ditegakkan
jika ditemukan perforasi membran timpani.
Pemeriksaan audiometri penting untuk menentukan fungsi
konduktif dan fungsi koklea. Dengan menggunakan audiometri nada
murni pada hantaran udara dan hantaran tulang serta penilaian
diskriminasi tutur, besarnya kerusakan tulang-tulang pendengaran
dapat diperkirakan dan bisa ditentukan manfaat operasi rekonstruksi
telinga tengah untuk perbaikan pendengarannya.
d. Pemeriksaan radiologi
Pemeriksaan radiologi dari mastoid perlu untuk melihat
perkembangan pneumatisasi mastoid dan perluasan penyakit. Foto
polos dan CT Scan dapat menunjukkan adanya gambaran
kolesteatoma dan keadaan tulang-tulang pendengaran juga dapat
diperhatikan.
e. Pemeriksaan mikrobiologi
Pemeriksaan mikrobiologi sekret telinga penting untuk
menentukan bakteri penyebab OMSK dan antibiotika yang tepat
(Ballenger, 1997; Mills, 1997; Helmi, 2005).
2.5.9 Komplikasi
Adams (1989) mengemukakan klasifikasi komplikasi sebagai berikut :
A. Komplikasi di telinga tengah :
1. Perforasi membran timpani persisten
2. Erosi tulang pendengaran
B. Komplikasi di telinga dalam :
1. Fistula labirin
2. Labirinitis supuratif
3. Tuli saraf (sensorineural)
C. Komplikasi di ekstradural :
1. Abses ekstradural
2. Trombosis sinus lateralis
3. Petrositis
D. Komplikasi ke susunan saraf pusat
1. Menigitis
2. Abses otak
3. Hidrosefalus otitis (Kenna dan Latz, 2006).
2.5.10 Penatalaksanaan
Ada dua hal yang penting diperhatikan apabila kita merawat penderita
OMSK yaitu kelainan patologi yang berperan sebagai sumber infeksi di dalam
telinga tengah serta seberapa jauh kelainan patologi tersebut sudah
mengganggu fungsi pendengaran (Wang, Nadol, Austin et al, 2000; Yuen,
Ho, Wei et al, 2000).
Prinsip terapi OMSK tipe benigna adalah konservatif atau
medikamentosa. Bila sekret keluar terus-menerus, maka diberikan obat
pencuci telinga berupa larutan H2O2 3% selama tiga sampai lima hari. Setelah
telinga yang mengandung antibiotika. Secara oral diberikan antibiotika sesuai
kultur dan tes sensitivitas (Alper, Dohar, Gulhan et al, 2000; Djaafar, 2004).
Bila sekret telah kering tetapi perforasi masih ada setelah diobservasi
selama 2 bulan, maka idealnya dilakukan miringoplasti atau timpanoplasti.
Operasi ini bertujuan untuk menghentikan infeksi secara permanen,
memperbaiki membran timpani yang perforasi, mencegah terjadinya
komplikasi atau kerusakan pendengaran yang lebih berat, serta memperbaiki
pendengaran (Djaafar, 2004).
Prinsip pengobatan pada OMSK tipe maligna adalah pembedahan,
yaitu mastoidektomi. Jadi bila terdapat OMSK tipe maligna maka terapi yang
tepat adalah dengan melakukan mastoidektomi dengan atau tanpa
timpanoplasti. Terapi konservatif dengan medikamentosa hanyalah
merupakan terapi sementara sebelum dilakukan pembedahan. Bila terdapat
abses retroaurikular, maka insisi abses sebaiknya dilakukan tersendiri
sebelum kemudian dilakukan mastoidektomi (Veldman, Braunius, 1998;
Djaafar, 2004).
2.6 Gangguan Pendengaran pada Otitis Media Supuratif Kronis
Gangguan pendengaran yang terjadi dapat bervariasi. Pada umumnya
gangguan pendengaran yang terjadi berupa tuli konduktif namun dapat pula
bersifat tuli saraf atau tuli campuran apabila sudah terjadi gangguan pada
telinga dalam misalnya akibat proses infeksi yang berkepanjangan atau
perforasi membran timpani serta keutuhan dan mobilitas sistem
penghantaran suara di telinga tengah (Djaafar, 2004). Perforasi yang lebih
besar dapat menyebabkan lebih banyak kehilangan suara yang
ditransmisikan ke telinga dalam (Maqbool, 1993). Suri dkk dalam
penelitiannya terhadap penderita OMSK tipe benigna di R.S. Sardjito
Yogyakarta menjumpai adanya hubungan yang bermakna antara besarnya
perforasi dengan derajat ketulian (Suri, Soekardono & Hulu, 1999). Hal yang
sama juga dijumpai oleh Rambe dalam penelitiannya terhadap penderita
OMSK di RSUP. H. Adam Malik Medan, bahwa terdapat hubungan yang
bermakna antara besarnya perforasi dengan derajat ketulian (Rambe, 2002).
Pada OMSK tipe maligna biasanya didapat tuli konduktif berat karena
putusnya rantai tulang pendengaran, tetapi seringkali kolesteatoma bertindak
sebagai penghantar suara ke foramen ovale sehingga gangguan
pendengaran mungkin ringan sekalipun proses patologis sangat hebat
(Djaafar, 2004). Pasien akan merasakan pendengaran yang makin buruk
apabila liang telinga dipenuhi oleh sekret dan akan berkurang apabila sekret
dibersihkan (Ramalingam, 1990).
Pada kenyataannya, gangguan pendengaran pada OMSK tidak
seluruhnya tuli konduktif murni. Tidak sedikit penderita OMSK menderita tuli
sensorineural atau tuli campur. Setiap kali ada infeksi didalam telinga tengah,
maka ada kemungkinan produk-produk infeksi akan menyebar melalui
fenestra rotundum ke telinga dalam, dan akan mengakibatkan ketulian
Rambe pada penelitiannya yang dilakukan antara April 2002 – Juli
2002 di RSUP. H. Adam Malik Medan terhadap 94 sampel telinga penderita
OMSK, mendapatkan jenis gangguan pendengaran yang terbanyak dijumpai
adalah tuli konduktif sebanyak 75 telinga (79,8%), tuli campur sebanyak 16
telinga (17%) dan tuli saraf sebanyak 3 telinga (3,2%) (Rambe, 2002).
Wisnubroto pada penelitian retrospektif di RS. Soetomo Surabaya
antara tahun 1999 – 2002, dari data rekam medis penderita OMSK yang
telah menjalani pembedahan telinga, tercatat hanya ada 475 rekam medis
yang dilengkapi hasil audiogram prabedah. Yang mengalami tuli konduktif
terdiri dari 93 (19,6%) kasus OMSK reversibel, 140 (29,5%) kasus OMSK
benigna dan 115 (24,2%) sebagian kasus OMSK maligna. Sisanya sebanyak
127 (26,7%) kasus OMSK maligna sudah mengalami tuli perseptif berat
sampai total (Wisnubroto, 2003).
Morisson (1969) melaporkan bahwa 25% dari kasus dengan
peradangan telinga tengah mengalami tuli sensorineural (Yeoh, 1997).
English et al (1973) pada penelitian terhadap 404 pasien dengan
OMSK, menjumpai adanya suatu hubungan antara lamanya penyakit dengan
derajat tuli sensorineural (Yeoh, 1997).
Cusimano et al (1989) juga melaporkan bahwa lamanya penyakit
mempunyai pengaruh terhadap terjadinya tuli sensorineural dan tidak
dijumpai adanya hubungan dengan umur sewaktu terjadinya serangan (Yeoh,
Nani dkk pada penelitiannya untuk mendeteksi ketulian sensorineural
terhadap penderita OMSK unilateral di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo
Ujung Pandang antara April 1996 – September 1996 menemukan dari 22
penderita yang ditemukan, terdapat 9 (40,9%) kasus yang terdeteksi adanya
ketulian sensorineural (Nani, Mangape & Sedjawidada, 1996).
De Azevedo et al pada penelitiannya terhadap 115 penderita OMSK
dengan dan tanpa kolesteatoma, mendapatkan 78 penderita OMSK dengan
kolesteatoma dan sebanyak 15 penderita (13%) mengalami tuli sensorineural
(De Azevedo et al, 2007).
Data subdivisi otologi THT-KL RSCM Jakarta antara Januari 2002 –
Desember 2006, dari 212 penderita OMSK tipe maligna yang menjalani
pembedahan telinga, didapatkan 53 penderita (25%) mengalami tuli
sensorineural (Restuti, 2007).
Insiden tuli campur (mixed hearingloss = MHL) pada OMSK telah
dilaporkan oleh banyak penulis. Paparella et al, sebagaimana dikutip oleh
Shenoi (1987) mendapatkan 279 kasus MHL diantara 500 telinga dengan
OMSK. Gardenghi melaporkan insiden MHL pada OMSK adalah 42%.
Sementara Bluvesteis melaporkan insiden MHL pada OMSK ini adalah 38%.
Nani (1996) melaporkan terdapat sekitar 5% dari 22 penderita OMSK
mengalami MHL. Di RSUP Dr. Kariadi Semarang, insiden MHL juga pernah
dilaporkan oleh Pradipto sebesar 12,75% dan Dullah (1996) mendapatkan
MHL sebanyak 44,5% dari 54 telinga dengan OMSK (Sari dan Samiharja,
Santoso dan Ahadiah pada penelitiannya terhadap penderita OMSK
tipe maligna dengan komplikasi ekstrakranial antara Januari 2004 –
Desember 2006 di RS. Dr. Soetomo Surabaya, mendapatkan dari 163
penderita ditemukan 56 penderita (34,36%) mengalami komplikasi
ekstrakranial dan jenis ketulian yang terbanyak ditemukan adalah MHL
(46,43%) (Santoso dan Ahadiah, 2007).
Terjadinya MHL pada OMSK ini menunjukkan bahwa lesi fungsional
telah terjadi di telinga tengah dan juga telinga dalam (Sari dan Samiharja,
1999).
Djafaar dalam penelitiannya yang dilakukan antara 1991–1993 di
RSCM Jakarta, menjumpai dari 145 pasien OMSK tipe berbahaya yang
berobat ditemukan 88 penderita (60%) tuli konduktif sedang berat, 8 orang
penderita (6%) dengan tuli campur, 18 penderita (12%) dengan tuli saraf
berat, dan sisanya 31 penderita (22%) tidak ada audiogramnya (Djaafar,
2001).
2.7 Audiometri Nada Murni
Audiometri nada murni adalah suatu cara pemeriksaan untuk
mengukur sensitivitas pendengaran dengan alat audiometer yang
mengunakan nada muni (pure tone) yaitu bunyi yang hanya mampunyai satu
frekuensi, dinyatakan dalam jumlah getaran per detik (Feldman dan Grimes,
Walaupun pemeriksaan audiometri nada murni tidak sepenuhnya
objektif, tetapi sampai sekarang masih merupakan yang paling banyak
dipakai untuk keperluan klinis oleh karena prosedurnya yang sederhana
namun dapat banyak memberi informasi tentang keadaan sistem
pendengaran (Feldman dan Grimes, 1997).
Audiometer yang tersedia di pasaran umumnya terdiri dari enam
komponen utama, yaitu:
a. Oskilator, yang menghasilkan berbagai nada murni
b. Amplifier, untuk menaikkan intensitas nada murni sampai dapat
terdengar
c. Pemutus (interrupter), yang memungkinkan pemeriksa menekan dan
mematikan tombol nada murni secara halus tanpa terdengar bunyi
lain (klik)
d. Attenuator, agar pemeriksa dapat menaikkan atau menurunkan
intensitas ke tingkat yang dikehendaki
e. Earphone, yag mengubah gelombang listrik yang dihasilkan oleh
audiometer menjadi bunyi yang dapat didengar
f. Sumber suara penganggu (masking), yang sering diperlukan untuk
meniadakan bunyi ke telinga yang tidak diperiksa (Feldman dan
Grimes, 1997).
Pada pemeriksaan audiometri nada murni perlu dipahami hal-hal
berikut ini :
Nada murni (pure tone) : merupakan bunyi yang hanya mempunyai satu frekuensi, dinyatakan dalam jumlah getaran per detik.
Bising : merupakan bunyi yang mempunyai banyak frekuensi, terdiri dari
narrow band (spektrum terbatas) dan white noise (spektrum luas).
Frekuensi : nada murni yang dihasilkan oleh getaran suatu benda yang sifatnya harmonis sederhana (simple harmonic motion). Jumlah getaran per
detik dinyatakan dalam Hertz.
Intensitas bunyi : dinyatakan dalam dB (decibel), dikenal dB HL (hearing level), dB SL (sensation level) dan dB SPL (sound pressure level).
Ambang dengar : bunyi nada murni yang terlemah pada frekuensi tertentu yang masih dapat didengar oleh telinga seseorang. Terdapat ambang dengar
menurut konduksi udara (AC) dan menurut konduksi tulang (BC). Bila
ambang dengar ini dihubung-hubungkan dengan garis, baik AC maupun BC,
maka akan didapatkan audiogram. Dari audiogram dapat diketahui jenis dan
derajat ketulian.
dapat didengar oleh telinga rata-rata orang dewasa muda yang normal (18-30
tahun).
Notasi pada audiogram : untuk pemeriksaan audiogram, dipakai grafik AC, yaitu dibuat dengan garis lurus penuh (intensitas yang diperiksa antara
125-8000 Hz) dan grafik BC yaitu dibuat dengan garis terputus-putus (intensitas
yang diperiksa antara 250-4000 Hz). Untuk telinga kiri dipakai warna biru
sedangkan untuk telinga kanan dipakai warna merah (Soetirto, Hendarmin &
Bashiruddin, 2004).
Dari audiogram dapat dilihat apakah pendengaran normal (N) atau
tuli. Jenis ketulian yaitu tuli konduktif, sensorineural atau tuli campur juga
dapat ditentukan (Soetirto, Hendarmin & Bashiruddin, 2004).
Derajat ketulian dihitung dengan menggunakan indeks Fletcher yaitu:
Ambang dengar (AD) = AD 500 Hz + AD 1000 Hz + AD 2000 Hz
3
Menurut kepustakaan terbaru frekuensi 4000 Hz berperan penting
untuk pendengaran, sehingga perlu turut diperhitungkan, sehingga derajat
ketulian dihitung dengan menambahkan ambang dengar 4000 Hz dengan
ketiga ambang dengar di atas, kemudian dibagi 4 (Soetirto, Hendarmin &
Ambang dengar (AD) =
AD 500 Hz + AD 1000 Hz + AD 2000 Hz + AD 4000 Hz
4
Dalam menentukan derajat ketulian, yang dihitung hanya ambang
dengar hantaran udara (AC) saja (Soetirto, Hendarmin & Bashiruddin, 2004).
Derajat ketulian ISO (International Standard Organization) :
0 – 25 dB : normal
>25 – 40 dB : tuli ringan
>40 – 55 dB : tuli sedang
>55 – 70 dB : tuli sedang berat
>70 – 90 dB : tuli berat
>90 dB : tuli sangat berat
(Soetirto, Hendarmin & Bashiruddin, 2004).
Manfaat audiometri nada murni :
a. Keadaan fungsi pendengaran masing-masing telinga secara kualitatif
b. Derajat gangguan pendengaran (kuantitatif) yaitu normal, tuli ringan, tuli
BAB 3