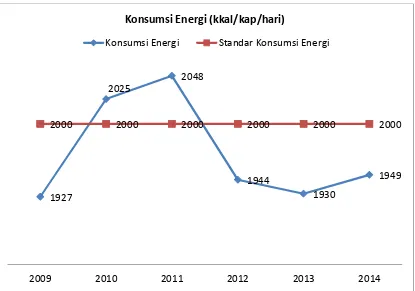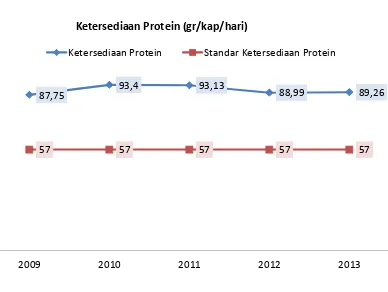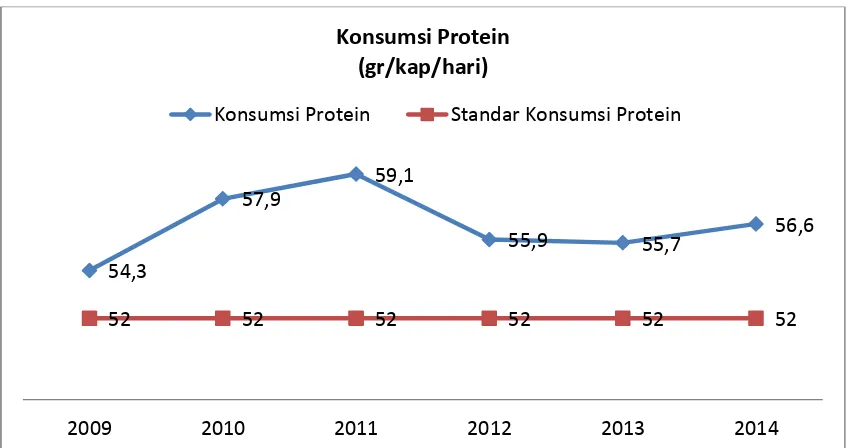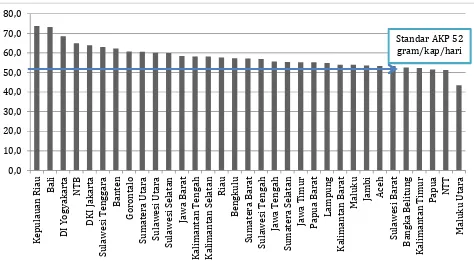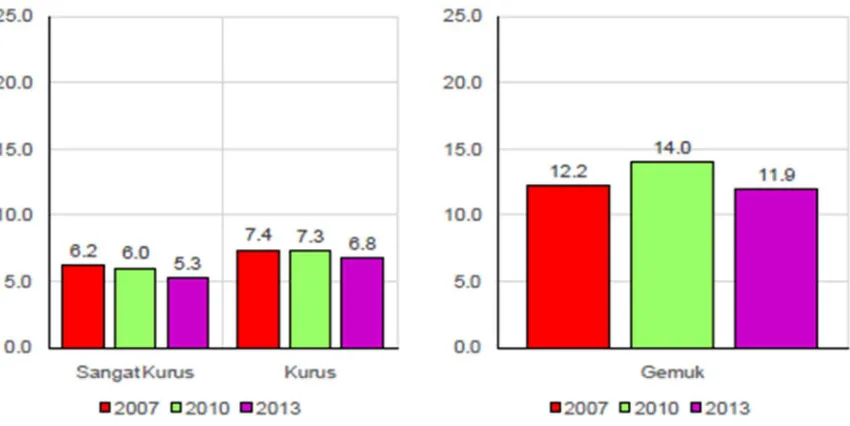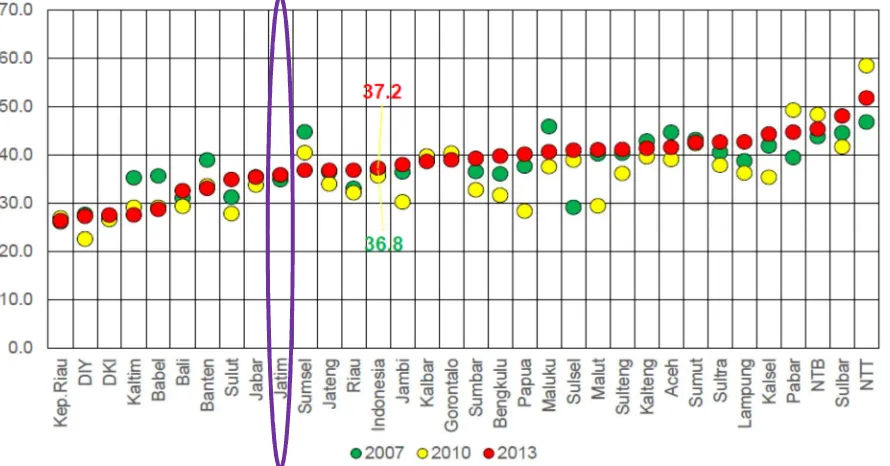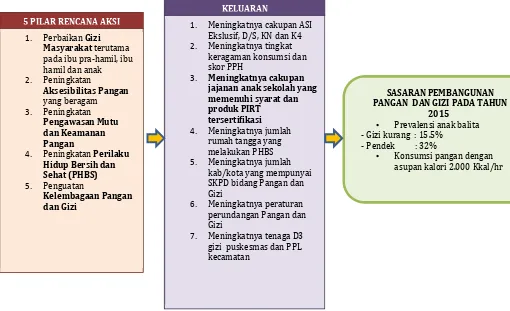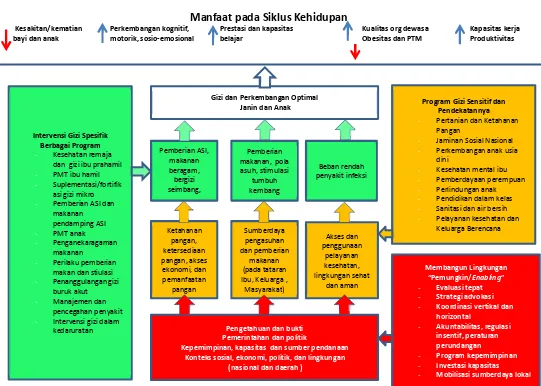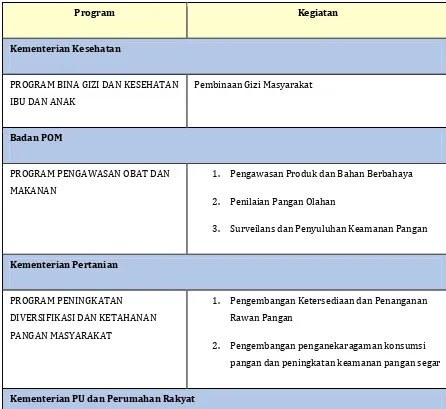i
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
Jl. Sudarman No. 1, 0331-421200, bappeda.jemberkab.go.id
ii
KATA PENGANTAR
Pangan dan Gizi saat ini merupakan kebutuhan mendasar untuk hidup
sehat sehingga merupakan isu penting dalam peningkatan kualitas sumber daya
manusia di suatu daerah. Kecukupan pangan suatu daerah akan terwujud bila di
wilayah tersebut ketahanan pangan telah berhasil dicapai. Berdasarkan Hasil
Sensus Penduduk Tahun 2000-2010, Kabupaten Jember merupakan daerah
dengan jumlah penduduk mencapai 2.451.081 jiwa dengan laju pertumbuhan
penduduk setiap tahunnya mencapai 0,067%. Pertambahan jumlah penduduk
ini menyebabkan kebutuhan pangan meningkat. Hingga saat ini belum ada
klasifikasi tingkat kerawanan pangan di Kabupaten Jember untuk
mengantisipasi tingkat kondisi kerawanan pangan. Kajian ini bertujuan
menganalisis situasi kerawanan pangan di tingkat kecamatan di Kabupaten
Jember, menganalisis kesesuaian intervensi dengan situasi kerawanan pangan
dan menyusun rekomendasi jenis intervensi pangan.
Data dianalisis secara deskriptif, diklasifikasikan ke dalam enam kategori
yaitu : (a) sangat rawan, (b) rawan, (c) agak rawan, (d) cukup tahan, (e) tahan,
dan (f) sangat tahan. Dasar yang digunakan adalah indicator kerawanan pangan
yaitu akses pangan sesuai indicator FIA (Food Insecurity Atlas) yang digunakan WFP (World Food Programme 2003) yang dipakai dalam analisis kerawanan pangan nasional. Gambaran umum ketersediaan pangan di Kabupaten Jember
dianalisis menggunakan data konsumtif normatif per kapita dibanding
ketersediaan produksi setara beras.
Akses pangan dianalisis menggunakan dua kriteria, yaitu (a) jumlah
rumah tangga miskin, (b) prosentase rumah tangga dengan akses listrik.
Kesehatan dan gizi dianalisis menggunakan enam kriteria, yaitu (a) Angka
Harapan Hidup (AHH), (b) prevalensi balita gizi kurang, (c) jumlah penduduk
per dokter sesuai dengan kepadatan penduduk, (d) persentase rumah tangga ke
akses air bersih, (e) persentase anak yang tidak diimunisasi dan (f) tingkat
konsumsi pangan. Dari indikator tersebut kemudian diranking sehingga di
dapat enam kategori kerawanan pangan di tingkat Kecamatan di Kabupaten
iii
Dalam rangka mendorong pengembangan dan peningkatan daya saing
Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Jember melalui analisis kerawanan
pangan di tingkat kecamatan di Kabupaten Jember, maka kajian mengenai
“Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi” perlu dilakukan agar arah kebijakan
pembangunan industri prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember dapat segera diwujudkan.
Laporan Akhir ini disusun sebagai informasi awal guna menjelaskan
alasan dan pertimbangan logis mengapa kajian ini perlu dilakukan disertai
dengan pendekatan penelitian secara sistematis yang menjelaskan
teknik-teknik analisis yang shahih dan relevan yang digunakan dalam kajian. Pada
laporan ini dijelaskan tahap-tahap analisis kajian secara lengkap, variabel
operasional dan parameter-parameter kajian yang diperlukan dalam analisis
berserta output kajian yang akan dicapai yang kesemuanya disajikan secara ringkas dan jelas.
Akhirnya kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi
kesempurnaan laporan ini. Semoga Laporan Akhir ini dapat memberikan
manfaat bagi semua pihak.
Jember, Juni 2015
iv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ... i
KATA PENGANTAR ... ii
DAFTAR ISI ... iv
DAFTAR TABEL ... vi
DAFTAR GAMBAR ... viii
BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1
1.2 Perumusan Masalah ... 2
1.3 Maksud dan Tujuan Kajian ... 3
1.4 Manfaat Kajian ... 4
1.5 Sasaran Kajian ... 4
1.6 Ruang Lingkup Kajian ... 4
BAB II. KERAWANAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.1 Difinisi Kerawanan Pangan ... 7
2.2 Indikator Kerawanan Pangan ... 8
2.3 Konsep Ketahanan Pangan ... 11
BAB III. KEBIJAKAN NASIONAL PANGAN DAN GIZI 3.1 Kondisi Pangan dan Gizi Nasional ... 16
3.2 Kebijakan pembangunan gizi masyarakat dalam RPJMN 2015 – 2019 ... 24
3.3 Kebijakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (RPJMN 2015 – 2019) ... 30
BAB IV. KEBIJAKAN PANGAN DAN GIZI PROVINSI JAWA TIMUR 4.1 Kondisi Umum ... 39
4.2 Peranan RAD-PG dalam Percepatan Perbaikan Gizi ... 41
4.3 Konsep Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Jawa Timur 2011-2015 ... 43
v
BAB V. METODE PENELITIAN
5.1 Desain, Lokasi, dan Waktu Kegiatan ... 57
5.2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan ... 57
5.3 Metode Pengumpulan Data ... 59
5.4 Metode Analisis ... 60
5.5Definisi Operasional ... 71
5.6 Jadwal Kegiatan ... 73
BAB VI. ANALISISDATA PANGAN DAN GIZI KABUPATEN JEMBER 6.1 Analisis Kondisi Umum Pangan dan Gizi ... 74
6.2 Analisis Wilayah Rawan Pangan ... 78
6.3 Strategi Pencapaian Pangan dan Gizi ... 122
6.4 Rumusan Rencana Aksi Pangan dan Gizi ... 126
BAB VII. KESIMPULAN DAN PENUTUP 7.1 Kesimpulan ... 141
7.2 Penutup ... 142
DAFTAR PUSTAKA ... 143
vi
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Sasaran RPJMN 2015-2019 tentang peningkatan
status gizi ... 33
Tabel 3.2 Program Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat ... 36
Tabel 4.1 Sasaran Penurunan Kerawanan Pangan dan Peningkatan Gizi Masyarakat ... 52
Tabel 4.2. Sasaran Ketersediaan dan Konsumsi Pangan di Jawa Timur ... 52
Tabel 4.3 Sasaran Pola Pangan Harapan (PPH) ... 53
Tabel 4.4 Indikator Penentuan Prioritas Lokasi Sasaran ... 54
Tabel 4.5 Prioritas Lokasi Sasaran RAD-PG Jawa Timur ... 55
Tabel 5.1 Jenis dan Sumber Data ... 61
Tabel 5.2 Indikator dan Definisi Komponen Kerawanan Pangan ... 62
Tabel 5.3 Penilaian pada masing-masing indikator kerawanan pangan ... 64
Tabel 5.4 Rangking tingkat kerawanan pangan ... 66
Tabel 5.5 Definisi Skala Saaty ... 69
Tabel 5.6 Jadwal Kegiatan ... 73
Tabel 6.1 Angka Kecukupan Protein dan Energi Masyarakat Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2008 ... 75
Tabel 6.2. Angka Kecukupan Protein dan Energi Masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2008 ... 77
Tabel 6.3 Formula dan Kriteria Penilaian Presentase Rumah Tangga Miskin ... 79
Tabel 6.4 Rumah Tangga Pra-Sejahtera dan Sejahtera I ... 79
Tabel 6.5 Formula dan Kriteria Penilaian Presentase RT dengan akses listrik ... 81
Tabel 6.6 Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Listrik ... 81
Tabel 6.7 Formula dan Kriteria Penilaian Angka Harapan Hidup ... 83
Tabel 6.8 Capaian MDGs4 Per Puskesmas Kabupaten Jember Tahun 2014 ... 83
vii
Tabel 6.10 Capaian MDGs1 Per Puskesmas Dan Kabupaten Jember Tahun 2014
... 85
Tabel 6.11. Formula dan Kriteria Penilaian Jumlah Penduduk per Dokter
... 87
Tabel 6.12 Jumlah Tenaga Medis (Dokter Umum & Spesialis) di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2014
... 88
Tabel 6.13 Jumlah Tenaga Medis (Dokter Gigi & Dokter Gigi Spesialis) di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2014
... 90
Tabel 6.14a Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010
... 92
Tabel 6.14b Perhitungan Rasio Jumlah Penduduk dengan Jumlah Dokter
... 93
Tabel 6.15. Formula dan Kriteria Penilaian Persentase
Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih
... 95
Tabel 6.17 Formula dan Kriteria Penilaian Persentase Balita
yang Tidak Diimunisasi ... 97
Tabel 6.18 (Universal Child Immunization) UCI Kabupaten
Jember ... 97
Tabel 6.19 Formula dan Kriteria Penilaian Tingkat
Konsumsi Pangan ... 99
Tabel 6.20 Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan
Kelompok Bahan Pangan Kecamatan Kaliwates ... 99
Tabel 6.21 Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan
Kelompok Bahan Pangan Kecamatan Sumbersari ... 100
Tabel 6.22 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Aktual Pedesaan
Golongan Pengeluaran I (< 100.000) ... 101
Tabel 6.23 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Aktual Pedesaan
Golongan Pengeluaran II (100.000-149.999)
... 102
Tabel 6.24 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Pedesaan
Golongan Pengeluaran III (150.000-199.999) ... 103
Tabel 6.25 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Pedesaan
Golongan Pengeluaran IV (200.000-299.999)
... 104
Tabel 6.26. Skor Pola Pangan Harapan Aktual Pedesaan
Golongan Pengeluaran V (300-000-499.999) ... 104
Tabel 6.27 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Pedesaan
Golongan Pengeluaran VI (500.000-749.999) ... 104
Tabel 6.28 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Pedesaan
Golongan Pengeluaran VII (750.000- 999.999) ... 105
Tabel 6.29 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Pedesaan
Golongan Pengeluaran VIII (>1.000.000)
viii
Tabel 6.30. Skor Pola Pangan Harapan Aktual Perkotaan
Golongan Pengeluaran I (< 100.000)
... 107
Tabel 6.31 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Perkotaan Golongan Pengeluaran II (100.000-149.999) ... 107
Tabel 6.32 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Perkotaan Golongan Pengeluaran III (150.000- 199.999) ... 108
Tabel 6.33 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Perkotaan Golongan Pengeluaran IV (200.000-299.999) ... 109 Tabel 6.34 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Perkotaan Golongan Pengeluaran V (300-000-499.999) ... 109
Tabel 6.35 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Perkotaan Golongan Pengeluaran VI (500.000-749.999) ... 110
Tabel 6.36 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Perkotaan Golongan Pengeluaran VII (750.000-999.999) ... 111
Tabel 6.37 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Perkotaan Golongan Pengeluaran VIII (>1.000.000) ... 111
Tabel 6.38 Tingkat Kecukupan Dan Kategori Energi Konsumsi Masyarakat Kabupaten Jember Wilayah Pedesaan ... 112
Tabel 6.39 Tingkat Kecukupan Dan Kategori Energi Konsumsi Masyarakat Kabupaten Jember Wilayah Perkotaan ... 113
Tabel 6.40 Rerata Total Tingkat Kecukupan Dan Kategori Energi Konsumsi Masyarakat Kabupaten Jember Wilayah Pedesaan dan Perkotaan ... 113
Tabel 6.41 Tingkat Kecukupan Dan Kategori Protein Konsumsi Masyarakat Kabupaten Jember wilayah Pedesaan ... 114
Tabel 6.42 Tingkat Kecukupan Dan Kategori Protein Konsumsi Masyarakat Kabupaten Jember wilayah Perkotaan ... 115
Tabel 6.43 Rerata Total Tingkat Kecukupan Dan Kategori Protein Konsumsi Masyarakat Kabupaten Jember wilayah Pedesaan dan Perkotaan ... 115
Tabel 6.44 Rekapitulasi Analisis Wilayah Rawan Pangan ... 116
Tabel 6.45 Hasil Pendataan Tinggi Badan Balita Tahun 2014 ... 119
Tabel 6.46 Pair Comparation Matrix ... 122
Tabel 6.47 Pair-wise Comparation Matrix-Ketahanan Pangan ... 123
Tabel 6.48 Pair-wise Comparation Matrix-Status Kesehatan ... 124
Tabel 6.49 Pair-wise Comparation Matrix-Status Gizi ... 124
Tabel 6.50 Overall Composite Weight ... 125
ix
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Kerangka berpikir kajian ... 6
Gambar 2.1 Faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan ... 9
Gambar 2.2 Kerangka berpikir penyebab masalah gizi (UNICEF 1990) ... 11
Gambar 3.1 Ketersediaan Energi dan Standar Ketersediaan Energi ... 19
Gambar 3.2 Konsumsi Energi dan Standar Konsumsi Energi ... 20
Gambar 3.3 Ketersediaan protein ... 21
Gambar 3.4 Konsumsi protein nasional ... 22
Gambar 3.5 Konsumsi Energi (kkal/kap/hari) per Provinsi Tahun 2014 ... 22
Gambar 3.6 Konsumsi protein (gram/kap/hari) per provinsi tahun 2014 ... 23
Gambar 3.7 Skor PPH dan Target ... 24
Gambar 3.8 Kecenderungan nasional: 2007 – 2013 proporsi gizi kurang dan pendek*) pada balita ... 25
Gambar 3.9 Kecenderungan nasional: 2007 – 2013 Proporsi kurus dan gemuk*) pada balita ... 26
Gambar 3.10 Kecenderungan prevalensi balita stunting di indonesia menurut provinsi ... 27
Gambar 3.11 Rata-rata tinggi badan anak umur 5-18 tahun dibanding rujukan (WHO 2007): 2007 – 2013 ... 27
Gambar 3.12 Sinergi lintas bidang interaksi K/L dalam mengukur hasil pembangunan ... 30
Gambar 3.13 Sasaran RPJMN 2015-2019 tentang peningkatan status gizi ... 33
Gambar 3.14 Intergrasi RAN-PG dan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi ... 34
Gambar 3.15 Konsep RAN-PG ... 35
Gambar 4.1 Kedudukan RAN/RAD-PG dalam perencanaan pembangunan nasional ... 42
x
Gambar 4.3 Kerangka Konsep Implementasi Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Jawa Timur 2011-
... 46
Gambar 4.4 Status Gizi Balita berdasarkan berat Badan Menurut Provinsi ... 47
Gambar 4.5 Status Gizi Balita berdasarkan berat Badan Jawa Timur, 2010 ... 47
Gambar 4.6 Status gizi balita berdasarkan tinggi badan ... 48
Gambar 4.7 Status gizi balita berdasarkan berat badan ... 48
Gambar 4.8 Peranan Jawa Timur Dalam Penyediaan pangan Nasional ... 49
Gambar 5.1 Tahapan Kajian dan Metode Analisisnya ... 58
Gambar 6.1 Rata-rata tinggi badan anak umur 5-18 tahun dibanding rujukan (WHO): 2007-2013 ... 117
Gambar 6.2 Konsep Jangka Menengah dan Panjang Perbaikan Gizi di Indonesia ... 118
Gambar 6.3 Dasar hukum kebijakan gizi masyarakat ... 121
Gambar 6.4 Kegiatan Direktorat Bina Gizi ... 121
Gambar 6.5 Lokasi sasaran untuk rumah tangga miskin ... 132
Gambar 6.6 Lokasi Sasaran untuk Rasio Jumlah Penduduk/Dokter ... 133
Gambar 6.7 Persentase Desa/Kelurahan (Universal Child Immunization) UCI ... 135
1
1.1 Latar Belakang
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, usaha untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia diatur dalam UUD 1945 pasal 28
ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap individu berhak hidup sejahtera, dan
pelayanan kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu
pemenuhan pangan dan gizi untuk kesehatan warga negara merupakan
investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa
Indonesia.
Kebijakan tentang pangan tertuang dalam Undang-Undang nomor 7
tahun 1996 tentang Pangan menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan
dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat.
Pemenuhan hak atas pangan dicerminkan di dalam definisi Ketahanan Pangan
yaitu: ”kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari
tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata
dan terjangkau“.
Kecukupan pangan yang baik mendukung tercapainya status gizi yang
baik, sehingga akan memperlancar penerapan Program Wajib Belajar 9 Tahun
sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menegaskan
bahwa “Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor
meliputi produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan dengan
kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya”.
Ketahananan pangan merupakan salah satu prioritas dalam Rencana
Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2010-2014 yang ditetapkan
melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010. Instruksi
Presiden No. 3 Tahun 2010 menginstruksikan perlunya disusun Rencana Aksi
Pangan dan Gizi Nasional dan Rencana Aksi Pangan dan Gizi di tingkat provinsi
2
Aksi Pangan dan Gizi disusun dalam program berorientasi aksi yang terstruktur
dan terintegratif dalam lima pilar rencana aksi yaitu perbaikan gizi masyarakat,
peningkatan aksesibilitas pangan, peningkatan pengawasan mutu dan
keamanan pangan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta
penguatan kelembagaan pangan dan gizi.
Permasalahan dalam hal konsumsi pangan yang dihadapi, tidak hanya
berupa ketidakseimbangan komposisi pangan, tetapi juga masalah masih belum
terpenuhinya kecukupan gizi. Penganekaragaman konsumsi pangan
mempunyai tujuan utama untuk peningkatan mutu gizi konsumsi pangan.
Berkaitan dengan itu, untuk dasar perencanaan dan untuk mengukur
keberhasilan, berbagai upaya di bidang produksi, penyediaan dan konsumsi
pangan penduduk baik nasional maupun lokal, diperlukan suatu indikator
seperti skor Pola Pangan Harapan (PPH).
Berdasarkan data PPLS 2011 yang dikeluarkan oleh BPS, jumlah rumah
tangga miskin di Kabupaten Jember mencapai 246.063 RTM. Angka ini
merupakan yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Masih banyaknya jumlah
penduduk miskin tersebut ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan,
kesehatan, kemampuan daya beli dan pendapatan membawa pengaruh yang
signifikan pada Human Development Index (HDI) atau Indek Pembangunan Manusia. Dalam hal ini Kabupaten Jember berada pada posisi bawah bila
dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Timur. Hal ini akan
mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pangan, kuantitas dan kualitas konsumsi
pangan dan status gizi penduduk.
Oleh karena itu, sangatlah penting bagi Pemerintah Kabupaten Jember
untuk merumuskan suatu kebijakan perencanaan pangan dan gizi untuk
mewujudkan ketahanan pangan yang berbasis sumberdaya lokal. Hal inilah
yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian tetang studi perumusan
kebijakan berupa PenyusunanRencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).
1.2 Perumusan Masalah
Rawan pangan merupakan kondisi tidak tersedianya pangan dengan
3
terjangkau. Hingga saat ini belum ada klasifikasi tingkat kerawanan pangan di
Kabupaten Jember untuk mengantisipasi kondisi rawan pangan.
Upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam mengatasi permasalahan
gizi buruk berupa PMT (Pemberian Makanan Tambahan), KUK (Kredit Usaha
Kecil), penanggulangan kemiskinan serta penyuluhan pangan dan gizi,
perbaikan sarana dan prasarana hingga saat ini belum dianalisis pengaruhnya
terhadap perbaikan gizi balita di Kabupaten Jember. Kajian ini melakukan
penelusuran kesesuaian program yang telah dilakukan instansi terkait terhadap
kerawanan pangan.
1.3 Maksud dan Tujuan Kajian
Penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan arahan dan
dijadikan sebagai salah satu bahan bagi pemerintah daerah Kabupaten Jember
dalam merumuskan kebijakan pangan dan gizi, dimana program-program yang
akan diterapkan diharapkan mampu menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,
berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu dapat juga dijadikan sebagai salah
satu acuan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan,
dan pada akhirnya kejadian kerawanan pangan dapat diatasi dan diantisipasi
sedini mungkin.
Tujuan Umum dari kegiatan ini adalah:
Merumuskan kebijakan pangan dan gizi untuk mendukung peningkatan
kualitas sumberdaya manusia sebagaimana termaktub dalam RPJMD
Kabupaten Jember
Tujuan Khusus dari kegiatan ini adalah:
a) Menganalisis situasi pencapaian pangan dan gizi di Kabupaten Jember
b) Merumuskan strategi pencapaian pangan dan gizi untuk menanggulangi
wilayah rawan pangan di Kabupaten Jember
c) Merumuskan rencana aksi pangan dan gizi guna mewujudkan ketahanan
4
1.4 Manfaat Kajian
Manfaat dari kajian ini adalah sebagai berikut:
a. Memberikan informasi mengenai produksi dan ketersediaan pangan,
distribusi dan akses pangan, dan pola konsumsi pangan di kabupaten
Jember.
b. Memberikan informasi tentang peta wilayah rawan pangan di Kabupaten
Jember sehingga berguna untuk perumusan kebijakan penentuan sasaran
bantuan pangan dan gizi masyarakat.
c. Memberikan informasi mengenai faktor – faktor utama penyebab rawan
pangan di kabupaten Jember sebagai dasar untuk menyusun
program-program prioritas dalam peningkatan ketahanan pangan.
d. Memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan untuk
merencanakan program-program terpadu lintas SKPD dalam rangka
menanggulangi wilayah rawan pangan di Kabupaten Jember.
e. Meningkatkan sinergitas lintas SKPD dalam menjalankan program
kegiatan terpadu, dan memperbaiki efektifitas intervensi pemerintah
dalam program peningkatan produksi pangan dan gizi masyarakat.
1.5. Sasaran Kajian
Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen operasional
tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi Kabupaten Jember sebagai panduan
dan acuan bagi institusi pemerintah, lembaga legislatif, organisasi non
pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain untuk berperan serta
meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan ketahanan
pangan dan perbaikan gizi.
1.6. Ruang Lingkup Kajian
Kajian Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Jember meliputi
strategi, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam perbaikan pangan
dan gizi untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan status gizi
masyarakat di Kabupaten Jember yang tercermin pada tercukupinya kebutuhan
5
Rencana Aksi Daerah dikembangkan berdasarkan visi dan misi
Kabupaten Jember, Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Jember, komitmen
pencapaian tujuan pembangunan millenium (MDGs), serta dokumen kebijakan
pembangunan lainnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan
masyarakat. Program dan kegiatan yang dikembangkan diarahkan untuk
mencegah, menangani dan menanggulangi wilayah rawan pangan di Kabupaten
Jember dari aspek ketersediaan pangan, aspek distribusi dan akses pangan, dan
aspek kesehatan dan gizi.
Wilayah rawan pangan dan gizi adalah suatu kondisi yang dicerminkan
aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan dan aspek kesehatan dan gizi.
1. Aspek akses pangan
Aspek akses pangan dilihat dari kemampuan memanfaatkan potensi
pangan di wilayah sehingga tersedia rumah tangga dalam jumlah dan kaulitas
yang cukup. Akses akses pangan dinilai berdasar persentase rumah tangga
miskin dan persentase akses jalan memadai.
Persentase rumah tangga miskin adalah gambaran penduduk yang tidak
memiliki akses produktif terhadap mata pencaharian. Semakin tinggi
persentase rumah tangga miskin, maka semakin kecil akses memperoleh
pangan.
Akses jalan menggambarkan kemudahan akses baik ke pasar bagi
produsen dan konsumen. Daerah yang terhubung dengan baik akan menerima
dukungan infrastruktur lain untuk meningkatkan mata pencaharian penduduk.
Akses kesehatan dan sanitasi dinilai dari fasilitas kesehatan, persentase
rumah tangga ke akses air bersih dan rasio jumlah penduduk per dokter
terhadap kepadatan penduduk.
Akses fasilitas kesehatan menceritakan rumah tangga mendapat
pelayanan kesehatan sehingga kemudahan pelayanan kesehatan menjadi sangat
penting dalam rangka menurunkan angka penduduk yang sakit. Akses air
minum yang aman dan bersih merupakan penyebab tidak langsung dari rawan
pangan dan gizi. Hal ini dikarenakan air yang tidak bersih meningkatkan
6 2. Aspek kesehatan dan gizi
Komponen kesehatan dan gizi merupakan indikator dampak langsung
dan tidak langsung terhadap tingkat kerawanan pangan rumah tangga. Dampak
langsung dihitung berdasarkan Angka Harapan Hidup (AHH), prevalensi balita
gizi kurang (BB/U) dan konsumsi pangan. Akibat tidak langsung dihitung dari
indikator rasio jumlah penduduk per dokter, persentase rumah tangga dengan
akses air bersih dan persentase anak yang tidak mendapat imunisasi. Indikator
yang digunakan merujuk indicator yang digunakan Dewan Ketahanan Pangan RI
dan Program Pangan Dunia PBB (2003).
Program pemerintah yang telah dilaksanakan melalui instansi terkait
dibandingkan dengan indikator kerawanan pangan pada masing-masing
kecamatan. Penilaian yang dihasilkan disampaikan rekomendasi yang sesuai
dengan kebutuhan dalam rangka mengurangi tingkat kerawanan pangan pada
masing-masing kecamatan. Kerangka berpikir kajian ini adalah sebagai berikut.
Gambar 1.1. Kerangka Berpikir Kajian
(Tingkat kecamatan) Ketersediaan Konsumtif Normatif)
Tingkat
kerawanan pangan Akses pangan 1. Persen RT Miskin 2. Persen RM akses Listrik
Program/Intervensi Pemerintah
Kesehatan dan Gizi
Dampak Langsung: 1. AHH
2. Prevalensi Balita Gizi Kurang 3. Tingkat Konsumsi Pangan Dampak Tak Langsung
1. Rasio Jumlah Penduduk per Dokter
7
BAB II. KERAWANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.1 Definisi Kerawanan Pangan
Kerawanan pangan adalah kondisi ketidakcukupan pangan baik yang
dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga/individu. Kerawanan pangan
dapat terjadi berulang-ulang pada waktu tertentu (kronis) dan dapat pula
akibat bencana alam maupun bencana sosial.
Kondisi rawan pangan dapat disebabkan: (a) tidak adanya akses
ekonomi bagi rumah tangga /individu untuk memperoleh pangan yang cukup;
(b) tidak adanya akses fisik untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak
tercukupinya pangan untuk kehidupan produktif bagi rumah tangga/individu;
(d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup baik dalam jumlah, mutu, ragam,
keamanan serta keterjangkauan harga (Murniningtyas dan Atmawikarta, 2006);
Badan Bimas Ketahanan Pangan (2001).
Rawan pangan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan memperoleh
pangan cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan
terjadi apabila setiap individu hanya mampu memenuhi 80% kebutuhan pangan
dan gizi hariannya. Kondisi kerawanan pangan yang lebih parah apabila setiap
individu tidak mampu memenuhi 70% dari kebutuhan pangan dan gizi
berturut-turut selama 2 bulan diikuti penurunan berat badan (Pusat
Pengembangan Distribusi Pangan (DKP), 2005).
Kerawanan pangan dapat dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu: (a) tingkat
nasional/regional, rumah tangga dan individu. Kerawanan pangan tingkat
nasional merupakan situasi dimana pasokan pangan lebih rendah dari
permintaan, sehingga harga tidak wajar. Kerawanan pangan nasional dapat
disebabkan ketidakmampuan mengimpor pangan yang memadai (Dewan
Ketahanan Pangan dan Program PBB (2003).
Dampak kerawanan pangan dan kekurangan gizi dapat terjadi baik pada
skala makro dan mikro. Dampak skala mikro adalah pada semua kelompok
umur yaitu orang tua, orang dewasa, anak-anak, bayi dan para wanita termasuk
wanita hamil. Dampak yang ditimbulkan adalah: (a) malnutrisi pada orang tua,
8
kesempatan bekerja dan pendapatan menurun dan umur harapan hidup
rendah; (b) penurunan derajat kesehatan dan kemampuan fisik usia produktif
dengan tingkat kesakitan meningkat, absensi meningkat, pertumbuhan dan
daya tangkap menurun, kriminalitas meningkat; (c) malnutrisi pada wanita
hamil dan meningkatnya angka kematian ibu hamil, perkembangan otak janin
dan pertumbuhan terhambat, berat bayi lahir rendah; (d) penurunan derajat
kesehatan pada anak-anak, keterbelakangan mental, penyapihan yang tidak
cukup waktu sehingga mudah terkena infeksi serta kekurangan amkanan; €
penurunan berat badan bayi, meningkatnya angka kematian, terganggunya
perkembangan mental dan meningkatnya resiko terkena penyakit kronis
setelah dewasa. Dampak skala mikro adalah timbulnya permasalahan pada
kehidupan masyarakat, ditandai sulitnya mata pencaharian, menurunnya daya
beli serta tingginya angka kriminalitas (Deptan 2006).
2.2 Indikator Kerawanan Pangan
Indikator pencapaian ketahanan pangan dibedakan atas indikator proses
dan indikator dampak. Indikator proses menggambarkan situasi pangan yang
ditunjukkan ketersediaan dan akses pangan. Indikator dampak meliputi
indikator langsung maupun tidak langsung. Indikator ketersediaan pangan
berkaitan dengan produksi pertanian, iklim, akses sumber daya alam,
pengelolaan lahan, pengembangan institusi, pasar, konflik regional dan
kerusuhan social. Indikator akses pangan meliputi sumber pendapatan, akses
kredit modal, strategi rumah tangga dalam memenuhi kekurangan pangan.
Indikator dampak secara langsung meliputi konsumsi, frekuensi pangan
dan status gizi, sedangkan indikator dampak secara tak langsung meliputi
penyimpanan pangan. Setiawan (2002) merangkum beragam indikator
ketahanan pangan rumah tangga sesuai aspek ketersediaan akses dan
9
Gambar 2.1. Faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan
Sumber : Setiawan 2002
Aspek ketersediaan dan stabilitas pangan dipengaruhi oleh sumberdaya
(alam, manusia dan sosial) serta produksi pangan (on farm dan off farm). Akses pangan menunjukkan jaminan bahwa setiap rumah tangga dan individu
mempunyai sumberdaya cukup dalam memenuhi kebutuhan pangan sesuai
ukuran gizi. Akses pangan tercermin dari kemampuan rumah tangga
meningkatkan pendapatan dan produksi pangan. Akses pangan tergantung juga
pada pengetahuan sumberdaya manusia serta sumberdaya sosial. Aspek
pemanfaatan pangan mencerminkan kemampuan mengubah pangan menjadi
energi yang tepat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemanfaatan pangan
meliputi konsumsi pangan dan status gizi.
Indikator dalam pengukuran ketahanan pangan ada tiga hal, yaitu : (a)
ketersediaan energi per kapita, (b) kemiskinan (besarnya pendapatan) dan (c)
status gizi anak (banyaknya anak yang menderita malnutrisi (Smith, Obeid,
Jensen dan Jhonson, 1999). Tingkat ketersediaan energi per kapita merupakan
ukuran dan ketersediaan pangan nasional. Ketersediaan energi per kapita
merupakan turunan dari neraca bahan makanan (food balance sheets) dan jumlah penduduk, data produksi dan perdagangan pangan serta penggunaan
benih, perubahan stok, tercecer dan yang digunakan untuk makanan digunakan Ketahanan Pangan
Food availabity Food access Food ulitization
Resources:
•Natural •Physical •Human
Production
•Fram •Non Farm
Consumption:
•Food •Non food
10
untuk mengetahui jumlah komoditas yang tersedia dan dikonsumsi setiap
tahun.
Pemerintah telah menyusun perangkat lunak dalam mendeteksi situasi
ketahanan pangan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan. Instrumen
tersebut diantaranya adalah Food Security Atlas (FSA) yang prinsipnya memberikan informasi tentang situasi pangan di suatu wilayah melalui
penjaringan data dan informasi dengan menggunakan indikator yang telah
disusun sebagai cerminan factor yang menentukan tingkat kerawanan pangan.
Peta rawan pangan dan gizi menggambarkan tingkat kerawanan
masing-masing wilayah, ditinjau dari tiga aspek, yaitu pangan, gizi dan kemiskinan yang
berguna bagi pemerintah daerah untuk mengindentifikasi daerah rawan
pangan, mempertajam penetapan sasaran untuk tindakan intervensi dan
memperbaiki kualitas perencanaan di bidang pangan dan gizi (Dewan
Ketahanan pangan 2007).
Penyusunan peta FSA dilakukan pada daerah rawan pangan kronis dan
transien. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan pangan berkelanjutan
yang terjadi sepanjang waktu. Kondisi ini disebabkan keterbatasan sumber daya
alam (SDA) dan keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) sehingga
menyebabkan kemiskinan. Rawan pangan transiens adalah keadaan rawan
pangan yang disebabkan kondisi tidak terduga antara lain: musibah bencana
alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat
mendadak (Departemen Pertanian 2006).
UNICEF (1990) diacu Atmawikarta dan Murniningtyas (2006)
mengembangkan kerangka berpikir mengenai penyebab masalah gizi. Kerangka
berpikir UNICEF menjelaskan sitauasi pangan dan gizi di suatu wilayah. Situasi
pangan dan gizi yang tidak sesuai akan mempengaruhi baik langsung maupun
11
Gambar 2.2. Kerangka berpikir penyebab masalah gizi
Outcome
Penyebab langsung
Penyebab tidak langsung
Akar masalah
Sumber : UNICEF 1990
2.3 Konsep Ketahanan Pangan
Pengertian ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2012 tidak hanya sampai pada level rumah tangga, namun terpenuhinya
pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari
tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam,
bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, Status gizi anak
balita
Intake Gizi Status Infeksi
Pola asuh pemberian ASI/ IMPASI, pola asuh psiko-sosial, penyediaan makan-an sapihmakan-an, praktek higien dan sanitasi makanan dan kesehatan lingkungan Ketahanan
pangan RT
Pelayanan kesehatan dan
kesehatan lingkungan
Komunikasi, informasi dan edukasi
Kuantitas, kualitas, akses dan pengelolaan sumberdaya rumahtangga dan lingkungan
12
keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan
produktif secara berkelanjutan.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 selain mengatur tentang
ketahanan pangan juga memuat tentang kedaulatan pangan, kemandirian
pangan. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri
menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan
yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang
sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian Pangan adalah
kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka
ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan
yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi
sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara
bermartabat.
Ketahanan pangan mempunyai dimensi sebagai berikut: (a)
Terpenuhinya pangan yang cukup diartikan ketersediaan pangan dalam arti
luas bukan hanya beras tetapi mencakup pangan yang berasal dari tanaman,
ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhanatas karbohidrat, protein, lemak,
vitamin dan mineral yangbermanfaat bagi pertumbuhan kesehatart manusia;
(b) Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari
cemaran biologis, kimia dan benda zat lain yang dapatmengganggu, merugikan
dan membahayakan kesehatan manusiaserta aman dari kaidah agama; (c)
Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, dapat diartikan pangan
harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air; (d) Terpenuhinya
pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah (Suryana, 2003).
Tersedianya pangan tingkat nasional tidak mencerminkan jaminan
kecukupan pangan di tingkat rumah tangga. Ketersediaan pangan dan akses
terhadap pangan (dimensi fisik dan ekonomi) merupakan determinan penting
dari ketahanan pangan (Braun, et al., 1992). Menurut Sen (1981), kendala akses terhadap pangan terkait dengan lemahnya entitlement (faktor kepemilikan) di tingkat rumah tangga yang menyebabkan ketidakmampuan melakukan kontrol
terhadap pangan. Hal ini mempunyai hubungan linear dengan tingkat
13
Konsep perolehan pangan (food entitlement paradigm) adalah: (a) indikator akhir ketahanan pangan adalah perolehan pangan cukup bagi
individu. Indikator akhir ketahanan pangan ialah ketahanan pangan individu
(individual food security; (b) ketersediaan pangan adalah syarat keharusan
tetapi tidak cukup untuk menjamin perolehan pangan yang cukup bagi setiap
individu, dan (c) ketahanan pangan dipandang sebagai sistem hierarkis;
ketahanan pangan nasional, provinsi (kabupaten, lokal), rumah tangga dan
individual (Simatupang, 2007).
Ketahanan pangan dapat terwujud ketika individu memiliki akses fisik
dan ekonomi yang konsisten terhadap pangan dengan cukup, aman dan bergizi
dalam memenuhi kebutuhan dan preferensi pangannya untuk kehidupan yang
aktif dan sehat. Kedaulatan pangan lahir dari meningkatnya akses terhadap
sistem pangan dan pangan tradisional. Hal ini mensyaratkan kedaulatan politik
dan penekanan pada transmisi pengetahuan tradisional (Socha, 2012).
Dalam Perspektif kesejahteraan, menurut hukum Engel, semakin tinggi
pendapatan (kesejahteraan) individu, pangsa pengeluaran pangan, khususnya
pangan pokok, akan semakin berkurang tetapi pangsa pengeluaran nonpangan
semakin bertambah. Rumah tangga yang memiliki pangsa pengeluaran pangan
relatif tinggi dapat disebut tergolong rumah tangga miskin. Sebaliknya, rumah
tangga yang pangsa pengeluaran pangannya relatif rendah dapat disebut rumah
tangga sejahtera (Saliem, et al. 2006).
Cakupan persoalan kemiskinan dan ketahanan pangan memiliki
keterkaitan yang sangat kuat. Menurut Maxwell dan Frankenberger (1992)
kemiskinan merupakan salah satu faktor determinan terjadinya ketidaktahanan
pangan yang akut (chronic food insecurity). Dalam konteks ketahanan pangan, faktor ketersediaan (food availability) dan aksesibilitas (food accessibility) pangan merupakan dua faktor penting dalam peningkatan ketahanan pangan
rumah tangga (Sayogyo, 1991; Soehardjo, 1996 dalam Saliem, et al. 2006). Kemiskinan dibagi atas kemiskinan absolut dan relatif. Kemiskinan
absolut terlihat dari kehidupan yang di bawah minimum, atau di bawah standar
yang diterima secara sosial, dan adanya kekurangan nutrisi. Kemiskinan relatif
14
pengukuran kemiskinan absolute, Sajogjo (1997) mengukur berdasarkan
pengeluaran perkapita pertahun yang dikonversikan dengan standar
kebutuhan beras, yakni kelompok miskin di desa 320 kg dan kota 480 kg; sangat
miskin di desa 240 kg dan kota 360 kg; kelompok melarat di desa 180 kg dan
kota 270 kg. Sedangkan menurut versi Bank Dunia tingkat kemiskinan dapat
dibagi menjadi beberapa kelas yakni : “extreme poverty” yakni dengan ukuran pengeluaran biaya hidup kurang dari 1 dollar AS perhari, dan “poverty” jika kurang dari 2 dollar AS perhari. Penilaian Bank Dunia ini hanya melihat
kemiskinan pada tingkat individual saja.
Kemiskinan sangat terkait dengan ketahanan pangan. Saat ini
pemerintah menjalankan paradigma ketahanan pangan berkelanjutan melalui
tujuh program pemberdayaan masyarakat. Program ketahanan pangan dan
program pro penduduk miskin berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan
relatif dari 24,2 menjadi 16,7 persen selama periode 1998 – 2004.
Analisis ketahanan pangan menunjukkan bahwa: (a) produksi komoditas
primer meningkat dan harga pangan stabil; (b) penduduk yang tinggal di
pedesaan, terutama bekerja di pertanian dan memiliki pendapatan lebih rendah,
cenderung memiliki aksesibilitas pangan lebih rendah dibandingkan penduduk
perkotaan; dan (c) kerawanan pangan regional di negara ini masih meluas
karena bencana alam, konflik, kelangkaan pangan musiman dan kenaikan harga
(Rusastra, et al, 2008).
Committee on World Food Security (2012) menyebutkan penduduk
miskin merupakan kelompok rentan terhadap kelaparan. Hal ini karena
terbatasnya sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari- hari, juga
sangat rentan bahkan terhadap goncangan sangat kecil yang akan mendorong
mereka mendekati kemelaratan, kelaparan, dan bahkan kematian dini.
Respon perlindungan sosial yang tepat terhadap kerawanan pangan
yang berhubungan dengan kemiskinan kronis adalah bantuan sosial yang
dikaitkan dengan usaha pengembangan mata pencaharian yang dapat
meningkatkan pendapatan penduduk. Penduduk yang saat ini tidak miskin
tetapi menghadapi resiko kemiskinan di masa datang adalah rentan terhadap
15
dirinya sendiri. Penduduk seperti ini membutuhkan jaring pengaman sosial
yang efektif. Sistem perlindungan sosial sebaiknya tidak dipandang sebagai
beban berat pada sistem fiskal. Intervensi perlindungan sosial yang didesain
dengan baik akan baik bagi pertumbuhan dalam pembangunan. Secara khusus,
dengan mencegah penurunan aset dan mereduksi resiko personal dalam
berinvestasi bagi penduduk miskin, perlindungan sosial dapat menjadi
16
BAB III. KEBIJAKAN NASIONAL PANGAN DAN GIZI
3.1 Kondisi Pangan dan Gizi Nasional
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat dengan pesat dalam 4
dekade terakhir ditandai dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat
Indonesia. Pada tahun 2010, pendapatan nasional kotor per kapita adalah USD
3.956 dan umur harapan hidup rata-rata adalah 71,5 tahun (UNDP, 2010).
Walaupun demikian, beberapa indikator keberhasilan pembangunan masih
memprihatinkan. Salah satu indikator yang diupayakan percepatan
pencapaiannya adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Tingkat kemiskinan
telah menurun dari 14,1 persen pada tahun 2009 menjadi 13,3 persen pada
tahun 2010 (BPS), namun masih diperlukan kerja keras untuk mengakselerasi
pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Kesepakatan MDGs tersebut adalah penurunan 50 persen dari kondisi tahun 1990, menjadi 7,5 persen pada
tahun 2015. Demikian pula kondisi kelompok rentan ibu dan anak masih
mengalami berbagai masalah kesehatan dan gizi, yang ditandai dengan masih
tingginya angka kematian ibu dan angka kematian neonatal, prevalensi gizi
kurang (BB/U) dan pendek (TB/U) pada anak balita, prevalensi anemia gizi
kurang zat besi pada ibu hamil, gangguan akibat kurang yodium pada ibu hamil
dan bayi serta kurang vitamin A pada anak balita. Pada tahun 2007 prevalensi
anak balita yang mengalami gizi kurang dan pendek masing-masing 18,4 persen
dan 36,8 persen sehingga Indonesia termasuk di antara 36 negara di dunia yang
memberi 90 persen kontribusi masalah gizi dunia (UN-SC on Nutrition 2008). Walaupun pada tahun 2010 prevalensi gizi kurang dan pendek menurun
menjadi masing-masing 17,9 persen dan 35,6 persen, tetapi masih terjadi
disparitas antar provinsi yang perlu mendapat penanganan masalah yang
sifatnya spesifik di wilayah rawan (Riskesdas 2010).
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya
menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia, hal ini sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Pada kenyataannya peta
penduduk rawan pangan yang diumumkan oleh BPS pada tahun 2009 masih
17
rawan pangan yaitu dengan asupan kalori kurang dari 1.400 Kkal per orang per
hari mencapai 14,47 persen, meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun
2008 yaitu 11,07 persen. Rendahnya aksesibilitas pangan, yaitu kemampuan
rumah tangga untuk selalu memenuhi kebutuhan pangan anggotanya,
mengancam penurunan konsumsi makanan yang
beragam, bergizi-seimbang, dan aman di tingkat rumah tangga. Pada akhirnya
akan berdampak pada semakin beratnya masalah kekurangan gizi masyarakat,
terutama pada kelompok rentan yaitu ibu, bayi dan anak.
Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa masalah gizi adalah
masalah intergenerasi, yaitu ibu hamil kurang gizi akan melahirkan bayi kurang
gizi. Pada hakekatnya masalah gizi dapat diselesaikan dalam waktu relatif
singkat. Intervensi paket kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut yang
dilaksanakan melalui pelayanan berkelanjutan (continuum care) pada periode kesempatan emas kehidupan (window of opportunity), yaitu sejak janin dalam kandungan, dan bayi baru lahir sampai anak berusia 2 tahun. Di Brazil, revalensi
pendek pada anak balita menurun lebih dari 30 persen, yaitu dari 37 persen
pada tahun 1974 menjadi 7 persen pada tahun 2006, dengan melakukan empat
prioritas penanganan yaitu meningkatkan: (1) akses pelayanan kesehatan dan
gizi yang berkelanjutan pada ibu dan anak; (2) akses pendidikan dan informasi
pada remaja putri dan perempuan; (3) cakupan penyediaan air dan sanitasi;
serta (4) daya beli keluarga (Monteiro et al, 2010). Sedangkan Thailand
menurunkan 50 persen kekurangan gizi pada anak hanya dalam waktu 4 tahun
(1982-1986) melalui fokus pelayanan untuk kelompok yang sama (SCN News
No. 36 mid-2008). Penelitian di Peru yang melibatkan anak pendek usia 6-18 bulan, membuktikan bahwa dengan intervensi yang tepat ketertinggalan
pertumbuhan tinggi badan dapat “dikejar” dan pada usia 4,5-6 tahun dapat
mempunyai kecerdasan yang sama dengan anak yang tidak pendek pada masa
bayi (Crookston et al, 2010).
Saat ini, situasi gizi dunia menunjukkan dua kondisi yang ekstrem. Mulai
dari kelaparan sampai pola makan yang mengikuti gaya hidup yaitu rendah
serat dan tinggi kalori, serta kondisi kurus dan pendek sampai kegemukan. Di
18
jelas peran gizi berkontribusi bermakna pada penanggulangan ke dua jenis
penyakit ini. Untuk mencapai status kesehatan yang optimal, dua sisi beban
penyakit ini perlu diberi perhatian lebih pada pendekatan gizi, baik pada
masyarakat kaya maupun pada kelompok masyarakat miskin (WHO, 2008). Hal
yang sama juga terjadi di Indonesia. Pada saat sebagian besar bangsa Indonesia
masih menderita kekurangan gizi terutama pada ibu, bayi dan anak secara
bersamaan masalah gizi lebih cenderung semakin meningkat dan berakibat
beban ganda yang menghambat laju pembangunan. Status gizi optimal dari
suatu masyarakat telah secara luas diterima sebagai salah satu dari prediktor
untuk kualitas sumberdaya manusia, prestasi akademik, dan daya saing bangsa
(The Lancet, 37: 340-357).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010- 2014
secara tegas telah memberikan arah Pembangunan Pangan dan Gizi dengan
sasaran meningkatnya ketahanan pangan dan meningkatnya status kesehatan
dan gizi masyarakat. Program Pembangunan yang Berkeadilan yang terkait
dengan Rencana Tindak Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium
(MDGs) telah dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010. Salah
satu dokumen yang harus disusun adalah Rencana Aksi Nasional Pangan dan
Gizi (RAN-PG) 2011-2015 dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)
2011-2015 di 33 provinsi. Penyusunan RAN-PG 2011-2015 diawali dengan
evaluasi aksi nasional yang tercantum dalam RAN-PG 2006-2010. Banyak
kemajuan telah dicapai dalam pembangunan pangan dan gizi yang meliputi
perbaikan gizi masyarakat, aksesibilitas pangan, mutu dan keamanan pangan,
perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan koordinasi dalam kelembagaan
pangan dan gizi. Keberhasilan tersebut antara lain ditandai dengan status gizi
masyarakat yang semakin membaik, ketersediaan pangan yang meningkat dan
mencukupi kebutuhan penduduk, dikeluarkannya berbagai peraturan
perundangan terkait dengan mutu dan keamanan pangan, meningkatnya
perilaku individu dan keluarga untuk hidup bersih dan sehat termasuk sadar
gizi, serta sudah semakin banyak terbentuk lembaga yang menangani pangan
dan gizi di berbagai tingkat administrasi pemerintahan. Walaupun demikian
19
pada evaluasi RAN-PG 2006-2010 menjadi perhatian utama untuk dijabarkan
dalam rencana aksi yang menjadi prioritas pembangunan pangan dan gizi
nasional selama lima tahun ke depan. Keterkaitan pembangunan pangan,
kesehatan dan gizi dengan penanggulangan kemiskinan, pendidikan,
pemberdayaan keluarga dan penyelenggaraan urusan wajib pelayanan
masyarakat di daerah perlu diperjelas sehingga setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dapat mengalokasikan kegiatan-kegiatan prioritas yang saling
menunjang sekaligus memberi arah pembangunan kewilayahan.
Perkembangan ketersediaan energi nasional dalam periode 2009-2013
dinyatakan oleh Gambar 3.1 di bawah ini.
Gambar 3.1. Ketersediaan Energi dan Standar Ketersediaan Energi
Sumber : Neraca Bahan Makanan 2009 – 2013
Dari Gambar 3.1 di atas dapat kita ketahui bahwa ketersediaan energi selalu
melebihi standar ketersediaan energi. Hal ini membuktikan bahwa hingga saat
ini kondisi ketersediaan energi masih dalam keadaan aman.
3320
3754 3646 3896 3849
2200 2200 2200 2200 2200
2009 2010 2011 2012 2013
Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)
20
Adapun kondisi perkembangan konsumsi energi nasional dari tahun
2009 hingga 2014 dalam satuan kkal/kapita/hari dinyatakan oleh Gambar 3.2
berikut ini.
Gambar 3.2. Konsumsi Energi dan Standar Konsumsi Energi
Sumber : Susenas, BPS 209-2014; diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran oleh BKP
Dari Gambar 3.2 di atas terlihat bahwa konsumsi energi berfluktuasi, tapi
cenderung meningkat, dengan pertumbuhan rata-rata 0,3% per tahun.
Konsumsi energi tahun 2014 sebesar 97,5% dari AKE 2000 kkal/kap/hari.
Perkembangan ketersediaan dan konsumsi protein nasional dalam kurun
waktu 2009-2013 disajikan oleh Gambar 3.3 berikut ini. 1927
2025
2048
1944
1930
1949
2000 2000 2000 2000 2000 2000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)
21
Gambar 3.3. Ketersediaan protein
Sumber : Neraca Bahan Makanan 2009 – 2013
Dari Gambar 3.3 di atas, kita memperoleh gambaran bahwa ketersediaan
protein dari tahun 2009 sampai dengan 2013 masih mencukupi. Akan tetapi ada
fenomena yang cukup unik, yaitu adanya kenaikan ketersediaan protein antara
tahun 2010 hingga 2011.
Berikut ini merupakan gambaran konsumsi protein nasional dalam
kurun waktu 2009 hingga 2014 yang dinyatakan oleh Gambar 3.4. Dari Gambar
tersebut dapat kita ketahui bahwa konsumsi protein tahun 2009-2014 lebih
besar dibandingkan dengan AKP (104,5 – 113,7%). Sedangkan laju
pertumbuhan rata-rata sebesar 0,9% per tahun, namun masih didominasi oleh
kontribusi protein nabati yang berasal dari kelompok padi-padian (beras).
87,75 93,4 93,13 88,99 89,26
57 57 57 57 57
2009 2010 2011 2012 2013
Ketersediaan Protein (gr/kap/hari)
22
Gambar 3.4. Konsumsi protein nasional
Sumber : Susenas, BPS 209-2014; diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran oleh BKP
Konsumsi Energi Per Provinsi Tahun 2014 disajikan dalam Gambar di
bawah ini.
Gambar 3.5. Konsumsi Energi (kkal/kap/hari) per Provinsi Tahun 2014
Sumber : Susenas 2014 triwulan 1; BPS diolah dan diJustifikasi dengan pendekatan pengeluaran oleh BKP
54,3
57,9
59,1
55,9 55,7 56,6
52 52 52 52 52 52
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Konsumsi Protein (gr/kap/hari)
Konsumsi Protein Standar Konsumsi Protein
0 500 1000 1500 2000 2500
23
Dari Gambar 3.5 dapat diketahui bahwa Bali merupakan provinsi yang memiliki
nilai konsumsi energi paling tinggi, sedangkan Maluku utara bernilai terendah
dan di bawah standar AKE (2000 kkal/kap/hari). Dalam hal ini, Jawa Tumur
juga berada di standar AKE nasional.
Konsumsi Protein Per Provinsi Tahun 2014 disajikan oleh Gambar 3.6 di
bawah ini.
Gambar 3.6. Konsumsi protein (gram/kap/hari) per provinsi tahun 2014
Sumber : Susenas 2014 triwulan 1; BPS diolah dan diJustifikasi dengan pendekatan pengeluaran oleh BKP
Dari Gambar 3.6 di atas diperoleh informasi bahwa hampir semua provinsi
memiliki AKP di atas standar AKP nasional (52 gram/kap/hari), kecuali
Provinsi Maluku Utara.
Perkembangan skor PPH nasional dalam kurun 2009–2014 ditampilkan
oleh Gambar 3.7 berikut ini.
24
Gambar 3.7. Skor PPH dan Target
Sumber : Susenas 2009, 2010, (2011-2014 triwulan 1); BPS diolah dan diJustifikasi dengan pendekatan pengeluaran oleh BKP.
Capaian skor PPH Tahun 2014 sebesar 83,4 atau 89,4% dari target skor PPH
berdasarkan Perpres No. 22 Tahun 2009 (skor PPH 93,3). Adapun
perkembangan rata-rata kualitas konsumsi pangan masyarakat tahun
2011-2014 menunjukkan sedikit penurunan.
3.2. Kebijakan pembangunan gizi masyarakat dalam RPJMN 2015 – 2019
Kondisi Umum
a. Kesehatan ibu dan anak membaik namun belum signifikan dan
kesenjangan masih cukup lebar
1. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih
cukup tinggi.
2. Disparitas Masih Lebar : Persalinan di fasilitas kesehatan tertinggi
berada di DIY (99%) dan terendah berada di Maluku (25,2%);
Cakupan Imunisasi dasar lengkap tertinggi berada di DIY (83,1%)
dan terendah berada di Papua (29,2%).
b. Status Gizi di Indonesia
1. Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting)
75,7 85,7 85,6 83,5 81,4 83,4
85,0 86,4 88,1 89,8 91,5 93,3
2009 2010 2011 2012 2013 2014
25
2. Wasting / kurus dialami oleh 12,1% balita
3. Ibu Hamil di Indonesia mengalami Anemia (37,1%)
c. Pengendalian Penyakit
1. Beban ganda penyakit: penyakit menular masih muncul sedangkan
penyakit tidak menular semakin meningkat
2. Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia cukup tinggi tahun 2013
adalah 0,43 persen
3. Faktor Risiko PTM (Penduduk >10 th kurang konsumsi buah dan
sayur : 93,5%)
d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Pada pelayanan kesehatan
rujukan, banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar
ketenagaan.
Proporsi balita gizi kurang dan mengalami stunting ditunjukkan oleh Gambar
3.8.
Gambar 3.8 Kecenderungan nasional: 2007 – 2013 proporsi gizi kurang dan pendek*) pada balita
26
Dari Gambar 3.8 di atas dapat diketahui bahwa proporsi gizi buruk dan gizi
kurang mengalami kenaikan dari tahun 2007 hingga 2013. Sedangkan untuk
proporsi balita sangat pendek mengalami penurunan. Adapun balita yang
mengalami pertumbuhan pendek mengalami kenaikan dalam kurun waktu yang
sama.
Kondisi nasional balita sangat kurus dan gemuk ditampilkan oleh Gambar 3.9
berikut ini.
Gambar 3.9. Kecenderungan nasional: 2007 – 2013 Proporsi kurus dan gemuk*) pada balita
Sumber Data : Riskesdas 2013
Dari Gambar 3.9 di atas dapat diperoleh informasi bahwa proporsi balita sangat
kurus, kurus, maupun gemuk mengalami penurunan dalam rentang waktu enam
tahun (2007-2013).
Kecenderungan prevalesi balita stunting secara nasional ditunjukkan oleh
27
Gambar 3.10. Kecenderungan prevalensi balita stunting di indonesia menurut provinsi
Sumber Data : Riskesdas 2013
Dari Gambar 3.10 tersebut dapat diketahui bahwa untuk Provinsi Jawa Timur,
dari tahun 2007 hingga 2013 prevalensi balita stunting memang mengalami
kenaikan, hanya saja tidak terlalu signifikan.
Gambar 3.11. Rata-rata tinggi badan anak umur 5-18 tahun dibanding rujukan (WHO 2007): 2007 – 2013
28
Gambar 3.11 merupakan informasi tentang adanya selisih antara rata-rata
tinggi badan anak 5-18 tahun dengan rujukannya. Untuk anak laki-laki terdapat
beda tinggi badan 12,5 cm, sedangkan bagi anak perempuan terdapat selisih
tinggi 9,8 cm dengan tinggi referensinya.
Isu ketahanan pangan mempengaruhi gizi masyarakat
Kondisi umum masyarakat adalah sebagai berikut:
• Penduduk sangat rawan pangan yaitu dengan asupan kalori kurang dari
1.400 Kkal per orang per hari mencapai 15,34 persen (BPS, 2010).
• Rata-rata konsumsi kalori penduduk 1930 kkal per kapita masih lebih
rendah dari Angka Kecukupan Energi (AKE) yaitu sebesar 2.000 kkal per
kapita per hari (2013)
• Ibu hamil mendapat asupan kalori di bawah kebutuhan minimum yaitu
44,4 persen (Riskesdas 2013).
Dari kondisi umum di atas, maka dapat dirumuskan beberapa poin
permasalahan yaitu:
Distribusi dan aksesibilitas pangan
Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat
Tidak semua rumahtangga mampu dan memiliki akses yang memadai
baik secara kuantitas maupun keragamannya
Sehingga tantangan yang harus dihadapi saat ini adalah:
Ketahanan pangan perlu terus ditingkatkan untuk menghindari
terjadinya krisis pangan yang akan berdampak pada penurunan
konsumsi energi dan penurunan konsumsi zat gizi mikro (vitamin dan
mineral) yang sangat diperlukan oleh anak-anak dan ibu hamil. Perlu
dilakukan Mitigasi Gangguan Terhadap Ketahanan Pangan.
Isu keamanan dan mutu pangan mempengaruhi gizi masyarakat
Kondisi unum yang berkaitan dengan keamanan dan mutu pangan nasional
adalah sebagai berikut:
29
• Baru sekitar separoh Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang
memenuhi syarat sebanyak yang memenuhi syarat.
• Sampai dengan tahun 2009, total Industri Rumah Tangga-Pangan (IRT-P)
yang ada di Indonesia adalah 33.902.
• Baru sekitar separoh IPRT yang mengikuti Penyuluhan Keamanan
Pangan dan memperoleh sertifikat.
• Belum semua tepung terigu difortifikasi.
Permasalahan yang harus dihadapi berkenaan dengan keamanan dan mutu
pangan adalah:
• Adanya produk industri pangan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
yaitu penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) pemanis dan
pengawet (benzoat) berlebih, penyalahgunaan bahan berbahaya formalin, boraks, pewarna bukan untuk makanan, dan cemaran mikroba.
• Produk TMS terkait dengan cemaran mikroba masih cukup dominan.
Kondisi-kondisi tersebut memunculkan tantangan baru yaitu:
Belum semua Produk Pangan, Garam Beriodium, PJAS dan Tepung Terigu yang
30
3.3. Kebijakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (RPJMN 2015 – 2019)
Percepatan perbaikan gizi nasional harus diduung oleh sinergi lintas
bidang interaksi K/L dalam mengukur hasil pembangunan yang dinyatakan
oleh Gambar 3.12 di bawah ini.
Gambar 3.12. Sinergi lintas bidang interaksi K/L dalam mengukur hasil pembangunan
Sumber Data : Riskesdas 2013
Isu strategis RPJMN 2015-2019 untuk subbidang Kesehatan dan Gizi
Masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia
DETERMINAN DAMPAK UKURAN
KEMKES/DINKES
SPESIFIK
30%
GIZI
KEMATIAN
IBU AKI
ANAK AKB
K/L & SKPD Terkait
SENSITIF
70%
KESAKITAN
PM Prevalensi/Kasus
PTM Prevalensi/Kasus
PREVENTIF-PROMOTIF KURATIF-REHABILITATIF
KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET
KERANGKA PELAKSANAAN
(Dana, Regulasi, Lembaga)
KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET
KERANGKA PELAKSANAAN
(Dana, Regulasi, Lembaga)
RENCANA STRATEGIS- RENCANA AKSI
31
2. Percepatan Perbaikan Status Gizi Masyarakat
3. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang
Berkualitas
5. Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan
Obat dan Makanan
6. Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
8. Peningkatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, serta Sistem
Informasi Kesehatan
9. Pengembangan dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
10.Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional
Adapun arah kebijakan RPJMN 2015-2019 yaitu:
1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja,
dan Lanjut Usia yang Berkualitas
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
6. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas
Farmasi dan Alat Kesehatan
7. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
8. Meningkatkan Ketersediaan, Persebaran, dan Mutu Sumber Daya
Manusia Kesehatan
9. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
10.Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem
Informasi
11.Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang
Kesehatan
12.Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
Strategi mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat dilakukan melalui
32
a. peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan;
b. peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan
fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja, calon
pengantin dan ibu hamil, termasuk pemberian makanan tambahan,
terutama untuk keluarga kelompok termiskin dan wilayah DTPK;
c. peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi,
sanitasi, hygiene, dan pengasuhan;
d. peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi terutama untuk ibu
hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK termasuk
melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat dan Pengembangan Anak
Usia Dini Holistik Integratif (Posyandu dan Pos PAUD);
e. penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi; dan
f. penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan
spesifik yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan rencana aksi pangan
dan gizi.
Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk
meningkatkan status gizi masyarakat perriode 2015-2019 dinyatakan oleh
33
Tabel 3.13. Sasaran RPJMN 2015-2019 tentang peningkatan status gizi
No Indikator Status Awal Target
2019
1 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
1. Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen) 37,1 (2013) 28
2. Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir
Rendah (BBLR)
10,2 (2013) 8
3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang
mendapat ASI eksklusif
38,0 (2013) 50
4. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)
19,6 (2013) 17
5. Prevalensi wasting (kurus) anak balita (persen) 12 (2013) 9,5
6. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (persen)
32,9 (2013) 28
Sumber Data : Riskesdas 2013
Intergrasi RAN-PG dan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi dinyatakan
34
Gambar 3.14. Intergrasi RAN-PG dan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi
Sumber Data : Riskesdas 2013
Konsep RAN-PG Tahun 2015 – 2019
Kerangka Pikir Aksi untuk Mencapai SDM Berkualitas, melalui pencapaian
status dan perkembangan gizi janin & anak yg optimal dipaparkan oleh Gambar
3.15 di bawah ini.
5 PILAR RENCANA AKSI
1. Perbaikan Gizi
Masyarakat terutama pada ibu pra-hamil, ibu hamil dan anak
4. Peningkatan Perilaku
Hidup Bersih dan
1. Meningkatnya cakupan ASI
Ekslusif, D/S, KN dan K4
2. Meningkatnya tingkat
keragaman konsumsi dan skor PPH
3. Meningkatnya cakupan jajanan anak sekolah yang memenuhi syarat dan SKPD bidang Pangan dan Gizi
6. Meningkatnya peraturan
perundangan Pangan dan Gizi
7. Meningkatnya tenaga D3
gizi puskesmas dan PPL kecamatan
SASARAN PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI PADA TAHUN
2015
• Prevalensi anak balita
- Gizi kurang : 15.5% - Pendek : 32%
• Konsumsi pangan dengan
35
Gambar 3.15. Konsep RAN-PG
Source: The Lancet, 2013: Executive Summary of The Lancet Maternal and Child Nutrition
Series
Strategi Gerakan 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan)Dalam Program Pangan
Dan Gizi adalah sebagai berikut:
1. Intervensi fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (ibu hamil, dan
anaksampai usia 2 tahun)dan dilanjutkan pada usia balita, anak sekolah,
remaja, pra hamil, dewasa, dan manula.
2. Perluasan stakeholder melalui kerjasama lintas sektor, pemerintah dan
swasta dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Intervensi Gizi Spesifik
Berbagai Program
- Kesehatan remaja dan gizi ibu prahamil - PMT ibu hamil - Intervensi gizi dalam
kedaruratan
Program Gizi Sensitif dan Pendekatannya
- Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Jaminan Sosial Nasional - Perkembangan anak usia
dini
- Kesehatan mental ibu - Pemberdayaan perempuan - Perlindungan anak - Pendidikan dalam kelas - Sanitasi dan air bersih - Pelayanan kesehatan dan
Keluarga Berencana
Membangun Lingkungan “Pemungkin/Enabling”
- Evaluasi tepat
- Strategi advokasi
- Koordinasi vertikal dan horizontal
Kepemimpinan, kapasitas dan sumber pendanaan Konteks sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan
(nasional dan daerah )
Manfaat pada Siklus Kehidupan
36
3. Pelibatan akademia, sektor swasta dan masyarakat madani di pusat dan
daerah.
4. Peningkatan akuntabilitas serta tatakelola pemerintahan yang baik serta
efektif.
5. Menyiapkan monitoring dan evaluasi yang terukur dan indikator
keberhasilan yang sejalan dengan RPJMN
Sedangkan Program Lintas 1: Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat dijabarkan
ke dalam Tabel 3.2 di bawah ini.
Tabel 3.2. Program Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Kegiatan
Kementerian Kesehatan
PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN
IBU DAN ANAK
Pembinaan Gizi Masyarakat
Badan POM
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN
1. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
2. Penilaian Pangan Olahan
3. Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Kementerian Pertanian
PROGRAM PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN
PANGAN MASYARAKAT
1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan
Rawan Pangan
2. Pengembangan penganekaragaman konsumsi
pangan dan peningkatan keamanan pangan segar