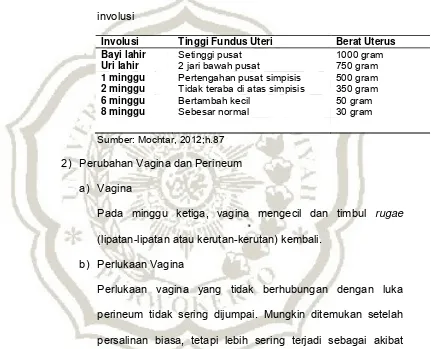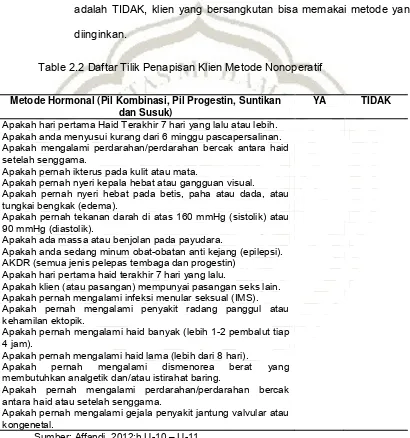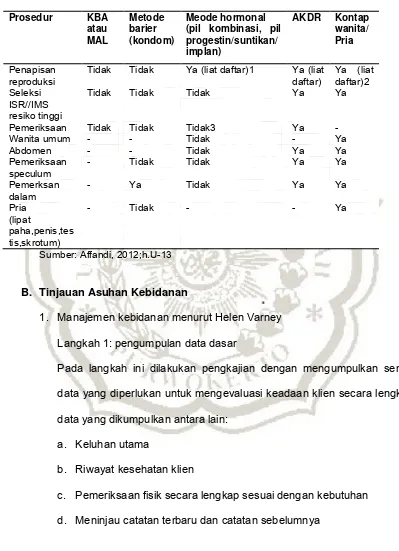BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Teori
1. Kehamilan
a. Pengertian Kehamilan
Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intra
uteri mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan.
Proses kehamilan merupakan matarantai yang bersinambungan dan
terdiri dari ovulasi, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi dan
pertumbuhan zigot, nidasi (implantasi) pada uterus, pembentukan
plasenta, dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterm
(Manuaba, 2010;h.75).
Masa kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau
penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi
atau implantasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi,
kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10
bulan lunar atau 9 bulan menurut kalender internasional. Kehamilan
terbagi dalam 3 trimester, dimana trimester kesatu berlangsung
ke-27), dan trimester ketiga 13 minggu (minggu ke-28 hingga ke-40)
(Prawirohardjo, 2014;h.213).
Periode antepartum adalah periode kehamilan yang dihitung
sejak pertama haid terakhir (HPHT) hingga dimulainya persalinan
sejati, yang menandai awal periode antepartum (Varney, 2007;h.492).
Kehamilan disimpulkan sebagai suatu masa yang di mulai
dengan pembuahan antara sperma dan sel telur serta berakhir
dengan permulaan persalinan, lamanya hamil normal adalah 280 hari
(40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid
terakhir.
b. Proses Terjadinya Kehamilan
1) Ovulasi
Ovulasi adalah proses pelepasan ovum yang dipengaruhi oleh
system hormonal yang kompleks. Selama masa subur yang
berlangsung 20 sampai 35 tahun, hanya 420 buah ovum yang
dapat mengikuti proses pematangan dan terjadi ovulasi. Proses
pertumbuhan ovum (oogenesis) asalnya epitel germinal – oogonium –folikel primer – proses pematangan pertama. Dengan pengaruh FSH, folikel primer mengalami perubahan menjadi
2) Spermatozoa
Pertumbuhan spermatozoa dipengaruhi oleh system hormonal
Yang kompleks dari pancaindra, hipotalamus, hipofisis, dan sel
interstitial Leydig sehingga dapat mengalami proses mitosis. Pada setiap hubungan seksual dikeluarkan sekitar 3 cc sperma yang
mengandung 40 sampai 60 juta spermatozoa setiap cc. bentuk
spermatozoa seperti cebong yang terdiri atas kepala (lonjong
sedikit gepeng yang mengandung inti), leher (penghubung antara
kepala dan ekor), ekor (panjang sekitar 10 kali kepala,
mengandung energy sehingga dapat bergerak).
Sebagian besar spermatozoa mengalami mengalami kematian
dan hanya beberapa ratus yang dapat mencapai tuba fallopii.
Spermatozoa yang masuk ke dalam alat genetalia wanita dapat
hidup selama tiga hari, sehingga cukup waktu untuk mengadakan
konsepsi (Manuaba, 2010;h.76).
3) Konsepsi
Konsepsi adalah suatu peristiwa penyatuan sel mani dengan
sel telur di tuba uterin. Dalam pembuahan satu sperma yang telah
mengalami proses kapasitas yang dapat melintasi zona pelusida
dan masuk ke vitelus ovum. Setelah ovum matang maka siap
sedangkan spermatozoa hidup selama 3 hari di dalam genetalia
interna (Manuaba, 2010;h.79).
4) Nidasi atau Implantasi
Nidasi adala masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi ke
dalam endometrium (Mochtar, 2012;h.17). Setelah pertemuan
kedua inti ovum dan spermatozoa, terbetuk zigot yang dalam
beberapa jam telah mampu membelah dirinya menjadi dua dan
seterusnya. Berbarengan dengan pembelahan inti, hasil konsepsi
terus berjalan menuju uterus. Hasil pembelahan sel memenuhi
seluruh ruangan dalam ovum yang besarnya 100 MU atau 0,1 mm
dan disebut stadium morula. Selama pembelahan sel di bagian
dalam, terjadi pembentukan sel di bagian luar morula yang
kemungkinan berasal dari korona radiate yang menjadi sel
trofoblas. Sel trofoblas dalam pertumbuhannya, mampu
mengeluarkan hormone korionik gonadotropin, yang mempertahankan korpus luteum gravidarum (Manuaba, 2010;h.80).
5) Pembentukan Plasenta
Terjadinya nidasi mendorong sel blastula mengadakan
diferensiasi. Sel yang dekat dengan ruangan ekoselum
sedangkan sel lain membentuk ectoderm dan ruangan amnion (Manuaba, 2010;h.82).
c. Perubahan Fisiologi Pada Kehamilan
1) Uterus
Rahim atau uterus yang semula besarnya sejempol atau
beratnya 30 gram akan mengalami hipertrofi dan hyperplasia, sehingga menjadi seberat 1000 gram saat akhir kehamilan. Otot
Rahim mengalami hyperplasia dan hipertrofi menjadi lebih besar, lunak, dan dapat mengikuti pembesaran Rahim karena
pertumbuhan janin (Manuaba, 2010;h.87).
Selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk menerima
dan melindungi hasil konsepsi (janin, plasenta, amnion) sampai
persalinan. Pada awal kehamilam penebalan uterus distimulasi
terutama oleh hormone estrogen dan sedikit oleh progesterone,
akan tetapi setelah kehamilan 12 minggu lebih penambahan
ukuran uterus di dominasi oleh desakan dari hasil konsepsi
(Prawirohardjo, 2014;h.175).
2) Serviks
Satu bulan setelah konsepsi servik akan menjadi lebih lunak
dan kebiruan, perubahan ini terjadi akibat vaskularisasi dan
merupakan organ yang kompleks dan heterogen mengalami
perubahan yang luar biasa selama kehamilan dan persalinan
(Prawirohardjo, 2014;h.177).
3) Ovarium
Dengan terjadinya kehamilan, indung telur yang mengandung
korpus luteum gravidarum akan meneruskan fungsinya sampai terbentuknya plasenta yang sempurna pada usia 16 minggu
(Manuaba, 2010;h.92).
Proses ovulasi selama kehamilan akan terhenti dan
pematangan folikel baru juga ditunda, folikel ini akan berfungsi
maksimal 6-7 minggu awal kehamilan dan setelah itu akan
berperan sebagai penghasil progesterone dalam jumlah yang
relative minimal (Prawirohardjo, 2014;h.178).
4) Vagina dan Perineum
Selama masa kehamilan peningkatan vaskularisasi dan
hiperemia terlihat jelas pada kulit dan otot-otot di perineum dan
vulva, sehingga pada vagina akan terlihat berwarna keunguan
yang dikenal dengantanda Chadwick. Dinding vagina mengalami banyak perubahan yang merupakan persiapan untuk mengalami
peregangan pada waktu persalinan dengan meningkatnya
5) Kulit
Pada kulit dinding perut akan terjadi perubahan warna menjadi
kemerahan, kusam, dan kadang-kadang juga akan mengenai
daerah peyudara dan paha. Perubahan ini dihasilkan dari
cadangan melanin pada daerah epidermal dan dermal. Estrogen
dan progesterone di ketahui mempunya peran dalam
melanogenesis (Prawirohardjo, 2014;h.179).
6) Payudara
Payudara mengalami pertumbuhan dan perkembangan
sebagai persiapan memberikan asi pada saat laktasi (Manuaba,
2010;h.92). Pada awal kehamilan perempuan akan merasakan
payudaranya menjadi lebih lunak, setelah bulan kedua payudara
akan bertambah ukuranya dan vena-vena dibawah kulit akan lebih
terlihat (Prawirohardjo, 2014;h.179).
7) Perubahan Metabolik
Sebagian besar penambahan berat badan bersal dari uterus
dan isinya, kemudian payudara, volume darah dan cairan
ekstraseluler. Asam folat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan
pembelahan sel dalam sintesis DNA/RNA (Prawirohardjo,
8) Perubahan Sistem Kardiovaskuler
Pada minggu ke-lima cardiac output akan meningkat dan perubahan ini terjadi untuk mengurangi resistensi vaskuler iskemik. Volume darah akan meningkat secara progesif mulai minggu ke 6-8 kehamilan dan mencapai puncaknya pada minggu
ke 32-34 dengan perubahan kecil setelah minggu tersebut.
Peningkatan volume plasma akan meningkat kira-kira 40-45%.
Hal ini dipengaruhi oleh aksi progesterone dan estrogen pada ginjal yang diinisiasi oleh jalur rennin-angiostensin dan aldosterone. Penambahan volume darah ini sebagian besar berupa plasma dan eritrosit. Eritroprotein ginjal akan meningkatkan jumlah sel darah merah sebanyak 20-30%, tetapi
tidak sebanding dengan peningkatan volume plasma sehingga
akan mengakibatkan hemodialusi dan penurunan konsentrasi
hemoglobin dari 15 g/dl menjadi 12,5 g/dl, dan pada 6%
perempuan bisa mencapain dibawah 11 g/dl.
Pada kehamilan lanjut kadar haemoglobin dibawah 11 g/dl itu merupakan suatu hal yang abnormal dan biasanya lebih
berhubungan dengan defisiensi zat besi daripada dengan
hipervolemia. Kebutuhan zat besi selama kehamilan kurang lebih 1000 mg atau rata-rata 6-7 mg/hari (Prawirohardjo,
9) Sistem Respirasi
Selama kehamilan sirkumferensia torak akan bertambah kurang lebih 6 cm, tetapi tidak mencukupi penurunan kapasitas
residu fungsional dan volume residu paru-paru karena pengaruh
diagfragma yang naik kurang lebih 4 cm selama kehamilan.
Perubahan ini akan mencapain puncaknya pada hari minggu ke
37 dan akan kembali hamper seperti sedia kala dalam 24 minggu
setelah persalinan (Prawirohardjo, 2014;h.185).
d. Tanda-Tanda Kehamilan
Berikut ini adalah tanda-tanda tidak pasti/dugaan adanya kehamilan.
1) Tanda tidak pasti/ tanda dugaan adanya kehamilan
a) Amenorea (terlambat datang bulan). Konsepsi dan nidasi menyebabkan tidak terjadi pembentukkan folikel de Graff dan
ovulasi. Dengan mengetahui hari pertama haid terakhir
dengan perhitungan tumus naegle, dapat ditentukan perkiraan persalinan.
b) Ngidam wanita hamil sering menginginkan makanan tertentu,
keinginan yang demikian disebut ngidam.
c) Mula dan muntah (emesis). Pengaruh estrogen dan
progesterone menyebabkan pengeluaran asam lambung yang
morning sickness. Dalam batas yang fisiologis, keadaan ini dapat diatasi. Akibat mual dan muntah, nafsu makan
berkurang.
d) Sinkope atau pingsan. Terjadinya gangguan sirkulasi ke daerah keapala (sentral) menyebabkan iskemia susunan saraf
pusat dan menimbulkan sinkope atau pingsan. Keadaan ini menghilang setelah usia kehamilan 16 minggu.
e) Payudara tegang. Pengaruh estrogen-progesteron dan
somatomamotrofin menimbulkan deposit lemak, air, dan garam pada payudara. Payudara membesar dan tegang.
Ujung saraf tertekan menyebabkan rasa sakit terutama pada
hamil pertama.
f) Sering miksi. Desakan Rahim ke depan menyebabkan kandung kemih cepat terasa penuh dan sering miksi. Pada triwulan kedua, gejala ini sudah menghilang.
g) Konstipasi atau obstipasi. Pengaruh progesterone dapat menghambat peristaltic usus, menyebabkan kesulitan untuk
buang air besar.
(hiperpigmentasi areola mammae, putting susu makin menonjol, kelenjar Montgomery mononjol, pembuluh darah menifes sekitar payudara), disekitar pipi (kloas gravidarum). i) Epulis. Hipertrofi gusi yang disebut epulis, dapat terjadi bila
hamil.
j) Varises atau penampakan pembuluh darah vena. Karena
pengaruh dari estrogen dan progesterone terjadi penampakan
pembuluh darah vena, terutama bagi mereka yang
mempunyai bakat. Penampakan pembuluh darah itu terjadi di
sekitar genitalia eksterna, kaki dan betis, dan payudara.
Penampakan pembuluh darah ini dapat mehilang setelah
persalinan (Manuaba, 2010;h.107-108).
2) Tanda kemungkinan hamil
a) Perut membesar
b) Uterus membesar, terjadi perubahan dalam bentuk besar dan
konsistensi rahim.
c) Tanda hegar ditemukannya serviks dan isthmus uteri yang lunak pada pemeriksaan bimanual saat usia kehamilan 4
sampai 6 minggu.
e) Tanda piskacek, pembesara dan pelunakan Rahim kesalah satu sisi rahim yang berdekatan dengan tuba uterin. Biasanya
tanda ini ditemukan di usia kehamilan 7-8 minggu.
f) Kontraksi-kontraksi kecil uterus jika di rangsang (Braxton Hicks).
g) Teraba Ballotemen.
h) Reaksi kehamilan positif (Mochtar, 2012;h.35).
3) Tanda pasti kehamilan
a) Gerakan janin dalam Rahim
b) Terlihat/teraba gerakan janin dan teraba bagian-bagian janin
c) Denyut jantung janin. Didengar dengan stetoskop Laenec, alat kardiotokografi, alat Doppler. Dilihat dengan ultrasonografi. Pemeriksaan dengan alat canggih, yaitu rontgen untuk melihat
karangka janin, ultrasonografi (Manuaba, 20110;h.109).
e. Ketidaknyamanan Pada Masa Kehamilan
1) Nausea
Nausea, dengan atau tanpa disertai muntah-muntah, ditafsirkan
2) Ptialisme
Ptialisme merupakan kondisi yang tidak lazim, yang dapat disebabkan oleh peningkatan keasaman di dalam mulut atau
peningkatan asupan zat pati, yang menstimulasi kelenjar saliva
pada wanita yang rentan mengalami sekresi berlebihan (Varney, 2007;h.537).
3) Keletihan
Keletihan yang di alami pada trimester pertama, namun alasanya
belum diketahui. Salah satu dugaan adalah bahwa keletihan
diakubatkan oleh penurunan drastis laju metabolism dasar pada
awal kehamilan, tetapi alas an hal ini terjadi masih belum jelas.
Untungnya, keletihan merupakan ketidaknyamanan yang terbatas
dan biasanya hilang pada akhir trimester pertama (Varney,
2007;h.537).
4) Nyeri Punggung Bagian Atas
Nyeri punggung bagian atas terjadi selama trimester pertama
akibat peningkatan ukuran payudara, yang membuat payudara
menjadi berat. Pembesaran ini dapat mengakibatkan tarikan otot
jika payudara tidak disokong adekuat. Metode untuk mengurangi
nyeri ini ialah dengan menggunakan bra yang berukuran sesuai
ukuran payudara. Dengan mengurangi mobilitas payudara, bra
ketidaknyamanan akibat nyeri tekan pada payudara yang timbul
karena pembesaran payudara (Varney, 2007;h.538).
5) Leukorea
Leukorea adalah sekresi vagina dalam jumlah besar, dengan
konsistensi kental atau cair, yang di mulai pada trimester pertama.
Upaya untuk mengatasi leukorea adalah dengan memperhatikan
kebersihan tubuh pada area tersebut dan mengganti panty
berbahan katun dengan sering (Varney, 2007;h.538).
6) Peningkatan frekuensi berkemih
Frekuensi berkemih selama trimester pertama terjadi akibat
peningkatan berat pada fundus uterus. Peningkatan berat pada
fundus uterus ini membuat istmus menjadi lunak (tanda hegar),
menyebabkan antefleksi pada uterus yang membesar. Hal ini menimbulkan tekanan langsung pada kandung kemih. Frekuensi
berkemih pada trimester ketiga paling sering dialami oleh wanita
primigravida setelah lightening terjadi. Efek lightening adalah bagian presentasi akan menurun masuk kedalam panggul dan
menimbulkan tekanan langsung pada kandung kemih. Tekanan ini
menyebabkan wanita merasa perlu berkemih (Varney,
7) Konstipasi
Wanita yang sebelumnya tidak mengalami konstipasi dapat
memiliki masalah ini pada trimester kedua atau ketiga. Konstipasi
diduga terjadi akibat penurunan peristaltis yang disebabkan
relaksasi otot polos pada usus besar ketika terjadi peningkatan
jumlah progesterone (Varney, 2007;h.539).
8) Hemoroid
Hemoroid sering didahului oleh konstipasi. Oleh karena itu, semua
penyebab konstipasi berpotensi menyebabkan hemoroid.
Progesterone juga menyebabkan hemoroid. Progesterone
menyebabkan relaksasi dinding vena dan usus besar (Varney,
2007;h.539).
9) Varises
Varises dapat diakibatkan oleh gangguan sirkulasi vena dan
peningkatan tekanan vena pada ekstremitas bagian bawah.
Perubahan ini diakibatkan penekanan uterus yang membesar
pada vena panggul saat wanita tersebut duduk atau berdiri dan
penekanan pada vena kava inferior saat ia berbaring. Pakaian
yang ketat menghambat aliran vena balik dari ekstremitas bagian
bawah, atau posisi berdiri yang lama memperberat masalah
10) Insomnia
Insomnia, baik pada wanita yang mengandung maupun tidak, dapat disebabkan oleh sejumlah penyebab, seperti kekhawatiran,
kecemasan, terlalu gembira menyambut suatu acara untuk
keesokan hari. Wanita hamil, bagaimanapun, memiliki tambahan
alas an fisik sebagai penyebab insomnia. Hal ini meliputi ketidaknyamanan lain selama kehamilan, dan pergerakan janin,
terutama jika janin tersebut aktif (Varney, 2007;h.541).
f. Tanda Bahaya pada Kehamilaan
1) Perdarahan
Perdarahan pada kehamilan muda atau usia kehamilan
dibawah 20 minggu, umumnya disebabkan oleh keguguran.
Penyebab lainnya antara lain karena kelainan kromosom yang
ditemui pada spermatozoa ataupun ovum, pembesaran uterus
yang diatas normal (molahidatidosa), pembesaran uterus yang tidak sesuai (lebih kecil) dari usia kehamilan, adanya massa di
adneksa biasanya disebabkan oleh kehamilan ektopik.
Perdarahan kehamilan lanjut atau di atas usia 20 minggu pada
umumnya disebabkan oleh plasenta previa. Perdarahan yang
segmen bawah Rahim yang menjadi tempat implementasi
plasenta tersebut (Prawirohardjo, 2014;h.282).
2) Preeklamsia
Pada umumnya ibu hamil dengan usia kehamilan di atas 20
minggu disertai dengan peningkatan tekanan darah di atas normal
sering diasosiasikan dengan preeklamsia. Data atau informasi
awal terkait dengan tekanan darah sebelum hamil akan sangat
membantu petugas kesehatan untuk membedakan hipertensi
kronis (yang sudah ada sebelumnya) dengan preeklamsia
(Prawirohardjo, 2014;h.283).
3) Nyeri hebat di daerah abdominal pelvikum
Tanda-tandanya :
(a) Trauma abdomen
(b) Preeklamsia
(c) Tinggi Fundus Uteri lebih besar dari usia kehamilan
(d) Bagian-bagian janin sulit diraba
(e) Uterus tegang dan nyeri
(f) Janin mati dalam Rahim
Bila hal tersebut diatas terjadi pada kehamilan trimester kedua
atau ketiga dan disertai dengan riwayat diatas, maka
yang disertai perdarahan maupun yang tersembunyi
(Prawirohardjo, 2014;h.283).
g. Asuhan Pada Kehamilan
Pengawasan antenatal memberikan manfaat dengan
ditemukannya berbagai kelainan yang menyertai kehamilan secara
dini, sehingga dapat diperhitungkan dan dipersiapkan
langkah-langkah dalam pertolongan persalinannya. Ibu hamil dianjurkan untuk
melakukan pengawasan antenatal sebanyak 4 kali, yaitu pada setiap
trimester, sedangkan trimester terakhir sebanyak dua kali (Manuaba,
2010;h.109-110).
Tujuan asuhan antenatal :
1) Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu
dan tumbuh kembang bayi.
2) Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan
sosial ibu dan bayi.
3) Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi
yang mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit
secara umum, kebidanan dan pembedahan.
4) Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan
5) Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan
pemberian asi eksklusif.
Dengan memperhatikan batasan dan tujuan pengawasan
antenatal, maka jadwal pemeriksaan adalah sebagai berikut:
a) Pemeriksaan pertama. Pemeriksaan pertama dilakukan
segera setelah diketahui terlambat haid.
b) Pemeriksaan ulang :
(1) Setiap bulan sampai usia kehamilan 6 sampai 7 bulan.
(2) Setiap 2 minggu sampai usia kehamilan 8 bulan.
(3) Setiap 1 minggu sejak usia kehamilan 8 bulan sampai
terjadi persalinan.
(4) Pemeriksaan khusus bila terdapat keluhan tertentu
(Manuaba, 2010;h.111).
h. Pemberian Pelayanan Antenatal
(Kemenkes, 2015;h.106).
Sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan:
1) Pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu) minimal 1
kali.
2) Pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu) minimal 1
3) Pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu-persalinan)
minimal 2 kali.
i. Pelayanan Antenatal (10 T)
(Kemenkes, 2013;h.72)
1) Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.
2) Pengukuran Tekanan Darah.
3) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA).
4) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
5) Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi
tetanus toksoid sesuai status imunisasi.
6) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama
kehamilan.
7) Penentuan presentasi janin dan denyut janjung janin (DJJ).
8) Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal
dan konseling, termasuk keluarga berencana).
9) Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin
dan darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan
golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya).
2. Persalinan
a. Pengertian Persalinan
Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks,
dan janin turun ke jalan lahir (Sumarah, dkk, 2009;h.1). Persalinan
adalah rangkaian peristiwa mulai dari kenceng-kenceng teratur
sampai keluarnya produk konsepsi (janin, plasenta, ketuban, dan
cairan ketuban) dari uterus ke dunia luar melalui jalan lahir atau
melalui jalan lain, dengan bantuan atau dengan kekuatan sendiri
(Sumarah, dkk, 2009;h.1).
Persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan
pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai dengan
kontraksi persalinan sejati, yang ditandai pleh perubahan progresif
pada serviks, dan diakhiri dengan pelahiran plasenta (Varney,
2008;h.672).
Persalinan dapat disimpulkan sebagai suatu proses
pengeluaran hasil konsepsi (janin dan uteri) yang telah cukup bulan
atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui
b. Sebab-Sebab Mulainya Persalinan
Ada beberapa teori yang memungkinkan terjadinya proses
persalinan :
1) Teori keregangan
Otot Rahim mempunyai kemampuan meregang dalam batas
tertentu. Setelah melewati batas waktu tersebut terjadi kontraksi
sehingga persalinan dapat di mulai. Keadaan uterus yang terus
membesar dan menjadi tegang mengakibatkan iskemia otot-otot uterus. Hal ini mungkin merupakan faktor yang dapat
mengganggu sirkulasi uteroplasenter sehingga plasenta mengalami degenerasi. Pada kehamilan ganda seringkali terjadi
kontraksi setelah keregangan tertentu, sehingga menimbulkan
proses persalinan (Sumarah, dkk 2009;h.3).
2) Teori penurunan progesterone
Proses penuaan plasenta terjadi mulai umur kehamilan 28
minggu, di mana terjadi penimbunan jaringan ikat, pembuluh
darah mengalami penyempitan dan buntu. Villi koriales mengalami perubahan-perubahan dan produksi progesterone
mengalami penurunan, sehingga otot Rahim mulai berkontraksi
terhadap oksitosin. Akibatnya otot rahim mulai berkontraksi
setelah tercapai tingkat penurunan progesterone (Sumarah, dkk
3) Teori oksitosin internal
Oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis pars posterior. Perubahan keseimbangan estrogen dan progesterone dapat
mengubah sensitivitas otot rahim, sehingga sering terjadi
kontraksi Braxton hicks. Menurunnya konsentrasi progesterone akibat tuanya kehamilan maka oksitosi dapat meningkatkan
aktivitas, sehingga persalinan dimulai (Sumarah, dkk 2009;h.3).
4) Teori prostaglandin
Konsentrasi prostaglandin meningkat sejak umur kehamilan
15 minggu, yang dkeluarkan oleh desidua. Pemberian
prostaglandin pada saat hamil dapat menimbulkan kontraksi otot
rahim sehingga terjadi persalinan. Prostaglandin dianggap dapat
merupakan pemicu terjadinya persalinan (Sumarah, dkk
2009;h.3).
5) Teori hipotalamus-pituitaritas dan glandula suprarenalis
Teori ini menunjukkan pada kehamilan dengan anensefalus sering terjadi keterlambatan persalinan karena tidak terbentuk
hipotalamus. Teori ini dikemukakan oleh Linggin (1973). Malpar
tahun 1933 mengangkat otak kelinci percobaan, hasilnya
kehamilan kelinci menjadi lebih lama. Pemberian kortikosteroid
yang dapat menyebabkan maturitas janin, induksi persalinan
c. Tanda dan Gejala Menjelang Persalinan
1) Lightening
Lightening merupakan penurunan bagian presentasi bayi ke pelvis minor, biasanya di masa ini ibu akan merasa sesak nafas
yang dirasakan sebelumnya akan berkurang karenapada saat
kejadian ini akan menciptakan ruang yang lebih besar di dalam
abdomen atas untuk ekspansi paru tetapi lightening tetap menimbulkan rasa tidak nyaman akibat tekanan bagian
presentasi pada struktur di area pervis minor (Varney,
2008;h.672-673).
2) Perubahan serviks
Selama masa hamil, servik dalam keadaan menutup, panjang
dan lunak, dan pada masaini servik masih lunak dan mengalami
penipisan (effacement) dan kemungkinan sedikit dilatasi. Perubahan servik ini terjadi akibat peningkatan intensitas
kontraksi Braxton Hicks. Dari perubahan inilah bisa meyakinkan ibu bahwa dirinya akan berlanjut ke proses persalinan begitu
muncul kontraksi (Varney, 2008;h.673).
3) Bloody Show
Di tandai dengan adanya plak lendir yang disekresi serviks
sebagai proliferasi kelenjar lendir serviks pada awal kehamilan,
lengket, biasanya keluar dalam bentuk massa. Hal ini
merupakan tanda pasti persalinan akan terjadi bila pada 48 jam
sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan vagina, karena tanda
tanda bloody show tersebut bisa terjadi karena trauma kecil saat pemeriksaan (Varney, 2008;h.673-674).
4) Adanya kontraksi/His
Kekuatan fisiologis utama selama persalinan adalah
kontraksi uterus yang menimbulkan nyeri pada tubuh, kontraksi
ini merupakan kontraksi yang involunter karena berada di bawah pengaruh saraf intrinsic.
Kontraksi uterus bersifat intermiten sehingga ada periode
relaksasi uterus diantara kontraksi, memiliki fungsi penting :
a) Mengistirahatkan otot uterus
b) Memberi kesempatan istirahat bagi wanita
c) Mempertahankan kesejahteraan bayi karena kontraksi
uterus
d) Menyebabkan kontriksi pembuluh darah plasenta
Durasi kontraksi uterus bervariasi, tergantung pada kala persalinan
wanita tersebut, kontraksi pada persalinan aktif berlangsung dari 45
sampai 90 detik dengan durasi rata-rata 60 detik. Pada persalinan
awal kontraksi hanya berlangsung 15 sampai 20 detik (Varney,
5) Penipisan dan pembukaan
Terjadi karena saluran serviks yang semula memiliki panjang dua
sampai tiga sentimeter memendek sampai pada titik saluran serviks
yang menghilang sehingga hanya menyisakan os eksternal dengan bagian bagian tepi tipis. Penipisan dan pembukaan awal bervariasi
antara primigravida dan multigravida yang memasuki persalinan,
serviks primigravida umumnya menipis 50 sampai 60 persen dan
membuka selebar ujung jari sampai 1 sentimeter sebelum
mencapai persalinan akibat kontraksi Braxton Hicks sebelum prosen persalinan dimulai (Varney, 2008;h.676).
d. Mekanisme Persalinan
1) Engangement
Engangement pada primigravida terjadi pada bulan terakhir kehamilan, sedangkan pada multigravida dapat terjadi pada awal persalinan. Engangement adalah peristiwa ketika diameter bipariental melewati pintu atas panggul dengan sutura sagitalis
melintang/oblik di dalam jalan lahir dan sedikit fleksi. Masuknya kepala akan mengalami kesulitan bila saat masuk ke dalam
sagitalis melintang di jalan lahir, tulang pariental kanan dan kiri
sama tinggi, maka keadaan ini disebut sinklitismus.
Kepala pada saat melewati pintu atas panggul dapat juga
dalam keadaan dimana sutura sagitalis lebih dekat ke promontorium atau ke sympisis maka hal ini disebut asinklitismus. Ada dua macam asinklitismus:
a) Asinklitismus Posterior yaitu keadaan bila sutura sagitalis mendekati sympfisis dan tulang pariental belakang lebih rendah dari pada tulang pariental depan. Terjadi karena
tulang pariental belakang dapat turun dengan mudah karena
adanya lengkung sacrum yang luas.
b) Asinklitismus Anterior yaitu keadaan bila sutura sagitalis mendekati promontorium dan tulang pariental depan lebih
rendah dari pada tulang pariental belakang (Sumarah,
2009;h.91).
2) Penurunan kepala
Dimulai sebelum onset persalinan/inpartu. Penurunan kepala
terjadi bersamaan dengan mekanisme lainnya (Sumarah,
3) Fleksi
a) Gerakan fleksi disebabkan karena janin terus didorong maju tetapi kepala janin terhambat oleh serviks, dinding panggul
atau dasar panggul.
b) Pada kepala janin, dengan adanya fleksi maka diameter
oksipitofrontalis 12 cm berubah menjadi
suboksipitobregmatika 9 cm.
c) Posisi dagu bergeser ke arah dada janin.
d) Pada pemeriksaan dalam ubun-ubun kecil lebih jelas teraba
daripada ubun-ubun besar (Sumarah, 2009;h.92).
4) Rotasi dalam
a) Rotasi dalam atau putar paksi dalam adalam pemutaran
bagian terendah janin dari posisi sebelumnya kearah depan
sampai dibawah simpisis.
b) Sebab-sebab adanya putar paksi dalam yaitu:
(1) Bagian terendah kepala adalah bagian belakang kepala
pada letak fleksi.
(2) Bagian belakang kepala mencari tahanan yang paling
sedikit yang di sebelah depan atas yaitu hiatus genetalis
antara muskulus levator ani kiri dan kanan (Sumarah,
5) Ekstensi
a) Gerakan ekstensi merupakan gerakan dimana oksiput berhimpit langsung pada margo inferior simpisis pubis. b) Penyebab dikarenakan sumbu jalan lahir pada pintu bawah
panggul mengarah ke depan dan atas, sehingga kepala
menyesuaikan dengan cara ekstensi agar dapat melaluinya. Gerakan ekstensi ini mengakibatkan bertambahnya
penegangan pada perineum dan intruitus vagina. Ubun-ubun kecil semakin banyak terlihat dan sebagai
hypomochlion atau pusat pergerakan maka berangsur-angsur lahirlah ubun-ubun kecil, ubun-ubun besar, dahi,
mata, hidung, mulut, dan dagu. Pada saat kepala sudah
lahir seluruhnya, dagu bayi berada di atas anus ibu
(Sumarah, 2009;h.95-96).
6) Rotasi luar
a) Merupakan gerakan memutar ubun-ubun kecil kearah
punggung janin, bagian belakang kepala berhadapan
dengan tuber iskhiadikum kanan atau kiri, sedangkan muka janin menghadap salah satu paha ibu. Bila ubun-ubun kecil
pada mulanya di sebelah kiri maka ubun-ubun kecil akan
berputar kea rah kiri, bila pada mulanya ubun-ubun kecil di
b) Gerakan rotasi luar atau putar paksi luar ini menjadikan
diameter biakromial janin searah dengan diameter anteroposterior pintu bawah panggul, dimana satu bahu di
anterior di belakang simpisis dan bahu yang satunya di
bagian posterior di belakang perineum.
c) Sutura sagitalis kembali melintang (Sumarah, 2009;h.97). 7) Ekspulsi
Setelah terjadinya rotasi luar, bahu depan berfungsi sebagai
hypomochlion untuk kelahiran bahu belakang. Kemudian setelah kedua bahu lahir disusul ahirlah trochanter depan dan belakang sampai lahir janin seluruhnya. Gerakan kelahiran bahu
depan, bahu belakang, badan seluruhnya (Sumarah,
2009;h.97-98).
e. Tahap-Tahap Persalinan
1) Persalinan Kala I
Persalinan Kala I adalah kala pembukaan yang
berlangsungantara pembukaan nol sampai pembukaan lengkap.
Pada permulaan his kala pembukaan berlangsung tidak begitu
kuat sehingga ibu/wanita masih dapat berjalan-jalan. Klinis
dapat dinyatakan mulai terjadi partus jika timbul his dan wanita
show). Lendir yang bersemu darah ini berasal dari lendir kanalis servikalis karena serviks mulai membuka atau mendatar.
Sedangkan darah berasal dari pembuluh-pembuluh kapiler yang
berada di sekitar kanalis servikalis tersebut pecah karena
pergeseran-pergeseran ketika serviks membuka. Proses ini
berlangsung kurang lebih 18-24 jam, yang terbagi menjadi 2
fase, yaitu fase lateng (8 jam) dari pembukaan 0 cm sampai
pembukaan 3 cm, dan fase aktif (7 jam) dari pembukaan serviks
3 cm sampai pembukaan 10 cm. dalam fase aktif ini masih
dibagi menjadi 3 fase lagi yaitu : fase akselerasi dimana dalam
waktu 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4 cm, fase dilatasi
maksimal yakni dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung
sangat cepat dari pembukaan 4 cm sampai 9 cm, dan fase
deselerasi dimana pembukaan menjadi lambat kembali. Dalam
waktu 2 jam pembukaan 9 cm menjadi 10 cm. kontraksi menjadi
lebih kuat dan lebih sering pada fase aktif.
Berdasarkan kurve Fridman, diperhitungkan pembukaan pada primigravida 1 cm/jam dan pembukaan pada multigravida
2 cm/jam. Dengan demikian waktu pembukaan lengkap dapat
2) Kala II (Pengeluaran)
Dimulai dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai bayi
lahir. Proses ini berlangsung 2 jam pada primigravida dan 1 jam
pada multigravida. Pada kala ini his menjadi lebih kuat dan
cepat, kurang lebih 2-3 menit sekali. Dalam kondisi yang normal
pada kala ini kepala janin sudah masuk dalam ruangan panggul,
maka pada saat his dirasakan tekanan pada otot-otot dasar
panggul, yang secara reflektoris menimbulkan rasa mengedan. Wanita merasa adanya tekanan pada rectum dan seperti akan
buang air besar. Kemudian perineum mulai menonjol menjadi
lebar dengan membukanya anus. Labia mulai membuka dan
tidak lama kemudian kepala janin tampak dalam vulva pada saat ada his. Jika dasar panggul sudah berelaksasi, kepala janin
tidak masuk lagi diluar his. Dengan kekuatan his dan mengedan
maksimal kepala janin dilahirkan dengan suboksiput di bawah
simpisis dan dahi, muka, dagu melewati perineum. Setelah his
istirahat sebentar, maka his akan mulai lagi untuk mengeluarkan
anggota badan bayi (Sumarah, 2009;h.4-8).
3) Kala III (pelepasan Uri)
Dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta,
uterus teraba keras dengnan fundus uteri berkontraksi lagi untuk
melepaskan plasenta dari dindingnya (Sumarah, 2009;h.7).
4) Kala IV (Observasi)
Dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama
post partum. Tujuan asuhan persalinan adalah memberikan
asuhan yang memadahi selama persalinan dalam upaya
mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman,
dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan sayang bayi.
Observasi yang dilakukan pada Kala IV adalah:
a) Tingkat kesadaran penderita.
b) Pemeriksaan tanda-tanda vital: tekanan darah, nadi dan
pernapasan.
c) Kontraksi uterus.
d) Terjadinya perdarahan.
Perdarahan dianggap masih normal jika jumlahnya tidak
melebihi 400 sampai 500 cc (Sumarah, 2009;h.8).
f. Asuhan Persalinan Normal
1) Asuhan kala 1
Menurut JNPK-KR (2014) persiapan asuhan persalinan pada
kala 1 yaitu: menyiapkan kelahiran (ruangan dan perlengkapan
obat-obatan yang dibutuhkan, memberikan asuhan sayang ibu kala 1
persalinan, kaji prinsip-prinsip umum asuhan sayang ibu,
mengatur posisi, pencatatan pada partograf (DJJ, HIS, Nadi
setiap ½ jam, pembukaan, penurunan bagian terendah janin,
TD, dan suhu setiap 4 jam, produksi urine setiap 2-4 jam.
2) Asuhan kala 2 dan kala 3
Menurut Sarwono Prawirohardjo (2014;341-347).
Melihat Tanda dan Gejala Kala Dua
a) Mengamati tanda dan gejala persalinan kala dua.
(1) Ibu mempunyai keinginan untuk meneran.
(2) Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada
rectum dan/ vaginanya.
(3) Perineum menonjol.
(4) Vulva-vagina dan sfingter anal membuka.
Menyiapkan Pertolongan Persalinan
b) Memastikan perlengkapan, bahan, dan obat-obatan esensial
siap digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan
menempatkan tabung suntik steril sekali pakai di dalam
partus set.
c) Mengenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih,
sepatu tertutup kedap air, tutup kepala, masker dan
d) Melepaskan semua perhiasan yang dipakai di bawah siku,
mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang
mengalir dan mengeringkan tangan dengan handuk satu kali
pakai/pribadi yang bersih.
e) Memakai satu sarung dengan DTT atau steril untuk semua
pemeriksaan dalam.
f) Mengisap oksitosin 10 unit k edalam tabung suntik (dengan
memakai sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril)
dan meletakkan kembali di partus set/wadah disinfeksi
tingkat tinggi atau steril tanpa mengontaminasi tabung
suntik).
Memastikan Pembukaan Lengkap dengan Janin Baik
g) Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan
hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan
kapas atau kasa yang sudah di basahi air disinfeksi tingkat
tinggi. Jika mulut vagina, perineum, atau anus
terkontaminasi oleh kotoran ibu, membersihkannya dengan
seksama dengan cara menyeka dari depan ke belakang.
Membuang kapas atau kasa yang terkontaminasi dalam
wadah yang benar. Mengganti sarung tangan jika
h) Dengan menggnakan teknik aseptik, melakukan
pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan
serviks sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah,
sedangkan pembukaan serviks sudah lengkap, lakukan
amniotomi.
i) Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara
mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan
kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian
melepaskannya dengan keadaan terbalik serta
merendamnya di larutan klorin 0,5% selama 10 menit.
Mencuci kedua tangan (seperti di atas).
j) Memeriksa Denyut Jantung Janin (DJJ) setelah kontraksi
berakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal
(100-180 kali/menit).
(1) Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal.
(2) Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam,
DJJ, dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan
Menyiapkan Ibu dan Keluarga untuk Membantu Proses
Pimpinan Meneran
k) Memberi tahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan
janin baik. Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman
sesuai dengan keinginannya.
(1) Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk
meneran. Melanjutkan pemantauan kesehatan dan
kenyamanan ibu serta janin sesuai dengan pedoman
persalinan aktif dan mendokumentasikan
temuan-temuan.
(2) Menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana
mereka dapat mendukung dan memberi semangat
kepada ibu saat ibu mulai meneran.
l) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu
untuk meneran. (pada saat ada his, bantu ibu dalam poisi
setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman).
m) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai
dorongan yang kuat untuk meneran:
(1) Membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai
keinginan untuk meneran.
(2) Mendukung dan memberi semangat atas usaha ibu
(3) Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai
dengan pilihannya (tidak meminta ibu berbaring
terlentang).
(4) Menganjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi.
(5) Menganjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi
semangat pada ibu.
(6) Menganjurkan asupan cairan pe oral.
(7) Menilai DJJ setai lima menit.
(8) Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan
terjadi segera dalam waktu 120 menit (2 jam) meneran
untuk ibu primipara atau 60 menit (1 jam) untuk ibu
multipara, merujuk segera. Jika ibu tidak mempunyai
keinginan untuk meneran.
(9) Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau
mengambil posisi yang aman. Jika ibu belum ingin
meneran dalam 60 menit, anjurkan ibu untuk mulai
meneran pada puncak kontraksi-kontraksi tersebut dan
beristirahat di antara kontraksi.
(10) Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan
terjadi segera 60 menit meneran, merujuk ibu dengan
Persiapan Pertolongan kelahiran Bayi
n) Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6
cm, letakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk
mengeringkan bayi.
o) Meletakkan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian, di bawah
bokong ibu.
p) Membuka partus set.
q) Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan.
Menolong Kelahiran Bayi
Lahirnya kepala
r) Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm,
lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain
tadi, letakkan tangan yang lain di kepal bayi dan lakukan
tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada kepal
bayi, membiarkan kepala keluar perlahan-lahan.
Menganjurkan ibu untuk meneran perlahan-lahan atau
bernapas cepat saat kepala lahir.
s) Dengan lembut menyeka muka, mulut, dan hidung bayi
dengan kain atau kasa yang bersih. (Langkah ini tidak harus
t) Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang
sesuai jika hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segera
proses kelahiran bayi:
(1) Jika tali pusat melilit leher janin dengan longgar,
lepaskan lewat bagian atas kepala bayi.
(2) Jika tali pusat melilit leher bayi dengan erat,
mengklemnya di dua tempat dan memotongnya.
u) Menunggu hingga kepal bayi melakukan putaran paksi luar
secara spontan.
Lahir Bahu
v) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan
kedua tangan di masing-masing sisi muka bayi.
Mengajurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya.
Dengan lembut menariknya kearah bawah dank e arah luar
hingga bahu snterior muncul di bawah arkus pubis dan
kemudian dengan lembut menarik kea rah atas dan kea rah
luar untuk melahirkan bahu posterior.
w) Setelah kedua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan mulai
kepala bayi yang berada di bagian bawah kea rah perineum,
membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tanga
menyangga tubuh bayi saat dilahirkan. Menggunakan
tangan anterior (bagian atas) untuk mengendalikan siku dan
tangan anterior bayi saat keduanya lahir.
x) Setelah tubuh dari lengan lahir, menelusurkan tangan yang
ada di atas (anterior) dari punggung ke arah kaki bayi untuk
menyangganya saat punggung kaki lahir. Memegang kedua
mata kaki bayi dengan hati-hati membantu kelahiran kaki.
Penanganan Bayi Baru Lahir
y) Menilai bayi dengan cepat (dalam 30 detik), kemudian
meletakkan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi
sedikit lebih rendah dari tubuhnya (bila tali pusat terlalu
pendek, meltakkan bayi di tempat yang memungkinkan). Bila
bayi mengalami asfiksia, lakukan resusitasi.
z) Segera membungkus kepala dan badan bayi dengan
handuk dan biarkan kontak kulit ibu-bayi. Lakukan
penyuntikan oksitosin/i.m.
aa) Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari
pusat bayi. Melakukan urutan pada tali pusat mulia dari klem
ke arah ibu dan memasang klem kedua 2 cm dari klem
bb) Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi
dari gunting dan memotong tali pusat di antara dua klem
tersebut.
cc) Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah dan
menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan
kering, mnutupi bagian kepala, membiarkan tali pusat
terbuka. Jika bayi mengalami kesulitan bernapas, ambil
tindakan yang sesuai.
dd) Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu
untuk memeluk bayinya dan memulai pemberian bayi
kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk memeluk
bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu
menghendakinya.
Oksitosin
ee) Meletakkan kain yang bersih dan kering. Melakukan palpasi
abdomen menghilangkan kemungkinan adanya bayi kedua.
ff) Memberi tahu kepada ibu bahwa ia akan disuntik.
gg) Dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, berikan
suntikan oksitosin 10 unit I.m di gluteus atau 1/3 atas paha kanan ibu bagian luar, setelah mengaspirasinya terlebih
Penegangan Tali Pusat Terkendali
hh) Memidahkan klem pada tali pusat.
ii) Meletakkan satu tangan si atas kain yang ada di perut ibu,
tepat di atas tulang pubis, dan menggunakan tangan ini
untuk melakukan palpasi kontraksi dan menstabilkan uterus.
Memegang tali pusat dan klem dengan tangan yang lain.
jj) Menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan
penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut.
Lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah
uterus dengan cara menekan uterus ke arah atas dan
belakang (dorso kranial) dengan hati-hati untuk membantu
mencegah terjadinya inversion uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan
menunggu hingga kontraksi berikut mulai.
(1) Jika uterus tidak berkontraksi, meminta ibu atau seorang
anggota keluarga untuk melakukan rangsangan putting
susu.
Mengeluarkan Plasenta
kk) Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran
arah atas, mengikuti kurva jalan lahir sambil meneruskan
tekanan berlawanan arah pada uterus.
(1) Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem
hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva.
(2) Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan
penegangan tali pusat selama 15 menit:
(a) Mengulangi pemberian oksitosin 10 unit I.M.
(b) Menilai kandung kemih dan dilakukan kateterisasi
kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptic
jika perlu.
(c) Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan.
(d) Mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit
berikutnya.
(e) Merujuk ibu juka plasenta tidak lahir dalam waktu 30
menit sejak kelahiran bayi.
ll) Jika plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan.
Memegang plasenta dengan kedua tangan dan dengan
hati-hati memutar plasenta hingga selaput ketuban terpilin.
Dengan lembut perlahan melahirkan selaput ketuban
(1) Jika selaput ketuban robek, memakai sarung tangan
disinfeksi tingkat tinggi atau steril dan memeriksa vagina
dan serviks ibu dengan seksama. Menggunakan jari-jari
tangan atau klem atau forseps disinfeksi tingkat tinggi
atau steril untuk melepaskan bagian selaput yang
tertinggal.
Pemijatan Uterus
mm) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir,
lakukan masase uterus, meletakkan telapak tangan di
fundus dan melakukan masase dengan gerakan melingkar
dengan lembut hingga uterus berkontraksi (fundus menjadi
keras).
Menilai Perdarahan
nn) Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu
maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa
plasenta dan selaput ketuban lengkap dan utuh. Meletakkan
plasenta di dalam kantung plastic atau tempat khusus.
(a) Jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan
masase selama 15 detik mengambil tindakan yang
oo) Mengevaluasi adanya laserasi pda vagina dan perineum
dan segera menjahit laserasi yang mengalami perdarahan
aktif.
Melakukan Prosedur Pascapersalinan
pp) Menilai ulang uterus dan memastikannya berkontraksi
dengan baik.
qq) Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan
ke dalam larutan klorin 0,5% membilas kedua tangan yang
masih bersarung tangan tersebut dengan air disinfeksi
tingkat tinggi dan mengeringkannya dengan kain yang
bersih dan kering.
rr) Menempatkan klem tali pusat disinfeksi tingkat tinggi atau
steril atau mengikatkan tali disinfeksi tingkat tinggi dengan
simpul mati sekeliling tali pusat sekitar 1 cm dari pusat.
ss) Mengikat satu lagi simpul mati di bagian pusat yang
berseberangan dengan simpul mati yan pertama.
tt) Melepaskan klem bedah dan meletakkannya ke dalam
larutan klorin 0,5%.
uu) Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya.
Memastikan handuk atas kainnya bersih atau kering.
ww) Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan
pervaginam:
(1) 2-3 kali dalam 15 menit pertama pascapersalinan.
(2) Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pascapersalinan.
(3) Setiap 20-30 menit pada jam kedua pascapersalinan.
(4) Jika uterus tidak berkontraksi dennganbaik, laksanakan
perawatan yang sesuai untuk menatalaksana atonia uteri.
(5) Jika ditemukan laserasi yang memerlukan penjahitan,
lakukan penjahitan dengan anesthesia local dan
menggunakan teknik yang sesuai.
xx) Mengajarkan pada ibu/keluarga bagaimana melakukan
masase uterus dan memeriksa kontraksi uterus. yy) Mengevaluasi kehilangan darah.
zz) Memeriksa tekanan darah, nadi, dan keadaan kandung
kemih setiap 15 menit selama satu jam pertama
pascapersalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua
pasca persalinan.
(1) Memeriksa temperature tubuh ibu sekali setiap jam
selama dua jam pertama pascapersalinan.
(2) Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang
Kebersihan dan Keamanan
aaa) Menempatkan semua peralatan si dalam larutan klorin
0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Mencuci dan mebilas
peralatan setelah dekontaminasi.
bbb) Membuang bahan-bahan yan terkontaminasi ke dalam
tempat sampah yang sesuai.
ccc) Membersihkan ibu dengan menggunakan air disinfeksi
tinggi. Membersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah.
Membantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering.
ddd) Memastikan bahwa ibu nyaman. Membantu ibu
memberikan ASI. Menganjurkan keluarga untuk memberikan
ibu minuman dan makanan yang diinginkan.
eee) Mendekontaminasi daerah yang digunakan untuk
melahirkan dengan larutan klorin 0,5% dan membilas
dengan air bersih.
fff) Mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin
0,5%, membalikkan bagian dalam ke luar dan merendamnya
dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.
ggg) Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir.
Dokumentasi
3) Asuhan kala 4
Menurut JNPK-KR (2014) penatalaksanaan persalinan
kala 4 yaitu: memastikan uterus berkontraksi dengan baik, beri
cukup waktu untuk melakukan kontak kulit bayi dan ibu,
melakukan penimbangan/pengukuran bayi, beri tetes mata
antibiotil profilaksis, dan vitamin K1 1 mg IM di paha kiri
anterolateral setelah 1jam kontak kulit ibu-bayi, memberikan
suntikan imunisasi Hepatitis (setelah 1 jam pemberian vitamin
K1) di paha kanan anterolateral, melanjutkan pemantauan
kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam, mengajarkan
ibu/keluarga cara melakukan massase uterus, mengevaluasi
dan estimasi jumlah kehilangan darah, memeriksa nadi ibu dan
keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama
pascapersalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua
pascapersalinan, memeriksa temperature tubuh ibu sekali setiap
jam selama 2 jam pertama pascapersalinan, memeriksa kembali
kondisi bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan
baik, serta suhu tubuh normal, melengkapi partograf (halaman
3. Bayi Baru Lahir
a. Pengertian Bayi Baru Lahir
Asuhan segera pada bayi baru lahir adalah asuhan yang
diberikan pada bayi tersebut selama jam pertama setelah kelahiran.
Sebagian besar bayi yang baru lahir akan menunjukkan usaha
pernapasan spontan dengan sedikit bantuan atau gangguan
(Prawirohardjo, 2010;h.N-30). Bayi baru lahir normal adalah bayi yang
lahir pada usia kehamilan 37-42 minggu dengan berat lahir antara
2500-4000 gram (Sondakh, 2013;h.150).
Bayi Baru Lahir Normal dapat disimpulkan bayi yang lahir
pada usia 37-42 minggu dengan berat badan 2500-4000 gr dan
panjang 50-55 cm.
b. Kriteria Bayi Baru Lahir Normal
(Sondakh, 2013;h.150)
1) Berat badan lahir bayi antara 2500 – 4000 gram
2) Panjang badan bayi 48-50 cm
3) Lingkar dada bayi 32-34 cm
4) Lingkar kepala bayi 33-35 cm
5) Bunyi jantung dalam menit pertama ±180 kali/menit. Kemudian
6) Pernapasa cepat pada menit-menit pertama kira-kira 80 kali/menit
disertai pernapasan cuping hidung, retraksi suprasternal dan intercostal, serta rintihan hanya berlangsung 10-15 menit.
7) Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan cukup
terbentuk dan dilapisi verniks kaseosa.
8) Rambut lanugo telah hilang, rambut kepala tumbuh baik.
9) Kuku telah agak panjang dan lemas.
10) Genitalia: testis sudah turun (pada bayi laki-laki) dan labia mayora
telah menutupi labia minora (pada bayi perempuan).
11) Refleks isap, menelan, dan moro telah terbentuk.
12) Eliminasi, urin, dan meconium normalnya keluar pada jam 24 jam
pertama. Meconium memiliki karakteristik hitam kehijauan dan
lengket.
c. Adaptasi Fisiologi Bayi Baru Lahir
1) System pernafasan
Rangsangan gerakan pernafasan pertama tejadi karena
tekanan mekanik dari toraks sewaktu melalui jalan lahir (stimulsi
mekanik), penurunan Pa O2 dan kenaikan Pa CO2 merangsang
kemoreseptor yang terletak di sinus karotikus (stimulasi kimiawi), rangsangan dingin di daerah muka dan perubahan suhu di dalam
Pernafasan pertama pada bayi normal terjadi dalam waktu 30
menit pertama sesudah lahir. Usaha bayi pertama kali untuk
mempertahankan tekanan alveoli, selain adanya serfaktan yang
dengan menarik nafas dan mengeluarkan nafas dengan merintih
sehingga udara tertahan di dalam. Respirasi pada neonatus
biasanya pernafasan diagfragmatik dan abnormal, sedangkan
frekuensi dan dalamnya belum teratur. Apabila surfaktan
berkurang, maka alveoli akan kolaps dan paru-paru kaku
sehingga terjadi atelectasis. Dalam keadaan anoksia neonates masih dapat mempertahankan hidupnya karena adanya
kelanjutan metabolism anaerobic (Muslihatun, 2010;h.12).
2) Suhu Tubuh
Terdapat empat mekanisme kemungkinan hilangnya panas
tubuh dari bayi baru lahir ke lingkungannya:
a) Konduksi
Panas dihantarkan dari tubuh bayi ke benda sekitarnya yang
kontak langsung dengan tubuh bayi (pemindahan panas dari
tubuh bayi ke objek lain melalui kontak langsung).
b) Konveksi
Panas hilang dari tubuh bayi ke udara sekitarnya yang sedang
bergerak (jumlah panas yang hilang tergantung kepada
c) Radiasi
Panas dipancarkan dari bayi baru lahir, keluar tubuhnya
kelingkungan yang lebih dingin (pemindahan panas antara 2
objek yang mempunyai suhu berbeda).
d) Evaporasi
Panas hilang melalui proses penguapan tergantung kepada
kecepatan dan kelembaban udara (perpindahan panas
dengan cara merubah cairan menjadi uap) (Muslihatun,
2010;h.12).
3) Metabolism
Pada jam-jam pertama energy didapatkan dari perubahan
karbohidrat. Pada hari kedua, energy berasal dari pembakaran
lemak. Setelah mendapat susu kurang lebih pada hari keenam,
pemenuhan kebutuhan energy bayi 60 % didapatkan dari lemak
dan 40 % dari karbohidrat (Muslihatun, 2010;h.14).
4) Adaptasi Kardiovaskuler
a) Denyut nadi berkisar 120-160 kali/menit saat bangun dan 100
kali/menit saat tidur.
b) Rata-rata tekanan darah adalah 80/46 mmHg dan bervariasi
sesuai dengan ukuran dan tingkat aktivitas bayi.
Dengan berkmbangnya paru-paru, pada alveoli akan terjadi
karbondioksida akan mengalami penurunan. Hal ini
mengakibatkan terjadinya penurunan resistensi pembuluh
darah dari arteri pulmonalis mengalir ke paru-paru dan ductus
arteriosus tertutup. Setelah tali pusat di potong, aliran darah
dari plasenta terhenti dan foramen ovale tertutup (Sondakh,
2013;h.152).
4) Adaptasi Neurologis
a) System neurologis bayi secra anatomi atau fisiologis belum berkembang sempurna.
b) Bayi baru lahir menunjukkan gerakan-gerakan tidak
terkoordinasi, pengaturan suhu yang labil, kontrol otot yang
buruk, mudah terkejut, dan tremor pada ekstremitas.
c) Perkembangan neonates terjadi cepat. Saat bayi tumbuh, perilaku yang lebih kompleks (misalnya: kontrol kepala,
tersenyum, dan meraih dengan tujuan) akan berkembang.
d) Reflex bayi baru lahir merupakan indikator penting
perkembangan normal (Sondakh, 2013;h.153-154).
5) Adaptasi Gastrointestinal
a) Enzim-enzim digestif aktif saat lahir dan dapat menyokong kehidupan ekstrauterin pada kehamilan 36-38 minggu.
b) Perkembangan otot dan reflek yang penting untuk
c) Pencernaan protein dan karbohidrat telah tercapai, p
encernaan, dan absorpsi lemak kurang baik karena tidak
adekuatnya enzim-enzim pankreas dan lipase.
d) Kelenjar saliva imatur saat lahir, sedikit saliva diolah sampai bayi berusia 3 bulan.
e) Pengeluaran meconium, yaitu feses berwarna hitam kehijauan, lengket, dan mengandung darah samar,
diekskresikan dalam 24 jam pada 90% bayi baru lahir yang
normal.
f) Variasi besar terjadi di antara bayi baru lahir tentang minat
terhadap makanan, gejala-gejala lapar, dan jumlah makanan
yang ditelan pada setiap kali pemberian makanan.
g) Beberapa bayi baru lahir menyusu segera bila diletakkan pada
payudara, sebagian lainnya memerlukan 48 jam untuk
menyusu secara efektif.
h) Gerakan acak tangan ke mulut dan menghisap jari telah
diamati di dalam uterus, tindakan-tindakan ini berkembang
baik pada saat lahir dan diperkuat dengan rasa lapar
6) Adaptasi Ginjal
a) Laju filtrasi glomerulus relative rendah pada saat lahir disebabkan oleh tidak adekuatnya area permukaan kailer
glomerulus.
b) Sebagian bayi baru lahir berkemih dalam 24 jam pertama
setelah lahir dan 2-6 kali sehari pada 1-2 hari pertama, setelah
itu mereka berkemih 5-20 kali dalam 24 jam (Sondakh,
2013;h.156).
7) Adaptasi Hati
a) Selama kehidupan janin dan sampai tingkat tertentu setelah
lahir, hati terus membantu pembentukan darah.
b) Selama periode neonatus, hati memproduksi zat yang
essensial untuk pembekuan darah.
c) Penyimpanan zat besi ibu cukup memadai bagi bayi sampai 5
bulan kehidupan ekstrauterin, pada saat ini bayi baru lahir menjadi rentan terhadap defisiensi.
d) Hati juga mengontrol jumlah bilirubin tak terkonjugasi yang
bersirkulasi, pigmen berasal dari hemoglobin dan dilepaskan
bersamaan dengan pemecahan darah merah.
e) Bilirubin tak terkonjugasi dapat meninggalkan system vascular
dan menembus jaringan ekstavaskular lainnya (misalnya: kulit,
kuning yang disebut jaundice atau ikterus (Sondakh, 2013;h157).
d. Penilaian Awal Bayi Baru Lahir
Segera setelah lahir, letakkan bayi di atas kain bersih dan kering yang
disiapkan pada perut bawah ibu. Segera lakukan penilaian awal
dengan menjawab 4 pertanyaan:
1) Apakah bayi cukup bulan?
2) Apakah air ketuban jernih, tidak bercampur meconium?
3) Apakah bayi menangis atau bernafas?
4) Apakah tonus otot bayi baik?
Jika bayi tidak cukup bulan atau ketuban bercampur meconium
dan atau tidak menangis atau tidak bernafas atau megap-megap
dan atau tonus otot tidak baik dilakukan langkah resusitasi
(JNPK-KR, 2014;h.124).
e. Pemeriksaan Neurologis
1) Reflex Morro/Terkejut
Apabila bayi di beri sentuhan mendadak terutama dengan jari dan
2) Reflek Menggenggam
Apabila telapak tangan bayi disentuh dengan jari pemeriksa,
maka ia akan berusaha menggenggam jari pemeriksa.
3) Reflex Rooting/Mencari
Apabila pipi bayi disentuh oleh jari pemeriksa, maka ia akan
menoleh dan mencari sentuhan itu.
4) Reflek Menghisap/Sucking Reflex
Apabila bayi diberi dot/putting, maka ia akan berusaha untuk
menghisap.
5) GlabellaReflex
Apabila bayi disentuh pada daerah os glabella dengan jari tangan pemeriksa, maka ia akan mengerutkan keningnya dan
mengedipkan matanya.
6) Gland reflex
Apabila bayi disentuh pada lipatan paha kanan dan kiri, maka ia
berusaha mengangkat kedua pahanya.
7) Tonick Neck Reflex
Apabila bayi diangkat dari tempat tidur (digendong), maka ia akan
berusaha mengangkat kepalanya.
f. Kunjungan Neonatal
Kunjungan neonatal tiga kali (dua kali pada minggu pertama dan satu
kali pada umur 8-28 hari) yaitu pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari,
dan umur 8-28 hari (Profil Kesehatan Indonesia, 2014;h.110).
Kunjungan Neonatus (KN) dilakukan sejak bayi usia 1 hari sampai 28
hari.
1) KN 1 dilakukan pada umur 6-48 jam (Profil Kesehatan Indonesia,
2014;h.110).
Tindakan yang dilakukan antara lain jaga kehangatan bayi,
memberikan ASI eksklusif, pencegahan infeksi, merawat tali
pusat, berikan imunisasi Hb 0.
2) KN 2 dilakukan pada umur 3-7 hari (Profil Kesehatan Indonesia,
2014;h.110).
Tindakan yang dilakukan antara lain menjaga tali pusat dalam
keadaan kering dan bersih, memberikan ASI eksklusif, menjaga
suhu tubuh bayi, pemeriksaan tanda bahaya, konseling ASI
eksklusif dan pencegahan hipotermi.
3) KN 3 dilakukan pada umur 8-28 hari (Profil Kesehatan Indonesia
2014;h.110).
Tindakan yang dilakukan yaitu sama dengan kunjungan pada
g. Tanda Bahaya pada Bayi Baru Lahir dan Neonatus
Beberapa tanda bahaya pada bayi baru lahir harus
diwaspadai, dideteksi lebih dini untuk segera dilakukan penanganan
agar tidak mengancam nyawa bayi. Beberapa tanda bahaya pada
bayi baru lahir tersebut, antara lain pernafasan sulit atau lebih dari 60
kali per menit, retraksi dada saat inspirasi. Suhu terlalu panas atau
lebih dari 38 ºC atau terlalu dingin atau kurang dari 36 ºC
Warna abnormal, yaitu kulit atau bibir biru atau pucat, memar
atau sangat kuning (terutama pada 24 jam pertama) juga merupakan
tanda bahaya bagi bayi baru lahir. Tanda bahaya pada bayi baru lahir
yang lain yaitu pemberian ASI sulit (hisapan lemah, mengantuk
berlebihan, banyak muntah), tali pusat merah, bengkak, keluar cairan,
bau busuk, berdarah serta adanya infeksi yang ditandai dengan suhu
tubuh meningkat, merah, bengkak, keluar cairan (pus), bau busuk,
pernafasan sulit.
Gangguan pada gastrointestinal bayi juga merupakan tanda
bahaya, antara lain mekoneum tidak keluar setelah 3 hari pertama
kelahiran, urine tidak keluar dalam 24 jam pertama, muntah
terus-menerus, distensi abdomen, feses hijau/berlendir/darah. Bayi mengigil atau menangis tidak seperti biasa, lemas, mengantuk,
terus-menerus, mata bengkak dan mengeluarkan cairan juga termasuk
dalam tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir.
4. Nifas
a. Pengertian Nifas
Masa nifas disebut juga masa post partum atau puerperium
adalah masa atau waktu sejak bayi dilahirkan dan plasenta keluar
lepas dari rahim, sampai enam minggu berikutnya, disertai dengan
pulihnya kembali organ-organ yang berkaitan dengan kandungan,
yang mengalami perubahan seperti perlukaan dan lain sebagainya
berkaitan saat melahirkan (Suherni, 2009;h.1).
Periode pascapartum/masa nifas adalah masa dari kelahiran
plasentadan selaput janin ( menandakan akhir periode intrapartum )
hingga kembalinya traktus reproduksi wanita pada kondisi tidak hamil
( Varney, 2008;h.958 ). Masa nifas atau puerperium dimulai sejak 1
jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu ( 42 hari )
setelah itu (Prawirohardjo, 2014;h.356).
Masa nifas dapat disimpulkan yaitu masa setelah keluarnya
plasenta sampai alat-alat reproduksi pulih seperti sebelum hamil dan