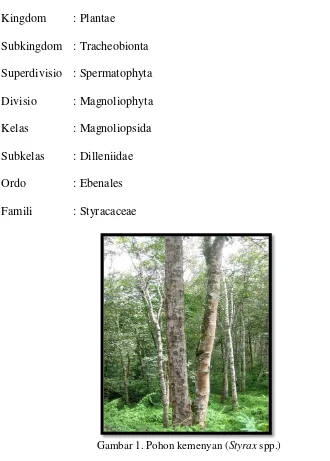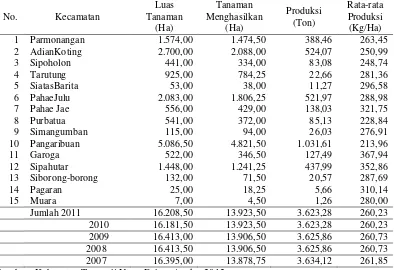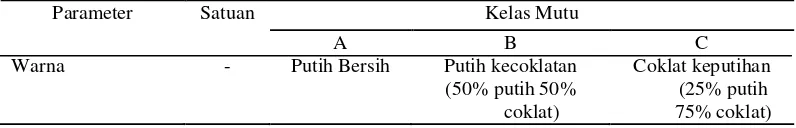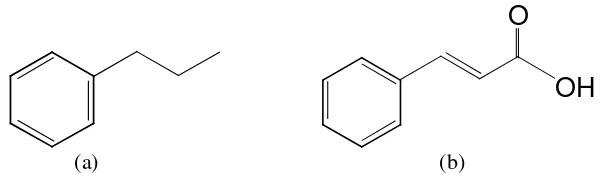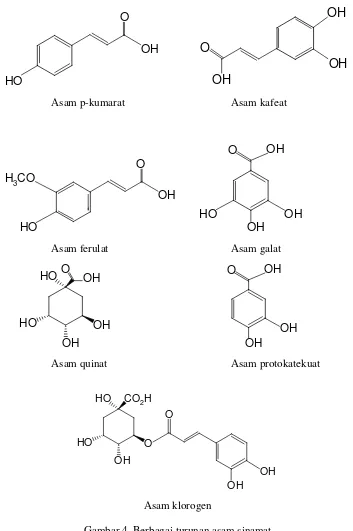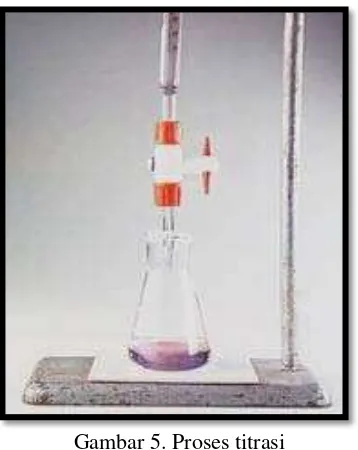TINJAUAN PUSTAKA
Taksonomi Kemenyan
Taksonomi pohon kemenyan menurut Jayusman (2014) sebagai berikut :
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Superdivisio : Spermatophyta
Divisio : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Subkelas : Dilleniidae
Ordo : Ebenales
Famili : Styracaceae
Gambar 1. Pohon kemenyan (Styrax spp.)
Van Steenis (1953 dalam Jayusman, 2014:10) menyebutkan bahwa secara umum
hanya empat jenis tanaman kemenyan yang dibudidayakan dan bernilai ekonomi
DRYLAND), Bulu (Styrax benzoine var. hiliferum), dan Siam (Styrax
tonkinennsis).
Umumnya masyarakat di Tapanuli dan Dairi, Provinsi Sumatera Utara
hanya membudidayakan jenis Toba dan Durame secara luas sedangkan jenis Bulu
kurang banyak dibudidayakan. Jenis kemenyan Siam hingga saat ini belum
banyak dikembangkan di Indonesia, namun telah dirintis penguasaan budidayanya
oleh Balai Penelitian kehutanan Sumatera.
Morfologi Pohon Kemenyan
Morfologi pohon Kemenyan menurut Jayusman (2014) sebagai berikut :
Pohon
Kemenyan termasuk pohon besar, tinggi dapat mencapai (20-40) m dan
diameter batang mencapai (60-100) cm. Batang lurus dengan percabangan sedikit.
Kulit beralur tidak terlalu dalam (3-7) mm dengan warna kulit merah anggur.
Daun
Kemenyan berdaun tunggal dan tersusun secara spiral. Daun berbentuk
oval bulat, bulat memanjang (ellips) dengan dasar daun bulat dengan ujung
runcing. Sebelah atas daun berwarna hijau dan sebelah bawah berwarna
kekuning-kuningan dengan pinggiran daun rata. Panjang daun mencapai (4-15) cm, lebar
daun (5-7,5) cm, tangkai daun (5-13) cm, helai daun mempunyai nervi (7-13)
pasang. Warna daun jenis Toba lebih gelap kecoklatan dan lebih tebal
dibandingkan jenis Durame dan Bulu.
Bunga
Kemenyan berkelamin dua, dengan tangkai bunga memiliki panjang
mahkota bunga masing-masing lima buah. Kemenyan berbunga secara teratur satu
kali setiap tahun. Waktu berbunga pohon kemenyan pada bulan November sampai
Januari.
Buah dan biji
Buah kemenyan berbentuk bulat gepeng dan lonjong berukuran (2,5-3)
cm. Biji berukuran (15-19) mm, dengan warna coklat keputihan. Biji kemenyan
terdapat di dalam buah dengan kulit buah berukuran (1,75-3,1) mm. Biji
kemenyan Toba berwarna coklat tua dan lebih gelap dibandingkan jenis Durame
dan Bulu.
Syarat Tumbuh Kemenyan
Tanaman ini umumnya tumbuh secara alami di Sumatera Utara, beberapa
syarat tumbuh kemenyan menurut Departemen Kehutanan dan Perkebunan (1999)
sebagai berikut :
Tanah
Tanaman kemenyan tidak memerlukan persyaratan yang istimewa
terhadap jenis tanah, dapat tumbuh pada tanah bertekstur berat sampai ringan dan
tanah yang kurang subur sampai yang subur lebih baik. Jenis tanaman ini tidak
tahan terhadap genangan, sehingga untuk pertumbuhan memerlukan tanah yang
mempunyai porositas tinggi, di samping itu yang perlu diperhatikan tingkat
keasaman tanah (pH tanah). Berdasarkan kenyataan di lapangan tanaman
kemenyan tumbuh baik pada tingkat pH tanah antara 4 -7.
Iklim
Tanaman kemenyan memerlukan banyak cahaya matahari dan curah hujan
mm/tahun, suhu bulanan (17-29) ᵒC dan kelembaban rata-rata 85,04% dengan iklim basah Schmidt dan Ferguson tipe A dan B. Menurut Wibowo (2012) tipe
iklim A adalah daerah sangat basah dengan ciri vegetasi hutan hujan tropika
(0 < Q < 14,3) dan tipe iklim B adalah daerah basah dengan ciri vegetasi hutan
hujan tropika (14,3 < Q < 33,3). Keadaan iklim sangat besar pengaruhnya
terhadap pertumbuhan tanaman kemenyan.
Topografi
Secara alamiah tanaman kemenyan yang banyak terdapat di Sumatera
Utara tumbuh mulai dari dataran rendah sampai ketinggian 1500 meter di atas
permukaan laut (mdpl), tetapi rata-rata tumbuh pada ketinggian antara (100-700)
mdpl. Jenis tanaman ini tumbuh pada keadaan lapangan dari mulai datar sampai
berbukit/bergelombang.
Jenis-Jenis Kemenyan
Menurut Jayusman (2014) jenis-jenis kemenyan ada empat yaitu sebagai
berikut :
Kemenyan Toba (Styrax paralleloneurum PERK)
Kemenyan Toba merupakan jenis yang paling banyak dibudidayakan di
daerah Tapanuli dan Dairi. Jenis ini tumbuh dan menyebar pada ketinggian > 600
mdpl di sentra produksi kemenyan di Tapanuli Utara. Penampilan daun jenis Toba
terkesan lebih gelap dan mengkilap dibandingkan jenis Durame dan Bulu. Getah
yang dihasilkan memiliki aroma balsamat tajam, warna putih kuning kecoklatan
dengan ukuran butiran getah panjang (3-7) cm dan lebar (1,5-2,5) cm. Kemenyan
Kemenyan Durame (Styrax benzoine DRYLAND)
Kemenyan Durame merupakan jenis kedua yang paling banyak
dibudidayakan di daerah Tapanuli. Jenis ini tumbuh dan menyebar pada
ketinggian mulai dari > 60 mdpl di daerah Sumatera Selatan dan Tapanuli Selatan,
sedangkan di sentra produksi kemenyan Tapanuli Utara banyak ditemukan pada
ketinggian > 600 mdpl. Umumnya kemenyan Durame dibudidayakan secara
campuran dengan jenis Toba dan Bulu. Penampilan daun jenis Durame terkesan
lebih terang warnanya dibandingkan jenis Toba. Getah yang dihasilkan memiliki
aroma balsamat agak tajam, warna putih-kuning kecokelatan dengan ukuran
butiran getah panjang (3-5) cm dan lebar (1-1,5) cm.
Kemenyan Bulu (Styrax benzoine var hiliferum)
Kemenyan Bulu merupakan jenis yang kurang banyak dikenal, hal ini
disebabkan oleh jumlah populasinya yang relatif sedikit. Jenis ini secara alam
banyak ditemukan di hutan alam Sibatuloteng-Simalungun dan cukup banyak
dibudidayakan di daerah Pahae dan Sarulla, Kabupaten Tapanuli Utara. Namun di
salah satu daerah Dolok Sanggul, jenis ini jarang atau sulit ditemukan. Getah yang
dihasilkan memiliki aroma balsamat kurang tajam, warna putih-kuning
kecokelatan dengan ukuran butiran getah panjang (3-5) cm dan lebar (1-1,5) cm.
Kemenyan Siam (Styrax tonkineensis Pierre)
Kemenyan Laos umumnya tumbuh pada elevasi (800-1600) mdpl. Jenis
ini dikelompokkan sebagai tanaman cepat tumbuh (fast growing species).
Penyebaran utama di negara Laos terdapat pada Provinsi Phongsali, Louang
Namtha, Oudomaxai, Louang Phabang dan Houa Phan (Pinyopusarerk, 1994).
lembut atau aroma vanila, besar butiran getah memiliki panjang (2,5-3,5) cm dan
lebar (1,5-1,9) cm.
Penyadapan dan Penakikan Getah Kemenyan
Kegiatan penyadapan secara umum terdiri dari kegiatan menakik,
membersihkan, dan mensugi. Kegiatan menakik merupakan kegiatan pertama
yang dilakukan dalam pengelolaan hutan kemenyan. Kegiatan menakik meliputi
kegiatan membersihkan semak-semak yang berdekatan dengan pohon kemenyan,
kemudian dilanjutkan dengan membersihkan pohon kemenyan dengan cara
mengguris (mengikis) bagian kulit pohon tersebut. Kegiatan ini dilakukan untuk
membersihkan lumut yang menempel pada kulit pohon sehingga getah yang
dihasilkan tidak kotor (Dede, 1998).
Pohon yang ditakik biasanya 10-15 pohon sesuai dengan besar batang.
Pohon yang ditakik kemudian ditinggalkan selama 3-4 bulan, selanjutnya pada
luka bekas takikan akan terbentuk getah yang sudah lengket dan mengering.
Kulit kering yang mengandung getah tadi dipotong dan dikupas dari batang
dengan menggunakan pisau panen dan kegiatan ini disebut “mensugi”. Hasil
panen yang diperoleh disebut kemenyan mata kasar (sidungkapi), mata halus,
tahir, dan juror. Produksi rata-rata antara (0,1-0,5) Kg/pohon. Setelah dilakukan
kegiatan pengumpulan getah maka + 2-3 bulan lagi getah akan keluar yang
mencuat dan menempel pada bekas luka takikan. Para petani kemudian memungut
hasilnya yang disebut kegiatan pembersihan (panen kedua). Kualitas getah yang
dihasilkan kemenyan tahir. Setelah 2-3 bulan kemudian maka getah ketiga akan
muncul lagi dan getah ini akan dikumpulkan pada saat akan dilakukan penakikan
Potensi dan Penyebaran Kemenyan
Pohon kemenyan menyebar pada berbagai negara meliputi Malaysia,
Thailand, Indonesia, dan Laos. Indonesia memiliki daerah sebaran pohon
kemenyan di Pulau Sumatera, Pulau Jawa bagian Barat dan Kalimantan Barat.
Sumatera memiliki sebaran terluas, terutama daerah Tapanuli dan Dairi.
Diperkirakan hampir 67% dari luas kebun kemenyan yang ada di Indonesia
terdapat di daerah Tapanuli Utara.
Gambar 2. Peta sebaran kemenyan di Tapanuli Utara Sumber : BPS Tapanuli Utara
Pada tahun 1910, produksi kemenyan Tapanuli Utara sekitar 1.200 ton,
kemudian naik menjadi sekitar 2.300 ton pada tahun 1930 dan pada tahun 1950
produksi meningkat menjadi sekitar 3.400 ton. Luas tanaman kemenyan pada
tahun 1990 adalah lebih kurang 22.793 ha. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki
tanaman paling luas yaitu 21.119 ha dengan produksi sekitar 4.000 ton. Pada
tahun 1993 luas tanaman kemenyan di Tapanuli Utara adalah 17.299 ha dengan
Tanaman kemenyan merupakan tanaman terluas yang diusahakan oleh
masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu pada tahun 2011 seluas 16.181,50
ha. Tanaman kemenyan tersebar di seluruh kecamatan Tapanuli Utara,
sebagaimana dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Luas dan produksi kemenyan di kabupaten Tapanuli Utara
No. Kecamatan 10 Pangaribuan 5.086,50 4.821,50 1.031,61 213,96 11 Garoga 522,00 346,50 127,49 367,94 Sumber : Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Angka, 2012.
Kualitas Getah Kemenyan
Menurut Sasmuko (1999) kualitas kemenyan yang diperdagangkan di
Sumatera belum memiliki suatu standar umum yang berlaku, baik dalam transaksi
pedagang dan eksportir. Perbedaan standar tersebut menurut petani, pedagang,
dan pengolah, antara lain:
Petani
Kemenyan dibedakan juga atas masa panennya, yakni masa panen besar
(getah mata kasar dan getah mata halus) serta masa panen menurun (getah tahir
Pedagang dan pengolah
Pengolah merupakan industri yang mengolah getah kemenyan dari
kemenyan mentah menjadi kemenyan tampangan. Kemenyan yang dibeli
pedagang berupa sam-sam (campuran), mata kasar dan mata halus (kualitas I dan
II), tahir (kualitas III), dan jurur (kualitas IV). Getah disortir dengan memakai
ayakan, sehingga dapat diatur sesuai dengan mutu yang diinginkan, dapat dilihat
pada tabel 2.
Tabel 2. Kualitas getah kemenyan menurut pedagang dan pengolah No. Mutu Keterangan
1. Kualitas I Kemenyan mata kasar atau sidungkapi adalah bongkahan kemenyan berwarna putih sampai putih kekuning-kuningan dengan rata-rata diameter > 2 cm.
2. Kualitas II Kemenyan mata halus adalah kemenyan berwarna putih sampai putih kekuning-kuningan berdiameter 1 - 2 cm.
3. Kualitas III Kemenyan tahir adalah jenis kemenyan yang bercampur dengan kulit atau kotoran lainnya, berwarna cokelat dan terkadang berbintik-bintik putih atau kuning serta besarnya lebih dari ukuran kemenyan mata halus. 4. Kualitas IV Kemenyan jurur adalah kemenyan yang biasa dicampur atau disamakan
dengan kemenyan tahir. Warnanya merah dan lebih kecil dari mata halus.
5. Kualitas V Kemenyan barbar adalah kulit kemenyan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit saat pembersihan.
6. Kualitas VI Kemenyan abu adalah sisa-sisa yang berasal dari semua kualitas getah kemenyan. Bentuk dan warnanya seperti abu kasar.
Sumber : Sasmuko, 1999
Perdagangan getah kemenyan di dalam negeri telah mengenal
penggolongan kualitas baik lokal maupun standar kualitas kemenyan nasional.
Standar Nasional Indonesia (SNI) kemenyan disusun karena diperlukan
persyaratan mutu getah kemenyan dalam rangka mengikuti perkembangan pasar
yang cukup tinggi dan teknologi pangan. Berdasarkan SNI 7940:2013 getah
kemenyan dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Klasifikasi dan persyaratan khusus pada getah kemenyan Parameter Satuan Kelas Mutu
A B C
Warna - Putih Bersih Putih kecoklatan (50% putih 50%
coklat)
Kadar abu % < 1 < 1 >1 - < 5
Kadar kotoran % < 1 < 1 >1 - < 2
Titik lunak 0C > 92 > 88 > 80 Kadar asam sinamat % > 30 21 - 29 < 20
Sumber: Standar Nasional Indonesia (SNI) No.7940-2013
Kandungan Kimia Kemenyan
Daun kemenyan mengandung saponin, flavonoid dan polifenol
(Hutapea, 1994). Getah kemenyan mengandung asam sinamat, asam benzoat,
esternya (seperti koniferilbenzoat, koniferilsinamat dan asam sinamilsinamat),
triterpenoid/steroid (berupa turunannya yaitu asam siaresinolik dan asam
sumaresinolik) (Stahl, 1985).
Manfaat Getah Kemenyan
Menurut Jayusman (2014) secara tradisional getah kemenyan digunakan
sebagai dupa pada upacara religi. Getah kemenyan juga digunakan pada industri
pembuatan rokok dengan mencampurkan tembakau rokok dan getah kemenyan.
Khan (2001) menyebutkan bahwa getah kemenyan mengandung asam sinamat
(C6H5CH-CHOOH). Kandungan asam sinamat pada getah kemenyan berperan
penting sebagai bahan penolong pada pembuatan berbagai bahan kimia. Seiring
perkembangan zaman asam sinamat digunakan pada berbagai industri kimia.
Menurut Jayusman (2014) penggunaan asam sinamat sebagai berikut :
Pembuatan obat-obatan (farmasi)
Asam sinamat pada bidang farmasi digunakan sebagai antiseptic,
expectorant (pelega pernafasan), obat katarak mata, dan pada pembuatan
Pembuatan parfum dan kosmetik
Asam sinamat pada pembuatan parfum dimanfaatkan sebagai fix active
yang berfungsi menahan aroma pada parfum agar tahan lama. Negara Perancis
telah menghasilkan parfum dengan paten bernama “Lait Virginal”. Pada
pembuatan kosmetik asam sinamat dimanfaatkan sebagai sun screening agent
yaitu sebagai pelindung kulit terhadap sinar matahari dan juga karena memiliki
sifat astrigent, sehingga dapat mengeluarkan kotoran-kotoran yang terdapat pada
kulit (wajah).
Pengawetan makanan dan minuman
Asam sinamat pada pengawet makanan dan minuman digunakan sebagai
food additive yaitu bahan tambahan untuk makanan dan minuman terutama
pengawetan. Menurut Botanical Dermatology Database (2004) bahwa jumlah
asam sinamat yang dibutuhkan untuk setiap kilogram/liter makanan atau minuman
untuk pengawetan sebanyak 1,25 mg.
Asam Sinamat
Asam sinamat adalah senyawa bahan alam dengan rumus kimia
C6H5CHCHCOOH atau C9H8O2, berwujud kristal putih, sedikit larut dalam air,
dan mempunyai titik leleh 133°C serta titik didih 300°C. Asam sinamat terdapat
dalam berbagai tanaman, misalnya mesoyi (Messoia aromatica Becc) dan
kemenyan (Styrax spp.). Senyawa ini memiliki berbagai aktivitas biologis, antara
lain antibakteri, anestetik, antiinflamasi, antispasmodik, antimutagenik, fungisida,
herbisida serta penghambat enzim tirosinase (Rudyanto et al., 2008).
Menurut Lenny (2006) asam sinamat termasuk turunan senyawa
senyawa fenol utama yang berasal dari jalur shikimat. Biosintesa senyawa
fenilpropanoida yang berasal dari jalur shikimat pertama kali ditemukan dalam
mikroorganisme seperti bakteri, kapang dan ragi, sedangkan asam shikimat
pertama kali ditemukan pada tahun 1885 dari tumbuhan lllicium religiosum dan
kemudian ditemukan dalam banyak tumbuhan.
O
OH
(a) (b)
Gambar 3. Kerangka dasar (a) fenilpropanoida, (b) asam sinamat
Pokok-pokok reaksi biosintesa dari jalur shikimat dimulai dengan
pembentukan asam shikimat dimulai dengan kondensasi aldol antara suatu tetrosa
yaitu eritrosa dan asam fosfoenolpiruvat. Pada kondensasi ini, gugus metilen
-CH2- dari asam fosfoenolpiruvat berlaku sebagai nukleofil dan beradisi dengan
gugus karbonil C=O dari eritrosa menghasilkan suatu gula yang terdiri dari 7 atom
karbon. Selanjutnya reaksi yang analog (intramolekuler) menghasilkan asam
5-dehidrokuinat yang mempunyai lingkar sikloheksana yang kemudian diubah
menjadi asam shikimat.
Berikutnya aromatisasi dari asam prefenat menghasilkan fenilpiruvat yang
menghasilkan fenilalanin melalui reaksi reduktif aminasi. Akhirnya, deaminasi
dari fenilalanin menghasilkan asam sinamat. Reaksi paralel sejenis terhadap
tirosin yang mempunyai tingkat oksidasi yang lebih tinggi menghasilkan asam
O
Asam p-kumarat Asam kafeat
O
Gambar 4. Berbagai turunan asam sinamat
Titrasi atau Volumetri
Menurut Rodiani (2013) analisis titrimetri atau analisa volumetri adalah
analisa kuantitatif dengan mereaksikan suatu zat yang dianalisis dengan larutan
yang dianalisis dan larutan standar tersebut berlangsung secara kuantitatif. Analisa
titrimetri merupakan satu bagian kimia analisis. Perhitungannya berdasarkan
hubungan stoikiometri dari reaksi-reaksi kimia dimana a molekul analit A,
bereaksi dengan t molekul reagensia T. Reagensia T disebut titran, ditambahkan
sedikit demi sedikit dari dalam buret.
aA + tT Produk
Larutan dalam buret bisa berupa larutan standar yang konsentrasinya
diketahui dengan cara standarisasi ataupun larutan dari zat yang akan ditentukan
konsentrasinya. Penambahan titran diteruskan sampai jumlah T secara kimia
setara atau ekuivalen, maka keadaan tersebut dikatakan telah mencapai titik
ekuivalensi dari titrasi itu. Untuk mengetahui kapan penambahan titran itu harus
dihentikan, digunakan zat indikator yang dapat menunjukkan terjadinya kelebihan
titran dengan perubahan warna. Perubahan warna ini bisa tepat atau tidak tepat
pada titik ekuivalensi. Titik dalam titrasi pada saat indikator berubah
warna disebut titik akhir titrasi.
Gambar 5. Proses titrasi
- Reaksi harus berjalan sesuai dengan suatu persamaan reaksi tertentu, tidak boleh ada reaksi sampingan.
- Harus ada perubahan yang terlihat pada saat titik ekuivalen tercapai, baik secara kimia maupun fisika.
- Harus ada indikator yang cocok untuk menentukan titik akhir titrasi, jika reaksi tidak menunjukkan perubahan kimia dan fisika.
- Reaksi harus berlangsung cepat, sehingga titrasi dapat dilakukan dalam beberapa menit (widiarto, 2009).
Skrining Fitokimia
Skrining fitokimia adalah pemeriksaan kimia secara kualitatif terhadap
senyawa-senyawa aktif biologis yang terdapat dalam simplisia dan ekstrak
tumbuhan. Senyawa - senyawa tersebut adalah senyawa organik, oleh karena itu
skrining terutama ditujukan untuk golongan senyawa organik seperti alkaloida,
flavonoid, triterpenoid/steroid, tanin, dan sapotanin. Skrining merupakan langkah
awal dari pemeriksaan tumbuhan tersebut untuk membuktikan ada tidaknya
senyawa kimia tertentu dalam tumbuhan tersebut yang dapat dikaitkan dengan
aktivitas biologinya (Farnsworth, 1996). Uraian beberapa metabolit sekunder
tersebut adalah sebagai berikut:
Alkaloid
Alkaloid merupakan golongan zat tumbuhan sekunder yang terbesar.
Alkaloid mencakup senyawa bersifat basa yang mengandung satu atau lebih atom
nitrogen, biasanya dalam gabungan, sebagai bagian dari sistem siklik. Alkaloid
sering bersifat racun bagi manusia dan banyak yang mempunyai kegiatan fisiologi
(Harbone, 1987). Pada umumnya alkaloid merupakan senyawa padat berbentuk
kristal atau amorf, tidak berwarna dan mempunyai rasa pahit. Dalam bentuk bebas
alkaloid merupakan basa lemah yang sukar larut dalam air tetapi mudah larut
dalam pelarut organik (Rusdi, 1998).
Flavonoid
Flavonoid merupakan senyawa polar yang umumnya mudah larut dalam
pelarut polar seperti etanol, metanol, butanol, aseton, dan lain-lain (Markham,
1988). Nurachman (2002) menambahkan bahwa senyawa-senyawa flavonoid
umumnya bersifat antioksidan dan banyak yang telah digunakan sebagai salah
satu komponen bahan baku obat-obatan.
Saponin
Saponin berasal dari bahasa Latin yaitu “sapo” yang berarti sabun dan
sifatnya menyerupai sabun. Saponin merupakan senyawa aktif permukaan yang
kuat yang menimbulkan busa jika dikocok dalam air dan pada konsetrasi yang
rendah sering menyebabkan hemolisis sel darah merah. Beberapa saponin bekerja
sebagai antimikroba dan saponin tertentu menjadi penting karena dapat diperoleh
dari beberapa tumbuhan dengan hasil yang baik dan digunakan sebagai bahan
baku untuk sintesis hormon steroid yang digunakan dalam bidang kesehatan
(Robinson, 1995).
Tanin
Tanin merupakan golongan senyawa aktif tumbuhan yang bersifat fenol.
Tanin memiliki aktivitas antibakteri, secara garis besar mekanismenya adalah
pembentukan iaktan senyawa kompleks tanin terhadap ion logam yang dapat
menambah daya toksisitas tanin itu sendiri (Akiyama et al., 2001).
Triterpenoid/steroid
Triterpenoid merupakan salah satu senyawa organik yang hanya tersebar
di alam. Triterpenoid banyak ditemukan dalam tumbuhan tingkat tinggi sebagai
minyak atsiri yang memberi bau harum dan bau khas pada tumbuhan dan bunga
(Thomson, 1993). Triterpenoid dari tumbuhan biasanya digunakan sebagai
senyawa aromatik yang menyebabkan bau pada eucalyptus, pemberi rasa pada
kayu manis, cengkeh, jahe dan pemberi warna kuning pada bunga.
Triterpenoid/steroid tumbuhan mempunyai manfaat penting sebagai obat